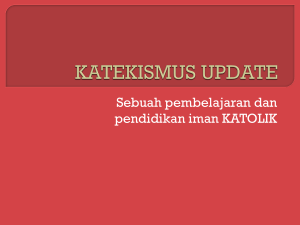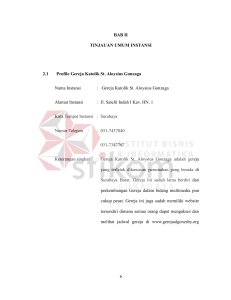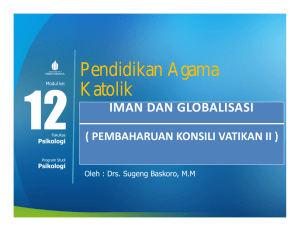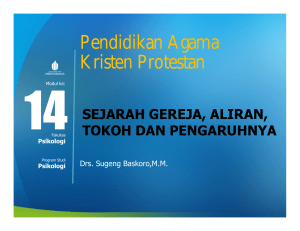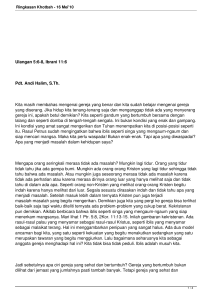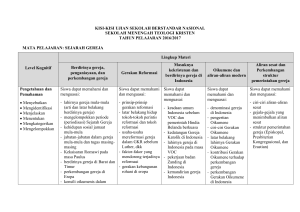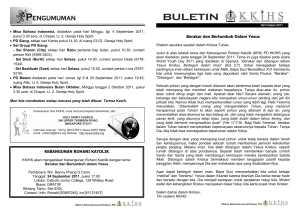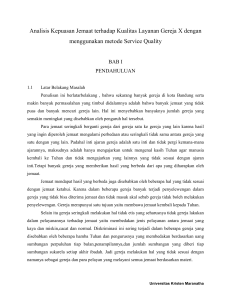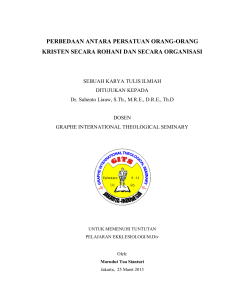menuju gereja yang makin mengindonesia seminar sehari 50 tahun
advertisement
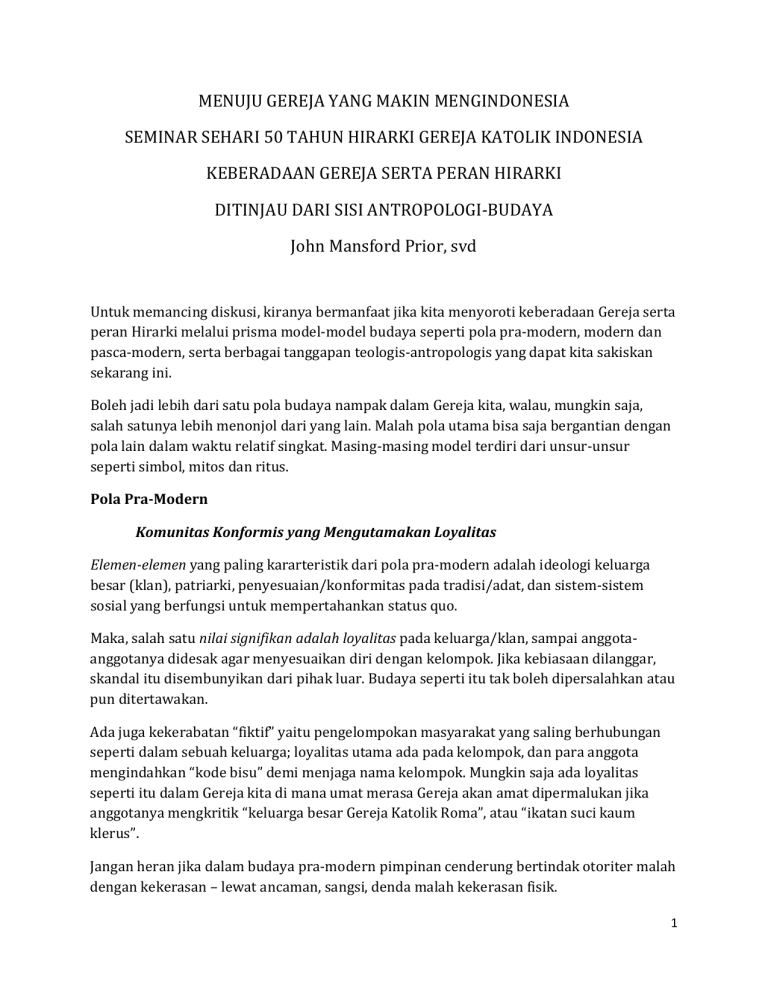
MENUJU GEREJA YANG MAKIN MENGINDONESIA SEMINAR SEHARI 50 TAHUN HIRARKI GEREJA KATOLIK INDONESIA KEBERADAAN GEREJA SERTA PERAN HIRARKI DITINJAU DARI SISI ANTROPOLOGI-BUDAYA John Mansford Prior, svd Untuk memancing diskusi, kiranya bermanfaat jika kita menyoroti keberadaan Gereja serta peran Hirarki melalui prisma model-model budaya seperti pola pra-modern, modern dan pasca-modern, serta berbagai tanggapan teologis-antropologis yang dapat kita sakiskan sekarang ini. Boleh jadi lebih dari satu pola budaya nampak dalam Gereja kita, walau, mungkin saja, salah satunya lebih menonjol dari yang lain. Malah pola utama bisa saja bergantian dengan pola lain dalam waktu relatif singkat. Masing-masing model terdiri dari unsur-unsur seperti simbol, mitos dan ritus. Pola Pra-Modern Komunitas Konformis yang Mengutamakan Loyalitas Elemen-elemen yang paling kararteristik dari pola pra-modern adalah ideologi keluarga besar (klan), patriarki, penyesuaian/konformitas pada tradisi/adat, dan sistem-sistem sosial yang berfungsi untuk mempertahankan status quo. Maka, salah satu nilai signifikan adalah loyalitas pada keluarga/klan, sampai anggotaanggotanya didesak agar menyesuaikan diri dengan kelompok. Jika kebiasaan dilanggar, skandal itu disembunyikan dari pihak luar. Budaya seperti itu tak boleh dipersalahkan atau pun ditertawakan. Ada juga kekerabatan “fiktif” yaitu pengelompokan masyarakat yang saling berhubungan seperti dalam sebuah keluarga; loyalitas utama ada pada kelompok, dan para anggota mengindahkan “kode bisu” demi menjaga nama kelompok. Mungkin saja ada loyalitas seperti itu dalam Gereja kita di mana umat merasa Gereja akan amat dipermalukan jika anggotanya mengkritik “keluarga besar Gereja Katolik Roma”, atau “ikatan suci kaum klerus”. Jangan heran jika dalam budaya pra-modern pimpinan cenderung bertindak otoriter malah dengan kekerasan – lewat ancaman, sangsi, denda malah kekerasan fisik. 1 Mitologi pra-modernitas bersifat patriarkis dan menyerahkan status subordinat pada perempuan, dan kaum lelaki didukung oleh struktur serta mekanisme adat untuk menegaskan atau malah memaksakan posisinya dengan mengorbankan kaum perempuan. Kejantanan disamakan dengan kehormatan, sedangkan bagi kaum perempuan terhormat berarti tunduk total pada ayah, suami atau kakak laki-lakinya. Otoritas sang ayahanda diberikan oleh Allah sendiri dan nyaris bersifat absolut. Kepemimpinan Feodal Para pembesar dalam komunitas yang berciri pra-modern mengandaikan bahwa mereka sendiri punya wewenang untuk mengambil keputusan dan mereka bertanggungjawab hanya ke atas. Boleh jadi di dalam Gereja kita masih terdapat anggota hirarki yang merasa perlu memberikan akuntabilitas hanya ke Roma selain kepada Tuhan Allah sendiri. Dalam budaya seperti itu otoritas kepausan dan hirarki hampir-hampir disamakan dengan otoritas Yang MahaEsa. Jika umat awam berpesta itu boros; jika uskup atau imam berpesta itu “pengungkapan iman”. Dalam dunia pra-modern, pastor-pastor yang terlibat dalam celaka lalu lintas di wilayah yang mayoritasnya Kristen, tak pernah diperkarakan kendati ada korban jiwa. Skandalskandal seks didiamkan - dan berjalan terus. Nama Gereja lebih mulia dari pada kondisi korban perlakuan busuk sang pastor. Kultur komunikatif-terbuka akan membongkar skandal-skandal ini dan mengutamakan perempuan dan laki-laki yang jadi korban – bukan nama baik institusi. Sangat jelas, bahwa selama berabad-abad Gereja Roma telah menyerap dan mengembangkan semangat serta kebiasaan dari kebudayaan-kebudayaan Eropa sekular pra-modern. Misalnya, sistem kepemimpinan monarkis-piramidal, birokrasi sentralistik di Roma, serta nilai-nilai patriarkhal. Pucuk kepemimpian Gereja memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan juridikatif dalam tangannya sendiri. Dalam komunitas demokratis, ketiga kekuasaan ini dipisahkan dengan jelas. Hirarki Gereja Katolik Roma sesungguhnya merupakan produk sebuah budaya patriarki, dan seperti sering digarisbawahi oleh Mangunwijaya (Gereja Diaspora, Jogja 1999), Gereja feodal-piramidal yang dibawa ke Indonesia cocok sekali dengan budaya-budaya Indonesia yang feodal-patriarkis. Patriarki Gereja Katolik Roma menyuburkan budaya-budaya Indonesia yang patriarkis dan demkian pun sebaliknya. Masyarakat yang feodal mementingkan simbol dan personifikasi kekuasaan. Maka, jangan heran kalau Gereja kita bersifat klerikal-kental dan para uskup serta para imam lebih menjadi pribadi kekuasaan dari pada pelayan. 2 Penyesuaian bukan Inkulturasi Melihat ciri-ciri pola budaya pra-modern, kita memperoleh kesan bahwa hampir seluruh kebudayaan-kebudayaan Indonesia bersifat pra-modern, yaitu berciri patriarkis lagi feodal. Karena itu, proses demokratisasi, yang dimulai sejak rejim Soeharto ditumbangkan, belum mampu membongkar budaya ini. Walau para pemimpin negara dipilih secara demokratis, mereka tetap menampilkan perannya seperti tua adat atau kepala keluarga yang feodal. Tata pengaturan demokratis tidak menjamin demokrasi jika budaya dominan bersifat pramodern. Yang diambil dari kebudayaan adalah posisi kekuasaan yang menguntungkan; maka kurang ada inisiatif untuk melakukan inkulturasi teologis yang sesungguhnya. Boleh jadi sistem pemilihan pembesar dalam Tarekat-Tarekat religius, yang nota bene bersifat quasi-demokratis, karena dilaksanakan dalam lingkup budaya yang didominasi oleh elemen-elemen pra-modern, sebetulnya tidak jauh berbeda dari proses pemilihan umum dengan fraksi-fraksi, blok etnis dan pengelompokan kepentingan-kepentingan lainnya. Di sini saya tidak menyinggung situasi yang amat berbeda di Papua yang budaya melanesianya lebih egalitarian. Kembali ke Akar: Yesus Kristus Tak ada satu pun dari elemen-elemen dari budaya pra-modern ini yang diwariskan oleh Yesus Kristus. Jika Gereja Katolik Indonesia hendak membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia dan mendukung proses demokratisasi yang sedang diperjuangkan, maka Gereja perlu kembali ke akarnya yakni Yesus sendiri dan ajaran-Nya dalam Kitab Suci. Yesus yang melarang para murid berlagak bagai pimpinan dunia (Mrk 10:35-45); Yesus yang memandang setiap situasi dari sudut para korban; Yesus yang mengundang “yang jahat dan yang baik” dari pinggiran dan persimpangan jalan untuk menggantikan para pemilik tanah dan pemilik modal (Mat 22:1-10; Luk 14:15-24); Yesus yang datang untuk mencerai-beraikan yang congkak hatinya dan menurunkan yang berkuasa dari tahtanya dan mengangkat orang-orang kecil. (Luk 1:51-53). Pola Pasca-Modern Dua unsur dari pola modernitas yang sangat menonjol adalah proses birokratisasi dan sentralisasi. Tapi, karena diberi cuma 10 menit untuk memancing diskusi, saya melewati pola modernitas begitu saja. Pada masa pasca-modern kepastian sudah runtuh, prinsip (adat) yang menata masyarakat secara tersentralistik sudah menghilang. Tolok ukur etika tunggal tidak ditemukan lagi. Keyakinan akan diri manusia yang satu dan koheren tengah memudar. Pembatasan, kepastian, tabu, peran pasti, sistem-sistem, pola, bentuk dan tradisi, pun perbedaan gender, 3 dilanggar. Sepertinya ambiguitas dan ketakpastian menjadi pola hidup utama pada masa pasca-modern. Jatidiri kita manusia sudah diperoleh dari rupa-rupa sumber. Kita hidup di dalam apa yang dijuluki “masyarakat jejaringan”. Karena itu, identias sosial diperoleh dari aneka sumber yang melintasi batas lingkup-lingkup budaya, malah batas bangsa sendiri. Identitas tidak lagi terbatas oleh sistem golongan sosial, gender, etnisitas, umur dan sebagainya. Sangat mungkin komunitas maya, bagi sementara sama saudara, lebih bermakna daripada komunitas geografis. Berhadapan dengan pola budaya pasca-modern ada orang yang menjadi skeptis atau sinis, lain menjadi serba pragmatis tanpa merasa perlu norma yang pasti, lain lagi menjadi amat relativistis. Tiga Tangapan dalam Gereja Kita bisa menyaksikan tiga jenis tanggapan terhadap perubahan pesat yang sedang melanda masyarakat dan Gereja pada masa pasca-modernitas ini, yaitu respons fundamentalistik, respons berupa protes, dan respons konsiliar-kolegial. Respons Fundamentalis Katolik Budaya pasca-modern menjadi “tempat pembibitan” tuntutan akan kepastian oleh kelompok-kelompok etnis, kelompok-kelompok fundamentalis, dan mereka yang coba merestorasi – yaitu mau mengembalikan Gereja ke suatu masa lampau seperti yang mereka rekonstruksikan dalam bayangan-bayangan mereka. Sekarang ini kita dapat menyaksikan gerakan kuat restorasionisme, sebuah arus balik dalam Gereja yang mengafirmasikan struktur, sikap dan devosi dari Gereja pra-Konsili. Ortodoksi kaku direkonstruksi dan ditekankan menggantikan kreativitas pastoral. Mereka memimpikan sebuah Gereja Roma yang berbudaya-tunggal bukan suatu Gereja majemuk, multi-budaya. Respons ini terlihat dalam proses re-klerikalisasi pada tingkat paroki di mana Dewan Pastoral kembali menjadi kaki-tangan sang pastor tertahbis. Komunitas-komunitas Basis Gerejani yang dirintis pada tahun 1970an, kini direduksi menjadi cuma satuan-satuan administratif dan devosional di dalam struktur dan organisasi paroki. Berbagai gerakan rohani baru seperti sebagian dari gerakan karismatik serta gerakan devosional lainnya, mengutamakan identitas Katolik Roma bukan dialog dengan masyarakat mayoritas. Roma juga terbawa – atau malah membawa – arus balik fundamentalistik ini misalnya dengan coba memaksa kita untuk re-romanisasi liturgi Gereja serta melatinisasi bahasa Indonesia yang dipakai di dalamnya. Bahayanya, gerakan restorasionisme ini bisa saja menjadi arus 4 umum dalam Gereja kita, presis terbalik dari tema kita hari ini: Menuju Gereja yang Makin Mengindonesia. Respons Berupa “Protes” Kita dapat menyaksikan bagaimana dengan merosotnya visi dan pembaruan Konsiliarkolegial, maka ada gejala bahwa umat semakin terpecah ke dalam sekian banyak kelompok, mana yang satu tidak mempedulikan, atau malah saling bertentangan, dengan yang lain. Ada umat yang masih tetap setia pada visi konsili tapi tidak punya akses pada kekuasaan dalam Gereja. Lain kelompok membentuk semacam sekte-sekte elitis dan punya akses pada modal besar; mereka mendesak solusi-solusi instan yang sangat otoriter, dan kadangkadang malah mengejar sambil memfitnah anggota-anggota kelompok lain. Ada umat lain lagi yang sudah jenu dengan segala pertentangan dalam Gereja dan diam-diam mundur. Gejala terakhir ini terlihat di antara umat yang tekun terlibat dalam proses demokratisasi negara dan dalam gerakan penegakan hak-hak asasi manusia. “Protes” tidak senantiasa harus dengan demo publik atau suara lantang, melainkan dengan diam-diam umat mempertanggungjawabkan imannya sendiri-sendiri, semakin terlepas dari Gereja institusional, tapi tetap “kental Katolik” dalam keyakinan, dan dalam nilai-nilai iman yang mendasari perjuangan hidup demi kesejahteraan umum. Respons Konsiliar-Kolegial Namun, masih tinggal beberapa orang yang setia pada wawasan Konsili Vatikan II dan yang hendak membentuk “status quo baru” dengan struktur-strukur serta sistem-sistem kekuasaan baru, dan yang berbasis mitologi Gereja (eklesiologi Konsili) yang sudah diperbarui. Dalam dokumen Lumen Gentium Gereja piramidal diganti dengan Gereja persekutuan, Gereja klerus dengan Gereja Umat, Gereja monarkis dengan Gereja umat Allah dalam perjalanan. Dalam dokumen Gaudium et spes, Gereja ghetto atau benteng tertutup (“masyarakat sempurna”) diganti dengan Gereja terbuka yang berdialog dengan dunia. Proses ini berat dan makan waktu lama dan menuntut ketabahan dan kesabaran. Proses berkepanjangan ini memerlukan pemimpin yang mampu hidup di tengah ambiguitas masyarakat kini dan di sini sementara mitologi baru (eklesiologi Konsili) pelan-pelan menjadi milik, dan struktur-struktur baru dapat dibangun di atas sistem nilai konsiliar. Tanggapan konsiliar-kolegial pernah cukup menonjol di Gereja Katolik Indonesia pada tahun 1960an dan 1970an, ketika ada upaya “indonesianisasi” dan “awamisasi”. Sekarang rasanya para uskup lebih menjadi “pastor paroki besar” yang menjalankan saja apa yang dipikirkan KWI dan diharapkan Roma dari pada menjadi pimpinan inspiratif dengan gagasan-gagasan teologis alternatif demi menjawab kerumitan dan kesimpang-siurnya zaman ini. 5 Kelompok konsiliar-kolegial ini hendak menemukan keseimbangan antara nilai hirarkis dan nilai kolegial dalam Konsili. Antara lain mereka menekankan nilai: kerjasama dengan segala pihak yang berkehendak baik, imajinasi, spiritualitas terlibat, kesetaraan gender, akuntabilitas (tanggung gugat), rekonsiliasi/pedamaian, dan pantang kekerasan. Pertanyaan Tema seminar kita adalah “Menuju Gereja yang Makin Mengindonesia”. Pertanyaan saya: Gereja mau menuju kebudayaan Indonesia mana: pra-modern, modern dan atau pascamodern? Budaya mana yang diharapkan dan yang paling sesuai dengan warta Yesus Kristus? Lantas gerakan-gerakan manakah bisa mendorong Gereja menuju “pengIndonesia-an yang diharapkan? John Mansford Prior, svd Candraditya Research Centre, Jalan Lerowulan 1, Wairklau-MAUMERE, NTT [email protected] 6