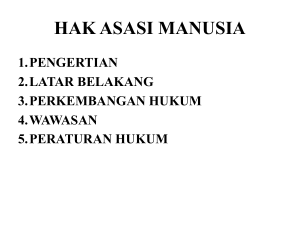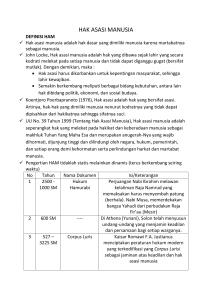Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti
advertisement

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya♣ Oleh: Ifdhal Kasim∗ BERBEDA dengan advokasi terhadap hak-hak sipil dan politik, advokasi terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidaklah terartikulasi dengan baik dan lantang dalam gerakan advokasi hak asasi manusia. Kurang lebih dari empat dekade gerakan advokasi hak asasi manusia lebih menekankan advokasi mereka pada isu-isu disekitar hak-hak sipil dan politik (civil liberties). Sementara advokasi terhadap isu-isu hak ekonomi, sosial dan budaya kurang mendapat perhatian yang memadai; ia menjadi seperti anak tiri dari gerakan advokasi hak asasi manusia. Fenomena ini bukan hanya di Indonesia, melainkan sudah merupakan fenomena global. Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty Internasional atau Human Rights Wacht, mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengarahkan gerakan advokasi hak asasi manusia itu terpusat pada hak-hak sipil dan politik.1 Sekarang saatnya kecenderungan ini dirubah, bukan mengubahnya dengan balik memusatkannya pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Tetapi meletakkan ke dalam perspektif indivisibility, yaitu meletakkannya ke dalam saling-kaitan antara kedua kategori hak tersebut. Bukan memisah-misahkannya seperti sebelumnya. Tulisan ini bukan bermaksud mendiskusikan konsep indivisibility tersebut,2 melainkan mengajak membicarakan kembali secara lebih dalam tentang hak-hak yang telah terlupakan itu. Signifikansinya mendiskusikan kembali hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu karena selama ini sudah terlanjur berkembang kesalahpahaman dalam memandang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut –yang pada akhirnya menempatkan kedudukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai pariah dalam gerakan advokasi hak asasi manusia. Selama ini telah berkembang pemahaman seakanakan hak-hak ekonomi tersebut bukan merupakan hak yang “riil” (not really rights),3 karena itu ia tidak memerlukan proteksi. Tulisan ini akan memeriksa kembali dengan kritis pandangan-pandangan yang seperti ini, selain bermaksud pula mendiskusikan ♣ Disampaikan pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta, Hotel Jogja Plaza, 25 Januari 2006. ∗ Adalah Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Manusia (ELSAM) Jakarta. 1 Tinjauan yang tajam mengenai fenomena ini dipaparkan oleh Christ Jochnick dalam tulisannya, A New Generation of Human Rights Activism (Human Rights Dialague: Carnegie Council,1997). 2 Pembahasan yang mendalam mengenai konsep ini dapat dibaca dalam Jack Donnelly, Universal Declaration of Human Rights in Theory and Practice (Ithaca, NY,: Cornell University Press, 1986). 3 Pandangan seperti ini, antara lain dikemukakan oleh Maurice Cranston, yang merupakan salah seorang tokoh terdepan dengan pandangan ini. Lihat tulisannya, What Are Human Rights? (London: The Bodley Head, 1973). 1 kemungkinan mengartikulasikan advokasi yang lebih lantang terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam gerakan advokasi hak asasi manusia di Indonesia. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Marilah kita awali dengan bahasan mengenai tempat hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional, sebelum kita memasuki bahasan pokok tulisan ini. Tidak berbeda dengan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional; bersama-sama dengan hak-hak sipil dan politik ia menjadi bagian dari the international bill of human rights. Sebagai bagian dari international bill of human rights, kedudukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan demikian sangat penting dalam hukum hak asasi manusia internasional; ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat ditempatkan di bawah hak-hak sipil dan politik -sebagaimana telah dikesankan selama ini. Pengikatan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu diwujudkan dengan mepositifikasikan hak-hak tersebut ke dalam bentuk perjanjian multilateral (treaty). Rumusannya tertuang dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya –yang dalam bahasa aslinya dikenal dengan Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 –bersama-sama dengan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Kedua kovenan ini memang dilahirkan secara bersamaan, sebagai bentuk kompromi dari pertentangan pada saat perumusannya ketika itu.4 Negara-negara yang telah menjadi pihak pada Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya itu, dengan meratifikasinya, hingga kini telah berjumlah 142 Negara.5 Tingginya tingkat ratifikasi terhadap kovenan ini menunjukkan, bahwa kovenan ini memiliki karakter universalitas yang sangat kuat. Karena ia telah diterima oleh lebih dari seratus negara. Sebagian ahli hukum hak asasi manusia internasional menganggap, perjanjian dengan karakter yang demikian ini, telah memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (international customary law);6 ia mengikat setiap negara dengan atau tanpa ratifikasi. 4 Pada saat perumusannya, para perancangnya berupaya merumuskan sebuah international bill of human rights, yang mencakup kedua kategori hak tersebut. Bukan memisahkannya ke dalam dua kovenan. Tetapi karena pertentang politik pada saat itu, yang berada dalam atmosfir Perang Dingin, akhirnya dipisahkan menjadi dua kovenan. Uraian ringkas mengenai ini dapat dibaca dalam Thomas Buergental, International Human Rights in A Nutshell (Wset Publising Co, 1995). 5 Menurut data ratifikasi yang dikeluarkan PBB, hingga tanggal 15 Juni 2000 CESCR telah diratifikasi oleh 142 Negara dan ditandatangani oleh 61 Negara. Cina merupakan negara yang terakhir (tgl 27 Oktober 1997) membuat ratifikasi terhadap kovenan ini. Lihat, Millenium Summit Multilateral Treaty Framework (New York: United Nations, 2000). 6 Argumen seperti ini diajukan dan dipertahankan oleh, di antaranya, yang paling vokal adalah Prof. Lois B. Sohn dan Browlie. Lihat Lois B. Sohn & T. Buergental, International Protection of Human Rights, 1973; dan Ian Browlie, Principles of Public International Law (New York: Oxford University Press, 1990). 2 Indonesia sampai sekarang belum menjadi pihak dari perjanjian multilateral itu. Padahal seperti diketahui, pada masa di bawah pemerintahan Orde Baru, Indonesia lah yang paling vokal berbicara mengenai pentingnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di forum-forum internasional untuk mematahkan tuduhan organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional atas keadaan hak asasi manusia di Indonesia. Sering kita dengar argumen pejabat tinggi Indonesia ketika itu, yang mengatakan bahwa Indonesia lebih mendahulukan hak-hak ekonomi ketimbang hak-hak politik. Slogannya ketika itu adalah: “pembangunan ekonomi yes!, kebebasan politik no!”. Atas dasar pandangan ini, rejim Orde Baru lalu memasung kebebasan politik warga negaranya; buruh, petani, mahasiswa dan seterusnya tidak boleh berorganisasi secara bebas dan independen. Kenyataannya, apa yang kita saksikan sekarang, pemasungan kebebasan politik tersebut tidak berhubungan dengan retorika rejim Orde Baru untuk memajukan dan menegakkan hakhak ekonomi, sosial dan budaya. Justru sebaliknya, pemasungan kebebasan politik itu, telah berakibat pada semakin memburuknya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pembahasan dari sudut legal ini menunjukkan betapa kuatnya kedudukan hakhak ekonomi, sosial dan budaya. Ia berkedudukan sama dengan hak-hak sipil dan politik. Tetapi persepsi atau pandangan yang berkembang mengenainya menunjukkan realitas yang lain, yakni memposisikannya dalam kedudukan yang tidak berimbang dengan hakhak sipil dan politik. Marilah kita periksa bagaimana persepsi umum tersebut. Persepsi Umum terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Sebuah Kritik Selama ini telah terbangun suatu persepsi populer mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. –yang telah diterima secara umum. Yaitu persepsi atau pandangan yang mengontraskan hak-hak ekonomi sosial dan budaya dengan hak-hak sipil dan politik. Kedua kategori hak ini dikontraskan secara diametral. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya digambarkan sekedar sebagai statemen politik, sementara hak-hak sipil dan politik dikatakan sebagai hak yang riil. Karena kedua kategori hak ini, yang diatur dalam masing-masing kovenan, memang menggunakan formulasi hukum yang berbeda. Kalau CESCR menggunakan formulasi “… undertakes to take steps, … to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant …”.7 Dipihak lain, ICCPR (Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik) menggunakan: “… undertakes to respect and to ensure to all induvidual within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant …”.8 Formulasi hukum yang berbeda ini dijadikan dasar untuk menarik garis pembeda yang tajam antara kedua kovenan tersebut. 7 Selengkapnya lihat pasal 2 (1) Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 8 Selengkapnya lihat pasal 2 (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. 3 Perbedaan tajam yang dibuat itu adalah dengan mengatakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak-hak positif (positive rights), sementara hak-hak sipil dan politik dikatakan sebagai hak-hak negatif (negative rights).9 Dikatakan positif, karena untuk merealisasi hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut diperlukan keterlibatan negara yang besar. Negara di sini haruslah berperan aktif. Sebaliknya dikatakan negatif, karena negara harus abstain atau tidak bertindak dalam rangka merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam kovenan. Peran negara di sini haruslah pasif. Makanya hak-hak negatif itu dirumuskan dalam bahasa “freedom from” (kebebasan dari), sedangkan hakhak dalam kategori positif dirumuskan dalam bahasa “rights to” (hak atas). Kedua kategori hak ini menuntut tanggung jawab negara yang berbeda. Kalau hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menuntut tanggung jawab negara --meminjam istilah yang digunakan Komisi Hukum Internasional-- dalam bentuk obligations of result, sedangka hak-hak sipil dan politik menuntut tanggung jawab negara dalam bentuk obligations of conduct. Sebagai hak-hak positif, maka hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dituntut di muka pengadilan (non-justiciable). Sebaliknya dengan hak-hak sipil dan politik, sebagai hak-hak negatif ia dapat dituntut di muka pengadilan. Misalnya, orang yang kehilangan pekerjaannya tidak dapat menuntut negara ke muka pengadilan, karena pelanggaran tersebut. Sebaliknya, orang yang disiksa oleh aparatur negara dapat dengan segera menuntut tanggung jawab negara atas pelanggaran tersebut ke muka pengadilan. Disamping membedakannya dengan cara positif dan negatif tersebut, juga dibuat perbedaan secara ideologis. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dikatakan bermuatan ideologis, sementara hak-hak sipil dan politik non-ideologis. Artinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya hanya dapat diterapkan pada suatu sistem ekonomi tertentu, sedangkan hak-hak sipil dan politik dapat diterapkan untuk semua sistem ekonomi atau pemerintahan apapun. Atau dalam kata-kata Philip Alston dan Gerald Quinn,10 “... civil and political rights are seen as essentially non-ideological in nature and are potentially compatible with most system of goverment. By contrast, economic, social and cultural rights are often perceived to be of a deeply ideological nature, to necessitate an unacceptable degree of intervention in the domestic affairs of states, and to be inherently incompatible with a free market economy”. Lebih jauh persepsi umum tersebut saya ringkas dalam bentuk tabel di bawah ini. Gambaran yang saya ringkas ini tentu merupakan penyederhanaan dari kompleksitas perbedaan yang dibuat atas kedua kategori hak tersebut. Tabel 1: Pembedaan ICESCR dan ICCPR 9 Lihat Vierdag, “The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, Netherlands Yearbook of International Law 1978, 69-105. 10 Philips Alston dan Gerald Quinn, “The Nature and Scope of States Parties Obligations under the International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, Vol 9 (May, 1987), No. 2. 4 Hak-hak Ekonomi (ICESCR) Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) Dicapai secara bertahap Dicapai dengan segera Negara bersifat aktif Negara bersifat pasif Tidak dapat diajukan ke Pengadilan Dapat diajukan ke Pengadilan Bergantung pada sumberdaya Tidak bergantung pada sumberdaya Ideologis Non-ideologis Sumber: van Hoof, The Legal Nature of Economic, Social and Cultural Rights: A Rebuttal of Some Traditional Views, 1984; Vierdag, The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1978. Dalam tinjauan yang akan dipaparkan di bawah ini akan terlihat bahwa sesungguhnya kontras yang dibuat itu hanya artifisial dan mitos belaka. Karena perbedaan tersebut tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh mengenai legal nature hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kajian-kajian mutakhir, seperti yang diprakarsai oleh Philip Alston, Asbojrn Aide, Audrey Chapman, Scott Leckie, Katarina Tomasevski (sekedar menyebut beberapa di antaranya), mengungkapkan ketidaksahihan pembedaanpembedaan tersebut. Mereka mengembangkan interpretasi dan pemahaman baru terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pandangan-pandangan mereka sangat mempengaruhi perumusan Prinsip-prinsip Limburg11 dan Pedoman Maastrict.12 Mengubah Persepsi Umum atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Marilah kita tinjauan pemahaman yang telah diterima secara umum tersebut. Apakah benar, bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu sepenuhnya merupakan 11 Prinsip-prinsip Limburg ini dirumuskan oleh para ahli hukum internasional sebagai suatu usaha untuk mengefektifkan pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dengan memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan-ketentuan CESCR. Prinsip-prinsip ini tidak mengikat secara hukum. Prinsipprinsip ini dimuat di bagian tiga buku ini. 12 Pedoman ini juga dirumuskan oleh para ahli hukum internasional yang tidak mengikat secara hukum. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memantau pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pedoman ini dimuat di bagian tiga buku ini. 5 hak-hak positif? Pemahaman demikian sebetulnya tidak benar. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak sepenuhnya merupakan hak-hak positif. Sebab cukup banyak hak-hak yang diakui di dalamnya menuntut negara agar tidak mengambil tindakan (state abstention) guna melindungi hak tersebut. Bukannya melulu mengharuskan negara aktif mengambil tindakan. Hal ini dapat kita lihat pada klausul-klausul seperti hak berserikat, hak mogok, kebebasan memilih sekolah, kebebasan melakukan riset, larangan menggunakan anak-anak untuk pekerjaan berbahaya, dan seterusnya, yang terdapat di dalam CESCR. Ketentuan-ketentuan itu menunjukkan dengan gamblang, bahwa yang diatur di dalam CESCR bukan hanya hak-hak dalam jenis “rights to”, tetapi juga hak-hak dalam jenis “freedom from”. Jadi mengatakan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya semata-mata merupakan hak-hak positif jelas menyesatkan. Makanya frasa undertakes to take steps, to achieve progressively dan to maximum of its available resources pada pasal 2(1) CESCR harus dilihat sebagai ketentuan yang memiliki hubungan yang dinamis dengan semua pasal lainnya.13 Hakikat kewajiban hukum yang timbul dari pasal ini bukan hanya menuntut negara berperan aktif, tetapi juga menuntut negara tidak mengambil tindakan (pasif). Makanya kurang tepat, tanggung jawab negara di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini dibedakan antara obligation of conduct dan obligation of result. Kedua kewajiban itu merupakan kewajiban yang sekaligus harus dipikul oleh negara dalam pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya, untuk mencukupi kebutuhan pangan, negara harus mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang tepat agar tujuan mencukupi pangan tersebut berhasil (obligation of result). Tetapi dalam waktu yang bersamaan, negara juga tidak diberbolehkan mengambil tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan memilih pekerjaan atau sekolah (obligation of conduct). Jadi jelas mengapa dikatakan keliru, jika tanggung jawab negara dikatakan terbatas pada obligation of result. Dalam sebuah konferensi yang diorganisir oleh International Commission of Jurist, David Matas14 --salah seorang yang terlibat dalam dalam konferensi tersebut, dengan tegas menolak pemisahan antara kedua bentuk tanggung jawab negara itu. Kita turunkan di sini pendapatnya: “Put in terms of distinction between obligations of conduct and obligations of result, the notion that economic, social and cultural rights are always and only obligations of result, and that political and civil rights are always and only obligations of conduct is false. For countries like Canada and the US all 13 Salah seorang sarjana yang memberi perhatian besar terhadap frasa-frasa kontroversial itu adalah Robert E. Robertson. Dalam tulisannya yang mengulas frasa ‘maximum available resources’, Robertson menunjukkan betapa tidak mudahnya memahami bahasa yang digunakan CESCR. Katanya, “It is a difficult phrase –two warring adjectives describing an undefined noun. ‘Maximum’ stands for idealism; ‘available’ stands for reality. ‘Maximum’ is the sword of human rights rhetoric; ‘available’ is the wiggle room for the State. Lihat, Robert E. Robertson, “Measuring State Compliance with the Obligation to Devote the “Maximum Available Resources” to Realizing Economic, Social and Cultural Rights,” Human Rights Quarterly, Vol. 16 (November 1994): Hlm.694. 14 Lihat David Matas, “Economic, Social and Cultural Rights and the Rule of Lawyers: North American Perspectives”, International Commission of Jurist: Special Issue, December 1995. 6 economic and social rights are obligations of conduct and not just obligations of result. For countries like Canada and the US, if an economic, social or cultural rights is not being realized, the reason is unwillingness and not incapacity”. Prinsip-prinsip Limburg juga menegaskan hal yang serupa. Kumpulan prinsip yang disusun oleh para ahli hukum internasional itu --yang didesain untuk memberi pedoman dalam mengimplementasikan CESCR, berusaha meletakkan arah baru dalam melihat tanggung jawab negara dalam konteks hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Yaitu dengan tidak memandangnya melulu bersifat positif. Hal ini dapat kita baca pada paragraf ke-16 Prinsip-prinsip Limburg itu. Di sana dikatakannya: “All States parties have an obligation to begin immediately to take steps towards full realization of the rights contained in the Covenant.” Selanjutnya pada paragraf ke-22, ditegaskan lagi: “Some obligations unders the Covenant require immediate implementation in full by all States parties, such as the probihation of discrimination in article 2(2) of the Covenant.” Jadi, meskipun CESCR menetapkan pencapaian secara bertahap dan mengakui realitas keterbatasan sumberdaya yang tersedia di satu sisi, pada sisi lain ia juga menetapkan berbagai kewajiban yang memiliki efek segera (immediate effect). Itu artinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak lagi dapat dilecehkan sebagai “bukan merupakan hak yang sebenarnya” alias sekedar “statemen politik”. Sama seperti hak-hak sipil dan politik, ia juga merupakan hak yang sebenarnya yang juga dapat dituntut pemenuhannya melalui pengadilan (justiciable). Terutama untuk hak-hak yang diatur pada pasal 3, 7(a) dan (i), 8, 10(3), 13(2), (3) dan (4), dan pasal 15(3). Hak-hak dalam pasal-pasal ini bersifat justiciable, yang dapat dituntut di muka pengadilan nasional masing-masing negara. Argumen maximum available resources atau progressive realization tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan pemenuhan segera hak-hak tersebut. Jadi anggapan selama ini mengenai non-justiciable dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya jelas menyesatkan. Selain tidak menyumbang apa pun bagi kepentingan advokasi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Begitu juga mengenai anggapan, bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu tidak cocok bagi semua sistem pemerintahan atau ekonomi. Karena ia ideologis! Anggapan ini juga keliru, karena hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini tidak pernah didesain untuk salah satu sistem ekonomi atau pemerintahan tertentu. Dengan kata lain, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini bersifat netral. Penjelasan mengenai netralitas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu dikuatkan oleh General Comment dari Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dikatakannya:15 Thus, in terms of political and economic sytems the Covenant is neutral and its principles cannot accurately be described as being predicated exclusively upon 15 Lihat General Comment 3, The nature of State parties obligations (Art. 2, para. 1 of the Covenant), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 (1994), para. 11. 7 the need for, or the desirability of, a socialist or a capitalist system, or a mixed, centrally planned, or laissez-faire economy, or upon any other particulary approach. In this regard, the Committee reaffirms that rights recognized in the Covenant are susceptible of realization within the context of a wide variety of economic and political systems. Dalam konteks pemahaman “baru” seperti inilah seharusnya kita memandang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Anggapan-anggapan lama yang membedakan secara diametral antara kedua kategori hak tersebut sudah selayaknya berlalu dalam cakrawala kita. Karena anggapan-anggapan itu tidak memberi sumbangan apapun bagi kepentingan advokasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Malah sebaliknya, dapat merusak upaya integritas penegakan hak-hak asasi manusia secara keseluruhan atau secara indivisible dan interdependent. Langkah pengadvokasian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan demikian harus diletakkan di atas paradigma baru tersebut. Penutup: Pentingnya Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Seperti sudah dikemukakan di awal, tulisan ini berusaha memeriksa dengan kritis anggapan-anggapan yang selama ini terbangun dalam memandang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan mengungkapkan mitos-mitos disekitar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu, kita bangun kembali suatu advokasi yang kuat untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sudah terlalu lama kita melupakan hak-hak ini! Jalan ke arah itu sebetulnya sudah dirintis. Belakangan ini semakin banyak ihtiar yang dilakukan para sarjana dan aktifis hak asasi manusia untuk memalingkan perhatian orang ke arah pengadvokasian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Mulai dari mendesak PBB merumuskan suatu Optional Protokol untuk CESCR hingga kepada upaya-upaya mengefektifkan monitoring terhadap pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Tidak kalah besar artinya, dalam keseluruhan upaya ini adalah, kajian yang dibuat oleh Sub-Komisi Hak Asasi Manusia PBB (melalu pelapor khusus-nya) mengenai impunitas dalam pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya --yang menurut saya telah menggugah perhatian orang akan semakin pentingnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kita di Indonesia barangkali bisa mulai dengan mendesakkan peratifikasian kovenan ini oleh pemerintah. Tentu saja langkah legal ini harus diikuti dengan langkah yang lain, seperti melakukan kampanye, kajian dan monitoring atas situasi hak-hak ini di Indonesia. Apalagi memang isu hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini belum begitu familiar dengan para aktifis hak asasi manusia di sini, yang lebih familiar dengan hak-hak sipil dan politik. Langkah menuju ke arah advokasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tampak menjadi tantangan yang sangat besar di Indonesia. Tapi tidak salah apabila kita mau merintisnya. Memang tak populer, tapi populer bukan alasan yang kuat untuk tidak melakukannya. *** 8 Senarai Pustaka 1. Christ Jochnick, A New Generation of Human Rights Activism (human Rights Dialogue: Carnegia Council, 1977). 2. David Matas, “Economic, Social and Cultural Rights and the Rule of Lawyers: North American Perspectives”, International Commission of Jurist: Special Issue, December 1995. 3. Jack Donnelly, Universal Declaration of Human Rights in Theory and Practice (Ithaca, NY,: Cornell University Press, 1986). 4. General Comment 3, The nature of States Parties Obligations (Art. 2, para. 1 of the Covenant), UN. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 , 1994. 5. Ian Browlie, Principles of Public International Law (New York: Oxford University Press, 1990) 6. Maurice Cranston, What Are human Rights? (London: The Bodley Head, 1973). 7. Lois B. Sohn & T. Buergental, International Protection of Human Rights, 1973. 8. Philip Alston & gerald Quinn, “The Nature and Scope of States Parties Obligations under the Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, Vol 9 (May, 1987). 9. United Nations, Millenium Summit Multilateral Treaty Framework, New York, United Nations, 2000. 10. Robert E. Robertson, “Measuring State Compliance with the Obligation to Devote the “Maximum Available Resources’” to Realizing Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quartely, Vol 16, November 1994. 11. Vierdag, “the Nature of the Rights Garnted by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Netherlands Yearbook of International Law, 1987. 9