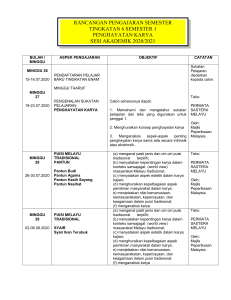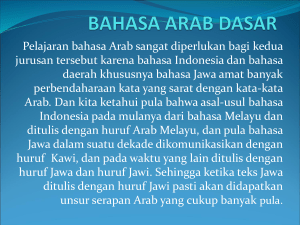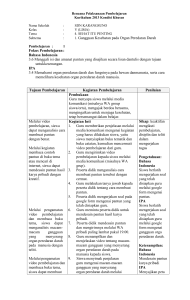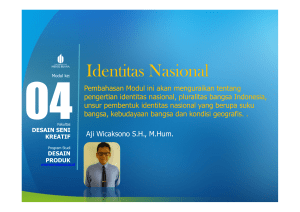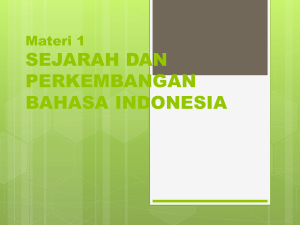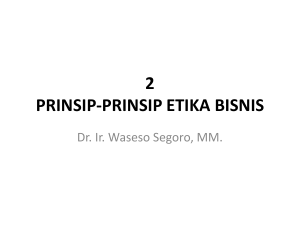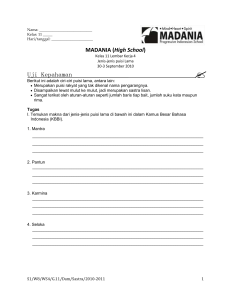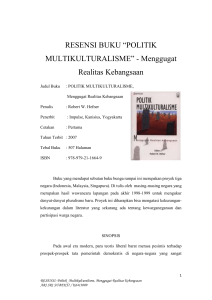Dari Ingatan ke Realitas Pemerintahan
advertisement
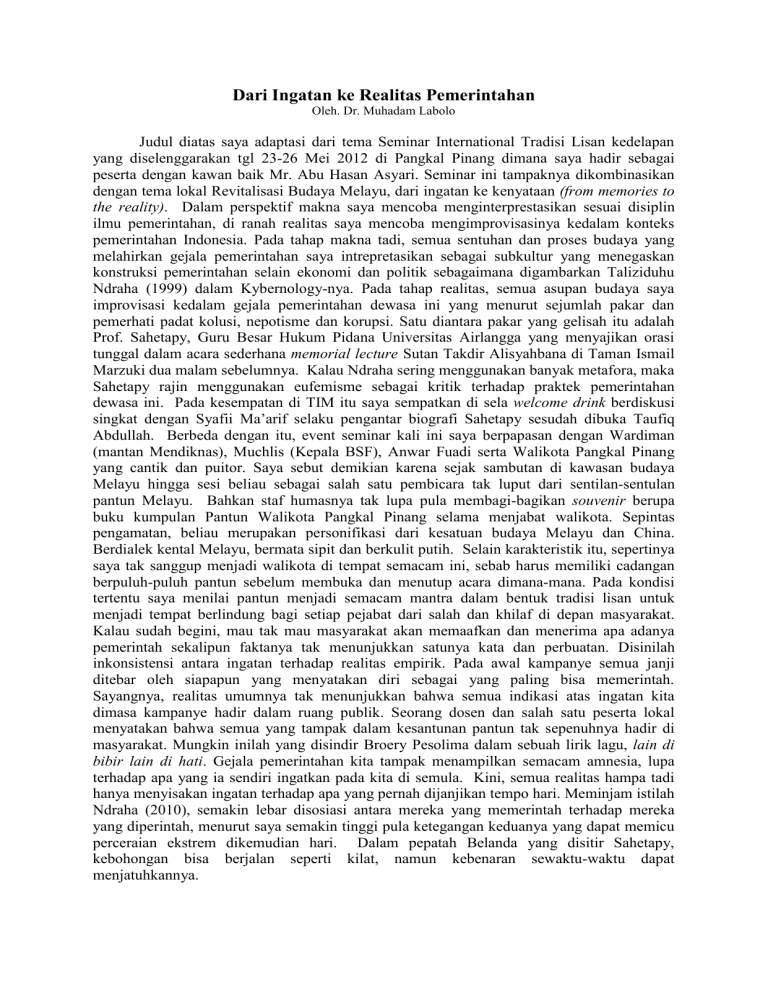
Dari Ingatan ke Realitas Pemerintahan Oleh. Dr. Muhadam Labolo Judul diatas saya adaptasi dari tema Seminar International Tradisi Lisan kedelapan yang diselenggarakan tgl 23-26 Mei 2012 di Pangkal Pinang dimana saya hadir sebagai peserta dengan kawan baik Mr. Abu Hasan Asyari. Seminar ini tampaknya dikombinasikan dengan tema lokal Revitalisasi Budaya Melayu, dari ingatan ke kenyataan (from memories to the reality). Dalam perspektif makna saya mencoba menginterprestasikan sesuai disiplin ilmu pemerintahan, di ranah realitas saya mencoba mengimprovisasinya kedalam konteks pemerintahan Indonesia. Pada tahap makna tadi, semua sentuhan dan proses budaya yang melahirkan gejala pemerintahan saya intrepretasikan sebagai subkultur yang menegaskan konstruksi pemerintahan selain ekonomi dan politik sebagaimana digambarkan Taliziduhu Ndraha (1999) dalam Kybernology-nya. Pada tahap realitas, semua asupan budaya saya improvisasi kedalam gejala pemerintahan dewasa ini yang menurut sejumlah pakar dan pemerhati padat kolusi, nepotisme dan korupsi. Satu diantara pakar yang gelisah itu adalah Prof. Sahetapy, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga yang menyajikan orasi tunggal dalam acara sederhana memorial lecture Sutan Takdir Alisyahbana di Taman Ismail Marzuki dua malam sebelumnya. Kalau Ndraha sering menggunakan banyak metafora, maka Sahetapy rajin menggunakan eufemisme sebagai kritik terhadap praktek pemerintahan dewasa ini. Pada kesempatan di TIM itu saya sempatkan di sela welcome drink berdiskusi singkat dengan Syafii Ma’arif selaku pengantar biografi Sahetapy sesudah dibuka Taufiq Abdullah. Berbeda dengan itu, event seminar kali ini saya berpapasan dengan Wardiman (mantan Mendiknas), Muchlis (Kepala BSF), Anwar Fuadi serta Walikota Pangkal Pinang yang cantik dan puitor. Saya sebut demikian karena sejak sambutan di kawasan budaya Melayu hingga sesi beliau sebagai salah satu pembicara tak luput dari sentilan-sentulan pantun Melayu. Bahkan staf humasnya tak lupa pula membagi-bagikan souvenir berupa buku kumpulan Pantun Walikota Pangkal Pinang selama menjabat walikota. Sepintas pengamatan, beliau merupakan personifikasi dari kesatuan budaya Melayu dan China. Berdialek kental Melayu, bermata sipit dan berkulit putih. Selain karakteristik itu, sepertinya saya tak sanggup menjadi walikota di tempat semacam ini, sebab harus memiliki cadangan berpuluh-puluh pantun sebelum membuka dan menutup acara dimana-mana. Pada kondisi tertentu saya menilai pantun menjadi semacam mantra dalam bentuk tradisi lisan untuk menjadi tempat berlindung bagi setiap pejabat dari salah dan khilaf di depan masyarakat. Kalau sudah begini, mau tak mau masyarakat akan memaafkan dan menerima apa adanya pemerintah sekalipun faktanya tak menunjukkan satunya kata dan perbuatan. Disinilah inkonsistensi antara ingatan terhadap realitas empirik. Pada awal kampanye semua janji ditebar oleh siapapun yang menyatakan diri sebagai yang paling bisa memerintah. Sayangnya, realitas umumnya tak menunjukkan bahwa semua indikasi atas ingatan kita dimasa kampanye hadir dalam ruang publik. Seorang dosen dan salah satu peserta lokal menyatakan bahwa semua yang tampak dalam kesantunan pantun tak sepenuhnya hadir di masyarakat. Mungkin inilah yang disindir Broery Pesolima dalam sebuah lirik lagu, lain di bibir lain di hati. Gejala pemerintahan kita tampak menampilkan semacam amnesia, lupa terhadap apa yang ia sendiri ingatkan pada kita di semula. Kini, semua realitas hampa tadi hanya menyisakan ingatan terhadap apa yang pernah dijanjikan tempo hari. Meminjam istilah Ndraha (2010), semakin lebar disosiasi antara mereka yang memerintah terhadap mereka yang diperintah, menurut saya semakin tinggi pula ketegangan keduanya yang dapat memicu perceraian ekstrem dikemudian hari. Dalam pepatah Belanda yang disitir Sahetapy, kebohongan bisa berjalan seperti kilat, namun kebenaran sewaktu-waktu dapat menjatuhkannya. Ditengah seremonial tadi saya sebenarnya tak terlalu merasa asing, sebab beberapa panitia dan peserta adalah mantan mahasiswa, kawan alumni dan rekan dosen dari berbagai universitas domestik yang pernah bertemu dalam acara Asean Folklor 2011 di Penang November tahun lalu. Sisanya para peneliti dan pakar dibidang sosiologi, antropologi, linguistik, sejarah dan sastra dari berbagai belahan dunia. Mereka bukan saja menguasai satu masalah secara spesifik namun pandai berbahasa Indonesia dan lebih dari itu bahasa lokal satu-dua di nusantara. Saya terkesan dengan pemakalah dari Perancis di sesi pleno yang membawakan topik tentang Budaya Suku Bajo di Indonesia. Saya bukan saja terkesan dengan isi orasi yang disampaikan, namun bahasa pengantar yang digunakan cukup complicated, yaitu Inggris, Indonesia dan sesekali menggunakan bahasa lokal Bugis-Bajo. Seusai acara saya gunakan kesempatan untuk berkunjung ke Pulau Penyengat bersama beberapa peserta. Pulau ini adalah pulau kecil yang menurut sejarah menjadi mahar bagi seorang putri yang diperistrikan raja setempat. Saya tidak akan menceritakan bagian ini sebab saya bukan seorang sejarawan. Bagi saya sebagai ilmuan pemerintahan hanya akan menjadikan semua realitas sejarah tersebut sebagai salah satu sumber dalam pengembangan kuliah yang bersinggungan dengan dinamika lokal, kearifan lokal, otonomi daerah, pengenalan hukum adat atau perbandingan pemerintahan lokal. Pada aspek politik lokal tentu berguna untuk menjustifikasi dan mengidentifikasi sumber-sumber kekuasaan, transisi kekuasaan, serta bagaimana pemerintahan dapat dipertahankan dalam jangka tertentu. Dalam hubungan ini saya semakin yakin bahwa kekuasaan yang direpresentasikan oleh pemerintah di tingkat lokal tak lepas dari hubungan yang bersifat diplomatik, konflik dan kawin-mawin. Ketiga faktor tadi menjadi episode terbesar dalam tradisi lisan yang disampaikan oleh guide local ketika berkunjung di sejumlah situs sejarah. Malam harinya saya dan Pak Abu Hasan, (satu-satunya ahli filsafat IPDN) yang turut mendampingi diajak makan malam oleh Mrs. Alexandria dan Mr. Mores. Keduanya berasal dari Jerman, peneliti serta dosen yang fasih berbahasa Indonesia. Sambil dinner di belakang Hotel Melia saya menikmati perdebatan sengit antara Abu Hasan dengan Mr. Mores yang bersemangat membedah asal mula masuknya kebudayaan Islam di Indonesia. Demikian menariknya diskusi tersebut, Mr. Mores yang kebetulan pernah berdomisili sementara di Jalan Kenanga samping kampus IIP Cilandak Jakarta mengajak Abu Hasan untuk meneruskan perbincangan tadi di kesempatan lain sambil membawa literatur masing-masing. Saya merasa Mr. Mores benar-benar penasaran dan tak menyangka bahwa Abu Hasan cukup menguasai sejarah masuknya Islam lengkap dengan literatur yang dipertahankan. Sebagai mantan mahasiswa pada mata kuliah filsafat pemerintahan jurusan politik pemerintahan IIP saya merasa kagum sambil menyimak bagian penting tentang motif-motif masuknya kebudayaan Islam di Indonesia. Saya ingin menimpali diskusi serius malam itu namun kuatir kekurangan referensi dari aspek sejarah Islam, maklum saya bukan ahli sejarah sebagaimana mereka bertiga. Saya sebenarnya memiliki banyak buku sejarah lokal, nusantara dan sejarah masuknya Islam, demikian pula catatan para pakar semacam Azzumardi Azra. Subuh dinihari sebelum bertolak ke Bali saya melanjutkan diskusi pendek dengan Abu Hasan bahwa kita mesti yakin dengan literatur domestik kalau tak ingin digiring oleh subjektivitas dan catatan peneliti barat yang bisa saja dibelokkan menurut kehendak dan kepentingan mereka. Terlepas dari itu kita juga mesti mengakui bahwa observasi peneliti barat terhadap kebudayaan kita jauh lebih intens dibanding peneliti kita sendiri. Saya merasa kita mesti menulis sejarah dengan nilai objektivitas tinggi agar dapat menjadi sumber literatur yang relatif dipercaya dibanding catatan para peneliti barat. Bagi kita, sejarah tak pernah bohong, kecuali penulisnya sendiri. Saya melanjutkan bahwa pendapat Abu Hasan tentang motif masuknya para pembawa risalah Islam dari Timur Tengah ke Indonesia boleh jadi bukan semata-mata untuk menyebarkan kebudayaan itu sendiri pada awalnya sebagaimana di debat oleh Mr. Mores. Saya sependapat jika penyebabnya adalah kondisi politik-pemerintahan yang tak menentu sehingga mendorong para pembawa budaya tadi mengisolasikan diri untuk menghindari konflik internal. Motif yang sama dapat kita lihat dalam catatan sejarah perjalanan Budha Gautama dan Kong Hu Tsu yang mencapai puncak pencerahan diri dikemudian hari. Saya juga berpikir mungkinkah migrasi (baca;hijrah) Nabi Muhammad dari Mekkah ke Medinah memiliki motif yang sama pada awalnya, selanjutnya berkembang kearah internalisasi nilainilai Islam dalam masyarakat Anshar. Sampai disini saya bergegas ke bandara Pangkal Pinang bersama Prof. Bani, seorang ahli linguistik dari Universitas Sebelas Maret mendahului sehari sebelum penutupan untuk mengajar DPRD Kota Tidore di Bali. Saya mengambil istrahat sejenak di pesawat Garuda karena penat menyaksikan musik tradisional Melayu asal Kelantan dan Opera China separuh malam di pinggiran pantai Kota Pangkal Pinang. (The Losari Hotel, Kuta Bali, 25 Mei 2012).