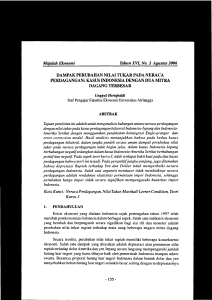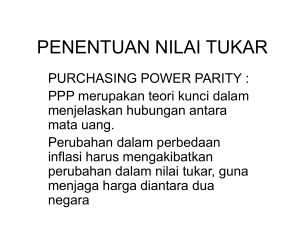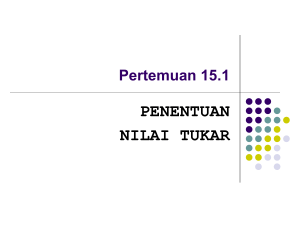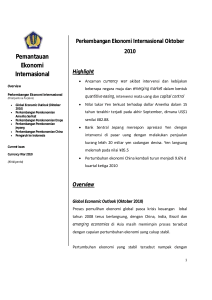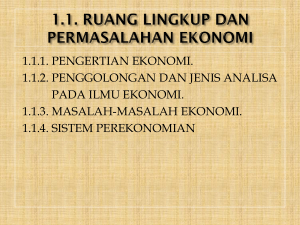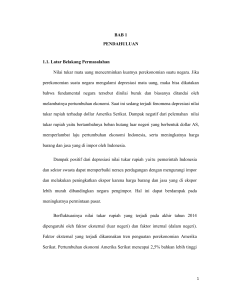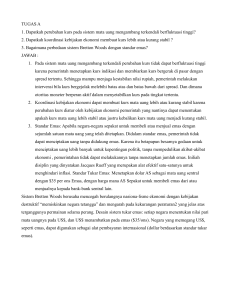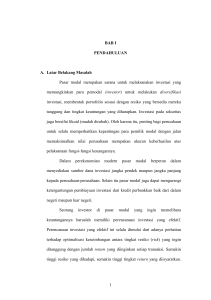Jakarta, 11 Januari 2010
advertisement

Jakarta, 24 Agustus 2015 Tiongkok Bukan Pemicu Currency Wars Dugaan China melancarkan currency wars merebak setelah yuan melemah sekitar 2,8% sepanjang Agustus 2015. Dampaknya terbukti meluas mengingat perlambatan ekonomi China -- yang diisukan sebagai pemicu currency wars – bakal menurunkan impor dari banyak negara termasuk Indonesia. Akibatnya, kecemasan itu tidak hanya terus memukul harga komoditas, energi, nilai tukar, harga obligasi negara dan saham di negara berkembang. Bahkan indeks saham S&P500 (SPX) sepekan lalu terkoreksi -5,8%, lebih dalam dibanding indeks saham negara berkembang di luar Jepang (MXAPJ) -5,7%. IHSG sendiri kembali anjlok 5,4% dengan penutupan 4335,9 sebagai angka terendah tahun ini. Lihat peraga. Kurs rupiah terus melemah mendekati 14000 per dollar. Sementara yield SUN bertenor 10 tahun mendekati 9%. Namun, berdasarkan pencermatan terhadap data moneter dan perdagangan internasional, kami menilai bukan China melainkan Jepang yang memicu perlombaan melemahkan mata uang untuk memacu ekspor sejak tiga tahun terakhir. Bagaimana penjelasannya? Nilai tukar adalah harga mata uang asing didalam mata uang domestik. Negara yang ingin memperlemah mata uangnya dapat menciptakan likuiditas yang melebihi kebutuhan di dalam negeri. Secara konvensional, penciptaan likuiditas ini dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga yang jauh lebih rendah dibanding proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara inkonvensional dilakukan melalui pembelian secara masif oleh bank sentral atas surat berharga negara dan korporasi. Aksi ini dikenal sebagai quantitative easing yang ditunjukkan oleh peningkatan rasio total asset bank sentral terhadap GDP. Ekspansi moneter yang melebihi kebutuhan kemudian dapat dipantau melalui trend penurunan rasio GDP nominal terhadap M2. GDP nominal mewakili aktivitas sektor riil yang membutuhkan likuiditas. Sedang di sisi lain, statistik moneter M2 mencerminkan akumulasi pasokan jumlah uang beredar. Rasio GDP nominal dan M2 ini dikenal sebagai velocity of money. Trend penurunan velocity of money ini menandakan pasokan uang melimpah melebihi kebutuhan. Akibatnya, harga uang menurun yang dicirikan oleh pelemahan kurs mata uang disamping inflasi. Sebetulnya Amerika Serikat sendiri menjadi biang utama currency wars sebab velocity of money sudah turun drastis sejak tahun 2000. Secara teori sebetulnya nasib dollar cenderung melemah. Namun operasi quantitative easing yang sangat masif dilakukan pemerintahan Sinzho Abe telah menyebabkan ratio total asset BoJ terhadap GDP melambung hingga 65% GDP. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding 30% baik untuk the Fed dan ECB – yang juga melakukan quantitative easing sejak akhir tahun 2014 lalu. Lihat peraga dibawah ini, total asset Bank of Japan berwarna hijau berbintik, merah untuk ECB dan biru untuk the Fed. Kami cermati velocity of money Jepang menurun jauh lebih pesat ketimbang Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, yen cenderung melemah. Selama tiga tahun terakhir, kurs yen terhadap dollar telah anjlok 35%. Ini lebih dalam dibanding kurs rupiah terhadap dollar yang melemah sebesar 31,8%. Lihat Tabel. Yang menarik, berdasarkan pengalaman 20 tahun terakhir, bursa Nikkei cenderung melesat seiring dengan pelemahan kurs yen. Indeks dollar DXY semakin menguat (super dollar) sejak pertengahan tahun 2014 setelah euro juga turut melemah menyusul aksi quantitative easing ECB sementara prospek pemulihan ekonomi masih terbatas. Dapat disimpulkan Indonesia tidak terlibat dalam currency wars walaupun BI nantinya menurunkan bunga untuk memacu pertumbuhan ekonomi. BI rate sekarang masih lebih tinggi dari proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pelemahan rupiah selama ini sendiri terjadi akibat defisit neraca berjalan menyusul kejatuhan harga komoditas primer yang masih menjadi andalan ekspor Indonesia. Kondisi defisit juga dialami negara seperti Russia, Brazil dan Malaysia yang lebih mengandalkan ekspor minyak bumi sehingga mata uang mereka lebih anjlok ketimbang Indonesia. Negara-negara inipun tidak dapat digolongkan memicu currency wars. Upaya mempertahankan mata uang dengan melakukan intervensi ternyata cenderung sia-sia bila yang terjadi adalah penguatan dollar. Contoh kasus nyata untuk ini adalah Malaysia. Seperti terlihat pada peraga dibawah ini, kurs ringgit Malaysia melemah drastis sejak pertengahan tahun lalu. Bahkan pelemahan selama tahun berjalan lebih dalam ketimbang rupiah. Upaya mempertahankan ringgit melalui intervensi pelepasan cadangan devisa nampak tidak membuahkan hasil. Cadangan devisa Malaysia terus merosot hingga menjadi $86 milyar atau lebih rendah dibanding Indonesia. Belajar dari pengalaman krisis moneter 1997 yang bermula di Thailand, Bank Indonesia sangat serius memperhatikan perkembangan ekonomi Malaysia. Apalagi Malaysia termasuk investor yang cukup besar dalam surat utang negara Indonesia. Yen Paling Kompetitif Mengingat suatu negara memiliki banyak mitra dagang dengan menggunakan mata uang berbeda, real effective exchange rate (REER) digunakan sebagai indikator daya saing. Pada dasarnya indeks ini menggabungkan berbagai kurs bilateral (seperti rupiah terhadap dollar, terhadap euro dan terhadap yen) dan kemudian disesuaikan dengan perbedaan inflasi domestik dan berbagai mitra dagang. Negara yang mata uangnya melemah dan mampu mengendalikan inflasi dinilai berpeluang menikmati peningkatan daya saing ekspor. Bank for International Settlement (semacam bank sentral untuk bank sentral) secara rutin mempublikasikan REER berbagai negara. Acuannya adalah suatu negara dinilai kompetitif bila indeks REER dibawah 100. Peraga Bloomberg berikut ini menggambarkan perkembangan REER untuk China (132,12), Indonesia (90,16), Jepang (69,07) untuk bulan Juli 2015. Kurs rupiah masih terbilang kompetitif yang berada diantara Yuan (kurang kompetitif) dan yen (sangat kompetitif). Cermati divergensi antara Yen dan Yuan terjadi sejak akhir 2012 sejalan dengan quantitative easing Bank of Japan. Menarik untuk mencermati kinerja perdagangan internasional kedua negara tersebut terhadap Amerika Serikat yang dianggap ekonomi yang paling kuat saat ini. Selama semester pertama tahun 2015 ini, Jepang mencatat surplus terhadap AS senilai $34,7 milyar yang ternyata secara tahunan tidak bertumbuh. Pada periode yang sama, surplus China mencapai $173,2 milyar dan tumbuh 15,9% YoY. Lebih lanjut, pada kelompok mesin dan alat transportasi yang secara tradisional menjadi andalan Jepang mencatat surplus $39 milyar namun turun 3,7%. Sebaliknya China menikmati surplus $100,6 milyar dan tumbuh 12,6%. Mencermati data itu nampaknya kurang beralasan bila devaluasi yuan menjadi tindakan untuk meningkatkan daya saing. Malah ada risiko Jepang terus melemahkan mata uangnya sebagai upaya untuk menaikkan kinerja ekspor. Pelemahan yuan diyakini sebagai dampak penerapan mekanisme pasar yang diminta oleh IMF. Seperti kita ketahui, China memperjuangkan yuan dimasukkan dalam mata uang internasional IMF berupa special drawing right (SDR). Mengadu Jepang dan China Prospek pemulihan dan kestabilan rupiah sendiri tetap dipengaruhi oleh keberhasilan Indonesia menurunkan defisit neraca berjalan. Sejauh ini, surplus neraca perdagangan baru dimungkinkan oleh penurunan impor yang lebih pesat. Pemerintah harus efektif memacu ekspor non-migas khususnya manufaktur padat karya ke negara maju khususnya Amerika Serikat. Selain ekspor, pemerintah harus memacu pariwisata yang lebih luas, tidak sebatas Bali dan Lombok, untuk memperkuat neraca jasa. Selain memacu ekspor dan pariwisata, Indonesia harus memanfaatkan pertarungan geo-politik regional. Boleh dibilang China dan Jepang adalah negara yang punya barang dan uang, tetapi kurang pasar. Sebaliknya kita punya pasar namun kurang barang dan uang. Ada titik temu yang harus dikelola dengan seksama agar menguntungkan Indonesia. Dapat kita saksikan pertarungan sengit antara Jepang dan China memperebutkan banyak proyek infrastruktur di Indonesia. Indonesia harus menikmati peningkatan perbaikan infrastruktur yang berkualitas yang dipasok dan dibiayai oleh pinjaman kedua negara tersebut dengan ongkos yang paling murah. Selain suku bunga, pemerintah juga perlu mempertimbangkan risiko penguatan mata uang kreditur terhadap rupiah. Peraga Bloomberg dibawah ini mengindikasikan selama 10 tahun terakhir depresiasi rupiah terhadap yuan (warna merah) jauh lebih besar ketimbang rupiah terhadap yen (coklat), walau yen cenderung lebih volatile. Dengan memanfaatkan konsep velocity of money Jepang yang terus turun, kami duga yen akan cenderung melemah. Sehingga ada pertimbangan memanfaatkan dana Jepang terlebih dengan suku bunga yang lebih rendah ketimbang penawaran China. Salam Budi Hikmat Chief Economist and Director for Investor Relation