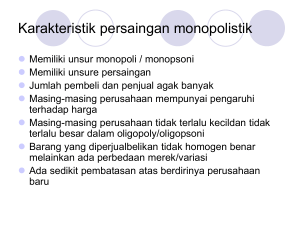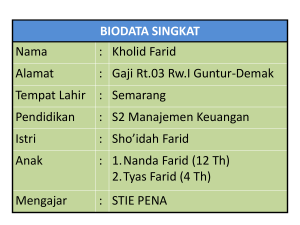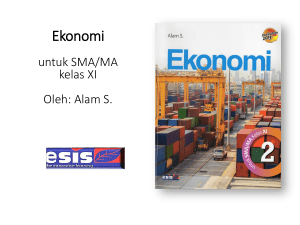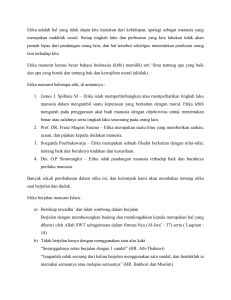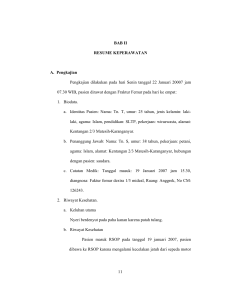Urgensi Manajemen Impor
advertisement

Urgensi Manajemen Impor Bayu Krisnamurthi Dalam konteks perdagangan internasional, masalah yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya bagaimana upaya mendorong ekspor untuk menghasilkan devisa, tetapi semakin besarnya persoalan impor berbagai produk kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal itu merupakan dampak dari globalisasi yang menuntut adanya keterbukaan ekonomi suatu negara terhadap kegiatan perdagangan antarnegara. Akan tetapi, persoalan yang muncul di sini adalah kemampuan Indonesia mengelola perdagangan agar bisa mendapatkan manfaat yang optimal masih menjadi kekuatan kita. kompas/johnny tg Padahal manajemen impor produk pertanian, terutama produk pangan memiliki urgensi yang tinggi. Mengingat kegiatan ini akan berakibat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beras, gula, dan paha ayam hanya merupakan beberapa contoh yang mengemuka akhir-akhir ini, yang memicu munculnya polemik. Pada kasus beras, impor masih terus menjadi perdebatan. Mereka yang setuju akan mengatakan bagaimana bisa harga beras yang lebih murah, termasuk dari impor karena akan menguntungkan konsumen, termasuk petani sendiri yang saat ini ditengarai merupakan netconsumers. Sebaliknya yang tidak setuju tindakan impor akhirnya akan menekan harga, sehingga petani tidak mendapat keuntungan yang memadai dan tidak memperoleh insentif yang cukup untuk mempertahankan usaha taninya. Selain itu, akan semakin memberatkan kehidupan petani dan dalam jangka panjang akan mengancam kemandirian ketahanan pangan Indonesia. Pada kasus gula, produk gula impor yang lebih murah dengan kualitas yang umumnya lebih tinggi, dipandang sangat dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga, maupun sebagai bahan baku penting berbagai kegiatan industri. Hal inilah yang menjadi dasar bagi keterbukaan terhadap impor. Di lain pihak, industri gula domestik tengah menghadapi masalah serius berkepanjangan dalam hal efisiensi dan kualitas produk industri gula dan secara langsung berhubungan pula dengan kepentingan ribuan petani tebu. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi para penentang keputusan untuk mengimpor gula. Kasus impor gula ini pun menyangkut masalah inefektivitas tarif, masalah gula "spanyol" (sedikit pakai nyolong-Red), sampai ke masalah keamanan pangan terkait dengan adanya dugaan gula industri yang tidak layak untuk dikonsumsi langsung oleh manusia, tetapi diedarkan langsung sebagai gula konsumsi. Pada kasus paha ayam, masalahnya lain lagi. Mereka yang tidak setuju impor mendasarkan pertimbangannya pada isu kehalalan produk dan perlindungan terhadap peternak dalam negeri, mengingat produk paha ayam tersebut "luar biasa" murah. Sebaliknya, yang memperbolehkan impor lebih mengkhawatirkan retaliasi oleh negara pengekspor paha ayam tersebut. Kalkulasi mereka jauh lebih besar nilai dan dampaknya bagi perekonomian, dibandingkan dengan impor paha yang hanya ''kecil'' saja nilainya. Bahkan, jika dibandingkan dengan nilai ekonomi seluruh industri peternakan ayam. *** KETIGA kasus di atas menggambarkan banyaknya kepentingan yang harus diperhatikan dalam mengelola impor. Namun, hal tersebut adalah lumrah. Manajemen aktivitas ekonomi memang merupakan ilmu dan seni untuk dapat mengambil keputusan di antara kepentingan berbagai pihak. Hal yang dibutuhkan adalah penetapan prinsip atau visi dasar terlebih dahulu dalam melakukan impor. Prinsip dan visi tersebutlah yang akan memandu langkah-langkah manajemen impor. Sebagai negara yang berdaulat, prinsip dasar impor yang dilakukan Indonesia seyogianya adalah untuk dapat menjunjung tinggi kedaulatan bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di antara pergaulan ekonomi masyarakat dunia. Artinya, Indonesia tetap memiliki kedaulatan dalam mengimpor produk yang dibutuhkannya, sehingga jika diputuskan untuk tidak mengimpor pun, maka hal tersebut dapat dilakukan tanpa berakibat buruk bagi rakyat secara keseluruhan. Kedaulatan tersebut tentu juga berarti bahwa Indonesia tidak menjadi negara yang dapat dipermainkan atau ditekan oleh negara lain, karena ketergantungan rakyatnya kepada produk impor. Hal ini sangat penting justru karena dunia sudah tidak lagi berbatas (borderless world) dan Indonesia memang ingin menjadi negara yang aktif dalam perdagangan internasional. Dengan prinsip dasar dan visi tersebut, Indonesia dapat mengembangkan manajemen impor yang lebih jelas dan tegas. Pada kasus beras, berbagai argumentasi sudah dikemukakan oleh para pakar bahwa Indonesia tidak boleh, dan tidak bisa menggantungkan kebutuhannya pada pasar internasional. Sebab, pasar internasional yang "tipis", dikuasai hanya oleh beberapa negara pengekspor saja dan bersifat residual (pasokan hanya diperoleh dari sisa produk cadangan produk negara pengekspor) telah dikemukakan sebagai alasan utama. Oleh sebab itu, Indonesia yang hingga saat ini realitasnya adalah menjadi "konsumen" dalam pasar dunia, juga harus dapat memperlakukan produk yang diimpor dari pasar internasional sebagai residual. Artinya, impor hanya akan dilakukan untuk memenuhi sebagian ceruk pasar (niche market) dalam negeri yang memang tidak dipenuhi oleh produk domestik. Ceruk pasar ini terjadi karena masalah selera khusus di antara konsumen (misalnya, untuk memenuhi selera para tamu hotel dan orang asing, atau selera beberapa konsumen di beberapa wilayah tertentu), dan bukan karena terjadinya kekurangan (shortage) produksi. Walaupun diperlukan usaha untuk menetapkan jumlah yang tepat, jumlah residual pasar beras Indonesia diperkirakan hanya akan sebesar sekitar lima persen dari total konsumsi nasional, atau sekitar 1,5 juta ton per tahun. Jika terdapat dorongan untuk mengimpor lebih dari jumlah tersebut, maka perlu dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk dalam negeri. Selain itu, juga harus mengusahakan penurunan tingkat konsumsi per kapita yang sekarang memang sudah sangat tinggi. Mengingat hal itu membutuhkan waktu, maka beberapa instrumen pengelolaan impor (import management) perlu dipergunakan. Tarif tetap merupakan instrumen utama. Tarif tersebut mungkin perlu pula dikaitkan dengan "kuota" jumlah residual tersebut. Di mana di atas "kuota" tersebut ditetapkan tarif yang lebih tinggi. Tarif dan kuota tersebut kemudian juga dapat dikaitkan dengan persyaratan karantina dan mutu beras yang diimpor, yang dikaitkan pula dengan ketersediaan fasilitas pengujian di pelabuhan tertentu. Intinya adalah perlu digunakan semua instrumen manajemen impor yang mungkin untuk dapat menjamin bahwa impor beras memang dilakukan hanya untuk mengisi ceruk pasar residual, baik dalam jumlah maupun mutu. Yang perlu pula digarisbawahi adalah bahwa format manajemen tersebut sejalan dengan ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati. Pada kasus gula, manajemen impornya tampaknya juga memiliki format yang serupa, yaitu melalui tarif, kuota, dan batasan atas kualitas produk, walaupun alasannya sedikit berbeda. Gula yang diimpor tampaknya terpaksa bukan jumlah dan jenis yang bersifat residual, tetapi karena memang sebagian dari jenis dan mutu gula yang dibutuhkan belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Untuk itu, pembatasan atas jenis gula yang diimpor perlu lebih jelas. Dalam arti, manajemen tarif atau kuota dilakukan berdasarkan jenis dan mutu tersebut. Dalam hal ini, penekanan pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk gula dalam negeri menjadi jauh lebih penting dibandingkan beras. Pada kasus paha ayam, manajemen impor perlu dilakukan dengan format yang berbeda. Hal yang perlu dikedepankan adalah masalah kualitas produk dikaitkan dengan faktor agama (kehalalan), yang juga dilindungi dalam berbagai kesepakatan perdagangan internasional. Disamping itu, isu fair trade juga perlu diperjuangkan. Adalah tidak fair, jika produk peternakan ayam yang dikelola oleh para peternak kecil harus bersaing dengan produk sisa (secondary option product). Yang tentunya harganya sangat luar biasa murah, karena bagi produsennya adalah masalah karena harus mengeluarkan biaya untuk membuangnya. Jika praktik dumping saja bisa digugat, maka kita dan mitra dagang kita harus bisa membuktikan bahwa untuk paha ayam bukan merupakan kasus perdagangan, tapi merupakan produk sisa yang juga tidak dibenarkan dalam kerangka fair trade. Beberapa pemikiran di atas tentulah baru merupakan ide-ide yang harus dibahas lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apa pun yang akan diputuskan, tampaknya urgensi adanya manajemen impor yang jelas dan tegas sudah sangat mendesak. Disamping bahwa apa pun yang akan dilakukan dalam manajemen impor, hal tersebut harus terkait erat dan menjadi bagian integral dengan usaha yang akan dilakukan pada sisi produksi dalam negeri. Namun, tampaknya persyaratan utama keberhasilan manajemen impor tersebut adalah bebasnya keputusan dan instrumen impor dari praktik korupsi dan kolusi yang jahat dan merusak itu. Untuk urusan yang satu ini, bukan hanya Presiden yang malu, karena Indonesia selalu impor pangan, tapi kita semua wajib malu. Sebab, ketidakmampuan menerapkan manajemen impor, tetap merupakan akibat dari ketidakberdayaan kita mengatasi kelakuan buruk sebagian kecil dari bangsa ini. Semua itu telah menimbulkan biaya kerugian yang besar bagi masa depan bangsa ini. (Penulis, Direktur Pusat Studi Pembangunan IPB) Urgensi Manajemen Impor Bayu Krisnamurthi Dalam konteks perdagangan internasional, masalah yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya bagaimana upaya mendorong ekspor untuk menghasilkan devisa, tetapi semakin besarnya persoalan impor berbagai produk kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal itu merupakan dampak dari globalisasi yang menuntut adanya keterbukaan ekonomi suatu negara terhadap kegiatan perdagangan antarnegara. Akan tetapi, persoalan yang muncul di sini adalah kemampuan Indonesia mengelola perdagangan agar bisa mendapatkan manfaat yang optimal masih menjadi kekuatan kita. kompas/johnny tg Padahal manajemen impor produk pertanian, terutama produk pangan memiliki urgensi yang tinggi. Mengingat kegiatan ini akan berakibat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beras, gula, dan paha ayam hanya merupakan beberapa contoh yang mengemuka akhir-akhir ini, yang memicu munculnya polemik. Pada kasus beras, impor masih terus menjadi perdebatan. Mereka yang setuju akan mengatakan bagaimana bisa harga beras yang lebih murah, termasuk dari impor karena akan menguntungkan konsumen, termasuk petani sendiri yang saat ini ditengarai merupakan netconsumers. Sebaliknya yang tidak setuju tindakan impor akhirnya akan menekan harga, sehingga petani tidak mendapat keuntungan yang memadai dan tidak memperoleh insentif yang cukup untuk mempertahankan usaha taninya. Selain itu, akan semakin memberatkan kehidupan petani dan dalam jangka panjang akan mengancam kemandirian ketahanan pangan Indonesia. Pada kasus gula, produk gula impor yang lebih murah dengan kualitas yang umumnya lebih tinggi, dipandang sangat dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga, maupun sebagai bahan baku penting berbagai kegiatan industri. Hal inilah yang menjadi dasar bagi keterbukaan terhadap impor. Di lain pihak, industri gula domestik tengah menghadapi masalah serius berkepanjangan dalam hal efisiensi dan kualitas produk industri gula dan secara langsung berhubungan pula dengan kepentingan ribuan petani tebu. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi para penentang keputusan untuk mengimpor gula. Kasus impor gula ini pun menyangkut masalah inefektivitas tarif, masalah gula "spanyol" (sedikit pakai nyolong-Red), sampai ke masalah keamanan pangan terkait dengan adanya dugaan gula industri yang tidak layak untuk dikonsumsi langsung oleh manusia, tetapi diedarkan langsung sebagai gula konsumsi. Pada kasus paha ayam, masalahnya lain lagi. Mereka yang tidak setuju impor mendasarkan pertimbangannya pada isu kehalalan produk dan perlindungan terhadap peternak dalam negeri, mengingat produk paha ayam tersebut "luar biasa" murah. Sebaliknya, yang memperbolehkan impor lebih mengkhawatirkan retaliasi oleh negara pengekspor paha ayam tersebut. Kalkulasi mereka jauh lebih besar nilai dan dampaknya bagi perekonomian, dibandingkan dengan impor paha yang hanya ''kecil'' saja nilainya. Bahkan, jika dibandingkan dengan nilai ekonomi seluruh industri peternakan ayam. *** KETIGA kasus di atas menggambarkan banyaknya kepentingan yang harus diperhatikan dalam mengelola impor. Namun, hal tersebut adalah lumrah. Manajemen aktivitas ekonomi memang merupakan ilmu dan seni untuk dapat mengambil keputusan di antara kepentingan berbagai pihak. Hal yang dibutuhkan adalah penetapan prinsip atau visi dasar terlebih dahulu dalam melakukan impor. Prinsip dan visi tersebutlah yang akan memandu langkah-langkah manajemen impor. Sebagai negara yang berdaulat, prinsip dasar impor yang dilakukan Indonesia seyogianya adalah untuk dapat menjunjung tinggi kedaulatan bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di antara pergaulan ekonomi masyarakat dunia. Artinya, Indonesia tetap memiliki kedaulatan dalam mengimpor produk yang dibutuhkannya, sehingga jika diputuskan untuk tidak mengimpor pun, maka hal tersebut dapat dilakukan tanpa berakibat buruk bagi rakyat secara keseluruhan. Kedaulatan tersebut tentu juga berarti bahwa Indonesia tidak menjadi negara yang dapat dipermainkan atau ditekan oleh negara lain, karena ketergantungan rakyatnya kepada produk impor. Hal ini sangat penting justru karena dunia sudah tidak lagi berbatas (borderless world) dan Indonesia memang ingin menjadi negara yang aktif dalam perdagangan internasional. Dengan prinsip dasar dan visi tersebut, Indonesia dapat mengembangkan manajemen impor yang lebih jelas dan tegas. Pada kasus beras, berbagai argumentasi sudah dikemukakan oleh para pakar bahwa Indonesia tidak boleh, dan tidak bisa menggantungkan kebutuhannya pada pasar internasional. Sebab, pasar internasional yang "tipis", dikuasai hanya oleh beberapa negara pengekspor saja dan bersifat residual (pasokan hanya diperoleh dari sisa produk cadangan produk negara pengekspor) telah dikemukakan sebagai alasan utama. Oleh sebab itu, Indonesia yang hingga saat ini realitasnya adalah menjadi "konsumen" dalam pasar dunia, juga harus dapat memperlakukan produk yang diimpor dari pasar internasional sebagai residual. Artinya, impor hanya akan dilakukan untuk memenuhi sebagian ceruk pasar (niche market) dalam negeri yang memang tidak dipenuhi oleh produk domestik. Ceruk pasar ini terjadi karena masalah selera khusus di antara konsumen (misalnya, untuk memenuhi selera para tamu hotel dan orang asing, atau selera beberapa konsumen di beberapa wilayah tertentu), dan bukan karena terjadinya kekurangan (shortage) produksi. Walaupun diperlukan usaha untuk menetapkan jumlah yang tepat, jumlah residual pasar beras Indonesia diperkirakan hanya akan sebesar sekitar lima persen dari total konsumsi nasional, atau sekitar 1,5 juta ton per tahun. Jika terdapat dorongan untuk mengimpor lebih dari jumlah tersebut, maka perlu dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk dalam negeri. Selain itu, juga harus mengusahakan penurunan tingkat konsumsi per kapita yang sekarang memang sudah sangat tinggi. Mengingat hal itu membutuhkan waktu, maka beberapa instrumen pengelolaan impor (import management) perlu dipergunakan. Tarif tetap merupakan instrumen utama. Tarif tersebut mungkin perlu pula dikaitkan dengan "kuota" jumlah residual tersebut. Di mana di atas "kuota" tersebut ditetapkan tarif yang lebih tinggi. Tarif dan kuota tersebut kemudian juga dapat dikaitkan dengan persyaratan karantina dan mutu beras yang diimpor, yang dikaitkan pula dengan ketersediaan fasilitas pengujian di pelabuhan tertentu. Intinya adalah perlu digunakan semua instrumen manajemen impor yang mungkin untuk dapat menjamin bahwa impor beras memang dilakukan hanya untuk mengisi ceruk pasar residual, baik dalam jumlah maupun mutu. Yang perlu pula digarisbawahi adalah bahwa format manajemen tersebut sejalan dengan ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati. Pada kasus gula, manajemen impornya tampaknya juga memiliki format yang serupa, yaitu melalui tarif, kuota, dan batasan atas kualitas produk, walaupun alasannya sedikit berbeda. Gula yang diimpor tampaknya terpaksa bukan jumlah dan jenis yang bersifat residual, tetapi karena memang sebagian dari jenis dan mutu gula yang dibutuhkan belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Untuk itu, pembatasan atas jenis gula yang diimpor perlu lebih jelas. Dalam arti, manajemen tarif atau kuota dilakukan berdasarkan jenis dan mutu tersebut. Dalam hal ini, penekanan pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk gula dalam negeri menjadi jauh lebih penting dibandingkan beras. Pada kasus paha ayam, manajemen impor perlu dilakukan dengan format yang berbeda. Hal yang perlu dikedepankan adalah masalah kualitas produk dikaitkan dengan faktor agama (kehalalan), yang juga dilindungi dalam berbagai kesepakatan perdagangan internasional. Disamping itu, isu fair trade juga perlu diperjuangkan. Adalah tidak fair, jika produk peternakan ayam yang dikelola oleh para peternak kecil harus bersaing dengan produk sisa (secondary option product). Yang tentunya harganya sangat luar biasa murah, karena bagi produsennya adalah masalah karena harus mengeluarkan biaya untuk membuangnya. Jika praktik dumping saja bisa digugat, maka kita dan mitra dagang kita harus bisa membuktikan bahwa untuk paha ayam bukan merupakan kasus perdagangan, tapi merupakan produk sisa yang juga tidak dibenarkan dalam kerangka fair trade. Beberapa pemikiran di atas tentulah baru merupakan ide-ide yang harus dibahas lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apa pun yang akan diputuskan, tampaknya urgensi adanya manajemen impor yang jelas dan tegas sudah sangat mendesak. Disamping bahwa apa pun yang akan dilakukan dalam manajemen impor, hal tersebut harus terkait erat dan menjadi bagian integral dengan usaha yang akan dilakukan pada sisi produksi dalam negeri. Namun, tampaknya persyaratan utama keberhasilan manajemen impor tersebut adalah bebasnya keputusan dan instrumen impor dari praktik korupsi dan kolusi yang jahat dan merusak itu. Untuk urusan yang satu ini, bukan hanya Presiden yang malu, karena Indonesia selalu impor pangan, tapi kita semua wajib malu. Sebab, ketidakmampuan menerapkan manajemen impor, tetap merupakan akibat dari ketidakberdayaan kita mengatasi kelakuan buruk sebagian kecil dari bangsa ini. Semua itu telah menimbulkan biaya kerugian yang besar bagi masa depan bangsa ini. (Penulis, Direktur Pusat Studi Pembangunan IPB)