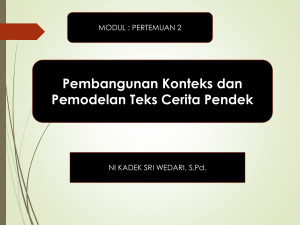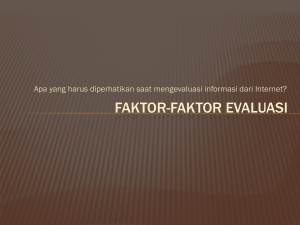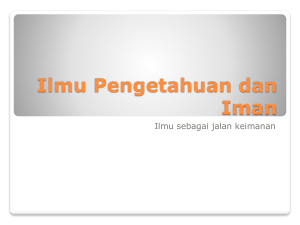teori sastra islam dalam pandangan taufiq al-hakim
advertisement
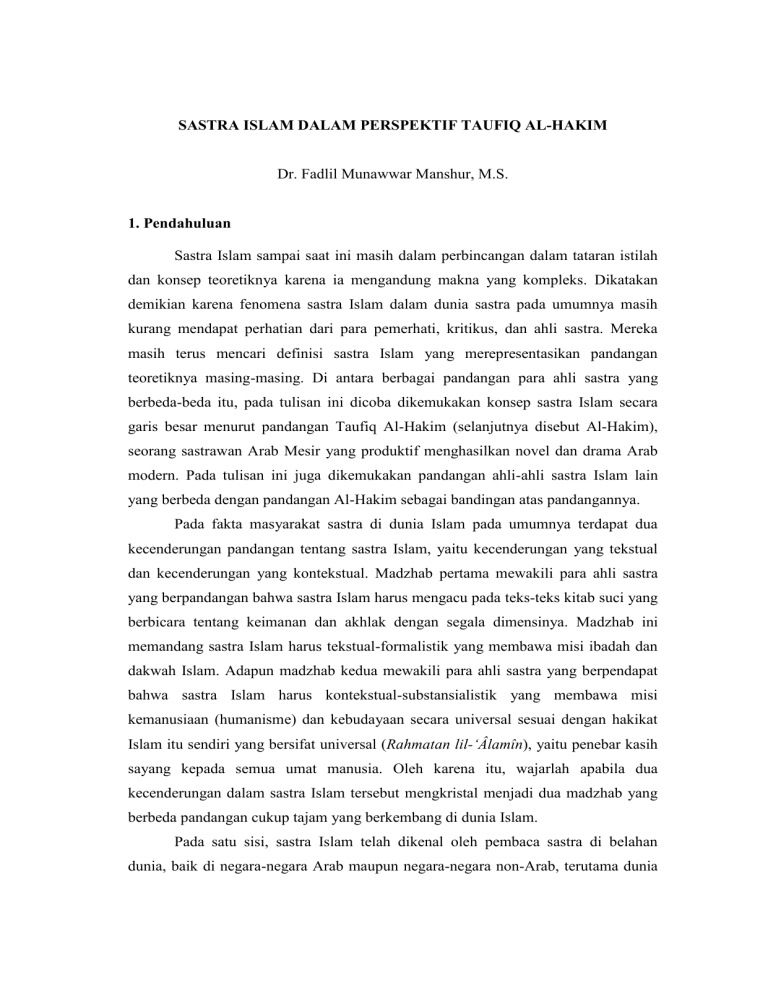
SASTRA ISLAM DALAM PERSPEKTIF TAUFIQ AL-HAKIM Dr. Fadlil Munawwar Manshur, M.S. 1. Pendahuluan Sastra Islam sampai saat ini masih dalam perbincangan dalam tataran istilah dan konsep teoretiknya karena ia mengandung makna yang kompleks. Dikatakan demikian karena fenomena sastra Islam dalam dunia sastra pada umumnya masih kurang mendapat perhatian dari para pemerhati, kritikus, dan ahli sastra. Mereka masih terus mencari definisi sastra Islam yang merepresentasikan pandangan teoretiknya masing-masing. Di antara berbagai pandangan para ahli sastra yang berbeda-beda itu, pada tulisan ini dicoba dikemukakan konsep sastra Islam secara garis besar menurut pandangan Taufiq Al-Hakim (selanjutnya disebut Al-Hakim), seorang sastrawan Arab Mesir yang produktif menghasilkan novel dan drama Arab modern. Pada tulisan ini juga dikemukakan pandangan ahli-ahli sastra Islam lain yang berbeda dengan pandangan Al-Hakim sebagai bandingan atas pandangannya. Pada fakta masyarakat sastra di dunia Islam pada umumnya terdapat dua kecenderungan pandangan tentang sastra Islam, yaitu kecenderungan yang tekstual dan kecenderungan yang kontekstual. Madzhab pertama mewakili para ahli sastra yang berpandangan bahwa sastra Islam harus mengacu pada teks-teks kitab suci yang berbicara tentang keimanan dan akhlak dengan segala dimensinya. Madzhab ini memandang sastra Islam harus tekstual-formalistik yang membawa misi ibadah dan dakwah Islam. Adapun madzhab kedua mewakili para ahli sastra yang berpendapat bahwa sastra Islam harus kontekstual-substansialistik yang membawa misi kemanusiaan (humanisme) dan kebudayaan secara universal sesuai dengan hakikat Islam itu sendiri yang bersifat universal (Rahmatan lil-‘Âlamîn), yaitu penebar kasih sayang kepada semua umat manusia. Oleh karena itu, wajarlah apabila dua kecenderungan dalam sastra Islam tersebut mengkristal menjadi dua madzhab yang berbeda pandangan cukup tajam yang berkembang di dunia Islam. Pada satu sisi, sastra Islam telah dikenal oleh pembaca sastra di belahan dunia, baik di negara-negara Arab maupun negara-negara non-Arab, terutama dunia Barat dan dunia Islam pada umumnya. Pengenalan pembaca sastra terhadap sastra Islam, terutama karya-karya sastra Arab yang bernafas Islam, dapat dilihat pada puisi (kasidah) dan novel Arab terkenal, bahkan masuk dalam kategori masterpiece, misalnya, antara lain, Kasidah Burdah dan kisah Alfu wa Laylah. Kedua karya sastra Arab-Islam ini telah banyak mengilhami kelahiran karya sastra dunia sehingga mendapat resepsi dan apresiasi yang luar biasa dari pembaca-pembaca sastra di dunia. Pada sisi yang lain para ahli sastra saat ini masih berusaha mendefinisikan teori sastra Islam dari perspektif ontologi dan epistemologinya. Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang dilontarkan oleh para ahli sastra di Indonesia, antara lain Mohammad Diponegoro dan Muhammad Ali (1986:54), yaitu : sejauh mana sastra Islam dapat ditandai dan ditafsirkan sepanjang jalur kriteria sastra; sampai batas mana suatu karya dapat diklasifikasikan ke dalam golongan sastra Islam; di mana standar atau ciri-ciri sastra Islam; adakah sastra Islam itu ditentukan oleh temanya, strukturnya atau gaya penulisannya, logat bahasa yang dipergunakannya, imajinasi penulisnya, atau kepribadian penulisnya, atau juga lingkungan pergaulan penulisnya. 2. Permasalahan Dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut dicoba diambil benang merahnya yang dirumuskan menjadi permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana sastra Islam memotret fenomena-fenomena kejadian di dunia yang merefleksikan kenyataan kehidupan keagamaan, dan apa fungsi sastra Islam dalam memaknai fenomena keagamaan itu. 2. Bagaimana sastra Islam mengemas rasa cinta manusia kepada Tuhannya, kepada alam semesta, dan kepada sesama manusia, serta bagaimana ia menggambarkan perputaran alam semesta dengan prinsip cinta pada keindahan. 3. Bagaimana sastra Islam mengkhususkan pandangannya hanya kepada Tuhan yang merupakan sumber dari segala sumber sesuatu yang kemudian tergambar dalam sifat-sifat Tuhan yang menjelma dalam makhluk-makhlukNya. 2 4. Bagaimana sastra Islam mengungkapan pengalaman keagamaan pengarang yang penuh makna dengan menggunakan bahasa simbolik, dan bagaimana sastra Islam diposisikan seperti agama yang berdiri di atas aturan-aturan moral. 3. Landasan Teori Dalam literatur-literatur yang terbaca terdapat beberapa istilah sastra yang berkaitan dengan ke-Islaman. Artinya, sastra Islam menurunkan derivat-derivatnya, seperti istilah sastra Islam itu sendiri yang dikemukakan oleh Baylu dan Miguel Asin (1985) dan Taufiq Al-Hakim (1972), istilah sastra keagamaan yang dikemukakan antara lain oleh Hoesin (1975:548) yang pembicaraannya difokuskan pada sejarah Nabi Muhammad saw dan cosmogony. Istilah yang terakhir ini berbicara tentang ilmu kejadian alam yang ditulis dalam bentuk puisi dan prosa yang indah. Derivat lainnya adalah istilah sastra kitab yang disampaikan, antara lain, oleh Braginsky (1998:275-276) yang bahasannya diarahkan pada karangan keagamaan yang khas ilmiah yang disusun oleh pengarang terutama untuk murid-murid pesantren dan anggota-anggota tarekat sufi. Pada keseluruhannya, sastra kitab terdiri atas karangan kitab tentang ilmu fikih, kitab tentang ilmu kalam, kitab tentang tasawuf, kitab tafsir Al-Quran, kitab tentang tajwid, dan kitab tentang nahwu atau tata bahasa Arab. Derivat berikutnya adalah istilah sastra pesantren (Manshur, 2007) yang berbicara tentang kitab-kitab keagamaan yang ditulis oleh kiai atau santri dan dikaji serta diamalkan oleh masyarakat pesantren di lingkungan masyarakat pesantren. Sastra pesantren lebih fokus pembahahsannya pada isi kitab yang diresepsi dan diproduksi oleh masyarakat pesantren, misalnya kitab yang memuat substansi fikih, ilmu kalam, tasawuf, tafsir, tajwid, atau nahwu. Jadi, sasta pesantren lebih tampak pada faktor tempat dan subjek produksinya serta fungsi keagamaannya, yaitu untuk menyebarkan akhlak dan pendidikan Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sastra keagamaan, sastra kitab, dan sastra pesantren pada hakikatnya adalah bagian dari sastra Islam. Dalam tradisi keilmuan apa pun setiap istilah mesti ada konsepnya. Konsep suatu ilmu bergantung pada nomenklatur ilmu itu. Demikian juga sastra Islam adalah suatu istilah yang konsep ilmunya bergantung pada pandangan atau penafsiran 3 seseorang terhadap Islam itu sendiri. Pada pembahasan ini diuraikan beberapa sudut pandang tentang sastra Islam. Sastra Islam dilihat dari contentnya berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam yang ditulis dengan dua cara, yaitu melalui teks nonfiksi dan teks fiksi. Contoh sastra Islam yang ditulis melalui teks nonfiksi dapat dilihat pada pandangan Norman Calder, Jawid Majoddedi, dan Andrew Ripin (2003) yang mengonsepkan bahwa kategori sastra Islam – dalam istilah sastra Barat disebut religious literature meliputi delapan unsur keilmuan Islam yang dapat menjadi sumber inspirasi lahirnya karya sastra Islam yang fiksi, yaitu (i) Al-Quran, (ii) kehidupan Muhammad saw, (iii) hadis, (iv) sejarah Islam, (v) tafsir Al-Quran, (vi) filsafat dan teologi, (vii) hukum dan ritual, dan (viii) tasawuf. Mengapa kedelapan unsur dalam tradisi keilmuan Islam ini dipandang sebagai sumber inspirasi bagi lahirnya sastra Islam, karena menurut Calder, Mojaddedi, dan Ripin, di dalam delapan unsur itu ada elemen-elemen kemanusiaan yang menjadi ciri utama sastra. Pertama, Al-Quran sebagai wahyu Allah diturunkan kepada manusia pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw yang dalam konteks ini Muhammad adalah manusia. Kedua, kehidupan Nabi Muhammad saw adalah fenomena besar dalam sejarah Islam yang tujuan kenabiannya adalah untuk semua umat manusia (Rahmatan lil-Âlamîn). Ketiga, Hadis adalah ucapan, tindakan, dan ketentuan Nabi Muhammad saw yang berisi ajaran teknis tentang beribadah yang baik dan benar yang harus dikerjakan oleh setiap manusia Muslim. Keempat, sejarah Islam adalah rekaman kejadian umat Islam yang berlangsung selama berabad-abad yang subjeknya adalah manusia-manusia Muslim yang gemilang, yang dapat dijadikan contoh bagi manusia-manusia saat ini. Kelima, tafsir Al-Quran adalah hasil pemikiran dan ijtihad para ulama Islam yang memaknai ayat-ayat Al-Quran untuk kemaslahatan manusia-manusia Muslim dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Keenam, filsafat dan teologi adalah dua cabang ilmu yang penting dalam tradisi keilmuan Islam, yang banyak melahirkan filosof dan teolog Muslim yang handal dan dihormati oleh masyarakat dunia. Ketujuh, hukum dan ritual adalah juga dua cabang ilmu yang berbicara tentang aturan-aturan dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap manusia Muslim, dan tradisi-tradisi masyarakat Muslim yang sampai saat ini masih hidup dan 4 dirasakan manfaatnya oleh sebagian kelompok manusia Muslim di belahan dunia. Kedelapan, tasawuf adalah cabang ilmu Islam yang sangat digemari oleh sejumlah besar kelompok sosial Muslim di berbagai negara, yang intinya adalah mengasah dan mendidik jiwa dan hati manusia Muslim dalam beribadah kepada Allah dan dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sastra Islam banyak membicarakan tentang kemanusiaan dalam perspektif agama Islam, yang intinya lebih mementingkan pada pemuliaan dan penghormatan terhadap pemikiran manusia dalam segala aspeknya sebagai makhluk utama ciptaan Allah. 4. Dua Madzhab Dominan dalam Sastra Islam Para ahli sastra Islam (di Indonesia, Malaysia, dan Mesir) mencoba mendefinisikan sastra Islam.menurut pandangan dan paradigmanya masing-masing yang satu sama lain berbeda. Di antara mereka adalah Sayyid Qutb (Mesir), Shahnon Ahmad (Malaysia), dan Abdurrahman Ra`fat Bâsyâ mewakili madzhab yang menyatakan bahwa ‘sastra Islam adalah sastra yang bersumber pada Allah dan berhikmah untuk manusia” (Ahmad, 1987:11, Jirâr, 1988:14). Madzhab ini disebut madzhab pertama. Konsep Sayyid Qutb dan Abdurrahman Ra`fat Bâsyâ yang mewakili madzgab pertama ini kemudian disempurnakan oleh Muhammad Qutb yang menyatakan bahwa sastra Islam adalah sastra yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan kepentingan ibadah (Ahmad, 1987:9). Karya sastra yang baik selalu mengajak pembaca untuk menjunjung tinggi norma-norma moral. Dengan demikian, sastra dianggap sebagai sarana pendidikan moral (Darma, 1995:105). Madzhab pertama ini mengisyaratkan bahwa pengarang harus Muslim atau Muslimah, nilainilai intrinsik dan tujuan penulisan karya sastranya juga harus bernafaskan moralitas Islam, yang semuanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Adapun madzhab kedua dipelopori, antara lain, oleh Kassim Ahmad (Malaysia), Mohammad Diponegoro, Muhammad Ali (Indonesia), dan Thaha Husen (Mesir) yang menyatakan bahwa sastra Islam bersifat universal meliputi pahampaham nasionalisme, sosialisme, rasionalisme, dan libralisme karena paham-paham ini pada hakikatnya adalah bagian dari ajaran Islam. Di samping itu, Islam dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mengisi dan saling 5 membutuhkan (Ahmad, 1987:19; Al-Hakim, 1972). Menurut madzhab kedua ini, sastra Islam tidak perlu dibatasi secara kaku dan ketat karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sesuai dengan hakikat Islam itu sendiri yang bersifat universal. Jadi, sasta Islam harus dilihat pada isinya yang berbicara tentang kehidupan manusia, masyarakat, dan kebudayaan Islam, bukan dinilai siapa yang menulis karya sastra itu. Bisa saja pengarangnya non-Muslim, tetapi isi karya sastranya berbicara tentang ajaran-ajaran Islam seperti kesalihan, kejujuran, keikhlasan, keberanian, dan keteladanan. Berikut ini dikemukakan dalam lintasan sejarah kebudayaan Islam, sejumlah sastrawan yang dipandang sebagai tokoh-tokoh yang memelopori penulisan karya-karya sastra Islam. Di antara para sastrawan dunia yang diketegorikan sebagai penulis sastra Islam adalah Hasan bin Tsabit, Ka’ab bin Malik, Abdullah bin Rawâhah (Jirâr, 1988:11), Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Mohammad Iqbal, Ahmad Qutb, Ali Ahmad Baktsir sampai pada Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, Hamka, dan raja penyair Indonesia, Amir Hamzah. Akan tetapi, berdasarkan madzhab pertama, nama besar seperti Thaha Husen (Mesir) tidak dimasukkan ke dalam golongan sastrawan yang menulis sastra Islam padahal ia telah banyak menulis karya masterpiece seperti “’Alâ Hamîsis-Sîrah” dan “Al-Wa’dul-Haqq”. Thaha Husen tidak dianggap sebagai sastrawan Islam karena menurut madzhab pertama, isi novel-novelnya tidak secara eksplisit-formal menggunakan simbol-simbol Islam. Demikian juga di Indonesia, ada nama besar seperti Achdiat K. Mihardja yang menulis novel kontroversialnya, “Atheis,” yang memperbandingkan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan atheisme/marxisme, tidak juga termasuk sebagai sastrawan Islam (Ali, 1986:54-55). Kenyataan tersebut menjadi persoalan besar dalam merumuskan definisi sastra Islam karena ternyata pandangan tekstualisme masih mendominasi pemaknaan sastra Islam. Jadi, sastra Islam selalu diarahkan untuk misi ibadah dan dakwah Islam. Fungsi sastra untuk menghibur pembaca – seperti dalam tradisi sastra Barat menjadi tidak relevan karena aspek menghibur dipandang tidak mencerminkan misi dan dakwah Islam. Kesulitan para ahli sastra mendefinisikan sastra Islam yang memadai dan menyeluruh itu karena kedua madzhab tersebut masing-masing memiliki argumentasi yang kuat. 6 Madzhab pertama menegaskan bahwa sastra Islam harus berfungsi ibadah kepada Allah dan dakwah Islam kepada masyarakat luas. Dalam konteks ini, content sastra Islam harus bersemangat ajakan untuk mengagungkan Allah dan Rasul-Nya serta menyebarkan hasil ijtihad ulama kepada masyarakat Muslim. Jadi, dimensi ekspresif (menyangkut orang atau penulis) dipandang sangat penting karena dia harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran-ajaran Islam dan simbolsimbolnya. Madzhab ini menegaskan bahwa sastra Islam harus ditulis oleh orang Islam dan berisi tentang ajaran-ajaran Islam, baik berbentuk puisi maupun prosa. Madzhab kedua menyatakan bahwa sastra Islam itu harus dibebaskan dari simbol-simbol tekstual dan personal dalam wujud karya sastranya. Madzhab ini menegaskan bahwa sastra Islam harus dilihat secara objektif hanya dari wujud teksnya, bukan dari misi yang dibawa oleh pengarangnya karena pada hakikatnya sastra adalah apa yang terbaca dalam teks, bukan siapa yang menulis teks. Penulis atau pengarang hanyalah wadah dari isi sastra yang tidak terlalu penting. Madzhab pertama lebih tepat disebut madzhab klasik-puritanistik kerena menempatkan sastra sebagai sarana ibadah dan dakwah Islam yang berfungsi mengajak manusia untuk menjalankan ajaran-ajaran agama. Jadi, madzhab pertama ini menekankan pandangannya pada fungsi sastra Islam sebagai pengajak pada kebaikan dan kesalihan serta pencegah pada perbuatan-perbuatan buruk dan tercela. Madzhab kedua lebih tepat disebut madzhab modern-liberalistik karena bahan sastra bisa apa saja, termasuk fakta sosial umat Islam yang hidup dan berkembang di alam kemodernan. Jadi, sastra Islam itu tidak harus menyampaikan hal-hal yang baik saja sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang termaktub dalam AlQuran dan Hadis, tetapi juga mengungkapkan kelemahan, kekurangan, ketercelaan, dan keburukan masyarakat Muslim yang secara faktual memang ada dalam kenyataan sosial. Pada tulisan ini, secara partikular, dipaparkan pandangan seorang ahli sastra yang bernama Taufiq Al-Hakim (Al-Hakim) yang membahas teori sastra Islam. AlHakim (1972:74-96) menulis buku berjudul Fannul-Adab yang salah satu babnya berbicara tentang sastra dan agama (al-Adabu wad-Dîn). Intisari sastra Islam yang ditulis dalam buku tersebut berikut ini dipaparkan sesuai dengan sudut pandang dan paradigma yang dianut oleh Al-Hakim. 7 Dalam konteks perdebatan dua madzhab sastra Islam, Al-Hakim lebih cenderung mensintesiskan madzhab pertama dan madzhab kedua, yaitu sastra Islam tetap bersumber pada Allah, berdimensi ibadah, dan bermisi dakwah Islam. Akan tetapi, di sisi yang lain sastra Islam juga harus modern dan liberal yang tidak perlu terikat secara kaku dengan aspek-aspek formalistik-tekstual. Jadi, sastra Islam itu harus berdimensi Ilahiah sekaligus kontekstual. Oleh karena itu, berikut ini dikemukakan pandangan Al-Hakim tentang sumber-sumber sastra Islam beserta ilustrasi-ilustrasi simbolisnya. 5. Sumber Sastra Islam Menurut Taufik al-Hakim, terdapat hubungan antara sastra dan Islam karena sastra dan Islam muncul dari tempat yang satu, yaitu berasal dari Tuhan Yang Mahatinggi yang memenuhi hati manusia dengan ketenangan, kesucian, dan keimanan. Sesungguhnya asal keindahan dalam sastra adalah perasaan yang tinggi, yang melingkupi jiwa manusia. Oleh karena itu, sastra berlaku seperti agama yang berdiri di atas aturan-aturan moral (Al-Hakim, 1972). Pandangan al-Hakim tersebut tentu tidak berarti mewakili seluruh ahli sastra. Sejak dahulu selalu terjadi pertentangan antara sastra yang berlandaskan moral dan sastra yang bebas dari urusan moral. Keindahan dalam sastra berlandaskan pada prinsip kemampuan menggambarkan hal-hal yang jelek dan hina tidak lebih rendah dari penggambaran tentang kebaikan dan kemuliaan. Al-Hakim adalah orang yang sangat memegang prinsip kebebasan dalam sastra dan memahami pentingnya sebuah kebebasan. Ia tidak menggambarkan sastra dalam hal-hal hina seperti menggambarkan yang mulia, dan ia juga tidak memunculkan hal-hal buruk seperti menggambarkan kebaikan. Demikian halnya agama Islam, saat diturunkan memberi gambaran kepada manusia tentang keburukan orang-orang musyrik, dosa orang-orang kafir, dan kejelekan orang-orang jahat pelaku kerusakan, sebagaimana memaparkan kepada manusia kemuliaan orang-orang mukmin, kebaikan orang-orang saleh. Akan tetapi, tujuannya bukanlah sekadar penggambaran tentang kebebasan, melainkan sebenarnya menggambarkan perasaan jiwa manusia tentang moral. Moralitas itu merupakan wujud keberagamaan manusia yang tercermin dalam sastra. Dalam hal 8 ini, agama Islam bertanggung jawab dan berfungsi mengawasi sastra. Jadi, karya sastra yang baik selalu memberi pesan kepada pembaca untuk berbuat baik. Pesan ini kemudian dinamakan “moral”, yaitu karya sastra yang baik selalu mengajak pembaca untuk menjunjung tinggi norma-norma moral. Dengan demikian, sastra dianggap sebagai sarana pendidikan moral (Darma, 1995:105). Selanjutnya, dalam konteks hubungan sastra dengan Islam bagaimana tanggung jawab sastra dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Apakah karya mungkin sastra itu dibuat sebebas dan semaunya yang tidak terikat dengan moral kemanusiaan ? Intensi para ahli sastra tentang baik atau buruk, apakah tidak dikedepankan atau dibelakangkan dalam penilaian sebuah karya sastra ?. Betulkah intensi pengarang tidak memiliki nilai dalam karya sastra ?. Semangat moralitas bagi para sastrawan harus tumbuh bersamaan dengan kepandaiannya dan dalam hal tertentu mencerminkan perilakunya. Sesungguhnya, sastra yang tidak bermoral dalam segala aspeknya akan menurunkan nilai karya sastra itu sendiri. Hal ini didasarkan pada satu asumsi bahwa sastra yang bernilai tinggi seharusnya membekas dalam jiwa, tetapi sebaliknya tidak membekas di hati pembaca sebagai perasaan mulia dan penuh kasih sayang. Jika diciptakan sebuah karya sastra yang menggambarkan bentuk pelanggaran aturan atau penghalalan sesuatu yang diharamkan, maka itu berarti sastra telah memberi andil dalam kemerosotan moral. Jika pandangan ini menjadi kecenderungan umum, maka sangat mungkin pandangan dan perilaku masyarakat akan mengikuti arus sastra seperti ini (Al-Hakim, 1972). Pada sisi yang lain Al-Hakim menyoroti hakikat sastra yang hidup di tengahtengah masyarakat. Menurut pandangannya, sastra Islam tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan, memberi nasihat, atau memberi petunjuk ke arah jalan yang benar, tetapi ia juga menciptakan sesuatu menjadi hidup dan berakar sehingga berkesan di hati dan pikiran manusia. Masalahnya adalah apakah sastra sebagai petunjuk ke arah yang benar itu membatasi bentuk sastra. Sebuah karya sastra, baik itu puisi maupun prosa akan terasa sebagai sebuah karya yang tinggi yang berisi pemikiran cemerlang. maka dalam hal ini, keberadaan pengarangnya menonjol di depan sastra. Dalam hal ini, keberadaan pengarang menjadi menonjol dalam penciptaan karya sastra. Jika 9 dalam karya sastra tidak ada pembaruan pemikiran, kecuali hanya berisi selera rendah, maka pengarang dan karyanya di hadapan sastra adalah juga rendah. Menurut al-Hakim, karya sastra Islam yang baik adalah yang berisi perasaan sempurna pengarang yaitu yang diungkapkan melalui gaya bahasa dan struktur ceritanya yang baik. Sebaliknya, lemahnya isi dan gaya bahasa serta struktur cerita akan mengecewakan hati pembacanya yang pada gilirannya sastra menafikan keteraturan dan kerapian. Al-Hakim juga memandang bahwa masalah sastra juga adalah masalah agama Islam. Pemuka agama yang berada di jalan yang lurus yang mencipta karya sastra dengan gaya bahasa yang indah selayaknya memberi kesan di hati pembacanya, jika tidak demikian, maka akan terjadi benturan antara tujuan dan jalan hidupnya. Jika sastrawan tidak mengetahui pentingnya sebuah garis kehidupan yang lurus, maka wahyu dapat menuntunnya agar karya sastra yang diciptanya tidak keluar dari garis wahyu itu. Para sastrawan yang tertuntun itu oleh wahyu itu (AlHakim menyebutnya sebagai “orang-orang suci”) akan melahirkan kecerdasan intelektual yang luar biasa. Dalam konteks ini, Al-Hakim menegaskan bahwa sastra dan Islam bersumber dari Tuhan karena Ia adalah sumber dari segala sumber. Dengan demikian, sastra dalam perspektif Islam harus bersumber dari nilai-nilai agama. Untuk mengetahui konsep sastra Islam menurut perspektif Al-Hakim beserta ilustrasi-ilustrasi simbolisnya, berikut ini dikemukakan simbol-simbol yang dapat menjadi sumber tematis sastra Islam. a. Simbol Pertama : “Air Kehidupan” Pada bagian ini Al-Hakim mengilustrasikan simbol ‘air kehidupan’ dengan cerita-cerita. Ada seorang Yahudi bernama Yasu’ yang keletihan berjalan meminta air minum kepada perempuan, namanya Samirah, yang selama ini mereka tidak pernah berinteraksi. Keengganan Samirah untuk memberikan air dijawab oleh Yasu’, “Jika kamu mengerti pemberian Allah, siapa pun yang berkata kepadamu, memintamu untuk berbagi, berikanlah untuk diminum! Sesungguhnya air telah memberimu kehidupan”. Yasu’ yang menganggap dirinya lebih baik dari bapak Samirah (juga Yusuf), Yakub, melanjutkan, “Semua yang minum air ini karena 10 kehausan, namun siapa yang meminum air pemberianku, kembali muncul di sana mata air, muncul hingga kehidupan padang pasir”. Yasu’ kemudian menjelaskan bahwa jumlahnya mungkin masih sedikit orang yang hilang hausnya karena meminum air dari sumur ini, dan muncullah dari situ air kehidupan, padahal, jutaan orang haus selalu ada di setiap masa. Sesungguhnya setiap orang di kedua sisinya terdapat sumur yang dalam. Ia telah melihat ada orang yang melemparkan timba emas ke sumurnya, lalu timba itu tidak menemukan apaapa di dasar sumur selain kekeringan; ada orang yang melemparkan timba kecerdasan, lalu timba itu tidak menemukan apa-apa di dasar sumur selain butiran kerikil. Al-Hakim mengutip cerita tersebut dari Kitab Injil (Al-Hakim, 1972). Air kehidupan dan timba untuk mencapainya sebenarnya tidak ada di setiap hati, tetapi berada di hati yang telah beroleh keberkahan dari langit. Kadang kita tidak merasakan kehadirannya meski telah melingkupi kita karena nikmat ini tidak dapat dilihat oleh semua mata. Contoh lain yang dikemukakan Al-Hakim ialah seorang tukang kayu yang bekerja sepanjang hari, memperoleh keuntungan harian, hidupnya senang, di rumahnya penuh sukacita dan nyanyian, dan tidurnya pulas dan tenang sampai pagi. Di sebelah rumahnya ada seorang lelaki kaya yang memperhatikan keadaannya, ia letih dan berkata dalam hati bahwa bagaimana bisa si tukang kayu yang miskin dapat menikmati hidup, sedangkan ia yang kaya, tidak berhenti bekerja dan tidak dapat tidur, dan harta tidak dapat menghilangkan hausnya akan kekayaan. Kemudian ia merencanakan sesuatu bagi si tukang kayu, ia lalu melemparkan sekantung penuh emas ke rumah si tukang kayu, kemudian menanti dan mengintip apa yang akan terjadi. Sesuatu yang mengherankan terjadi; nyanyian penuh sukacita dari rumah si tukang kayu mendadak berhenti, jantung berdegup, pikirannya mulai sibuk dan kalap, tidur nyenyak mulai tersingkir berganti dengan tidak tidur sepanjang malam, dan sibuklah ia siang dan malam mengurusi harta yang ‘jatuh’ padanya; bagaimana cara memanfaatkannya dan membuatnya berkembang. Hari demi hari, malam demi malam berlalu, awan yang dahulu menetap di rumah si orang kaya kini menetap di rumah si tukang kayu; awan kesulitan yang tidak pernah beranjak; kini si tukang kayu selalu berlari menjauhi bayangan air. 11 Sumber air di sumur itu telah berkurang, dan datanglah rasa haus yang tidak pernah hilang selamanya. Pelajaran dari Yasu’ dan si tukang kayu merupakan berkah bagi setiap individu dan lembaga. Sesuatu yang tidak pernah berhenti dikerjakan merupakan tanda kehausan. Jika kita mengikuti alur kehausan ini, maka kita akan selalu bergelut dengan kekuasaan. Bila kita meminum kekuasaan, maka kita akan tetap dan terus haus. Demikian itulah air kehidupan. Sesungguhnya apa yang kita cari ada di dekat kita, hanya kita belum mengetahuinya karena tidak dapat dilihat oleh semua mata. Berkah kekayaan dan kekuasaan tidak akan pernah membuat kita tenang jika tidak dijalankan sesuai dengan moral keagamaan. b. Simbol Kedua : Hakikat yang Sempurna Pada episode ini, Al-Hakim menampilkan cerita legenda seorang filosof Cina. Pada sebuah desa di hutan belantara hidup seorang lelaki tua dengan anaknya dan seekor kuda. Suatu hari, musibah datang, kudanya menghilang entah ke mana, pun telah ditanyakan kepada tetangga tentang kehilangan itu, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Selang beberapa hari kuda tersebut kembali kepada tuannya, tetapi ia tidak sendirian, namun ia datang diiringi sekelompok kuda liar. Para tetangga gembira karena hal itu berarti nasib baik, tetapi bagi lelaki tua hal itu belum tentu sebagai nasib baik. Kemudian kuda-kuda liar itu digembalakan oleh anak lelaki tua, suatu ketika ia menaiki seekor kuda liar itu dan jatuh terjerembab ke tanah hingga kakinya patah. Para tetangga sedih dan berduka atas musibah dan nasib buruk ini, tetapi bagi lelaki tua hal itu belum tentu suatu musibah. Setahun berlalu, terjadi peperangan. Para pemuda yang ditentarakan untuk dikirim ke medan perang mayoritas meninggal dunia kecuali anak si lelaki tua yang cacat kakinya. Karena alasan inilah ia tidak pergi ke medan perang sehingga dirinya selamat dari kematian. Setiap kejadian, nasib baik atau buruk, dalam pergantian siang dan malam, manusia dengan pandangannya yang terbatas dan ingatannya yang lemah, tidak dapat melihat suatu kejadian kecuali apa yang terjadi saat ini, akibat yang tiba-tiba. Pandangan manusia juga tidak dapat merangkum semua kejadian dalam satu 12 penilaian menyeluruh karena kejadian-kejadian tersebut akan terus berlangsung, dan mata manusia tidak dapat melihat hal-hal yang ghaib. Jika manusia mampu merangkum segala kejadian yang telah ia ketahui, baik kemarin, sekarang, maupun yang akan datang; dan dapat merangkai segala kejadian dalam satu penilaian, maka akan ditemukan sesuatu yang menakjubkan. Seseorang yang kaya, membagikan harta kepada ahli warisnya, dan ahli waris ini memiliki anak-anak yang fakir. Niscaya di antara para fakir ini ada seseorang yang membuat pembaharuan. Begitulah siklus kehidupan. Suatu saat ia datang saat dibutuhkan dan saat yang lain ia akan sirna. Dari sebuah kebahagiaan akan timbul rasa duka, dan dari kedukaan akan timbul bahagia. Malapetaka tidak akan terus datang dan juga tidak pernah tak terjadi. Pada hakikatnya, sebuah perkara tidak selamanya dianggap baik ataupun buruk, karena semua hal akan terus berganti bagaikan roda yang berputar. Tidak selamanya tetap di satu tempat. Yang kita sebut nasib adalah cara pandang kita yang terbatas pada posisi kita berada dan waktu di mana kita berada. Sesungguhnya kebahagiaan dan kesedihan kita atas sebuah nasib, hanya sedikit kesabaran kita menunggu. Urusan kita hanya sebagai penonton sebuah kisah drama, kadang tertawa dan kadang menangis sesuai peran yang dimainkan oleh tokoh drama itu, tanpa harus menunggu berakhirnya cerita. Adanya sarana merasa dan mengetahui yang ada pada diri kita telah membentuk suatu keadaan yang sesuai dengan kehidupan kita yang singkat. Kita simpulkan dari setiap perkara yang terjadi berlangsung di awal dan di akhir. Kehidupan ini bukanlah sebuah episode dari serial yang panjang (Al-Hakim, 1972). Manusia yang diberikan hikmah, pada hakikatnya adalah bagaikan mata yang diberi penglihatan untuk melihat hal yang kompleks, bukan hanya sebahagian, dan terus-menerus memantau tanpa henti. Seorang sastrawan yang besar juga harus memiliki mata seperti ini yang dapat melihat hakikat kesempurnaan pada kehidupan manusia. Mata yang melihat musibah bukanlah sesuatu yang hina, kendatipun bagi manusia hal tersebut sangat menyulitkan. Oleh karena itu, hikmah jarang terjadi di bumi; karena hikmah sendiri dapat mengetahui sebuah malapetaka yang terusmenerus terjadi. Hikmah itulah yang dapat melihat hakikat yang sempurna. 13 c. Simbol Ketiga : Revolusi Akal Dalam legenda Cina, seekor kera naik ke atas langit, berceloteh dan menyombongkan diri, bertekad memperoleh kemahiran dan semua makna ‘kepandaian’. Ia merasa sebagai makhluk yang berada di tempat paling tinggi, mulai menjerit, berteriak, memberontak, dan protes. Ia tidak membawa Budha dalam memandang permasalahannya, lalu Budha pun memanggil kera, “Jika engkau benar-benar pintar seperti katamu, maka lompatilah telapak tangan kananku, jika engkau dapat melakukannya maka aku akan meletakkanmu di singgasana seperti keinginanmu, jika engkau tidak mampu, aku akan turunkan engkau ke bumi untuk menebus dosa-dosamu bertahuntahun, sebelum engkau datang lagi padaku dengan celotehanmu” (Al-Hakim, 1972). . Si kera merasa perkataan Budha itu hanya sebagai pembodohan karena ia dapat melompat ratusan langkah, dan telapak tangan Budha tidaklah lebih dari dua jengkal. Tetapi karena Budha berjanji akan menepati janjinya, kera pun menerimanya – dengan penuh percaya diri dan tenang. Budha merentangkan tangan kanannya, si kera mulai mengunyah daun ‘lotus’ dan memanjatnya, bernafas sejenak sampai dadanya terasa lapang. Kemudian ia mengumpulkan segala kekuatan dan terus melompat, terasa ada hembusan angin karena kecepatannya melompat bagaikan anak panah melesat dari busur dengan segala kekuatan angin dari kedua sayapnya. Sampailah ia di suatu tempat yang tampak lima tiang besar berdiri tegak di sana, hingga ia terpikir telah tiba di ujung dunia. Sekarang ia akan kembali menagih janji dan meminta tahta kepada Budha. Rencana dipersiapkan untuk bertemu Budha, agar tidak terjadi pertengkaran. Ia meninggalkan jejak – dengan sombong dan percaya diri ia tinggalkan sesuatu pada tiang tengah, sebagai tanda bahwa ia telah sampai di tempat itu. Si kera kemudian melompat hingga berdiri kembali di atas tangan Budha, dan meminta tahta yang telah dijanjikan. Dengan tenang Budha mengatakan bahwa ia belum beranjak dari telapak tangannya. Lantas kera menjelaskan bahwa ia telah pergi ke ujung dunia, melihat ada lima tiang yang menjulang ke langit, dan ia meninggalkan jejak di sana. Budha kemudian mengajak kera untuk melihat telapak tangan kanannya. Dengan teliti kera memperhatikannya, tampaklah ia di telapak kanan Budha itu, tidak ada (terhapus) jejak yang ia sebutkan tadi. 14 Bagi Al-Hakim, kera itu tidak lain hanyalah sebagai simbol akal manusia. Ia pintar dan giat, memiliki lompatan yang cepat, mampu dengan kecepatan geraknya memamerkan diri – menyita perhatian kita tertuju padanya, dan memupus harapanharapan kita. Kadang-kadang ia berhasil juga mengelabui kita, bahwa ia satu-satunya yang memiliki kekuatan besar. Kita pun telah melihat kecepatan mata seseorang terhadap sesuatu, membuat kita kagum. Ada dari kita yang mengikutinya, bahkan layaknya hanya dia yang patut dipercaya. Mereka yang mengikutinya tidak melihat apa-apa selain yang diperlihatkan pada mereka saja, tidak mempercayai selain hanya yang diletakkan di tangannya. Ia berteriak, mengaku adalah segalanya, tidak ada satu tempat pun yang tidak dijelajahi, mampu melompat ke semua tempat, bahkan sampai ke langit. Tetapi takdir Tuhan menggariskan bahwa kemampuannya hanya sebatas melompat dari pohon ke pohon, dan tidak untuk melompat ke awan. Secara akal (kera), ia telah mengetahui rahasia terkecil (biji-bijian), mungkin dapat melompat melewati awan, berusaha untuk sampai ke bulan, lalu melompat ke planet-planet lain, dan terus ke seantero bumi. Akan tetapi, takdir Tuhan berkata lain bahwa ia sangat bodoh untuk berpikir mengusai bumi, melompati tangan Tuhan pun ia tidak akan bisa sampai ke ujungnya, atau keluar dari arealnya, atau mengetahui apa saja yang ada di sekitarnya, atau yang ada di luarnya. Kadang-kadang akal menerima tantangan ini, dan meyakini akan menang (Al-Hakim, 1972). Adanya tangan (kekuasaan) ini cukuplah untuk menguasai pandangan yang mengandung falsafah dan ilmu. Untuk dapat mengetahui batasan-batasannya, dapat mengumpulkan tenaga dan melompat dengan kedua kaki, yang terdiri atas logika, penelitian, eksperimen, dan produksi; dengan meminta bantuan dari semua pihak yang berada di bawah kekuasaannya, berupa pandangan, angan-angan (cita-cita), pemikiran, dan ketekunan; kemudian melompat dengan lompatan yang diperhitungkan dengan asumsi bahwa ia mampu untuk sampai pada batas dunia. Akan tetapi, takdir Tuhan telah menggariskan bahwa : “Janganlah engkau gigih dengan tenaga sia-sia, jangan pula mencoba yang tidak mungkin. Engkau masih dalam genggamanku, ada titik bimbang dan titik lemahnya. Cukuplah melompat sedapatmu karena aku menciptakanmu untuk melompat seukuran itu. Aku letakkan dalam tabiatmu melompat. Janganlah engkau keluar dari tabiat yang telah aku tetapkan untukmu, jangan 15 pula menghidar dari gerakan yang telah menjadi fitrahmu. Jika engkau hanya berdiam, dan melawan tabiat yang aku inginkan agar engkau begerak dan berevolusi, berhenti melompat, maka engkau telah melawan kehendakku. Jika berlebihan dalam lompatanmu dan merasa mampu melampaui yang mustahil engkau lampaui, niscaya engkau hanya mengantarkan diri kepada kekecewaan, putus asa yang bekepanjangan, dan ejekan atas kesungguhanmu. Lihatlah pada jejak yang hilang ini! Itu semua engkau bicarakan sejak awal, yaitu berupa ilmu, pikiran, falsafah, eksperimen, dan cita-cita” (Al-Hakim, 1972). d. Simbol Keempat : Mukjizat Agama Mukjizat adalah tanda kenabian seseorang yang disyariatkan oleh Allah, yang tidak dapat direkayasa oleh manusia. Seseorang boleh menganggap dirinya dapat menyembuhkan penyakit atau dapat berhubungan dengan ruh orang-orang mati, tetapi tidak akan menganggap dirinya sebagai nabi karena tidak dapat mendatangkan mukjizat karena mukjizat merupakan syariat agama. Pada zaman dahulu, ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, tetapi ketika diminta bukti kenabiannya, mereka cukup menyiapkan sesuatu yang sederhana yang dapat dikagumi khalayak dan mengherankan. Bila disakiti, mereka akan mengarah pada hal-hal lucu yang membuat orang lain tertawa, untuk mengalihkan pandangan agar terhindar dari tiang gantungan dan cambukan (AlHakim, 1972). Pada masa khalifah Harun ar-Rasyid, ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Ketika dijajal dengan berbagai pertanyaan, ia meminta kepada Khalifah agar menjadikan mereka yang mengelilinginya sebagai pemotong jenggotnya, dan mengubah gambar kebaikan untuk Khalifah. Harun ar-Rasyid pun tertawa kemudian mengampuninya. Pada masa Khalifah al-Makmun, seseorang yang mengaku nabi pun muncul. Ketika orang-orang meminta mukjizat kepadanya, ia memperlihatkan sebilah tongkat, yang jika dimasukkan ke dalam air tongkat itu pun akan mencair. Orang-orang menganggap bahwa hal itu adalah sebuah tipuan, dan kemudian menawarkan tongkat mereka untuk dijadikannya mencair. Ia berdalih, bukankah Fir’aun berkata kepada Musa bahwa tidak menerima apa yang dilakukan Musa dengan tongkatnya, biarlah Fir’aun memberikan tongkatnya kepada Musa untuk dijadikan ular. Khalifah Makmun pun tertawa dan meninggalkannya (Al-Hakim, 1972). 16 Ada lagi seorang lain bernama Ibrahim Kalil, yang dinilai memiliki mukjizat tidak terbakar oleh api. Ketika orang-orang mau membuktikan – akan membakarnya ke dalam api, ia meminta sesuatu yang lebih ringan dari itu. Khalifah Makmun menawarkan seperti mukjizat Nabi Musa, yang tongkatnya bisa membelah laut, tangannya dimasukkannya ke kantongnya dan kemudian keluar menjadi putih. Ia merasa lebih berat dari permintaan pertama. Ditawarkan pula mukjizat Nabi Isa, yaitu menghidupkan orang mati, ia berteriak menenangkan hadirin karena ia telah mendapatkan yang lain. Lalu ia menunjuk hakim Yahya bin Aktsam untuk memukul kakinya dan kemudian menghidupkannya kembali. Hakim Yahya berkata, “Akulah yang pertama mempercayaimu, pukullah pundak orang yang tidak percaya!” Mereka pun tertawa. Selain itu, seseorang yang mengaku sebagai nabi juga oleh Khalifah Makmun dimintanya saat itu juga untuk mengadakan buah semangka, tetapi ia meminta waktu tiga hari. Ia merasa tidak mampu, dan berdalih bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam tujuh hari dan mengeluarkannya dalam tiga bulan. Ia meminta Khalifah bersabar hanya untuk tiga hari. Masalah kenabian di masa lampau adalah masalah mukjizat. Saat ini, jika ada orang yang mengaku sebagai nabi, mereka lontarkan dirinya ke bulan dan dan melayang ke angkasa, seperti buah semangka, berjalan mengelilingi alam; ini adalah tugas para ilmuwan bumi untuk menelitinya. Ilmuwan angkasa berpendapat, perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran lama tentang hal langit merupakan pemikiran yang salah. Langit adalah tempat observasi bintang dan mikroskop tidak merekam hal lain kecuali keraguan-raguan yang besar. Bulan itu sebenarnya tidak lebih dari tabung besar yang berisi gas ringan. Seseorang dapat menarik dan memikatnya pada bentuk tertentu sehingga menimbulkan semburan gas dengan kecepatan tinggi yang membuat ukuran bulan menyusut dari aslinya, menjadi seukuran semangka (Al-Hakim, 1972). Ilmuwan kimia berpendapat, hal yang terjadi itu harus dilihat kembali pada susunan bahan yang membentuk benda-benda langit, tidak diragukan bahwa bendabenda itu bisa berubah dari keras menjadi lunak, atau dari besar menjadi kecil. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melarang seseorang memiliki tabiat tertentu untuk menjalani perubahan ini. Psikolog mengatakan bahwa masalahnya tidak berkaitan 17 dengan bulan atau yang sejenisnya, seseorang yang memiliki kemampuan dan kekuatan magnetik dapat melangkah ke area yang lebih luas. Demikianlah, para ilmuwan dan peneliti dalam setiap kegiatan meneliti, menelaah, menyelidiki, serta menyimpulkan, terdapat banyak pertentangan teknis yang tersebar dalam teori-teori ilmiah, tetapi tidak ada seorang ilmuwan pun yang mengambil sifat kenabian, atau mencoba menerima adanya hubungan langsung antara seseorang dengan Allah. Mukjizat pada zaman sekarang masih menjadi bukti atas kenabian, berkembang setiap waktu dan menjadi trend. Dahulu bom atom juga dipandang sebagai “mukjizat”, tetapi sekarang sudah menjadi kuno. Masa-masa yang akan datang dijamin adanya mukjizat baru lagi, manusia dapat menerimanya dengan terkagum-kagum sesaat, kemudian meninggalkannya dan menelaah kembali sesuatu yang baru di masa mendatang. Ilmuwan kita sekarang ini masih menerima mukjizat nabi, meskipun jika hal itu ada niscaya akan dimaksukkan ke laboratorium mereka untuk diteliti, tanpa menganggapnya sebuah bukti dan tanda bahwa itu adalah langsung dari Allah. Pada zaman sekarang, sepantasnya orang menerima bahwa nabi mendapat mukjizat yang telah ditetapkan untuk dirinya. Mengapa tidak muncul lagi nabi-nabi palsu padahal rintangan-rintangan yang besar menghadang, karena yang diminta adalah mukjizat yang tersulit, yaitu hukum syariat (Al-Hakim, 1972). .Syariat yang datang dari langit cocok bagi seluruh manusia, baik di dunia maupun di akhirat, di langit dan di bumi. Syariat ini turun karena adanya pengulangan dari syariat-syariat sebelumnya. Ada sesuatu yang baru, Allah telah menetapkannya sebagai pegangan hidup manusia. Setiap mukjizat yang ada di bumi masih lebih kecil dibanding dengan mukjizat yang paling besar, yaitu agama Islam yang telah dipancarkan Allah melalui cahaya hidayah-Nya. Manusia akan mengikuti agama ini sampai hari kiamat. e. Simbol Kelima : Iman dalam Kehidupan Pada sebuah rumah sakit, seorang wanita merasa menang dalam perjuangannya melawan kematian, ia sekarang dalam kondisi pemulihan. Dalam menanti kesembuhannya, ia terus membaca, berpikir, dan merenung atas apa yang telah dialami selama ini. Ia merasa telah kehilangan sebagian imannya, 18 membayangkan bahwa kesembuhannya diselimuti kabut kegelapan dan menjulurkan tangan untuk menggapai cahaya. Wanita itu bagaikan kapal yang sedang diterjang gelombang laut, terbentur jatuh, dan keluar dari badai malam setelah dia merasakan kesakitan. Ia terombang-ambing dalam menggapai hidayah di bawah sorotan matahari di ujung menara dan pancaran fajar. Untuk menguatkan iman wanita itu, diperlukan ilmu dan pesan-pesan agama. Sesungguhnya, menara yang akan menunjukkan keimanan dalam hidup wanita itu adalah menara yang berdiri di antara dirinya, yaitu hatinya sendiri. Hati yang selalu berdenyut dalam diri seiring waktu, bagaikan gerakan kapal yang terseret dalam derasnya aliran badai. Inilah hati, mengapa harus dengan kesedihan mempertahankan hidup? Mengapa persinggahan keimanan semakin terasa sulit, bagaikan penyakit yang merusak wajah, mengkhawatirkan, dan menolak balasan ? (Al-Hakim, 1972). Wanita itu menjalani setiap langkah hidupnya dengan penuh aturan. Kekacauan malam dan siang, gerak langkah yang tidak tenang, dan detak jantungnya yang tiada reda, tidak menjadikannya bisu, justru menjadi kekuatan dalam hidupnya. Hati adalah pertahanan dalam hidup, dan akan memperjuangkan hidup dari kebatilan karena hati percaya pada hakikat kehidupan. Al-Hakim kemudian menyerukan bahwa janganlah memohon pertolongan terhadap pemikir dan jangan pula kepada para ahli filsafat, apalagi meminta pertolongan kepada burung-burung yang terbang, karena hal itu adalah cermin budi pekerti terburuk. Kekuasan Allahlah yang meletakkan iman dalam kehidupan. Secara umum dalam uraian di atas Al-Hakim berpandangan bahwa ada keterkaitan antara sastra dan agama karena muncul dari tempat yang satu. Sesungguhnya asal keindahan dalam seni adalah perasaan yang tinggi, yang melingkupi jiwa manusia saat terhubung dengan karya-karya sastra. Oleh karena itu, seyogyanya sastra itu dapat bersanding dengan agama yang berdiri di atas aturan-aturan moral. Dalam agama, orang selalu membutuhkan suatu pegangan atau pedoman yang dibawakan oleh rasul atau nabi. Dalam sastra, orang dapat menanamkan rasa khidmat kepada Tuhan untuk memberi makna kepada eksistensi manusia, meningkatkan kecerdasan dan kualitas intelektual, ataupun untuk pembinaan mental dan pengembangan wawasan budaya. 19 Seperti juga agama, sastra juga membicarakan masalah-masalah manusia. Dengan cara yang berbeda, sastra dan agama dianggap sebagai sarana untuk menumbuhkan jiwa humanitat, yaitu jiwa yang halus, manusiawi, dan berbudaya (Darma, 1995:107). Dapat dikatakan bahwa sastra dan agama memiliki objek garapan yang sama untuk tujuan yang sama, yakni mempelajari manusia untuk memanusiakan manusia. Sastra Islam dapat dipilih sebagai media dalam menyampaikan pengalaman keagamaan. Al-Hakim dalam mengemukakan pandangannya sering menggunakan anekdot-anekdot dan kisah perumpamaan atau alegori, yang sangat mempengaruhi corak kegiatan intelektualnya. Kisah Yasu’ dan perempuan Samirah, tukang kayu yang miskin dan tetangganya yang kaya, kehidupan seorang lelaki tua dan anaknya yang kehilangan seekor kuda, seeokor kera yang naik ke atas langit, kisah nabi-nabi palsu, dan seorang wanita dalam perjuangannya melawan kematian, semuanya merupakan ilustrasi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan keruhanian, yaitu menyampaikan hikmah. Sebagai seorang sastrawan, Al-Hakim meyakini bahwa karya sastra yang bermutu tinggi dapat membangunkan cinta yang tidur di dalam hati, baik cinta yang bersifat duniawi dan inderawi maupun cinta yang bersifat ketuhanan dan ruhaniah. Dengan menyampaikan pengalaman-pengalaman keagamaan yang penuh makna dan menggunakan bahasa simbolik, Al-Hakim berharap agar pembaca memperoleh pencerahan dan hikmah. Al-Hakim mengekspresikan pengalaman estetik transendental yang berhubungan erat dengan tauhid, penyaksian bahwa Tuhan itu satu. Rujukan penghayatannya adalah kitab-kitab suci agama. Sastra Islam merupakan ekspresi dari pengalaman yang mengungkapkan renungan dan falsafah hidup, bertujuan meningkatkan taraf hubungan jiwa manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, seyogyanya sastra itu berlaku layaknya agama, berdiri di atas aturanaturan moral, mengukuhkan iman sambil menjelaskan tentang hukum syariat, menggambarkan tahap-tahap atau martabat-martabat, pengenalan diri, memberi perintah tentang bahaya yang mengancam serta memberi nasihat mengenai cara-cara untuk mengatasi bahaya tersebut. Melalui uraian dan dialog-dialog tokoh dalam cerita yang ditampilkan, AlHakim menyatakan bahwa untuk mencapai kehidupan sejati, seseorang tidak dapat 20 hanya dengan melakukan usaha intelektual semata dan tidak pula dengan perasaan rindu berlebihan, tetapi juga dengan kesadaran untuk menjaga akidah, kesadaran penghambaan diri kepada Allah, dan kesadaran pada sikap tolong-menolong kepada sesama manusia. 6. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sastra Islam pada hakikatnya berbicara tentang fenomena-fenomena kejadian di dunia yang merefleksikan kenyataan kehidupan keagamaan. Artinya, sastra Islam berfungsi merefleksikan kenyataan di balik fenomena keagamaan. Salah satu fenomena keagamaan adalah rasa cinta manusia kepada Tuhannya, kepada alam semesta, dan kepada sesama manusia. Kenyataan ini menggerakkan perputaran alam semesta dengan prinsip, yaitu cinta pada kebenaran Tuhan, cinta pada kemanusiaan, dan cinta pada keindahan. Dengan begitu, sastra Islam melingkupi alam kejadian secara menyeluruh dan mengkhususkan pandangannya kepada Tuhan yang merupakan sumber dari segala sumber yang ada. Sastra Islam adalah ungkapan pengalaman keagamaan pengarang yang penuh makna dengan menggunakan bahasa simbolik. Sastra Islam bertujuan untuk : (i) mencerahkan pembaca dengan hikmah kehidupan, (ii) mengekspresikan pengalaman estetik transendental pengarang yang berhubungan erat dengan tauhid, (iii) menegaskan bahwa rujukan sastra Islam adalah Al-Quran dan Hadis, (iv) mengekspresikan dan mengungkapkan pengalaman pengarang tentang falsafah hidup, yaitu meningkatkan hubungan jiwa manusia dengan Tuhan. Sastra Islam juga menegaskan bahwa sastra itu seperti agama yang berdiri di atas aturan-aturan moral, mengukuhkan iman, memberi penjelasan tentang hukum syariat, menggambarkan martabat-martabat kemanusiaan, mengenal diri sendiri, memberi peringatan tentang bahaya yang mengancam manusia, dan memberi nasihat mengenai cara-cara untuk mengatasi bahaya yang mengancam keselamatan dan kemuliaan manusia. Sastra Islam juga dapat mengungkapkan kenyataan-kenyataan sosial yang benarbenar terjadi pada masyarakat, baik yang positif maupun yang negatif. Hal ini didasarkan pada satu asumsi bahwa kehidan masyarakat Muslim yang hanya terjadi yang baik-baik saja, tetapi juga banyak yang buruknya. Jadi, sastra Islam dapat mengungkapkan dua sisi dari kehidupan masyarakat. 21 DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Shahnon, Kassim Ahmad. 1987. Polemik Sastera Islami. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur. Ali, Muhammad. 1986. Ihwal Dunia Sastra. P.T. Bina Ilmu, Surabaya. Baylu, Shalih Adam. 1985. Min Qadhâyâ al-Adabil-Islâmy. Darul-Manarah, Jeddah. Braginsky, V.S. 1998. Yang Indah, Berfaedah dan Kamal, Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7 – 19. Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta. Calder, Norman et al. 2005. Classical Islam, A Sourcebook of Religious Literature. London and New York, Routledge. Darma, Budi. 1995. Harmonium. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Al-Hakim, Taufiq. 1972. Fannul-Adab. Dârul-Kitâbil-Lubnâny, Bayrût. Hoesin, Oemar Amin. 1975. Kultur Islam, Sejarah Perkembangan Kebudayaan Islam dan Pengaruhnya dalam Dunia Internasional. Bulan Bintang, Jakarta. Jirâr, Ma’mûn Farîz. 1988. Khashâ`ishu al-Qisshatil-Islâmiyyah. Dârul-Manârah, Jeddah. Manshur, Fadlil Munawwar. ”Kasidah Burdah Al-Bûshîry dan Popularitasnya dalam Berbagai Tradisi : Suntingan Teks, Terjemahan, dan Telaah Resepsi”. Disertasi Doktor (2007) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya. 2000. Edisi Keempat, Cetakan Pertama. Penerjemah H. Zaini Dahlan dan Azharudin Sahil. UII Press, Yogyakarta. 22 23