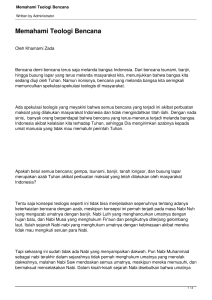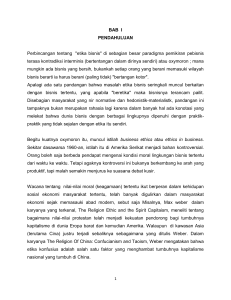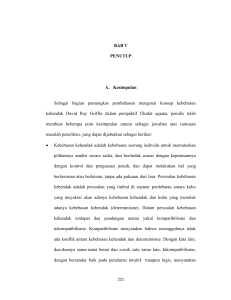Kritik Teologi Menggugat Kerancuan Nalar Berketuhanan dan
advertisement

Kritik Teologi Menggugat Kerancuan Nalar Berketuhanan dan Stagnasi Kemasyarakatan Oleh: Husein Heriyanto Adakah teologi1 yang mencerahkan intelek dan sekaligus membebaskan dari belenggu-belenggu mental dan sosial yang selama ini memasung potensi kreatif dan progresif kita? I. Prolog Marilah kita mulai kajian teologi kritis ini dengan mensketsa berbagai fenomena kehidupan sehari-hari, yang konkret dan nyata, tidak dibuat-buat, tidak direka-reka, tidak ditebak-tebak. Langkah ini adalah ciri pertama teologi kritis, yaitu refleksi yang bertitik tolak dari kenyataan riil dan bermuara pula pada kenyataan riil. Teologi kritis menentang keras setiap refleksi yang direka-reka tanpa dasar realitas, sekaligus sangat menentang setiap pemikiran yang memusuhi kehidupan nyata, yang menelikung daya kritis akal, mengelabui kemurnian fitrah, memistifikasi (melegitimasi) status quo. Teologi kritis bangkit melawan teologi formal-tradisional yang membunuh potensi kreatif manusia atas nama Tuhan. Teologi kritis menentang setiap pandangan agama yang melarikan diri dari kehidupan nyata (escapism) atas nama Tuhan, akhirat, apalagi hanya atas nama kewalian Kyai-Ulama. Fenomena 1 Hampir semua kasus yang menyangkut tragedi kemanusiaan di negeri kita tidak kunjung tuntas, entah karena dipetieskan, ditutup-tutupi, diperdagangkan, dengan konsesi-konsesi politik-ekonomi, ataupun karena intervensi pihak-pihak yang dominan, termasuk para investor asing. Kita tidak perlu menengok peristiwa masa lalu seperti pembunuhan Marsinah dan wartawan Udin, pembantaian Tanjung Priok dan Lampung, perampasan tanah dan perkebunan rakyat oleh negara seperti kasus Kedung Ombo, Cimacan, BUMN perkebunan (PTP), dan lain sebagainya. Tidak perlu kita ungkap kasus-kasus penjarahan kekayaan alam yang melimpah ruah oleh para konglomerat pemegang HPH dan perusahaan-perusahaan (domestik dan asing) di Aceh, Riau, Kalimantan, Papua, yang sekaligus menyingkirkan penduduk setempat dan meracuni mereka dengan limbah-limbah berbahaya (asap kebakaran hutan, kasus Freeport, Indorayon, dan sebagainya). Semua kasus ini raib begitu saja tanpa penyelesaian yang tuntas dan transparan. Cukuplah bagi kita untuk menengok trageditragedi kemanusiaan semenjak gerakan reformasi bergulir, seperti tragedi Mei 1998, Trisakti, Semanggi, perampokan ratusan triliun rupiah dana BLBI oleh puluhan bank, dan teristimewa macetnya pengusutan praktik KKN dan pelanggaran HAM rezim Suharto. Rezim Gus Dur yang diharapkan dapat menunaikan amanah gerakan reformasi untuk mengikis praktik KKN justru menambah banyak persoalan. Sebut saja kasus PLN (menolak menggunakan pendekatan hukum, tapi menggunakan pola lobi dan konsesi), Buloggate, Bruneigate, dan kasus Syahril Sabirin. Supremasi hukum yang merupakan salah satu tuntutan utama dari 6 visi Reformasi ditinggalkan begitu saja. Malah rezim sekarang ini tidak jauh berbeda dengan rezim Orde Baru dan Orde Lama yang mensubordinasi hukum di bawah supremasi politik dan kekuasaan. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa kita yang katanya bangsa religius sulit sekali menerapkan supremasi hukum? Sejak proklamasi (terutama setelah masa demokrasi terpimpin 1957) sampai sekarang yang terjadi adalah supremasi militer, politik, ataupun ekonomi. Nilai-nilai budaya dan pandangan hidup manakah yang menyulitkan kita untuk menyatakan bahwa: 1. Semua orang mulai dari presiden sampai tukang becak sama kedudukannya di mata hukum. 2. Penegakan hukum di atas segala kepentingan politik serta ekonomi, dan tidak dapat ditawar-tawar lagi (seperti Syahril Sabirin sekarang ini). 3. Hukum adalah penegakkan nilai keadilan. 4. Keadilan adalah tonggak utama bangunan masyarakat, apapun agama dan teologi yang dianut masyarakat. 5. Keadilan adalah tanah subur bagi tumbuhnya nilai-nilai moral lain seperti kebaikan, kejujuran, kesucian, keberanian (lihat QS. 16:90) Sejauh mana fenomena ini terkait dengan teologi formal- tradisional ? Fenomena 2 Ketertinggalan bangsa kita, khususnya umat Islam, dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah tak terbantahkan. Etos keilmuan masyarakat kita sangat rendah. Belum tumbuh tradisi intelektual dan diskursus-diskursus ilmiah dalam lembagalembaga pendidikan yang menggairahkan masyarakat kita sehingga memicu untuk selalu memperluas wawasan dan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Pertimbangan ekonomi (perut), sosial (popularitas), dan politik (kekuasaan) jauh lebih diutamakan ketimbang urusan pendidikan dan pengembangan SDM yang unggul. Kita bisa lihat pada alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sejak Orla sampai sekarang tidak pernah mencapai di atas 7%. Padahal, APBN negara-negara Asia Tenggara saja mencapai rata-rata 20-25 %. Rendahnya alokasi dana pendidikan di Indonesia merupakan indikator paling jelas betapa rendahnya komitmen kita kepada pengembangan potensi SDM. Secara global Cak Nur menulis, "... sekarang ini dunia Islam praktis merupakan kawasan bumi yang paling terbelakang di antara penganut agama-agama besar. Negeri-negeri Islam jauh tertinggal oleh Eropa Utara, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru yang Protestan; Eropa Selatan dan Amerika Selatan yang Katholik: Eropa Timur yang Katholik Ortodox; Israel yang Yahudi; India yang Hindu; Cina, Korea Selatan, Taiwan Hongkong, Singapura yang Budhis Konfusianis; Jepang yang Budhis Taois; Thailand yang Budhis. Praktis di semua penganut agama besar di muka bumi ini, para pemeluk Islam adalah yang paling rendah dalam sains dan teknologi."2 Cukup mengherankan bagaimana etos keilmuan dan tradisi intelektual Islam yang begitu tinggi pada abad 8-14 M sirna begitu saja. Pesantren-pesantren yang pasti mengetahui sabda Nabi Saww, "tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat", justru membelenggu potensi kreatif anak didik. Lembaga-lembaga pendidikan kita telah melakukan learning shut down (pembisuan kebutuhan belajar) karena dipasung konsep-konsep dogmatis seperti takdir, nasib, pasrah, pahala, surga. Selain pula metode pengajaran yang bersifat kultus individu pada guru, dosen, kiai, ulama yang selalu dianggap benar. Tidak ada budaya kritis dalam masyarakat kita. Sejauh mana fenomena ini terkait dengan teologi ? Fenomena 3 Anda letih dan frustrasi dengan program-program pemberdayaan dan pengembangan SDM karena sulit memperoleh dukungan masyarakat? Alihkan perhatian dan tenaga kreatif anda pada bidang politik atau ritual religius! Buat parpol yang mengatasnamakan rakyat, atau buat proposal mendirikan masjid, bimbingan haji, dan lomba tilawatil Quran, atau ritual-ritual lainnya. Dipastikan Anda jauh lebih mudah menggalang dana, bantuan moril, dan sebagainya. Kenapa? Masyarakat kita akan mendukung siapapun, entah koruptor ataupun penguasa lalim, yang mendirikan masjid atau naik haji meski dengan hasil rampokan uang rakyat. Alasannya, bukankah masjid adalah simbol kekuasaan Tuhan dan penyembahan manusia yang hina penuh dosa kepada Tuhan Yang Suci? Sebaliknya masyarakat kita (termasuk pemerintah) kikir membelanjakan hartanya untuk membangun perpustakaan, sekolah yang bermutu, apalagi yang namanya litbang-litbang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Membeli komputer canggih oke, tapi mendirikan pusat penelitian pengembangan komputer, nanti dulu! Membangun masjid oke, tapi memberdayakan marbot (pengurus masjid), pedagang kecil, petani, buruh, nanti dulu! Kenapa? Karena membangun masjid dianggap melayani Tuhan, sedang memberdayakan orang lemah, hanya melayani manusia, tidak lebih dari itu. Sejauh mana fenomena ini relevan dengan teologi ? Fenomena 4 Seorang pejabat tinggi negara kita dua bulan yang lalu pernah berkata, "Kami ini kan manusia biasa, wajar kami keliru. Hanya Tuhan yang sempurna sajalah yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita". Dua bulan sebelumnya seorang menteri juga pernah berkomentar agak mirip. Ketika para wartawan menanyakan ketidakjelasan dan inkonsistensi pemerintah RI dalam menjalankan program ekonomi nasional, sang menteri terdesak dan tidak punya jawaban argumentatif lagi. Lalu ia dengan lirih berkata, "Sudahlah, percayalah kepada kami. Anda tahu siapa presiden kita sekarang. Beliau kan selama ini jujur dan dekat dengan rakyat. Kenapa kita tidak percayakan saja kepadanya?" Adakah relevansinya fenomena ini dengan teologi ? Fenomena 5 Seorang sarjana dari desa tiba-tiba saja telah menjadi direktur perusahaan besar; lengkap dengan simbol seorang eksekutif sukses: ponsel, mobil mewah, rumah berkolam renang, dan pacar/istri cantik. Demikian gambaran sebuah sinetron. Dalam sinetron lain diperagakan bahwa tanpa alur cerita yang logis, seorang suami yang mengaku pecinta sejati mencoba bunuh diri hanya karena sang istri ‘ngambek’. Sinetron-sinetron lainnya yang menguasai layar TV tak kalah irasional dan irealistis. Mereka menjual mimpi-mimpi indah dan imajinasi-imajinasi yang mematikan kreativitas melalui tokoh-tokoh jin, tuyul, manusia super, atau lampu aladin. Ketika dikritik keras bahwa film-filmnya hanya menjual mimpi-mimpi kosong yang meninabobokan masyarakat, sang produser Raam Punjabi membela diri dengan berkata, "Ya, saya memproduksi film seperti itu karena laku dan diminati publik. Masyarakat kita tidak suka melihat kenyataan yang sesungguhnya bahwa mereka tengah mengalami kesulitan hidup." Benarkah masyarakat kita tidak berani menghadapi kenyataan atau realitas, malah lari darinya, kemudian berpaling pada mimpi-mimpi yang dijajakan sinetron, judi arisan berantai, dan sebagainya? Adakah relevansi fenomena ini dengan teologi ? II. Membedah Teologi Formal-Tradisional Kelima fenomena di atas perlu kita angkat untuk keperluan analisis pandangan hidup dan nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, sistem kepercayaan masyarakat turut mengkonstitusi (memberikan bentuk) pandangan hidup dan nilai-nilai sosial yang pada gilirannya berdampak pada tataran sosial dan praksis. Sistem kepercayaan yang mengendap dalam alam kesadaran atau ketidaksadaran masyarakat itulah yang kita sebut sebagai teologi formal-tradisional. Apa yang dimaksud dengan teologi formal-tradisional? Tak lain dari teologi yang dianut secara turun temurun tanpa pernah melakukan kajian ilmiah kritis. Disebut formal karena sistem kepercayaan ini lebih berfungsi sebagai simbol identitas kelompok/mazhab daripada sumber pemahaman yang konstruktif terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Misalnya, kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah (aswaja) mengklaim diri sebagai pengikut Asy’ari atau Maturidi, tanpa pernah mengkaji secara kritis faktor-faktor sejarah, sosial politik, dan budaya yang ikut mengkonstruksi teologi Asy’ari. Bahkan, ajaran-ajarannya pun mungkin banyak yang tidak mengenalnya. Demikian pula dengan kaum cendekiawan yang merasa bangga dan mengklaim diri sebagai pengikut Mu’tazilah, lebih sebagai simbol kaum rasionalis yang merupakan ciri Mu’tazilah, daripada pemahaman otentik terhadap Tuhan (Zat, Sifat, Perbuatan). Kelima fenomena yang dipaparkan di atas lebih berkaitan dengan teologi yang dianut mayoritas bangsa kita, yaitu Asy’ari. Kita menganalisis fenomena-fenomena itu secara relatif dan mendasar, serta mengkaji relevansi fenomena tersebut dengan teologi mayoritas umat Islam dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui, teologi Asy’ari menjadi teologi mayoritas setelah penguasa Abbasiyah AlMutawakkil menjadikan Asy’ari sebagai teologi resmi kekhalifahan, dan menganiaya tokoh-tokoh teologi lainnya, serta membakar buku-buku yang dianggap bertentangan dengan teologi resmi. Teologi ini juga memperoleh justifikasi yang lebih kuat setelah Al-Ghazali menyatakan diri sebagai pengikut Asy’ari serta memadukan teologi ini dengan ajaran tasawufnya (abad 12 M). Fenomena 1: Teologi Kekuasaan-Voluntarisme Kesulitan kita menerapkan supremasi hukum ada kaitannya dengan teologi yang dianut mayoritas umat Islam, yaitu Asy’ari. Teologi ini menjadikan sifat Tuhan Yang Mahakuasa dan berkehendak apa saja sebagai sifat yang utama di atas sifat-sifat lainnya, seperti Mahaadil, Mahabijak, Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu, kata ‘Kuasa’ dan ‘Kehendak’ menjadi kata kunci teologi Asy’ari. Frithjof Schuon menyebutnya teologi voluntarisme’3 Tesis utama teologi ini adalah Tuhan Yang Mahakuasa berkehendak apa saja, dan apapun yang terjadi di dunia adalah hasil kehendak Tuhan. ‘Baik’ dan ‘buruk’, keduanya diciptakan Tuhan. Asy’ari bahkan mengatakan, Tuhan dapat saja menghukum orang yang tak bersalah dan memasukkannya kedalam neraka jika Ia menghendaki, dan sebaliknya mengganjar orang fasiq dan zhalim ke dalam surga. Pandangan Asy’ariyyin tentang Tuhan dengan gamblang menggambarkan Tuhan Raja Diraja Yang Maha Berkehendak tanpa ada kriteria-kriteria rasional. Akal harus di tundukkan demi pengagungan kekuasaan Tuhan. Kriteria lain harus dicampakkan karena dianggap membatasi kekuasaan-Nya. Misalnya kriteria bahwa Tuhan pasti membalas kebaikan orang yang berbuat kebaikan; bahwa Tuhan adalah Zat Yang Mahaadil dan menepati janji, tidak mungkin Tuhan melanggar hukum-hukum yang Dia buat sendiri. Kriteria semacam ini ditolak Asy’ari. Dengan demikian, makna kata ‘Kuasa’ oleh Asy’ari dipahami sebagai fakta yang diterima begitu saja (seringkali dianalogikan dengan raja yang berkuasa tanpa batas dan hukum); sebagai kata benda yang berkonotasi kepemilikan , hegemoni. Tidak ada nilai-nilai lain yang menyertai kekuasaan Tuhan seperti keadilan, kebijakan, kasih sayang. Kuasa lebih dipahami sebagai ‘Fakta’ atau thing (sesuatu) daripada sebagai Nilai yang termanifestasikan (memancar) kepada segala sesuatu. Untuk membedakan kuasa dalam konsepsi fakta dengan nilai, kita dapat mengutip Sabda Nabi Suci saw, "al-ilm nuurun" (ilmu adalah cahaya) dan sabda Sayyidina Ali kw, "Harta akan berkurang jika diberikan, sedang ilmu akan bertambah jika diberikan". Dari dua sabda ini ingin ditunjukkan bahwa apa yang disebut harta berkonotasi sebagai fakta atau thing. Sedangkan ilmu adalah nilai atau cahaya yang memancar ke segala arah tanpa mengurangi sumbernya. Asy’ari lebih melihat Tuhan sebagai thing, fakta. Oleh karena itu, untuk meneguhkan kekuasaan Tuhan, ia harus menafikan kebebasan kehendak manusia dan alam (hukum alam; Asy’ariyyah menolak prinsip kausalitas). Jelaslah teologi kekuasaan Voluntarisme ini merupakan lahan subur bagi sang penguasa untuk mengelabui rakyat dengan mengatasnamakan kehendak Tuhan, takdir Tuhan terhadap segala perilaku hegemoniknya. Sang penguasa memaksa rakyat percaya bahwa, "Situasi Anda atau masyarakat Anda adalah situasi yang harus di terima karena merupakan manifestasi kehendak Tuhan. Itu adalah takdir dan nasib..." Ali Syariati menyebut konsepsi takdir dan nasib sebagai bentuk teologi persembahan Mu’awiyah. Menurut Hasan Hanafi, teologi tradisional ini merupakan sejarah persembahan kepada sang penguasa, pengabdian kepada para sultan. Memuji sultan berarti sama dengan bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya, menentang sultan berarti menentang Tuhan. Bagaimana cara kerja teologi Asy’ari menghambat terciptanya supremasi hukum? Jawabannya bahwa, pertama, teologi Asy’ari menolak segala kriteria rasional terhadap konsepsi kuasa, sedangkan supremasi hukum justru bersandarkan pada kriteria-kriteria yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Kedua, teologi Asy’ari adalah teologi kekuasaan, sedangkan supremasi hukum menurut teologi keadilan yang merupakan teologi yang ditegakkan di atas nilai-nilai keadilan, rasionalitas, transparansi, dan dapat diuji (variability, flexifiable) Fenomena 2: Teologi Sim Salabim Ketertinggalan umat Islam dalam ilmu pengetahuan terkait erat dengan teologi yang dianut mayoritas umat Islam. Watak esensial ilmu dengan watak esensial teologi Asy’ari sangat bertolak belakang. Perbedaan mendasar kedua paradigma itu adalah: 1. Ilmu pengetahuan tegak atas dasar prinsip kausalitas yang bisa dipelajari, sedangkan teologi Asy’ari justru menolak prinsip kausalitas (teologi mukjizat, sim salabim). 2. Ilmu pengetahuan berkembang sejalan dengan daya kritis, kreativitas, dan rasa ingin tahu manusia. Sementara teologi Asy’ari justru menekankan ketundukan manusia tanpa banyak menggunakan nalar. 3. Ilmu pengetahuan mengandalkan kegiatan ilmiah yang bekerja secara proses (process oriented). Adapun teologi Asy’ari lebih terfokus pada hasil (product oriented). Fenomena 3: Teologi Dikotomis-Ritualisme Kurangnya apresiasi terhadap program-program pemberdayaan SDM dibanding program-program ritual, berkorelasi erat dengan teologi Asy’ari. Fenomena ini merupakan implikasi alamiah dari pandangan Asy’ariyyin yang kurang mengapresiasi potensi-potensi insaniah manusia. Manusia hanya dilihat sebagai budak atau pelayan Tuhan, tanpa kemampuan sedikit pun untuk memahami atau mengenalNya (sifat dan perbuatan Tuhan). Frithjof Schuon menyebutkan bahwa teologi Asy’ari ini tidak memungkinkan manusia mencintai Tuhan, karena cinta mensyaratkan pengenalan dan apresiasi kepada Tuhan yang Maha Bijak, Indah, Mengetahui, Kasih. Untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan, potensi manusia harus dinegasikan, kecuali budak Tuhan belaka. Asy’ari menganggap bahwa bila kita mengakui potensi-potensi insani yang kreatif, mandiri, bebas, maka kekuasaan Tuhan akan berkurang. Logika yang dipakai Asy’ari adalah logika biner (dikotomi), yaitu logika on-off (either or logic). Pilih Tuhan atau manusia saja. Logika biner ini juga digunakan Nietzsche dan Sartre. Asy’ari memilih Tuhan dengan menafikan manusia, sedangkan Nietzsche dan Sartre memilih manusia dan menafikan Tuhan. Fenomena 4: Teologi Legitimatif (Mistis) Ucapan kedua pejabat itu merepresentasikan cara pandang mayoritas masyarakat kita, yaitu membela diri dengan jalan mengalihkan persoalan kepada Tuhan atau penguasa. Ucapan pejabat yang pertama kerap kita dengar, yaitu berlindung di bawah nama Tuhan untuk menutupi kesalahan diri, atau atas nama makhluk yang hina penuh dosa (seraya menyebut Tuhan yang suci ) untuk membersihkan diri. Teknik ini disebut juga mistifikasi, karena membawa persoalan aktual yang nyata ke dalam wacana mistis, gaib yang tak bisa diverifikasi/difalsifikasi. Karena tidak bisa diverifikasi, maka diri yang bersangkutan menjadi terlindungi/terselamatkan. Ucapan pejabat yang kedua lebih sebagai upaya pelarian dari tanggung jawab rasionalitas dan transparansi kebijakan dengan berlindung di bawah pernyataan "kehendak baik penguasa". Penguasa yang dianggap baik dan jujur tak perlu lagi diminta pertanggungjawaban yang reasonable dan transparan. Cukup kita yakini bahwa penguasa itu jujur, dan tinggal percaya saja kepadanya. Jika ada ucapan penguasa yang tidak dimengerti, maka anggap saja ‘pemikiran penguasa itu melampaui pemikiran kita orang biasa’, karenanya tidak perlu repot-repot mempertanyakan. Bahkan, jikapun keadaan telah sampai melahirkan indikator-indikator yang gamblang tentang kegagalan penguasa, maka kita tetap saja harus harus ’husnuzhan’ (berprasangka baik) pada penguasa. Mungkin saja ini adalah proses awal yang membutuhkan pengorbanan kita semua. Logika mistifikasi untuk melegitimasi /status quo/ penguasa ini adalah sebagai berikut : Premis mayor : Penguasa adalah orang baik dan selalu benar Premis Minor : Jika penguasa Salah, lihat premis mayor Konklusi : Penguasa selalu baik dan benar Dalam argumen yang digunakan logika legitimatif ini disebut argumentum ad hominem (kebenaran ditentukan manusia). Logika ini bertolak belakang dengan ucapan Sayyidina Ali, ‘Carilah kebenaran, lalu nilailah manusia atas kriteria kebenaran itu’. Fenomena 5: Teologi Eskapisme Sikap dan cara pandang masyarakat kita yang mudah terbuai mimpi-mimpi indah merupakan implikasi lebih lanjut dari teologi sim salabim, teologi legitimatif. Karena menolak rasionalitas, keteraturan, dan kejelasan kriteria (transparancy), dan sebaliknya cenderung melegitimasi status quo yang ada, maka penganut teologi ini cenderung tidak berani menghadapi realitas. Mereka lebih senang mengkhayalkan realitas imajinatif melalui mimpi-mimpi dan penciptaan tokoh-tokoh ilusif —mitos seperti Ratu Adil, Nyi Roro Kidul. Masyarakat kita juga mudah sekali dibujuk dengan program-program irrasional seperti judi, arisan berantai, ‘nyepi’, jampi-jampi, yang semuanya adalah pelarian dari kegagalan meraih cita-cita dalam konteks realitas nyata. III. Teologi Alternatif: Teologi Kritis Antitesis dari teologi formal-tradisional yang telah membelenggu potensi kreatif dan progresif umat Islam harus dicari, entah dengan penemuan atau melalui konstruksi di atas prinsip-prinsip Tauhid. Teologi alternatif itu dapat kita namakan teologi kritis. Disebut kritis karena menekankan daya nalar yang tajam, sikap yang selalu ingin tahu (sense of curiosity) dan sebagai sikap tengah antara absolutisme dan nihilisme. Di satu sisi, kita meyakini adanya Kebenaran Mutlak, yaitu Tuhan itu sendiri. Akan tetapi di sisi lain, kita juga menyadari relativitas diri dalam mencerap kebenaran sehingga tak pernah sempurna atau selesai. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah sikap yang selalu terbuka, mencari ilmu tiada henti, selalu bergerak ke arah yang lebih baik/sempurna. Beberapa prinsip yang melandasi Teologi Kritis adalah : 1. Pandangan bahwa Tuhan bukan sebagai ‘Fakta’ atau ‘Thing’, tapi sebagai ‘Nilai’ atau ‘Cahaya’. Allah swt sendiri memperkenalkan diriNya sebagai Cahaya (QS. 24:35), Tuhan Mahakuasa dengan Keadilan dan Kearifannya, Tuhan Adil dengan Kekuasaanya. Sifat-sifat Tuhan satu sama lain tidak terpisahkan. Tidak ada sifat yang saling mensubordinasi, melainkan aspek-aspek pemahaman terhadap Wujud Yang Satu. Sifat dan Zat Tuhan tidak terpisahkan, bahkan identik. Oleh karena itu, ketika Tuhan menepati janjiNya, itu tidak dipahami sebagai keterikatan Tuhan, melainkan sifat menepati janji (Adil) itu sendiri adalah esensi dari Wujud Tuhan sendiri. ’Alim, Hakim, Rahman, Rahim, adalah Tuhan itu sendiri. 2. Pandangan Tuhan sebagai ‘Nilai’ bermakna juga bahwa Tuhan berhubungan erat dengan nilai-nilai eksistensial kita selaku makhlukNya. Nilai-nilai kita sebagai manusia adalah manifestasi sifat-sifat Tuhan, seperti keadilan, pengetahuan, kearifan, kebaikan, harapan kesempurnaan, kebenaran, kreativitas, kasih sayang, keindahan. Setidaknya, terdapat 6 gugus nilai: 1. Nilai Vital: hidup, kehendak, melihat, mendengar, mencipta. 2. Nilai etis: baik, adil, jujur, amanah, sabar. 3. Nilai estetis: indah, terpuji, keharmonisan. 4. Nilai intelektual: mengetahui, bijak, arif. 5. Nilai keagungan (jalal): kuasa, mulia, perkasa. 6. Nilai kudus (kesucian): suci, ikhlas, asketis, sederhana. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa melayani manusia berarti identik dengan melayani Tuhan. Menegakkan keadilan berarti ingin menghadirkan Tuhan, karena Tuhan adalah Al-’Adl. Menuntut ilmu bermakna mendekati Tuhan, karena Tuhan adalah Al’Alim. 3. Sebagai konsekuensi logis dari prinsip kedua, teologi kritis menolak logika dikotomis yang diciptakan Asy’ari. Ada lima (5) jenis dikotomi yang hendak dihilangkan, yaitu : a. Tuhan-Alam (Alam adalah ayat-ayat, manifestasi sifat-sifat Tuhan). b. Tuhan-Manusia (manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia) c. Iman-Ilmu d. Ruh-Jasad e. Wahyu-Intelek (Intelek atau qalb adalah wahyu batin imanen) 4 Teologi kritis lebih menekankan isi dari pada formal ritual, artinya lebih memfokuskan diri kepada upaya menyingkap nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dalam keseluruhan eksistensi, alias tidak hanya dalam ritual formal belaka. Menyingkap nama Tuhan tidak hanya dilakukan di masjid atau Ka’bah, tapi di mana dan kapan saja manusia berada dalam totalitas eksistensinya yang darinya termanifestasikan nama-nama Tuhan. Penyingkapan nama-nama Tuhan (Asma Al-Husna) itu juga dilakukan dengan seluruh fakultas dan potensi manusia yang terintegrasi, baik secara teoritis maupun praksis . Dzikir, tafakkur, amal shaleh (amal sosial) merupakan modus-modus penyingkapan nama-nama Tuhan. 5 Konsekuensi dari persoalan keempat adalah terbukanya peluang bagi siapa saja tanpa pandang mazhab, ideologi, dan bahkan agama, untuk masuk dalam anutan teologi kritis, teologi nilai, teologi cahaya, teologi rasional-iluminasionis, sepanjang ia menyingkap nama-nama Allah dalam keseluruhan eksistensinya. TEOLOGI NILAI TEOLOGI FORMAL Tuhan sebagai Thing, fakta Teologi Kekuasaan - Voluntarisme Teologi Sim Salabim Teologi Dikotomis - Ritualisme Teologi Eskapisme Teologi Legitimatif Teologi Formal Eksklusif Tuhan sebagai 'Nilai', Cahaya Teologi Keadilan - Rasionalisme Teologi Pengetahuan Teologi Integrasi Teologi Realisme Teologi Eksplanasi - Kritis Teologi Pluralisme