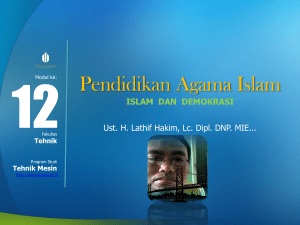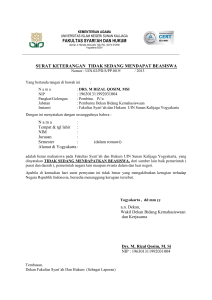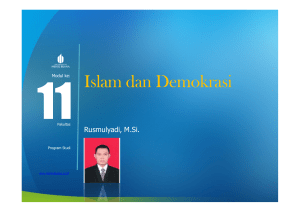1 PLURALISME AGAMA: AKAR PERDAMAIAN MERAWAT
advertisement

PLURALISME AGAMA: AKAR PERDAMAIAN MERAWAT HARMONISASI Firdaus Muhammad1 Abstract: Pluralism is society of etnic, region, religion, languge, and culture. The pluralism characteristic (identifying feature) this nation is really the God willing to create life which is high respect the tolerance values. As God creates, human being is same. They have believing, tradition, self culture, many view of life. Then Islam religion, experience or inspire the meaning, peature, gold of their life and implementing islam as their way or view of life to give or to come their safety life of world and here after later. So, Islam function is muslim personality formed which have brilliant brain, be science, be heart honor, and be obadent to the God. The end, It means that Islam always save peace and harmonization of the world. Key Words: Religious Pluralism, Peace, Harmonization Pendahuluan Wacana pluralisme agama menjadi bagian penting dalam kajian keislaman kontemporer di Indonesia. Pluralisme menjadi akar perdamaian dalam merawat harmonisasi agama, termasuk dalam konteks relasi agama dan negara. Harmonisasi agama dan negara selalu urgen dikaji dan didiskusikan, apalagi belakangan pluralism agama kembali tercabik, termasuk soal intern Islam, Sunni versus Syiah di Madura yang belum terselesaikan. Negara dianggap gagal meredamnya. Dalam kaitan itu, pluralisme agama penting dijadikan pijakan dalam mewujudkan perdamaian guna menjaga harmonisasi agar umat beragama terlindungi dalam naungan egara tanpa mengintervensi substansi tetapi menciptakan suasana beragama yang kondusif dan toleran. Sejak zaman klasik, zaman modern dan bahkan sampai sekarang, persoalan-persoalan kenegaraan di dalam Islam masih merupakan komuditas aktual yang selalu menarik untuk didiskusikan, lebih-lebih ketika berbagai ideologi Barat mulai menanamkan pengaruhnya di dunia Islam. Perdebatan berkisar pada beberapa persoalan yang cukup mendasar, diantaranya adalah sejauh mana keharusan kaum muslimin untuk mendirikan sebuah negara, apa bantuk dan sistem pemerintahan yang harus dijalankan oleh umat Islam dalam 1 Dosen Dakwah Universitas [email protected]. Islam Negeri 1 (UIN) Alauddin Makassar. E-mail: konteks kehidupan bernegara, bagaimanakah seharusnya dibangun hubungan anatara agama dan negara, dan apakah umat Islam dituntut untuk mendirikan sebuah negara yang berlabelkan Islam. Munculnya beberapa persoalan kenegaraan di atas, sesungguhnya disebabkan karena baik al-Qur’an maupun hadits tidak pernah memberikan penjelasan secara eksplisit tentang konsep-konsep kenegaraan yg harus di jadikan acuan umat Islam di dalam mengatur dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan nabi Muhammad SAW pun setelahs beliau wafat tidak meninggalkan konsep kenegaraan yang baku. Hal ini memberikan indikasi bahwa persoalan kenegaraan di dalam Islam masih terbuka untuk berkembang dan diperdebatkan.2 Historisitas Pluralitas di Zaman Nabi Secara historis telah membuktikan, bahwa pada periode Makkah nabi Muhammad tidak memiliki kekuasaan politik untuk mem-back up misi kenabiannya. Sementara di Madinah, di samping sebagai tokoh spiritual dan agama ia juga berkedudukan sebagai pemimpin politik, kendatipun dalam kenyataannya nabi tidak pernah memproklamirkan diri sebagai seorang penguasa, raja atau pemimpin negara. Tetapi paling tidak, dari usaha-usaha yang dilakukan nabi setibanya di Madinah, seperti mengadakan perjanjian tertulis antara kelompok muhajirin dan anshar, memberikan jaminan dan proteksi kepada komunitas Yahudi di dalam menjalankan agama dan keselamatan harta benda mereka, menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat, mengatur hubungan antara umat Islam dan non-muslim,3 dan lain-lain, maka cukup untuk dijadikan argumentasi bahwa sejak periode Madinah nabi telah membangun sebuah pemerintahan, atau minimal telah membentuk tatanan masyarakat yang bernaung di bawah kepemimpinannya. Periode Madinah menurut hemat penulis merupakan periode berdirinya masyarakat dan pemerintahan Islam yang pertama di dalam sejarah, sebab di dalam periode ini, secara de-facto telah diletakkan dasar-dasar yang kuat bagi berdirinya 2Harun Nasution dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern Dalam Islam, ( Jakarta : Yayasan Obor, 1985 ), hlm. 10. 3Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan ( Yogyakarta : UII, 1984 ), hlm. 17. 2 sebuah negara. Istilah negara dalam pengertian ilmu politik merupakan suatu komunitas manusia yang mendiami daerah tertentu, merdeka secara legal dari dominasi dan pengendalian luar, memiliki suatu pemerintahan dan adanya ikatan bersama. Sehingga dari batasan ini terdapat unsur-unsur adanya wilayah, adanya penduduk, adanya pemerintah dan adanya kedaulatan.4 Dalam negara yang pertama didirikan nabi di Madinah tersebut ternyata unsurunsur negara telah terpenuhi, walaupun dalam bentuknya yang masih sederhana. Rakyat atau penduduk adalah masyarakat Islam ( Muhajirin dan Anshar ) sebagai kelompok mayoritas dan masyarakat non-muslim ( Yahudi dan Nasrani ) sebagai kelompok minoritas; Undang-undang yang dipergunakan adalah syari’at Islam; daerah yang ditempati secara permanen adalah Madinah, dan pemerintahnya Muhammad SAW beserta para sahabat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang dibina nabi di Madinah merupakan manifestasi dari sebuah pemerintahan Islam dalam formatnya yang sederhana. Corak pemerintahan berbentuk teo-demokrasi, 5 sebab dalam periode ini nabi mengatur kehidupan sosio-kultural umat berdasarkan kepada wahyu yang diterima dari Allah, dan dalam hal-hal yang tidak ada wahyunya, nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Demikian juga pada masa Khulafa’ al-Rasydin dan periode-periode berikutnya, corak pemerintahan Islam selalu berkembang dan mengalami perubahan- prubahan. Pada masa Khulafa” al-Rasyidin corak pemerintahan berbentuk republik-demokratis, karena pada masa ini budaya musyawarah sangat dikembangkan dan merupakan bagian dari langkah yang di ambil para khalifah didalam menyelesaikan persoalanpersoalan yang secara eksplisit tidak diatur, baik di dalam al-Qur’an maupun hadits. Sedangkan pada periode dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, corak pemerintahan bergeser kepada bentuk dinasti atau kerajaan. Sistem pemerintahan dinasti yang muncul pada abad ke-7 dan bertahan lebih dari 1200 tahun, pada abad ke-20 berubah dan mengambil bentuk Republik-Konstitusional dan demokratis, seperti Republik 4Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991 ), Cet.13, hlm. 44. 5Harun Nasution, Perkembangan Modern..., hlm. 10. 3 Turki, Republik Pakistan, Republik Mesir, Republik Syria, Republik Irak, Republik Indonesia, dan lain-lain.6 Tinjauan sejarah di atas, ternyata sistem kenegaraan di dalam Islam dengan berbagai persoalannya tidak memberikan gambaran yang jelas dan baku yang dapat dijadikan acuan bagi umat Islam dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Islam juga tidak memberikan garis yang jelas bahwa sebuah nergara harus dikemas dalam bentuk “ Negara Islam “ yang secara eksklusif tidak memberikan ruang bagi komunitas non-muslim untuk menjalankan ajaran agamanya serta mengembangkan kultur yang dimilki secara bebas, elegan dan penuh toleransi. Karena pada dasarnya Islam adalah agama yang sangat mengembangkan sikap toleransi, agama yang menghargai pluralitas dan kemajemukan, sebagaimana yang telah diimplimentasikan oleh nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah yang sangat heterogen dan pluralis. Negara Islam dan Persoalan Kemajmukan Umat Persoalan soal Negara Islam sendiri masih diperdebatkan. Kata-kata arab yang berarti negara atau pemerintahan ( dawlah dan hukumah ) tidak pernah disebut di dalam al-Qur’an. Term dawlah merupakan perkembangan baru, dan agaknya dimaksudkan untuk menunjukkan konsep Barat tentang nation state. Demikian juga dengan kata hukumah yang merujuk pada kata hakama-yahkumu dalam al-Qur’an, 7 yang pada akhirnya memunculkan konsep hakimiyyah atau kekuasaan pemerintahan. Kata hukm dan bentuk derivatifnya yang banyak disebut di dalam al-Qur’an, ternyata menunjukkan banyak arti dan perlu dipahami dalam konteksnya masing-masing.8 Mencermati tuntutan al-Qur’an tentang kehidupan bernegara sesungguhnya tidak menunjuk kepada sebuah model tertentu tentang sebuah negara yang harus diikuti oleh umat Islam di berbagai negara. Alasan untuk ini tentunya tidak terlalu sulit untuk 6 Ibid, hlm. 11-12. Selanjutnya lihat Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ( Jakarta : UI Press ), hlm. 30. 7Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur’an ( Ttt : Dar al-Fikr li alTaba’ wa al-Nasyr, 1981 ), hlm. 34. 8Ibid. 4 dicari dan dieksplorasi. Pertama, al-Qur’an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia; ia bukan sebuah kitab ilmu politik. Kedua, merupakan suatu kenyataan bahwa institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia selalu mengalami perubahan dari masa ke masa.9 Atau dengan memakai ungkapan lain, diamnya alQur’an dalam konteks ini berarti memberikan suatu jaminan yang sangat esensial serta sengaja terhadap kekuatan hukum dan sosial. 10 Dalam kajian Islam kontemporer, term “ Negara Islam “ atau “ Dawlah Islamiyah “. Baik di dalam al-Qur’an maupun kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama sebelum abad ke-20 tidak dijumpai istilah Negara Islam atau Dawlah Islamiyah. Hadits-hadits dan praktek-praktek kehidupan nabi selama membangun masyarakat Islam Madinah tidak pernah menyinggung masalah ini. Begitu juga dengan Piagam Madinah, baik secara eksplisit maupun implisit tidak ditemukan ide tentang Dawlah Islamiyah, tatanan masyarakat Islam Madinah hanya disebut sebagai al-Mujtama’ alIslamy atau komunitas masyarakat Islam. Menurut Robert N.Bellah, praktek kenegaraan yang dijalankan oleh nabi Muhammad di Madinah merupakan tatanan yang sangat modern dan demokratis pada masanya. Namun dalam kenyataannya nabi tidak pernah menyebut negara Madinah sebagai Negara Islam. Ide Negara Islam sesungguhnya merupakan produk abad ke-20 yang diintrodusir pertama kali oleh Muhammad Rasyid Ridha di dalam karyanya yang berjudul alKhilafah , yang kemudian ditindak lanjuti oleh Hasan al-Banna ( 1906-1949 ) dan dirumuskan secara konseptual oleh Sayyid Qutb ( 1903-1979 ). Dengan demikian, ide dan gagasan Negara Islam sesungguhnya merupakan produk ijtihad para pemikir politik.Islam abad ke-20 yang bertitik tolak dari pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip kenegaraan yang terdapat di dalam al-Qur’an. Hampir tidak terdapat kesepakatan bulat di kalangan para pemikir politik Islam kontemporer tentang pengertian dan hakikat Negara Islam serta hal-hal yang terkandung di dalam konsep Negara Islam itu sendiri. Namun demikian, setidak-tidaknya secara teoritis terdapat kesepakatan minimal bahwa suatu negara disebut sebagai Negara Islam apabila negara tersebut 9Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan ( Jakarta : LP3ES, 1987 ), hlm. 16. 10Ibid. 5 mendasarkan diri di atas agama Islam dan memberlakukan syari’at Islam dalam aturan dan perundang-undangan negara. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum Islam merupakan prasyarat formal dan utama bagi eksisnya Negara Islam. Suatu negara dapat dianggap sebagai Negara Islam apabila negara tersebut benar-benar telah melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengintegrasikannya ke dalam Undang-Undang negara. 11 Dalam spektrum kajian politik Islam, Rasyid Ridha merupakan sosok ulama terkemuka di awal abad ke-20 yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep Negara Islam Modern. Ia menyatakan bahwa premis pokok dari konsep Negara Islam adalah syari’at merupakan sumber hukum tertinggi. Dalam pandangan Ridha, syari’at mesti membutuhkan bantuan kekuasaan (power) dalam upaya mengimplimentasikannya, dan adalah mustahil untuk dapat menerapkan syari’at Islam tanpa kehadiran Negara Islam. Dengan demikian, penerapan syari’at Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang amat menentukan ( the single most desicive criterion ) untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam. Beberapa statemen di atas dapat diformulasikan, bahwa Negara Islam adalah negara di mana peraturan dan perundang-undangan didasarkan kepada ajaran Islam atau syari’at Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi. Suatu negara yang dihuni oleh mayoritas muslim tidak otomatis menjadi Negara Islam kecuali syari’at Islam tentang sosio- politik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi. Dan di dalam sejarah pemikiran politik Islam kontemporer, nama al-Maududi nampaknya dikenal sebagai tokoh yang mampu mengkonstruksi konsepsi Negara Islam yang relatif utuh dan terperinci, 12 kendatipun pada tataran aplikasinya sangat sulit untuk di realisasikan, lebih-lbih terhadap negara yang penduduknya memiliki ke-anekaragaman agama, ras dan budaya. 11Ibid, hlm. 140 konseptual konstruksi Negara Islam yang dibangun oleh al-Maududi, antara lain adalah : bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah, manusia hanya bertindak sebagai pelaksana dari kedaulatan Allah; Dasar negara adalah syari’at Islam; Untuk melaksanakan syari’at Islam, sistem pemerintahan harus dalam bentuk khilafah yang bersipat universal dan tidak mengenal batas-batas geografis, ras, bahasa dan budaya. 12Secara 6 Pluralitas, Sebuah Kemestian Realitas kehidupan beragama, pluralitas dan kemajemukan dalam konteks kehidupan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Di manapun manusia berada pluralitas agama, ras dan budaya merupakan sesuatu yang inheren dengan kehidupan manusia. Agaknya sulit dibayangkan ketika ada belahan bumi tertentu yang hanya dihuni oleh komunitas tertentu dengan latar belakang agama, ras dan budaya yang tunggal. Sebab pada dasarnya Allah menciptakan manusia bersukusuku dan berbangsa-bangsa dengan latar belakang kultur yang berbeda-beda pula (Baca, Q.S. al-Hujurat (49) : 13 ). Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada munculnya problem-problem sosiologispolitis apabila dihadapkan dengan tatanan norma-norma serta aturan dan perundangundangan yang ditetapkan di dalam kerangka Negara Islam. Lebih-lebih apabila di dalam bingkai Negara Islam tersebut terdapat kelompok-kelompok yang secara ekstrim menafikan dan tidak menghargai eksistensi kemajemukan. Dalam kaitannya dengan keyakinan keberagamaan, biasanya kelompok semacam ini cenderung memunculkan pola-pola keberagamaan yang eksklusif yang mungkin dapat dikategorikan sebagai kelompok fundamentalis, yang menggunakan sudut pandang yang sangat terbatas. Dengan kata lain, bahwa pemahaman keagamaan mereka lebih bersipat eksklusif dengan pandangan bahwa hanya keyakinan dan agama merekalah yang benar, sementara agama yang lain sesat dan jauh dari kebenaran. Dalam terminologi Azyumardi Azra kelompok ini biasanya dicirikan dengan 4 ( empat ) ciri pokok; Pertama, fundamentalisme merupakan oppositionalism terhadap ancaman yang dianggap membahayakan eksistensi agama. Kedua, menolak hermeneutika; penafsiran kritis terhadap teks-teks dan penafsirannya. Dalam konteks ini, maka al-Qur’an harus difahami secara literal tanpa memberi peluang terhadap alternatif pemaknaan yang lain. Ketiga, gerakan atau kelompok fundamentalis menolak pluralisme dan relativisme. Pemahaman dan sikap keberagamaan yang tidak selaras dengan pandangan kelompok fundamentalis dianggap sebagai bentuk dari relativisme keagamaan yang tentunya harus ditolak. Keempat, kelompok ini menolak perkembangan historis dan sosiologis 7 dengan anggapan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari ajaran kitab suci.13 Problem lain yang diprediksi akan muncul dalam kerangka Negara Islam, adalah kemungkinan terjadinya benturan-benturan dan konflik berkepanjangan antar intern umat Islam akibat tarik menarik kepentingan. Karena dalam kenyataannya, terdapat dua arus pemikiran kontradiktif dalam kaitannya dengan keharusan mendirikan Negara Islam. Arus pertama berpendapat, bahwa untuk melaksanakan syari’at Islam dalam tatanan kehidupan umat diperlukan suatu kekuasaan pemerintahan yang bernaung di bawah panji-panji Negara Islam. Arus ini menegaskan penolakannya terhadap pemisahan antara agama dan negara, karena dalam pandangan mereka Islam adalah din dan dawlah. Islam juga merupakan agama yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk mengatur persoalan-persoalan kenegaraan. Arus inidalam perjuangannya sangat bersemangat untuk mendirikan Negara Islam, karena menurut mereka tanpa adanya Negara Islam, maka kehidupan Islam tidak mungkin dapat direalisasikan secara utuh. Para pionir dalam arus pemikiran ini, antara lain Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, Hasan al-Banna dan Abul A’la al-Maududi. Sedangkan arus kedua memandang bahwa keterutusan Muhammad SAW hanya membawa satu misi, yaitu misi spiritual keagamaan ( risalah ruhiyah diniyah ) yang sama sekali tidak bermaksud membangun sebuah negara. Oleh karena itu mereka menolak keterlibatan agama dalam urusan urusan negara atau pemerintahan; hubungan agama dan negara merupakan hubungan yang terpisah dan tidak mungkin untuk dipersatukan, sebab agama hanya mengatur persoalanpersoalan spiritual umat, sedangkan negara mengatur persoalan-persoalan duniawi. Menurut arus pemikiran ini, di dalam Islam tidak ada ruang untuk berpendapat 13 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme Hingga Post Modernisme ( Bandung : Mizan, 1996 ), hlm.109-110. 8 bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhamad mengandung kewajiban mendirikan sebuah Negara Islam yang wujudnya dalam bentuk sistem khilafah. Institusi negara dalam pandangan mereka tidak terlalu penting dan yang paling penting adalah komitmen untuk mengimplimentasikan nilai-nilai ajaran Islam. Di antara para tokoh yang menganut arus pemikiran yang kedua ini, antara lain Ali Abd. Al-Raziq dan Thaha Husein, keduanya tokoh intelektual yang berasal dari Mesir. Di dalam kancah pemikiran politik di dunia Islam, kedua arus pemikiran di atas pada akhirnya melahirkan dua bentuk kecenderungan yang antagonistis dalam pengelolaan sebuah negara, terutama pasca penjajahan dan setelah berdirinya negara-negara nasional di dunia Islam. Dua kecenderungan itu ialah kecenderungan sekularistik dan kecenderungan religius yang masing-masing pendukungnya oleh sebagian pakar disebut nasionalis sekuler atau aliran substansialis dan nasionalis religius atau aliran skripturalis religius. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat heterogen, baik dari sisi agama, ras, adat istiadat maupun budaya. Secara konstitusional, setiap warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama, dan secara yuridis formal memiliki perlakuan yang sama di muka hukum. Heteroginitas dan kemajemukan ini pula yang membuat kenyataan bahwa Indonesia bukan negara agama ( religious state ) tetapi “ nation state “, yang oleh karenanya para Founder Fathers negara kita menjadikan Pancasila serta UndangUndang Dasar 1945 sebagai falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. Atas dasar ini, maka konsepsi Negara Islam menurut hemat penulis kurang pas, dan bahkan tidak relevan untuk konteks ke-Indonesiaan. Selain dari itu, konsepsi Negara Islam yang ditawarkan oleh para pemikir politik Islam semacam al-Maududi dan kawankawan, nampaknya sangat normatif, ideologis dan formalistis. Sehingga pada tataran aplikasinya sangat sulit untuk diwujudkan, dan tidak mustahil akan menimbulkan problem-problem politis, ketegangan-ketegangan keberagamaan serta konflik-konflik berkepanjangan, baik intern maupun antar umat beragama. Komunitas muslim, tentu saja menginginkan agar syari’at Islam dapat berlaku dalam negara di mana mereka berada, dan berkeinginan agar hukum Islam dapat mewarnai keputusan-keputusan politik. Akan tetapi, untuk merealisasikan keinginan 9 dan harapan tersebut- menurut penulis tidak harus menggunakan konsep Negara Islam, atau secara formal memberi label negara dengan label Islam. Membangun tatanan masyarakat Islam yang secara konsekuen melaksanakan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, menurut penulis merupakan langkah konkret dalam upaya mewujudkan keinginan dan harapan dia atas. Di satu sisi, konsepsi Negara Islam memang harus diakui sebagai cerminan dari bentuk sebuah negara ideal di dalam Islam yang sangat ideologis dan formalis. Tetapi di sisi lain nampaknya memiliki kelemahan-kelemahan, di mana secara doctriner memiliki kecenderungan eksklusif terutama dalam konteks merespon arus modernisasi. Dalam konsep Negara Islam ditemukan doktrin yang menyatakan bahwa nilai dan tradisi yang benar hanyalah yang berasal dari Islam, semua nilai dan tradisi yang bukan dari Islam adalah sesat dan harus ditolak, bahkan bila perlu penolakannya melalui proses kekerasan. Doktrin lain yang cenderung eksklusif, adalah pandangan bahwa kebudayaan Barat merupakan musuh Islam, dan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Barat dianggap berbahaya. Dua contoh konkret dari konsepsi Negara Islam di atas, menurut hemat penulis lebih bersipat apologistis dan pemaksaan terhadap klaim kebenaran, sehingga sulit mengakomodir hal-hal yang berasal dari luar Islam atau sama sulitnya menerima pemikiran-pemikiran orang lain. Penutup Beragama sejatinya menjadi kebutuhan dengan memadukan spiritualitas dan rasionalitas. Upaya meresonansikan keberagamaan dengan memaksimalkan kekuatan jiwa dan akal melahirkan pribadi paripurna. Tidak ada agama bagi orang tidak berakal, sepatutnya dimaknai sebagai proses pemahaman dan spiritualitas yang tercermin dalam pengalaman agama. Tetapi akal tidak sepatutnya diberhalakan dalam beragama. Akal sebagai pijakan rasionalitas memiliki keterbatasan dalam memahami agama, terutama dalam dimensi transendensi-ketuhanan. Merasionalkan agama acapkali melahirkan kegamangan. Karenanya, ritus spiritualitas agama menjadi bagian penting yang justru lazim diabaikan cendekiawan agama. Menakar kesadaran keberagamaan dengan akal, maka tidak tertutup kemungkinan lahirnya analogi-analogi yang tidak relevan. Alih-alih dapat menyakinkan, justru berbuah kecaman. 10 Kedatipun begitu, bagaimanapun agama merupakan kumpulan ajaran yang mutlak dan transeden. Lain halnya dengan politik, kapan dan dimanapun yang namanya politik adalah sesuatu yang relatif dan berubah-ubah sepanjang masa. Politik digerakkan untuk kepentingan-kepentingan yang beragam sehingga cenderung bertabrakan kepentingan satu dengan lainnya. Agama adalah ajaran suci yang justru paradoks dengan konflik, agama meniscayakan kedamaian dan sebaliknya politik selalu berurusan dengan persoalan konflik kepentingan. Muhammed Abid Abed alJabiri (1992) – pengusung al ’Aql al-Siyasi al-Arab – dalam Wijhah-nya mengkhawatirkan perbedaan kepentingan soal agama, bila digerakkan oleh kepentingan politik tertentu akan memunculkan sektarianisme dan primordialisme yang kemungkinan berakhir pada konflik. Politisasi agama juga menjadi kecenderungan lain sebagai implikasi beragamnya kepentingan kelompok, artinya politisasi agama muncul dari kondisi atau faktor tertentu. Disinilah problemnya. Bila menghindar dari jalur politik-struktural tentu akan meninggalkan “ruang” yang memungkinkan memperjuangkan kemaslahatan umat Islam, lalu akan diambil oleh “orang lain”. Maka alternatif yang lebih selamat adalah memperjuangkan kemaslahatan umat dengan komitmen membangun moralitas politik, bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja. Di Indonesia pemikiran politik Islam di Indonesia, baik langsung maupun tidak, banyaknya juga terpengaruh dari polarisasi di atas. Akibatnya, pemikiram politik ini terjebak dalam dikotomi dan polarisasi yang sebenarnya kurang bermakna kondusif bagi suatu pengembangan konseptual, sebab pemikiran tersebut sejak awal telah mengesankan ekslusifisme yang menolak setiap masukan yang dianggap tidak Islami, dalam hal ini nilai-nilai yang berasal dari pemikir-pemikir Barat yang juga cukup berpengaruh, terutama di awal pembentukan republik Indonesia 11 12

![Modul Agama [TM12] - Universitas Mercu Buana](http://s1.studylibid.com/store/data/000296276_1-33954cb90007e13aff298fe7ca956f57-300x300.png)