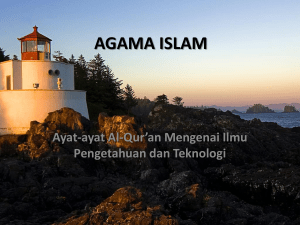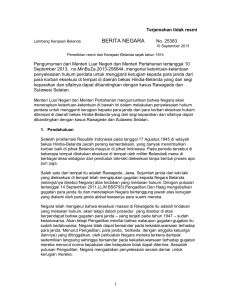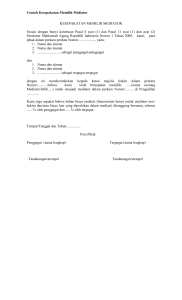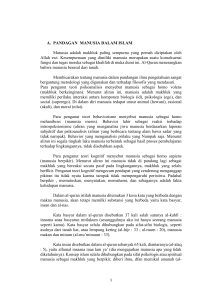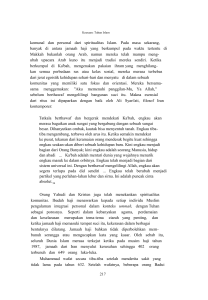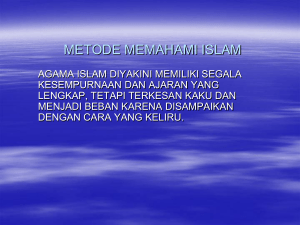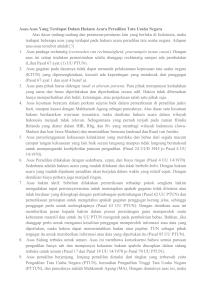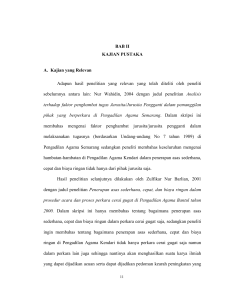Bantahan HTI Terhadap Permohonan Pengujian Materiil
advertisement

Bantahan HTI Terhadap Permohonan Pengujian Materiil UU Tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Bantahan Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama oleh Tim Advokasi Kebebasan Beragama Sebagaimana telah diketahui, Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 berisi tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Undang-undang itu kini sedang dimintakan Tim Advokasi Kebebasan Beragama untuk dicabut. Jika dicermati, undang-undang itu bagian dari upaya negara untuk melindungi warganya dari beredar dan tersebarnya penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang terhadap pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Juga, dari perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sebagai salah satu agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam dan umatnya termasuk di antara yang dilindungi oleh undang-undang itu. Apabila undang-undang itu dicabut sebagaimana diinginkan penggugat, maka perlindungan terhadap kesucian dan kemurnian Islam menjadi terancam. Ketika undang-undang ini masih berlaku saja, berbagai penafsiran dan praktik keagamaan yang menyimpang terus bermunculan, apalagi jika dihapus. Demikian pula dengan berbagai tindakan yang menjurus pada permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap Islam. Maka bisa dipastikan, jika larangan terhadap semua perbuatan itu dicabut, penyimpangan, dan penodaan terhadap Islam akan semakin marak. Namun anehnya, dalam materi gugatannya tim penggugat juga menjadikan Islam dan realitas umat Islam sebagai dasar argumentasinya; sehingga dikesankan bahwa gugatan mereka seolaholah sejalan atau tidak bertentangan dengan Islam. Padahal, setelah dikaji secara cermat dan mendalam, argumentasi yang digunakan penggugat ternyata banyak mengandung kelemahan, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta. Bahkan di antara isinya mengandung unsur provokasi yang bisa menyulut konflik. Beberapa di antaranya adalah: 1. Dalam materi gugatannya penggugat mengatakan (38a, hal. 19): Seperti dalam Islam, misalnya yang mengenal banyak aliran keagamaan: Sunni, Syi’ah, Mu’tazilah, Khawarij, dan seterusnya. Dalam satu aliran dikenal pula beragam mazhab. Setidaknya ada empat mazhab fikih dalam aliran Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Pada level teologi, Sunni bahkan terbagi pula dalam aliran Asy’ariyah dan Maturidiyah. Begitu juga, penggugat menyatakan (154, hal. 53): Bahwa keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama menimbulkan problematika tentang siapa otoritas yang dipakai untuk menafsirkan bahwa suatu agama telah dimusuhi, disalahgunakan, atau dinodai. Penggugat juga menegaskan (169, hal. 60): Bahwa seyogyanya dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan/atau agama negara tetap berada di tengah dengan tidak berpihak pada salah satu ajaran/aliran/tafsir. Realitas beragamnya kelompok dan madzhab di tengah kehidupan umat Islam ini dijadikan sebagai dasar argumentasi bahwa pokok-pokok ajaran tidak memiliki ketentuan yang baku. Padahal kenyataannya tidak demikian. Memang benar, bahwa di tengah kehidupan umat Islam terdapat banyak madzhab seperti yang disebutkan oleh penggugat. Namun banyaknya madzhab dan kelompok di dalam Islam tidak membuat Islam itu kehilangan alat ukur untuk menilai apakah sebuah madzahab atau kelompok masih berada dalam koridor Islam atau sudah keluar darinya. Alat ukur itu tidak lain adalah alQuran dan al-Sunnah. Sebab, keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, baik dalam perkara akidah -yang menjadi perkara pokok atau ushûl- maupun syariah -yang disebut sebagai perkara cabang atau furû’. Jika dikatakan, bukankah semua kelompok dan madzhab berhak untuk mengklaim bahwa pendapatnya diambil dari al-Quran dan al-Sunnah, mengapa masih terjadi perbedaan? Bukankah itu menunjukkan bahwa panafsiran terhadap keduanya bersifat relatif sehingga tidak bisa menafikan satu sama lain? Kalau ada yang berpendapat demikian, itu menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui -atau purapura tidak tahu– fakta al-Quran dan al-Sunnah. Sebagai sebuah kalam (perkataan) -kaum liberal sering menyebutnya sebagai ‘teks’–, al-Quran dan al-Sunnah memang berpotensi menimbulkan beragam penafsiran. Akan tetapi tidak semua ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw bersifat demikian. Sebab, dalâlah (penunjukan makna) dalam kedua sumber itu ada yang bersifat qath’iy (tegas dan jelas) sehingga tidak memungkinkan penafsiran lebih dari satu makna; dan ada yang bersifat zhanniy (samar dan berisi dugaan), yang membuka peluang terjadinya perbedaan. Realitas inilah yang dinyatakan oleh al-Qur’an surat Ali Imran [3]: 7, bahwa ayat al-Quran terbagi menjadi dua, yakni: ayat muhkamât dan ayat mutasyâbihât. Ayat muhkamât adalah ayat yang jelas makna dan penunjukannya, tidak ada kesamaran di dalamnya,[1] dan hanya mengandung satu makna[2] sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.[3] Contohnya adalah firman Allah Swt: ﴾ ﴿ ٌَ َد ََ ْ َّللاَ ُْ ْ ُل Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa (QS al-Ikhlash [112]: 1). Dalâlah atau penunjukan makna ayat ini sangat jelas. Tidak bisa ditafsirkan lain kecuali bahwa Allah itu hanya satu. Jika ada yang menafsirkan ayat ini bahwa Allah Swt itu ada dua, tiga, atau, empat, maka dapat dipastikan penafsirannya telah menyimpang dari kandungan ayat ini. Demikian juga dengan firman Allah Swt: ﴾ََر َْتَال ﴿الْ بَْ َ ْءََ َّلل ش ْ ْ َْ َّللةَْح فَاَ ْ َ َّْ إَْ ْ لَ ْا Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (QS al-Isra’ [17]: 32). Berdasarkan ayat ini, zina merupakan perbuatan tercela dan dilarang. Jika ada yang menafsirkan sebaliknya, misalnya menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang diperbolehkan, bahkan perbuatan terpuji dan diperintahkan, jelas merupakan penafsiran yang menyimpang. Sedangkan ayat mutasyâbihât adalah kebalikan dari ayat muhkamât. Ayat mutasyâbihât adalah ayat yang maknanya mengandung kesamaran dan multitafsir, sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu kemungkinan makna.[4] Contoh firman Allah Swt: ﴾َر ْ ﴿ُ َْا ْ ال ْ لِّ َالاَ َُ َّللةسش Atau kalian menyentuh perempuan (QS an Nisaa [4]: 43). Kata lâmastum di dalam ayat tersebut dipahami oleh sebagian mujtahid dengan makna haqîqiy (denotatif), yakni menyentuh dalam arti sebenarnya. Sebagaian lainnya, memahami lafadz tersebut dengan makna majâzi (konotatif), yakni berarti jima’ (bersetubuh).[5] Pada dalil-dalil yang bersifat zhanniy inilah ladang untuk berijtihad itu terbuka. Karena sifatnya yang multitafsir, maka perbedaan ijtihad di dalamnya masih dibolehkan, dan ditolelir oleh Islam. Dalam ranah inilah yang kemudian berkembang menjadi banyak madzhab. Semua madzhab itu, selama mendasarkan pada dalil-dalil yang mu’tabar, masih terkatagori sebagai al-madzâhib alIslâmiyyah (madzhab Islam). Dalam konteks inilah, sebenarnya perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat shalat Tarawih dan qunut shalat Shubuh itu berada. Anehnya, hal ini justru dijadikan alasan gugatan oleh penggugat (hal. 23). Hal yang sama tentu tidak berlaku pada perkara-perkara yang dibangun dari dalil yang bersifat qath’iy. Karena makna yang ditunjukkan sudah sedemikian jelas, sehingga tidak diperlukan lagi ada ijtihad di dalamnya. Tidak boleh pula terjadi perbedaan dan perselisihan dalam memahaminya. Allah Swt melarang sekaligus mengancam orang-orang yang berbeda pendapat mengenai hal-hal yang ketentuannya sudah jelas (al-bayyinât) di dalam Kitab dan Sunnah dengan azab yang berat. Allah Swt berfirman: ﴾َّللت ْال ْ َِْر ْاَُاة َ َْر ََ َُ َّللةَتََْشس ُ ُْ َّ ََْ َُ ْال ُ ٌ﴿ ْ َم بَْ ْءءٌََ َّلل ْاَّلل َلاََُْْ َء َّلل ِّ َم ََْ ََل َِّْ ْا ْ َُُ ْالْ بْ ََ َ َّلل ْ َة Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat (QS Ali Imran [3]: 105).[6] Dalam Islam, semua perkara yang menjadi pokok agama (ushûl al-dîn) didasarkan kepada dalil yang qath’iy ini. Yang tercakup di dalamnya adalah iman kepada Allah Swt, malaikat-malaikatNya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan al-qadhâ’ wa al-qadar. Maka siapa pun yang mengingkari perkara itu, seluruhnya atau sebagian, telah keluar dari Islam. Demikian pula dengan perkara-perkara hukum yang telah diketahui urgensinya dalam Islam (ma’lumun min ad-din bi ad-dharurah), seperti wajibnya shalat, puasa, zakat, haji, atau haramnya membunuh, berzina, mencuri, hukuman qishash bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri, dan sebagainya adalah termasuk perkara yang tidak memerlukan ijtihad.[7] Siapa pun yang mengingkarinya, maka terjerumus dalam kekufuran. Dengan demikian, meskipun di tengah umat Islam banyak madzhab dan kelompok bermunculan, dengan mudah dapat diidentifikasi dan diklasifikasi, apakah sebuah kelompok atau aliran tersebut masih berada dalam koridor Islam atau sudah darinya. Di dalam Islam telah jelas perkara apa yang harus sama, dan perkara apa yang diperbolehkan berbeda. Islam juga telah menetapkan sejumlah pemikiran dasar, baik yang tercakup dalam rukun Islam, rukun iman, maupun sejumlah pemikiran yang dinyatakan oleh dalil-dalil yang qath’iy. Jika ada kelompok yang mengklaim sebagai kelompok Islam, tetapi pandangan dan pemikirannya bertentangan dengan sejumlah pemikiran dasar di atas, maka kelompok tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kelompok Islam. Bertolak dari sini, maka argumen penggugat yang menyebut bahwa banyak kelompok menyulitkan penentuan perkara mana yang termasuk dalam pokok-pokok ajaran Islam telah gugur dan harus ditolak. Begitu juga, sangat jelas bahwa otoritas yang menentukan apakah suatu agama dimusuhi adalah ajaran agama itu sendiri, dan tentu melalui pemimpin kaum Muslim. Misalnya, al-Quran secara qath’iy menetapkan bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, maka Ahmadiyah yang telah menyatakan adanya Nabi lain setelah Nabi Muhammad jelas-jelas telah menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan hal itu, gugatan bahwa Negara harus tidak berpihak pada salah satu ajaran/aliran/tafsir termasuk ajaran/aliran/tafsir yang menodai Islam menjadi tidak relevan. Sebab, Negara mestinya harus bertindak menjaga kemurnian agama, khususnya Islam dan berpihak kepada Islam. Negara juga memberikan kebebasan kepada agama lain untuk tetap hidup. Baru dalam hal-hal yang furu’ (cabang), Negara boleh memberikan kebebasan kepada masing-masing orang untuk melaksanakan keyakinannya. Bila ada penodaan terhadap agama Islam, maka pelakunya harus dihukum oleh Negara. Adapun penghilangan peran Negara dalam masalah agama ini sesungguhnya merupakan ciri khas pandangan Liberal, baik di bidang ekonomi maupun agama. Pandangan seperti ini jelas bertentangan dengan Islam itu sendiri yang justru meniscayakan peranan negara, baik di bidang agama maupun ekonomi, dan tentu dalam seluruh bidang yang lain. Selain itu, juga bertentangan dengan konstitusi negara ini. 2. Penggugat memaknai kebebasan beragama (45, hal. 27): Bahwa kebebasan ‘memeluk’ suatu agama atau keyakinan meliputi pula kebebasan memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk berganti agama atau keyakinan dengan agama lainnya atau memeluk pandangan atheistik …. Pemaknaan seperti ini jelas tidak sesuai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sini jelas, bahwa yang dikehendaki oleh penggugat adalah kebebasan apapun, kemunculan aliran atau agama baru apapun, termasuk kebebasan menjadi atheis. Ini adalah usulan yang akan menghancurkan sendi-sendiri Negara. Karenanya pandangan seperti ini harus ditolak dan batal. 3. Dalam materi gugatannya penggugat mengatakan (38a, hal.19): Perbedaan pemikiran keagaaman dalam Islam tidak hanya menyangkut doktrin pinggiran (furu’iyyah), melainkan juga masalah yang lebih fundamental (ushuli). Perdebatan antara Sunni dan Mu’tazilah bahkan mengenai hubungan antara zat Allah dan sifatnya. Mu’tazilah mengatakan bahwa al-Quran itu makhluk, oleh karenanya tidak kekal. Sementara Sunni menganggapnya kekal dan melekat pada diri Allah.” Begitu juga, dalam materi gugatannya penggugat menyatakan (144, hal. 51): Ahmad Bin Hambal (Tahun 241H/855), dipenjara dan disiksa karena rezim saat itu mengambil aliran Mu’tazilah sebagai aliran keagamaan resmi Negara, hal mana Ahmad bin Hambal dianggap menyimpang dari doktrin Mu’tazilah. Setelah Negara mengganti aliran keagamaan resmi, maka saat itu pula Ahmad Bin Hambal dipulihkan dari status penyimpangannya, bahkan diakui sebagai ulama besar. Dalam khazanah tsaqâfah Islam memang dikenal istilah ushûl dan istilah furû’. Istilah ushûl aldîn merujuk kepada perkara akidah, sementara istilah furû merujuk kepada perkara syariah. Telah diungkap di muka, bahwa dalam perkara ushûl al-dîn umat Islam tidak diperbolehkan berbeda. Terhadap perkara ushûl, manusia diwajibkan meyakininya. Siapa pun yang mengingkarinya meyebabkan seseorang jatuh pada kekufuran. Akan tetapi, di dalam perkara pokok itu sendiri terdapat perkara-perkara yang menjadi cabangnya (far’[un] min amri ushûliy). Tentu ada perbedaan di antara keduanya. Jika perkara pokok tidak boleh terjadi perbedaan, sementara dalam perkara cabang dari perkara yang mendasar itu masih memungkinkan terjadi perbedaan. Dalam perkara ushûl, dalil yang digunakan sebagai dasarnya harus bersifat yang qath’iy, baik tsubût (ketetapannya sebagai dalil) maupun dalâlah (penunjukan maknanya)-nya. Sementara dalam far’[un] min amri ushûliy memungkinkan terjadinya perbedaan karena tidak harus dibangun dari dalil yang qath’iy. Perbedaan dalam perkara inilah yang kemudian melahirkan berbagai madzâhib i’tiqâdiyyah (madzhab akidah), seperti Ahlussunnah, Muktazilah dan Jabariyah. Sebagai contoh, Iman kepada adanya malaikat-malaikat Allah Swt merupakan perkara ushûl. Keimanan ini didasarkan pada dalil yang qath’iy, baik tsubût maupun dalâlah-nya. Sedangkan perkara nama-nama malaikat beserta tugasnya merupakan pembahasan cabang. Apabila perkara itu didasarkan kepada dalil yang qath’iy, maka wajib dimani. Seperti mengimani kebaradaan malaikat Jibril dan Mikail. Maka siapa pun yang mengingkari keberadaannya, telah menyimpang dan keluar dari Islam. Namun jika keberadaannya didasarkan pada dalil yang bersifat dzanni, baik tsubût maupun dalâlah-nya, maka pengingkaran terhadapnya tidak mengakibatkan kekufuran. Misalnya, keberadaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena dalil mengenainya tidak sampai qath’iy, maka kalau ada yang mengingkarinya tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Demikian juga dengan keimanan pada al-Quran. Bahwa al-Quran adalah kalâmul-Lâh, kitab yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw, semua isinya benar, di dalamnya tidak ada penambahan, pengurangan, dan perubahan adalah merupakan perkara yang wajib diimani. Ini merupakan perkara ushûl. Keimanan terhadapnya didasarkan pada dalil-dalil yang qath’iy. Maka siapa pun yang mengingkarinya bisa dinyatakan telah dari Islam. Berbeda halnya dengan pembahasan apakah al-Quran adalah makhluk atau bukan. Ini termasuk dalam pembahasan perkara cabang. Dalil-dalil yang menjelaskan perkara ini tidak sampai pada derajat qath’iy. Maka perbedaan pandangan dalam perkara ini tidak sampai mengantarkan kepada kekufuran. Inilah sesungguhnya yang terjadi dalam kasus perdebatan antara Ahlussunnah dengan Mu’tazilah. Imam Ahmad, misalnya, sekalipun tidak sependapat dengan penafsiran Mu’tazilah yang menganggap al-Quran adalah makhluk, namun beliau tidak menyebut pengikut Mu’tazilah telah keluar dari Islam. Demikian juga sebaliknya. Kasus dipenjaranya Imam Ahmad bin Hambal juga tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi, karena ini merupakan bentuk kesalahan kebijakan Khalifah saat itu. Sebab, di dalam Islam seorang Khalifah tidak boleh mengadopsi satu mazhab tertentu, karena negara, dalam pandangan Islam, bukanlah negara madzhab. Pandangan Imam Ahmad bin Hambal pun bukan merupakan penyimpangan dari Islam, karena tidak menyangkut pokok akidah. Namun, hal ini berbeda dengan penyimpangan yang dilakukan Ahmadiyah, misalnya. Sebab, Ahmadiyah, Moshadek, Lia Eden, dll menyimpang dari pokok-pokok akidah. Karenanya, peristiwa Imam Ahmad bin Hambal tidak dapat dijadikan argumen untuk memberi justifikasi penyimpangan akidah. Hizbut Tahrir sendiri berpandangan, perkara ini tidak perlu dibahas, apalagi menjadi bahan perdebatan berkepanjangan. Alasannya, tema tersebut merupakan perkara ghaib, sementara dalildalil tentangnya tidak sampai pada derajat qath’iy. Maka sikap terbaik adalah mendiamkannya, tidak menambah dan mengurangi. Karena itu, contoh-contoh yang digunakan oleh penggugat tidak relevan untuk menggugat undang-undang yang melarang penafsiran yang menyimpang dari pokok ajaran agama yang dianut, dan oleh karena harus ditolak. 4. Dalam materi gugatannya penggugat mengatakan bahwa rumusan pokok ajaran agama berbeda pada tiap kelompok. Untuk melegalisasinya dinyatakan (38a, hal.19): Misalnya apa yang didefinisikan sebagai ajaran pokok Islam oleh Ahmad bin Naqib al-Misri berbeda dengan yang didefinisikan oleh Abu Bakar al-Jazairi, Ali al-Tamimi, dan Abd al-‘Aziz bin Abu Allah bin Baz. (lihat Abdullah Saeed hal. 44-47). Jika al-Misri mengatakan bahwa ada 9 pokok Islam yang dihukum berat adalah jika: (1) merendahkan di depan sebuah berhala atau objek, seperti matahari dan bulan; (2) mengeluarkan kata-kata yang berarti ketidakpercayaan, seperti “saya adalah Allah” atau Allah itu tiga”; (3) menyangkal keberadan Allah, keabadian-Nya tanpa awal dan akhir, atau untuk menyangkal segala karakteristik di mana ada konsesus seluruh Muslim terhadap-Nya; (4} Menghina Allah dan rasul-Nya; (5) Bersikap sinis pada nama Allah, perintahNya, laranganNya, janjiNya, atau ancamanNya; (6) menyangkal ayat al-Quran atau pun yang disepakati oleh intelektual menjadi bagiannya, atau menambah ayat yang awalnya tidak ada di dalamnya; (7) meyakini bahwa pembawa pesan Allah atau Nabi adalah pembohong atau menyangkal mereka dikirim; (8) menyangkal kewajiban yang sudah dikonsesuskan oleh Muslim seperti shalat, bahkan rakaah dari 1 dari 5 kali shalat wajib; (9) menyangkal keberadaan malaikat atau jin atau surga. Sementara itu al-Jazairi mengatakan bahwa ada 5 hal pokok yang dihukum berat: (1) Menghina Allah atau Nabi atau Malaikat; (2) menyangkal untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya atau kenabian Nabi atau memegang keyakinan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad; (3) menolak kewajiban Islam (faridah) di mana ada kesepakatan umum seperti shalat, zakat puasa, naik haji, berlaku baik pada orang tua, atau jihad; (4} yakin bahwa tindakan pelanggaran hukum seperti adultery, minum alcohol, pencurian pembunuhan, atau praktek black magic adalah legal; (5) menolak bab, ayat atau surat dari al-Quran. Kedua definisi di atas dijadikan contoh oleh penggugat untuk memperkuat argumentasinya bahwa perkara pokok dalam Islam itu berbeda-beda. Padahal, jika dicermati kedua definisi yang diberikan para ulama itu tidak berbeda, apalagi saling bertentangan. Kalaupun tampak ada perbedaan, itu hanyalah terletak pada redaksional bahasa, bukan substansial. Poin 1 yang disebutkan al-Jazairi: (1) Menghina Allah atau Nabi atau Malaikat, tidak berbeda dengan poin 4 dan 5 yang disebutkan al-Misri: (4) Menghina Allah dan rasul-Nya; (5) Bersikap sinis pada nama Allah, perintah-Nya, larangan-Nya, janjiNya, atau ancaman-Nya. Perkara pokok yang dijelaskan oleh keduanya sesungguhnya adalah sama, yakni melakukan penghinaan atau pelecehan teradap perkara yang disucikan dan wajib diimani. Demikian juga dengan poin 2 yang didefinisikan al-Jazairi: Menyangkal untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya atau kenabian Nabi atau memegang keyakinan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad; sejalan dengan poin 2, 3, dan 7 yang disebutkan al-Misri: (2) mengeluarkan kata-kata yang berarti ketidakpercayaan, seperti “saya adalah Allah” atau Allah itu tiga”; (3) menyangkal keberadan Allah, keabadian-Nya tanpa awal dan akhir, atau untuk menyangkal segala karakteristik di mana ada konsesus seluruh Muslim terhadap-Nya; (7) meyakini bahwa pembawa pesan Allah atau Nabi adalah pembohong atau menyangkal mereka dikirim. Perkara pokok yang dijelaskan oleh keduanya sesungguhnya juga sama, yakni penolakan dan pengingkaran terhadap keimanan kepada Allah Swt dan rasul-Nya. Keimanan Allah Swt di sini mencakup semua sifat-Nya yang didasarkan pada dalil yang qath’iy, semisal tentang keesaan dan keabadian Allah Swt. Demikian juga keimanan kepada Nabi-nabi Allah Swt. Keimanan terhadap mereka membawa konsekuensi bahwa mereka terjaga dari kesalahan, termasuk dari perbuatan bohong. Tercakup di dalamnya adalah keimanan kepada Nabi Muhammad saw sebagai seorang Nabi dan Rasul sekaligus sebagai penutupnya. Ini adalah perkara pokok yang wajib diimani. Maka pengingkaran terhadapnya menyebabkan pelakunya terjatuh dalam kekufuran. Poin 4 yang disebutkan al-Jazairi: Yakin bahwa tindakan pelanggaran hukum seperti adultery, minum alcohol, pencurian pembunuhan, atau praktek black magic adalah legal; sama dengan poin 8 yang didefinisikan al-Misri: Menyangkal kewajiban yang sudah dikonsesuskan oleh Muslim seperti shalat, bahkan rakaat dari 1 dari 5 kali shalat wajib. Perkara pokok yang dikemukakan keduanya sesungguhnya menunjuk kepada perkara yang sama, yakni mengingkari perkara hukum yang telah disepakati oleh kaum Muslim. Haramnya alkohol, pencurian, black magic atau sihir adalah perbuatan haram yang didasarkan pada dalil-dalil qath’i, baik tsubût maupun dalâlah-nya. Demikian pula dengan wajibnya shalat 5 waktu merupakan perkara yang qath’iy. Tidak ada perbedaan di kalangan kaum Muslim tentang wajibnya. Maka apabila ada orang yang menyelisihinya, sudah pasti dia keluar dari Islam. Poin 5 yang disampaikan oleh al-Jazairi: Menolak bab, ayat atau surat dari al-Quran; sama dengan poin 6 yang disampaikan oleh al-Misri: menyangkal ayat al-Quran atau pun yang disepakati oleh intelektual menjadi bagiannya, atau menambah ayat yang awalnya tidak ada di dalamnya. Kedua penjelasan ini menunjuk kepada satu tindakan yang sama, yakni mengingkari al-Quran dan kemurniannya, baik seluruhnya maupun sebagian. Termasuk dalam perkara pokok keimanan adalah keimanan akan kebenaran seluruh isi al-Quran; tidak ada penambahan, pengurangan, atau perubahan. Maka siapa pun yang mengingkarinya, maka telah mengeluarkannya dari Islam. Sesungguhnya, kedua penjelasan ulama mengenai perkara pokok yang wajib dihukum berat itu dapat ditarik benang merah. Bahwa setiap pengingkaran terhadap perkara yang dibangun atas dalil yang qath’iy (tusbût dan dalâlah), baik dalam perkara ushûl maupun perkara furu’ dapat mengeluarkan seseorang dari keimanan atau murtad. Demikian juga penghinaan dan pelecehan terhadap perkara yang disucikan (umûr muqaddasah) dalam Islam. Sementara murtad dalam pandangan Islam terkatagori sebagai perbuatan kriminal yang hukumannya sangat berat, yakni hukuman mati. Jelaslah bahwa definisi perkara pokok yang dijelaskan oleh kedua ulama itu tidak berbeda sebagaimana anggapan penggugat. Kalaupun tampak ada perbedaan, itu hanya menyangkut redaksional bahasanya. Oleh karena itu, dengan sendirinya hal ini tidak bisa digunakan sebagai dasar argumentasi penggugat. 5. Dalam materi gugatannya mengatakan (38b dan c, hal.21, 22): “Bahwa apa yang disebut penyimpangan tafsir sesungguhnya adalah perbedaan tafsir antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, maka kegiatan yang dianggap menyimpang oleh satu kelompok belum tentu dianggap menyimpang oleh kelompok lainnya.” Pernyataan penggugat ini jelas berusaha merancukan antara perbedaan (ikhtilâf) dengan penyimpangan (inhirâf). Padahal, dalam Islam keduanya menunjukan fakta yaang berbeda. Jika ikhtilâf masih diperbolehkan, sementara inhirâf jelas dilarang, bahkan inhirâf bisa menyebabkan pelakunya terjerumus dalam kekufuran. Karena itu, kerancuan terhadap keduanya bisa berakibat sangat fatal. Sebagai contoh, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah tentang qunut dan tidak qunut dalam shalat Subuh adalah masalah ikhtilâf. Ini berbeda dengan perbedaan antara Ahmadiyah, yang menyatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dengan kelompok Islam yang menyatakan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Pandangan Ahmadiyah ini disebut inhirâf (penyimpangan), bukan ikhtilâf. Sebagaimana telah diungkap di depan, dalâlah (penunjukan makna) dalam al-Quran dan Hadits Nabi saw ada dua macam, yakni: qath’iy dan zhanniy. Firman Allah Swt: ﴾ُْ ُاَ َُ فل ََّ ََْ ََ َء َّْ ُ َْا ََْ ََ َء ْ َّللةُْ ْاف ََّ إُْ َ اَ ََ ََم ِّ َم ٌَْ َتد ُْ ََّ َْْ ن َ ْ َِّْ إَْ ْء َ ق َ ال ََم ْاٌْ َل إَْ ْء ْ َُاَ َُ ََْم إْء َ َ َل إْس ﴿ََْلِّ الَ َ ْلدَ َّللةسش ََْي Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah (QS al-Baqarah [2]: 237). Kata al-ladzî bi yadihi uqdat al-nikâh dalam ayat ini memang dapat menimbulkan penafsiran ganda, yakni suami atau wali perempuan. Sebab, merekalah yang melakukan akad. Jika ditafsirkan ‘suami’, maka yang dimaksud dengan pemberian maaf suami adalah dengan memberikan mahar sebesar jumlah yang ditetapkan. Namun jika ditafsirkan ‘wali perempuan’, maka maksudnya adalah membebaskan suami dari kewajiban membayar mahar. Berbeda halnya dengan firman Allah Swt: ك ْْ ْ ِ ْالْ بَْ َسَ ََ َّلل َّللة َََ َ ءْ َر ْ ِ َََ َرِّم ْاا ِّْْلُ َِّ َرِّس ْ لُ ْل َََ ُء ِّ َم َِّ َ ءْ ل ْاةْ َ ُْ َال ْمتَْ َا ََ َُ ْالْ بََ َسَ ََ َّلل َّللة َََ َ ء ْ ِْف ْؤ َّلل َذْسل ْاَّللة َََْْء ْءد ن َْلَاَََ َرِّسَ َّلل ْاةْ َْ َت ُل َِّ َرِّ ُم ْل َََ ُء ِّ َم َِّ َ ء كُ ْاةْ َ ُْ َال ْمتْ ََ َُ َُاة ََّ َْ َلالَ َّْ ف ْؤ َّللةسََ ْاَّللاَ َْ َلال َّْ ْ ْ ْ با ةُسَس ةْ َُْ َه َُ ََْاْ ُْ َءا َ ْاَََتَْ ش Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS al-Baqarah [2]: 221). Ayat ini sangat jelas, tidak menimbulkan banyak tafsir bahwa haram bagi laki-laki Mukmin menikahi wanita Musyrikah, dan wanita Mukminah dinikahi laki-laki Musyrikah. Jika ada yang berkesimpulan sebaliknya, membolehkan pernikahan tersebut jelas telah melakukan penafsiran menyimpang. Jelaslah, menyamakan perbedaan (ikhtilaf) dengan penyimpangan (inhiraf) merupakan kesalahan serius. Karena itu, argumentasi penggugat dalam hal ini harus ditolak. 6. Dalam materi gugatannya penggugat mengatakan (38c, hal.22): Sebagai ilustrasi, dalam penafsiran dan keyakinan orang NU, ziarah kubur dan tahlil adalah bagian dari ibadah (kegiatan keagamaan). Bagi orang Muhammadiyyah atau Wahabi, ziarah adalah bid’ah yang menimbulkan syirik. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Swt. Karena itu, dalam penafsiran orang Muhammadiyyah, orang NU telah melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang. Apabila rumusan hukum positif membutuhkan penjatuhan pilihan pada pebafsiran tertentu, penafsiran Muhammadiyyah misalnya, maka akan ada puluhan juta warga NU yang dikriminalisasi karena melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang.” Argumentasi penggugat ini jelas salah dan tidak dapat diterima. Pertama, klaim bahwa ziarah kubur menurut orang Muhammadiyah dan Wahabi adalah bid’ah menimbulkan syirik, sementara syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Swt merupakan kesimpulan gegabah. Ziarah kubur merupakan perbuatan yang memiliki landasan dalil syar’i. Meskipun Hadits yang dijadikan dalil bersifat zhanniy, tetapi dari segi penunjukkannya jelas. Rasulullah saw bersabda: ََا ْ َا َ ََ َََْْ ْه َََاَ ََ َُ ْال َم ْْ َْد َّللةَ َتَ َ إ Sebelumnya aku pernah melarang kalian berziarah kubu, maka (sekarang) berziarahlah (HR Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i dari Abu Buraidah, Ibnu Majah dari Ibnu Mas’ud, dan Ahmad dari Abu Said al-Khudri). Muhammadiyyah dan Wahabi juga tidak menganggap ziarah kubur sebagai bid’ah, apalagi menimbulkan kesyirikan. Dalam buku Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah oleh AR Fakhruddin disebutkan: Ziarah tidaklah hanya pada waktu-waktu tertentu. Setiap waktu boleh, pagi, siang, sore, semuanya boleh. Tidak harus hari Kamis sore, tidak harus Jum’at sore, tidak harus bulan Ruwah, Bulan Syawal, 17 Agustus, 20 Mei, 5 Oktober, 10 November dan sebagainya. Setiap waktu boleh.[8] Dalam buku itu pun disebutkan adab-adab berziarah kubur. Hanya saja, ada catatan penting yang diajukan: Berziarah bukan untuk meminta berkah. Bukan untuk meminta pangestu. Tetapi untuk mengambil percontohan. Banyak orang yang telah meninggal, tetapi tidak banyak diingat-ingat orang. Sedang orang-orang yang berjasa kepada masyarakat selalu diingat-ingat akan jasanya. Ziarah bukan untuk mendewa-dewakan, lebih-lebih untuk memper-Tuhan-kan seseorang adalah bukan pada tempatnya.[9] Demikian juga dengan Wahabi. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam fatwanya juga mengatakan bahwa ziarah kubur, baik kuburan para wali maupun kaum Muslim secara umum dalam rangka untuk mengingat kematian, mendoakan mereka, dan memintakan ampun adalah perbuatan yang disyariahkan.[10] Tokoh salafi lainnya, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin juga menyatakan: Apabila seseorang berziarah kubur dengan tujuan untuk belajar, dzikir, dan mendoakan mereka sebagaimana doa yang diucapkan Rasulullah saw ketika berziarah, maka ini merupakan ziarah syari’yyah yang diperintahkan untuk dilakukan, baik laki-laki maupun perempuan, siang maupun malam.[11] Memang dalam beberapa rincian tentang masalah ini ada perbedaan-perbedaan. Tetapi, kalau dikatakan bahwa Wahabi dan Muhammadiyah menganggap ziarah kubur sebagai bid’ah yang menimbulkan syirik jelas merupakan pembelokan fakta, bahkan biasa dianggap sebagai provokasi yang dapat menyulut konflik antar kelompok. Kedua, bahwa undang-undang itu berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap perbedaan penafsiran orang NU dan Muhammadiyyah merupakan ilusi dari penggugat. Sepanjang pemberlakuan Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tidak pernah terdengar terjadinya kriminalissi itu. Tidak ada orang NU yang dikriminalisasi karena telah melakukan tahlilan dan ziarah kubur, sebaliknya orang Muhammadiyyah yang tidak melakukan seperti yang dilakukan orang NU tidak ada yang dikriminalisasi. Sebab, para ulama mengetahui bahwa tahlilan dan ziarah kubur merupakan perkara dalam ranah ikhtilâf. Bertolak dari dua alasan ini, maka argumentasi penggugat di atas tidak sesuai dengan fakta dan harus ditolak. 7. Dalam materi gugatannya penggugat mengatakan (38b, hal.21): Islam pasti adalah penyimpangan nyata dari agama Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, sementara Islam hanya menganggap Yesus sebagai Nabi. Jika dirujuk ke dalam sejarah, maka semua agama sebetulnya muncul sebagai bentuk penyimpangan terhadap doktrin-doktrin agama tradisional sebelumnya. Ini jelas merupakan kesimpulan yang gegabah dan mengada-ada. Bahwa akidah Islam bertentangan dengan agama Nasrani atau Yahudi adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Akan tetapi adanya kontradiksi itu tidak bisa disebut bahwa Islam merupakan sempalan dari agama Nasrani dan Yahudi. Sebab, sesuatu bisa disebut sebagai sempalan dari yang lain jika keduanya berasal dari pangkal (agama) yang sama. Dan ini tidak terjadi pada Islam. Sejak awal, Islam dideklarasi sebagai agama sendiri yang berbeda dengan agama-agama lainnya. Dalam kehidupannya, Rasulullah saw sama sekali tidak pernah menjadi pemeluk dua agama tersebut. Beliau juga tidak pernah menjadikan kitab kedua agama itu untuk menjustifikasi ajarannya, ataupun beliau menafsirkannya secara menyimpang. Bahkan, mereka sedang menunggu Nabi baru tersebut (Muhammad) sebagaimana tertera dalam kitab mereka. Jika demikian, dari mana bisa dikatakan Islam merupakan penyimpangan nyata dari agama Kristen seperti yang dikemukakan penggugat? Bukankah ungkapan tersebut justru hanya akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan antarumat beragama? Ini tentu berbeda halnya dengan Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku beragama Islam, namun ajaran yang disampaikannya nyata-nyata bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, Nabi Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tidak ada Nabi dan Rasul sesudah beliau. Maka, siapa pun dan kelompok mana pun yang mengakui ada nabi lagi, seperti yang dilakukan oleh Mirza Ghulan Ahmad, telah menyimpang dan keluar dari Islam. Begitu juga dengan Lia Eden, Ahmad Mosadeq, dkk seperti yang dipersoalkan penggugat, memang nyata-nyata bisa dianggap telah melakukan penyimpangan dari Islam. Keberadaan sekte semacam ini bisa disebut sebagai penyimpangan. Keberadaannya juga amat membahayakan umat Islam. Karena pengikut Ahmadiyyah masih mengaku sebagai Muslim, sebagian ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw juga masih digunakan untuk menjustifikasi keyakinan mereka dan panduan sebagian ibadah mereka. Simbol-simbol Islam juga masih mereka gunakan. Namun, sudah banyak diotak-atik di sana sini. Realitas ini jelas akan mengecoh sebagian umat Islam yang awam sehingga menganggapnya masih sebagai bagian dari Islam. Bertolak dari kenyataan itu, maka argumentasi penggugat jelas salah dan harus ditolak. 8. Dalam materi gugatannya penggugat mengatakan (143, hal. 51): Contoh: Pada Tahun 763 Masehi Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, serta seluruh pengikutnya telah dituduh kafir dan murtad. Beliau ditangkap dan dipenjara, disiksa dan diracun hingga meninggal dunia di penjara. Meskipun demikian, ajaran dan pengikut Mazhab Hanafi, sampai saat ini tetap hidup dan malah semakin berkembang.” Sejarah yang diajukan contoh oleh penggugat bertentangan dengan sejarah yang benar. Tidak ada satu pun buku sejarah yang menceritakan bahwa Abu Hanifah serta seluruh pengikutnya dituduh kafir dan murtad. Memang benar beliau pernah dipenjara oleh khalifah saat itu, akan tetapi bukan lantaran dia dituduh kafir. Abu Hanifah dipenjara karena menolak tawaran khalifah Abu Ja’far al-Manshur sebagai qadhi. Bisa diduga, pembelokan fakta itu hanya digunakan untuk membenarkan gugatannya. Karena itu, argumentasi itu harus ditolak. Secara umum, penggunaan alasan sebagian dalil dalam Islam, realitas umat Islam dan sejarahnya adalah tidak relevan, tidak sesuai dengan fakta, digunakan tidak pada konteksnya, dan mengandung unsur provokasi. Karena itu, semua argumentasi penggugat harus ditolak. 9. Secara umum, Tuntutan penggugat adalah UU no. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Dengan kata lain, mereka menghendaki UU tersebut tidak berlaku. Artinya, mereka menginginkan bebas melakukan penafsiran seenak perutnya terhadap ajaran agama (khususnya Islam) dan penyimpangan terhadap ajaran pokok agama (pasal 1), penyimpangan tersebut tidak dianggap melanggar hukum (pasal 2 dan 3). Selain itu, mereka ingin bebas melakukan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama, juga bebas melakukan hal tersebut supaya orang tidak menganut agama apapun juga (Pasal 4). Intinya, penggugat menginginkan bebasnya bermunculan aliran sesat dan penistaan/penodaan terhadap ajaran agama (Islam). Hal ini menunjukkan bahwa mereka mendewakan HAM dan demokrasi. Mereka telah menjadikan HAM dan demokrasi sebagai agama baru. Semakin banyak aliran sesat muncul maka akan semakin kokoh agama HAM dan demokrasi tersebut. Ini jelas sikap permusuhan terhadap agama-agama. Karenanya, tidak mengherankan bila penggugat secara halus menggiring kepada atheisme. Dalam butir 45 dasar mereka menggugat disebutkan: “Bahwa kebebasan ‘memeluk’ suatu agama atau keyakinan meliputi pula kebebasan memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk berganti agama atau keyakinan dengan agama lainnya atau memeluk pandangan atheistik ….” Karenanya, kalau dulu gerakan ini adalah kelompok sepilis (Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme), kini berkembang menjadi kelompok Sepilis A+, yakni sekulerisme, pluralisme, liberalisme, atheisme, plus pengokohan penjajahan. Berdasarkan hal tersebut maka MK sudah seyogyanya menolak permohonan penggugat. Sebab, bila tidak, dampaknya akan sangat berbahaya: Pertama, aliran sesat akan bermunculan laksana jamur di musim hujan. Mereka akan merasa bebas dengan dalih HAM. Kedua, penghancuran Islam akan terjadi secara terang-terangan dan massif. Sekarang saja kartun penghina Nabi, tuduhan bahwa Islam melecehkan perempuan, al-Quran kitab kekerasan, al-Quran kitab paling porno, harus ada amandemen terhadap al-Quran, cerita kutukan terhadap homoseks kaum Nabi Luth dalam al-Quran adalah cerita bohong, penulisan al-Quran banyak fiktif, dll terjadi di Indonesia. Bila MK mengabulkan tuntutan kelompok Sepilis A+ ini maka akan terjadi penodaan terhadap Islam secara bebas tanpa konsekuensi hukum. Hari ini MK mengabulkannya, besok berbagai penghinaan dan penyerangan terhadap Islam akan bertebaran. Ketiga, bila ini terjadi maka akan terjadi kekisruhan dan konflik di tengah masyarakat. Stabilitas akan terkoyak. Umat Islam akan disibukkan dengan persoalan ini. Sementara, penghancuran akidah dan akhlak terus berlangsung dengan mulus. Yang untung adalah pihak asing penjajah dan antek-anteknya yang memang sejak awal memusuhi Islam dan kaum Muslim serta tidak menginginkan Indonesia aman. Akhirnya kami mengingatkan para hakim MK, bahwa apa yang Anda putuskan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT satu per satu: ك ﴾ ََِّّْللر َُ َه ََ َُ ْا ْ َم ْاةْْ َل ا ََِاَ ََ ْح إََ ْء ْ ََّْللمك ْ ََْ ْلُْ َ سَْ َ َُ ُْا َْ ِّْءد ْابَْ ْءَ اَ َُ َِّْ ْل ةَسَْ َ َُ ْا ْ َُر َ َُ َّللة ْ َْ ََْ ْءك ِّْ َْ ََ َُ َا ْء َُد ْال َس ََ َُ َِّْ َ َس ْ ﴿اَ َُ بَْ ََ َال ََ َّْ ْْ ْال ََاَ َُ ََُْ َه َُ إَ ََ َُ َا ْءْ َرَ ةْْ َل بَْ ْ د ْق ََْ َََسْ ََ َُ ْا “Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami kurniakan kepadamu; dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafa`at yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah).” (QS al-An’am [6]: 94) 1 Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 315; Sa’id Hawa, al-Asâs fî Tafsîr, vol. 2 (Kairo: Dar al-Salam, 1999), 707; al-Qasimi, Mahâsin al-Ta’wîl, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 252 2 al-Qurthubi, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 8-9 3 Wahbah al-Zuhayli, al-Tafsîr al-Munîr , vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 150 4 al-Qurthubi, al-Jâmi’ li Ahkam al-Qur’ân, vol. 2, 9; al-Wahidi al-Naysaburi, al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur’ân al-Majîd, vol. 1 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 414 5 Ali Ash-Shabuny, Rawai’ul Bayan Fi Tafsiri Ayat al-Ahkam, Jilid 2: 486-489 6 al-Syafi’i, Ar-Risalah, terj. Ahmadie Toha (Jakarta, Pustakan Firdaus, 1992), 268 7 Ibid, 1052 [8] AR Fakhruddin, Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah (Malang: UMM Press, 2005), 41 [9] Ibid, 41 [10] Abdullah bin Biaz, Hukm Ziyârah al0-Qubûr wa Adhrahah, lihat: http://www.binbaz.org.sa/mat/4112 [11] Ibnu Shalih Utsaimin, http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_743.shtml