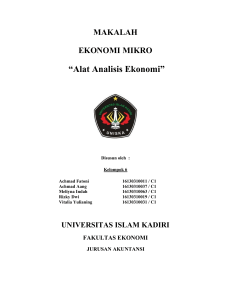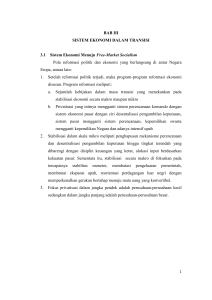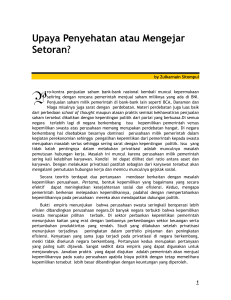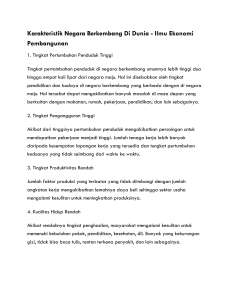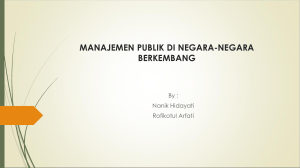F20291/Analisis Ekonomi Muhammad Chatib Basri
advertisement

Analisis Ekonomi Muhammad Chatib Basri Negeri yang Kekurangan Aliran Listrik, Jalan, dan Air Bersih 23-09-02 TANGGAL 12 September malam, gelap gulita yang menaungi Jabotabek dan Banten-akibat padamnya listrik-mungkin hanya pertanda awal tentang buruknya infrastruktur di negeri ini. Rumah tangga yang kalang kabut, kemacetan lalu lintas, dan terhentinya beberapa proses produksi hanyalah indikasi dini tentang dampak infrastruktur yang memprihatinkan. Konsumen pun mengeluh, kenapa listrik padam? Bukankah tarif listrik sudah mulai dinaikkan? Sebuah keluhan yang sah. Namun, soal ini juga harus dilihat dalam perspektif lebih jauh, yakni kendala infrastruktur. Beberapa hari sebelumnya, sebuah pesawat penerbangan dari Makassar ke Jakarta nyaris mengalami nasib yang naas karena oksigen tak berfungsi, ketika pesawat masuk ke ruang hampa. Untung pesawat masih berhasil kembali ke Makassar. ags Di tempat lain kita mendengar soal bahaya yang muncul di jalur utama pantai utara Jawa. Kerusakan jalan, yang diperparah dengan penurunan tanah, jelas membahayakan pengendara yang lewat di sana. Kita juga membaca tentang defisit pasokan air minum di Jawa Barat. Proses pasokan ke konsumen yang biasanya bisa berjalan selama 24 jam, kini, menurut Koran Tempo, hanya mampu berjalan selama 6-18 jam. Harian Kompas menunjukkan, bagaimana Indonesia merupakan negara dengan infrastruktur terburuk di Asia. Bukti-bukti anekdotal di atas sebenarnya bercerita tentang akibat dari krisis ekonomi yang mulai terasa. Krisis ekonomi memaksa adanya pemotongan biaya di mana-mana, termasuk biaya pemeliharaan. Pada September 1997 misalnya, Kepres 39 memutuskan untuk menunda pembangunan banyak proyek infrastruktur, termasuk swasta. Selain itu, banyak proyek swasta yang mengalami kesulitan keuangan atau gagal memperoleh sumber dana. Akibatnya, praktis tak ada pembangunan infrastruktur yang signifikan selama lima tahun krisis ekonomi. Mudah ditebak, infrastruktur yang lama mengalami depresiasi dan tak bisa berfungsi sepenuhnya. Apa implikasi dari semua ini? Jawabnya jelas, yakni pertama, rentannya keselamatan kita dan timbulnya kerugian yang diderita masyarakat. Kedua, meningkatnya beban yang ditanggung kelompok. Dan, ketiga, sulitnya mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan. Soal kerugian dan rentannya keselamatan masyarakat telah banyak dibahas termasuk di Harian Kompas kemarin. Saya akan lebih memfokuskan diri pada masalah dampaknya bagi penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, dan alternatif pembiayaannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan disini; Pertama, kualitas infrastruktur yang rendah akan memberatkan penduduk miskin dan perusahaan kecil. Dalam kasus air misalnya, penetapan harga yang murah tanpa didukung oleh infrastruktur seperti akses air bersih, justru hanya akan memberikan keuntungan kepada pedagang dan bukan kelompok miskin. Contohnya, air bersih yang dijual pemerintah dengan harga murah, dijual kembali oleh para pedagang kepada masyarakat -yang tak memiliki akses air- dengan harga yang berlipat (menurut studi World Bank tahun 1988, bisa 4-9 kali lebih mahal). Karena itu, bisa dibayangkan, kelangkaan pasokan air bersih di Jawa Barat akan menaikan harga dengan amat tajam, yang akhirnya sangat membebani kelompok miskin, di sisi lain memberikan keuntungan berlipat bagi pedagang. Dalam kasus listrik, Ikhsan dan Usman dari LPEM-FEUI menunjukkan, peningkatan pasokan listrik akan membantu kelompok miskin. Alasannya, harga yang mereka bayar untuk energi menjadi lebih murah. Biaya rata-rata untuk penyambungan rumah tangga yang sebesar Rp 1.147 - bila ada peningkatan pasokan listrik jelas berada di bawah biaya rata-rata yang sebesar Rp 7.428 per kWh untuk mereka yang tidak memiliki sambungan (sebagian mereka adalah kelompok miskin). Penyediaan akses listrik akan menurunkan biaya konsumsi energi, untuk mereka yang tidak memiliki sambungan, menjadi Rp 1.183 per kWh. Bagaimana dengan industri? Data Statistik Industri menyebutkan bahwa sebagian besar pengguna generator adalah perusahaan yang besar (dengan pekerja lebih dari 100 orang), sedang persentase penggunaan generator di perusahan kecil dan menengah (dengan pekerja kurang dari 100) relatif kecil. Artinya, perusahaan kecil dan menengah lebih tergantung kepada pasokan PLN, sedangkan mayoritas perusahaan memiliki pembangkit listriknya sendiri. Ini adalah sesuatu yang logis karena penyediaan generator atau membeli listrik dari perusahaan lain membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Jadi cuma yang besar yang mampu. Walau demikian setelah krisis, sejalan dengan meningkatnya harga solar, sebagian perusahaan besar pun ikut mengandalkan sumber listriknya dari PLN untuk menghemat biaya. Implikasinya, keterbatasan PLN akan memukul industri, terutama yang kecil dan menengah. Kasus yang sama juga terjadi pada air bersih, seperti yang ditunjukan oleh studi yang dilakukan oleh Lee, Anas, dan Oh dari World Bank (1996). Dari sini kita bisa melihat bahwa kelompok yang paling dirugikan oleh keterbatasan infrastruktur adalah kelompok miskin dan industri kecil dan menengah. *** KEDUA, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Studi LPEM (2002) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor nonmigas bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga soal-soal di sisi penawaran, seperti persoalan infrastruktur. Kendala infrastruktur akan membuat proses produksi menjadi tersendat, sehingga secara ekonomi sebenarnya terjadi kenaikan harga relatif barang-barang non-traded (seperti infrastruktur, yang tidak bisa di ekspor atau impor) dibandingkan harga barang traded (barang yang bisa diekspor atau impor). Implikasinya ekspor akan menurun karena hilangnya daya kompetisi, yang pada gilirannya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Studi awal yang saya lakukan menunjukkan elastisitas penyediaan listrik terhadap PDB berkisar 0,5-0,54 persen. Artinya, kenaikan 1 persen penyediaan listrik akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5-0,54 persen. Artinya untuk pertumbuhan ekonomi 6-7 persen - guna menyerap lapangan kerja dan mengurangi rasio utang/PDB-dibutuhkan input berupa penjualan listrik sebesar 11-14 persen per tahun. Bandingkan angka ini dengan tingkat penggunaan listrik sekarang dan ke depan yang diperkirakan sekitar 7-8 persen. Dengan kondisi ini, jelas terlihat bahwa infrastruktur yang ada tak mampu menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Itu sebabnya pemadaman reguler terjadi. Ironisnya ini tetap terjadi pada saat subsidi mulai dikurangi. Artinya, pengurangan subsidi pun belum mencukupi. Tanpa investasi baru atau repowering, system yang ada akan rawan sekali terhadap gangguan. Ini terjadi di banyak sektor infrastruktur kita. Dan situasi menjadi semakin buruk lagi karena berbagai inefisiensi dan juga masalah KKN, serta ketidaktransparanan dalam pelbagai proyek infrastruktur. Studi yang saya lakukan pada periode 1990-an menunjukkan, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur dan daya terpasang listrik sebesar 15 persen, pertumbuhan ekonomi dapat didorong 8 persen lebih tinggi (misalnya dari 6 menjadi 6,5 persen). Ini menunjukkan bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan dibutuhkan perbaikan infrastruktur. Dalam kaitan dengan akses kredit di daerah, studi awal LPEM menunjukkan bahwa infrastruktur seperti jalan beraspal dan sambungan telepon memiliki dampak positif bagi permintaan kredit di daerah. Peningkatan prosentase jalan beraspal sebesar 1 persen misalnya dapat meningkatkan permintaan kredit didaerah sebesar 0.1 persen. Artinya, perbaikan infrastuktur memperbaiki perekonomian yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan kredit. *** SETELAH kita tahu betapa krusialnya soal investasi untuk infrastruktur, pertanyaan berikutnya adalah sumber pembiayaannya. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, dari sisi internal, yakni peningkatan efisiensi dengan memberlakukan harga pasar dan memperbaiki good governance. Kedua, meningkatkan pembiayaan dari pemerintah. Akan tetapi ada kendala besar disini, yakni ruang anggaran praktis terbatas karena alokasi dana untuk pembayaran bunga dan cicilan utang. Solusinya mengundang swasta untuk masuk atau privatisasi. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan, privatisasi infrastruktur tanpa mengubah stuktur pasarnya tak selalu menjamin harga yang lebih murah bagi konsumen. Penyebabnya, sunk cost (biaya investasi yang tidak bisa diperoleh kembali) yang tinggi. Sunk cost yang tinggi akan mengakibatkan hambatan untuk masuk (barriers to entry) dalam sektor infrastruktur. Untuk menutupi sunk cost yang tinggi, secara rasional perusahaan menuntut monopoli profit. Artinya perusahaan akan masuk ke dalam sektor ini, jika mendapat keuntungan sebagai monopolis. Kalau ini yang terjadi, maka privatisasi hanya sekedar mengubah monopoli pemerintah menjadi monopoli swasta. Lalu buat apa privatisasi? Lalu apa solusinya? Untuk mengompensasi sunk cost yang tinggi ini pemerintah bisa melakukan tax deductible atau pengurangan pajak. Jika swasta mau membangun infrastuktur, berikan pengurangan pajak. dengan demikian ada insentif swasta untuk masuk ke dalam pasar tanpa perlu monopoli profit. Dalam struktur pasar seperti ini, maka harga yang dibayar konsumen adalah harga pasar persaingan -yang relatif murah. Saya tahu bahwa usulan pengurangan pajak akan berpengaruh kepada penerimaan anggaran. Namun, bukankah dengan masuknya swasta, biaya pembangunan infrastruktur dapat diperkecil? Dengan demikian efek anggarannya sebenarnya tak berbeda jauh. Di luar ide ini, satu hal penting yang harus diingat adalah insentif swasta untuk masuk sebenarnya tak hanya tergantung soal sunk cost, namun juga kepastian peraturan dan hukum. Bila ini tak dilakukan, insentif pajak tak akan banyak menolong dan infrastuktur tetap tak bisa diperbaiki. Implikasinya masa depan yang gelap dan kering -dalam arti yang sesungguhnya, karena padamnya listrik dan kurangnya air bersih-bukan hal yang musykil. Kita semua jelas tak menginginkan ini.*