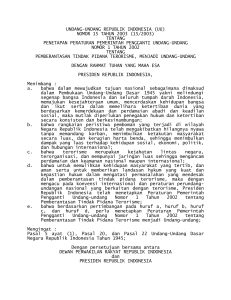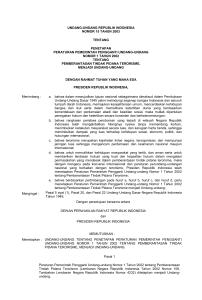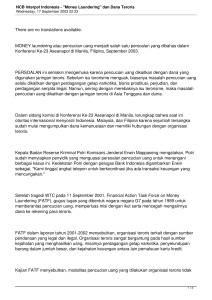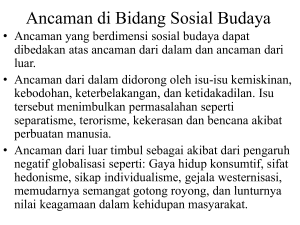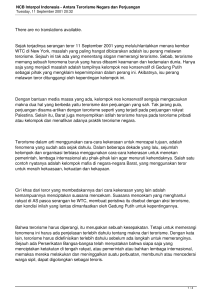Terorisme vs Internal Security Act
advertisement
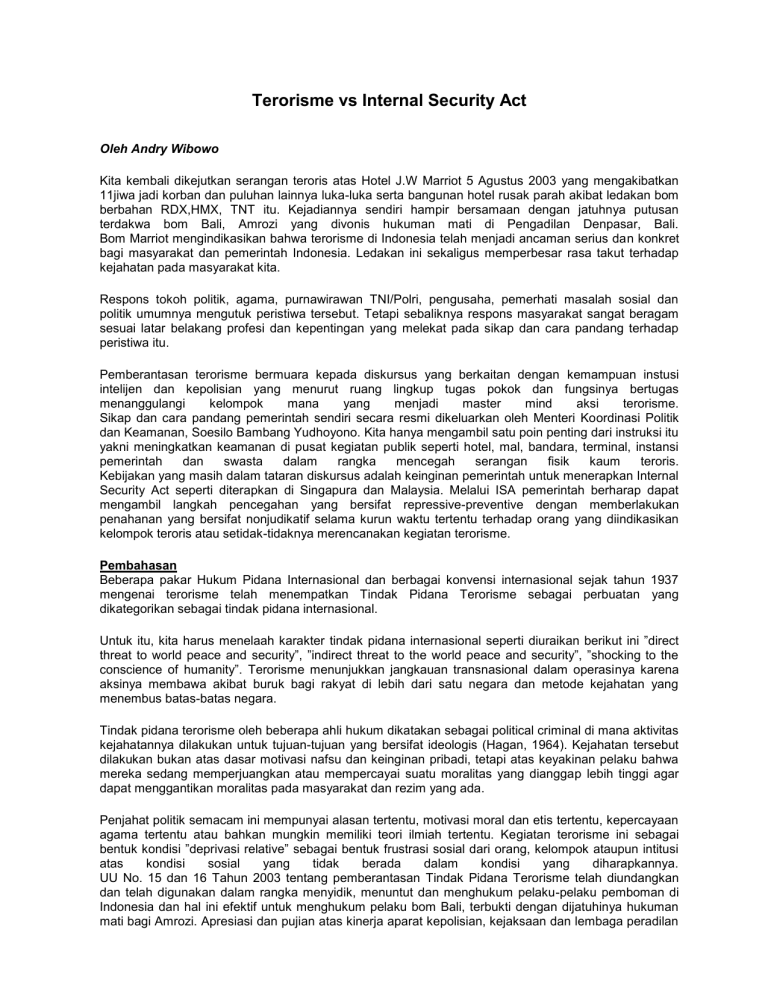
Terorisme vs Internal Security Act Oleh Andry Wibowo Kita kembali dikejutkan serangan teroris atas Hotel J.W Marriot 5 Agustus 2003 yang mengakibatkan 11jiwa jadi korban dan puluhan lainnya luka-luka serta bangunan hotel rusak parah akibat ledakan bom berbahan RDX,HMX, TNT itu. Kejadiannya sendiri hampir bersamaan dengan jatuhnya putusan terdakwa bom Bali, Amrozi yang divonis hukuman mati di Pengadilan Denpasar, Bali. Bom Marriot mengindikasikan bahwa terorisme di Indonesia telah menjadi ancaman serius dan konkret bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Ledakan ini sekaligus memperbesar rasa takut terhadap kejahatan pada masyarakat kita. Respons tokoh politik, agama, purnawirawan TNI/Polri, pengusaha, pemerhati masalah sosial dan politik umumnya mengutuk peristiwa tersebut. Tetapi sebaliknya respons masyarakat sangat beragam sesuai latar belakang profesi dan kepentingan yang melekat pada sikap dan cara pandang terhadap peristiwa itu. Pemberantasan terorisme bermuara kepada diskursus yang berkaitan dengan kemampuan instusi intelijen dan kepolisian yang menurut ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya bertugas menanggulangi kelompok mana yang menjadi master mind aksi terorisme. Sikap dan cara pandang pemerintah sendiri secara resmi dikeluarkan oleh Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan, Soesilo Bambang Yudhoyono. Kita hanya mengambil satu poin penting dari instruksi itu yakni meningkatkan keamanan di pusat kegiatan publik seperti hotel, mal, bandara, terminal, instansi pemerintah dan swasta dalam rangka mencegah serangan fisik kaum teroris. Kebijakan yang masih dalam tataran diskursus adalah keinginan pemerintah untuk menerapkan Internal Security Act seperti diterapkan di Singapura dan Malaysia. Melalui ISA pemerintah berharap dapat mengambil langkah pencegahan yang bersifat repressive-preventive dengan memberlakukan penahanan yang bersifat nonjudikatif selama kurun waktu tertentu terhadap orang yang diindikasikan kelompok teroris atau setidak-tidaknya merencanakan kegiatan terorisme. Pembahasan Beberapa pakar Hukum Pidana Internasional dan berbagai konvensi internasional sejak tahun 1937 mengenai terorisme telah menempatkan Tindak Pidana Terorisme sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana internasional. Untuk itu, kita harus menelaah karakter tindak pidana internasional seperti diuraikan berikut ini ”direct threat to world peace and security”, ”indirect threat to the world peace and security”, ”shocking to the conscience of humanity”. Terorisme menunjukkan jangkauan transnasional dalam operasinya karena aksinya membawa akibat buruk bagi rakyat di lebih dari satu negara dan metode kejahatan yang menembus batas-batas negara. Tindak pidana terorisme oleh beberapa ahli hukum dikatakan sebagai political criminal di mana aktivitas kejahatannya dilakukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat ideologis (Hagan, 1964). Kejahatan tersebut dilakukan bukan atas dasar motivasi nafsu dan keinginan pribadi, tetapi atas keyakinan pelaku bahwa mereka sedang memperjuangkan atau mempercayai suatu moralitas yang dianggap lebih tinggi agar dapat menggantikan moralitas pada masyarakat dan rezim yang ada. Penjahat politik semacam ini mempunyai alasan tertentu, motivasi moral dan etis tertentu, kepercayaan agama tertentu atau bahkan mungkin memiliki teori ilmiah tertentu. Kegiatan terorisme ini sebagai bentuk kondisi ”deprivasi relative” sebagai bentuk frustrasi sosial dari orang, kelompok ataupun intitusi atas kondisi sosial yang tidak berada dalam kondisi yang diharapkannya. UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diundangkan dan telah digunakan dalam rangka menyidik, menuntut dan menghukum pelaku-pelaku pemboman di Indonesia dan hal ini efektif untuk menghukum pelaku bom Bali, terbukti dengan dijatuhinya hukuman mati bagi Amrozi. Apresiasi dan pujian atas kinerja aparat kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan dalam menangani kasus bom Bali dinyatakan oleh berbagai kalangan di dalam dan luar negeri. Di samping aspek praktis dalam pemeriksaan kasus bom Bali tersebut, sebenarnya UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 juga sudah lebih keras dibandingkan dengan KUHP dan undang-undang sebelumnya yang dibuat dalam rangka menanggulangi tindak pidana yang dikategorikan sebagai ordinary crime. Sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat extra ordinary crime. UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 juga dibuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang tidak lagi bersifat umum tetapi sudah bersifat spesifik antara lain penerapan asas Retroaktif serta Non Lapse of Time kecuali terdakwa meninggal dunia dan hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang bersifat universal. Tetapi peristiwa bom Marriot telah menyentakkan kita semua bahwa ancaman terorisme masih menghantui kehidupan kita dan pemerintah merasa memerlukan suatu instrumen hukum yang lebih keras untuk menghadapi kelompok-kelompok teroris. Dengan harapan pencegahan terorisme dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Faktor lainnya adalah adanya pandangan bahwa dalam memerangi terorisme peran inteleijenlah seharusnya lebih dikedepankan karena dengan alasan struktur dan aktivitas kelompok terorisme identik dengan struktur dan aktivitas intelijen. Pendapat ini sangat bersifat sektoral dan masih terbuka diperdebatkan khususnya dalam kerangka berpikir regulasi dan pola penanggulangan terorisme secara global karena Indonesia terikat pada penandatanganan konvensi-konvesi internasional yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Apalagi jika kita melihat akar permasalahan timbulnya terorisme, maka penanggulangan terorisme tidaklah arif jika hanya dilihat dari aspek tersebut dan terkesan menyederhanakan permasalahan. Wacana pembentukan ISA sebagai suatu Perspective Regulation untuk memberantas terorisme haruslah tetap dalam kerangka sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan situasi kultural masyarakat Indonesia. Sehingga ISA atau regulasi apa pun yang dapat berfungsi sebagai Represive-Preventive Measures tetap dilandaskan kepada nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan Rules of Law dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan demikian visi pemerintah untuk menanggulangi terorisme sebagai implementasi kewajiban negara melindungi warganya tidak terjebak kepada suatu tindakan yang mengarah kepada abuse of power yang dapat menimbulkan terorisme bentuk lain yaitu State Terrorism, dan akan menempatkan Pemerintah Indonesia sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia di mata masyarakat Internasional. Kasus Timor Timur cukuplah bagi sejarah bangsa ini yang telah menempatkan prajuritprajurit terbaiknya sebagai pesakitan meskipun kita semua tahu bahwa mereka yang duduk sebagai pesakitan dalam peradilan HAM Timor Timur adalah patriot dari rakyat dan negara ini. Jika saya dapat berpendapat dalam kesempatan ini, UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat tetap dijadikan Prime Regulation dalam rangka menanggulangi Tindak Pidana Terorisme. Prinsip Proprio motu dalam article 15 Rome Statute of the International Criminal Court dapat dicoba untuk diadopsi dalam UU No. 15 dan 16 Tahun 2003. Di mana informasi intelijen dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi penyidik untuk berinisiatif melakukan penyidikan terhadap kelompok yang dicurigai yang kemudian diikuti dengan pengujian informasi tersebut di lembaga peradilan agar informasi tersebut dapat dijadikan bukti materiil dalam rangka proses penuntutan selanjutnya. Selain dari pada itu sebagaimana pasal tentang makar (aanslag) Pasal 104-108 KUHP maka percobaan (Pasal 53 KUHP) melakukan terorisme dapat ditangkap dan dituntut sesuai dengan UU No. 15 dan 16 2003. Dalam hal ini pula telah berlaku prinsip Represive-Preventive sebagaimana yang diinginkan oleh berbagai pihak saat ini. Kesimpulan Kita sebagai bangsa yang beradab sepakat bahwa tindak pidana terorisme adalah kejahatan yang mengancam peradaban umat manusia. Pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut harus dilakukan secara serius dan memberdayakan seluruh rakyat dengan tetap mengacu kepada norma dan etika yang berlaku secara universal. Untuk itu, saya mengajukan usul yang sederhana saja yakni agar aparat hukum dan keamanan di Indonesia harus melihat dari sisi internasional aksi terorisme. Pemerintah harus memanfaatkan hukum pidana positif dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi. Penulis Kepala Kepolisian Sektor Koja, Jakarta Utara