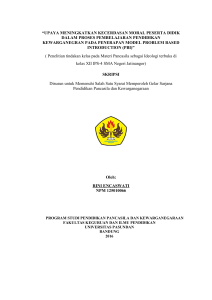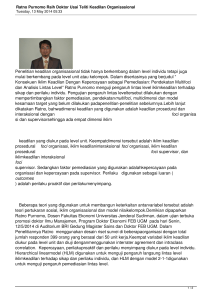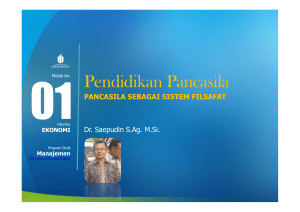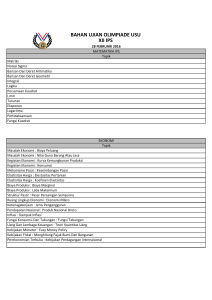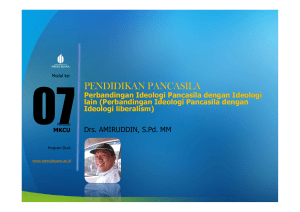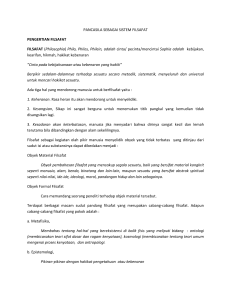membaca ulang pemaknaan keadilan sosial - e
advertisement

MEMBACA ULANG PEMAKNAAN KEADILAN SOSIAL DALAM GAGASAN REVOLUSI HUKUM SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO Shidarta email: [email protected] Abstract Soediman Kartohadiprodjo was one of few Indonesian legal scholars taking interest in Pancasila, the state ideology promulgated by Soekarno. Soediman believe that social justice, the core concept of Pancasila corresponds with the “kekeluargaan” principle as found in the constitution. However, he used the the term welfare or happines rather than social justice since the latter, according to him, tends to adopt liberalist and individualist principles, which according to him contradicts with Pancasila. He also endorsed the idea of “legal revolution”as a mean to increase the Indonesian populace’ awareness about recent legal development post independence. This article discusses and critizes Soediman’s idea on social justice and legal revolution. Keywords: Pancasila, social justice, welfare state, law revolution. Abstrak Soediman Kartohadiprodjo adalah salah satu dari beberapa sarjana hukum Indonesia yang memiliki ketertarikan untuk menjelajahi Pancasila sebagai ideologi yang pertama kali dikembangkan Soekarno. Soedirman percaya bahwa keadilan sosial adalah konsep inti yang sesuai dengan "kekeluargaan" prinsip sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi. Namun ia lebih suka menggunakan istilah kesejahteraan atau kebahagiaan daripada keadilan sosial karena yang terakhir menurut dia cenderung mengadopsi individualisme liberal dan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ia juga mengungkapkan idenya untuk menyampaikan "revolusi hukum" dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum Indonesia melalui sistem hukum yang baru dikembangkan setelah kemerdekaan. Artikel ini membahas gagasan keadilan sosial Soediman dan gagasannya tentang revolusi hukum serta memberikan beberapa kritik atas pikirannya. Kata kunci: Pancasila, keadilan sosial, negara kesejahteraan, revolusi hukum. Latar Belakang Soediman Kartohadiprodjo (1908-1970) adalah ilmuwan hukum yang cukup berpengaruh dalam era perjuangan kemerdekaan sampai memasuki periode pemerintahan Orde Lama. Tema besar yang kerap muncul dalam tulisantulisannya adalah tentang Pancasila, yang diyakininya memiliki otentisitas untuk disebut sebagai karya agung bangsa Indonesia. Perang dingin yang terjadi dalam kancah politik global, yang pada tingkatan tertentu juga menyentuh ‘perang 20 ideologi’ antar-blok dunia, membuat Soediman makin yakin pada posisi Pancasila sebagai tawaran alternatif bagi bangsa Indonesia untuk tampil percaya diri dengan pandangan hidupnya sendiri. Tulisan ini berinisiatif mengangkat satu sisi pemikiran dari Soediman Kartohadiprodjo.1 Pilihan jatuh pada konsep ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ yang telah diformulasikan sebagai sila kelima Pancasila. Konsep ini termasuk penting karena merupakan aspek aksiologis bernegara yang paling gamblang dirumuskan melalui kata kerja “mewujudkan keadilan sosial” di dalam Pembukaan UUD 1945. Penggunaan kata kerja aktif ini memperlihatkan kesungguhan bangsa ini untuk secepatnya mengatasi problema ketidakadilan yang menjadi kondisi faktual bangsa ini selama hidup di alam penjajahan. Perubahan kondisi kehidupan bangsa ini akan cepat diatasi apabila tata hukum warisan kolonial juga ikut berubah. Untuk itu, Soediman pun sepakat dengan gagasan adanya revolusi hukum. Sebagai ahli hukum yang memiliki ketertarikan pada filsafat hukum, Soediman sadar bahwa keadilan adalah tujuan ideal dalam berhukum bagi semua bangsa. Tatkala Soediman Kartohadiprodjo memahami Pancasila dengan segala orisinalitas dan otentisitas keindonesiaan itu, berarti akan ada kemungkinan versi keadilan yang khas dalam kerangka pikir bangsa Indonesia itu. Juga akan ada potensi keadilan versi bangsa Indonesia itu bakal terwujud melalui mekanisme percepatan yang disebutnya revolusi hukum. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diangkat dalam tulisan ini, yakni apakah sebenarnya makna keadilan sosial bagi bangsa Indonesia menurut pandangan Soediman Kartohadiprodjo dan bagaimana kaitannya dengan gagasan revolusi hukum yang diajukannya? Jawaban terhadap pertanyaan ini memiliki makna penting karena membuka katup diskursus tentang keadilan sosial yang relatif terbungkamkan 1 Catatan: beberapa sekuens pemikiran ini sempat dipresentasikan dalam seminar; lihat Shidarta, “Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial dan Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo”, makalah Seminar dalam rangka lomba debat hukum Piala Soediman Kartohadiprodjo, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 6 Maret 2015. 21 pasca-kejatuhan Pemerintahan Orde Baru. Sejak saat itu, topik-topik dan wacana tentang Pancasila seakan menjadi usang dan tidak lagi menarik. Akibatnya, banyak pihak berusaha memberi tafsir baru atas topik-topik ini, padahal bukan tidak mungkin pembahasan tentang topik-topik ini sudah pernah ditampilkan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, termasuk oleh tokoh sekelas Soediman Kartohadiprodjo. Mengingat ada jarak waktu cukup jauh antara tulisan ini dengan hadirnya karya-karya Soediman yang menjadi objek kajian tulisan ini, maka sejak awal disadari akan ada keterbatasan pandangan penulis untuk mengkaji pemikiran Soediman Kartohadiprodjo tersebut secara komprehensif. Oleh sebab itu, metode penelitian terhadap karya-karya Soediman hanya dibatasi pada dua buku penting. Pertama, buku beliau berjudul Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Jilid I: Hukum Perdata, Jakarta: PT Pembangunan & Ghalia Indonesia (edisi tahun 1982). Kedua, buku bunga rampai (kompilasi tulisan) yang diedit serta diterbitkan kembali, berjudul Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Jakarta: Gatra Pustaka (edisi tahun 2010). Penelitian sepenuhnya dilakukan berdasarkan kajian pustaka, dan dalam beberapa kesempatan diperkaya dengan diskusi dengan narasumber yang pernah menjadi asisten Soediman Kartohadiprodjo dalam waktu cukup lama di Universitas Katolik Parahyangan, yaitu Bernard Arief Sidharta. Tata Hukum Berkeadilan Sosial Di dalam buku Soediman Kartohadiprodjo, “Pengantar Tata Hukum di Indonesia” (Jilid 1: Hukum Perdata”) terbitan bersama antara PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia (dipublikasikan pertama kali tahun 1956 dan sampai dengan tahun 1982 sudah mengalami cetak ulang kesepuluh), terdapat ulasan yang cukup menarik tentang pemikiran Soediman berkenaan dengan Pancasila. Walaupun buku jilid pertama ini didesain sebagai pengantar tata hukum di Indonesia untuk bidang hukum perdata, pada sekitar 50 halaman pertama terdapat ulasan pengarangnya tentang hukum dan manusia, manusia sebagai zoon politikon, 22 manusia dalam tafsiran bhineka tunggal ika, manusia Indonesia dan Pancasila, Pancasila dan bangsa Indonesia, serta zoon politikon dan Indonesia. Paparan tentang Pancasila yang menyita cukup banyak halaman awal dari bukunya tersebut ternyata ditambah lagi dengan satu bab tambahan yang dijadikan penutup buku, berjudul “Menuju ke Tata Hukum Nasional”. Di sini lagilagi rekomendasi Soediman Kartohadiprodjo terkait Pancasila, kembali dikedepankan. Ia menganjurkan agar tata hukum Indonesia harus dijalankan dan ditafsirkan dengan jiwa Pancasila. Dalam jiwa Pancasila ini fungsi hukum adalah pengayoman. Soediman Kartohadiprodjo menulis pandangannya dengan katakata sebagai berikut:2 Menurut Panca Sila, yang berintikan pada kekeluargaan, yang maknanya ialah, mengakui adanya perbedaan kepribadian individu, tetapi tidak kepribadian yang bebas, yang tidak menghiraukan adanya yang lain, melainkan yang terikat dalam satu kesatuan --“kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan” ---maka diakuilah adanya perbedaan antara kelompok-kelompok pergaulan hidup manusia yang satu dan lainnya. Kelompok-kelompok ini dilihatnya tidak terpisah satu sama lain secara tajam seperti kita jumpai dalam penggolongan pada masa penjajahan menurut pasal 163 IS, melainkan pengakuan kelompok seperti kita mengakui adanya kelompok pergaulan hidup Jawa, Sunda, dan sebagainya. Selaras dengan itu, maka Bung Karno juga menganjurkan, ‘janganlah kita mengadakan lagi perbedaan lagi anara ‘orang Indonesia asli’ dan ‘orang Indonesia tidak asli’, melainkan seperti halnya kita mengakui dan mengenal suku Batak, Minangkabau dan sebagainya kita sebut juga yang tadinya kita namakan orang Indonesia tidak asli sebagai suku Tiong Hoa, suku Arab, suku India dan sebagainya… Kutipan di atas memperlihatkan keinginan Soediman untuk menghadirkan suatu tata hukum Indonesia yang memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak lagi mempersoalkan asal usul dan latar belakang golongannya. Semua komponen bangsa Indonesia diikat dengan semangat 2 Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jilid I: Hukum Perdata, PT Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 246. 23 kekeluargaan dan tata hukum Indonesia wajib untuk mengayomi seluruh bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali. Keadilan adalah Kesejahteraan dan Kebahagiaan Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “sosial” digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan [hidup dengan] rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaikbaiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprodjo sebagai “bahagia”.3 Jadi, menurut Soediman Kartohadiprodjo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila keilma Pancasila adalah sama dengan “keadilan sosial” atau “kesejahteraan sosial”.4 Istilah “kesejahteraan” jelas bukan orisinal dari Soediman. Ia mengambilnya dari pidato Soekarno di hadapan sidang Badan Penyelelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 1 Juni 1945. Soekarno merangkaikan prinsip kesejahteraan ini dengan prinsip demokrasi, sehingga lahirlah terminologi sosio-demokrasi. Menurut Soekarno di dalam prinsip kesejahteraan tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Istilah “sosio-demokrasi” dipinjamnya dari Fritz Adler, yang mendefinisikan sosio-demokrasi sebagai “politiek ekonomische democratie” (demokrasi politik-ekonomi). Pendeknya, di satu sisi ada demokrasi politik, dan di sisi lain ada demokrasi ekonomi.5 Pemikiran Soekarno tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini adalah hasil endapan lama Soekarno sebagaimana terlihat dalam paparannya tentang marhaenisme. Bagi Soekarno, marhaneisme adalah asas dan cara 3 4 5 Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 161. Id, hlm. 171. Baca Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 491-492. 24 perjuangan sosialisme ala Indonesia berlandasarkan prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menghendaki hilangnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Intinya, Indonesia tidak saja harus mencapai kemerdekaan politik, tetapi juga disebutkannya kemerdekaan dengan ekonomi. prinsip Dalam politieke terminologi rechtvaardigheid lain Soekarno, dan sociale rechtvaardigheid. 6 Selain Soekarno, adalah Mohammad Hatta yang memberi warna sangat kuat pada penjabaran prinsip sosio-demokrasi ala Indonesia ini. Pada masa sidang kedua BPUPK tanggal 11 Juli 1945, badan ini membentuk tiga panitia, yaitu panitia perancang hukum dasar, panitia perancang keuangan dan ekonomi, dan panitia perancang pembelaan tanah air, yang masing-masing dipimpin oleh Soekarno, Hatta, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Soekarno lalu membentuk lagi panitia kecil yang bertugas merumuskan undang-undang dasar di bawah pimpinan Soepomo. Mereka semua bekerja cepat. Dalam rapat besar BPUPK tanggal 13 Juli 1945 inilah Hatta memberi banyak sanggahan terhadap hasil rancangan Soepomo, yang akhirnya menjadi bab-bab tentang warga negara dan kesejahteraan sosial. Hatta memberi masukan terkait dengan keadilan dan kesejahteraan sosial secara lengkap sebagai berikut: (1) Orang Indonesia hidup dalam tolongmenolong; (2) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang; (3) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif; (4) Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah; (5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga; (6) Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain; dan (7) Fakir dan miskin dipelihara oleh pemerintah.7 Derivasi atas konsep kesejahteraan sosial sebagaimana dijabarkan oleh ekonom semacam 6 7 Id, pada hlm. 521-522, 532. Id, pada hlm. 533-536. 25 Hatta, tidak pernah disinggung-singgung oleh Soediman di dalam tulisantulisannya. Kesejahteraan sosial disebut-sebut oleh Soediman sebagai tujuan hidup manusia dalam alam semesta. Suatu konsep yang lebih bernada filosofis daripada ekonomis! Untuk itu, Soediman Kartohadiprodjo menulis sebagai berikut:8 Menurut “penggalian” Bung Karno, seperti yang dinyatakan untuk pertama kalinya, maka menurut Bangsa Indonesia itu ialah “Kesejahteraan Sosial”, dan dengan demikian Bung Karno menamakan Sila yang kelima itu Sila Peri-Kesejahteraaan Sosial; suatu nama yang kiranya lebih tepat dari pada nama yang diberikan kemudian dan yang sekarang lebih didengar dan dikenal orang: Peri-Keadilan Sosial. Tetapi nampaknya: Apakah tidak lebih tepat kalau Sila ini kita namakan Sila Peri-Kebahagiaan? “Kesejahteraan Sosial” dianggap lebih tepat dari pada “Keadilan Sosial”---seperti dikemukakan tadi— karena lebih menunjukkan manusia dalam keadaan passief, padahal yang dilihatnya ialah “apa yang menjadi maksud dan tujuan manusia”, jadi manusia dalam keadaan aktief. Sifat “aktief” ini cukup ditunjukkan dengan istilah “kesejahteraan sosial”. Tetapi sebaliknya “kesejahteraan” itu lebih membuka ke arah fikiran materiil padahal kehidupan manusia itu membutuhkan tidak saja bahan materiil tetapi pula spirituil. Manusia selalu berusaha untuk mengadakan kelarasan dalam pemenuhannya kebutuhan-kebutuannya materiil dan spirituil. Kalau terdapat kelarasan tadi, atau kalau kelarasan itu dapat sangat didekati, maka kita namakan orang itu dalam keadaan bahagia. Dengan alasan inilah, maka ditanyakan apakah tidak cukup alasan untuk menamakan Sila kelima ini Sila Peri-Kebahagiaan. Preferensi Soediman untuk menggunakan kata “kesejahteraan” daripada “keadilan” ini dapat dibenarkan dengan penjelasan filosofis bahwa apabila suatu ketidakadilan ternyata dialami semua orang, maka secara konseptual sudah terjadi pemerataan ketidakadilan. Bukankah pemerataan ini suatu keadilan juga? Lain halnya jika kata “kesejahteraan” yang dipakai karena ketidaksejahteraan bagi semua orang tidak lalu identik dengan kesejahteraan bagi semuanya. Dengan memakai kata “kesejahteraan” akan mengundang kita untuk membawa pikiran Soediman kepada konsep negara (hukum) kesejahteraan. 8 Soediman, 1982, Id, pada hlm. 30-31. 26 Artinya, hukum digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial. Jika meminjam istilah Soekarno, “hukum adalah alat revolusi”. Kebetulan, Soediman adalah sedikit dari pemikir hukum Indonesia yang sangat sering mengadopsi kata “revolusi” di dalam tulisan-tulisannya. Dan menarik, bahwa Soediman Kartohadiprodjo memahami revolusi di sini secara lebih sempit sebagai revolusi hukum.9 Suatu pemahaman yang agak bertolak belakang dengan sindiran Bung Karno sendiri---yang notabene lebih meyakini revolusi secara lebih luas sebagai “revolusi total”---yang mengatakan, “Met juristen kunt je geen revolutie maken” (dengan kaum yuris kamu tak bakalan bisa membuat revolusi). Apa yang dimaksudkannya dengan revolusi hukum? Soediman Kartohadiprodjo mengungkapkan hal ini dalam konteks kesadaran hukum bangsa Indonesia yang harus berubah, tidak lagi mengikuti alam pikiran khas penjajah kolonial Barat. Ia menyampaikan pandangannya sebagai berikut:10 … maka Revolusi yang kita lakukan ini adalah dalam maknanya revolusi dalam hukum, karena apa yang dianggap biasa, adil dan hukum itu kita tidak menerimanya, kita tolak sebagai hukum. Jadi, revolusi kita adalah revolusi hukum. … bahwa Revolusi kita itu dijiwai oleh Pancasila. Kalau begitu, Pancasila ini mengandung jiwa menentang penjajahan. Bahwa jiwa Pancasila itu bertentangan dengan jiwa penjajahan. Disebabkan itu maka jiwa Pancasila itu bertentangan, bahkan berlawanan dengan hukum yang menerima sebagai adil penjajahan itu. Di manakah letak perbedaan yang menyebabkan pertentangan antara jiwa Pancasila dan pikiran yang menjiwai hukum yang menerima dan membuka diadakan penjajahan itu? . . . Berdasarkan itu maka dengan Revolusi kita ini, yang merupakan Revolusi juga dalam hukum, kita prinsipiil harus mengubah, artinya tidak mengikuti hukum yang membuka kemungkinan dapat diadakannya penjajahan; dan dalam pada itu, dengan diterimanya Pancasila sebagai filsafat Negara kita itu, kita harus mengikuti cara berpikir sesuai dengan filsafat Pancasila tadi--ialah menurut kepribadian nasional Bangsa Indonesia---yang berarti mengubah cara berpikir kita yang diajarkan kepada kita menurut “demokrasi liberal”, tetapi pula tidak mengikuti caranya berpikir menurut aliran Komunis. 9 10 Soediman, 2010, Id, pada hlm. 236. Id, hlm. 238, 243. 27 Negara Kesejahteraan Bagi peminat kajian tentang gagasan negara-negara hukum (rule of law; rechtsstaat), konsep “kesejahteraan sosial” adalah sebuah model alternatif negara hukum yang lazim disebut negara kesejahteraan (welfare state). Istilah negara kesejahteraan (welfare state) juga dipakai berkali-kali oleh Hatta.11 Sayangnya, Soediman tidak cukup elaboratif untuk menjelaskan konsep “kesejahteraan sosial” versinya, tetapi yang dikemukakannya dan hubungannya dengan revolusi hukum untuk mewujudkan tujuan bernegara bagi bangsa Indonesia tersebut. Kendati demikian, Soediman tidak ketinggalan menyinggung beberapa kata kunci penting, yang ternyata juga di kemudian hari muncul dalam tulisan-tulisan para ahli hukum kontemporer, seperti oleh Brian Tamanaha dalam bukunya “On the Rule of Law: History, Politics, Theory”.12 Brian Tamanaha pertama-tama membedakan antara model negara hukum formal dan negara hukum substansial. Tamanaha menyebutkan tiga hal yang sering tidak disinggung sebagai aspek pokok negara hukum oleh model negara hukum formal, yaitu demokrasi (democracy), isi hukum (content of the law), dan hak asasi manusia (human rights). Demokrasi merupakan mekanisme untuk memilih pemimpin politik sehingga bisa terbentuk legitimasi kekuasaan untuk membentuk hukum yang mengikat bagi rakyat. Isi hukum menuntut penghormatan atas berbagai sistem budaya, sosial, dan politik, sehingga dijamin tidak akan ada aturan yang opresif dan tak bermoral dapat hadir di tengah masyarakat. Sementara itu, walaupun dua hal di atas sudah mencakupi, hak asasi manusia tetap perlu ditambahkan karena perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hal mutlak.13 Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II, Idayu Press, Jakarta, 1983, pada hlm. 169. Brian Tamanaha, On the Rule of Law : History, Politics, Theory, Cambridge University Press, New York, 2004. 13 Palombella, G. & Walker N. Eds., Relocating the Rule of Law, Oxford & Portland, Oregon, 2009, pada hlm. 13–14. 11 12 28 Tamanaha kemudian memaparkan enam alternatif formulasi negara hukum.14 Secara skematis, ia terlebih dulu membagi formulasi tersebut menjadi dua kategori, yang disebutnya versi formal dan versi substantif. Apa yang disebutnya dengan kategori formal berasal dari teori-teori formal tentang negara hukum yang lebih menekankan pada aspek legalitas, sementara kategori subsantif negara hukum lebih berfokus pada isi, yaitu nilai-nilai keadilan dan moral. Tentu saja, Tamanaha mengingatkan bahwa dalam versi moral ini juga terdapat implikasi substantif, demikian juga sebaliknya. Setiap versi ini memuat tiga bentuk berbeda, bergerak dari perkembangan dari yang lebih tipis (thinner) ke lebih tebal (thicker). Alhasil ditemukan enam model negara hukum (modifikasi skema oleh Shidarta), dengan ciri-ciri sebagai berikut: Versi formal Versi substantif 14 Lebih Tipis 1. RULE-BY-LAW Transisi 2. LEGALITAS FORMAL Negara dikonsepkan bertindak berlandaskan hukum, tetapi cenderung menjadi alat pemerintah (“rule by the government”). Hanya ada sedikit pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah. Makna seperti ini sama seperti “Rechsstaat” versi Jerman. Dianut oleh negara dengan sistem hukum yang masih belum demokratis. Norma hukum sudah dibuat jelas, tegas, konsisten, non-retroaktif. Masih terbuka kemungkinan negara melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia, namun tetap dibenarkan sepanjang sah menurut hukum tertulis dari negara. 5. HAK ATAS KEHORMATAN &/KEADILAN Negara melindungi hakhak fundamental masyarakat terkait persamaan kedudukan di hadapan hukum (keadilan). Di sini ada larangan atas perbudakan, rasisme, dll. 4. HAK-HAK INDIVIDUAL Negara melindungi hak-hak individual, seperti hak privasi, hak milik, hak kebebasan berkontrak. Brian Tamanaha, Id, pada hlm. 91-113. 29 Lebih Tebal 3. DEMOKRASI+ LEGALITAS Dianut oleh negara dengan sistem hukum yang sudah demokratis. Negara mulai mereduksi perannya untuk membuat hukum. Demokrasi tanpa legalitas, negara akan kehilangan legitimasi. Sebaliknya, legalitas tanpa demokrasi, negara akan berbalik menjadi opresif (circumvented). 6. KESEJAHTERAAN SOSIAL Negara memberi perhatian pada pemenuhan kesejahteraan sosial sebagai tujuan bernegara dengan tetap mengusung hak individu dan demokrasi. Berangkat dari skema rumusan negara hukum di atas, tampak bahwa tipe pertama dan kedua masih belum memuat tiga aspek kunci tersebut. Baru pada rumusan ketiga, demokrasi dimunculkan, tetapi masih belum bisa sepenuhnya terlepas dari negara hukum formal. Barulah pada formulasi keempat, kelima, dan keenam tampak tiga aspek tadi mulai dimasukkan secara makin tebal. Apabila konsep “kesejahteraan sosial” (welfare state) yang disebutkan oleh Tamanaha ini disandingkan dengan pemikiran Soediman, sebenarnya terlihat keduanya memiliki titik singgung. Soediman juga meyakini pentingnya demokrasi, isi hukum, dan hak asasi manusia. Ada baiknya dapat dicermati apa yang telah disampaikan oleh Soediman terkait tiga aspek tersebut. Pertama, tentang demokrasi. Soediman Kartohadiprodjo pernah membuat satu tulisan agak panjang pada tahun awal tahun 1964 terkait pembelaannya terhadap demokrasi terpimpin ala Soekarno.15 “… apa yang diajukan Bung Karno itu adalah tepat, juga dari sudut yuridis,” tegas Soediman Kartohadiprodjo.16 Dalam tulisannya itu ia mencurigai konsep demokrasi yang berlaku saat itu terlalu dekat dengan individualisme. Soediman khawatir pola demokrasi Barat itu akan dipakai sebagai patokan yang tidak selalu cocok dengan sistem di Indonesia, yang kemudian disimpulkan bahwa sistem kita itulah yang keliru dan terlalu tradisional. Soediman malahan ingin agar demokrasi ala Indonesia yang disebutnya “Pemerintahan Pancasila” itu sebagai tawaran baru sebagai dasar pembentukan dunia baru (to build the world anew). Cara pandang Soediman ini tentu sulit dipahami oleh generasi sekarang yang menilai, baik Orde Lama maupun Orde Baru, sama-sama tidak mampu memberi contoh kehidupan demokrasi yang bisa membawa pada “kesejahteraan sosial”. Sejarah mencatat bahwa Soekarno dan Soeharto turun dari tampuk kekuasaan dengan kondisi negara yang karut-marut. Secara konseptual penolakan Soediman terhadap individualisme Barat tidak membuatnya menolak perlindungan terhadap individu. Sebagai ganti dari 15 16 Soediman, 2010, Id, hlm. 295-329. Id, pada hlm. 328. 30 demokrasi dengan paham individualisme itu digantinya dengan musyawarahmufakat. Soediman Kartohadiprodjo menyatakan musyawarah-mufakat sebagai cara memperoleh kebahagiaan.17 Di sini, katanya, tidak tertutup kemungkinan ada perbedaan antara manusia yang hidup berkelompok itu dalam mencari jalan menuju ke hidup bahagia tadi. Soediman Kartohadiprodjo (mengatakan, musyawarah, apalagi mufakat, mengandung arti “voorondersteld” (mengandaikan) adanya perbedaan. 18 Justru karena adanya perbedaan itu, maka diperlukan musyawarah-mufakat. Perbedaan ini bukan perbedaan kedudukan, tetapi perbedaan pendapat. Soediman menyatakan, bahwa mengakui adanya perbedaan, berarti mengakui kepribadian masing-masing manusia yang berkelompok itu.19 Bukan pendapat salah seorang yang akan menguasai pendapat orang-orang lainnya, tetapi pendapat bersama yang dicapai melalui musyawarah-mufakat. Dengan demikian, menurut pemikiran bangsa Indonesia, kepribadian individu tidak saja diakui, tetapi juga dilindungi. Kedua, tentang isi hukum. Soediman Kartohadiprodjo menyatakan, “Isi sesuatu (kaidah) hukum disandarkan pada kesadaran hukum pergaulan hidup yang menciptakan (kaidah) hukum itu. Maka, kalau negara dalam politik hukumnya juga mencakup isinya hukum, maka negara dalam politik hukumnya itu tidak dapat mengabaikan kesadaran hukum yang terdapat dalam pergaulan hidup.” 20 Dapat disimpulkan di sini bahwa Soediman Kartohadiprodjo ingin memperjelas posisi pemikirannya bahwa berlakunya hukum dalam suatu negara ditentukan oleh politik hukum negara yang bersangkutan, di samping kesadaran hukum masyarakat dalam negara itu.21 Jadi, isi hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum ini didefinisikannya sebagai keinginan batin untuk mencapai keadilan tata-tertib dalam pergaulan hidup manusia.22 Kata “keadilan” Id, pada hlm. 163. Id, pada hlm. 170. 19 Id, pada hlm. 163-164. 20 Soediman, 1982, Id, pada hlm. 38. 21 Id, pada hlm. 46. 22 Id, pada hlm. 38. 17 18 31 di sini dilekatkannya dengan “tata tertib”. Keduanya, di dalam wacana filsafat hukum memang sejak lama dipandang seperti dua sisi dari sekeping uang logam. Di sini terlihat bahwa Soediman berusaha untuk menjelaskan tentang dua arus kekuatan dalam pembentukan hukum. Arus pertama adalah arus energi yang disebutnya dengan politik hukum, yaitu energi yang memastikan haluan hukum Indonesia. Arus ini menentukan sisi formalitas dalam hukum. Sisi formalitas hukum ini menjamin hukum hadir dan diterapkan dengan penuh ketertiban. Arus kedua adalah arus nilai yang disebut Soediman sebagai kesadaran hukum masyarakat. Nilai-nilai ini muncul dalam pergaulan kemasyarakatan (living law). Dalam suasana demokrasi terpimpin yang cenderung segala keputusan ditentukan dari atas (top-down), nilai-nilai yang menjadi isi hukum ini dapat mudah sekali terdistorsi oleh pemegang kekuasaan. Benar bahwa kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan itu sudah coba diatasi dengan beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan negara di dalam konstitusi. Orde Baru menuduh pemerintahan sebelumnya telah menyimpang dari ketentuan konstitusi. Orde Baru kemudian berikrar untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Realisasi ikrar ini terbukti “jauh panggang dari api” dalam rangka membawa negara ke alam “kesejahteraan sosial”. Ketiga, tentang hak asasi manusia. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, baik demokrasi maupun hak-hak asasi manusia, jiwanya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap individu.23 Pahamnya adalah individualisme, suatu paham yang disandarkan pada pemikiran “men are created free and equal.” Masingmasing individu menyerahkan kekuasaannya kepada yang bertugas menertibkan pergaulan hidup, tetapi pada tiap-tiap individu ada kekuasaan yang tidak terpisahkan dari manusia, yaitu hak-hak asasi manusia. Soediman mengatakan, kalaupun ada penolakan, maka yang ditolaknya adalah dasar pemikiran (individualisme) itu, bukan jiwanya. Soediman mengusulkan pengganti individualisme ini dengan paham kekeluargaan. “Paham 23 Soediman, 2010, Id, hlm. 318. 32 kekeluargaan yang berasal dari keluarga ini, dan mengingat corak susunannya membawa pada kesimpulan bahwa paham kekeluargaan yang menjiwai Pancasila itu mempunyai tolak pangkal pemikirannya dari “kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan,” tulis Soediman Kartohadiprodjo.24 Praktik-praktik kenegaraan selama ini memperlihatkan paham kekeluargaan seperti dibayangkan oleh Soediman tidak pernah merefleksikan gagasan yang dikatakan sejalan dengan Pancasila itu. Kejatuhan Orde Lama ditandai dengan pembantaian begitu banyak rakyat Indonesia, demikian juga kejatuhan Orde Baru yang merampas nyawa manusia dengan cara-cara yang jauh dari semangat kekeluargaan: semangat Kesatuan dan Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan. Eksperimen terhadap gagasan paham kekeluargaan ini mengantarkan Indonesia pada episode pencarian alternatif gagasan lain yang pernah dintroduksi oleh Soepomo, yaitu paham negara integralistik. Gagasan ini menimbulkan prokontra karena memiliki kecenderungan untuk mengarahkan negara menjadi otoriter. Konsep “kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan” yang sering diulang-ulang oleh Soediman ini tentu menarik untuk dikaji dengan perspektif yang sama seperti penglihatan orang atas paham integralistik Soepomo. Misalnya, kita dapat mempertanyakan bagaimana konsep tadi memposisikan individu-individu berhadapan dengan negara? Apakah individu-individu itu melebur dan kehilangan eksistensinya untuk kemudian menjadi satu negara, ataukah justru sebaliknya bahwa individu-individu itulah yang sebenarnya eksis berdiri sendiri sementara negara adalah tatanan yang mereka sepakati sepanjang ada tujuan bersama. Dengan meminjam istilah dari Aquinas, Franz Magnis-Suseno menyebut perbedaan kedua jenis eksistensi itu sebagai unum in se dan unum ordinis. 25 Soepomo memilih konsep pertama, namun bagaimana dengan 24 25 Id, hlm. 319. Franz Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Kanisius, 1992, hlm. 97-98. 33 Soediman? Kesatuan dalam perbedaan sekilas dapat diasosiasikan kepada unum ordinis, sementara perbedaan dalam kesatuan mengarah ke unum in se. Pertanyaan selanjutnya dapat pula diajukan: apabila Soediman menginginkan agar sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ini dieja sebagai kesejahteraan sosial atau kebahagiaan, maka berapa banyak individu yang bisa disejahterakan dan dibahagiakan itu untuk dapat diklaim sudah terdapat “kesejahteraan sosial”? Apabila Soekarno mengatakan bahwa dalam prinsip kesejahteraan sosial itu tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, maka orang dapat dengan mudah mengatakan prinsip ini adalah sebuah utopia. Pengemuka teori-teori keadilan menunjukkan kesejahteraan sangat jarang dapat didistribusikan secara merata, sehingga akhirnya pasti selalu akan ada kelompok yang mendapatkan manfaat lebih atas suatu surplus yang hendak dibagikan. Paham komunisme yang berusaha keras mengatasi hal ini dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas, dalam kenyataannya gagal total mewujudkannya. Soediman, misalnya, tidak sempat menjawab pertanyaan apakah politik hukum yang memberi “kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar” masih sejalan dengan kesejahteraan sosial yang Pancasilais? Umumnya isu tentang keadilan muncul ketika ketidakadilan terjadi. Dalam filsafat politik, negara dianjurkan untuk menghindari munculnya ketidakadilan akibat struktur politik, sosial, dan ekonomi yang berlangsung secara tidak fair. Ketidakadilan struktural seperti inilah yang harus dicegah oleh negara. Soediman mencermati hukum peninggalan kolonial secara struktural telah menciptakan ketimpangan-ketimbangan sosial ini, dengan sengaja mendesain privelese bagi satu kelompok sosial dan secara bersamaan memarginalkan kelompok sosial lainnya. Di era kemerdekaan, sistem hukum Indonesia yang akan dibangun harus menghindari dari cara-cara berhukum seperti ini. Hanya saja, Soediman menyadari bahwa tidak mudah untuk menggantikan sistem hukum peninggalan kolonial itu. Untuk itulah ia memperkenalkan gagasan tentang revolusi hukum. 34 Sekilas istilah “revolusi hukum” ini akan membawa kita kepada makna sebagai upaya mengubah secara cepat dan masif pemaknaan konsep-konsep hukum untuk disesuaikan dengan kepentingan kita sebagai bangsa yang merdeka. Benarkah seperti itu yang dimaksud oleh Soediman? Lalu, siapa dan bagaimana melakukan revolusi hukum tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada satu sekuens menarik dari tulisan Soediman ketika ia mengomentari apa yang telah dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri/Menteri Kehakiman Sahardjo saat menerbitkan Surat Edaran Nomor 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963. Surat edaran ini memita agar para penguasa, terutama para hakim untuk lebih leluasa mengenyampingkan beberapa pasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) yang sudah tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia. Atas dasar surat edaran ini, Mahkamah Agung lalu menyatakan tidak belaku lagi beberapa pasal dalam BW, yaitu Pasal 108, 110, 284 ayat (3), 1682, 1579, 1238, 1460, 1603x ayat (1) dan ayat (2). Soediman Kardohadiprodjo menelisik langkah Sahardjo dengan kata-kata sebagai berikut:26 Gagasan Dr. Sahardjo ini nampaknya lahir dari rasa tidak puas bahwa kita yang dalam keadaan revolusi dengan tujuan membina suatu masyarakat berdasarkan filsafat Bangsa Indonesia, Panca Sila, terpaksa masih harus membiarkan berjalannya peraturan-peraturan hukum yang dasar pikirannya berlainan, bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang menjadi cita-cita kita, hanya karena sesuatu keadaan formil, yaitu bahwa kita belum sempat merobah dan mengganti ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan cita-cita kita. Rasa inilah nampaknya yang menjadi sumber gagasan Dr. Sahardjo itu. Kalau itu benar, maka inti dari pada gagasan itu adalah masalah penafsiran. Bukankah yang merupakan persoalan itu adalah: bagaimanakah kita akan menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada tetapi yang tidak sesuai dengan cita-cita kita tentang hukum itu? Bukankah cara menjalankan peraturan itu adalah penafsiran peraturan? 26 Soediman, 1982, Ibid, hal. 243. 35 Soediman menegaskan bahwa ia setuju sepenuhnya dengan apa yang dimaksudkan oleh Sahardjo dengan gagasannya itu, namun ia buru-buru menggugat dengan pertanyaan: “Tetapi perlukah ini menjalankan sesuatu yang begitu ‘drastis’ (teristimewa)? Apakah tidak ada jalan lain? Jalan yang lebih luwes?”.27 Artinya, Soediman tidak setuju revolusi hukum ini dilakukan dengan cara yang drastis. Ia lebih memilih jalan yang lebih luwes! Apa yang dimaksud dengan jalan luwes tersebut lagi-lagi tidak ditemukan secara eksplisit dalam tulisan Soediman. Ia hanya mengatakan, persoalannya terletak pada penafsiran. Boleh jadi, ia ingin agar pasal-pasal itu tidak harus secara drastis dicabut namun tafsir maknanya saja yang disesuaikan. Saran ini justru kontradiksi dengan ulasannya dalam menyikapi Pasal 163 de Indische Staatsregeling (IS). Ia merasa gelisah karena pasal ini masih diikuti sebagai aturan penggolongan penduduk di Indonesia ketika itu. Ia menyatakan: “Tafsiran ini yang pada umumnya diikuti selama zaman kolonial, sekarangpun masih berlaku. Keadaan ini sangat mengecewakan, tetapi selama politik hukum kita, istemewa mengenai hukum perdata nasional, belum ditentukan dengan tegas, dan karenanya pasal 163 IS itu masih berlaku, maka tafsir ini terpaksa harus kita lakukan”.28 Kata-kata “tafsir ini terpaksa harus kita lakukan” memperlihatkan sikap yang terbilang ambivalen dalam suatu revolusi hukum yang disarankan oleh Soediman. Tampak bahwa beliau masih mengharapkan agar ketentuan Pasal 163 IS itulah yang harus diubah (bahkan dicabut?) baru kemudian kita bisa menyesuaikannya dengan tafsir baru. Penutup Jika kembali kepada pertanyaan awal: apakah sebenarnya makna keadilan sosial bagi bangsa Indonesia menurut pandangan Soediman Kartohadiprodjo dan 27 28 Id. Id, pada hlm. 57. 36 bagaimana kaitannya dengan gagasan revolusi hukum yang diajukannya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, keadilan sosial dalam pandangan Soediman adalah sebuah gagasan yang sangat abstrak. Walaupun ia memulai analisisnya dengan menyatakan bahwa tiap-tiap individu pasti memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan [hidup dengan] rukun, Soediman tidak ingin terjerumus pada paham individualistis. Ia menekankan pentingnya keempat hal di atas untuk dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Kemampuan menjaga keempat hal ini dimaknainya dengan kebahagiaan. Jadi, keadilan sosial adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kebahagiaan. Kedua, apabila kata kunci dari keadilan sosial adalah kesejahteraan dan kebahagiaan, maka tatkala kata-kata kunci tersebut diterapkan di dalam konteks negara hukum, gagasan ini seharusnya dapat juga dibaca sebagai gagasan negara [hukum] kesejahteraan. Pandangan kekinian selalu melekatkan konsep negara [hukum] kesejahteraan ini dengan demokrasi, isi hukum, dan hak asasi manusia. Tampak ada paradoks pemikiran Soediman terkait ketiga komponen penting konsep negara [hukum] kesejahteraan ini. Paradoks ini terjadi karena sikap politik Soediman yang terkesan kuat sangat suportif terhadap pandanganpandangan Soekarno. Ketiga, revolusi hukum dimaknai oleh Soediman sebagai perubahan kesadaran hukum untuk hidup sebagai bangsa merdeka. Untuk itu, ia ingin agar penafsiran terhadap sistem hukum positif yang diwarisi dari kaum penjajah juga harus diubah, misalnya tentang komposisi penduduk Indonesia yang masih berpegang pada Pasal 163 IS. Pandangannya tentang revolusi hukum yang harus luwes dan tidak drastis ini memperlihatkan suatu ‘contradictio in terminis’ terhadap kata revolusi itu sendiri. Keempat, permikiran Soediman tentang keadilan sosial dan revolusi hukum (sebagai bagian dari revolusi total Soekarno) memberi penguatan pada 37 gagasan-gagasan besar dari Soekarno, tokoh yang demikian inspiratif bagi Soediman. Jika gagasan Soediman ini dibaca ulang dalam konteks yang sudah berubah di era sekarang, diperlukan penyesuaian-penyesuaian pemikiran sesuai konteks pada saat ini. Daftar Pustaka Darmodiharjo, Darji & Shidarta (1996). Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada/Rajawali Pers. Hatta, Mohammad (1983). Kumpulan Pidato II. Jakarta: Idayu Press. Kartohadiprodjo, Soediman (1982). Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Jilid I: Hukum Perdata. Jakarta: PT Pembangunan & Ghalia Indonesia. Kartohadiprodjo, Soediman (2010). Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Jakarta: Gatra Pustaka. Latif, Yudi (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Magnis-Suseno, Franz (1992). Filsafat sebagai Ilmu Kritis. Yogyakarta: Kanisius. Palombella, G. & Walker N. Eds. (2009). Relocating the Rule of Law. Oregon: Oxford & Portland. Shidarta (1996). “Mengkaji Kembali Keberadaan Sistem Hukum Indonesia.” Majalah Hukum Trisakti, Tahun 21/No.21/Januari 1996: 59-77. Shidarta (2008). Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. Bandung: Refika Aditama. Shidarta (2013). Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. Shidarta (2015). “Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial dan Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo.” Makalah seminar dalam rangka lomba debat hukum Piala Soediman Kartohadiprodjo, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 6 Maret 2015. Shidarta & Anthon F. Susanto (2014). Pengembangan Hukum Teoretis. Bandung: Logoz. Tamanaha, Brian. (2004). On the Rule of Law: History, Politics, Theory. New York: Cambridge University Press. 38