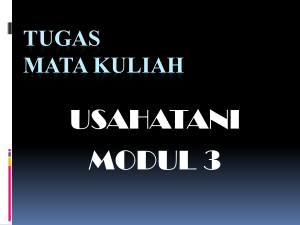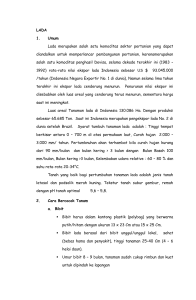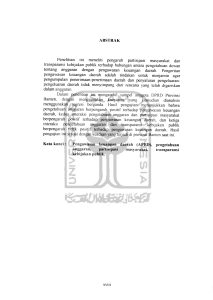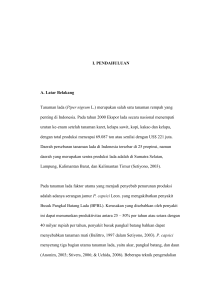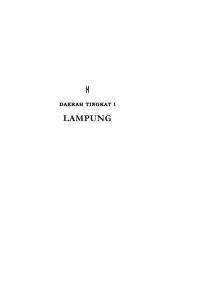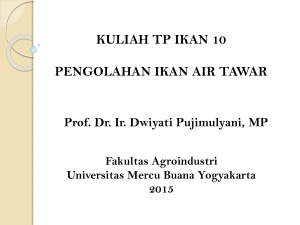Dampaknya bagi Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten
advertisement

18 Artikel Lada Si Emas Panas: Dampaknya bagi Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten Ery Soedewo Balai Arkeologi Medan Lada menjadi komoditas ekspor utama pada abad ke-17 dari kepulauan nusantara, terutama di Sumatera dan Jawa (Banten). Pada awal abad ke-16, Aceh tidak banyak menghasilkan lada. Hingga awal abad ke-17 pun kondisi tersebut tidak berubah. Pusat-pusat penghasil utama lada di Pulau Sumatera mula-mula lebih ke selatan letaknya, di pantai baratnya. 1. Pendahuluan Lada atau merica merupakan salah satu rempah yang dihasilkan di kepulauan nusantara. Rempah ini tampaknya diperkenalkan sedini abad ke-14 oleh para pedagang dari India (terutama Malabar) di beberapa tempat di bagian utara Pulau Sumatera, bersamaan dengan penyebaran agama Islam (Lombard, 2006: 59). Hasil nyata dari diperkenalkannya tanaman ini dilihat langsung oleh Ma Huan seorang penerjemah muslim Cina dalam ekspedisi maritim laksamana kekaisaran Dinasti Ming, Cheng Ho pada abad ke-15 M. Pelayaran armada Cheng Ho yang dimulai pada tanggal 19 Januari 1431 dari pelabuhan Nanking akhirnya tiba di Su-menta-la (Samudera) pada tanggal 12 September 1432 setelah singgah di beberapa tempat dalam perjalanannya (Chun, 1979: 15-17). Saat berada di Samudera itulah Ma Huan menyaksikan kebun lada dibudidayakan di lereng pegunungan. Ma Huan memerikan budi daya tanaman itu sebagai berikut, “tumbuhannya menjalar, menghasilkan bunga yang berwarna putih dan kuning; ladanya sendiri dihasilkan dari buahnya; berwarna hijau saat muda dan berwarna merah saat sudah tua; para petani menunggu untuk memanennya hingga buahnya setengah tua. Setelah dipanen, buahnya dijemur di bawah terik matahari, setelah kering lalu dijualnya. Setiap 100 chin dihargai 80 keping uang emas, yang senilai 1 liang perak” (Chun, 1979: 118). Harga yang tinggi dari rempah tersebut mengundang banyak pedagang dari berbagai negara berdatangan ke pusat-pusat HISTORISME penghasil dan perdagangan lada. Di kepulauan nusantara dua tempat yang dikenal sejak abad ke-16 sebagai penghasil lada adalah Aceh dan Banten. Kedua kesultanan tersebut menikmati masa-masa kejayaan perdagangan lada yang mengakibatkan tidak saja makin makmurnya kedua negara tersebut pada suatu masa, namun juga suatu akibat buruk yang mungkin tidak pernah diperkirakan akan menghampiri kedua kesultanan itu. Dalam tulisan singkat ini akan dipaparkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan budi daya lada sekaligus perdagangannya yang membawa berbagai dampak bagi peradaban di Aceh dan Banten. 2. Pusat-Pusat Budidaya Lada 2.1 Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka Lada menjadi komoditas ekspor utama pada abad ke-17 dari kepulauan nusantara, terutama di Sumatera dan Jawa (Banten). Pada awal abad ke-16 dikatakan oleh Pires bahwa Aceh tidak banyak menghasilkan lada. Hingga awal abad ke17 pun kondisi tersebut tidak berubah, menurut Beaulieu (pada tahun 1621), ”Sekarang ini belum mencapai 500 bahar setiap tahun, lagi pula kecil-kecil ladanya”, lebih lanjut dikatakannya bahwa karena keperluan akan beras, salah seorang raja terdahulu telah menyuruh cabut pohonpohon lada (Lombard, 2006: 101).1 1 “Dahulu jumlahnya besar, tetapi sang raja melihat bahwa orang Aceh terlalu gemar menanamnya sampai melalaikan penggarapan tanah sehingga setiap tahun bahan makanan mahal sekali; maka raja itu menyuruh cabut semuanya”. ERY SOEDEWO Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007 Universitas Sumatera Utara 19 Artikel Pusat-pusat penghasil utama lada di Pulau Sumatera mula-mula lebih ke selatan letaknya, di pantai baratnya. Parmentier pada tahun 1529 singgah di pelabuhan Tiku untuk mengisi palka kapalnya dengan rempah yang tinggi nilainya itu. Kata Beaulieu, “Di Pasaman, kebun-kebun lada mulai ditemukan, letaknya pada kaki sebuah gunung yang tinggi sekali, yang kelihatan dari jarak tiga puluh mil jika langit cerah, ladanya bagus-bagus dan besar, tujuh mil dari sana terletak Tiku yang lebih berlimpah-limpah lagi ladanya; di tempat-tempat tadi ada saja ladanya” (Lombard, 2006: 102). Kelompok perkebunan yang kedua terdapat di Semenanjung Malaka, Pulau Langkawi, dan Kedah. Oleh karena kesal disuruh Iskandar membayar harga lada terlalu tinggi, Beaulieu pada suatu pagi membongkar sauh dan menuju ke utara dengan harapan akan mendapat harga yang lebih baik dari Sultan Kedah, saingan Sultan Aceh. Ia singgah di Langkawai yang perkebunan ladanya, “ada di kaki gunung seperti juga di dataran rendah sepanjang 3 hingga 4 mil, tumbuhannya dipelihara seperti tumbuhan anggur yang tinggi cabang-cabangnya...yang merawat di situ tak lebih dari 100 tawanan” (Lombard, 2006: 102). Lalu Beaulieu ke Kedah minta izin pada sultan untuk mengadakan pembelian; dilihatnya bahwa di sana pun tumbuh tanaman lada, bukan main indahnya, meskipun kurang banyak jumlahnya. Dalam hubungan inilah Beaulieu memerikan tentang tanaman lada dan pemeliharaannya: “..., tumbuhnya di tanah yang baru dibuka dan yang gemuk; di negeri ini lada ditanam pada kaki segala macam pohon, dan pohon itu yang dililiti dan dijalarinya seperti cara tanaman hop. Mereka yang mau membuat tanaman lada, menanam tunas dari pohon lada yang sudah tua di salah satu semak; semua rerumputan yang tumbuh di sekitarnya harus dibersihkan atau disiangi dengan tekun. Tunas itu tumbuh tanpa berbuah sampai tahun ketiga; lalu mulailah ia pada tahun keempat keluarlah buahnya berlimpah-limpah dan besar-besar, dan tanaman semacam itu menghasilkan enam, tujuh pon lada, dan tak pernah buahnya sebesar dan sebanyak pada tahun panen HISTORISME pertama dan kedua, dan juga tahun ketiga yang rata-rata boleh dikatakan sama. Pada panen ke-4, ke-5, dan ke-6 hasilnya kurang sepertiga, yaitu pada umur sembilan tahun. Tahun kesepuluh, kesebelas, dan keduabelas buahnya hampir tak ada lagi dan kecil-kecil; lalu habis sama sekali” (Lombard, 2006: 102-103). “Pada bulan Agustus lada itu besar dan hijau, dan rasanya sangat pedas, tapi oleh penduduk dimakan sebagai salada atau diacar, yaitu dicampur dengan buah-buahan lain dalam kuah cuka yang dapat disimpan satu tahun penuh. Pada bulan Oktober lada itu merah, pada bulan November warnanya menjadi hitam...” (Lombard, 2006: 103). Dalam dunia beriklim sesuai, lada merupakan tanaman yang bandel, mudah tumbuh dari setekan pada beberapa batang yang berbuku, melilitkan diri pada setiap benda yang berdiri dekatnya, dan berpegang dengan akar yang tumbuh dari tiap-tiap buku, dengan panjang ruas kira-kira enam sampai sepuluh inci. Mungkin tanaman ini mengambil sebagian dari makanannya melalui akar-akar ini. Bila dibiarkan di tanah, akar itu akan menjadi panjang masuk tanah dan tanaman lada tak akan berbuah karena junjungan diperlukan untuk memungkinkan lada mengeluarkan tangkai buahnya. Batang lada dapat mencapai dua puluh hingga dua puluh lima kaki, akan tetapi akan tumbuh lebih subur bila dibatasi pada dua belas atau lima belas kaki. Bila lada mencapai dua puluh kaki, bagian bawah batang tak berdaun dan tak berbuah, sedangkan pada ketinggian lima belas kaki batangnya akan berbuah kira-kira satu kaki di atas tanah. Batangnya segera kayu, dalam waktu singkat akan tumbuh menjadi besar. Daunnya hijau tua dengan permukaan yang mengkilap, berbentuk jantung, ujungnya runcing, rasanya tidak pedas, dan hampir tidak ada baunya. Cabangnya rendah, tak tumbuh melebihi dua kali batangnya dan mudah patah pada sendinya. Bunganya kecil dan putih, sedangkan buahnya bulat menjadi berwarna merah menyala bila matang dan tak mengalami kerusakan. Tangkai buah tumbuh subur dari cabang-cabang dalam gerombol kira-kira dua puluh sampai lima puluh butir tiap tandan yang memanjang, tiap butir ERY SOEDEWO Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007 Universitas Sumatera Utara 20 Artikel berpegang pada tangkai yang sama, yang mengakibatkan butir-butirnya tumbuh dan membuat tangkainya kaku (Marsden, 1999: 94-95). 2.2 Pulau Jawa Pusat perdagangan dan perkebunan lada di Pulau Jawa yang terbesar adalah Banten. Pada abad ke-16 aktivitas perdagangan ladanya telah menarik banyak pedagang mancanegara. Pada tahun 1522 Banten mengekspor 1000 bahar lada setiap tahun ke berbagai penjuru dunia, terutama ke Cina dan Eropa (Chris, 1881: 4 dalam Untoro, 2006: 167). Pada masa itu, lada merupakan bahan rempah yang sangat diminati oleh orang-orang di benua Eropa, sehingga para pedagang asing berdatangan ke kawasan penghasil lada di Nusantara. Menurut J. Bastin (1960: 9--10), keperluan lada Eropa pada abad ke-16 terus meningkat, tercatat sebelum 1506 sebanyak 1,5 juta ton per tahun, menjelang tahun yang sama naik 2 juta ton, bahkan di tahun 1509 menjadi 6 hingga 7 juta ton (Untoro, 2006: 167). Lada yang dikeluarkan dari pelabuhan Banten selain dihasilkan dari kebun-kebun di Banten sendiri, juga diproduksi di kebun-kebun lada di wilayah kekuasaan Banten di Pulau Sumatera seperti Lampung, Palembang, dan Bengkulu (Untoro, 2006: 167). Di Banten sendiri, lada dibudidayakan di kawasan pedalaman, namun tidak disebutkan secara pasti lokasinya di daerah mana. Colenbrader (1923: 163) menjelaskan banyak petani lada datang dengan perahu dari pedalaman ke Kota Banten di pesisir pada waktu musim hujan (Untoro, 2006: 169). Kedatangan petani lada ini sangat diharapkan oleh para saudagar, karena mereka dapat membeli dan mengumpulkannya sebelum dibawa ke negeri masing-masing. Setiap tahun mereka berusaha mendapatkan lada sebanyak mungkin agar dapat diangkut sesuai dengan kapasitas kapal (Untoro, 2006: 169). 3. Dampak Budidaya Perdagangan Lada dan Dampak langsung dari meningkatnya permintaan lada oleh pasar luar negeri HISTORISME adalah timbulnya persaingan antar para pedagang asing, sehingga masing-masing berusaha untuk memperkuat posisinya dengan bermacam cara. VOC misalnya, berusaha mempengaruhi Sultan Banten agar mendapatkan hak monopoli perdagangan lada. Sedangkan para pedagang dari Cina tidak lagi menunggu kedatangan petani lada di pasar, tetapi langsung ke tempat penanaman lada di pedalaman (Untoro, 2006: 169). Usaha ini tampaknya mendatangkan keuntungan berlipat ganda, sehingga ada pedagang dari Cina memindahkan pemukimannya ke arah selatan. Walaupun jumlah lada yang mereka dapatkan terbatas karena sarana transportasi tidak memadai, jalan darat sulit ditembus dan jalan satu-satunya adalah melalui sungai, namun kegiatan tersebut tetap berlangsung. Bahkan tidak jarang para pedagang dari Cina menukarkan barang dagangan yang dibawa dari negerinya, dengan lada secara langsung (Untoro, 2006: 170). Lada yang dikeluarkan dari pelabuhan Banten setiap tahun cukup banyak. Tercatat di tahun 1603, orang Belanda mengimpor dari pelabuhan ini sejumlah 259.200 pon lada, sedangkan pada tahun 1608 kapal Belanda bernama Bantam berhasil mengapalkan 8.440 karung lada. Pada tahun 1618, tampak 10 kapal dagang Cina dengan kekuatan antara 1000 hingga 1500 ton datang ke Banten dengan membawa berbagai mata dagangan. Kapal-kapal ini memuati bahan rempah terutama lada sekembalinya ke Cina (Untoro, 2006: 170). Permintaan lada yang besar dan harganya yang tinggi, mengakibatkan pemasukan devisa yang sangat besar bagi kas Kesultanan Banten. Selain itu pendapatan diperoleh pula dari bea cukai terhadap barang yang masuk dan keluar pelabuhan Banten. Untuk barang ekspor yang bukan hasil Banten sendiri, dikenakan pajak yang lebih besar daripada hasil dalam negeri seperti lada. Besarnya pajak yang berlaku agaknya tidak sama untuk setiap saudagar, disebutkan pedagang Belanda dikenakan 8%, sedangkan pedagang Cina hanya 5%, tetapi para pedagang Cina diharuskan membawa hadiah barang keramik dari negerinya (Untoro, 2006: 171). ERY SOEDEWO Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007 Universitas Sumatera Utara 21 Artikel Dalam bercocok tanam lada (Piper nigrum) faktor utama penentu keberhasilan panen lada adalah pemilihan tempat yang cocok. Biasanya, tempat yang paling cocok adalah tanah di tepi sungai atau anak sungai. Ketinggian permukaan tanah jangan terlalu rendah sehingga dapat digenangi air karena humus biasanya terdapat di tempat seperti itu (Marsden, 1999: 92). Sebenarnya, air pun mempermudah pengangkutan hasilnya kelak. Lereng-lereng curam harus dihindarkan, kecuali lereng landai karena kegemburan tanah akan bertambah akibat penanaman, biasanya, humus pun hanyut terbawa air bila hujan lebat. Tanah-tanah datar yang tidak ditumbuhi atau hanya ditutupi rumput yang hijau terbukti tidak memenuhi syarat. Tanpa bantuan bajak atau pupuk kandang, kesuburan tanah habis terkena terik matahari (Marsden 1999: 92--93). Biasanya para petani lada akan mengganti ladangnya dan meninggalkan lahannya yang dipersiapkan dengan susah payah setelah menanamnya selama satu atau dua musim. Hal ini berarti hutan-hutan ditebangi dan tanahnya dibersihkan untuk penanaman lada langsung (Marsden, 1999: 93). Di Banten akibat sistem pertanian lada yang ekstensif ini mengakibatkan terjadinya sedimentasi yang besar. Dampak langsungnya tentu saja pendangkalan alur sungai dan bahkan yang terparah adalah terjadinya sedimentasi di daerah muara sungai yang berakibat makin dangkalnya pelabuhan alam Banten. Hal ini mengakibatkan kapal-kapal besar tidak dapat lagi merapat di pelabuhan Banten (Untoro, 2006: 183). Kondisi demikian digambarkan oleh para pelaut asing yang berdagang di Banten pada abad ke-18. Seperti yang diuraikan oleh Valentijn (1726) bahwa untuk masuk ke pedalaman melalui sungai sangat sulit, sebab sungai Cibanten sudah sangat dangkal. Kecuali bila musim hujan tiba, air sungai agak tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan itu (Untoro, 2006: 192). Berdasarkan data tersebut dapat ditafsirkan bahwa kelancaran transportasi antara pedalaman dan pesisir yang dihubungkan lewat Sungai Cibanten telah mengalami hambatan. Akibatnya sumber daya yang berasal dari pedalaman tidak HISTORISME mudah lagi untuk dibawa ke pesisir setiap saat, demikian sebaliknya komoditi yang berasal dari Kota Banten akan sulit menembus masuk ke daerah hulu (Untoro, 2006: 192). Van Breugel (1787) menyatakan bahwa pantai Banten penuh lumpur sehingga kapal perang tidak dapat mendekati kota. Meskipun secara tidak langsung kondisi lingkungan semacam ini dapat menjadi pertahanan alami yang ampuh di masa perang, namun menjadi kendala besar bagi pelabuhan dan kota dagang di masa damai. Kapal-kapal dagang dengan muatan yang sarat akan sulit merapat (Untoro, 2006: 192). Sebagaimana di Kesultanan Banten, budi daya dan perdagangan lada telah mendatangkan banyak pemasukan bagi kas kesultanan. Namun, demikian halnya dengan Banten, sisi negatif perdagangan lada juga dirasakan oleh Aceh di samping beragam keuntungan yang diperoleh darinya. Lada bagi Aceh bukan saja berfungsi sebagai mata dagangan yang mendatangkan devisa, namun juga dimanfaatkan sebagai alat diplomasi politik dengan negara lain. Hal ini terjadi ketika Aceh memohon bantuan dari Turki persenjataan berat untuk menyerang Malaka. Sultan Iskandar Muda mengutus para duta menuju Turki dengan di bekali padi, beras, dan lada ke dalam 3 buah kapal. Namun dalam perjalanan para awak menjumpai banyak kesulitan, sehingga mereka baru mencapai Konstantinopel setelah 3 tahun, dalam masa itu mereka memakan nasi dari beras yang di bawa dan menjual hampir seluruh lada yang dimuat dalam 3 kapal itu, dan yang tertinggal hanyalah secupak lada. Meskipun demikian, Sultan Rum (Turki) berbaik hati dengan menganugerahkan kepada para utusan itu permintaan yang mereka harapkan sebagai mana yang dikehendaki oleh Sultan Aceh. Di samping meriam-meriam itu Sultan Turki juga mengirimkan pada Aceh para tukang untuk membangun benteng besar di Aceh, istana, dan juga Gunongan. Di akhir abad ke-18, terjadi perkembangan yang luar biasa dalam pembudidayaan lada di daerah selatan pantai barat Sumatera yang berada dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. ERY SOEDEWO Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007 Universitas Sumatera Utara 22 Artikel Menjelang tahun 1820 daerah ini menyediakan sekitar setengah dari pasokan lada dunia. Sementara kompeni dagang Belanda dan Inggris masih harus berjuang untuk mendapatkan muatan terbatas dari pos-pos dagang mereka di daerah tersebut, para pedagang swasta berduyun-duyun ke Aceh untuk membeli lada dari wilayah ini (Reid, 2005: 164). Para pedagang swasta tersebut terdiri dari para pedagang Inggris dan Cina dari Pulau Penang, pedagang dari Perancis, Arab, India, dan Amerika. Pada tahun 1823 empat kapal besar Perancis yang bersaing dengan 27 kapal Amerika berhasil mengangkut muatan berupa lada dari pantai-pantai di Aceh. Dua puluh tahun kemudian para pedagang Perancis menduduki tempat ketiga setelah para pedagang swasta Amerika dan Inggris. Sembilan atau sepuluh kapal Perancis mengunjungi Pulau Penang setiap tahunnya, dan sebagian besarnya mengunjungi pelabuhanpelabuhan di Aceh untuk membeli lada (Reid, 2005: 164). Keberhasilan perdagangan lada di Aceh ditentukan antara lain oleh kefasihan para pedagang swasta asing tersebut dalam berbahasa Melayu atau Aceh, sebagai alat antisipasi terhadap beragam bahaya selama transaksi dengan para pedagang maupun penguasa di pelabuhan-pelabuhan Aceh. Mereka yang berhasil menguasai kemampuan tersebut akan terjamin keberhasilannya dalam perdagangan bahkan nyawa mereka. Salah satu contoh tentang keberhasilan ini adalah seorang pedagang swasta Perancis yakni Kapten Martin dari Marseilles. Dia meninggalkan pelabuhan Marseilles pada tahun 1838 menuju Sumatera via Bourbon untuk membeli lada yang kemudian dijualnya di pelabuhan Pulau Penang. Dia lalu datang lagi untuk mengangkut muatan lada keduanya yang dijualnya di Singapura. Akhirnya dia memuat 80.000 kg timah di Pulau Penang bersamaan dengan muatan ladanya yang ketiga dari Aceh, lalu kembali lagi ke Perancis via Bourbon dan tiba di Marseilles pada bulan November 1839, suatu perjalanan selama 20 bulan (Reid, 2005: 165). Pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 ketika kekuasaan sultan-sultan Aceh terhadap pelabuhan-pelabuhannya semakin HISTORISME melemah, perdagangan lada di tempattempat itu berlangsung sebagaimana masa western di Amerika, yang dikenal sebagai masa “diplomasi kapal perang”. Para kapten kapal dagang yang mampu menunjukkan arah dengan baik menuju pelabuhan-pelabuhan lada di Aceh, disertai kesabaran, serta kejujuran tidak akan banyak menemui kesulitan, bahkan bakal mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari para pedagang lada di Aceh (Reid, 2005: 165). Namun, sebagai akibat naik turunnya harga yang begitu cepat dalam perdagangan lada, mengakibatkan timbulnya banyak konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh otoritas politik Aceh. Untuk menyelesaikan itu para pedagang asing tersebut tidak jarang menggunakan kekuatan senjata api untuk menyelesaikannya. Hal demikian acap kali dilakukan oleh Inggris dan Belanda di kepulauan nusantara, termasuk di antaranya di pelabuhanpelabuhan Aceh. Selain para pedagang dari kedua negara tersebut ternyata orang Amerika pun pernah juga menggunakan cara ini. Hal itu dilakukan ketika lima awak kapal dagang Frienship tewas oleh serangan yang dilakukan oleh penguasa pelabuhan Kuala Batee di pantai barat Aceh. Peristiwa terbunuhnya kelima awak kapal tersebut mendorong terjadinya serangan pertama kali oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan Asia Tenggara pada Februari 1832, dengan dikerahkannya kapal perang Pottomac yang menghancurkan Kuala Batee (Reid, 1995: 235).2 Serangan serupa dilakukan lagi pada tahun 1838 terhadap Meukek yang terletak tidak jauh dari Kuala Batee sebagai balasan atas terbunuhnya Kapten Endcot dan Kapten Wilkins di pelabuhan lada tersebut (Reid, 2005: 165). Belum lagi hilang dari ingatan serangan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1838, setahun berikutnya (1839) terjadi lagi serangan atas Meukek, kali ini oleh Angkatan Laut Perancis. Hal ini terjadi setelah seorang kapten Perancis bernama Van Tseghem dari Nantes mengalami luka tusuk akibat diserang oleh seorang pedagang Aceh 2 Anthony Reid, 1995. Witnesses to Sumatra A Travellers’ Anthology. Kuala Lumpur: Oxford University Press, Hal.235. ERY SOEDEWO Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007 Universitas Sumatera Utara 23 Artikel kaya setelah terjadi percekcokan antara keduanya. Gempuran terhadap Meuke kali ini dilakukan oleh kapal perang Angkatan Laut Perancis, La Dordogne yang berpangkalan di Bourbon (Reid, 2005: 165). 4. Penutup Lada banyak dicari oleh para pedagang mancanegara untuk dipasarkan lagi di tempat asal masing-masing baik sebagai bumbu masakan maupun bahan obat-obatan. Kebutuhan yang tinggi terhadap rempah yang satu ini meningkatkan harga jualnya di pasaran internasional. Kondisi demikian mengakibatkan persaingan antar pedagang tak terelakkan. Mereka mencoba memaksakan monopoli terhadap mata dagangan eksklusif ini. Akibatnya, para pedagang asing itu tidak hanya bersaing antar mereka, bahkan juga menimbulkan tentangan dari para produsen lada, seperti Aceh dan Banten. Lebih jauh lagi upaya monopoli oleh kompeni dagang asing terhadap lada ternyata mengakibatkan kedaulatan kedua negara tersebut hilang, dalam masa yang berbeda. Banten sejak akhir abad ke-17 otomatis sudah sangat tergantung pada VOC, sedangkan Aceh baru pada awal abad ke-20 secara politis –secara de facto– sudah tidak berwujud sebagai suatu negara dengan menyerahnya Sultan Aceh terakhir Alauddin Muhammad Daud Syah pada tahun 1903 kepada Belanda. Dampak lain yang diakibatkan oleh ekstensifikasi budi daya lada – sebagaimana kasus Banten– adalah rusaknya lingkungan, khususnya daerah perairan baik pedalaman maupun pesisirnya. Terjadinya sedimentasi yang tinggi mengakibatkan pendangkalan alur sungai dan pelabuhan laut, sehingga proses pengangkutan hasil HISTORISME produksi dari pedalaman ke pelabuhan menjadi terganggu, juga kapal-kapal besar yang hendak mengangkut lada dari pantai kesulitan untuk berlabuh karena terjadinya pendangkalan di daerah pelabuhan. Singkat kata budi daya dan perdagangan lada memang membawa kemakmuran bagi Aceh dan Banten, namun ketidakarifan dalam pengelolaannya mengakibatkan kehancuran bagi kedua negara itu. Keuntungan yang diberikan lada pada puncak kejayaannya bagaikan emas bagi yang berusaha darinya, tetapi lada juga benar-benar pedas tidak saja secara harfiah namun juga panas bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam bisnisnya. Kepustakaan Chun, Feng Chen. 1979. Ma Huan Ying-Yai Sheng-Lan ‘The Overall Survey of The Ocean’s Shores’. London: Cambridge University Press. Lombard, Denys. 2006. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Forum Jakarta Paris, École française d’Extrême-Orient. Marsden, William. 1999. Sejarah Sumatra. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. Reid, Anthony. 1995. Witnesses to Sumatra A Travellers’ Anthology. Kuala Lumpur: Oxford University Press. .........., 2005. An Indonesian Frontier Acehnese & Other Histories of Sumatra. Singapore: Singapore Unioversity Press Untoro, Heriyanti O. 2006. Kebesaran dan Tragedi Kota Banten. Jakarta: Yayasan Kota Kita. ERY SOEDEWO Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007 Universitas Sumatera Utara