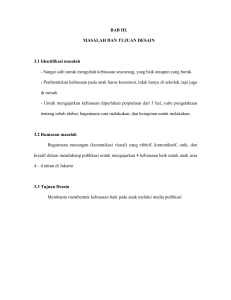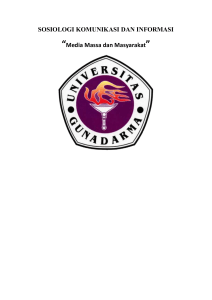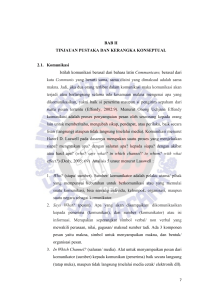Memotret Deliberasi Politik Berbasis Agama di
advertisement

Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 79-97 ISSN 2302-5719 Vol II, Nomor 1 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama: Memotret Deliberasi Politik Berbasis Agama di Indonesia dengan Perspektif Filsafat Politik Jürgen Habermas ALEXANDER AUR Dosen Religiositas dan Etika Universitas Multimedia Nusantara dan KALBIS Institute Surel: [email protected] Diterima: 13 Februari 2014 Disetujui: 4 April 2014 ABSTRACT Enlightenment (Aufklärung) is not entirely successful confining religion to be a problem for private realm. Religion still exists in the public sphere. Today, religion is pushed into the democratic constitutional state. Jürgen Habermas argues that a dialogue between democratic state and religion is important today. Democratic state has rationality when religion has a place in the deliberation process. Thus, religion gives the normative principles for the democratic state. Yet religion can not be the basis for a democratic state. Therefore, it is beneficial for democracy if religion should translate its metaphysical language into the language espoused by the secular democratic state. Religious metaphysical assumptions must be tested by the secular reason and the institutional translation proviso. By meeting the terms of the secular reason, democratic state and religion can learn from each other and do dialogue. Keywords: negara hukum demokratis, tindakan komunikatif, rasio prosedural, agama rasional, situasi epistemik pluralitas. dirinya, dan sekarang merangsek ke ruang publik dalam berbagai bentuk. Terorisme Dalam sejarah politik dunia, khususnya di berwajah agama, partai-partai politik berbenua Eropa, setelah kelahiran Pencerahan basis agama, gerakan-gerakan kemanusia­ (Aufklärung) yang mengusung rasio sekuan berbasis spiritualitas lembaga-lembaga lar, agama didomestifikasi menjadi urusan agama, gerakan pembaharuan politik berprivat, dan dilenyapkan dari ruang publik. nuansa agama merupakan beberapa contoh Meski demikian, setelah sekian lama dido- konkrit agama yang eksis di ruang publik. mestifikasi, Pencerahan tidak sepenuhnya Fenomena domestifikasi agama dan berhasil mengurung agama dalam ruang merangseknya agama ke dalam ruang puprivat. Alih-alih “mematikan” agama de­ blik merupakan fenomena yang berlang­ ngan mendomestifikasikannya, yang terjadi sung dalam bingkai hubungan agama dan malah sebaliknya: agama memetamorfosis negara. Parakitri T. Simbolon memetakan Pendahuluan 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 79 4/24/2014 10:01:20 AM 80 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama tiga pola hubungan agama dan negara (Parakitri T. Simbolon dalam JB. Kristanto dan Nirwan Ahmad Arsuka (ed.), 2002: 430), yakni integral simetris, integral asimetris, dan sipil. Dalam pola integral simetris hubungan agama dengan negara tidak dipisahkan, keduanya bersatu. Pola ini sering disebut theocracy. Dalam pola integral asimetris, hubungan antara agama dengan negara bisa berbentuk “agama dalam negara” atau “negara dalam agama.” Pada bentuk “agama dalam negara”, agama tetap harus tunduk pada kekuasaan negara meskipun agama mempunyai pengaruh yang besar. Pada bentuk “negara dalam agama”, negara tunduk pada kekuasaan agama meskipun negara mempunyai pengaruh yang besar. Sedangkan dalam pola sipil, berdasarkan format formal negara dan agama dipisahkan tetapi pada format praktik satu agama atau lebih yang dominan.1 Negara hukum demokratis dan agama masing-masing mempunyai tujuan. Dengan bertumpu pada kedaulatan rakyat, nujuan negara hukum demokratis adalah membentuk tatanan sosial demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan hidup para warga negara di dunia ini. Dengan kata lain, alasan adanya sebuah negara terletak pada usaha manusia untuk membentuk sebuah tatanan sosial, dan tatanan itu diatur dengan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia di dunia saja. Sedangkan tujuan agama adalah mengarahkan para pemeluknya (umat beriman) untuk memperoleh kesalehan hidup di dunia ini, dan 1 VOL II, 2014 kesalehan itu sebagai antisipasi bagi kehidupan setelah kematian (hidup di akhirat). Meskipun agama mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi bukan berarti agama berada di luar negara hukum demokratis. Agama merupakan salah satu unsur dalam negara hukum demokratis. Itu artinya, agama turut berperan secara aktif dalam menguatkan negara hukum demokratis. Tetapi problem yang sering kali terjadi adalah konflik antara agama dengan negara hukum demokratis. Tidak jarang, konflik yang terjadi bersifat saling menaklukkan satu sama lain. Hal yang terjadi pada akhirnya adalah agama takluk di hadap­ an negara atau negara takluk di hadapan agama. Atau sekurang-kurangnya dari sisi negara, aparatus negara ragu-ragu dalam menyikapi secara tegas relasi konfliktual tersebut. Relasi konfliktual yang meng­ arah pada penaklukkan ini tidak sehat bagi demokrasi itu sendiri. Demokrasi sebagai bentuk dan cara berpolitik, yang di dalamnya semua unsur dimungkinkan berpartisipasi-aktif membangun hidup bersama, maka upaya-upaya penaklukkan terhadap demokrasi mesti diantisipasi dan diatasi oleh semua unsur. Agama dengan klaim metafisiknya mem­ punyai kecenderungan untuk menakluk­ kan demokrasi. Supaya tidak menjadi “duri dalam daging” demokrasi serta tidak melumpuhkan demokrasi dengan klaimklaim metafisiknya, agama mesti mampu berkomunikasi dengan negara hukum de­mokratis. Komunikasi dapat berlang­ sung bila, bahasa agama ditranslasikan ke Parakitri T. Simbolon memberikan contoh negara yang menganut tiga pola hubungan negara dan agama tersebut. Negara-negara yang menganut integral simetris antara lain Vatikan, Tibet sebelum dikuasai Tiongkok, Iran di bawah Khomeini, dan mungkin Arab Saudi. Negara-negara yang menganut pola integral asimetris antara lain mulai dari sangat lunak sampai keras seperti Inggris dan Pakistan. Negara-negara yang menganut pola sipil dengan variasinya masing-masing, antara lain Malaysia, Brunei, Filipina, dan Indonesia. Malaysia dan Brunei menetapkan adanya agama negara tetapi tetap menjamin hak-hak agama lain. Filipina dan Indonesia mengakui pluralitas agama dengan satu agama yang dominan. 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 80 4/24/2014 10:01:20 AM Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama dalam bahasa negara hukum demokrasi. Mengapa agama harus mentranslasikan bahasanya ke dalam bahasa negara hukum demokratis? Uraian ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Uraian didasarkan pada pemikiran Jurgen Habermas tentang agama dalam negara hukum demokratis. Pembahasan berikut berpijak pada tesis ini: agama dan negara hukum demokratis dapat saling berdialog hanya jika agama mengubah dirinya dari agama mitis menjadi agama rasional dan negara hukum memberi ruang (kesempatan) bagi agama untuk berdeliberasi. Tulisan ini terbagi dalam beberapa bagian. Pertama akan diuraikan upaya Habermas melampaui positifikasi rasio sekular oleh Pencerahan (Aufklärung).2 Upaya Habermas ini juga mendasari optimismenya bahwa rasio sekular merupakan proyek modernitas yang belum tuntas. Kedua, akan diuraikan teori Habermas tentang tindak­ an komunikatif, etika diskursus, dan demokrasi deliberatif. Ketiga, akan disajikan pemikiran Habermas tentang agama di dalam negara hukum demokratis. Keempat, akan disampaikan potret deliberasi politik berbasis agama di Indonesia. Dalam pemikirannya tentang posisi agama dalam negara hukum demokratis, Habermas menempatkan pokok itu dalam bingkai teorinya tentang tindakan komunikatif (communicative action), etika diskursus (discourse ethics), dan demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, artikel tentang pemikiran Habermas mengenai agama ini ditempat- ALEXANDER AUR 81 kan dalam bingkai teori Habermas tentang tindakan komunikatif, etika diskursus, dan demokrasi deliberatif. Ada dua alasan perihal penempatan itu: pertama, supaya kita dapat memahami pemikiran Habermas tentang status sosiologis-politik agama secara tepat, utuh, dan tidak keluar dari arena pemikirannya secara keseluruhan. Kedua, supaya kita bisa menimba inspirasi dari Habermas terutama tentang keberadaan dan peran agama atau politik berbasis agama dalam konteks perpolitikan di Indonesia. 1. Rasio Komunikatif: Upaya Habermas Melampaui Rasio Instrumenal Sebelum memaparkan pemikiran Haber­ mas tentang rasio komunikatif, terlebih da­hulu digambarkan secara singkat kemunculan ilmu pengetahuan modern. Paparan tentang hal itu didasarkan pada analisis yang dibuat Francisco Budi Hardiman (1990, 22-26). Dalam analisisnya, Budi Hardiman mengatakan ilmu pengetahuan yang mendasarkan posisinya pada ke­sanggupan rasio manusia lahir untuk memeroleh pengetahuan. Dari tujuan itu, ilmu pengetahuan melakukan positivikasi rasio sehingga menjadi rasio instrumental. Positivikasi dilakukan oleh para filsuf dan ilmuwan yang beraliran positivisme.3 Pencerahan (Aufklärung) menjadi titik awal bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dalam ilmu pengetahuan modern, rasio manusia menjadi acuan utama untuk memeroleh pengetahuan. Dalam filsafat modern itu sendiri, terdapat dua P�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ara eksponen Mazhab Frankfürt generasi pertama, seperti Adorno dan Horkheimer mencemaskan bahwa Pencerahan telah menggiring rasio menjadi sangat instrumental. 3 Francisco Budi Hardiman mencatat bahwa meskipun positivisme yakin bahwa pengetahuan yang sahih adalah pengetahuan yang berdasarkan fakta objektif. Dengan menyingkirkan pengetahuan yang melampaui fakta, positivisme mengakhiri riwayat ontologi atau metafisika, karena ontologi menelaah apa yang melampaui fakta indrawi. Meski demikian, positivisme terutama ilmu-ilmu positif seperti fisika, kimia, biologi, menerima warisan ontologi atau metafisika dalam dua hal. Pertama, ilmu-ilmu positif mewarisi sikap teoritis murni sebagai metodologi. Kedua, ilmu-ilmu positif masih menyimpan pengandaian dasar ontologi bahwa struktur dunia dan struktur masyarakat tidak tergantung dari subjek yang mengetahuinya. 2 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 81 4/24/2014 10:01:20 AM 82 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama blok besar yakni rasionalisme dan empirisisme. Rasionalisme menekankan bahwa pengetahuan murni dapat diperoleh melalui kemampuan rasio manusia itu sendiri. Oleh karenanya, pengetahuan bersifat a priori. Sedangkan empirisisme menekankan bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui pengalaman empiris. Oleh karenanya, pengetahuan bersifat a posteriori. Dalam perkembangan selanjutnya, pe­ ngetahuan empiris-analitis menjadi ilmu alam yang direfleksikan secara filosfis sebagai pengetahuan yang benar mengenai realitas. Pada titik ini ilmu alam dikembangkan sebagai teori murni dengan bantuan rasionalisme serta empirisisme. Para ilmuwan alam pun memahami alam sebagai sebuah kosmos dengan seluruh hukumnya yang teratur, tertib, dan tetap. Dari rahim filsafat empirisme, kemudian lahir positivisme yang dirintis oleh Auguste Comté. Bagi positivisme, fakta objektif merupakan pengetahuan yang benar. Positivisme tidak percaya pada ontologi atau pengetahuan yang melampaui fakta. Dari positivisme inilah lahir pula sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Positivisme dalam ilmu sosial mengandung tiga pengandaian yang saling bertautan. Pertama, prosedur metodologis ilmu alam dapat diterapkan secara langsung pada ilmu sosial. Artinya, subjektivitas seperti kepentingan serta kehendak manusia sama sekali tidak berpengaruh terhadap perilaku manusia yang menjadi objek yang diamati. Dengan demikian, perilaku manusia sebagai objek ilmu pengetahuan setara dengan dunia alamiah. Kedua, hasil penelitian dirumuskan ke dalam ‘hukum’ sama layaknya dalam ilmu alam. Ketiga, ilmu sosial tidakbisa-tidak bersifat teknis yang murni instrumental. 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 82 VOL II, 2014 Positivisme logis mendapat kritik keras dari Mazhab Frankfürt yang dikenal dengan sebutan Teori Kritis. Para eksponen Teori Kritis generasi pertama antara lain T.W. Adorno dan Horkheimer. Mereka berpendapat bahwa positivisme logis me­ rupakan saintisme. Pencerahan telah membuat manusia menghadapi alam dengan kalkulasi. Pencerahan melahirkan konsep rasionalitas yang positivistik. Rasionalitas pencerahan adalah rasio instrumental (Zweckrastionalität). Pencerahan membuat rasio kehilangan tujuan pada dirinya sendiri. Di tangan positivisme, rasio menjadi instrumental, tukang atau alat untuk kalkulasi, verifikasi, dan pelayan klasifikasi. Bagi Adorno dan Horkheimer, pendakuan Pencerahan akan netralitas rasio instrumental, justru menunjukkan bahwa karena netralitasnya itulah, rasio instrumental tunduk pada berbagai tujuan dan dapat dipakai oleh siapa saja. Ciri instrumental dalam cara berpikir manusia tampak dalam perhatian yang ketat terhadap prinsip-prinsip kerja rasio sehingga dapat diterapkan untuk tujuan apa saja yang dikehendakinya. Dalam situasi yang demikian, rasio instrumental dapat menjadi alat untuk memanipulasi. Bagi Mazhab Frankfürt, rasionalitas sebagaimana diperjuangkan pencerahan itu tidak memeroleh kemajuan apapun, dan menampakkan kembali mitos yang sebelumnya disingkirkan. Rasio pencerahan justru menciptakan kembali mitos dengan berorientasi pada hal di luar dirinya yakni ekonomi dan politik. Rasio lalu tunduk terhadap ekonomi dan politik. Pola kerja rasio pencerahan itu sama dengan/atau merupakan peniruan (mimesis) pola masyarakat tradisional yang tunduk terhadap sesuatu yang metafisik di luar dirinya. Alih-alih netral dan tak memikirkan tujuan pada dirinya sendiri, rasio pencerahan justru 4/24/2014 10:01:20 AM Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama merupakan pengulangan atas mitos lama (Hardiman, 1990: 30, 64-65).4 2. Tindakan Komunikatif Sebagai generasi baru Teori Kritis, Habermas optimis bahwa rasionalitas merupakan proyek modernitas yang belum tuntas. Ia bermaksud mengatasi positivikasi rasio oleh positivisme logis dengan teorinya tentang rasio komunikatif (Hardiman, 1990: 86).5 Dalam teori tindakan komunikatif, Habermas membedakan antara tindakan strategis dengan tindakan komunikatif. Secara fundamental, teori tindakan komunikatif terletak dalam pembedaan dua konsep rasionalitas yang menuntun pengetahuan kepada tindakan. Dua konsep rasionalitas yang dimaksud adalah rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif. Kedua konsep itu merupakan bagian dari tindakan. Rasionalitas instrumental adalah rasionalitas yang mengarahkan tindakan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan secara pribadi. Rasionalitas ini akan bersifat instrumental bila diarahkan kepada alam, misalnya dalam bentuk kerja. Rasionalitas ini juga bersifat strategis apabila diarahkan untuk memengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh pihak lain, seperti dalam bentuk hubung­ an dominasi. Tindakan manusia di bawah kendali rasionalitas instrumental bersifat mengobjekkan. ALEXANDER AUR 83 Sedangkan rasionalitas komunikatif adalah rasionalitas yang mendasari tindak­ an untuk saling pengertian di antara dua orang subjek atau lebih yang sedang bertukar pikiran untuk mencapai tafsir yang harmonis perihal dunia. Jika tindakan strategis adalah pemanfaatan orang lain demi kepentingan subjek tertentu, maka sebaliknya tindakan komunikatif didasarkan atas perbincangan argumentatif yang bebas, tanpa dominasi, yang bermuara pada kesepakatan bersama. Perbedaan mendasar keduanya adalah tindakan strategis bersifat monologis, sedangkan tindakan komunikatif bersifat dialogis (Habermas, 1996: 2-3). Konstruksi konseptual Habermas me­ ngenai tindakan komunikatif tersebut tidak terlepas dari konsepnya tentang rasionalisasi dalam bidang komunikasi (interaksi). Baginya, suatu tindakan komunikatif bersifat rasional apabila dalam dan melalui tindakan itu, manusia mampu mengura­ ngi berbagai penindasan dan mengura­ngi kekerasan pada tingkat pribadi-pribadi yang menjadi partisipan dalam komunikasi, sehingga pribadi-pribadi bisa mengembangkan diri. Dengan kata lain, melalui tindakan komunikatif rasional, setiap pribadi terbebaskan dari berbagai penindasan dan kekerasan. Rasionalisasi yang sesungguhnya bagi Habermas adalah rasionalisasi humanis, dan hal itu seharusnya ditem- Teori Kritis lahir di tengah ketegangan dialektis di antara ilmu pengetahuan khususnya sosiologi dan filsafat. Teori Kritis tidak berhenti pada fakta objektif yang sebagaimana yang diagung-agungkan oleh positivisme logis. Realitas sosial bagi Teori Kritis merupakan fakta sosiologis yang di dalamnya terdapat aspek-aspek transendental yang melampaui data empiris. Dengan demikian, Teori Kritis dapat melakukan dua macam kritik yaitu kritik transendental dan kritik imanen. Kritik transendental berupaya menemukan syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan dalam diri subjek. Kritik imanen merupakan upaya menemukan kondisi-kondisi sosio-historis dalam konteks tertentu yang berpengaruh terhadap pengetahuan manusia. Dalam bingkai dua kritik itu, Teori Kritis merupakan Kritik Ideologi. 5 Generasi pertama Teori Kritis memahami praksis (praxis) sebagai kerja (Arbeit). Konsep praksis merupakan sebuah kategori dalam filsafat ilmu pengetahuan, yang bermaksud menunjukkan hubungan antara teori dan praktik. Praktik merupakan perwujudan konkrit dari teori. Filsafat ilmu pengetahuan bermaksud menunjukkan hubungan antara rasionalitas dalam teori dan rasionalitas dalam praktik. Berbeda dengan generasi pertama Teori Kritis, Habermas membedakan antara kerja dengan interaksi atau komunikasi. Kerja dan komunikasi merupakan dua dimensi dari praksis. 4 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 83 4/24/2014 10:01:20 AM 84 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama puh melalui rasio komunikatif (Hardiman, 1990: 98). Humanisasi dicapai bukan melalui positivikasi rasio manusia seperti yang dilakukan positivisme melainkan melalui tindakan komunikatif (Deflem, 1996: 2-3).6 Bagi Habermas, rasio modern tetap mempunyai dimensi emansipatif serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, ia mengajukan konsep mengenai rasio prosedural. Rasio ini tidak terpisah dari rasio komunikatif. Melalui rasio prosedural, berbagai keputusan atau kesepakatan yang merupakan buah dari proses-proses rasional mendapat kesahihannya. Dalam rasio prosedural, prosedur diakui secara bersama-sama oleh semua orang yang terlibat aktif dalam proses-proses rasional (intersubjektif).7 Rasio prosedural inilah yang kelak menjadi “jiwa” dari demokrasi deliberatif. Relasi antarmanusia menurut Habermas bersifat rasional karena semua orang yang terlibat dalam relasi itu bermaksud agar terjadi kesalingpahaman certa bermuara pada kesepakatan bersama. Artinya, setiap tindakan yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama merupakan tindakan komunikatif. Dengan demikian, tindakan komunikatif mengandung rasio komunikatif. Kesalingpahaman dan kesepakatan sebagai tujuan dari tindakan komunikatif merupakan daya kerja dari rasio komunikatif. Tujuan tindakan komunikatif bisa tercapai jika rasio komunikatif bekerja dalam tindakan komunikatif. Habermas menekankan bahwa tindak­ an komunikatif yang rasional harus bebas dari tekanan, paksaan, dan dominasi VOL II, 2014 sehingga semua orang yang terlibat aktif di dalam komunikasi menerima kesepakatan yang dihasilkannya. Dengan demikian, kesepakatan itu memiliki legitimasi kebenaran, kejujuran, dan ketepatan. Komunikasi yang demikian terjadi dalam dunia-kehidupan (Lebenswelt). Dalam dunia-kehidupan, hal-hal yang dianggap benar diterima begitu saja tanpa dipersoalkan. Selain itu, dalam dunia-kehidupan, anggota-anggota masyarakat sama-sama membangun dan mengedepankan solidaritas. Apakah hubungan antara dunia-kehidupan dan tindakan komunikatif? Bagi Habermas, mengikuti analisis Budi Hardiman, dunia-kehidupan memungkinkan terjadinya tindakan komunikatif. Duniakehidupan menjadi basis bersama bagi para pelaku tindakan komunikatif. Oleh karenanya, dunia-kehidupan membantu pencapaian sebuah kesepakatan (konsensus). Dalam perkembangan lebih lanjut, masyarakat berkembang menjadi modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang tersistematisasi. Masyarakat yang tersistematisasi itu tampak dalam sistem-sistem yang ada dalam masyarakat modern, yakni sistem pasar (uang) dan sistem kekuasaan negara. Habermas mengeksplisitkan perbedaan dunia-kehidupan dan sistem dengan istilah “solidaritas” untuk duniakehidupan (Lebenswelt) dan “sistem” untuk “uang” dan “kuasa”. Solidaritas, uang, dan kuasa adalah tiga komponen penyangga integritas masyarakat modern. Yang ideal bagi Habermas adalah keseimbangan antara sistem dan dunia-kehidupan. Hubungan antara dunia kehidupan, pasar, dan negara Habermas juga mencatat bahwa untuk menghindari salah paham (misunderstanding) dalam tindakan komunikatif, dan untuk memperoleh pemahaman bersama, maka para partisipan komunikasi tidak bisa hanya mengandalkan tindakan berbicara (speech-act) melainkan juga harus memerhatikan bentuk-bentuk tindakan lain yang tidak linguistik seperti tanda-tanda dan simbol-simbol. 7 Penjelasan tentang pengertian rasio prosedural sangat menarik disampaikan oleh F. Budi Hardiman dengan contoh di bidang peradilan yang dipaparkan dalam Hardiman, 2009: 32-33. 6 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 84 4/24/2014 10:01:20 AM Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama ALEXANDER AUR 85 berlangsung secara seimbang (Hardiman, tuan prinsip D mengenai klaim kesahihan 2009: 38-41). universalisasi norma. 2.1. Etika diskursus Dalam bingkai opitimismenya pada pro­ yek modernitas yang segera dituntaskan, Habermas berusaha membangun sebuah masyarakat yang komunikatif (masyarakat kosmopolit). Masyarakat yang demikian adalah tujuan universal masyarakat. Oleh karena itu, Habermas tidak melepaskan konsepnya dari fakta pluralisme dalam masyarakat modern. Untuk memperkuat masyarakat komunikatif, Habermas meng­ ajukan proposal berupa etika diskursus untuk menata kembali norma-norma hidup bersama (Stephen, 1995: 12).8 Etika diskursus (Regh, 1994; 161-166), menuntut dua prinsip pokok yang harus diberlakukan agar norma sungguh-sungguh bersifat moral. Pertama, norma harus dapat diterima oleh semua orang atau berlaku umum. Prinsip ini disebut prinsip universalisasi (prinsip U). “Semua pihak yang (mungkin akan) terkena dampak kepatuhan hukum atas norma dapat menerima konsekuensi dan efek sampingnya, yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan setiap orang,” demikian ketentuan prinsip U mengenai kesahihan sebuah norma. Kedua, kepastian akan universalisasi norma itu ditempuh melalui diskursus (prinsip D). “Norma-norma hanya dapat diklaim sebagai sahih kalau mendapat persetujuan dari semua peserta yang kemungkinan terkena dampak dari norma itu dalam sebuah diskursus praktis,” demikian keten- 2.2. Negara Hukum Demokratis Habermas melihat bahwa ciri dasar kehidup­ an bersama manusia adalah komunikasi. Oleh karena itu, demokrasi harus menjadi medium bagi perwujudan berbagai struktur komunikasi dalam negara hukum modern. Dengan demikian, negara hukum dapat mendekati asas-asas normatif dari dalam dirinya sendiri.9 Model demokrasi yang tepat untuk itu adalah demokrasi deliberatif. Model demokrasi ini sesuai dengan prinsip rasio prosedural dan etika diskursus yang telah dikemukakan di atas. Fokus utama demokrasi deliberatif adalah prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Keputusan-keputusan politis atau kesepakatan-kesepakatan politis yang dicapai harus melalui prosedur-prosedur yang rasional. Dalam prosedur yang rasional, para warga negara atau kelompok-kelompok kecil yang mempunyai kepentingan dalam negara dapat memperjuangkan kepenting­ an-kepentingannya. Berbagai kepentingan warga negara dideliberasi berdasarkan prosedur-prosedur rasional. Melalui pro­ ses deliberasi itulah, sebagian kecil warga negara yang tidak sepakat dengan suara mayoritas, bisa menerima dan mematuhi pendapat-pendapat yang disepakati oleh sebagian besar warga negara sebagai suara mayoritas. Dalam proses deliberasi, semua orang yang terlibat mempunyai kesetaraan sebagai warga negara. Etika diskursus yang diajukan Habermas juga merupakan upayanya untuk mengatasi imperatif kategoris dalam Etika Kant yang lebih menekankan prosedur individual atau etika yang dilakukan secara individual. Habermas meragukan tesis Kant bahwa sebuah norma dapat berlaku secara universal apabila dipastikan oleh suara hati setiap pribadi. Tesis Kant ini sulit diterapkan dalam masyarakat yang pluralistik. 9 Tentang asas-asas normatif itu, dikemudian hari saat berdiskusi dengan Ratzinger, hal itu diungkapkan kembali ketika Habermas menggali akar-akar religius rasio sekular. 8 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 85 4/24/2014 10:01:21 AM 86 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama 3. Agama dalam Negara Hukum Demokratis Di atas, kita sudah melihat alur berpikir Habermas ditinjau dari rasio komunikatif, etika diskursus, sampai demokrasi deliberatif. Pada bagian ini, dipaparkan pemikiran Habermas tentang agama dalam negara hukum demokratis. Ia memulainya de­ ngan pertanyaan: Apakah negara hukum demokratis memiliki akar-akar religius? Bagian ini penting untuk diperhatikan karena terkait dengan posisi agama dalam negara hukum demokratis. Habermas memang mengakui bahwa negara hukum demokratis atau rasio sekuler mempunyai akar religius. Meski demikian, basis negara hukum demokratis tidak kembali bertumpu pada agama. Mengapa? Dalam sebuah diskusi dengan Kardinal Ratzinger, Habermas menggali dan menanggapi secara kritis akar-akar religius rasio sekuler.10 Dalam bingkai teks berjudul ”Prepolitical Foundations of the Constitutional State?” (Habermas, 2008: 101-113; Kleden dan Sunarko, 2010: 1-28), ��������������� Habermas mengemukakan beberapa pokok pemikirannya. Pertama, negara sekuler tidak mendasarkan diri pada berbagai pengandaian kosmologis tertentu sebagaimana diandaikan hukum kodrat. Konsekuensinya, negara sekuler tidak memihak kelompok agama tertentu dengan seluruh sistem nilainya, dan setiap warga negara mempu­nyai kesetaraan dalam memainkan perannya dalam negara hukum demokratis. Dengan mengacu pada pertanyaan kritis yang diajukan Bökenförde tentang seberapa jauh warga masyarakat dapat menyatukan diri dalam negara dengan jaminan kebebasan individu saja tanpa ada ikatan; Habermas me­ ngatakan bahwa proses demokrasilah yang menjadi ikatan yang menyatukan para 10 VOL II, 2014 warga negara. Proses demokrasi menjadi syarat kemungkinan bagi para warga negara untuk memperjuangkan kepentingankepentingannya. Tentunya, demokrasi yang dimaksudkan Habermas pada poin pertama di atas adalah demokrasi deliberatif yang mengacu pada rasio prosedural dan digerakkan oleh rasio komunikatif. Rasio komunikatif yang ada dalam diri warga negara menggerakkan mereka untuk menyatukan diri dalam negara secara bebas dan tanpa tekan­ an, melalui demokrasi deliberatif. Kedua, berdasarkan perspektif kognitif dan motivasi, negara hukum demokratis bisa mencukupi dirinya secara internal. Tetapi, ada faktor eksternal yang merusak jaringan solidaritas para warga negara dan proses demokrasi, yakni pasar (Habermas, 2008: 107-108; Kleden dan Sunarko, 2010: 13-17). Rasio pasar mempunyai cara kerja yang berbeda dengan rasio negara. Pasar mempunyai metode pengelolaan yang berbeda dengan administrasi negara. Rasio pasar menggiring warga ke dalam individu-individu yang menggunakan kebebasan individualnya secara ketat. Bersamaan dengan itu, bidang-bidang yang menjadi wewenang negara hukum demokratis untuk mengaturnya semakin berkurang. Privatisme warga negara kian menguat, sementara proses demokratisasi para warga negara kian melemah. Habermas menyebut fenomena itu sebagai penyimpangan modernisasi. Dalam kondisi seperti ini, negara hukum demokratis mesti melegitimasi dirinya dengan perangkat hukum yang dibuat oleh para warga negara. Gagasan pokok dalam poin kedua tersebut dikemukakan Habermas ketika ia mengulas masalah dunia-kehidupan (Lebenswelt) serta sistem. Jika dalam urai- Diskusi dengan Ratzinger itu berlangsung di Katholiche Akademie München, Jerman tanggal 19 Januari 2004. 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 86 4/24/2014 10:01:21 AM Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama annya tentang dunia-kehidupan dan sistem, Habermas mengatakan bahwa sistem – yak­ni pasar dan negara – mengoloni dunia-kehidupan, maka dewasa ini rasio pasar justru mengoloni dunia-kehidupan serta negara secara sekaligus. Dalam situa­ si kolonisasi rasio pasar – yang merupakan bentuk penyimpangan dari modernitas – Habermas mengatakan bahwa para warga negara harus mengatasinya dengan memaksimalkan rasio komunikatif melalui mekanisme rasio prosedural.11 Setiap usaha para warga negara untuk mencapai kesepakatan dalam bidang tertentu untuk stabilitas kehidupan bersama, para warga harus mematuhi prosedur-prosedur tertentu yang digunakan untuk mencapai kesepakatan tertentu yang dimaksud. Prosedurprosedur yang berlaku merupakan produk dari rasio. Prosedur-prosedur rasional yang tersedia menjadi medium bagi para warga untuk berdeliberasi. Proses deliberasi me­ lalui rasio prosedural inilah yang disebut Habermas sebagai tindakan komunikatif. Hal itu berarti, rasionalitas dari sebuah kesepakatan merupakan pencapaian bersama dari para warga yang terlibat dalam proses deliberasi. Ketiga, menjawab keraguan yang diajukan oleh Bökenförde bahwa apakah negara hukum bisa mencukupi dirinya dengan asas-asas normatif dalam dirinya, Habermas mengatakan bahwa dari perspektif kognitif hukum yang telah mengalami positivisasi tetap membutuhkan pandangan religius dan metafisik untuk memastikan secara kognitif prinsip-prinsip etis hukum dalam negara hukum demokratis. Sedang- ALEXANDER AUR 87 kan dari perspektif motivasi, Habermas mengharapkan bahwa para warga negara menggunakan hak-haknya secara aktif dalam proses pembuatan hukum untuk kepentingan komunal sekaligus kepentingan bersama (Habermas, 2008: 104-105; Kleden dan Sunarko, 2010: 7, 9). Pada poin ini, Habermas mengakui bahwa negara hukum demokratis tetap membutuhkan agama atau ”kekuatan pemandu” (sustaining power) sebagai pemasti kognitif asas-asas normatif dalam negara hukum demokratis (negara sekuler). Keberadaan agama atau ”kekuatan pemandu” bukan berarti negara mengganti asas-asas normatif dari dirinya dengan asas-asas normatif dari agama atau ”kekuatan pemandu” lain. Sebaliknya, Habermas hendak mengatakan bahwa agama – dengan asasasas normatif metafisik – sebagai bagian dari dunia-kehidupan juga mempunyai kesempatan sama untuk berpartisipasi dalam negara hukum demokratis. Partisipasi agama merupakan bentuk kongkret dari perspektif motivasi. Tentunya, model partisipasi tetap dalam bingkai demokrasi deliberatif yang mengacu pada rasio prosedural. Partisipasi agama dalam bingkai rasio prosedural itulah sekaligus merupakan pemasti kognitif rasio prosedural. Dengan kata lain, jika agama tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam negara hukum demokratis, maka demokrasi deliberatif kurang (tidak) memiliki rasionalitas. Jika agama didomestifikasikan dan tidak punya kesempatan untuk berdeliberasi di ruang publik, maka rasio prosedural mengalami F. Budi Hardiman menjelaskan gagasan Habermas tentang rasio prosedural dengan mengambil contoh di bidang hukum yakni peradilan. Proses pengadilan hanya mungkin dan dapat terlaksana bila ada ide tentang keadilan. Ide keadilan adalah unsur konstitutif dari pengadilan. Ide itu juga bersifat regulatif karena berlaku sebagai prosedur untuk memeriksa apakah proses pengadilan berlangsung adil atau tidak. Hal yang penting dalam rasio prosedural adalah prosedur yang diakui secara intersubjektif. Lewat prosedur itulah produk-produk dari setiap proses rasional memperoleh kesahihannya. Dari situ tampak bahwa sifat rasional merupakan hasil pencapaian bersama. Sifat rasional dari klaim rasio tertentu dicapai secara komunikatif, melalui pemahaman timbal-balik antar subjek. 11 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 87 4/24/2014 10:01:21 AM 88 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama defisit rasionalitas. Demokrasi deliberatif memiliki kepastian rasional apabila agama dilibatkan dalam debat-debat di ruang publik politis. Keempat, Habermas memberi catatan kritis tentang masalah hermeneutika teksteks agama seperti tentang kesalahan dan keselamatan. Hal-hal itu ditafsirkan dan dihayati secara hermeneutik selama bertahun-tahun. Selama teks-teks agama itu tidak mengalami distorsi dalam penafsiran dan tidak jatuh dalam dogmatisme dan pemaksaan suara hati, maka rasio sekuler bisa belajar juga dari agama, atau masyarakat sekuler dan masyarakat religius bisa saling belajar (Habermas, 2008: 108-113; Kleden dan Sunarko, 2010: 20-28). 3.1.Dari Agama Mitis ke Agama Rasional Habermas mengakui bahwa setiap agama pada hakikatnya adalah ”pandangan hidup” atau ”comprehensive doctrine” (doktrin yang lengkap) (Habermas, 2008: 111; Kleden dan Sunarko, 2010: 24). Dengan pendasaran-pendasaran mitis dan metafisik, agama juga memberikan elan vital kepada para penganutnya (orang beriman) yang hidup di tengah-tengah masyarakat modern. Bahkan, etika substansial yang dianut banyak orang pun berakar pada tradisi agama-agama. Masyarakat modern yang pluralistik itu sendiri terdiri atas orangorang beriman serta orang-orang tidak beriman (Adam, 2006: 1). Masyarakat modern berada dalam dua area besar yakni duniakehidupan dan sistem yang di dalamnya ada pasar dan negara. Ada masyarakat (individu atau kelompok) yang menjadi bagian integral dari dunia-kehidupan, pasar, dan negara secara serentak. Ada masyarakat (individu atau kelompok) yang menjadi bagian dari negara dan pasar saja. Masyarakat modern hidup dalam sebuah ruang publik (public sphere) yang sama. Ruang publik itu sendiri bersifat politis ka- 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 88 VOL II, 2014 rena dihuni oleh masyarakat modern yang pluralistik dengan segala kepentingannya. Dalam kondisi masyarakat modern dan ruang publik yang demikian, agama meng­ hadapi tantangan yang serius. Habermas dengan tegas mengatakan bahwa ruang publik politis atau negara hukum demokratis tidak bisa menjadi ”religius” atau ”ditradisikan” berdasarkan doktrin lengkap agama apapun (��������������������������������� Adam, 2006: 2)������������������� . Tampak jelas pendirian Habermas bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Agama mempunyai domain kerja yang sangat berbeda dengan negara. Meski demikian, agama tidak boleh didomestifikasikan karena bertentangan dengan hakikat demokrasi. Mengacu pada gambaran idealnya tentang keseimbangan antara dunia-kehidup­ an, negara, dan pasar, Habermas menantang – agama yang olehnya dikategorikan sebagai bagian dari dunia-kehidupan – untuk menunjukkan eksistensinya dalam ruang publik politis atau negara hukum demokratis. Hal itu serius bagi agama karena di satu sisi ajaran-ajaran agama bersifat mitis dan metafisik, di sisi lain, ruang publik bersifat rasional dan post-metafisik. Habermas secara tegas berargumen bahwa hanya sebuah forum sekulerlah yang dapat secara memadai menjadi pemandu atau penata bagi perbedaan antara ruang metafisik dengan ruang post-metafisik. Forum sekuler yang dimaksud adalah negara hukum demokratis atau ruang publik politis. Negara hukum demokratis menjadi forum yang di dalamnya semua partisipan berdeliberasi sekaligus berargumentasi sesuai dengan rasio prosedural untuk mencapai kesepakatan bersama yang adalah tujuan tindakan komunikatif. Dalam proses deliberasi, pengandaian-pengandaian metafisik agama diuji secara rasional atau dengan cara berpikir post-metafisik. Artinya, agama harus mentransformasi diri dari agama mitis (religious-metaphysical) ke 4/24/2014 10:01:21 AM Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama agama rasional (religious-post-metaphysical) (Adam, 2006: 125-126). Melalui pengujian dalam proses deliberasi, dan dalam koridor etika diskursus, agama mitis bisa menjadi agama rasional. Jika berhasil menjadi agama rasional, maka etika substansial agama-agama bisa memberi warna dalam etika universal. Meski demikian, Habermas tetap tidak mengizinkan agama campur-tangan secara langsung dalam negara. Agama bisa masuk ke dalam negara setelah melewati institutional translation proviso. Institusi ini semacam dewan yang bertugas menterjemahkan bahasa (ajaran-ajaran) agama yang bersifat mitis-religius dan partikular ke dalam bahasa universal yang bersifat sekuler. Melalui hal itu, pengandaian-pengandaian metafisik agama diuji oleh rasio post-metafisik dan bahasa agama diterjemahkan ke dalam bahasa rasio sekuler. Dalam konteks ini, warga negara yang tidak beriman bisa membantu dalam proses alih bahasa kitab suci. Jika mekanisme itu dicapai, maka agama bisa bermanfaat bagi demokrasi, dan negara hukum demokratis (Habermas, 2008: 131-132). Dengan demikian, antara warga ber­ agama dengan warga sekuler dalam masyarakat post-sekuler dapat saling belajar satu sama lain. Apalagi, warga negara beriman didorong untuk mengenakan cara berpikir (episteme) post-metafisik di tengah pluralitas agama. Warga negara beriman juga harus tunduk certa mengakui rasio sekuler yang menjadi basis legitimasi untuk negara hukum demokratis (Habermas, 2008: 138139). ALEXANDER AUR 89 4. Hubungan Negara dengan Agama di Indonesia: Melacak Deliberasi Politik Berbasis Agama Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, hu­ bungan antara negara dengan agama me­ ngalami pasang-surut (Parakitri T. Simbolon dalam Kristanto dan Arsuka (ed.), 2002: 430).12 Hubungan yang demikian mengindikasikan bahwa deliberasi politik antara negara dengan agama pun mengalami pasang-surut. Situasi pasang-surut deli­berasi politik berbasis agama dengan negara itu bisa kita telusuri dari beberapa peristiwa historis berikut ini. 4.1 Penolakan Piagam Jakarta: Islam menemukan “Situasi Epistemik” Pluralitas Persoalan hubungan negara dan agama sungguh disadari oleh para pendiri bangsa sebagai hal yang krusial. Oleh karena itu, dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuklah Panitia Sembilan yang di­ pimpin oleh Soekarno untuk membahas hal itu. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan13 berhasil merumuskan pembukaan UUD. Oleh Muhammad Yamin, pembukaan UUD 1945 itu disebut Piagam Jakarta karena dalam sila pertama Pancasila berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Menjelang pengesahan UUD 1945, atas prakarsa Muhammad Hatta, frasa “De­ ngan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dari sila pertama Untuk kepentingan tulisan ini, kurun waktu yang dijadikan sebagai acuan adalah setelah Indonesia menjadi sebuah merdeka sampai sekarang. Meski demikian, sejarah hubungan agama dan negara bisa ditelusuri sejak zaman kerajaan-kerajaan, zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Sejarah mengenai hal itu dapat dibaca dalam Parakitri T. Simbolon, “Pasang-surut Hubungan Agama dan Negara di Indonesia” dalam Kristanto dan Arsuka, 2002: 429-442. 13 Panitia Sembilan terdiri dari Soekarno, Achmad Soebardjo, Abdul Kahar Muzakkir, Alex Andries Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Mohammad Hatta, Abdul Wahid Hasyim, Agus Salim, Muhammad Yamin. 12 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 89 4/24/2014 10:01:21 AM 90 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama Pancasila dihapus. Penghapusan itu di­ setujui oleh empat tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Hasan. Hatta memprakarsa penghapusan frasa tersebut setelah utusan Angkatan Laut Jepang (Kaigun) menemui Hatta untuk menyampaikan keberatan dari wakil Protestan serta Katolik dari Indonesia Timur dengan frasa tersebut. Bila frasa itu tetap dipertahankan menjadi bagian dari sila pertama Pancasila, maka UUD 1945 mengandung diskriminasi. Konsekuensi lebih lanjut adalah Indonesia Timur akan keluar dari Republik Indonesia (Soeprapto, 2013: 8). Hatta berargumen bahwa UUD adalah pokok daripada pokok, sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia de­ ngan tanpa kecuali. Jalan pikiran Hatta itu disetujui oleh keempat tokoh Islam dengan argumentasi bahwa dengan penghapusan frasa tersebut, sama sekali tidak melenyapkan “semangat Piagam Jakarta” (Parakitri T. Simbolon dalam Kristanto dan Arsuka (ed.), 2002: 436). Dari argumen keempat tokoh Islam yang setuju dengan argumen Hatta, menunjukkan bahwa unsur diskriminatif tidak terletak pada makna atau isi dari frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Unsur diskriminatif terletak pada bahasa formal. Bila bahasa formal yang terwujud melalui frasa itu dimasukkan menjadi bahasa formal UUD, maka tampak jelas unsur diskriminatifnya. Karena UUD merupakan hukum umum, maka bahasa formal dalam hukum umum harus mencerminkan keumumannya. Sedangkan bahasa formal yang tampak jelas dalam frasa tersebut 14 VOL II, 2014 menunjukkan kekhususan. Atas dasar itu, keumuman bahasa formal yang diutamakan dalam UUD, yang tampak dalam rumusan formal sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam ruang partikular Islam, syariat Islam merupakan unsur konstitutif agama Islam. Islam dihayati sebagai sebuah agama oleh pemeluk-pemeluknya karena salah satu unsur konstitutifnya itu. Kewajiban menjalankan syariat merupakan sebuah imperatif etis untuk berbuat baik dalam konstelasi hidup beriman orang Islam. Mengenai hal itu, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa saat diturunkannya al-Qur’ân kepada Rasullulah SAW, Tuhan berpesan bahwa dalam setiap kelompok dalam Komunitas Madina, Allah telah menetapkan sistem hukum (syir’ah, syarî’ah) dan cara hidup (minhâj) agar setiap orang dalam komunitas keagamaannya masingmasing berusaha terus-menerus berbuat baik (Madjid, 1992: 312-324).14 Ada dua hal yang muncul dari kete­ rang­an Nurcholish Madjid tersebut. Pertama, cakupan hukum agama adalah partikular. Dari sisi formal, hukum agama – dari setiap agama – hanya berlaku dalam agama tertentu dan bagi penganut agama tertentu itu. Dalam konteks Piagam Jakarta, penghapusan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya”, menunjukkan bahwa hukum syariat bersifat partikular dan hanya berlaku bagi penganut Islam. Penghapusan frasa itu, menunjukkan juga bahwa partikularitas hukum agama, tidak bisa begitu saja diuniversalkan melalui rumusan formal produk hukum (undang-undang) yang Nurcholish Madjid menempatkan penjelasannya tentang konsep “hukum” dalam al-Qur’ân pada konteks historis yakni Madînah. Pada zaman Rasullulah s.a.w., masyarakat Madînah bukan masyarakat homogen melainkan heterogen. Selain ada komunitas Islam, juga ada komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, dan komunitas pagan. Terhadap komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasullulah SAW mengatakan bahwa Allah pun menurunkan hukum bagi komunitas-komunitas itu, dan setiap anggota komunitas harus menjalankan hukum yang diturunkanNya itu. 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 90 4/24/2014 10:01:21 AM Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama berlaku umum. Tentu, Tentu, ketidakbisaan itu sama sekali tidak membatasi dampak etis dari partikularitas hukum agama. Kedua, dampak etis hukum agama. Bagi orang Islam, hukum (syir’ah, syarî’ah) merupakan sarana untuk berbuat baik dan menghasilkan kebaikan bagi hidup bersama. Hukum syariah yang bersifat partikular itu, dalam pengahayatan konkritnya, mendatangkan dampak etis berupa kebaikan. Dampak etis itu bukan saja bagi hidup orang Islam tetapi juga bagi orang lain di luar Islam. Rumusan yang jelas mengenai hal itu adalah “Islam sebagai rahmatan lil âlamin. Rumusan itu menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam bersifat partikular, tetapi dampak etis dari penghayatan (pelaksanaan) hukum Islam itu bersifat universal (publik). Dan dampak etis inilah yang disoroti oleh keempat tokoh Islam yang sepakat dengan argumen Hatta yang menekankan dimensi universal dari UUD 1945. Dalam perspektif deliberasi Habermas, argumen Hatta dan keempat tokoh Islam mengenai penghapusan frasa yang bersifat partikular tersebut, menunjukkan bahwa agama Islam berhasil menemukan dan menetapkan “situasi epistemik” di hadapan agama lain yang dianut oleh para warga negara Indonesia bagian timur. Hatta dan keempat tokoh Islam berhasil merelati­ visasikan posisi hukum (syariah) Islam dalam ruang publik (negara Indonesia) tanpa harus merelativisasikan syariat sebagai inti dogmatis Islam. Bahkan, bila dipandang dari perspektif institusional translation proviso, Hatta dan keempat tokoh Islam berhasil mentransformasikan Islam yang mitis dan partikular menjadi Islam yang rasional dan universal. Islam yang mitis dan partikular tercermin dalam inti dogmatisnya, yakni menjalankan hukum syariah. Sedang­kan 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 91 ALEXANDER AUR 91 Islam yang rasional dan universal tercermin dalam rahmatan lil âlamin. Keberhasilan Islam menemukan dan menetapkan “situasi epistemik” tersebut tidak semata-mata bersifat politis seperti yang dinilai oleh Paraktri T. Simbolon. Ia menilai bahwa penghapusan frasa tersebut menunjukkan bahwa kesatuan dan persatuan nasional menjadi dasar pola hubung­ an antara agama dengan negara RI. Pola itu bersifat politis sekaligus negatif karena penghapusan itu menampakkan penolakan terhadap hubungan resmi antara agama Islam dengan kekuasaan negara. Penolakan akan bersifat positif bila dilanjutkan de­ ngan menetapkan pola lain sebagai penggantinya (Parakitri T. Simbolon dalam Kristanto dan Arsuka (ed.), 2002: 436). Keberhasilan Islam tersebut bersifat politis sekaligus filosofis. Dalam konteks menetapkan sebuah hukum dasar – UUD 1945 – bagi negara RI yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, sifat politis memang tak terhindarkan. Keputusan Hatta dan keempat tokoh Islam, dan selanjutkan diafirmasi oleh para anggota sidang BPUPKI, memang merupakan keputusan dan kesepakatan politis. Keputusan dan kesepakatan itu juga mempunyai dasar filosofis yang terletak pada dimensi universal (dimensi publik) yang merupakan aspek konstitutif dari UUD 1945. Dimensi universal inilah yang menjadi dasar pemikiran Hatta untuk memprakarsa penghapusan frasa tentang syariah Islam dari sila pertama Pancasila. Keputusan dan kesepakatan itu juga bukan merupakan penolakan terhadap hubungan resmi antara agama – secara khusus Islam – dengan kekuasaan negara. Agama-agama tetap dimungkinkan untuk mempunyai hubungan yang resmi dengan kekuasaan negara, melalui pembentukan 4/24/2014 10:01:21 AM 92 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama partai politik-partai politik, dan berbagai organisasi massa berbasis agama.15 Melalui partai politik serta organisasi massa berbasis agama, agama-agama mempunyai kemungkinan terlibat aktif dalam kekuasaan negara. Keterlibatan aktif tidak berarti memindahkan begitu saja hukum agama menjadi hukum positif negara, melainkan harus melalui proses pengujian atas hukum agama-agama yang akan diintegrasikan ke dalam hukum positif negara. Pengujian itu berdasarkan nalar sekuler yang terepresentasi melalui UUD 1945. Fakta mengenai berbagai partai politik berideologi agama serta organisasi massa berasaskan agama menunjukkan bahwa politik berbasis agama memang dimungkinkan di Indonesia. Di atas ideologi Pancasila, setiap warga negara dari latar belakang agama apapun dimungkinkan untuk beraktivitas politik dengan semangat agama. Kemungkinan itu semakin luas bila kita melihat pada imperatif-imperatif agama yang berkaitan dengan urusanurusan publik. Agama-agama mempunyai imperatif moral yang menjadi landasan etis untuk menyikapi atau merespon persoalanpersoalan publik. Warga masyarakat di dalam negara hukum demokratis yang dapat berpartisipasi dalam ruang publik tidak hanya 15 VOL II, 2014 dari satu agama, melainkan dari berbagai agama yang berbeda dan ada pula yang tidak beragama. Itulah fakta pluralitas dalam negara hukum demokratis. Itulah “situasi epistemik” masyarakat modern yang plural. Mengingat bahwa pluralitas merupa­kan keniscayaan demokrasi dan modernitas, maka agama yang berpolitik dan bertindak politis harus menetapkan “situasi epistemik”, yakni harus merelativisasikan posisinya di hadapan pluralitas warga dan agama-agama. Tentu saja relativisasi posisi tidak dengan sendirinya mengakibatkan relativisasi inti dogmatisnya (Borradori, 2005: 105). Dalam merelativisasi posisi, agama tidak mengabaikan situasi epistemik masyarakat plural, dan tidak menuntut penerapan ortodoksinya secara ketat dalam masyarakat plural. Dalam konteks Indonesia, meskipun ideologi Pancasila memungkinkan agama berpolitik dan bertindak politis, tetapi tidak berarti bahwa agama mengabaikan situasi epistemik masyarakat plural. Sebaliknya, agama seharusnya menetapkan “situasi epistemik” supaya sinkron dengan situasi epistemik masyarakat plural. Agama yang mengabaikan situasi epistemik masyarakat plural dan bernafsu mengatur masyarakat plural dengan inti dogmatisnya (hukum agama), maka agama itu akan menjadi Pada era Orde Lama, partai politik-partai politik berideologi agama Islam antara lain, Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Masyumi Indonesia (MI), Partai Syariah Islam Indonesia (PSII), dan Perti. Sedangkan partai politik yang berideologi Katolik dan Protestan adalah Partai Katolik Indonesia dan Partai Kristen Indonesia. Pada masa Orde Baru, partai politik berbasis agama hanya 1: Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada masa reformasi, beberapa partai politik baru berbasis agama tampil sebagai peserta pemilu, antara lain PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa), Partai Keadilan Sejahtera, PBB (Partai Bulan Bintang), dan PDS (Partai Damai Sejahtera). Agama juga tampil dalam bentuk organisasi-organisasi massa, baik yang berbasis massa agama secara umum maupun berbasis massa kampus. Organisasi massa kampus, antara lain HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia). Organisasi-organisasi massa agama umum antara lain, PK (Pemuda Katolik), ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbuth Tahrir Indonesia) dsb.. Berbagai organisasi massa berbasis agama tersebut tampil ke publik, dan merespon masalah-masalah publik. Berbasis semangat keagamaannya masing-masing, setiap organisasi massa itu terdorong untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup berbangsa dan bernegara. Meski demikian, dorongan itu mesti tetap sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 92 4/24/2014 10:01:21 AM Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama horor sekaligus teror bagi demokrasi, kemanusiaan maupun pluralitas. 4.2 Gerakan Anti Pancasila: Ketiadaan Deliberasi Politik Agama Pada masa-masa awal kekuasaan Orde Baru, roda pemerintahan yang dikendalikan oleh Soeharto mempersempit ruang politik bagi agama untuk berdeliberasi dalam kancah perpolitikan Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan Orde Baru adalah memfusikan beberapa partai politik berbasis agama. Partai politik-partai politik berbasis agama Islam seperti NU, PSII, dan Perti difusikan menjadi PPP. Partai politik yang berbasis agama di luar agama Islam, seperti Partai Katolik dan Partindo difusikan ke dalam partai nasionalis PDI. Orde Baru menerapkan depolitisasi dan deideologisasi agama sebagai rekayasa politik untuk melemahkan peran politik agama. Kelompok agama yang paling merasakan dampak dari penghilangan delibe­ rasi politik berbasis agama adalah Islam. Selama kurang lebih 25 tahun peran politik agama Islam dipangkas. Akses Islam ke lingkaran kekuasaan politik negara ditutup. Strategi itu dipertajam dengan kebijakan politik berbunyi Pancasila sebagai asas tunggal dalam berpolitik dan aktivitas organisasi. Kebijakan itu tertuang dalam UU No. 3/1985 yang merupakan perubahan atas UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta UU No. 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Melalui kebijakan itu, Orde Baru sekaligus menyatakan bahwa Islam tidak boleh menjadi asas organisasi sosial-politik. Bahkan, Islam politik menjadi sasaran teropong kecurigaan ideologis Orde Baru. Aktivis Islam politik dicurigai sebagai anti terhadap Pancasila (Hasani dan Naipospos (ed.), 2012: 28-29; Magnis-Suseno dalam Kristiyanto (ed.), 2010: 304). 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 93 ALEXANDER AUR 93 Kebijakan politik orde baru tersebut mendatangkan tanggapan serius dari Islam politik. Pada mulanya, hampir semua partai politik dan organisasi-organisasi Islam menentang kebijakan itu. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah menerima kebijakan tersebut. Seiring de­ ngan itu, gerakan radikal untuk menentang Pancasila sebagai asas tunggal pun terus berlangsung. Dua tokoh Islam yang menolak tegas Pancasila sebagai asas tunggal adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir. Organisasi yang menolak Pancasila sebagai asas organisasi adalah PII (Pelajar Islam Indonesia). PII dibubarkan Orde Baru pada tahun 1988. Selain itu, banyak pula cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga dibubarkan Orde Baru. Pembubaran cabang-cabang HMI ini, belakang­ an terkenal dengan istilah HMI (MPO). Dalam konstelasi filsafat politik Habermas, gerakan menentang Pancasila sebagai asas tunggal dari beberapa tokoh dan organisasi Islam lebih merupakan cerminan dari dua problem. Pertama, ketiadaan deliberasi politik bagi agama dalam negara. Dengan mengharuskan Pancasila sebagai ideologi bagi partai politik dan ormas yang berasaskan agama, negara (pemerintah Orde Baru) telah menutup pintu masuk sekaligus tidak menyediakan akses bagi agama untuk berdeliberasi secara politik. Pemerintah Orde Baru tidak menyediakan prosedur-prosedur rasional – yang merupakan cermin dari negara hukum demokratis – bagi agama untuk memperjuangkan kepentingannya. Problem kedua ini merupakan akibat dari problem pertama. De­ ngan tidak disediakan prosedur-prosedur rasional oleh negara, maka tidak ada pula kemungkinan bagi agama untuk melakukan translasi bahasa agama berdasarkan prosedur-prosedur rasional yang dianut 4/24/2014 10:01:21 AM 94 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama oleh negara hukum demokratis. Tiadanya kemungkinan bagi agama untuk mentranslasikan bahasa agama itu membuat agama juga tidak dapat menyumbangkan nalar metafisiknya dalam menguatkan negara hukum demokratis. Sebuah negara disebut negara hukum demokratis apabila negara itu (baca: peme­ rintah) membuka kemungkinan bagi agama untuk melakukan translasi doktrin-doktrin metafisiknya ke dalam bahasa universal dan sekuler. Doktrin-doktrin metafisik agama harus diuji melalui proses deliberasi yang sesuai dengan prosedur-prosedur rasional dalam negara hukum demokratis. Jika berhasil melewati proses deliberasi itu, maka doktrin-doktrin metafisik agama menjadi pemasti kognitif prinsip-prinsip etis negara hukum demokratis. Dengan demikian, gerakan anti Pancasila dari seke­ lompok orang Islam merupakan cermin kegagalan pemerintah Orde Baru dalam menyediakan kemungkinan bagi agama untuk berdeliberasi politik dan mentranslasikan bahasa agama. 4.3 Radikalisme dan Terorisme Agama: Respon Ekstrim Agama terhadap Demokrasi Pasca keruntuhan rezim pemerintahan Orde Baru, gerakan radikal agama (Islam) dan terorisme berwajah agama yang dilakukan oleh sekelompok orang Islam semakin marak. Front Pembela Islam (FPI) dan Jamaah Islamiyah (JI) merupakan dua contoh dari sekian banyak kelompok yang berkarakter radikal dan teroristik (Hasani dan Naipospos (ed.), 2012: 37). Sebuah gerakan disebut radikalistik dan teroristik karena berciri menggunakan kekerasan, bom, organisasinya bersifat tertutup, dan menyerang simbol-simbol negara (Hasani dan Naipospos (ed.), 2012: 42). Pada bagian akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute terhadap 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 94 VOL II, 2014 relasi dan transformasi organisasi radikal di Jawa Tengah dan Yogyakarta, terdapat lampiran tentang 10 (sepuluh) dosa demokrasi menurut kelompok radikal dan teroris agama (Hasani dan Naipospos (ed.), 2012: 317-320). Bagi kelompok radikal dan teroris, demokrasi memiliki beberapa cacat antara lain, demokrasi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai akidah, demokrasi tidak membedakan antara orang beriman dengan orang tak beriman, dan dalam demokrasi, partai politik memanfaatkan sarana dan tindakan religius untuk kepen­ tingan partai politik. Bagi kelompok radikal dan teroris agama, sistem demokrasi harus dianulir dan diganti dengan sistem khilafah Islam. Inilah yang oleh Habermas disebut sebagai “ortodoksi yang mengarah kepada fundamentalisme.” Ortodoksi semacam itu memang secara sengaja (sadar) mengabaikan situasi epistemik masyarakat plural, yang menjadi ciri khas demokrasi. Bahkan, de­ ngan cara kekerasan kelompok radikal dan teroris mewajibkan penerimaan ortodoksi itu secara politis. Berhadapan dengan fenomena itu, negara hukum demokratis ditantang untuk meredefinisi demokrasi dan mereformulasi prosedur-prosedur rasional, supaya negara hukum demokratis tidak terjebak dalam praktik-praktik yang mengatasnamakan demokrasi, tetapi sesungguhnya merupakan penyimpangan dari demokrasi. Penyimpangan demokrasi yang paling vulgar dan kentara adalah kolonisasi rasio pasar atas negara hukum demokratis dan dunia-kehidupan. Rasio pasar yang berwatak instrumental menjadi warna dominan dalam praktik-praktik politik dan agama. Demokrasi transaksional tampil secara kongkret dalam ucapan para politikus yang fasih menggunakan istilah-istilah seperti “suara terbanyak”, “aset politik”, “ongkos politik”, dan sebagainya. Istilah- 4/24/2014 10:01:22 AM Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama istilah yang diucapkan para politisi merupakan proyeksi dari praktik yang sesungguhnya. Hal itu menunjukkan bahwa rasio pasar tengah mengoloni praktik politik dalam negara hukum demokratis. 4.4 Agama yang Berpolitik: Agama yang Membela dan Merawat Kemanusiaan dan Demokrasi Sejak keruntuhan rezim politik Orde Baru, kesempatan agama untuk berpolitik terbuka. Banyak partai politik berbasis ideologi agama muncul dan terlibat dalam perpolitikan riil. Partai politik berbasis ideologi agama Islam yang paling eksis sejak Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009. Partai politik-partai politik yang dimaksud adalah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai politik-partai politik tersebut akan menjadi peserta pemilu 2014. Dengan berbasis ideologi Islam, partai politik-partai politik itu merupakan representasi agama (Islam) yang berpolitik secara riil dalam negara hukum demokratis Indonesia. Agama yang berpolitik bukan monopoli agama Islam. Agama-agama lain pun berpolitik melalui organisasi massa berhaluan agama. Melalui ormas-ormasnya, agamaagama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu juga terlibat secara aktif dalam merespon isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan hidup, korupsi, terorisme, ketidakadilan ekonomi, pelanggaran hak-hak asasi, dan sebagainya. Agamaagama yang merespon isu-isu publik juga merupakan modus politik agama dalam negara hukum demokratis Indonesia. Dalam perspektif filsafat politik Ha­ bermas di atas, tantangan yang paling serius bagi agama-agama yang berpolitik, baik melalui partai politik maupun organisasi massa, adalah mentranslasikan 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 95 ALEXANDER AUR 95 doktrin-doktrin metafisiknya ke dalam bahasa negara hukum demokratis. Apabila agama gagal melakukan itu, maka agama menjadi “duri dalam daging” demokrasi. Tanpa melakukan translasi doktrin-doktrin metafisiknya, maka agama yang berpolitik justru menjadi horor bagi kemanusiaan dan demokrasi. Doktrin-doktrin metafisik agama dapat menjadi pemasti kognitif prinsip-prinsip etis negara hukum demokratis apabila agama memastikan suatu “situasi epistemik” di dalam modernitas atau di dalam negara hukum demokratis. Agama yang demikian adalah agama yang merelativisasikan posisinya berhadapan dengan agama-agama lain tanpa merelativisasikan inti dogmatismenya sendiri (Borradori, 2005: 105). Dengan demikian, agama yang berpolitik adalah agama yang membelamerawat kemanusiaan dan demokrasi. Penutup Habermas berpikir tentang status sosiologis dan politis agama dalam negara hukum demokratis. Bukan karena ia sangat berbakat dalam hal agama, melainkan ka­ rena ia memandang bahwa agama merupakan salah satu elemen dalam negara hukum demokratis. Dalam bingkai teori tindakan komunikatif, etika diskursus, dan demokrasi deliberatif, Habermas meng­ ingatkan agama bahwa jika agama bermanfaat bagi demokrasi, maka agama ha­rus menerjemahkan bahasa agama ke dalam bahasa sekuler. Pengandaian-pengandaian metafisik agama harus diuji dengan rasio sekuler, supaya agama tidak menjadi horor sekaligus teror bagi negara hukum demokratis. Dalam sejarah politik di Indonesia, partisipasi agama dalam politik mengalami pasang surut. Pada masa-masa persiap­ an kemerdekaan Indonesia dan penetap­ an UUD 1945, para pendiri bangsa yang 4/24/2014 10:01:22 AM 96 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama berasal dari organisasi-organisasi agama berdeliberasi perihal rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara. Doktrin agama (Islam) yang hendak dimasukkan dalam rumusan dasar negara didiskusikan dan diperdebatkan. Hasil dari itu adalah rumus­ an Pancasila yang sekarang menjadi dasar bagi negara hukum demokratis Indonesia. Pada masa Orde Baru, agama dibekukan dari aktivitas politik riil. Doktrin-doktrin agama dilarang untuk diintegrasikan ke dalam politik negara. Partai politik-partai politik baik yang berdasarkan agama maupun nasionalis diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai basis ideologi. Demikian pula, organisasi massa-organisasi massa berhaluan agama pun harus menjadikan Pancasila sebagai basis ideologinya. Kebijakan Orde Baru ini menimbulkan perlawanan, khususnya dari agama Islam. Keruntuhan Orde Baru menjadi angin segar bagi agama untuk berpolitik secara riil. Partai politik-partai politik berbasis agama lahir, dan menjadi peserta pemilu. Beberapa partai politik berbasis ideologi agama (Islam) berhasil eksis serta me­ nempatkan politisinya di DPR, dan masuk menjadi bagian dari pemerintahan. Dalam periode ini, agama mendapat kesempatan luas untuk berpolitik baik melalui politik riil maupun melalui keterlibatannya dalam isu-isu dan persoalan-persoalan publik. Dalam perkembangan demokrasi yang kian matang di Indonesia, agama memang harus dipisahkan dari negara hukum demokratis. Pemisahan ini tidak berarti agama tidak mempunyai ruang politik untuk ekspresi politik. Agama tetap mempunyai ruang politik untuk ekspresi politik. Dalam ekspresi politiknya, agama harus merelativisasikan posisinya di dalam negara hukum demokratis tanpa harus merelativisasikan doktrin-doktrin metafisiknya. Artinya, agama tidak bisa menjadi dasar 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 96 VOL II, 2014 bagi negara hukum demokratis. Hal lain yang harus dilakukan agama adalah me­ nerjemahkan doktrin-doktrin metafisiknya ke dalam bahasa universal supaya bisa diterima oleh warga negara hukum yang lain, baik yang beragama maupun tidak beragama. Pada titik ini, doktrin-doktrin metafisik agama bisa menjadi pemasti kognitif prinsip-prinsip etis negara hukum demokratis. Jika agama gagal menerjemahkan doktrin-doktrin metafisiknya, maka agama yang berpolitik hanya menjadi teror sekaligus horor yang mengancam kemanusiaan, demokrasi, dan mencoreng agama itu sendiri. Kegagalan ini yang mesti diantisipasi oleh agama bila agama bermaksud memberi makna pada negara hukum demokratis. DAFTAR PUSTAKA Adam, Nicholas. (2006). Habermas and Theology. Cambridge: Cambridge University Press. Budi-Kleden, Paul dan Adrianus Sunarko (ed.). (2010). Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan. Maumere-Yogyakarta: Penerbit Ledalero-Lamalera. Borradori, Giovanna. (2005). Filsafat dalam Masa Teror: Dialog dengan Jürgen Habermas dan Jacques Derrida. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Deflem, Mathieu (ed). (1996). Habermas, Modernity and Law. London: SAGE Publication. Habermas, Jürgen. (2008). Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays. Malden, MA: Polity Press. _______. (1996). ”Postscript to Between Facts and Norms” dalam Mathieu Deflem (ed.). Habermas, Modernity and Law. London: SAGE Publication. _______. (1984). The Theory of Communicative Action, vol. 1. Boston: Beacon Press. 4/24/2014 10:01:22 AM Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama Hardiman, F. Budi. (1990). Kritik IdeologiPertautan Pengetahuan dan Kepentingan. Yogyakarta: Kanisius. _______. (1993). Menuju Masyarakat Komunikatif. Yogyakarta:Kanisius. _______. (2009). Demokrasi Deliberatif – Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius. Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (ed.). (2012). Dari Radikalisme menujuTerorisme – Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Jakarta: SETARA Institute. Kieser, Bernard. (2004). “Agama Bubar jika Tidak Bercampur Nalar: Being religiosus a la Habermas” dalam Majalah BASIS, nomor 11-12, tahun ke-53, NovemberDesember. Kristanto, JB dan Nirwan Ahmad Arsuka (ed.). (2002). Bentara Esei-esei 2002, Ja- 006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 97 ALEXANDER AUR 97 karta: Penerbit Buku Kompas. Madjid, Nurcholish. (1992). Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. Magnis-Suseno, Franz. (2010). “Perkembangan Hubungan Kristiani-Muslim di Indonesia” dalam A. Eddy Kristiyanto (ed.), Spiritualitas Dialog: Narasi Teologis tentang Kearifan Religius. Yogyakarta: Kanisius. Regh, William. (1994). Insight and Solidarity: A Study in the Discourse Ethics of Jurgen Habermas. California: University of California Press. Soeprapto. (2013). Pancasila: Makna dan Perumusannya. Jakarta: LPPKB. Stephen, K. White (ed.). (1995). The Cambridge Companion to Habermas. New York: Cambridge University Press. 4/24/2014 10:01:22 AM