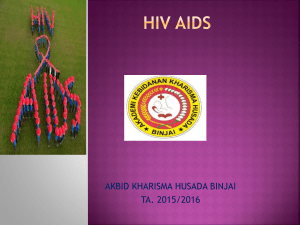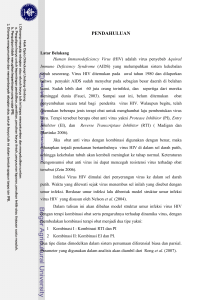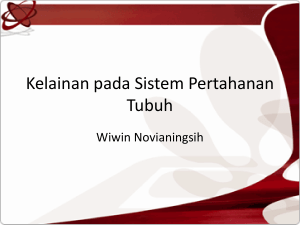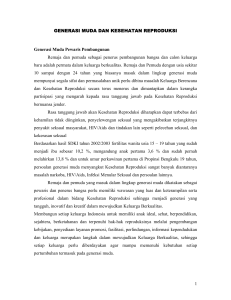1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alergi obat
advertisement

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alergi obat merupakan bagian dari kelompok kejadian reaksi simpang obat. Kejadian alergi obat timbul akibat adanya suatu reaksi imunologis yang tidak dapat diprediksikan setelah pemberian obat tertentu pada subjek yang rentan (Khan et al., 2010). Alergi obat terjadi sebanyak 15-20% dari seluruh kejadian reaksi simpang obat yang dapat meningkatkan mobiditas, perpanjangan rawat inap hingga resiko kematian (Thong et al., 2011). Manifestasi yang timbul akibat kejadian alergi sagat bervariasi. Manifestasi pada kulit (utrikaria, eksantem, pustula, bulla, SSJ, TEN), darah (anemia, trombositopenia, granulositopenia), hepatitis, paru, ginjal hingga reaksi multi organ dapat terjadi (Khan et al., 2010). Salah satu subjek yang rentan mengalami reaksi alergi obat adalah pasien dengan infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus). Pasien dengan infeksi HIV harus menjalani terapi kombinasi ARV (antiretroviral) seumur hidup. Pasien akan menjalani pengobatan menggunakan obat ARV untuk mencegah perburukan sistem imun dan mencegah kemungkinan infeksi oportunistik. USAID mempublikasikan bahwa hingga Juni 2015 sebanyak 15,8 juta orang didunia menjalani pengobatan menggunakan ARV (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS UNAIDS, 2015). Sedangkan, di Indonesia jumlah pasien HIV/AIDS 1 2 yang menjalani pengobatan ARV hingga Sebtember 2014 sebanyak 45.631 orang (Kemenkes, 2014). Penggunaan ARV pada individu dewasa di Indonesia telah diatur dalam Pedoman Nasional Pengobatan Antiretroviral yang diadaptasi dari rekomendasi WHO yang diterbitkan tahun 2013. Panduan tersebut merekomendasikan penggunaan kombinasi tiga jenis ARV yang terdiri dari dua jenis NRTI (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor) dan satu NNRTI (Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor) sebagai lini pertama pengobatan. Salah satu obat golongan NNRTI yang sering digunakan adalah nevirapine (NPV). Nevirapine memiliki efikasi yang baik, ketersediaan yang banyak dan harga yang terjangkau, sehingga secara luas digunakan terutama untuk daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas (Sabbatani S et al. dalam Tansuphaswadikul et al., 2007). Nevirapine bekerja melawan aktivitas HIV melalui ikatannya dengan reverse transcriptase sehingga menghentikan aksi DNA polymerase termasuk menghentikan replikasi HIV (Boehringer Ingelheim, 2005). Namun penggunaan nevirapine ini seringkali menimbulkan reaksi hipersensitivitas dengan manifestasi yang beragam berupa ruam kulit, jaundice, hepatotoksik dan SSJ (Sindrom Stevens Johnson). Salah satu masifestasi yang sering muncul dan mudah dikenali adalah reaksi pada kulit. Manifestasi kulit dapat berupa utrikaria, eksantem, pustula, bulla, SSJ dan TEN dalam berbagai derajat keparahan hingga dapat mengancam keselamatan jiwa (Milpied-Homsi et al., 2015). 3 Dalam sebuah penelitian didapatkan bahwa dari 180 pasien HIV yang menjalani pengobatan nevirapine sebanyak 25 orang atau sebanyak 13,8% yang mengalami reaksi hipersensitivitas (Dickinson et al., 2014). Risiko terjadinya reaksi simpang akibat nevirapine juga 2,2 kali lebih besar dibandingkan pada penggunaaan NNRTI lain yaitu efavirenz (EFV) (Shubber et al. 2013). Namun hingga saat ini belum ada faktor yang diidentifikasi secara pasti untuk memprediksi timbulnya reaksi hipersensitivitas ini. Apabila pasien mengalami reaksi hipersensitivitas akibat penggunaan nevirapine maka proses pengobatan akan terganggu atau bahkan harus dihentikan. Persentase penderita yang harus berhenti menggunakan nevirapine karena reaksi hipersensitivitas sebanyak 6,2% (Wit et al., 2008). Hal ini juga akan meningkatkan kemungkinan lost of follow up pasien dalam pengobatannya. Padahal, pengobatan ARV ini membutuhkan konsistensi dan kepatuhan karena proses pengobatannya akan dilalani seumur hidup. Jumlah pasien HIV di Indonesia hingga September 2014 yang mengalami lost of follow up dari pengobatan ARV adalah sebanyak 15.046 (17,91%) orang dari jumlah total pasien yang pernah menjalani pengobatan ARV yaitu 84.030 orang (Kemenkes, 2014). Selain menjalani terapi ARV, setiap pasien yang didiagnosis terinfeksi HIV juga akan ditentukan stadium klinis sesuai manifestasi yang muncul. Stadium klinis WHO adalah parameter klinis yang digunakan untuk memandu keputusan klinis dalam tata laksana pasien HIV/AIDS. Parameter ini di rancang agar dapat digunakan pada tempat dengan keterbatasan sumberdaya sehingga akses pelayanan laboratorium sulit didapat (WHO, 2005). 4 Stadium klinis ini ditetapkan berdasarkan tanda klinis tertentu yang mudah dinilai dan telah disepakati sebelumnya. Semakin parah manifestasi yang muncul merujuk pada stadium klinis yang lebih tinggi (Kemenkes, 2011). Tingkat keparahan dari tanda-tanda yang muncul ini juga menggambarkan seberapa luas organ-organ dalam tubuh pasien mengalami kerusakan atau penurunan fungsi akibat proses imunodefisiensi. Oleh karena itu stadium klinis pasien juga merupakan salah satu faktor yang penting dipertimbangkan dalam pemberian obat pada pasien HIV. Tingkat imunitas pasien secara tidak langsung dapat digambarkan melalui stadium klinis infeksi HIV. Stadium klinis tiga dan empat (stadium berat) memiliki spesifisitas 73% untuk menentukan ambang batas jumlah CD4 <200 sel/mm3 (imunosupresi berat)(Munthali et al., 2014). Telah diketahui bahwa hipersensitivitas terhadap obat pada pasien dengan infeksi HIV lebih sering melibatkan peran sel T klon CD4 dan CD8 sebagai mediator imunitas (MilpiedHomsi et al., 2015). Padahal terdapat penurunan jumlah dan/atau disfungsi sel T CD4 pada pasien HIV menimbulkan defek kualitatif dan kuantitatif sistem imun (Longo et al., 2012). Hingga saat ini terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetaahui faktor risiko terjadinya alergi nevirapine. Salah satunya adalah penelitian oleh de Maat dalam Milpied-Homsi et al., (2015) yang menyebutkan bahwa wanita, individu dengan set T CD4 tinggi serta viremia HIV yang tidak terkontrol pada awal percobaan memiliki risiko yang lebih tinggi terjadi ruam akibat nevirapine. Namun hingga saat ini belum ada penelitian yang 5 menghubungkan antara variabel stadium klinis infeksi HIV dengan kejadian alergi nevirapine. Dengan diketahuinya hubungan stadium klinis infeksi HIV dan alergi nevirapine, diharapkan akan mempermudah dokter untuk memprediksi kemunginan alergi nevirapine pada pasien yang menjalani terapi ARV sehingga dapat diantisipasi sejak dini. Selain itu diharapkan kepatuhan pasien dalam pengobatan HIV/AIDS akan meningkat dan diikuti oleh peningkatan harapan serta kualitas hidup pasien. B. Perumusan Masalah Rumusan masalah yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah: 1. Apakah stadium klinis infeksi HIV yang lebih ringan berpengaruh terhadap peningkatan kejadian alergi obat nevirapine? 2. Apakah stadium klinis infeksi HIV yang lebih ringan berpengaruh terhadap peningkatan derajat keparahan ruam kulit akibat alergi nevirapine? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui pengaruh antara stadium klinis infeksi HIV yang lebih ringan terhadap peningkatan kejadian alergi obat nevirapine. 6 2. Mengetahui pengaruh antara stadium klinis infeksi HIV yang lebih ringan terhadap peningkatan derajat keparahan ruam kulit akibat alergi nevirapine. D. Manfaat Penelitian 1. Membantu dokter dan praktisi kesehatan lain dalam menentukan pilihan terapi serta prognosis pemberian nevirapine pada penderita HIV pada stadium klinis tertentu. 2. Mendorong peningkatan tingkat keberhasilan terapi ARV dengan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan ARV karena alergi obat dapat diprediksikan dan dicegah. 3. Data yang dihasilkan pada penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkorelasi dengan penelitian ini. E. Keaslian Penelitian Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan hubungan tingkat imunitas berupa jumlah CD4 dan predisposisi genetik dengan alergi/reaksi hipersensitivitas nevirapine yang tercantum dalam tabel 1. Adapun penelitian mengenai hubungan antara stadium klinis infeksi HIV dengan alergi obat nevirapine belum pernah dilakukan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan stadium klinis infeksi HIV yang ringan dan berat dengan risiko alergi dalam pemberian nevirapine di Yogyakarta. 7 Tabel 1. Keaslian Penelitian Penulis (tahun terbit) Tansuphaswadikul et al. (2007) Wit et al. (2008) Tujuan Penelitian Menentukan faktor predisposisi dan insidensi toksisitas pasien AIDS yang menjalani pengobatan nevirapine pada praktik klinis. Mengetahui apakah rekomendasi untuk menghindari pemberian nevirapine pada penderita “naive” juga berlaku untuk penderita yang mengalami penggantian terapi menjadi kombinasi berbasis nevirapine. Metode Tempat dan jumlah sampel Cohort Thailand, 206 Cohort Belanda, 3.752 Kiertiburanakul et al. (2009) Mengembangkan model dan skor risiko prediksi kejadian ruam terkait nevirapine pada penderita HIV dengan kadar CD4 yang rendah. Crosssectional Thailand, 222 Carr et al. (2013) Mengidentifikasi penanda prediktif human leukocyte antigen (HLA) yang dihubungkan dengan hipersensitivitas terhadap nevirapine. Kasus-kontrol Malawa, 117 Cohort Taiwan, 338 Tseng et al. (2014) Mengetahui insidensi dan faktor yang diasosiasikan dengan ruam kulit dan toksisitas hari pada pasien HIV yang menjalani terapi ARV kombinasi mengandung nevirapine ditambah dua NRTI. Hasil Insidensi toksisitas nevirapine pada pasien AIDS dengan jumlah CD4 yang rendah adalah 1,09/100 orang tiap bulan. Pada penderita naive, nilai median CD4 awal kelompok yang mengalami reaksi hipersensitivitas akibat nevirapine lebih tinggi (263 sel/mm3) dibandingkan kelompok yang tidak mengalami reaksi hipersensitivitas (230 sel/mm3). Jumlah CD4 >100 vs <100 sel/mm3 ketika inisiasi nevirapine mimiliki odd ratio 2,69 terhadap kejadian ruam yang diasosiasikan dengan pemberian nevirapine. OR mutlak terhadap risiko SSJ dihubungkan dengan HLA-C*04:01 adalah 5,17. Sedangkan alel didalam lokus HLA-DQB1 melindungi terhadap munculnya hipersensitivitas nevirapine. Baseline fungsi hati yang abnormal diasosiasikan dengan kejadian ruam kulit. Pada analisis regresi logistik CD4 yang lebih tinggi dengan tiap peningkatan 50 sel/ml memiliki OR 1,51, 95% CI 1,12–2,03.