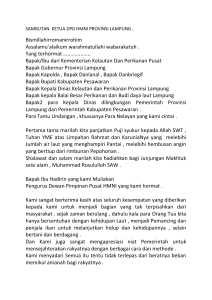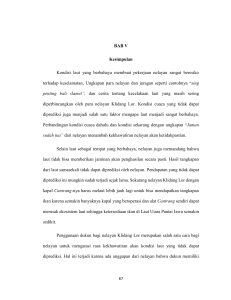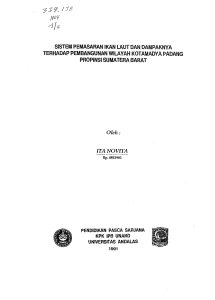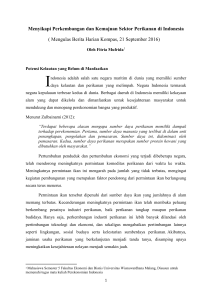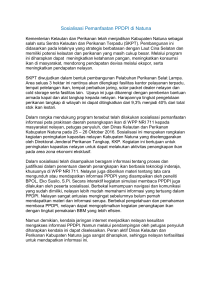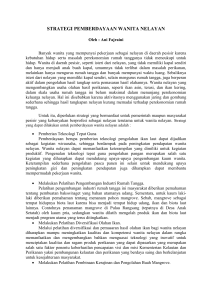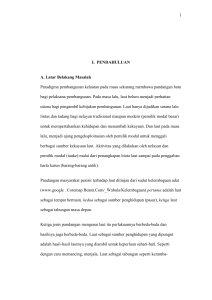BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
advertisement

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah “Ngapote wak lajereh e tangale, Reng majeng tantona lah pade mole Mon e tengghu deri abid pajhelenna, Mase benya’a ongghu le ollena Duuh mon ajhelling odiknah oreng majengan, Abhantal ombak asapok angin salanjenggah Ole…olang, paraonah alajereh, Ole…olang, alajereh ka Madure Reng majeng bennya’ ongggu bebejenena, Pabila alako bendhe nyabenah.” Lagu Tondu’ Majeng beralun dari sound system salah satu perahu, menambah hiruk pikuk pelabuhan ikan di Desa Pasongsongan pada suatu pagi. Pagi itu, seperti biasanya, pelabuhan ramai dengan berbagai rupa aktivitas. Ada kuli angkut yang berebut bagian mendaratkan ikan dari perahu, istri-istri juragan dan juru catatnya yang menghitung hasil tangkapan, para pedagang yang tawar menawar harga, para nelayan yang membetulkan perahu dan alat tangkapnya, petugas pelabuhan yang manarik retribusi, serta mereka yang hanya sekedar duduk-duduk di gubuk menikmati udara pantai di pagi hari. 2 Bersama beberapa warga setempat saya duduk di gubuk bambu tepi pantai, sekedar berbincang-bincang sembari menyaksikan ragam aktivitas di sekitar kami. Dari kejauhan perahu-perahu ‘ole-olang’, berdatangan membawa teka-tekinya masing-masing. Sebagian tampak sumringah dengan senyum riang merias wajah mereka karena hasil tangkapannya melimpah, sebagian yang lain tampak lesu karena sudah bekerja semalam suntuk tapi tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Tondu’ Majeng yang berarti “Datang Mayang” adalah lagu berbahasa Madura yang tak lain menjadi salah satu lagu daerah Jawa Timur. Pada saat mendengarkan lagu tersebut saya berpikir sepintas lalu: betapa dekatnya masyarakat Madura dengan dunia nelayan atau dunia penangkapan ikan. Memang tidak semua orang Madura bekerja sebagai nelayan, tetapi usaha tersebut setidaknya menjadi sektor yang paling penting bila dibandingkan dengan sektor yang lain, sektor pertanian misalnya. Senada dengan pikiran di atas, Masyhuri (1995: 66) menyatakan dalam bukunya yang berjudul Menyisir Pantai Utara bahwa pada mulanya dunia penangkapan ikan di Madura memiliki perkembangan yang lebih baik bila dibandingkan dengan di Jawa. Hal itu dikarenakan oleh pertanian yang kurang berkembang di Madura akibat tanahnya yang kurang subur. Sehingga kebanyakan penduduk Madura berkonsentrasi penuh pada usaha penangkapan ikan. Nelayan di dalam lagu Tondu’ Majeng digambarkan dengan keadaannya yang “ole olang” alias tidak stabil layaknya perahu yang dihempas ombak dan senantiasa “abhental omba’ asapo’ angin salanjengah” (berbantal ombak dan 3 berselimut angin selamanya). Ini menjadi suatu gambaran tentang kehidupan nelayan yang serba tak menentu dan berada dalam bayang-bayang ketidakberdayaan yang dimetaforakan dalam kalimat “berbantal ombak berselimut angin”. Kondisi tersebut membuat nelayan selalu digambarkan sebagai sebuah masyarakat yang hidupnya tidak stabil dan sangat dekat dengan kemiskinan. Pujo Semedi (1998) misalnya, dalam tulisannya mengenai nelayan kecil di Desa Kirdowono mengatakan bahwa hidup para nelayan adalah kehidupan yang miskin dan semakin miskin, bukan hidup yang bergerak dalam keseimbangan. Secara sederhana ia menggambarkan kehidupan nelayan di Desa Kirdowono dengan sebuah pemeo sende dayung adol sarung (sandar dayung, jual sarung). Pandangan mengenai dekatnya masyarakat nelayan dengan kemiskinan barangkali juga bersemayam di dalam kepala kita. Menurut Kusnadi (2008: 20), awal mula mencuatnya masalah-masalah kemiskinan nelayan ke permukaan secara intensif adalah setelah satu dekade dilaksanakannya kebijakan nasional yang dikenal dengan istilah revolusi biru (blue revolution) tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap pada awal 70-an. Akibatnya, sumber daya perikanan terus dikuras untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Seiring berjalannya waktu, kelangkaan sumber daya tidak dapat dielakkan. Kehidupan nelayan berada di ambang ketidak-stabilan. Miskin, akhirnya menjadi kata yang seolah-olah sangat lugas untuk menggambarkan kehidupan nelayan. 4 Sebelum tiba di lokasi penelitian, gambaran itu juga terkonnstruksi di dalam benak saya. Ketika membayangkan masyarakat nelayan, sesuatu yang tergambar di dalam pikiran adalah rumah-rumah berdinding gedek (bambu) di area tepi pantai, berlantai semen atau bahkan tanah, pemukiman kumuh, orang-orang berkulit hitam legam, serta tubuhnya kerempeng karena jam kerja yang tidak sesuai dengan asupan gizinya. Saya juga membayangkan akan bertemu dengan orang-orang yang suka mengeluhkan pekerjaannya karena tak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya seperti sering saya jumpai bila berkunjung ke suatu desa. Bukankah nelayan itu identik dengan pedapatan yang tidak pasti? Namun, saya tidak menjumpai rumah-rumah gedek seperti dalam bayangan itu. Sebaliknya, rumah-rumah tembok, berkeramik, dan sebagian justru bertingkat berdiri di perkampungan itu. Parabola-parabola televisi juga tampak bertebaran di depan tiap-tiap rumah. Pemandangan tersebut kemudian mengharuskan untuk memikirkan kembali rencana penelitian karena tiadanya kesesuaian dengan bayangan semula. Pada akhirnya saya pun harus lebih berhati-hati dalam memposisikan nelayan, apalagi menggeneralisir secara mentah-mentah bahwa nelayan selalu miskin. Sebab, perkara demikian tidak bisa dilepaskan dengan konteks. Setelah beberapa hari di lokasi penelitian dan mulai berbaur dengan para nelayan saya sering mendengar pernyataan seperti ini: “Lebur Mas, alako ka tasek… (jadi nelayan itu enak, Mas)”, “kalau nelayan itu gemuk-gemuk Mas, soalnya banyak tidurnya”, atau “kalau nelayan di sini makmur…”. Kalimat tersebut tentu sangat menarik perhatian saya, pasalnya kalimat-kalimat tersebut 5 terdengar sangat kontradiktif dengan dunia nelayan yang mana di dalam lagu Tondu’ Majeng1 dunia nelayan digambarkan dengan suatu istilah “ole-olang” dan sebuah metafora “asapok angin abhental ombak”. Bagaimana bisa seorang nelayan berkata bahwa menjadi nelayan itu enak? Jangan-jangan pernyataan tersebut hanyalah ungkapan basa-basi saja? Tidak juga, sebab hampir sebagian besar masyarakat baik dari pelaku dan bukan pelaku seringkali mengungkapkan hal yang mengindikasikan bahwa menjadi nelayan itu “enak”. Entah apa penyebabnya, pernyataan tersebut demikian membekas di dalam ingatan sehingga membuat saya memfokuskan tulisan ini pada pandangan-pandangan nelayan mengenai pekerjaan mereka –aktivitas menagkap ikan– yang seringkali dibayangkan sebagai pekerjaan berisiko tinggi. B. Tinjauan Pustaka Antropologi maritim menjadi sebuah sebuah sub-disiplin dalam ilmu antropologi mulai dikenal pada kisaran tahun 1960 hingga tahun 1970 sebagai suatu reaksi atas adanya Revolusi Biru yang ditandai dengan adanya motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap sebagai upaya memaksimalkan eksploitasi sumberdaya laut yang tidak terbatas. Sementara itu, penemuanpenemuan selanjutnya menyatakan bahwa sumberdaya laut tidaklah tidak terbatas, oleh karenanya sumberdaya laut perlu dijaga keberlanjutannya (van Ginkel, 2007) Meskipun demikian, jauh sebelumnya karya-karya etnografi mengenai masyarakat pesisir / nelayan sudah ditulis. Di antara karya yang cukup terkenal 1 Begitu juga di dalam berita-berita surat kabar, dan buku-buku tentang nelayan. 6 adalah tulisan Malinowski (1918) tentang masyarakat nelayan Trobiand dan tulisan Raymond Firth (1946) yang berjudul Malay Fishermen. Sebagai sebuah sub-disiplin yang relatif baru antropologi maritim memiliki sedikit –jika ada- metode, konsep dan teori yang khusus. Sebagian besar dari apa yang disebut sebagai antropologi maritim lebih banyak berasosiasi dengan subdisiplin lain seperti antropologi ekonomi (economic anthropology), antropologi ekologi (ecological anthropology), antropologi pemberdayaan (development anthropology), dan antropologi pariwisata (tourism anthropology) (J.C. Johnson, 1996; van Ginkel, 2007: 3). Kajian mengenai masyarakat pesisir / nelayan di Indonesia masih relatif sedikit bila dibandingkan dengan kajian mengenai masyarakat petani misalnya. Diantara beberapa kajian yang sedikit itu, tulisan Masyhuri (1996) yang berjudul “Menyisir Pantai Utara” adalah referensi yang sangat laris dan menjadi bacaan wajib bagi peneliti yang hendak mengkaji masyarakat nelayan di Indonesia utamanya masyarakat nelayan pantai utara pulau Jawa dan Madura. Tulisan tersebut memberikan gambaran yang bersifat menyejarah mengenai pasangsurutnya usaha dan perekonomian masyarakat nelayan dalam kurun waktu hampir seratus tahun. Karya antropologi yang juga menyejarah bisa dilihat dalam tulisan Pujo Semedi (2003) yang berjudul “Close to the Stone, Far from the Throne”. Buku yang merupakan hasil penelitian disertasi di sebuah kampung nelayan Wonokerto Kulon, Jawa Tengah itu secara sinkronik ia memberikan gambaran mengenai 7 bagaimana negara memberikan pengaruh pada kehidupan sosial-ekonomi nelayan dalam kurun waktu abad 19 hingga abad 20. Semedi menuliskan bahwa perkembangan teknologi penangkapan ikan telah membawa kehidupan nelayan ke arah yang lebih baik meskipun tidak ada jaminan mereka bisa bertahan lama dengan hal itu. Adapun karya lain yang membahas mengenai masyarakat pesisir di Madura dan beberapa daerah tapal kuda bisa dijumpai pada tulisan-tulisan Kusnadi (2002, 2003, 2009). Meskipun kebanyakan dari tulisannya berupa potongan-potongan kasus dari berbagai tempat yang dikumpulkan menjadi sebuah buku, ia cukup intens menulis tema-tema kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Dalam banyak tulisannya ia kerap menyebutkan bahwa kemiskinan strukrural menjadi penyebab terpuruknya nelayan. Para nelayan yang mana berada di lapisan sosial paling bawah sengaja “dimiskinkan” oleh struktur yang menjeratnya, sehingga tak memungkinkan ia untuk lepas dari jeratan tersebut. Sepasang suami istri berkebangsaan Belanda yang bernama Anke Niehof (1985) dan Roy Jordan (1985) pernah melakukan sebuah riset di wilayah Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan dan menghasilkan buku yang cukup tebal. Riset yang mereka lakukan memang tidak secara khusus membahas mengenai masyarakat nelayan, tetapi karena mereka melakukan riset di wilayah pesisir mau tidak mau ia harus memberikan banyak ulasan mengenai kondisi masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Di dalam tulisan tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai kondisi masyarakat nelayan di area pantai utara pulau Madura pada kisaran waktu tahun 80an. 8 Pada tahun 2004 Nihof dan Jordan kembali mempublikasikan sebuah tulisan – tulisan tersebut adalah hasil dari riset lanjutannya – yang lebih memfokuskan pada usaha penangkapan ikan di kampung nelayan di Pasean. Di dalam tulisan itu ia juga sedikit membandingkan antara usaha penangkapan ikan di Pasean dan di Pasongsongan. Menurutnya, bedanya model pembagian hasil antara kedua masyarakat tersebut telah membentuk kecenderungan yang berbeda pula. Bila di Pasean kebanyakan nelayan memilih berdikari dengan membeli perahu klotok sendiri daripada bergabung dengan perahu purse seine, di Pasongsongan malah terjadi sebaliknya: kebanyakan nelayan lebih memilih bergabung pada perahu purse seine. C. Perumusan Masalah Pekerjaan melaut adalah pekerjaan yang berisiko tinggi dan selalu diliputi oleh berbagai ketidakpastian. Menjadi aneh ketika nelayan-nelayan di Pasongsongan mengatakan justru sebaliknya: menjadi nelayan itu enak. Berawal dari rasa keanehan tersebut kemudian timbul keingintahuan saya untuk menelusuri lebih lanjut pandangan-pandangan mereka (para nelayan) terhadap pekerjaannya. Maka dari itu beberapa pertanyaan dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana posisi sektor perikanan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir Pasongsongan? 2. Mengapa para nelayan Pasongsongan menganggap melaut sebagai pekerjaan yang enak (lebur)? 3. Rasio-rasio seperti apa yang mereka ungkapkan guna menjelaskan bahwa melaut adalah pekerjaan yang enak (lebur)? 9 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Ikan-ikan yang tersaji di meja makan ataupun yang masih berjejer di lapaklapak pedagang sebuah pasar tradisional atau supermarket bukanlah sesuatu yang serta merta ada. Ia telah melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Berawal dari nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap milik juragannya. Juragan menjualnya kepada tengkulak lokal. Tengkulak memproses ikan, menggarami, menaburkan es, mengepak, lalu mengirimkannya kepada tengkulak besar baik di dalam kota maupun di luar kota. Baru setelahnya ikan-ikan itu bisa sampai ke pasar-pasar tradisional atau supermarket dan pada akhirnya tersaji di meja makan. Barangkali karena panjangnya alur tersebut, nelayan yang telah mengangkat ikan-ikan itu dari laut ke darat sampai akhirnya tersaji di meja makan justru seringkali terlupakan atau malah kita berlagak tidak tahu menahu. Tulisan ini adalah bentuk apresiasi saya terhadap semua nelayan di negara yang dikenal dengan sebutan negara maritim ini, sekaligus merupakan sebuah langkah awal untuk memahami dinamika dan persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat nelayan. Dikatakan sebuah langkah awal karena penelitian ini adalah penelitian tentang masyarakat nelayan yang pertama kali saya lakukan dan jangka waktunya relatif sebentar. Sebab, untuk benar-benar bisa memahami dinamika dan persoalan-persoalan masyarakat nelayan dibutuhkan waktu penelitian yang lebih lama dan lokasi yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa mengetahui bagaimana siklus masyarakat nelayan dari setiap perbedaan musim secara jelas. Lagipula, kita tidak bisa menyamaratakan keadaan masyarakat 10 nelayan di satu tempat dengan tempat yang lain karena ia tak bisa lepas dengan berbagai konteks. Selain sebagai syarat untuk menempuh sarjana strata satu jurusan Antropologi Budaya, barangkali penelitian ini tidak memiliki tujuan praktis. Saya hanya berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wacana dan syukur-syukur dapat menarik minat untuk penelitian selanjutnya baik oleh segenap pembaca maupun bagi saya sendiri. E. Kerangka Pikir Nelayan menurut Townsley (1998)2 adalah orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Kajian antropologi mengenai dunia perikanan setidaknya bermula dari sebuah konsepsi bahwa dunia perikanan merupakan sebuah fenomena manusia (human phenomenon), sebuah tempat di mana aktivitas manusia berhubungan dengan ekosistem laut dan sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources). Memang aktivitas menangkap ikan (fishing activity) merupakan suatu atribut yang mendefinisikan perikanan (fishery), karena tanpanya ia hanya akan menjadi domain perairan (aquatic realm) di mana spesies laut hidup (Mc. Goodwin, 2001). Oleh karena itu, kajian antropologi mengenai dunia perikanan bukanlah sekedar kajian tentang wilayah geografis, metode penangkapan ikan, jenis alat tangkap, atau spesies ikan tertentu, akan tetapi lebih menekankan pada bidang yang lebih manusiawi, yakni subyek atau pelaku dunia perikanan. 2 Dikutip dari Johanes Widodo & Suadi. 2006. “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut”. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. 11 Dunia nelayan adalah suatu aktivitas yang diliputi oleh ketidakpastian dan risiko-risiko. Secara ekologis, kondisi cuaca yang esktrim, fluktuasi alam, lokasi ikan yang tak tampak, tangkapan yang melebihi kapasitas, dan eksploitasi berlebihan merupakan faktor-faktor yang berada di bawah kontrol nelayan. Selain itu, ada pula tekanan-tekanan ekonomi yang selalu berubah, termasuk ketidaktentuan berkaitan dengan akses, pasar dan harga, relasi dengan pedagang, dan kompetisi antar nelayan (Acheson, 1981; van Ginkel, 2005). Akibatnya, nelayan, utamanya nelayan buruh, seringkali diposisikan sebagai masyarakat termiskin. Pada buku Konflik Sosial Nelayan, Kusnadi (2002: 1) memberikan judul bab yang bagitu provokatif: Nelayan Buruh, Lapisan Sosial Paling Miskin di Pedesaan Pesisir. Pada bagian tersebut ia membahas salah satunya tentang akar kemiskinan. Menurutnya beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat nelayan (nelayan buruh) miskin adalah faktor alamiah (diantaranya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa) dan faktor non alamiah yang meliputi keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sangat jelas, tulisan Kusnadi sangat politis. tujuan akhir pada tulisan-tulisan Kusnadi adalah masuknya upaya pemberdayaan pada masyarakat nelayan seperti aktivasi Koperasi atau (dalam buku yang berbeda) Program Pemberdayaan 12 Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang digulirkan pada tahun 2001 hingga 2008 yang kemudian dianggap sebagai solusi bagi pengentasan kemiskinan nelayan. Saya merasa curiga dengan hasil penelitian yang demikian, sebab ada sesuatu yang membonceng di belakang si peneliti (dalam hal ini program pemberdayaan). Pada akhirnya, peneliti menjadi tidak lagi merdeka dalam melihat sebuah fenomena dan terkesan hanya meninggalkan rasa kasihan bagi pembacanya (lihat Popkin 1986: vi). Bila Kusnadi beranggapan bahwa terbatasnya teknologi menjadi salah satu faktor pemiskinan nelayan, Semedi (1998: 10) malah berpendapat sebaliknya. Menurut Semedi, justru teknologi kerja yang semakin canggih akan mengantar para nelayan pada tingkat eksploitasi yang lebih tinggi dan lebih cepat menghabiskan sumberdaya. Pada akhirnya, hal tersebut hanya akan membawa nelayan pada kebangkrutan usaha. Di luar perbedaan pandangan keduanya sejatinya terdapat kesamaan dalam fokus perhatian kedua peneliti tersebut, yakni memposisikan nelayan sebagai masyarakat miskin yang mana titik acuannya adalah rendahnya atau semakin merendahnya pendapatan nelayan. Lalu, mengapa nelayan di Pasongsongan mengklaim dirinya sejahtera? Apakah itu berarti pendapatan nelayan sudah mencukupi kebutuhan hidup layak? Sepertinya tidak juga. Karena bagaimanapun, para nelayan berada dalam ketidakstabilan. Lalu, apa? Saya teringat kalimat pakar fenomenologi Berger dan Luckmann (1991) dalam bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality, bahwa suatu realitas itu dibangun (dikonstruksi) secara sosial. Dunia kehidupan sehari-hari 13 yang dialami tidak hanya nyata tetapi juga bermakna. Kebermaknaannya adalah subjektif, artinya dianggap benar atau begitulah adanya sebagaimana yang dipersepsi manusia (Berger, 1990 dalam Manuba, 2010). Kemampuan manusia dalam memaknai tentu berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya, yang mana berasal dari pengalaman dan interaksi antar subyek. Interaksi antar subyek bersifat dialektikal yang mana di situ juga terjadi proses interpretasi dan refleksi sehingga terbentuk kesadaran bersama, yaitu realitas yang objektif. Bila Semedi mengatakan bahwa kemiskinan nelayan bersifat absolut, dalam arti mereka miskin karena mereka memang miskin, bukan sekedar miskin dalam perbandingan dengan kelompok lain, maka pada konteks nelayan di Pasongsongan saya justru berpikir sebaliknya, bahwa merasa miskin atau tidak miskin bukan melulu persoalan pendapatan (materi) belaka, akan tetapi ada hal lain, yakni perbandingan. Perbandingan menjadi penting diperhatikan karena di situ ada proses interpretasi dan refleksi. Jangan lupa, konon manusia adalah makhluk yang berpikir dan berefleksi. F. Metode Penelitian Tulisan ini merupakan hasil dari sebuah penelitian lapangan (fieldwork) yang berlangsung selama dua bulan dengan menggunakan metode etnografi. Data-data diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan masyarakat pesisir desa Pasongsongan. Dari metode tersebut banyak didapatkan informasi mengenai pengalaman-pengalaman dan kehidupan sosial-budaya masyarakat nelayan. Observasi terlibat (participatory observation) dilakukan dengan cara ikut bekerja melaut bersama salah satu perahu nelayan. Dengan cara 14 itu saya dapat mengalami (experiencing) bagaimana para nelayan bekerja, mulai dari menyiapkan bekal hingga pulang membawa hasil (uang). Studi kepustakaan baik berupa buku, jurnal, artikel koran maupun laman internet juga dilakukan guna menjelaskan dinamika masyarakat nelayan dan mengonfirmasi data yang telah saya kumpulkan di lokasi penelitian. Kemampuan berbahasa lokal (Madura) dan penampilan yang tak jauh berbeda dengan warga lokal, seringkali saya dikira sebagai warga lokal atau setidaknya orang dari desa tetangga yang sedang bekerja di sekitar di desa tersebut. Sebagian mengira saya adalah seorang nelayan, ada yang menyangka sebagai pedagang ikan, ada juga yang mengira sebagai pekerja proyek pembangunan di pelabuhan. Anggapan tersebut menjadikan kemudahan dan sekaligus kesulitan dalam proses penelitian. Kemudahan yang dimaksud, saya dapat dengan mudah meleburkan jarak dengan masyarakat karena mereka mengganggap saya adalah bagian dari mereka. Akan tetapi hilangnya jarak tersebut justru menciptakan kesulitan tersendiri, utamanya untuk menggali informasi secara lebih dalam, sebab ketika saya mengajukan sebuah pertanyaan tertentu mereka justru tampak heran. Selain itu, kedekatan kultur kadang justru menjadi bumerang karena seringkali muncul anggapan di dalam pikiran saya: “ini sama dengan di tempat saya”, “oh… ini pasti maksudnya begini, dan lain-lain. Namun demikian, sedari awal saya menyadari hal itu akan terjadi. Untuk mengantisipasinya saya selalu berupaya untuk membuat jarak melalui bahasa. Setiap kali berkenalan dengan seseorang, saya justru menggunakan bahasa Indonesia, meskipun saya bisa berbahasa lokal. Cara itu membuat mereka mencari 15 tahu tentang saya, siapa dan dari mana. Saya memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke lokasi penelitian, lalu mereka dapat bercerita lebih banyak. Dengan cara tersebut banyak informasi didapatkan tanpa membuat mereka merasa heran..