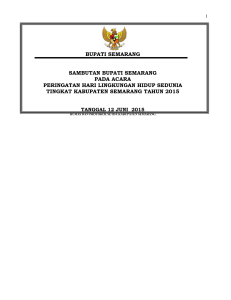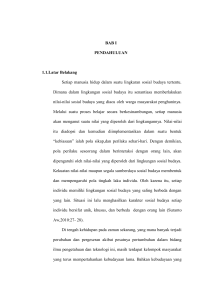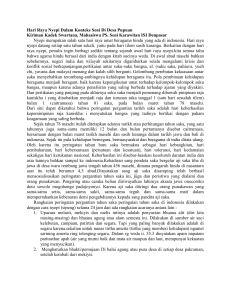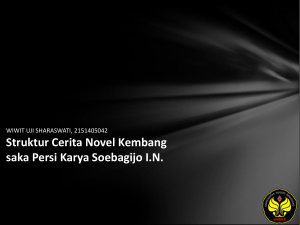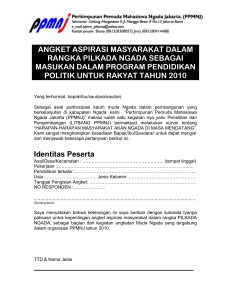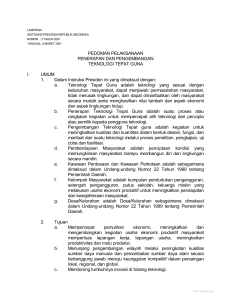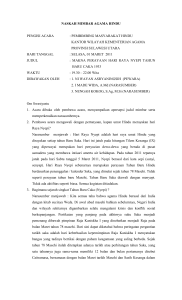REBA ORANG NGADA: SEBUAH REFLEKSI TERHADAP TATA
advertisement
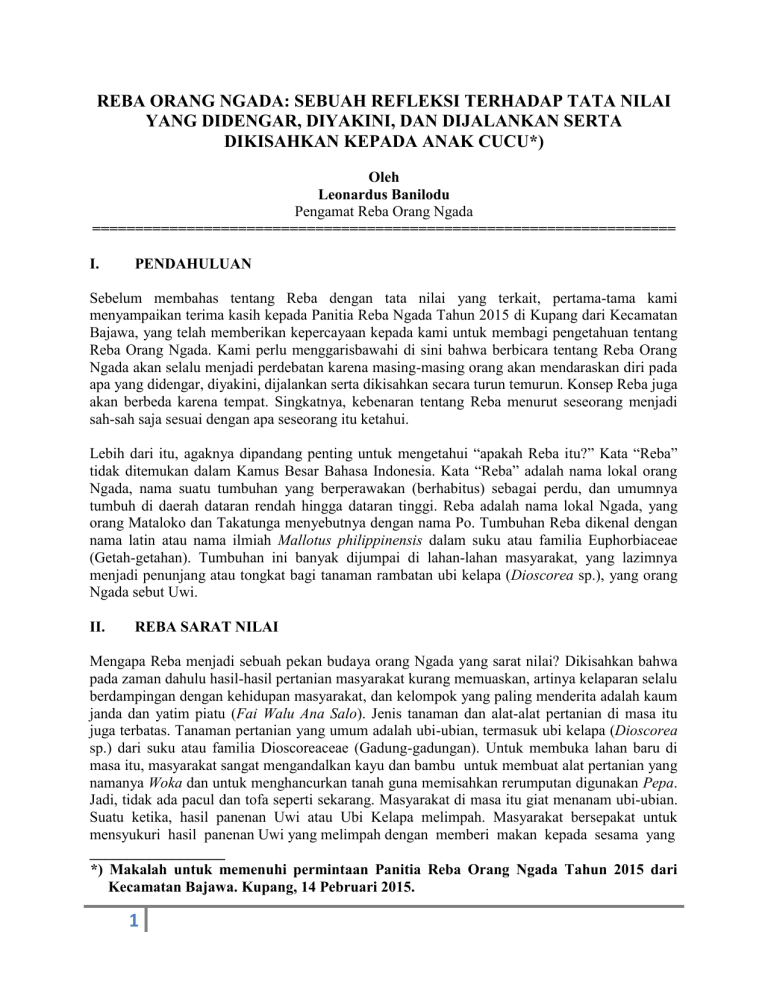
REBA ORANG NGADA: SEBUAH REFLEKSI TERHADAP TATA NILAI YANG DIDENGAR, DIYAKINI, DAN DIJALANKAN SERTA DIKISAHKAN KEPADA ANAK CUCU*) Oleh Leonardus Banilodu Pengamat Reba Orang Ngada ==================================================================== I. PENDAHULUAN Sebelum membahas tentang Reba dengan tata nilai yang terkait, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Panitia Reba Ngada Tahun 2015 di Kupang dari Kecamatan Bajawa, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk membagi pengetahuan tentang Reba Orang Ngada. Kami perlu menggarisbawahi di sini bahwa berbicara tentang Reba Orang Ngada akan selalu menjadi perdebatan karena masing-masing orang akan mendaraskan diri pada apa yang didengar, diyakini, dijalankan serta dikisahkan secara turun temurun. Konsep Reba juga akan berbeda karena tempat. Singkatnya, kebenaran tentang Reba menurut seseorang menjadi sah-sah saja sesuai dengan apa seseorang itu ketahui. Lebih dari itu, agaknya dipandang penting untuk mengetahui “apakah Reba itu?” Kata “Reba” tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata “Reba” adalah nama lokal orang Ngada, nama suatu tumbuhan yang berperawakan (berhabitus) sebagai perdu, dan umumnya tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi. Reba adalah nama lokal Ngada, yang orang Mataloko dan Takatunga menyebutnya dengan nama Po. Tumbuhan Reba dikenal dengan nama latin atau nama ilmiah Mallotus philippinensis dalam suku atau familia Euphorbiaceae (Getah-getahan). Tumbuhan ini banyak dijumpai di lahan-lahan masyarakat, yang lazimnya menjadi penunjang atau tongkat bagi tanaman rambatan ubi kelapa (Dioscorea sp.), yang orang Ngada sebut Uwi. II. REBA SARAT NILAI Mengapa Reba menjadi sebuah pekan budaya orang Ngada yang sarat nilai? Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu hasil-hasil pertanian masyarakat kurang memuaskan, artinya kelaparan selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat, dan kelompok yang paling menderita adalah kaum janda dan yatim piatu (Fai Walu Ana Salo). Jenis tanaman dan alat-alat pertanian di masa itu juga terbatas. Tanaman pertanian yang umum adalah ubi-ubian, termasuk ubi kelapa (Dioscorea sp.) dari suku atau familia Dioscoreaceae (Gadung-gadungan). Untuk membuka lahan baru di masa itu, masyarakat sangat mengandalkan kayu dan bambu untuk membuat alat pertanian yang namanya Woka dan untuk menghancurkan tanah guna memisahkan rerumputan digunakan Pepa. Jadi, tidak ada pacul dan tofa seperti sekarang. Masyarakat di masa itu giat menanam ubi-ubian. Suatu ketika, hasil panenan Uwi atau Ubi Kelapa melimpah. Masyarakat bersepakat untuk mensyukuri hasil panenan Uwi yang melimpah dengan memberi makan kepada sesama yang __________________ *) Makalah untuk memenuhi permintaan Panitia Reba Orang Ngada Tahun 2015 dari Kecamatan Bajawa. Kupang, 14 Pebruari 2015. 1 berkekurangan, terutama kaum janda dan yatim piatu. Disepakati pekan syukuran itu namanya Reba, karena Ubi Kelapa tumbuh merambat dengan suburnya pada pohon-pohon Reba. III. TAHAPAN REBA Reba adalah suatu pekan budaya orang Ngada (Woe Ngadha) setahun sekali di mana semua orang berdendang dan menari, dan sarat dengan pesan-pesan adat. Dalam kalender musim tradisional orang Ngada, Reba adalah puncak dari pergantian musim dalam setahun, dan sekaligus sebagai Tahun Baru Adat, untuk Reba Langa tepatnya 15 Januari setiap tahun, yang pada tanggal inilah belakangan ditandai dengan Misa Inkulturasi, sehingga Pembukaan Reba (Dheke Reba) di setiap Rumah Adat (Sao Meze Tangi Lewa) bergeser ke tanggal 16 Januari. Memasuki pekan budaya Reba, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui di setiap rumah adat (Sao Ngaza). Pertama adalah pembukaan Reba (Kobe Dheke), yang didahului dengan acara makan nasi bercampur kelapa garukan atau parutan, yang dalam bahasa adat disebut Ka Maki Rebha. Untuk Ka Maki Rebha, lazimnya dilaksanakan pertama di rumah adat yang berkedudukan sebagai Rumah Pokok (Saka Pu’u) dan selanjutnya diikuti di rumah-rumah adat dalam rumpun (One Woe) yang telah siap untuk memberikan anak cucu. Rumah Pokok di sini berkaitan makna dengan Lambang Persatuan Suku (Ngadhu Ne’e Bhaga). Dalam satu suku, lazimnya ada satu Ngadhu Ne’e Bhaga, atau bisa lebih dari satu, tergantung besar kecilnya suku. Jadi, dalam satu suku, paling sedikit terdapat empat rumah adat, yakni Saka Pu’u, Saka Lobo, Kaka Saka Pu’u, dan Kaka Saka Lobo. Atau paling banyak terdapat enam atau lebih rumah adat (tergantung jumlah rumah adat yang berstatus Dai), yakni Saka Pu’u, Saka Lobo, Kaka Saka Pu’u, Kaka Saka Lobo, Dai Kaka Saka Pu’u, dan Dai Kaka Saka Lobo. Setelah Ka Maki Rebha secara bergilir di rumah-rumah adat, tahap berikutnya adalah Dheke Rebha di rumah adat masingmasing. Kedua kegiatan ini lazimnya dilakukan pada malam hari dengan menghadirkan semua anggota keluarga dari rumah adat yang bersangkutan, kecuali berhalangan hadir karena alasan kesehatan atau jauh di perantauan. Pada malam Kobe Dheke ini, tidak ada agenda evaluatif atau pembicaraan penting di dalam rumah adat. Yang terjadi adalah makan bersama, yang didahului dengan memberi makan nenek moyang (Ti’i Ka Inu Ebu Nusi) karena diyakini bahwa pada malam Kobe Dheke semua nenek moyang dalam rumah adat dan suku hadir. Selanjutnya, bertawa ria atau berceritera apa saja di antara semua anggota keluarga. Pada malam ini pula akan terjadi saling meminjam pakaian adat untuk dipakai pada esok harinya ketika akan menari bersama (O Uwi), atau saling kompromi tentang hidangan rumah adat untuk menjamu para tamu undangan jika ada rencana dari kampung lain yang masuk atau datang O Uwi. Selain itu, terdapat acara adat yang lazimnya digandengkan dengan acara Dheke Reba adalah mengizinkan anak manantu (laki-laki atau perempuan, dan biasanya anak menantu perempuan) untuk masuk rumah adat (Tege Ana Tua). Acara lain yang dapat digandengkan dengan Pembukaan Reba adalah acara peminangan adat (Ka Maki Rene) untuk perempuan atau untuk laki-laki. Memasuki pekan Reba, tidak diperkenankan melakukan jual beli atau mendatangkan ikan mentah (segar). Sejak malam Dheke Reba hingga berakhirnya Reba (Kobe Sui), di tungku api rumah adat (Lika Lapu Sao Meze), tidak boleh menggoreng jagung atau memasak sayur-sayuran. Kedua adalah hari berdendang dan menari (O Uwi). Tahap ini biasanya diawali dengan kegiatan berdendang dan menari keliling kampung (Kelo Ghae Gili Nua). Tujuannya adalah untuk 2 mengajak sanak saudara untuk segera berpakaian adat, keluar dari rumah masing-masing, dan O Uwi bersama-sama di tengah kampung. O Uwi ini bisa dilakukan untuk satu kampung saja, atau bersama-sama dua atau tiga kampung, tergantung kesepakatan sebelumnya. Jumlah hari bisa dua atau tiga hari, juga tergantung kesepakatan dan kemampuan fisik dan suara. Karena jika tidak menjaga kemampuan fisik dan suara, di pasca O Uwi, orang merasakan kepegalan kaki, keletihan fisik dan berbicara dengan suara parau atau suara menghilang. Sajian utama di hari O Uwi adalah nasi daging (maki sui) dengan minuman alkohol (tua ara). Ketiga adalah Penutupan Reba (Kobe Su’i), yang didahului dengan makan bersama semua anggota dan anak cucu dalam suku (Dhoi) di tugu atau tumpukan batu suku (Loka). Makan bersama ini dilakukan pada siang hari, lazimnya di pagi hari. Karena setelah acara Dhoi, masih ada orang yang bersiap diri untuk O Uwi, apakah di kampung sendiri atau di kampung tetamngga. Pada acara Dhoi di Loka, semua rumah adat yang tergabung dalam suku (Woe) harus membawa Tofa Ubi (Sua Uwi) masing-masing sebagai tanda kedaulatan adat di dalam suku, juga nasi daging dan minuman tua ara. Jumlah Sua Uwi, bisa empat jika satu Ngadhu Ne’e Bhaga dan tidak ada Dhai, atau enam atau lebih jika ada Dhai. Acara penting di Loka adalah 1) pesanpesan oleh Tua Adat (Po Pena Pu’u Ngia Dela One Woe) dan tukar pikiran dalam suku (Papa Ti’i Go Magha Zeta One Woe), 2) makan bersama (Nalo), 3) ritual penyegaran tofa ubi (Bura Zua), dan 4) berdendang dan menari bersama keliling kampung (Kelo Ghae) dengan mengedepankan orang-orang (biasanya anak-anak) yang memikul Zua Uwi masing-masing, serta bubar ke rumah masing-masing. Setelah acara Dhoi di pagi hari, pada malam hari akan dilakukan acara Penutupan Reba (Kobe Su’i) di masing-masing rumah adat sesuai kesepakatan dari anggota keluarga di rumah adat yang bersangkutan. Acara Kobe Su’i ini terdiri dari 1) ritual untuk sembelih ayam (ngaza manu dan ghiri ate manu), 2) memotong-motong daun ubi dengan menyapa semua kedatangan anggota keluarga serta anak cucu dari berbagai penjuru (Su’i O Uwi) yang hasil potongan daun ubi akan dibagikan kepada seisi rumah untuk dimakan, 3) memberi makan nenek moyang (yakni dua piring atau wati nasi, daging - hati ayam dan dua gelas atau tempurung minuman tua ara), 4) makan minum bersama seluruh anggota dalam rumah adat, dan 5) pesan-pesan dari lelaki tertua dalam rumah (Po Gege Wiri Meta Go Pene). Hal penting pada acara Dhoi dan Kobe Su’i adalah pesan-pesan adat, yang akan disampaikan pada butir di bawah ini. IV. LINGKUP PESAN-PESAN ADAT REBA Kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan pembangunan, di satu sisi telah membawa kita kepada berbagai kemajuan hidup, tetapi di sisi lain telah melahirkan kita menjadi insan-insan yang individualistik, tidak mengenal saudara dan saudari, meremehkan atau merendahkan satu dengan yang lain, berperkara dengan sesama orang di dalam satu rumah adat atau di dalam satu suku. Bersamaan dengan bertumbuh suburnya sikap-sikap individualistik demikian, terjadilah pemutarbalikan dan penanaman tata nilai kepada anak cucu yang tidak benar hanya untuk sekedar mengamankan sikap individualistik diri. Lagi pula, jika sikap-sikap individualistik tersebut dipicu oleh sikap menguasai dari laki-laki yang adalah sang suami dari saudari perempuan. Dia laki-laki sang suami akan mendorong isterinya untuk bersikap sesuka hatinya terhadap saudara laki-laki dari dari isteri. Sikap dan tindakan sewenang-wenang dari sang laki-laki yang adalah suami dari saudari perempuan tidak dapat dibenarkan. Dia laki-laki 3 sebagai suami tidak memiliki hak adat di rumah adat isterinya. Dia memiliki hak adat di rumah adat yang didiami oleh saudarinya. Jadi, jika perlu diberi teguran dan sanksi adat. Berikut ini adalah pesan-pesan adat penting yang dapat selalu disampaikan, dipesankan, dan diluruskan, sehingga tidak menyesatkan anak cucu di kemudian hari. 1. Pesan-pesan Adat pada Acara Dhoi di Loka Pesan-pesan adat penting pada acara Dhoi di Loka adalah terkait dengan kepemilikan umum sebagai Suku (Woe), yaitu 1) tanah suku (Tana One Woe), 2) bambu suku (Bheto Ngadu Bhaga), 3) kedudukan hierarkis rumah adat sebagai Saka Pu’u, Saka Lobo, Kaka Saka Pu,u, Kaka Saka Lobo, Dai Kaka Saka Pu,u, dan Dai Kaka Saka Lobo. Di dalam satu suku, lazimnya terdapat satu atau lebih lahan yang luasnya ratusan bahkan ribuan hektar. Tanah ini adalah milik bersama atau komunal dari semua rumah adat yang terhimpun di dalam satu suku. Tanah ini tidak dibenarkan untuk diklaim kepemilikan sebagai milik orang perorang atau milik dari rumah adat tertentu. Komunal artinya bahwa semua keturunan di dalam satu suku memiliki hak yang sama untuk menanam (Tuza Mula) guna memelihara anak cucu. Hal yang berbahaya dan pasti menimbulkan pecah belah di dalam suku adalah adanya upaya mengklaim kepemilikan hanya pada rumah adat tertentu (Melo Da Ne’e Go Boro), atau ada upaya sertifikasi tanah oleh orang perorang karena merasa tidak perlu takut bahwa masih ada orang lain. Hal ini berati sudah terdapat upaya sadar untuk menghilangkan hak adat orang lain dalam satu suku. Sertifikasi dapat saja dilakukan, tetapi harus atas nama suku, dan beban PBB dikenakan kepada orang memanfaatkan tanah tersebut. Lazimnya terdapat sejumlah rumpun bambu di suatu lahan luas sebagai bambu milik suku. Bambu suku (Bheto Ngadhu Bhaga) juga merupakan milik komunal di dalam satu suku. Bambu ini biasanya dimanfaatkan jika ada kepentingan suku atau untuk merehabitasi rumah adat tertentu, namun harus sepengetahuan dan seizin tua adat dalam suku. Bambu ini tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan orang perorang, apa lagi untuk tujuan ekonomi. Untuk satu suku terdapat sejumlah rumah adat dengan kedudukan hierarkis sebagai Saka Pu’u, Saka Lobo, Kaka Saka Pu,u, Kaka Saka Lobo, Dai Kaka Saka Pu,u, dan Dai Kaka Saka Lobo. Kedudukan hierarkis ini disepakati dan dibentuk semenjak sejumlah orang mendaulatkan diri ke dalam satu suku. Kedudukan hierarkis ini tidak dapat dirubah karena ada jabatan sebagai gubernur, bupati, kepala dinas atau jabatan lainnya. Walaupun manusia yang berada di Rumah Pokok (Sao Saka Pu’u) adalah manusia yang tidak berpendidikan, tidak memiliki kedudukan, hanya sebagai petani, mereka tetap dihormati sebagai manusia di Rumah Pokok dan harus didatangi oleh manusia dari Sao Kaka Saka Pu’u atau dari Sao Dai Kaka Saka Pu’u. Lebih dari itu, kekurangan atau keterbatasan di Rumah Pokok (Sao Saka Pu’u) adalah juga seharusnya menjadi tanggung jawab adat (tidak tertulis) dari Sao Kaka Saka Pu’u, dan kekurangan atau keterbatasan di Sao Kaka Saka Pu’u adalah juga harus menjadi tanggung jawab adat dari Sao Dai Kaka Saka Pu’u, demikian pula sebaliknya di Sao Saka Lobo, Sao Kaka Saka Lobo, dan Sao Dai Kaka Saka Lobo, dan juga hubungan antara Sao Saka Pu’u dan Sao Saka Lobo. Jadi, pesan ini adalah Papa Wiu Zale One Woe We Modhe Gore. Mae Papa Lomo. 4 2. Pesan-pesan Adat pada Acara Kobe Su’i di Rumah Adat (Sao Meze Tangi Lewa) Pesan-pesan adat penting pada acara Kobe Su’i di Rumah Adat (Sao Meze Tangi Lewa) adalah terkait dengan kepemilikan umum sebagai Rumah Adat (Sao Ngaza), yaitu 1) tanah rumah adat (Tana One Sao), 2) bambu rumah adat (Bheto Ngaza Sa’o), 3) kedudukan hierarkis adat laki-laki yang kawin keluar (La’a Kawo Api Ngata) dan perempuan yang mendiami rumah (Di’i We Noa Pui Papu). Di dalam satu rumah adat, lazimnya terdapat sejumlah lahan yang adalah tanah adat milik rumah adat (Ngia Ngora One Sao). Tanah ini adalah milik bersama atau komunal dari semua anggota keluarga (laki-laki atau perempuan) yang adalah keturunan langsung dari satu rumah adat, termasuk orang yang telah dibelis (Kaba Maza Wea Mezi) yang telah disahkan melalui mandi air kelapa (Neku Fu) kepada perempuan yang dibelis itu. Tanah komunal ini tidak benar untuk diklaim kepemilikannya sebagai tanah milik orang perorang. Lagi-lagi, sebagai milik komunal artinya bahwa semua keturunan di dalam satu rumah adat memiliki hak sama untuk menanam (Tuza Mula) guna memelihara anak cucu. Hal yang berbahaya dan menimbulkan pecah belah di dalam satu rumah adat adalah adanya upaya mengklaim kepemilikan hak atas tanah adat hanya pada orang perorang melalui sertifikasi tanah. Jika demikian, maka ini berati sudah terdapat upaya sadar untuk menghilangkan hak adat orang lain yang juga di dalam satu rumah adat. Jika demikian, masih perlukah memiliki Rumah Adat (Sao Meze Tangi Lewa)? Sertifikasi tanah dari rumah adat dapat saja dilakukan, tetapi harus atas nama rumah adat, dan beban PBB dikenakan kepada orang yang memanfaatkan tanah tersebut. Sertifikasi tanah adat (girik) oleh orang perorang dapat dilakukan jika tanah adat tersebut telah diperoleh melalui jual beli dengan pemiliknya yang sah. Fenomena ini hendaknya menjadi suatu perhatian penting bagi pihak yang berurusan dengan sertifikasi tanah adat, apa lagi proses sertifikasi tanah adat telah dilakukan secara diam-diam dan menyalahi prosedur sertifikasi tanah adat (girik). Selayaknya, para pihak harus memberi pengertian secara baik dan benar tentang proses sertifikasi tanah adat (girik). Sangat disayangkan jika para perempuan memproses sertifikasi tanah adat untuk menjadi kepemilikan orang perorang tanpa sepengetahuan saudara laki-laki. Pertanyaan di sini, “siapa yang memberikan hak kepemilikan itu kepada perempuan untuk boleh memproses sertifikasi tanah adat menjadi milik pribadi orang perorang?” Dalam rumah adat, juga terdapat sejumlah rumpun bambu di satu atau lebih lahan. Bambu rumah adat (Bheto Ngaza Sao) juga merupakan milik komunal di dalam satu rumah adat. Bambu ini biasanya dimanfaatkan jika ada kepentingan untuk merehabitasi rumah adat. Bambu ini diperkenankan untuk dimanfaatkan orang perorang, namun sepengetahuan atau seizin lelaki tertua di dalam rumah adat. Hal ketiga adalah kedudukan hierarkis laki-laki yang kawin keluar (La’a Kawo Api Ngata) dan perempuan yang mendiami rumah (Di’i Wi Sao Noa Pui Papu). Isu ini ramai diperbincangkan dan terkadang menyesatkan. Konsep Matriarka di Ngada, tidak sepenuhnya sebagai kebalikan dari Konsep Patriarka di banyak wilayah di Indonesia. Dalam sejumlah tata cara adat, laki-laki memiliki peran penting dan berkeputusan. Bo Nua, laki-laki. Saka Ngadhu, laki-laki. Sa Ngaza, laki-laki. Wake Sao Meze Tangi Lewa, laki-laki. Ria Ulu Ngana, laki-laki. Podhu Zele Mata Raga, laki-laki. Ti’i Ka Ebu Nuzi, laki-laki. Doi Ngawu, laki-laki. Keputusan peminangan anak perempuan sebagai dibelis oleh calon suami atau calon suami kawin masuk adalah laki-laki Jadi, 5 semuanya, laki-laki. Kedhi-kedhi Go Nopo Besi artinya kecil-kecil dia laki-laki. Dia laki-laki berkedudukan penting dan berkeputusan atas segala sesuatu di dalam Rumah Adat. Benar bahwa yang mendiami rumah adat (Di’i Sao Wi Noa Pui Papu) adalah perempuan, tetapi ada yang memberikan hak itu kepada perempuan, yaitu saudara laki-laki. Perempuan diberikan hak untuk menjaga dan merawat rumah adat (Di’i Sao Wi Noa Pui Papu) dan mengolah tanah untuk menanam demi anak cucu (Tuza Mula Wi Polu Kedhi Banga). Mendiami rumah adat dan duduk di tungku api untuk memasak (Podhu Zili Tolo Lapu Noa Pana Teki), bukan untuk memiliki karena yang memiliki adalah tetap saudara laki-laki. Artinya, perempuan yang mendiami Rumah Adat tidak sewenang-wenang terhadap saudara laki-lakinya. Dia perempuan harus menjaga harkat dan martabat saudara laki-lakinya. Ketika dia perempuan sewenangwenang (dalam kata dan tindakan) terhadap saudara laki-lakinya, maka saudara laki-lakinya dapat membuat keputusan “apakah saudari perempuannya tetap menjaga Rumah Adat ataukah dibiarkan mengikuti suaminya?” Jadi, tidak benar bahwa Konsep Matriarka di Ngada dimaknai sebagai perempuan yang berhak atas segala harta. Bahkan sampai-sampai saudara laki-laki memanfaatkan lahan untuk tanam menanam pun dilarang oleh saudari perempuan. Apakah benar bahwa saudara laki-laki dengan serta merta kehilangan hak adatnya karena dia kawin keluar? Tidak benar! Saudara laki-laki tetap memiliki hak adat di Rumah Adat yang didiami oleh saudari perempuannya. Dia laki-laki boleh memanfaatkan lahan adat untuk tanam menanam guna memelihara isteri anaknya dan tidak boleh mengalihkan hak atas lahan tersebut kepada isteri anaknya. Kecuali, pengalihan hak atas tanah berkaitan dengan urusan adat, misalnya untuk Penghargaan Terhadap Mertua Laki-laki atau Mertua Perempuan, yang dikenal dengan Saga, dan ada tiga penghargaan, yakni Penghargaan Pertama (Saga Wunga), Penghargaan Kedua (Saga Kisa), dan Penghargaan Ketiga (Saga Repo). Jika pengalihan lahan ini terjadi untuk Saga, maka kepemilikan atas lahan bukan isteri anaknya, tetapi kepada Sao Adat dari pihak isteri anaknya. Konsep bahwa laki-laki kawin keluar (La’a Kawo Api Ngata), itu artinya saudara laki-laki di Rumah Adat isteri anak, dia laki-laki tidak memiliki hak adat apapun. Dia hidup memberikan nafkah kepada isteri anak selama dia laki-laki masih kuat, produktif. Tetapi, ketika dia laki-laki sudah tua dan tidak produktif lagi, biasanya (dahulu) dia laki-laki akan pulang ke rumah saudari perempuan. Dan ketika saudara laki-laki meninggal dunia, yang membuat keputusan untuk penguburan saudara laki-laki adalah anak saudaranya (yang namanya Tange Tobo), bukan anak kandung yang membuat keputusan. Da Ringu Roe Woe Lau Zele Ngia Ana Dhadhi. Napa Da Wau Ngia Ana Weta. Hal ini penting untuk diluruskan agar tidak menyesatkan anak cucu tentang Konsep Matriarka di Ngada. V. PENUTUP Demikian sedikit pengetahuan yang didengar, diyakini, dan dijalankan serta dikisahkan kepada anak cucu. Kiranya pemikiran ini dapat menjadi bahan diskusi dan pertukaran pikiran dengan kelompok atau orang-orang yang lebih berpengetahuan tentang Reba Orang Ngada. Mohon maaf, jika ada yang tidak sependapat dengan isi tulisan ini karena masih sangat banyak yang perlu dibahas. Terima kasih. 6