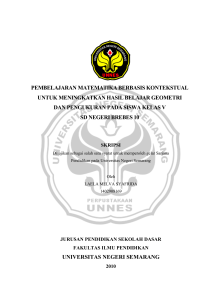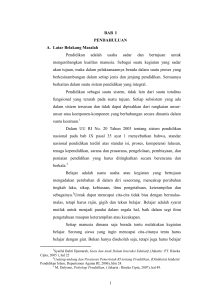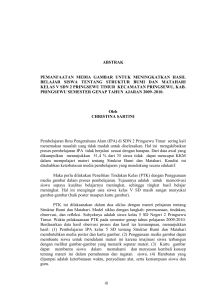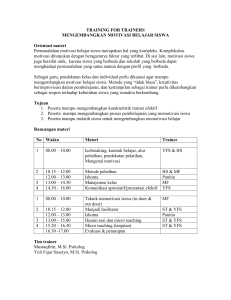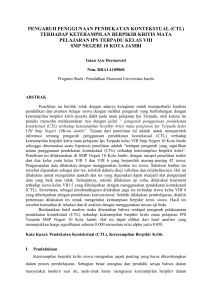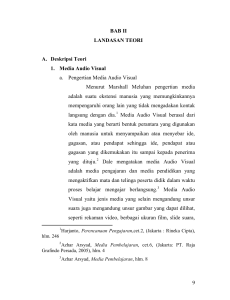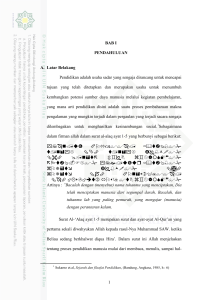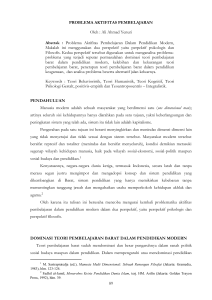Refleksi Kritis dari Lapangan - Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan
advertisement

M. Mushthafa, Jembatan untuk Pendidikan Kontekstual | 175-181 Jembatan untuk Pendidikan Kontekstual: Refleksi Kritis dari Lapangan M. Mushthafa Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika), Guluk-Guluk, Sumenep. Judul buku : Mendidik Pemenang Bukan Pecundang Penulis : Dhitta Puti Sarasvati & J. Sumardianta Penerbit : Bentang Pustaka, Yogyakarta Cetakan : Pertama, April 2016 Tebal : xvi + 324 halaman Salah satu kritik mendasar terhadap dunia pendidikan saat ini adalah kenyataan bahwa pendidikan, yakni sistem persekolahan, dipandang masih belum mampu menjawab tantangan zaman. Lulusan sekolah masih banyak gagap menghadapi kenyataan hidup di masyarakat saat mereka terjun dan bergelut langsung dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pertanda yang dapat dikemukakan terkait dengan problem krisis sosial-ekologis yang dihadapi umat manusia saat ini. Dalam pandangan sejumlah pihak, sekolah dipandang belum cukup mampu untuk menanamkan kepekaan ekologis atau melek ekologis (ecological literacy) terhadap para siswa di sekolah sehingga siswa gagal memberi tanggapan kritis atas krisis sosial-ekologis yang dihadapi umat manusia. Di sisi yang lain, kesenjangan praktik pendidikan di sekolah dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman juga terasa kurang terjembatani oleh dunia akademis, yakni pendidikan tinggi yang mengelola jurusan keguruan dan ilmu pendidikan. Buku berjudul Mendidik Pemenang Bukan Pecundang yang 176-181 | ’Anil Islam Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016 ditulis oleh dua orang praktisi pendidikan ini kiranya dapat menjadi jembatan untuk menghidupkan kembali pendidikan kritis dan pendidikan kontekstual. Pendidikan kritis dan pendidikan kontekstual yang dimaksudkan di sini adalah model pendidikan yang mampu menanamkan kepekaan kepada para peserta didiknya atas situasi masyarakat yang bergerak cepat dan praktik pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman di masa mendatang. Dhitta Puti Sarasvati, penulis buku ini, adalah lulusan Teknik Mesin ITB dan Pendidikan Matematika Universitas Bristol (UK) yang saat ini mengajar di Fakultas Pendidikan, Sampoerna University, setelah sebelumnya menjadi guru honorer dan juga aktif di Ikatan Guru Indonesia (IGI). Sedangkan J. Sumardianta, penulis lainnya, mengajar di SMA Kolese De Britto, Yogyakarta. Pada bagian pengantar, dijelaskan bahwa “buku ini ditulis bagi para pendidik, calon pendidik, dan orangtua untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia nyata” (hlm. xiv). Generasi seperti apa yang diharapkan dapat lahir dari sekolah ideal oleh penulis buku ini? Dari judulnya, pembaca bisa menjawab: generasi pemenang, bukan generasi pecundang. Penulis buku ini menjelaskan makna “pemenang” pada tulisan pertama dengan membuat pembedaan antara generasi muda tipe pengemudi (driver) dan penumpang (passenger). Dengan mengutip Rhenald Kasali, dijelaskan bahwa generasi pemenang memiliki sejumlah ciri, misalnya visioner, proaktif dan siap memelopori perubahan, siap turun tangan, mampu melihat solusi dalam tiap masalah, suka bekerja keras, menjadi trend setter, dan sebagainya. Sementara itu, generasi penumpang yang juga diidentikkan dengan pecundang digambarkan bermental pasif, kurang mandiri, cepat menyerah, mudah mengeluh dan frustrasi, sulit mencari alternatif jalan keluar, dan sebagainya (hlm. 5-8). Sesuai dengan karakternya yang merupakan kumpulan tulisan, maka dalam buku ini tidak ada uraian yang sifatnya sistematis untuk menjawab cara sekolah membentuk generasi pemenang itu. Pembaca harus menyimpulkan sendiri bagaimana generasi pemenang itu dibentuk oleh sekolah. Dalam menjelaskan M. Mushthafa, Jembatan untuk Pendidikan Kontekstual | 177-181 masalah ini, buku ini memberi jawaban secara teoretis maupun praktis. Maksudnya, ada jawaban yang digali dari gagasan atau teori, ada pula yang dijawab melalui pemaparan praktik yang baik (good practice) di lapangan. Misalnya, buku ini mengutip pendapat Prof. Soedjatmoko bahwa jantung sekolah berkualitas ada tiga, yakni perpustakaan, laboratorium, dan interaksi (hlm. 17-18). Perpustakaan merupakan sumber informasi yang untuk konteks saat ini sebenarnya tak dapat digantikan sepenuhnya dengan internet. Perpustakaan dalam bentuknya yang konvensional yang memuat buku-buku, majalah, dan semacamnya, pada tingkat mendasar mendorong siswa di sekolah untuk memiliki kemampuan mencari dan mengolah informasi. Tanpa kemahiran dasar ini, internet yang menyediakan informasi tak terbatas akan jauh berkurang nilainya. Internet hanya akan menjadi gudang data belaka. Malahan jika siswa—atau bahkan juga guru—langsung masuk ke dunia internet tanpa dasar kemampuan melek informasi yang cukup maka bisa saja ia terperangkap pada mentalitas instan. Jika perpustakaan berfungsi sebagai penyedia informasi, laboratorium adalah tempat siswa melakukan praktik, bereksplorasi, bereksprimen, dan meneliti. Tentu saja, laboratorium yang dimaksudkan di sini bukanlah laboratorium dalam arti sempit. Laboratorium dapat berupa alam terbuka, pasar tradisional, dan sebagainya. Satu hal yang digarisbawahi buku ini adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia sangatlah beruntung karena memiliki kondisi alam dan kondisi sosial budaya yang sangat kaya yang sebenarnya dapat menjadi laboratorium yang luar biasa maknanya bila mampu dimanfaatkan secara baik oleh guru dan siswa. Interaksi adalah unsur penting yang ketiga pada ciri sekolah berkualitas. Interaksi adalah roh yang menjadikan para pelaku di sekolah bersatu dalam semangat belajar dan meraih kehidupan yang lebih baik. Interaksi, atau juga disebut relasi, meliputi jalinan mendalam antara guru dan murid, guru dan orangtua, murid dan orangtua, termasuk juga relasi masyarakat sekolah dan pengetahuan. 178-181 | ’Anil Islam Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016 Jalinan antara para pelaku, terutama antara guru dan murid, akan memberikan sentuhan yang mengilhamkan perubahan baik pada tataran kognitif maupun sikap. Jalinan yang baik akan mengikat para pemangku kepentingan di sekolah pada misi mendasar sekolah sebagai salah satu motor penggerak peradaban. Namun demikian, dalam iklim pembelajaran yang penuh beban administrasi dan berlangsung begitu formal, interaksi yang hangat di sekolah tidak mudah kita temukan. Justru terkadang interaksi yang hangat ini ditemukan di sekolahsekolah pinggiran. Puti dalam buku ini memberi contoh sebuah sekolah di Garut, Jawa Barat, yang pada setiap Jum’at sore menggelar acara kumpul-kumpul secara guyub antara guru, perwakilan murid, orangtua, dan masyarakat, untuk membicarakan perbaikan mutu sekolah. Selain tiga hal pokok yang menjadi jantung pendidikan berkualitas tersebut, buku ini juga menyinggung tujuan pendidikan dan pembelajaran, termasuk orientasi belajar. Pada tingkat yang sederhana, proses pembelajaran diorientasikan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Pada tingkat lainnya, proses pendidikan juga diorientasikan untuk menanamkan kecintaan siswa pada ilmu. Selain itu, proses pendidikan juga dilakukan untuk membentuk sikap siswa menghadapi tantangan zaman, termasuk hidup bersama dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Demikan juga, belajar perlu diorientasikan agar mendorong siswa menjadi manusia yang terus-menerus berusaha agar lebih bermartabat, lebih kritis, lebih toleran, dan menjadi lebih baik (hlm. 90-95). Ada satu bagian dalam buku ini yang cukup menarik yang menggambarkan orientasi pembelajaran. Puti yang lulusan perguruan tinggi terkemuka dan sebelumnya juga menempuh pendidikan yang baik di lembaga unggulan merasakan bahwa ternyata keseluruhan proses pendidikan formal yang diikutinya tidak cukup berhasil mengenalkan dan menanamkan kepekaan atas realitas sosial masyarakat yang timpang. Pengalaman Puti sebagai guru honorer di sebuah sekolah pinggiran di Bandung M. Mushthafa, Jembatan untuk Pendidikan Kontekstual | 179-181 membuka dan menggugah kesadarannya bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati pendidikan berkualitas. Kesadaran akan realitas sosial yang timpang ini justru baru muncul saat Puti bekerja sebagai guru dan pendidik (hlm. 29). Dari kenyataan ini terlihat betapa orientasi dan proses pendidikan di negeri ini tampaknya memang masih belum berhasil mengarah pada model pendidikan kritis dan pendidikan kontekstual sebagaimana yang menjadi semangat pemaparan buku ini. Namun demikian, buku ini juga beusaha mengangkat praktik-praktik pendidikan yang sederhana tapi mencerahkan untuk keluar dari keterbatasan sistem persekolahan yang ada saat ini. Misalnya, Puti bertutur tentang Komunitas Sahabat Kota (KSK) di Bandung yang merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun sejumlah anak muda lokal di Bandung untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak dengan memanfaatkan berbagai potensi setempat. Komunitas yang lahir pada tahun 2007 ini percaya bahwa anak-anak belajar paling baik dari lingkungan hidup mereka. Untuk itu, komunitas ini mengajar anak-anak untuk menjelajahi kota tempat mereka tinggal dan belajar dari sana. Misalnya, mereka diajak untuk membuat peta hijau, yakni peta yang berkaitan dengan berbagai potensi dan masalah lingkungan hidup. Dari komunitas ini, pembaca bisa melihat upaya-upaya kreatif untuk mendorong anak-anak peka terhadap lingkungan dan menjadikan lingkungan sebagai pengilham dan sekaligus sumber belajar (hlm. 257). Sebagai bagian dari refleksi dari lapangan, buku ini berhasil keluar dari model pendekatan yang semata terfokus pada unsur mikro dalam proses pendidikan di sekolah dan menghindar dari pembicaraan terkait kebijakan pengurus publik. Buku ini tidak saja mengangkat isu-isu yang bersifat mikro dan personal, tapi juga secara kritis mengupas beberapa kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Misalnya, terkait wajib belajar yang dicanangkan pemerintah, buku ini mengingatkan bahwa wajib 180-181 | ’Anil Islam Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016 belajar itu yang terpenting adalah soal penerapannya, yakni bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Menurut Puti, kebijakan wajib belajar terutama bukan soal apakah 12 tahun atau 9 tahun, tapi lebih pada soal yang mendasar, yakni terkait dengan ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh warga, kualitas layanan pendidikan yang baik, dan perubahan paradigma bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara (hlm. 104-109). Dalam buku ini, Puti juga mengkritik penerapan kebijakan pendidikan inklusi yang cenderung hanya sekadar menerima murid yang berkebutuhan khusus tanpa persiapan yang cukup. Akibatnya, murid yang berkebutuhan khusus tersebut menjadi terlantar di sekolah (hlm. 35-36). Terkait berbagai hal ideal yang dibicarakan tentang dunia pendidikan, baik yang dikupas langsung dalam buku ini maupun yang dibicarakan masyarakat umum, buku ini mengingatkan bahwa, bagaimanapun, gagasan-gagasan besar tentang hal ideal dalam dunia pendidikan harus diikuti dengan kerja-kerja konkret untuk mengurus detail yang memungkinkan gagasangagasan besar tersebut dapat terwujud (hlm. 119). Buku ini berhasil mengisi ruang kosong yang ada di antara dunia akademis dalam bidang kajian pendidikan dan praktik pendidikan yang berlangsung di masyarakat. Dengan menghadirkan potret kerja-kerja pendidikan di lapangan yang dibarengi dengan refleksi kritis dan juga perbandingan dengan praktik pendidikan di tempat yang lain, dan kadang juga disorot dengan perspektif teori, buku ini berupaya untuk mengembalikan watak kritis dan kontekstual kerja pendidikan. Dengan cara ini, buku ini tampaknya cukup mampu untuk menjadi pemantik awal sebagai jembatan di antara dunia praktik dan dunia teoretis, khususnya dunia teoretis yang berkembang di lingkungan akademis di perguruan tinggi ilmu kependidikan, menuju pendidikan yang kritis dan kontekstual. Tentu saja, sebagai sebuah jembatan, buku ini tak akan banyak bernilai jika faktanya catatan-catatan dari lapangan seperti yang ada dalam buku ini tidak mendapat tempat di dunia akademis. M. Mushthafa, Jembatan untuk Pendidikan Kontekstual | 181-181 Kehadiran buku ini pada gilirannya juga menyiratkan satu pesan yang kuat bagi dunia akademis bahwa kerja-kerja akademis haruslah terus dijaga ketersambungannya dengan realitas masyarakat melalui refleksi atas aksi-aksi di lapangan. Dengan demikian, membekali kemampuan refleksi kepada para mahasiswa kependidikan atau siapa pun yang akan terjun mengabdi di dunia pendidikan sangatlah penting, karena refleksi dari lapangan ini akan menjadi sumbangan yang sangat berharga bagi dunia pendidikan. Dari sudut pandang dunia pesantren, buku ini memberi tantangan agar para pegiat pendidikan di pesantren juga mampu merefleksikan praksis yang mereka lakukan di lapangan. Kiranya sangat banyak hal menarik di dunia pendidikan pesantren yang penting untuk direfleksikan dan diangkat untuk dibagikan dengan khalayak luas. Kita mengenal sebuah buku yang sudah menjadi klasik yang ditulis oleh KH Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-Orang dari Pesantren, yang menuturkan secara renyah dan cukup reflektif dunia pendidikan pesantren yang khas. Buku ini menghidupkan kembali visi mendasar pendidikan sebagai landasan perubahan individu dan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan landasan sikap kritis dan kemampuan berpikir kontekstual. Untuk ke sana, buku ini di antaranya memaparkan praktik-praktik inspiratif dan juga gagasangagasan kritis untuk menegaskan visi mendasar pendidikan tersebut.