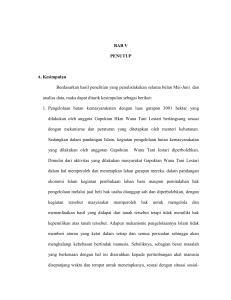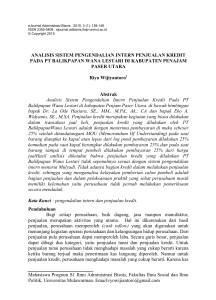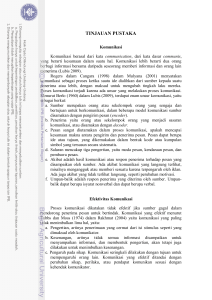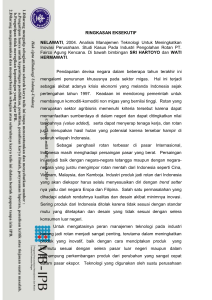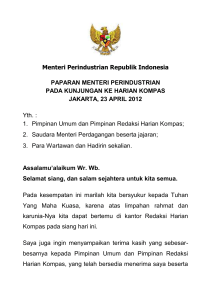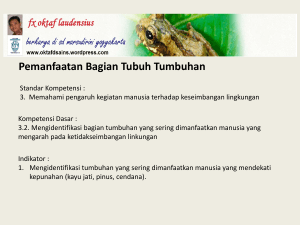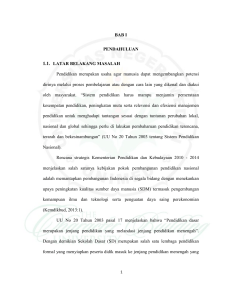Masyarakat Adat Wana Dan Kearifan Lingkungan Berbagai
advertisement

Masyarakat Adat Wana Dan Kearifan Lingkungan Oleh Jabar Lahaji Berbagai kalangan menyebut suku Wana, terutama yang hidup dan menetap di wilayah Cagar Alam Morowali, sebagai “suku terasing”. Penyebutan seperti itu sebetulnya didasarkan pada wilayah mereka yang “terisolir”, dan mengacu pada suatu keadaan ketidakberdayaan dari suku ini. Setidaknya terdapat dua ‘keuntungan’ sekaligus ‘kerugian’ bagi masyarakat Wana dengan munculnya istilah demikian yaitu; pertama, terdapat suatu upaya agar mereka kemudian menjadi tidak terisolir dan kemudian berdaya; kedua, terjadi perhatian yang luar biasa terhadap mereka. Dengan istilah terisolir itu, kemudian timbul berbagai upaya agar mereka tidak terisolir lagi yang lantas memunculkan berbagai ‘proyek prestisius’ yang antara lain melahirkan program resettlement. Tidak dapat disangkal, program itu telah menelan dana yang sangat besar, tetapi secara jujur harus dikatakan bahwa program tersebut sama sekali tidak berhasil. Perhatian yang sangat besar terhadap mereka kemudian melahirkan suatu ekses yang bisa jadi mempunyai dampak yang cukup serius dalam perkembangan evolusi masyarakatnya. Karena istilah terisolir itu pula, mereka seakan-akan menjadi tontonan, atau alat peraga hidup bagi orang-orang yang merasa lebih modern. Dalam konteks evolusi masyarkat, kehidupan masyarakat Wana sebetunya hampir di alami oleh hampir semua suku bangsa yang pernah ada di dunia. Demikianlah, dalam skala dan watak mayarakat dikenal dengan istilahistilah band, segmentary society (tribes), chiefdom, dan state. Berdasarkan Pendataan tahun 2000-2001, populasi suku Wana berjumlah 1.767 jiwa. Pola hidup suku mereka dipengaruhi oleh sistem adat yang mereka anut dengan menyandarkan hidup mereka pada hutan Adat. Penyikapan-penyikapan mereka terhadap hutan, dengan demikian, bisa dikatakan merupakan the way of life, petunjuk dalam menjalani hidup, yang memberi arah hidup orang Wana sehari-hari. Diluar hari-hari mengerjakan lahan kebun dan masa menuai tanaman, keseharian mereka dihabiskan di hutan tropis Cagar Alam Morowali. Dalam kesahajaannya, di hutan seolah-olah selalu ada hari esok yang pasti bagi orang Wana, dan mereka menyongsong pagi dengan amat ceria dan kepastian bahwa di luar sana selalu ada tersedia apa saja yang mereka butuhkan dalam hidup. Pola Hidup: Hutan, Pertanian dan Strategi Adaptif Kehidupan orang Wana sangat tergantung kepada kearifan lingkungan alam sekeliling mereka. Oleh karena itu mereka sangat mempercayai adanya ruh (spirit) yang menjaga atau memelihara setiap jengkal tanah dan hutan. Setiap kerusakan lingkungan ataupun perubahan siklus alam yang tidak berjalan sebagaimana biasanya, dipercayai sebagai tanda murkanya sang penjaga. Agar para penjaga yang memelihara lingkungan-- misalnya setiap bukit atau bagian dari hutan--tidak murka, mereka lantas memberi persembahan atau sesajen (kapongo) ketika, misalnya, mereka akan membuka lahan ladang baru. Perlengkapan kapongo terdiri atas sirih, pinang, kapur, dan tembakau, yang diletakkan pada sebuah “rumah” yang tingginya sekitar 40-50 cm dari permukaan tanah. Ketergantungan orang Wana terhadap lingkungan alam tercermin dari berbagai kapongo yang mereka lakukan. Kapongo-kapongo itu antara lain adalah: untuk menanam padi dilakukan membangunaka, membuka lading baru; momposokiopo, mengambil rotan, mangingka kapongo, meminta hujan; memperapi uja (dilaksanakan di genangan air yang ditengahnya terdapat batu), meminta matahari bersinar terang; memperapi eo (dilakukan di puncak gunung yang tinggi). Menarik bahwa untuk mendirikan rumah mereka malah tidak melakukan kapongo. Juga tidak ada aturan arah hadap, tidak ada aturan bentuk rumah seperti pada beberapa suku lainnya di Indonesia. Singkatnya, dalam mendirikan rumah orang Wana benar-benar berpatokan semata-mata pada selera belaka. Ini membuktikan bahwa cara pandang mereka terhadap lingkungan alam signifikan dibandingkan dengan tempat tinggal. Masing-masing kapongo tersebut mempunyai mantera karena kapongo dipersembahkan kepada masing-masing spirit yang melindungi kebutuhan, misalnya spirit yang menjaga hutan, yang berkuasa atas matahari, yang berkuasa atas danau, dan yang menjaga hutan. Penguasaan terhadap hal ihwal yang berhubungan dengan hutan yang tercermin dari sistem klasifikasi/kategori mereka terhadap hasil hutan sungguh mengagumkan. Untuk rotan (lauro/galu) misalnya, mereka membaginya dalam 22 (dua puluh dua) kategori yaitu: lauro epe, lauro tongisi, sambuta, nanga, (rotan batang), ngkuku, mangkaufa, yuwo, kiyufi, nanga mumu, nanga fonti, tojee, laru, siombo, lauro taipoyu,fatu, lonye, tohiti, vana, rasa, tumani yao (besar), tumani makuni, dan kulifi. Untuk bambu (balo), mereka memakai lima klasifikasi/kategori yaitu: balo fatu, balo fuyu, kojo, payu, dan balo fombo (Yayasan Sahabat Morowali pers.com). Pertanian sistem perladangan dimulai dengan penebangan hutan sekunder-memakai kapak atau parang, sama sekali bukan gergaji apalagi chain saw- sesuai dengan ukuran jenis ladang yang mereka butuhkan,--totos, bonde, ataukah tou-- dengan terlebih dahulu melaksanakan kapongo. Suku Wana jarang sekali melakukan pembersihan. Mereka kemudian juga membangunkepe pamuja kodi yaitu pondok kecil yang berfungsi sebagai tempat istirahat. Semua pekerjaan itu mereka lakukan secara gotong-royong. Tidak dilakukan penggemburan tanah sebelum dilakukan penanaman. Di wilayah budaya Wana, tidak dikenal alat yang bernama cangkul, melainkan tugal, parang, dan kapak dalam mengerjakan ladang. Tugal (sua) adalah sebatang kayu berukuran kira-kira satu setengah meter yang ujungnya runcing dengan diameter lingkaran batang yang memungkinkan dipegang. Alat ini dipakai untuk membuat lobang ke dalam tanah tempat menanam benih: bulir padi, biji kacang-kacangan, potong-potongan batang ubi kayu, biji jagung dan sebagainya. Jenis parang beragam sesuai dengan fungsi peruntukanya; parang untuk pria dewasa, pria yang masih kanak-kanak, wanita, parang untuk memaras/menebang semak belukar, parang untuk menebang pohon besar dan seterusnya. Pada umumnya orang Wana hanya mengenal dua jenis kapak, yaitu kapak yang dapat dipakai untuk memotong kayu dan yang lainnya untuk membelah. Pada umumnya parang dan kapak dibuat di Uewaju oleh seorang laki-laki yang berprofesi sebagai penempa besi. Bahan dasar besi atau besi tempa lebih disukai daripada bahan bekas per mobil yang didatangkan dari luar wilayah adat. Mereka tidak mengenal adanya lokasi penambangan bijih besi atau quarry site sebagaimana yang terjadi pada Aboriginal people di teluk Bone bagian Utara. Awal masa penanaman biasanya mulai dilakukan pada bulan Oktober setiap tahun. Jenis-jenis ladang totos, bonde, dan tou tidak dibuka secara bersamaan, tetapi lebih banyak dibuka secara berkesinambungan yaitu lebih dahulu membuka totos kemudian bonde dan terakhir tou. Terkadang pula pembukaan ladang itu dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan si pembuka ladang; misalnya seseorang hanya membutuhkan untuk membuka tou atau hanya bonde. Kebanyakan anak yang akan menjelang dewasa telah mencoba membuka dan sekaligus mengelola sendiri ladang jenis totos. Ladang jenis totos biasanya ditanami jagung, ubi kayu dan padi (pae) tiga bulan, bonde ditanami padi enam bulan, jagung, ubi kayu dan sayur, sedang tou ditanami jagung, padi enam bulan, tebu, kacang panjang, dan sayur bayam. Di Sangkeoe areal Pasongke,tou ditanami juga dengan tembakau. Kategori padi (pae) terdiri atas tiga macam yaitu pae loto atau pae meta (padi/beras hitam), pae puyu atau padi pulut (terdiri atas tiga klasifikasi yaitu pae puyu meta, pae puyu buya dan pae puyu madea atau meraa), dan pae uva yaitu padi yang menghasilkan beras putih. Menurut pengakuan orang-orang Wana, bibit jenis padi tersebut tidak didatangkan dari luar wilayah adat Wana, melainkan bibit asli lokal yang dapat diperoleh pada daerah-daerah terisolir lain seperti Langitoya, Kajumarangke, dan Kallangbatua. Lama penyimpanan bibit padi sekitar dua tahun, dan jika bibit tersebut tidak digunakan selama masa dua tahun, maka bibit itu kemudian dimakan atau dimusnahkan. Penyakit padi yang dapat dijumpai hanya ada dua jenis yaitu; pertama, daun dan batang padi menguning yang mereka sebutparinji; Kedua, daun dan batang padi menjadi hitam yang mereka sebut undo. Kedua paenyakit itu dipercaya menular melalui manusia yaitu jika ada tanaman padi yang terserang kemudian seseorang melewatinya lantas orang tersebut kemudian melewati ladang padi lainnya, maka ladang yang kedua tadi pasti akan terserang penyakit yang sama pula. Parinji dapat dibasmi dengan memarut nanas lalu airnya disiramkan pada tanaman padi, sedangkan undo dapat diobati dengan cara merendam udang selama tiga hari, lalu airnya disiramkan pada padi tersebut. Menurut penuturan orang-orang tua suku Wana, hama tikus, belalang, dan kupu-kupu tidak pernah menyerang ladang pertanian mereka sampai dengan kedatangan para transmigran yang bermukim diluar cagar alam. Pantangan bagi orang Wana membakar udang ataupun ikan gabus saat padi mulai tumbuh. Tetapi jika padi sudah mulai berbuah, kedua jenis ikan ini sudah dapat disantap lagi. Ruparupanya, terdapat kearifan di sini yakni selama penanaman padi hingga mulai bebuah, saat itulah terjadi perkembangbiakan ikan gabus dan udang. Dalam ingatan orang-orang tua suku Wana, pada tahun 1960an orang-orang Posangkelah yang mensuplai beras kepada penduduk Batubare di pesisir teluk Tomini. Bahkan orang-orang asal Baturubelah yang menjemput beras di Posangke dengan memakai rakit melalui Sungai Solato. Waktu itu, setiap bonde dapat menghasilkan sampai 300 ikat padi pertahunnya (satu ikat padi dapat menghasilkan 5 liter beras). Pada waktu itu pula, kalau diadakan maroa (pesta syukuran panen) pelaksanaannya bisa berlangsung hingga tiga hari tiga malam berturut-turut sambil makan dan minum pongas. Pada kesempatan itu, yang dibicarakan adalah melulu soal adat, soal bagaimana menanam yang baik, soal cara mengusir hama penyakit, sampai dengan menyampaikan tata cara melaksanakan kapongo kepada anak-anak muda. Masih dalam kurun waktu itu, meskipun mereka semua (pria, wanita, dewasa, maupun anak-anak) menenggak pongas sebanyak-banyaknya, tetapi tidak pernah terjadi pertengkaran di antara mereka. Sekarang sebaliknya, orang Posangkeh yang mencari beras hingga ke Batubare--dan mendapatkan kualitas beras yang rendah. Tidak hanya itu, beras kemudian bahkan menjadi ‘makanan mewah’ di Posangke. Sebelum masa tanam berlangsung, kebanyakan orangWana makan vona yakni ubi kayu yang di parut lalu diperas, dibuat dalam bentuk gumpalan, kemudian diasapi sehingga dapat bertahan cukup lama. Menjelang masa panen totos, mereka kemudian menyantap ubi kayu yang dipetik dari totos. Kemudian setelah panen bonde atau tou, barulah mereka makan nasi. Padi tiga bulan biasanya mulai ditanam pada bulan-bulan September-Oktober, sedangkan padi enam bulan biasanya ditanam pada bulan November-Desember, sehingga terdapat kesinambungan dalam perladangan. Kalau ladang besar, dilakukankapongo membangunaka (upacara persembahan yang terutama dilakukan di Posangke), tetapi jika kebun itu kecil biasanya tidak perlu membangunaka. Perlengkapan membangunaka adalah sirih, pinang, nasi, air sayur, semuanya dalam jumlah sedikit. Benda-benda tersebut diletakkan diatas daun lamoro (disebut boku kapongo) yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk wadah penyimpanan. Selain dibacakan mantera, jika Pue Allah berkenan memberikan kesuburan kepada lahan kebunnya dan menyebabkan hasil panennya melimpah, maka peladang akan memberikan lagi kapongo yang lebih banyak . Di luar kesibukan sebagai peladang, orang Wana melakukan pencarian hasil hutan sambil mengadakan perburuan. Pada umumnya hanya kaum pria yang mencari rotan karena pertimbamgan resiko, tetapi ada juga beberapa wanita yang melakukannya. Lokasi mencari rotan biasanya di sekitar areal lingkungan hidup mereka seperti di Buyu Likontovu dan Kallang Batua bagi orang Wana yang hidup di areal Kallang, sementara damar dicari di Ngoyo. Orang Uewaju lebih banyak mencari rotan di Linte, Bongka, Poontovu; jaraknya dua malam berjalan kaki dari Uewaju. Menurut orang Wana, tingkat kesulitan dan resiko yang ditanggung dalam mencari rotan lebih besar dibanding mencari damar, tetapi kebanyakan orang Wana mengabaikan hal itu oleh karena adanya pesanan ataupun jerat utang yang ditanamkan oleh middle man atau pedagang pengumpul-yang mereka sebut bos-dari kota. Di atas bos masih ada bos besar yang berkedudukan di kota sebagai pemilik modal dan tidak berhubungan secara langsung dengan orang Wana. Pola pencarian rotan dan damar yang demikian sama untuk Kajupoli, Posangke, dan Uewaju. Meskipun demikian, secara spesifik pengambilan rotan pada daerah Kajupoli lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan damar dari kedua daerah lainnya itu karena: 1) pengiriman lebih mudah melalui Sungai Morowali; 2) pada KM 2 (Morowali Tua) berdiam beberapa orang pedagang pengumpul, serta; 3) Jarak tempuhnya dengan daerah pesisir lebih dekat. Dalam aktivitas pencarian rotan, damar, ataupun hasil hutan lainnya, orang Wana terkadang juga dilakukan aktivitas perburuan. Perburuan biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu: secara aktif dan pasif. Perburuan secara pasif dilakukan dengan cara memasang jerat yang diperuntukan baik bagi hewan buruan besar (babi, rusa, dan sebagainya) maupun hewan buruan kecil (ayam hutan dan burung lainnya). Perburuan yang dilakukan secara aktif dilakukan dengan mempergunakan sumpit. Terdapat dua macam anak sumpit yang beracun dan yang tidak beracun. Anak sumpit yang beracun adalah anak sumpit yang pada bagian ujungnya yang runcing dilekatkan racun yang sangat mematikan yang disebut impo, berasal dari pohon impo. Impountuk binatang merayap diambil dari getah pohon impo yang berasal dari bagian akar, untuk binatang berkaki empat diambil dari bagian batang pohon hingga dahan, sedang impo untuk hewan yang terbang diambil dari bagian ranting hingga pucuk pohon. Meskipun tersedia peralatan perburuan, kegiatan berburu bagi orang Wana nampaknya bukan suatu pekerjaan utama. Oleh karena itu, tidak ada kegiatan atau upacara yang dilaksanakan sebelum dilakukan kegiatan perburuan. Demikianlah, big gamememang dikenal dalam kehidupan orang Wana, cuma agak jarang. Kalaupun dilakukan, bukan tujuan utama atau bukan usaha khusus. Kalau kebetulan orang Wana menjumpai hewan buruan, diucapkan syukur, kalau tidak dapat, tidak dianggap sial. Paradoks: Ekonomi Kota dan Ketidakseimbangan Sayangnya, sendi-sendi adat yang ditulis diatas kini hanya diketahui dan dijalankan oleh sebagian kecil orang Wana. Beberapa orang Wana sekarang mulai berfikir dalam kerangka "ekonomin kota", yang tentu saja berimplikasi pada terciptanya manuver untuk memperoleh keuntungan. Demikianlah kata “kejujuran” agaknya sudah mulai hilang dari ingatan mereka, demikian juga dengan kata “dosa”. Lalu, gaya hidup ekonomi kota yang cenderung konsumeris secara tidak langsung akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Bagaimana tidak, desakan untuk segera membayar utang, desakan untuk memiliki barang, akan menyebabkan keengganan menggarap lahan yang dirasakan membutuhkan waktu yang cukup lama. Menggarap hasil hutan dirasakan akan segera memenuhi kebutuhan, sehingga kebutuhan itu menjadi prioritas. Tebang pilih bukan tujuan lagi. Segala sesuatu yang berada di hutan yang dapat dikonversikan menjadi lembaran-lembaran uang menjadi prioritas. Akibat ekspansi "ekonomi kota" yang tercermin dari gaya hidup mereka beberapa di antaranya dapat dicontohkan disini. Tidak sulit untuk mencari tape recorder berkapasitas besar di Kajupoli. Setiap pendatang akan segera disuguhi oleh musik ataupun dendang lagu dangdut Bugis-Makasar di situ, yang disertai dengan dentuman bas dan gemerincingan treble yang kuat. Tidak sulit juga untuk mencari pakaian jeans dari segala merk yang mereka pakai, mulai dari Lepis (bukan Levi’s), Calvin Claine, Lea, hingga Levi’s yang dipasangkan dengan sarung. Cukup sulit pula menemukan seorang Wana tanpa jam melingkar di tangan saat diadakan suatu pesta, terutama di Kajupoli. Tetapi, jangan coba bertanya apakah mereka mengerti tentang lirik lagu yang didendangkan, jangan pula bertanya tentang waktu kepada pemilik jam tangan, sebab mereka sama sekali tidak mengerti tentang sistem waktu dua puluh empat jam!. Sungguh suatu “gaya hidup etalase” yang kini mulai melanda mereka! Bagi orang Wana, terutama pada daerah transisi antara pegunungan dan pesisir, tape recorder yang membutuhkan baterai paling banyak adalah yang paling bagus, atau dengan kata lain kecanggihan suatu tape recorder ditentukan oleh banyaknya baterai yang dibutuhkan. Semakin mahal suatu barang, semakin baik pula dia. Harga rata-rata tape recorder yang mereka bayar, misalnya, adalah empat hingga enam kali lebih tinggi dibandingkan harga pasar sebenarnya. Biasaanya harga itu tidak dibayar tunai melainkan kebanyakan diangsur dengan subtitusi utang hasil hutan. Keterpurukan kebanyakan orang Wana disebabkan adanya ketergantungan ekonomi kepada middle man yang disertai arus informasi teknologi yang bias. Besarnya desakan kebutuhan untuk membayar hutang terkadang menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan berbagai kapongo yang mesti dilakukan dalam suatu kegiatan, sehingga keseimbangan spiritual menjadi terganggu. Akibatnya, orang Wana, terutama yang hidup dipesisir, terperangkap dalam paradoks dunia spiritual dan materialistik. Dunia spritual diwakili oleh sistem budaya yang mereka anut, sedang dunia materialistik diwakili oleh ekonomi kota. Kehidupan transisional ini, walau bagaimanapun, dengan belajar dari sejarah perkembangan masyarakat yang pernah terjadi, akan berlangsung dengan selang waktu yang amat panjang, dan akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan kultural orang Wana. Padahal sering sekali diucapkan bahwa kebudayaan Indonesia dibangun dari berbagai kebudayaan lokal, oleh karenanya kebudayaan lokal itu harus tetap dipelihara, dilestarikan. Mudah-mudahan ucapan itu bukan semata retrorika politik wawasan nusantara belaka, bukan pula lips service, tetapi diwujudkan, dengan membuat kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat Wana dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada satu dua orang pemilik modal. Beberapa kasus di dunia menunjukkan adanya klaim kelompok Aboriginal people terhadap kebijakan pemerintah atas terjadinya apa yang mereka sebut the lost generation. Kita tidak menghendaki hal itu terjadi bukan? Hari Esok Suku Wana: Cultural Heritage Site Rupa-rupanya, tudingan bahwa kehadiran orang Wana di Cagar Alam Morowali akan merusak lingkungan cagar alam akan menjadi benar jika dilihat dari perilaku orang Wana pesisir belakangan ini. Tapi jangan lupa bahwa perilaku itu tercipta sebagai akibat dari perkenalan mereka dengan ekonomi kota. Penguatan adat dan pengembalian pengetahuan asli yang akan menyadarkan mereka tentang jatidiri mereka, tentang hak-hak mereka adalah suatu alternatif yang mungkin bisa dipakai untuk menjembatani hal ini. Demikianlah, cover multiple sides dan kearifan sangat mutlak diperlukan dalam menghadapi orang Wana. Jika tidak, suku Wana dengan segala bentuk keunikan budayanya hanya akan menjadi ‘sejarah’ belaka, padahal kemungkinan besar suku ini bisa menjadi salah satu suku yang dapat dijadikan sebagai suatu model etnografi dalam menggambarkan sejarah peradaban umat manusia. Dengan kata lain menciptakan cultural heritage site pada wilayah adat suku Wana adalah jawaban yang dianggap paling masuk akal. Penulis adalah Direktur Yayasan Sahabat Morowali Sulawesi Tengah