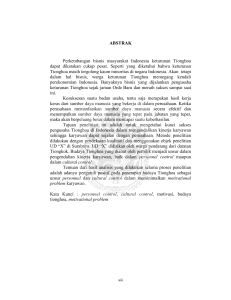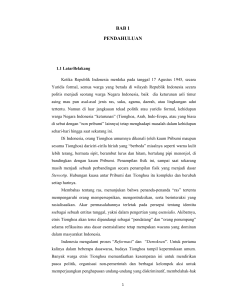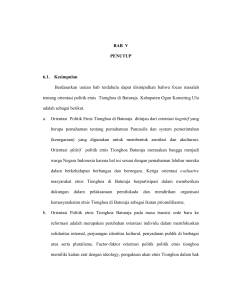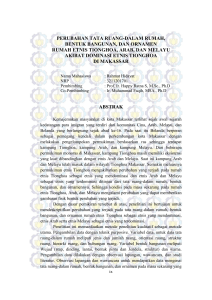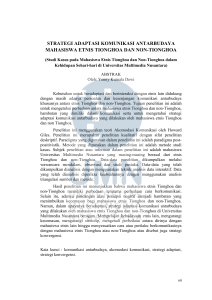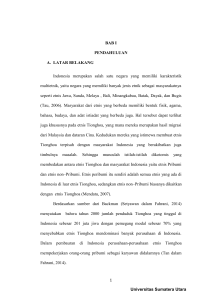1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Identitas
advertisement

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Identitas bagi kebanyakan orang dipahami sebagai hal yang umum, sekaligus bersifat pribadi karena terkait dengan identifikasi diri. Identitas etnis, dalam hal ini identitas etnis Tionghoa1, ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Selain karena ia merupakan hasil proses „pelabelan politis‟ yang mempunyai sejarah yang panjang, identitas Tionghoa sejak awal penciptaannya juga berjalin berkelindan dengan konsep ras, kelas dan agama. Hal ini menyebabkan identitas Tionghoa tidak saja unik, namun sekaligus kompleks. Secara lebih spesifik, bisa dikatakan bahwa keunikan tersebut muncul karena ia terbentuk dalam konteks sejarah Indonesia yang berbeda dengan sejarah Negara-negara lain. Selain itu, kompleksitas etnis Tionghoa juga terjadi karena terbentuk melalui proses dialogis yang panjang dengan kelompok-kelomok lain (Eropa dan Pribumi) dalam konteks sosial ekonomi, politik dan kultutral. Karena itu, “masalah Tionghoa” bukan merupakan semata-mata warisan kolonial, sebab yang disebut “Etnis Tionghoa” dan “Pribumi” pada tahap selanjutnya juga berperan menguatkan sekat-sekat rasial warisan kolonial itu. Fenomena tersebut misalnya, bisa kita jumpai dalam konsep keindonesiaan yang sejak awal didefinisikan sebagai “kepribumian” dan bukan 1 Penggunaan kata “Cina” dan “Tionghoa” secara bergantian sepanjang tulisan ini digunakan secara semantik, tanpa ada tendensi politik apapun. Karena walau bagaimanapun penulis menyadari bahwa penggunanaan kedua kata tersebut secara politis, akan memberikan makna yang berbeda. Bagi sebagian orang Tionghoa, penggunaan kata “Cina”, alih-alih “Tionghoa” bisa bermakna penghinaan. 1 “kewarganegaraan”. Akibatnya, tidak seorang (Tionghoa) pun bisa benar-benar menjadi Indonesia tanpa terlebih dahulu meninggalkan ke-Tionghoa-annya, sesuatu yang jelas mustahil. Karenanya, orang Tionghoa yang telah berstatus warga negara Indonesia pun tetap dipandang sebagai “orang asing” atau “pendatang” (Chang Yau Hoon, 2012). Di sisi lain, perilaku kultural orang Tionghoa sendiri, dalam batas tertentu sebagaimana dikemukakan Chang, mengentalkan streotip Tionghoa di mata pribumi sebagai “orang asing”. Mereka distigmakan secara sosial sebagai eksklusif, asosial dan kaya. Menurut Araya dkk. (2002), prasangka terhadap pihak lain, mudah muncul ketika invividu memiliki referensi-referensi inisial yang sudah tertanam kuat dalam skema kognitifnya. Hal inilah yang akan membentuk bank data yang tersusun dari ciri-ciri pihak terkait, sehingga sewaktu-waktu ketika ada peristiwa yang mengaktifkannya, misalnya kerusuhan massa, maka dalam sekejap semua ciri-ciri itu terlintas dalam kognisi. Serangkaian tragedi sejarah yang menimpa orang-orang Tionghoa di Indonesia, secara langsung memengaruhi proses pencarian identitas mereka (Suryadinata, 2002: 32). Mereka merasa berada di persimpangan jalan, kebingungan harus memilih jalan mana yang dapat mengantarkan mereka untuk lebih bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Bachrun dan Hartanto (2001) melihat krisis identitas di kalangan orang Tionghoa dikarenakan segala upaya yang mereka lakukan untuk bisa diterima sebagai orang Indonesia hancur berantakan dalam waktu singkat, seiring meletusnya tragedi Mei 1998. Merespons situasi pasca-1998, Thung Ju Lan (1998) menemukan setidaknya ada empat orientasi pembentukan identitas orang-orang Tionghoa di Indonesia. 2 Pertama, mereka menganggap bahwa dirinya adalah orang Tionghoa dan akan selalu menjadi orang Tionghoa. Kedua, mereka yang merasa telah berhasil berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Ketiga, mereka yang merasa telah mampu melampaui batas-batas etnis, budaya dan negara. Keempat, mereka yang menolak proses identifikasi diri berdasarkan motif-motif budaya dan politik. Susetyo (2002), mencoba melihat proses pencarian identitas yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia dan berusaha menariknya ke persoalan yang lebih mendasar, yakni dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa misalnya, perbedaan status etnis antarwarga diberlakukan secara tegas. Orang-orang Eropa menempati kelas sosial tertinggi dan berhak mendapatkan fasilitas publik yang paling baik. Orang Tionghoa yang digolongkan sebagai “Timur Asing” (Vreemde Oosterlingen), berada di posisi kedua bersama orang Arab dan India. Sementara orang pribumi (inlander) adalah pihak yang paling dirugikan karena berada pada kelas sosial terendah. Sebagai kelas kedua di masyarakat, orang-orang Tionghoa menunjukkan kecenderungan merapat kepada penguasa, tentu dengan maksud mengamankan posisi sosial dan ekonomi mereka. Sikap seperti ini semakin terlihat terutama pasca tragedi 1740 di Batavia.2 Peristiwa tersebut telah meninggalkan trauma mendalam bagi mereka, sehingga 2 Dalam beberapa literatur, perisitiwa ini juga dikenal sebagai„Tragedi Kali Angke‟.Dalam tragedi ini, tidak kurang dari 10.000 orang Tionghoa yang tinggal di batavia dibantai secara sadis oleh penguasa VOC. Pembantaian dipicu oleh protes yang dilakukan oleh warga Tionghoa atas pemberlakuan surat ijin tinggal berbatas bagi mereka yang menetap baik di dalam dan di luar tembok Batavia. Aturan tersebut membuat warga Tionghoa mengalami kebangkrutan, bahkan banyak diantara pedagang Tionghoa beralih profesi menjadi buruh kasar akibat tidak kuat membayar pajak yang diberlakukan pemerintahan VOC Belanda. Kemudian muncul ketidakpuasan yang dilanjutkan dengan perlawan terhadap pemerintahan VOC sehingga sejak September 1740 mulai terjadi kerusuhan-kerusuhan kecil di luar komplek tembok Batavia yang dilakukan oleh warga Tionghoa. Aksi perlawanan akhirnya memuncak pada 7 Oktober 1740. Saat itu, lebih dari 500 orang Tionghoa dari berbagai penjuru berkumpul guna melakukan penyerangan ke Kompleks Benteng Batavia. Setelah sebelumnya menghancurkan pos-pos penjagaan VOC di wilayah Jatinegara, Tangerang dan Tanah Abang secara bersamaan. Lalu, 8 Oktober 1740, kerusuhan terjadi disemua pintu masuk Benteng Batavia. Ratusan etnis Tionghoa yang berusaha masuk dihadang pasukan VOC dibawah pimpinan Van Imhoff. 3 wajar saja jika sikap mereka di tahun-tahun setelahnya menjadi lebih lunak di hadapan penguasa kolonial. Secara sistematis, mereka mulai melakukan mobilitas sosial, misalnya dengan mengikuti pendidikan ala Eropa, mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Eropa hingga memeluk agama Kristen atau Katolik yang nota bene merupakan agama mayoritas orang Eropa. Di era kemerdekaan, contoh lain dari mobilitas ini bisa dilihat pada kelompok-kelompok yang memperjuangkan terwujudnya asimilasi menyeluruh [total assimilation] dengan penduduk pribumi. Satu yang paling mengemuka adalah anjuran untuk memeluk agama Islam di kalangan orang-orang Tionghoa Indonesia. Menurut Junus Jahja, salah seorang tokoh utama asimilasi, kondisi pasca peristiwa 1965 merupakan peluang bagi orang-orang Tionghoa untuk melakukan pembauran. Pembauran yang lebih tepat untuk konteks Indonesia, lanjut Jahja, adalah dengan memeluk agam Islam, karena tidak bisa dipungkiri, Islam merupakan representasi paling nampak dari identitas golongan pribumi Indonesia. Asumsinya, dengan memeluk Islam, orang-orang Tionghoa tentu akan lebih mudah diterima oleh golongan pribumi, karena mereka telah memiliki kesamaan identitas sebagai umat Islam (Jahja, 1982: 15). Demi memperkuat pendapatnya, mereka kemudian merujuk data sejarah yang mengungkapkan bahwa keberadaan orang-orang Tionghoa Muslim di Indonesia, sebenarnya bukanlah fenomena baru. Jauh sebelum Belanda menjajah negeri ini, orang-orang Tionghoa Muslim telah terlebih dahulu hadir dan lambat laun membangun kawasan-kawasan koloni di sepanjang kota-kota pesisir di Nusantara. Mereka umumnya para imigran laki-laki yang datang bergelombang 4 dalam kelompok-kelompok kecil, digerakkan oleh motif memperbaiki taraf hidup, menyelamatkan diri dari ancaman bencana alam, atau menghindari konflik politik di negeri mereka. Kebanyakan imigran ini datang dari daerah-daerah seperti Guanzhou dan Guangdong. Kehadiran mereka umumnya disambut baik oleh penduduk Nusantara. Bahkan dari interaksi tersebut, terjadi perkawinan campur dengan perempuan-perempuan pribumi yang melahirkan keturunan yang disebut generasi Tionghoa peranakan (Jacobson, 2003). Sejarah di atas membuktikan bahwa orang-orang Tionghoa Muslim jaman dulu sudah berhasil melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga Belanda menginjakkan kakinya di Nusantara. Hubungan harmonis antara orang-orang Tionghoa dan penduduk pribumi praktis berakhir setelah Belanda menerapkan politik pecah belah (devide et impera) untuk merusak hubungan keduanya. Kebijakan inilah yang berangsur-angsur membuat etnis Tionghoa terpisah dengan penduduk pribumi (Susetyo, 2002). Kebijakan diskriminatif tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan yang memasukkan orang-orang Tionghoa ke dalam kelompok pribumi (inlader) jika mereka ketahuan mempraktekkan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat pribumi, baik itu tradisi, adat istiadat, maupun memeluk agama (Islam) yang dianut oleh kelompok pribumi. Dengan demikian, orang-orang Tionghoa yang memeluk Islam secara otomatis akan diturunkan derajatnya menjadi sama dengan penduduk pribumi (The Siauw Giap, 1993: 7275). 5 Konsekwensi lanjutan dari peraturan tersebut adalah kecenderungan di kalangan orang-orang Tionghoa non Muslim untuk tidak mengakui anggota keluarga mereka yang memeluk Islam, karena Islam dianggap identik dengan penduduk pribumi yang bodoh, miskin dan terbelakang (Ali, 2007). Kondisi inilah yang dianggap sebagai awal dari merenggangnya hubungan antara masyarakat pribumi dan golongan Tionghoa dan sekaligus membentuk pola yang cenderung antagonistik. Beragam stereotip negatif tentang islam yang dikaitkan dengan penduduk pribumi hingga sekarang masih berkembang di kalangan orang-orang Tionghoa, sebut saja terbelakang, miskin, bodoh, pemalas, tidak toleran dan sebagainya (Jacobson, 2003). Karena faktor itu pula kebanyakan keluarga Tionghoa di Indonesia kurang simpatik terhadap anggota keluarga mereka yang masuk Islambahkan sering kali berujung pada penolakan sebagai bagian dari keluarga sendiri (The Siauw Giap, 1993: 83-84). Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sejarah keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia merupakan sejarah perjuangan untuk mendapat pengakuan dan penerimaan dari masyarakat pribumi. Sebagai kelompok pendatang, mereka dituntut mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang berlaku di negara baru yang mereka diami agar kehadirannya bisa diterima oleh masyarakat pribumi. Salah satunya adalah dengan memeluk agama Islam. Ketertarikan saya untuk meneliti keberadaan etnis Tionghoa muslim di Makassar juga didasarkan pada asumsi awal bahwa etnis Tionghoa muslim telah mengalami stereotip berlapis. Pertama, sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari kebudayaan Tionghoa, mereka tetap akan dianggap sebagai “orang asing” atau 6 “pendatang” oleh Pribumi. Akibatnya, meskipun mereka telah menjadi “anggota” kelompok etnis pribumi dengan memeluk agama Islam sebagai agama mayoritas, mereka belum benar-benar dipandang menjadi Indonesia. Kedua, dengan berpindah keyakinan [agama], mereka telah dianggap bukan merupakan bagian dari keluarga besar etnis Tionghoa. Dengan kata lain, mereka dianggap telah menanggalkan identitas Tionghoa, terutama yang berkaitan dengan agama dan budaya leluhur. Ali (2007) menyebut mereka ini sebagai “minoritas” dari yang “minoritas” (a minority’s minority). Sebagai orang Tionghoa mereka adalah minoritas di hadapan mayoritas penduduk pribumi. Sementara sebagai Muslim mereka menjadi minoritas di tengah-tengah golonga mereka yang umumnya nonmuslim. 1.2. Rumusan Masalah Bertitiktolak dari paparan latar belakang di atas, maka problematisasi yang diajukan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana etnis Tionghoa muslim mengonstruksi identitas mereka di hadapan orang Tionghoa non muslim dan orang muslim non Tionghoa? Selanjutnya untuk mempertajam rumusan masalah tersebut, peneliti akan menguraikannya menjadi sub-sub pertanyaan sebagai berikut: Sejak kapan komunitas Tionghoa Muslim ada di Makassar? Apa saja yang mendorong munculnya komunitas muslim tersebut? Bagaimana orang Tionghoa muslim di Makassar menampilkan identitas keislamannya dalam kehidupan sehari-hari? 7 Bagaimana interaksi Tionghoa muslim dengan sesama Tionghoa non muslim dan dengan sesama muslim non Tionghoa? 1.3. Tujuan Penelitian Sebagaimana pernyataan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan pertanyaan tersebut, yakni dengan mengurai ekspresi identitas keislaman etnis Tionghoa muslim yang ada di Makassar. 1.3.1 Manfaat Penelitian Manfaat teoritis (akademis) Riset ini diharapkan dapat mengungkap sekaligus menjelaskan bentuk akulturasi antara Tionghoa Muslim dan Muslim non Tionghoa, di mana akulturasi yang terjadi merupakan bentuk akulturasi dua lapis. Pada lapis pertama, Tionghoa Muslim mengakulturasikan antara keislaman dengan ketionghoaan. Pada lapis kedua, keislaman dan ketionghoaan yang telah terakulutrasi itu, diakulturasi kembali dengan budaya masyarakat setempat. Manfaat lain kajian ini adalah sebagai wacana yang diharapkan akan memperkaya perspektif dengan warna yang lebih dekat pada ranah cultural studies. Manfaat Praktis Selama ini, kajian mengenai keberadaan etnis Tionghoa muslim, belum banyak menarik minat para peneliti. Padahal peran dan keberadaan mereka 8 bisa menjembatani terbangunnya harmonisasi yang terkait dengan isu rasial. Tentunya dengan riset ini, diharapkan akan membuka wacana bagi para pemangku kebijakan dan pihak terkait lainnya. 1.4. Tinjauan Pustaka Kajian tentang etnis Tionghoa di Makassar sudah banyak dilakukan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi. Namun sejauh pengamatan penulis, sangat sedikit penelitian yang benar-benar fokus mengkaji keberadaan etnis Tionghoa Muslim dalam perspektif cultural studies. Penelitian yang mengambil topik etnis Tionghoa Muslim itu diantaranya, dilakukan oleh Aminuddin Ram yang berjudul: Alih Agama di Kalangan Etnik Tionghoa: Studi Kasus Mualaf Tionghoa di Makassar. Penelitian ini mengeksplorasi proses alih agama di kalangan etnik Tionghoa dengan berfokus pada aspek tahapan, motif, tipe alih agama, dan orientasi nilai budaya mualaf Tionghoa serta konformitasnya dengan nilai budaya Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konteks makro dan konteks mikro sangat besar pengaruhnya terhadap proses alih agama di kalangan mualaf Tionghoa. Pengaruh tersebut bisa bersifat mendorong, namun bisa pula bersifat menghambat. Penelitian ini juga mengungkap bahwa mayoritas mualaf Tionghoa dapat digolongkan sebagai pencari agama aktif, yang didorong oleh motif intelektual. Penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa pertimbangan rasional juga mempengaruhi para mualaf dalam menentukan sikap. Hampir semua mualaf tersebut termasuk dalam kategori tipe transisi tradisi dan pada tahap pasca 9 komitmen terjadi transformasi ke tipe intensifikasi. Kajian ini pun menunjukkan tingkat konformitas orientasi nilai budaya mualaf Tionghoa dan nilai budaya Islam, yang berada pada kedudukan tinggi. Penelitian lain yang mengangkat topik serupa dilakukan oleh Afthonul Afif berjudul Identitas Tionghoa Muslim Indonesia:Pergulatan Mencari Jati Diri. Dengan pendekatan psikologis, hasil kajian ini menunjukkan bahwa komnuitas Tionghoa muslim tidak homogen. Studi Afif ini menegaskan bahwa dalam komunitas muslim Tionghoa, berbagai variasi muncul dan berkembang sedemikian massifnya, sehingga mereka tidak bisa dikatakan monolitik. Sebagai entitas yang tidak homogen, dalam kehidupan sehari-hari, mereka tersegragasi ke dalam kategori-kategori yang beragam, berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial-budaya, rentang usia, gender, pendidikan, tempat tinggal dan sebagainya. Dengan demikian, sungguh gegabah jika kemudian mereka dipandang sebagai kelompok yang membawa beban sosial dan ekspresi identitas yang sama. Dengan begitu, cara pandang ini, sekaligus telah berkontribusi membongkar prasangka tak berdasar tentang etnis Tionghoa di Indonesia. Namun demikian, penentuan konteks situasi dan pelibatan pihak yang diteliti dengan sendirinya ikut memberikan batasan-batasan tertentu, sehingga tidak merepresentasikan kondisi golongan Etnis Tionghoa Muslim Indonesia secara keseluruhan. Dengan kata lain, kajian tersebut belum memberikan pemahaman dan penjelasan yang memadai mengenai proses dan dinamika pembentukan identitas golongan Tionghoa Muslim secara menyeluruh. Begitu pun penggunaan perspektif teoretis dan metode tertentu yang pada kenyataannya 10 juga telah menghasilkan jenis temuan yang lebih spesifik yang kurang mampu menjelaskan fenomena di luar kerangka tersebut. Studi lain tentang etnis Tionghoa muslim juga dilakukan oleh Rezza Maulana. Dengan menyorot keberadaan Tionghoa muslim di Yogyakarta, studi Rezza ini menunjukkan munculnya fenomena “Tionghoa Muslim” yang signifikan, dalam arti orang Tionghoa yang memeluk islam, namun pada saat yang sama, mempertahankan bahkan menonjolkan identitas ke-Tionghoa-annya. Fakta unik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perayaan Imlek di masjid yang dimulai pada 2005 (Maulana: 2010), disertai tanggapan beragam muslim nonTionghoa, ikhwal ritual “hibrid” tersebut. Spirit dari fenomena seperti ini bisa pula ditemui pada beberapa masjid yang didirikan oleh beberapa pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di beberapa wilayah di Indonesia. Alih-alih memberinya nama yang berbau Arab, masjid tersebut malah diberi nama “Muhammad Cheng Ho”, nama yang mengacu pada tokoh muslim Tiongkok yang melakukan muhibah ke Nusantara beberapa abad silam. Pemilihan nama sekaligus arsitektur masjid yang mengacu pada masjid di Beijing ini, seolah hendak menegaskan identitas ke-Tionghoa-an para pendirinya (Kwartanada dalam Maulana, 2010: 19). Studi ini juga mengkonfirmasi bahwa situasi dan perkembangan sosial masyarakat Cina di tanah leluhur mempengaruhi situasi orang-orang Cina (Huaren) yang sudah menetap di tanah rantau, dalam batas tertentu3. Meskipun 3 Hua-jin (Hokkian) atau Hua-ren(Mandarin) adalah istilah untuk menyebut seluruh orang keturunan Cina dimanapun mereka berada, tanpa memandang kewarganegaraan. Sebelum Tiongkok mengubah kebijakannya terkait kewarganegaraan, seluruh warga keturunan Tionghoa di seluruh dunia, diklaim sebagai warga negaranya. Orang-orang Tionghoa di Indonesia yang telah melepas kewarganegaraan RRT mereka dapat disebut Huaren, Huayi atau Waiji Huaren, namun tidak dapat lagi disebut Hua-kiao atau Hua-qiao. Dalam bukunya “Hoakiau di Indonesia”, Prammoedya Ananta Toer menggunakan 11 responnya bisa sangat berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi sosial politik setempat. Secara umum, kajian ini juga menjelaskan beberapa momentum penting bagi hubungan dan perkembangan orang Tionghoa pada umumnya dan khususnya Tionghoa muslim di Yogyakarta. Aspek kehidupan orang Tionghoa muslim, seperti profesi, aktivitas sosial, organisasi dan pendidikan, juga dibahas dalam kajian ini, yang berbasis pada pengalaman individu dan kecenderungan orang Tionghoha muslim dalam menyikapi hidup. Berbagai pengalaman subjektif yang muncul, setidaknya membentuk pengalaman intersubjektif yang pada gilirannya bergerak menuju sebuah tataran sosiohistoris faktual dan kontekstual, khas Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Sumanto Al Qurtubi tentang Cina dan Proses Islamisasi Jawa, juga menarik untuk dicermati. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, Sumanto menunjukkan upaya sistematis rejim penguasa yang berusaha membungkam fakta historis Cina Islam nusantara, di jawa khususnya. Sumanto menyebut pembungkaman terhadap sejarah dan peran Cina Islam begitu efektif, sehingga memunculkan semacam anomali bahwa keberadaan Cina Islam merupakan fenomena asing, aneh dan berasal dari dunia lain (Al Qurtubi, 2003). Selain penelitian yang dilakukan oleh para sarjana non-Tionghoa di atas, ada pula beberapa penelitian tentang Tionghoa muslim yang dilakukan oleh sarjana Tionghoa, diantaranya adalah penelitian Wai Weng Hew yakni, “Negotiating Etnicity and Religiosity: Chinese Muslim Identities in Post New kata “Hoakiau”secara inovatif, yang berasal dari sitilah Tionghoa yang muncul pada masa itu. Menurut Pram, Hoakiau di Indonesia adalah semua warga keturunan yang lahir di Indonesia. Adapun Benny G Setiono menyebut bahwa Hoakiau adalah semua warga Negara Tiongkok yang tinggal di Negara-negara di luar daratan Tiongkok. Sedangkan Huaren adalah orang-orang yang nenek moyangnya berasal dari daratan Tiongkok, tetapi telah menjadi warga Negara di Negara-negara tempat mereka tinggal. Khusus untuk orang-orang Tionghoa di Indonesia, Benny menybutnya sebagai Huayi. 12 Order Indonesia, (2011)” dan “Expressing Chinese, Marketing Islam (2012)”. Dalam penelitian pertamanya, Hew menguraikan dan menganalisis munculnya identitas budaya Cina Muslim pasca Orde Baru di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas, jumlah Tionghoa Muslim relatif kecil, namun dengan mengkaji identitas mereka dapat membantu kita untuk lebih memahami „kebangkitan Islam‟ dan „euforia Cina‟ di Indonesia saat ini, setidaknya pasca era Orde Baru. Hal yang akan memperluas wawasan dan pemahaman kita di tengah keterbatasan kosmopolitanisme etnis dan agama. Ada tiga poin penting yang menjadi titik tekan penelitian ini. Pertama, kemunculan budaya Tionghoa Muslim mencerminkan penerimaan budaya Tionghoa dalam masyarakat Indonesia, dan toleransi Islam terhadap ekspresi budaya yang berbeda. Kedua, meskipun dicakup oleh stereotip etnis dan konservatisme agama, budaya Tionghoa Muslim merangkul semacam bentuk keterbatasan ketionghoaan yang inklusif dan Islam kosmopolitan, di mana penegasan identitas Tionghoa dan religiusitas Islam tidak selalu berarti pemisahan rasial dan pengucilan agama. Ketiga, budaya Tionghoa Muslim mendamaikan ketidaksesuaian yang dirasakan antara Islam dan ke-tionghoa-an, serta membuka lebih banyak ruang untuk kontestasi identitas, meskipun tidak selalu ditempatkan dalam konteks wacana islam yang pluralis. Kendati demikian, temuan lain dari penelitian ini juga mengungkap adanya paradoks dalam proses negosiasi etnisitas dan religiusitas di kalangan Tionghoa Muslim. Di satu sisi, terjadi peningkatan penerimaan keragaman budaya dan agama di antara banyak pemimpin muslim, namun di sisi lain, ada juga 13 peningkatan intoleransi dari proses pembauran agama dan perbedaan intra-agama dalam beberapa bagian dari masyarakat muslim Indonesia. Secara umum, penelitian ini menggunakan konsep kesalehan fleksibel untuk memeriksa mencairnya religiusitas Islam dan beberapa konsep identifikasi untuk mengungkap pergeseran nilai-nilai etnisitas di kalangan mualaf Tionghoa Muslim, sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Sedangkan dalam “Expressing Chinese, Marketing Islam”, Hew lebih menyorot perihal penggunaan simbol-simbol ke-tionghoa-an oleh para penceramah yang nota bene adalah etnis Tionghoa yang berpindah agama ke Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara proses komodifikasi dalam hal penampilan identitas di ruang publik dan penampilan identitas keseharian para penceramah tersebut. Dengan kata lain, mereka (penceramah/ulama) telah “menjual” ketionghoaan, namun tidak hidup dengan cara-cara yang lazim dipakai oleh orang Tionghoa pada umumnya. Sebagaimana yang digambarakan oleh Hew dalam penelitian ini bahwa tiga dari lima penceramah, yakni Koko Lim, Tan Mei Hwa dan Anton Medan, secara sadar menggunakan identitas ketionghoaan dan keislaman secara bersamaan demi menarik minat penonton. Kombinasi elemen Tionghoa dan Islam dalam berceramah, menurut Hew, bisa dibaca sebagai sebuah bentuk “penampilan hybrid” antara ke-tionghoa-an dan keislaman yang merupakan bentuk penggabungan yang disengaja, meski tidak selalu mencerminkan identitas keseharian mereka. 14 Dalam hal membangun citra pemberitaan terkait keulamaan, mereka memilih untuk menunjukkan keseharian mereka sebagai figur yang “lebih muslim dibanding muslim Indonesia yang lain” dan “lebih cina dibanding cina non muslim yang lain”. Alih-alih menunjukkan jati diri, mereka malah menampilkan sebuah pesona publik dengan simbol-simbol atau atribut yang berhubungan dengan ke-cinaa-an, semisal pakaian tradisional cina. Denga kata lain, mereka selalu belajar untuk menampilkan kecinaan seotentik mungkin dan di saat bersamaan juga menampilkan kesalehan sebagai muslim. Tanpa disadari, proses inilah yang kerap bermuara pada esensialisasi idenitas budaya (Tionghoa) dan berkontribusi pula terhadap sebuah pemahaman kritis islam. Sarjana Tionghoa lain yang penelitiannya berkaitan dengan wacana Tionghoa muslim adalah Syuan-yuan Chiou. Dalam “A Controversy surrounding Chinese Indonesian Muslim: Practice of Imlek Salat in Central Java”, Chiou menemukan bahwa ekspresi keislaman bagi para Tionghoa Muslim ini, terbagi dalam dua bentuk. Pertama, penggunaan argumen historis untuk menemukan warisan sejarah dari Tiongoha Muslim dalam narasi sejarah makro islamisasi di Jawa. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan sejarah muslim Cina pada abad kelima belas dan abad keenam belas. Kedua, Tionghoa Muslim di Indonesia mulai mempraktekkan islam dalam contoh yang konkrit. Hal ini mislanya mereka lakukan dengan membangun masjid yang bergaya khas "Cina". Mereka juga memainkan musik populer islami, nashid, dengan lirik mandarin dan berpakaian khas Cina. Mereka juga mulai mewacanakan ritual baru dalam ibadah agam Islam dengan ritual yang berhubungan dengan terapi kesehatan yang ada di daratan 15 Cina serta penggunaan salat sebagai ritual umum untuk merayakan tahun baru Cina, yang dikenal secara lokal di Indonesia sebagai Imlek. Praktik salat sebagai bagian dari perayaan selama tahun baru Cina inilah yang disebut sebagai “salat imlek”. Penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa perdebatan seputar salat imlek, menyebabkan kalangan Tionghoa Muslim mengalami kesulitan untuk menentukan pandangan mana yang pantas untuk diadopsi, mengingat begitu banyak kontroversi yang terlibat di dalam perdebatan perihal salat imlek. Selain itu, kalangan Tionghoa Muslim sendiri harus menghadapi tekanan, di mana mereka benar-benar “di-liyankan” oleh kalangan Islam mayoritas (pribumi). Hal ini dikarenakan meningkatnya protes kalangan Islam pribumi untuk beberapa aspek dari perayaan Imlek yang didasarkan pada ide-ide keagamaan Khong Hu Chu. Sebagai sebuah etnik minoritas yang menganut agama mayoritas, cina muslim indonesia harus menghadapi kritik, bahkan lebih parah ketika ritual mereka semisal „salat imlek‟ tersebut berlangsung dalam masyarakat mayoritas muslim yang tidak toleran terhadap praktik ritual sinkretis di dalam agama Islam. Ada pun penelitian yang dilakukan oleh Darwin Darmawan (2012) dengan topik “Identitas Hibrid Orang Cina” bisa dikatakan lebih memiliki kedekatan dengan ranah cultural studies, meski fokusnya mengkaji keberadaan komunitas Cina Kristen. Dengan menggunakan perspektif non esensialis tentang identitas, serta sejumlah konsep dalam teori-teori poskolonial, misalnya seperti „hibriditas‟, „ruang ketiga‟ dan „ambivalensi‟, Darwin menjelaskan pokok perkara yang menjadi fokus penelitiannya. Identitas dalam kajian Darwin, tidak hanya dipahami 16 sebagai suatu “sense of self” yang terberi, alami dan diterima begitu saja; namun di sisi lain, identitas juga tidak dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya dikonstruksikan secara sosial (socially constructed), sebagaimana yang ditawarkan dalam perspektif anti esensialis yang juga merupakan roh dari perspektif cultural studies. Perspektif non-esensialis berupaya melampaui keduanya; atau bermain secara kreatif di antara kedua perspektif ekstrem tersebut. Artinya, bahwa identitas itu terberi memang diakui, tapi tidak sepenuhnya. Begitu pula bahwa identitas merupakan hasil konstruksi sosial, jelas juga diakui, namun tidak bisa pula diterima secara total. Berdasarkan paparan penelitian terdahulu yang mengangkat topik tentang etnis Tionghoa Muslim, perlu ditekankan bahwa penelitian yang saya lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama menyangkut problematisasi identitas etnis Tionghoa Muslim di Makassar. Problematisasi itu menyangkut upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Muslim dalam mengonstruksi identitas, baik di hadapan orang-orang Tionghoa non Muslim maupun di hadapan orang-orang Muslim non Tionghoa. Perbedaan lain dalam penelitian saya adalah upaya untuk menguraikan keberagaman interaksi yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa Muslim baik secara invidu maupun kelompok. Terakhir, penelitian ini juga akan mengungkapkan bentuk akulturasi yang muncul dari interaksi dua kebudayaan yang berbeda. 17 1.5. Landasan Teori Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian ini, penulis akan menggunakan konsepsi Stuart Hall mengenai identitas. Menurutnya, identitas tidak pernah tunggal tetapi berbentuk secara bergelombang lintas wacana, praktik dan posisi yang berbeda-beda. Kesemuanya itu merupakan produk perkembangan sejarah, dan terus menerus berproses, yang diwarnai perubahan dan transformasi. Hall mendefinisikan identitas sebagai proses yang terbentuk melalui sistem bawah sadar. Sistem bawah sadar berjalan melalui waktu dan membentuk bayangan imajiner yang tidak pernah menemui titik akhir. Dalam kaitan ini, Hall lebih menilai identitas sebagai proses menjadi (becoming) daripada nilai baku atau taken for granted. 1.5.1. Identitas Budaya Dalam buku, Identity, Community, Culture, Difference, Stuart Hall berpendapat bahwa identitas budaya bukanlah sesuatu yang jelas dan tanpa masalah karena identitas budaya adalah suatu produk yang tidak pernah selesai, selalu dalam proses pembentukan dan terbentuk dalam suatu representasi. Representasi ini pun berada dalam proses yang terus menerus dan bersifat personal dan lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hall, ada dua cara untuk memikirkan tentang identitas budaya. Pertama, dengan memosisikan identitas budaya dalam satu budaya yang sama, secara kolektif dengan menyembunyikan hal lain secara paksa dengan orang-orang yang mempunyai sejarah dan keturunan yang sama. Identitas budaya 18 di sini memaksakan orang-orang tersebut sebagai one people yang stabil dan tidak berubah. Identitas di sini adalah identitas yang bersifat esensialis. Kathryn Woodward menjelaskan bahwa identitas yang bersifat esensialis: suggest there is one clear, authentic set of characteristics which all share and which do not alter across time (Woodward, 1997: 11). Dengan demikian, identitas esensialis adalah identitas yang mempunyai satu karakteristik yang sama seperti sejarah dalam satu budaya. Kedua, memosisikan identitas budaya dengan mengakui adanya persamaan dan perbedaan. Identitas di sini adalah identitas yang non esensialis yang fokus kepada perbedaan dan juga persamaan karakteristik. Dalam pengertian yang kedua ini, Hall menjelaskan bahwa identitas budaya adalah persoalan bagaimana seseorang membentuk dirinya seperti sebagai becoming dan being (Cultural Identity dan Diasporan dalam Identity, Community, Cultural Difference, 53). Identitas budaya masuk ke dalam dunia masa depan sekaligus dunia masa lalu. Di sini dijelaskan bahwa identitas budaya sangat bergantung kepada bagaimana seseorang menjadikan identitas budaya itu sebagai sebuah posisi dan bukan esensi, sehingga orang itu dapat menjadi “siapa saja” di mana pun ia berada. Hall menjelaskan mengenai identitas budaya yang masalah identifikasinya bersifat tidak tetap. Identitas adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti pembentukannya, bukan hanya sesuatu yang „ada‟, namun sesuatu yang terus „menjadi‟. Lebih jauh, Hall menunjukkan posisinya dalam pengertian identitas sebagai sesuatu yang cair dan terus mengalami pembentukan, “Cultural identity is not a fixed essence at all, lying unchanged out side history and culture. It is not some universal and transcendental spirit 19 inside us on which history has made no fundamental mark… it has its histories –and histories have their real, material and simbolyc effects” (Stuart Hall, 1990: 227). Hall menegaskan bahwa identitas bukan sesuatu yang kaku dengan karakteristik tetap yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Identitas adalah sesuatu yang terus menerus dibentuk dalam kerangka sejarah dan budaya, sesuatu yang diposisikan pada suatu tempat dan waktu, sesuai dengan konteks. Pencarian identitas seseorang selalu terkait dengan permasalahan bagaimana orang tersebut berusaha menempatkan dirinya (positioning) dalam suatu lingkup masyarakat yang telah menempatkan dirinya dengan lingkup lain (being positioned). Hal ini juga berkaitan erat dengan persamaan dan perbedaan dalam identitas budaya. Perbedaan dan persamaan inilah yang ada dalam cakupan identitas budaya. Identitas juga dipaparkan oleh Hall sebagai suatu hal yang selalu berubah dan tidak pernah tetap. Oleh karena itu, seseorang dapat mengalami perubahan identitas seiring dengan kehidupannya. 1.5.2. Dramaturgi Kemudian untuk menganalisis interaksi yang terjadi antara etnis Tionghoa Muslim dengan komunitas di luar mereka, penulis juga akan menggunakan teori Dramaturgi dari Ervin Goffman. Dalam bukunya yang kemudian terkenal sebagai salah satu sumbangan besar bagi teori ilmu sosial The Presentation of Self in Every Day Life, Goffman yang mendalami fenomena interaksi simbolik mengemukakan kajian mendalam mengenai konsep Dramaturgi. 20 Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri, dari setiap identitas tersebut. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgi masuk dan menguasai interaksi tersebut. Dalam dramaturgi, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”. Untuk mencapai tujuannya, menurut konsep dramaturgi, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung peran tersebut. Layaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunaan kata (dialog) dan tindakan non-verbal lain. Hal ini tentunya bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan. Dengan konsep dramaturgis dan permainan peran yang dilakukan oleh manusia, terciptalah suasana-suasana dan kondisi interaksi yang kemudian memberikan makna tersendiri. Ketika seorang Tionghoa Muslim menjalin interaksi dengan komunitas di luar mereka, segala bentuk tindakan atau penampilan akan dibatasi sebagai pola yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini terungkap pada saat seorang Tionghoa Muslim melakukan tindakan atau penampilan (performance) yang diungkapkan pada kesempatan lain. Ia dapat saja menyajikan suatu „pertunjukan‟ bagi orang lain, namun kesan (impression) orang lain terhadap „pertunjukan‟ tersebut dapat berbeda-beda. Seseorang dapat bertindak sangat meyakinkan atas tindakan yang 21 diperlihatkannya, walaupun pada kenyatannya perilaku keseharian orang tersebut tidak mencerminkan tindakan atau perilaku yang demikian. Segala tindakan atau penampilan seorang Tionghoa Muslim akan berbeda ketika ia berhadapan secara fisik baik dengan sesama Tionghoa non-muslim dan muslim non-Tionghoa. Ia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Dalam mengembangkan perilaku tersebut, perlu di bedakan antara panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan ini merupakan bagian penampilan individu yang secara teratur berfungsi sebagai metode umum untuk tampil di depan publik sebagai sosok yang ideal, sebagaimana yang dikatakan Goffman (dalam Supardan, 2011: 158), sebagai tindakan yang bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi demi memuluskan jalan mencapai tujuan. Dengan kata lain, panggung depan ini adalah kesempatan sosial atau perjumpaan ketika individu memainkan peran formalnya. Adapun panggung belakang terdapat sejenis „masyarakat rahasia‟ yang tidak sepenuhnya dapat dilihat di atas permukaan. Panggung belakang ini benar-benar mirip dengan wilayah belakang panggung (baca: teater). Tradisi dan karakter yang ditampilkan dalam wilayah ini sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan di panggung depan. 1.5.3. Liminalitas Sebagai upaya memahami objek kajian sekaligus menguraikan dinamika yang terjadi, peneliti juga menggunakan konsep yang relevan dalam pembahasan 22 dan diskusi teoritis. Dalam kaitan ini, konsep “liminalitas” yang diungkapkan Homi K Bhabha dalam The Location of Culture, sangat membantu dalam menjelaskan proses „interaksi‟ yang terjadi antara kebudayaan Islam dan Tionghoa. Menurut Bhabha, identitas budaya bukanlah identitas bawaan yang dibawa sejak lahir (given) dari kekosongan. Identitas kultural bukan pula entitas yang ditakdirkan, tidak bisa direduksi atau ciri historis yang menetapkan konvensi kultural. Pandangan oposisi biner “penjajah” dan “terjajah” tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang terpisah satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri. Bhabha mengungkapkan bahwa negosiasi kultural mencakup perjumpaan dan pertukaran tampilan budaya yang terus menerus yang pada saatnya akan menghasilkan pengalaman timbal balik akan perbedaan budaya (Bhabha, 2007). Bahwa bukan hanya yang terjajah yang mengambil atau meniru kaum penjajah, dalam beberapa hal, kaum penjajah pun mengambil atau meniru dari kaum terjajah, meskipun dalam porsi yang lebih sedikit. Bhabha mengaskan bahwa baik penjajah maupun terjajah tidak independen satu sama lain. Relasi-relasi kolonial distrukturkan oleh bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka dan kontradiktif. Menurut Bhabha, antara penjajah dan terjajah terdapat “ruang antara” yang memungkinkan keduanya untuk berinteraksi. Diantara keduanya terdapat ruang yang longgar untuk suatu resistensi (Bhabaha, 2007: 4). Konsep liminalitas Bhabha digunakan untuk mendeskripsikan suatu “ruang antara” di mana perubahan budaya dapat berlangsung, yaitu ruang antar-budaya di mana strategi-strategi kedirian personal maupun komunal dapat dikembangkan. Dapat pula dilihat sebagai suatu proses 23 gerak dan pertukaran antara status yang berbeda-beda dan berlangsung secara terus menerus. Teori liminalitas Bhabha ini memang terkesan menghindari oposisi biner yang konfrontatif atau saling menaklukkan. Sebaliknya, yang hendak ditawarkan Bhabha adalah bahwa ruang itu mampu berperan sebagai ruang untuk sebuah interaksi simbolik. Dengan demikian, ruang ketiga Bhabha mampu memberikan kontribusi penting bagi pemahaman perbedaan budaya (Bhabha, 2007: 34). Teori liminalitas Bhabha menempatkan orang Tionghoa Muslim pada posisi ruang ketiga atau ruang antara, yang mempertemukan budaya Tionghoa dengan budaya Islam. Konstruksi identitas berlangsung atau terus beroperasi tanpa ada ujung yang jelas. Sebagaimana yang diungkapkan Bhabha bahwa dalam proses tersebut tidak ada konfrontasi yang saling menaklukkan diantara dua budaya, yang ada justru interaksi yang sangat indah di „ruang ketiga‟. 1.6. Metode Penelitian 1.6.1. Korpus Penelitian Korpus, penelitian ini adalah kajian tentang keberadaan identitas Tionghoa Muslim, dengan dasar petimbangan sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu identitas, agama masih merupakan isu yang menarik untuk dikaji. Hal ini dibuktikan dengan terus bermunculannya kajiankajian tentang identitas dari beragam perspektif keilmuan. 24 2. Kajian tentang identitas, terutama yang terkait dengan ke-tiongho-an telah mendapat tempat tersendiri di kalangan peneliti ilmu-ilmu sosial, setidaknya setelah era Orde Baru. 3. Islam dalam wacana ke-tionghoa-an masih dianggap sebagai suatu hal yang asing, tidak lazim bahkan tidak sedikit kalangan yang menempatkan keduanya pada posisi yang antagonisitik. 1.6.2. Fokus Penelitian Penelitian ini akan mengurai narasi dari etnis Tionghoa muslim yang tidak hanya dibatasi pada keaktifan dalam kegiatan keagamaan (baca: Islam) semata. Aktivitas kelompok etnis Tionghoa Muslim dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial juga akan menjadi fokus kajian ini. 1.6.3. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan mengambil lokasi di Makassar, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dengan keberadaan etnis Tionghoa. 2. Makassar sebagai salah satu kota multi etnis, yang mana Tionghoa Muslim merupakan salah satu etnis yang ada. 3. Makassar sebagai kota yang dihuni oleh beragam etnis, tentu telah mengalami banyak dinamika yang melibatkan komunita etnis Tionghoa, baik secara langsung maupun tidak langsung. 25 1.6.4. Teknik Pemilihan Informan Subjek yang akan menjadi informan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, adalah pengurus Perhimpunan Islam Tionghoa [PITI] Makassar yang akan dipilih secara terstruktur. Kedua adalah anggota PITI yang selanjutnya akan menggunakan metode bola salju (snow ball sampling). Ketiga, adalah individu, lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di luar komunitas non Tionghoa Muslim yang memiliki interaksi cukup tinggi dengan komunitas etnis Tionghoa Muslim di Makassar. 1.6.5. Teknik Pengumpulan Data Sebagai teknik dalam pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatoris. Wawancara mendalam akan dilakukan kepada beberapa pihak yang telah dipilih sebagai nara sumber utama. Ada pun observasi partisipatoris dilakukan melalui pengamatan dan interaksi secara langsung dengan komunitas etnis Tionghoa Muslim, baik melalui organisasi resmi mereka (Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia), maupun secara non formal, yakni pihak-pihak di luar komunitas Tionghoa Muslim yang ada di Makassar. 1.6.6. Teknik Analisis Data Metode analisis data umum yang digunakan adalah metode interaktif, yakni analisis yang dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data di lapangan hingga pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data model 26 interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 1.7. Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN BAB II: GAMBARAN UMUM PENELITIAN. Pada bab ini penulis akan menarasikan sejarah dan dinamika keberadaan Tionghoa muslim di Makassar melalui: 1) Asal muasal munculnya komunitas Tionghoa Muslim. 2) Uraian mengenai wacana keislaman dalam masyarakat Tionghoa. 3) Penjelasan tentang sebab-sebab munculnya pemisahan antara Islam dan etnis Tionghoa. 4) Peninjauan kembali wacana “pengislaman” etnis Tionghoa sebagai sebuah bentuk asimilasi, sebagaimana yang pernah disarankan oleh pemerintahan Orde Baru. BAB III: PEMBAHASAN Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana interaksi orang Tionghoa Muslim dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan sesama orang Tionghoa non muslim maupun terhadap orang muslim non- Tionghoa? Apakah konstruksi identitas yang dibangun oleh komunitas etnis Tionghoa muslim bersifat tunggal? atau ada ruang yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan konteks lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perangkat analisis data di lapangan, berupa 27 wawancara mendalam dan observasi, bagian ini akan mengungkap perihal tersebut. BAB IV: ANALISIS SERTA PEMBAHASAN TEORITIS TENTANG HUBUNGAN ETNISITAS (BUDAYA), KELAS DAN AGAMA Pada bab ini, penulis akan melalukan analisis dan pembahasan teoritis mengenai relasi etnisitas, kelas dan agama. Bagaimana ketiga entitas tersebut (etnisitas, kelas dan agama) berjalin berkelindan dan ikut membentuk identitas orang Tionghoa Muslim di Makassar. Penulis juga akan mengulas mengenai interpretasi sosial konteks, di mana ke-Tionghoa-an dan ke-Islam-an hadir dan diperbincangkan, serta penjelasan mengenai“keislaman” sebagai salah satu agensi yang berperan dalam proses negosiasi identitas komunitas Tionghoa muslim di Makassar. BAB V: PENUTUP Sebagai penutup, pada bab ini, penulis akan memeriksa sekaligus memproblematisasikan, dengan mempertanyakan apakah konstruksi identitas yang dibangun oleh komunitas Tionghoa muslim di Makassar merupakan bentuk negosiasi? Jika benar demikian, faktor apa saja yang mempengaruhinya? 28