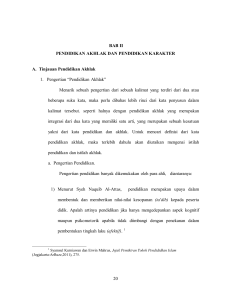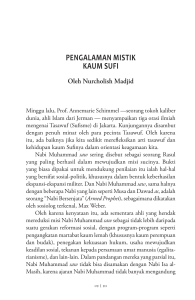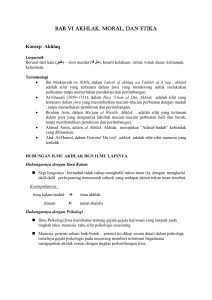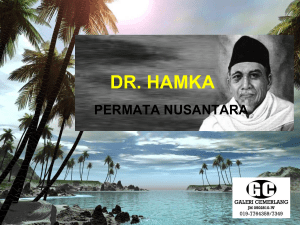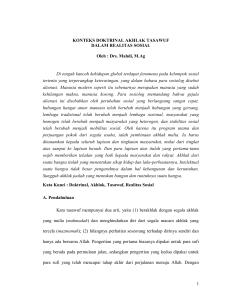BAB I Pengantar Ke Etika Islam Ketika tulisan ini dirangkai
advertisement

BAB I Pengantar Ke Etika Islam Ketika tulisan ini dirangkai, terminologi jihad kembali bergaung kembali menyusul munculnya film kontroversial ”The Innocence of Islam” sebuah film yang dibuat di Amerika dab dipandang menghina Islam dan kepribadian Nabi Muhammad saw. Penghinaan terhadap Islam rupanya tidak sampai di sini, dalam waktu bersamaan, di Prancis muncul karikatur Nabi yang dimuat dalam salah satu Majalah terbitan Prancis. Tak pelak, kondisi ini memicu semangat ”jihad” Islam militan di sejumlah negara. Di Indonesia, produk Amerika dan sejumlah hal yang ber”bau” Amerika merasa terancam. Sejumlah rumah makan seperti KFC, Mc De, Pitza Hut dan sejenisnya menutup peyananan selama beberapa hari. Sejumlah ormas dan aktivitas Islam melakukan tablig Akbar, Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah aktivitas lainnya yang memiliki ciri khas ”militan” rajin melakukan unjuk rasa di sejumlah tempat. Cara-cara seperti ini merupakan sebuah paradigma aktivitas Islam yang ingin menyuarakan aspirasinya di dalam kehidupan yang serba pluralis ini. Cara menyampaikan pendapat atau memprotes terhadap sesuatu yang tidak disenangani dilakukan dengan tindakan-tindakan unjuk rasa yang seringkali merujung kepada anarkisme, bentrok dengan pihak keamanan, menyeweeping orang asing dan membuat orang lain tertekan. Kebencian terhadap orang yang menodai Islam ditebarkan kepada mereka yang sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk terjadinya kasus. Sering justifikasi kesalahan dan penghakiman diberikan kepada mereka yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan sebuah objek kasus yang dipersoalkan. Itulah sebabnya, kita pernah dikagetkan oleh bom di Legian Bali yang menewaskan ratusan jiwa dan melukai ribuan orang. Menurut investigasi, Imam Samudra cs bertanggung jawab atas terjadinya ledakan bom tersebut. Menurut Imam, apa yang dia lakukan merupakan sebuah jihad untuk memerangi orang kafir. Imam Samudra cs pun akhirnya harus berhadapan dengan regu tembak (mati) beberapa hari setelah Idul Adha. Orang yang menolak dan mengutuk aksi pengeboman mencap Imam Samudra cs sebagai teroris, akan tetapi orang yang bersimpati kepadanya menganugrahi predikat ”mujahid” dan menganggap mereka mati syahid. Menanggapi hal in, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun angkat bicara melalui Komisi Fatwanya bahwa kematian Imam Samudra cs bukan syahid, wallahu A’lam. Di Situbondo, tahun1996 silam, massa demonstran yang tampak emosi dan marah berteriak-teriak dengan pekikan takbir (Allahu Akbar) membakar sebuah gereja seperti orang kesetanan. 17 Januari 2000, di Mataram tercatat sembilan buah gereja dibakar, empat orang tewas dan beberapa rumah rusak akibat konflik antar agama. Mereka beranggapan bahwa tindakan itu dikategorikan sebagai jihad. (Abu Yazid:Fiqh Realitas:100). Banyak masyarakat muslim memahami dan mengidentikkan term jihad dengan perang melawan kaum kafir. Karena itu, tidak aneh ketika seseorang melakukan serangkaian pengeboman sebagai aksi teror kepada orang yang mereka anggap musuh Allah, menganggap aksinya sebagai sebuah jihad. Term jihad ternyata mengalami sebuah distori yang cukup parah akibat kegagalan memahami makna hakiki jihad bahkan melupakan konteks sejarah, hukum, syarat dan etika jihad. Konsekuensinya, makna agung jihad ternodai dengan aksi-aksi terorisme. Efeknya, muncul stigma di sana-sini bahwa agama Islam identik dengan terorisme, dan ini merupakan celah yang dimanfaatkan oleh 1 orang-orang yang tidak senang dengan Islam untuk merusak citra Islam. Motivasi Jihad Term jihad dapat dijumpai di dalam al-Qur’an maupun hadis. Al-Quran sebagai pedoman utama telah menyebut jihad sebanyak 41 kali dan memberikan penafsiran yang selalu berbeda dalam setiap ruang dan waktu. Ibn Rusyd menyatakan bahwa jihad adalah mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapai rida Allah (Ibn Rusyd: Muqaddiman:259). Al-Barusawi memberikan makna jihad sebagai upaya menghilangkan sifat egoisme untuk menciptakan kedamaian (al-Barusawi: Ruh al-Bayan:388). Al-Fairuzabadi berpendapat bahwa jihad merupakan pengorbanan dengan segala kemampuan baik dengan tenaga maupun dengan perkataan (al-Fairuzabadi: Qamus al-Muhit: 296). Dari sejumlah pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jihad merupakan perjuangan sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan dan keluhuran. Mungkin sebagian orang bertanya kenapa umat Islam sangat tertarik dengan jihad? Doktrin agama ternyata telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap pola pikir masyarakat yang berangan-angan ingin mengecap kenikmatan surgawi. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad saw pernah menyatakan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah (salah satu di antaranya berperang melawan orang kafir) balasannya adalah surga tanpa melalui proses hisab. (H.R. Bukhari-Muslim). Di dalam hadis lain Nabi bersabda: ” Demi Zat yang jiwaku dalam genggamanNya, aku ingin terbunuh di jalan Allah, lalu aku dihidupkan kembali, lalu aku terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi lalu aku terbunuh lagi.”(H.R. Bukhari). Keinginan Nabi untuk berulang kali terbunuh dalam peperangan, lalu ingin dihidupkan kembali menunjukkan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah sungguh akan mendapatkan kenikmatan dan balasan surga dari Tuhan. Atas dasar pemahaman doktrin seperti ini, masyarakat termotivasi untuk mendapatkan surga secara instant, meski terkadang tanpa harus melakukan rutinitas ritual agama dan kesalehan sosial yang menjadi kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Lalu betulkan bahwa jihad itu harus selalu identik dengan perang? Ternyata tidak, hanya saja mayoritas masyarakat memang secara massif telah mengidentikan jihad dengan perang, sebab makna jihad selalu merujuk kepada nostalgia masa lalu. Sayyed Tantawi di Mesir menyatakan bahwa jihad tidak harus dengan perang, tetapi jihad mestinya dapat menjadi sebuah gerakan yang dapat membangun umat Islam dalam realitas kekinian dan kedisinian yang multikompleks. Standar kejayaan umat Islam bukanlah karena kekuatan perangnya, melainkan karena ketinggian peradaban dan kebudayannya (Zuhairi M, al-Qur’an: 426). Atas dasar inilah, seorang perempuan Mesir Khazandarah mewakafkan hartanya untuk membangun asrama mahasiswa putri untuk belajar di Universitas alAzhar Cairo, yang oleh Syekh Muhammad al-Gazali dianggap sebagai jihad yang perlu diteladani. Demikian Juga Muhammad Yunus (Peraih Nobel) dari Bangladesh membangun Gramen Bank, sebuah Bank Internasional yang diperuntukkan bagi kaum miskin demi melepaskan diri dari kemiskinan, dapat dikategorikan sebagai jihad. Oleh karena itu, jihad dapat dikelompokkan kepada empat bagian. Pertama, jihad bi al-Qalb yaitu berperang 2 melawan hawa nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan. Kedua, jihad bi al-lisan yaitu mengajak manusia untuk melakukan perintah Tuhan dan mencegah segala bentuk kemunkaran (termasuk di dalamnya menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak di depan penguasan yang zalim). Ketiga, jihad bi al-yad yaitu upaya sungguhsungguh untuk menegakkan keadilan dan kebenaran melalui kekuasaan/wewenang yang dimiliki dengan tatap menjaga koridor etika jihad. Keempat jihad difa’i yaitu jihad yang dilakukan lantaran ingin mempertahankan agama atau negara. Jihad dan Etika Islam Tidak dapat dibantah bahwa term jihad sebenarnya seakar kata dengan term ijtihad dan mujahadah. Ketiga istilah ini terambil dari akar kata Juhd yang bermakna ”kesungguhan, kesukaran atau kemampuan” (Majma, al-Mu’jam al-Wasit: 142). Kesamaan akar kata dari ketiga istilah ini memberi konsekuensi bahwa jihad sesungguhnya tidak terlepas dari ijtihad dan mujahadah. Ketiganya harus bersinergi dalam implementasinya di lapangan jika ingin mendapatkan nilai hakiki sebuah jihad. Dengan kata lain, jihad tanpa ijtihad dapat berujung kepada sebuah ”kekonyolan”. Jihad dengan ijtihad tetapi tidak menyertakan mujahadah dapat berbuah tragedi kemanusiaan. Orang tidak seharusnya pergi kegitu saja untuk berjuang ke medan perang tanpa harus mempertimbangkan secara ijtihadi kondisi dan potensi yang dimilikinya. Sejarah telah membuktikan di saat seorang sahabat Nabi yang hanya bermodalkan semangat keberagamaan (khammasah diniyah) ingin ikut berperang, namun belum memiki kematangan, kemampuan dan strategi perang, Nabi pun melarangnya ikut dan menyuruhnya melakukan jihad yang lain yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih hidup (H.R.Imam Turmuzi: 1879) Menyikapi keinginan sebagian masyarakat Indonesia yang ingin berjihad ke Palestina, diperlukan sebuah ijtihad yang bertujuan mencermati, mempertimbangkan dan menganalisis kemampuan, kesiapan dan pengenalan medan perang dalam perang modern. Sudahkah semua itu terpenuhi? Ini memerlukan sebuah ijtihad. Jika tidak, kepergian sebagian masyarakat tersebut dapat berujung kepada kematian . Lalu betulkah pula jika mereka terbunuh di Palestina, kematiannya dianggap syahid? Tentu semuanya tergantung kepada niat dan muatan substantif dari peristiwa tersebut. Jihad juga harus tetap memperhatikan aspek mujahadah yaitu sebuah dimensi spiritualitas yang menjunjung tinggi hak dan nilai-nilai universal kemanusiaan. Jihad dilakukan bukan atas dasar kebencian yang penuh dengan emosi, tetapi jihad dilakukan atas dasar untuk mencapai ridha Tuhan. Dalam kaitan ini kita dapat belajar dari sejarah jihad yang lakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Suatu ketika di saat Nabi memimpin perang melawan kafir Quraish, tanpa sengaja, cambuk yang diayunkan untuk memacu kuda mengenai punggung sahabatnya bernama Ukasah. Di saat Nabi sakit dan beberapa saat menjelang ajalnya, beliau bertanya kepada seluruh sahabat yang hadir siapa di antara mereka yang pernah beliau sakiti? Tentu sahabat Nabi tidak dapat menjawab, sebab mana mungkin Nabi yang agung itu melakukan sebuah kesalahan apalagi menyakiti para sahabatnya. Namun di saat hening itu, Nabi terus meminta kepada sahabatnya agar memberitahu siapa yang pernah disakiti Nabi. Ukasah kemudian mengaku bahwa cambuk Nabi pernah mengenai punggungnya. 3 Nabi pun meminta Ukasah untuk memukul punggungnya dengan seutas cambuk. Cerita di atas memberikan pemahaman kepada kita, bahwa di saat jihad suci sekalipun, Nabi berupaya untuk tidak menyakiti orang lain, meski nilai pahala jihad tersebut boleh jadi dapat menghapus sebuah kesalahan yang tidak disengaja, akan tetapi Nabi agung, Panglima perang, Kepala negara Muhammad saw itu, tetap meminta balasan dari apa yang pernah dilakukannya kepada Ukasah. Oleh karena itu, Nabi berpesan kepada sahabatnya ketika berperang untuk (1) tidak membunuh orang tua, perempuan dan anak-anak; (2) tidak membunuh musuh yang menyerah, dan (3) tidak membabat pepohonan. Bukankah ini semua efek dari nilai mujahadah dalam jihad? Sayyidina Ali pernah mengurungkan aksinya untuk membunuh musuhnya di saat duel (satu lawan satu) dalam sebuah peperangan hanya karena lawannya meludahi wajahnya di saat dia ingin menghunjamkan pedang ke dada musuhnya. Sang musuh bingung dan bertanya kenapa Ali kenapa membatalkan niat untuk membunuhnya? Ali menjawab bahwa tujuannya berperang hanya semata-mata karena Allah (perang di jalan Allah), tetapi di saat ludah mengenai wajahnya, dadanya bergemuruh, hatinya panas dan emosi memuncak. Akhirnya Ali membatalkan niatnya untuk membunuh, sebab jika dia lakukan, perbuatannya bukan lagi jihad fi sabilillah, tetapi membunuh atas dasar dendam, kemarahan dan emosi. Panglima perang Amr bin Ash pernah menunda peperangan menyerang musuh hanya disebabkan di atas tendanya ada seekor merpati yang sedang bertelor. Dia perintahkan kepada prajuritnya untuk menunda penyerangan hingga merpati tersebut menetas, sebab ia khawatir akan mengganggu kelangsungan kehidupan anak-anak burung merpati tersebut. Cerita sejarah di atas menunjukkan kepada kita, bahwa betapa etika berada di atas segalanya. Tidak salah rasanya Nabi mendeklarasikan bahwa kehadirannya di muka bumi adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Tuhan Sebagai Sumber Etika Allah swt adalah sumber etika. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Zat yang memiliki nama-nama yang indah yang dikenal dengan istilah al-Asma al-Husna. Ketika Tuhan menyempurnakan kejadian manusia, kemudian dia meniupkan sebagian ruhNya (QS. Al-Sajadah: 9), maka Tuhan mengambil persaksiannya kepada manusia dengan ungkapan (QS. Al-A’raf: 172) ”Alastu birabbikum” (bukankah Aku Tuhanmu). Pada saat itu manusia menjawab ”bala syahidna” (Benar.. kami bersaksi, Engkau Tuhan kami) Ketika itulah, sebagian ruh Tuhan yang suci itu ditiupkannya ke dalam diri manusia, dan atas kehendakNya, manusia dihidupkan dan kemudian terlahir dari rahim ibu. Kelahiran manusia yang membawa ruh suci ini yang kemudian menyebabkan manusia terlahir dalam keadaan fitrah (suci), tidak membawa dosa dari warisan apapun. Lalu apakah makna hakiki fitrah? Berdasarkan informasi QS. Al-Rum: 30 dan hadis riwayat Bukhari-Muslim, bahwa fitrah merupakan unsur mulia yang Allah tanamkan di dalam diri manusia. Fitrah merupakan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi potensi dasar manusia untuk menjadi khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi. Sejak lahir, setiap anak manusia diberikan nilai-nilai inti ini. Allah telah meniupkan sebagian ruh sucinya yang di dalamnya menyimpan potensi ketuhanan sehingga manusia disebut Homo Devinous. Nilai-nilai fitrah itu antara lain 4 adalah kasih-sayang, keadilan, kesucian, kedamaian, kesantunan, keramah-tamahan, pemaaf, pemberi, kelembutan, keindahan, kepedulian, kepekaan, kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya yang kesemuanya bersifat universal karena ia sesungguhnya bersumber dari Allah. (QS. al-Isra: 110) Nilai fitrah mendorong manusia untuk mencari yang baik, benar, dan indah yang kesemuanya merupakan ibu kandung sah dari etika, ilmu dan seni. Dengan fitrah, manusia kembali pada kesucian batin yang dapat mengantarnya untuk menuntut ilmu sehingga menjadi ilmuwan, mengekspresikan keindahan sehingga menjadi seniman, dan melakukan kebaikan sehingga menjadi budiman. Itulah sebabnya di saat manusia masih bayi atau menjadi anak-anak, nilai fitrah yang hadir di dalam dirinya tampak “menyala”. Kejujuran, kepolosan, dan sifat memaafkan menjadi ciri khas dan karakter mereka. Kejujuran anak-anak melampaui kejujuran orang tua, demikian pula sifat pemaafnya menjadi ciri utama mereka. Jika bertengkar di pagi hari, mereka sudah baik di sian hari. Jika berkelahi dengan temannya di siang hari, baik di sore hari. Jika ribut dengan temannya di malam hari, maka mereka tidak menyimpan dendam di dalam tidurnya. Besok pagi mereka bergendengan tangan lagi pergi ke sekolah. Itulah sebabnya memandang wajah anak-anak begitu indah dan nyaman dipandang mata. Orang tua yang bekerja di kantor seharian akan merasakan segar kembali ketika melihat anakanaknya yang kecil menyambutnya di rumah. Anak-anak fitrah itu merupakan miniatur manusia-manusia surga yang tidak memiliki dendam dalam kehidupannya. Hanya saja, seirama dengan perkembangan umur dan interaksinya dengan lingkungan, manusia mulai melupakan perjanjian primordial yang pernah dia nyatakan ketika di alam rahim (zurriyat) dengan janji akan selalu tunduk kepada Allah (QS. Al-A’raf: 172), dan menjunjung tinggi nilai fitrah. Mereka berpaling dari petunjuk Tuhan dan mulai mengotori ruh suci dengan sifat-sifat tercela. Meski mempunyai mata tapi mereka tidak dapat melihat, punya telinga tidak dapat mendengar, dan memiliki hati tapi tidak paham dengan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang (QS. al-A’raf: 179). Binatang buas seperti harimau sekalipun, jika sudah kenyang, tidak akan mengenyangkan perutnya lagi, meski makanan atau seekor tikus berkeliaran di depan hidungnya. Sebaliknya, meski sudah kenyang, manusia ingin terus memperbesar perutnya, ia haus dengan kekayaan, jabatan dan kedudukan. Ia rebut semuanya itu meski harus menghalalkan segala cara. Untuk mengembalikan manusia dan mengingatkan manusia akan fitrah dan perjanjian yang pernah diucapkannya di dalam zurriyat dahulu, Allah memberikan cara atau media kepada manusia melalui sejumlah ibadah, misalnya salat, haji atau puasa yang diwajibkan kepada umat Islam (orang beriman). Cara ini sesungguhnya merupakan salah satu cara Tuhan mengembalikan manusia kepada fitrahnya dengan mengimplementasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Sakralitas salat, puasa atau haji yang dilakukan dengan iman dan kesungguhan dapat membongkar karat, kotoran dan debu yang menutupi jiwa/ruhani manusia. Untuk itulah Nabi Muhammad saw., bersabda: Barang siapa berpuasa dan mendirikan shalat malam di bulan ramadhan dengan penuh keimanan dan sungguh-sungguh, maka ia keluar dari dosanya seperti anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya (fitrah). Di hadis lain Nabi berkata: Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Hampir semua ibadah ritual yang diajarkan Nabi saw memiliki nilai etis yang harus diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai fungsional yang terkandung dalam dimensi ibadah harus menjadi karakter dalam 5 kehidupan manusia, sebab jika tidak maka ibadah yang dilakukan tidak lebih dari sekadar ritualitas yang boleh jadi tidak dipandang dan dianggap oleh Allah. Contoh sederhana adalah nilai kepedulian atau kepekaan sosial yang Tuhan ajarkan baik melalui salat dengan simbolisasi salam ke kiri atau ke kanan, atau dalam puasa dengan simbolisasi zakat fitrah. Semua umat Islam mengeluarkan zakat fitrah dengan kadar yang sama yaitu empat liter beras. Kenapa semua sama? Karena fitrah manusia sama (setiap anak manusia lahir dalam keadaan fitrah), maka zakat fitrah dalam bentuk simbol itupun sama kadarnya. Seorang presiden dan rakyat jelata, orang dewasa/tua dan anak kecil sama-sama diwajibkan mengeluarkan kurang lebih empat liter beras. Zakat fitrah berupa beras sesungguhnya hanya merupakan simbolisasi dari makna fitrah kepedulian, kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, indikator fitrah bukan terletak pada seberapa banyak beras yang dia sumbangkan, sebarapa mewah dan bagus baju yang ia kenakan, tetapi seberapa besar kemampuannya men-zakat-kan (menumbuh-kembangkan) fitrahnya berupa nilai-nilai mulia tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab Jika surga ditentukan oleh beras, maka tentu penduduk di daerah penghasil beras terbesar lah yang paling banyak masuk surga. Dengan demikian, ibadah ritual sesunggunnya tidak mencetak manusia-manusia egois yang hanya “saleh” di hadapan Tuhan, tetapi lupa dengan orang di kiri-kanannya. Tuhan kurang suka kepada orang yang hanya menangis di atas sajadahnya, tetapi tidak pernah menangis (iba) dan tidak peduli kepada kaum dhuafa (Q.S. Al-Maun :4-7). Tuhan menghendaki manusia kembali kepada fitrah dengan cara mengimplementasikan dan menumbuhkembangkan potensi fitrahnya dalam aksi dan karya nyata sebagai cermin dari kesalehan sosial serta refleksi tugas dan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Jika fitrah sebagai bagian dari etika dapat terimplementasi dalam kehidupan, maka manusia akan mengalami kemajuan baik dari sisi pengetahuan maupun peradaban. Kemajuan yang diperoleh manusia tidak terkait dengan agama formal yang dianut oleh penduduk sebuah bangsa, tetapi kemajuan sangat erat kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai agama atau fitrah dalam kehidupan. Jika fitrah atau etika diabaikan oleh manusia, maka akan terjadi degradasi moral dalam kehidupan, sebab dia telah berpaling dari sumber etika (Allah). Masyarakat akan mengalami kehancuran jika mereka berpaling dan tidak lagi berpegang kepada kejujuran (al-Mu’min), keadilan (al-Adl), kedamaian, (al-Salam), memaafkan (al-afw) dan lain-lain yang kesemuanya ini merupakan sifat-sifat Allah. Bukankah Nabi saw pernah berkata: Berakhlak kalian dengan akhlak Allah. Potret Indonesia Di Indonesia, mayoritas penduduk beragama Islam, tetapi tidak semua penduduk memiliki keimanan yang baik kepada Tuhannya. Setiap warga yang beragama Islam jika ditanya apakah dia beriman (percaya) kepada Allah? Hampir dipastikan mereka akan menjawab ya, bahkan dia marah jika disebut tidak beriman, meskipun tidak mengerjakan shalat, puasa dan amal kebaikan lainnya. Semua orang Islam mengaku beriman (percaya) kepada Tuhan. Fenomena seperti ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Banyak orang Islam mengaku beriman kepada Allah di hadapan Nabi, tetapi Allah menjawab dengan firmannya:”Orang-orang Arab itu berkata: Kami telah beriman. Katakan (wahai Muhammad) kepada mereka; Engkau belum beriman, tetapi katakanlah : Kami telah berislam. Sebab iman itu belum masuk ke dalam hatimu”. (Q.S. al- 6 Hujarat:14) Di dalam ayat tersebut Allah menegur orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi hanya sebatas ucapan ( di lidah) saja. Banyak orang yang beragama (baca-Islam) disebabkan faktor keturunan dan sebagian kecil karena faktor konversi agama, akan tetapi, imannya belum masuk dan mengakar di dalam hati. Krisis kepercayaan (keimanan) inilah yang kemudian berimplikasi kepada terjadinya krisis moral. Manusia hanya takut kepada tsunami yang menerjang, tetapi tidak takut kepada Zat yang mendatangkan tsunami. Masyarakat hanya takut kepada gempa bumi, tetapi tidak pernah takut kepada Zat yang menggoncang bumi. Di dalam doa-doa yang dipanjatkan, lisan mereka menyebut dan mengakui Allah Maha mendengar/melihat dan maha mengetahui (Innaka anta al-sami al-alim), tetapi setelah berdoa, pengakuan itu kemudian dibatalkan sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang seakan-akan menganggap Tuhan tidak melihat dan mengetahui perbuatannya. Agama Formal dan Etika Fungsional Kejahatan korupsi yang terjadi tidak cukup hanya dihadapi dengan perangkat perundang-undangan, sebab there is a man behind the rule. Terdapat orang-orang berada di balik peraturan tersebut yang belum memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan aturan. Sudah saatnya kita harus memulai kembali menanamkan nilai-nilai spiritualitas kepada anak-anak sejak dini. Kesalahan paradigma pendidikan anak selama ini disebabkan penonjolan aspek intelektualitas yang lebih besar daripada moral dan spiritual. Perhatikan kehidupan pendidikan kita sehari-hari di rumah tangga. Jika anak mendapat nilai sangat baik (80-100) dalam bidang matematika, biologi dan lain-lain, seorang ibu/bapak sangat memuji kecerdasan anaknya bahkan menjanjikan hadiah jika dia juara. Sebaliknya, jika sang anak mendapat nilai merah (40-55), sang ibu/bapak marah dan jengkel bahkan bisa berkata ”kenapa bisa begini? Seyogianya seorang ibu/bapak tidak boleh marah atau gembira dulu dengan prestasi anaknya, tetapi tanyakan kepada anak bagaimana cara dia mengerjakan soal-soal di kelas, apakah jujur atau membuka buku atau menyontek pekerjaan temannya. Jika anak mengerjakan tugasnya dengan jujur (tidak membuka buku dan menyontek), lalu dia mendapatkan nilai merah (karena salah), seorang ibu/bapak harus memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kejujuran anaknya.Yang dihargai bukan nilai 40 atau 50-nya, tetapi kejujuran anak. Demikian pula di sekolah, seorang guru agama sering memberi apresiasi jika anak dapat dengan tepat menyebut rukun/syarat wudhu, tanpa memperhatikan apakah nilai-nilai moral yang terkandung dalam wudhu itu (kebersihan jiwa dan raga) tercermin dalam perilaku anak. Karena itulah al-Quran mengajarkan agar kecerdasan emosi dan spiritual (nilai-nilai akhlak) ditanamkan lebih dahulu kepada anak di rumah tangga (Q.S. Luqman;11-19). Demikian juga hadis nabi yang berbunyi ” Addibu auladakum... mengindikasikan persoalan moral (adab) harus dikedepankan. Daniel Golmen menyimpulkan, kesuksesan manusia bukan ditentukan semata oleh kecerdasan IQ, tetapi juga sangat ditentukan oleh EQ dan SQ.(Daniel Golmen: 13) Di Jepang proses penaman nilai moral berlangsung sejak dini. Hadipranata (mantan Konselor RI di Jepang) pernah mengadakan penelitian terhadap moral anak-anak (baca-TK) Jepang dengan anak-anak (TK) SRIT (Sekolah Rakyat Indonesia Tokyo). Dua sikap yang diobservasi adalah; 1) kejujuran, dan 2) kebersihan. Di dalam sebuah laboratorium TK, sengaja disediakan swalayan tanpa penjaga (swalayan kejujuran), kursi dan 7 sapu. Ruangan sengaja dikotori dengan sobekan kertas. Kondisi ini sama sekali tidak diketahui, baik oleh TK Jepang maupun TK SRIT. Kesempatan pertama masuk ke laboratorium adalah TK SRIT. Apa yang terjadi? Ketika pertama kali masuk, TK SRIT bukan mengambil sapu lalu membersihkan ruangan, tetapi menyerbu makanan dan memperebutkan kursi. Anehnya, kata Hadipranta, banyak anak-anak yang tidak membayar di Swalayan. Ruangan menjadi gaduh hingga terdengar tangisan anak-anak karena tidak kebagian makanan dan kursi. Tiba giliran anak-anak TK Jepang. Ketika diberikan kesempatan masuk ruangan, mereka tidak menyerbu makanan, tetapi mengambil sapu dan membersihkan ruangan, lalu sebagian duduk di kursi dan sebagian lain mengambil makanan. Menurut pengamatan Hadipranata, anak-anak TK Jepang tersebut membayar makanan sesuai dengan harga yang tertera di makan tersebut. Hadipranata lalu bertanya kepada anak-anak TK Jepang kenapa mereka sangat jujur dan menjaga kebersihan. Anak-anak itu menjawab ”jika kami mengambil makanan tanpa bayar, pasti yang punya swalayan rugi, jika rugi pasti penjualnya tidak mau lagi berjualan, jika tidak ada penjual, ke mana kami harus membeli makanan? Sejak kecil mereka sudah sadar makna kejujuran. Begitu pula penanaman nilai kebersihan. Mereka diajarkan tiga kewajiban bersih yaitu; 1) wajib bersih kamar tidur, 2) wajib bersih ruang makan, 3) wajib bersih kamar mandi/wc. Orang Jepang tidak mengenal hadis Nabi ” Kebersihan itu bagian dari iman”, tetapi mereka lebih dahulu mengamalkan ajaran Islam. Ary Ginajar Agustian (penulis Buku ESQ Power) ketinggalan camera digitalnya di terminal kereta api Jepang selama kurang lebih enam jam. Namun sungguh luar biasa, ketika kembali ke terminal semula, dia masih menemukan camera tersebut di atas kursi di mana dia pernah duduk. Camera itu aman di tengah hilir-mudik manusia yang jumlahnya ribuan orang. Bandinkan dengan terminal kita, jangankan camera, Handphone saja yang tersimpan di saku bisa hilang, apalagi ditinggal di kursi terminal. Ary kemudian pulang menggunakan taksi ke hotel tempat dia menginap. Mungkin karena melamun, sang sopir kelupaan menurunkan Ary Ginanjar persis di depan hotel, tetapi kelewatan 20 meter. Ketika hendak dibayar, sang sopir menutup argonya dan berkata: Maaf, ini kesalahan saya, Bapak tidak usah membayar!” Bandingkan dengan kondisi di Indonesia, pernahkah sopir minta maaf dan tidak mau dibayar jika terlewat dari tempat kita singgah. Mungkin sebaliknya kita lah yang dimarahi sopir karena tidak mengingatkannya. Apa gerangan yang menyebabkan orang Jepang memiliki komitmen dengan kejujuran dan kedisiplinan. Di samping warisan nilai-nilai Bushido kaum Samurai, ternyata mereka juga belajar dari sekuntum bunga Sakura, bunga yang hanya hidup sekali dalam satu tahun yaitu seminggu selama bulan April. Akan tetapi di saat di merekah selama seminggu itu, orang-orang senang melihat, mendekat dan menciumnya. Bunga Sakura memberikan rona-rona keindahan bagi yang melihatnya, menaburkan kesejukan bagi yang mendekatinya dan menebarkan aroma indah bagi yang menciumnya. Bunga Sakura mewarnai falsafah hidup orang Jepang, meski hidup bunga Sakura singkat tetapi selalu memberikan yang baik dan terbaik kepada orang lain. Falsafah Sakura inilah yang tercermin dalam kehidupan mereka. Karena sadar hidup tidak lama, maka tiada waktu yang terlewat kecuali untuk berkarya berbuat kebaikan dan membangun peradaban. Karena itu, ambillah falsafah bunga Sakura! Suatu hari Panglima pasukan kerajaan Romawi merasa tidak percaya dengan situasi yang menimpa pasukannya karena selalu mengalami kekalahan melawan pasukan Islam. Menurutnya, sangat tidak mungkin 8 pasukannya yang terlatih, memiliki jumlah yang banyak dilengkapi dengan persenjataan lengkap menelan kekalahan dari pasukan Islam yang jumlahnya relatif kecil. Untuk itu, Panglima mengutus mata-mata (spionase) menyelinap masuk ke wilayah pasukan Islam untuk menyelidiki rahasia kekuatan pasukan Islam yang selalu sukses menaklukan wilayah yang dikuasai oleh tentara Romawi. Dari hasil investigasinya, mata-mata (spionase) tersebut melaporkan kepada Panglima sebuah rahasia di balik kekuatan pasukan pasukan Islam. Menurutnya, pasukan Islam itu memang relatif kecil dan sedikit, tetapi mereka adalah segolongan kaum yang pada malam hari seperti “pendeta” (orang yang taat beribadah), dan di siang hari seperti “singa”. Laporan seorang spionase ini menggambarkan bagaimana etos masyarakat/pasukan Islam pada saat itu. Mereka bukan saja taat beribadah ritual di malam hari, tetapi sangat energik di siang hari. Rahasia kesuksesan mereka adalah kemampuan memadukan antara semangat ritualitas dengan nilai fungsionalitas agama. Islam dipandang sebagai agama langit, tetapi nilai-nilainya harus membumi. Oleh karena itu, belum sempurna keislaman dan keimanan seseorang jika beragama hanya sebatas simbolik-dekoratif, tidak mampu mengaktualisasikan nilai ke dalam aksa nyata. Itulah sebabnya begitu banyak teks suci, baik dari al-Quran dan hadis yang mengingatkan manusia agar keberagamaan harus mencerminkan nila-nilai fungsional. Di dalam QS al-Maun (1-7) Allah mengancam orang yang salat disebabkan mereka tidak mampu menerapkan esensi salat dalam kehidupan. Nabi juga mengingatkan bagi orang yang berpuasa agar mampu mengimplementasikan nilai puasa. Jika tidak, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Demikian juga halnya dengan ibadah haji, betapa banyak orang tidak mendapatkan predikat haji mabrur, dikarenakan ibadahnya hanya sebatas simbol dan dekoratif. Agama bukanlah sebuah produk pemikiran manusia seperti budaya yang penuh dengan simbol dan dekorasi, tetapi agama merupakan institusi kewahyuan dan keilahian yang Allah berikan kepada umat manusia. Ia sarat dengan nilai dan makna. Esensi agama bukan rangkaian sejumlah simbol seperti di dalam budaya, akan tetapi merupakan sistem nilai yang harus terefleksi fungional dalam setiap gerak dan tindakan manusia. Hanya saja, disebabkan agama datang dan hadir di tengah masyarakat yang tidak hampa dari budaya, maka agama seringkali berbaur dengan budaya. Di suatu waktu, agama mampu mewarnai budaya, sebaliknya terkadang budaya juga mengintervensi agama. Akibatnya, para penganut agama terkadang sulit membedakan mana agama an sich dan mana budaya. Menurut Clifford Geert (1995 ) budaya memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberagamaan seseorang, bahkan manusia tidak mampu melepaskan diri dari kehidupan yang memang dikelilingi oleh budaya. Karena manusia hidup pada sebuah lingkungan yang berbudaya, maka setiap individu yang hidup di dalam sebuah lingkungan tertentu, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh tradisi lingkungan tersebut. Dari sinilah kemudian nilai agama berubah menjadi ritual-formal. Kondisi ini menurut , Nurchalis Madjid (1992), membawa akibat adanya realitas keragaman penerapan prinsip-prinsip umum dan universalitas agama, yaitu keanekaragaman terkait dengan tatacara dan ekspresi ritual keberagamaan di dalam masyarakat, dengan sedikit mengabaikan nilai fungsional yang terkandung di dalamnya. Akibatnya keberagamaan manusia menjadi kering. Yang tumbuh dipermukaan adalah pertikaian masalah khilafiyah akibat ritualitas agama yang berbeda, sementara moralitas dan 9 akhlak yang menjadi esensi utama agama justeru terabaikan. Dalam kehidupan beragama, sudah saatnya masyarakat mampu berhijrah dari tradisi ritual ke tradisi fungsional. Artinya, ritualitas yang selama ini dijalankan harus mampu memberikan nilai-nilai kebaikan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Misalnya, ritual zikir (akbar) yang sering dilaksanakan dalam peringatan tahun baru Islam atau kegiatan lainnya tidak selalu harus dimaknai dengan zikir lisani (zikir dengan lisan), tetapi dapat ungkapan kalimat zikir itu diaplikasikan dengan zikir amali. Jika yang dipahami dan dilaksanakan masyarakat selama ini hanya sebatas zikir lisani, maka zikir ini bisa jadi kurang efektif ”merayu” Tuhan untuk merubah sebuah bangsa dari bangsa yang miskin menuju bangsa yang modern. Perubahan semacam ini harus disertai dengan zikir amali. Banyak orang yang beranggapan bahwa membersihkan selokan atau menyapu halaman hanya sebuah aktifitas duniawi, padahal dalam perspektif agama, kegiatan ini dipandang sebagai zikir amali. Demikian juga ketika masyarakat berkumpul dan bersama-sama mengumpulkan beras dan pakaian layak pakai, lalu membagikannya kepada fakir-miskin ke empat penjuru, maka Allah pasti ”tersenyum” bangga kepada hambaNya yang sudah berzikir amali karena mengikuti sifat Allah (al-Rahman-al-Rahim). Bukan hanya lidah yang dapat berucap dengan kalimat zikir, tetapi seluruh sel-sel darah, nadi dan denyut jantungpun berzikir menyebut nama Allah. Contoh lain, salat dan puasa yang mengajarkan kejujuran tidak boleh kehilangan makna fungsionalnya. Demikian pula ibadah zakat dan haji yang mengajarkan kepekaan dan kepeduliaan tidak boleh lagi dimaknai secara dekoratif dan demontratif. Dalam hal kehidupan bernegara. Indonesia harus mampu berhijrah dan keluar dari degradasi moral ke sebuah masyarakat yang berperadaban. Kejujuran, kedisiplinan, keadilan, kasih sayang, kebersamaan harus menjadi nilai inti kehidupan bernegara dan berbangsa. Nilai agama mengajarkan manusia untuk pandai-pandai membaca realitas sosial guna memperkaya perspektif batin dalam menghadapi tantangan moral zaman. Doktrin aqidah, syariah dan muamalah yang terdapat di dalam agama (baca; Islam) harus menjadi lebih fungsional dan menjadi pegangan dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Aqidah fungsional mewakili dimensi afektif (religious conscousness) yang dapat menjadikan manusia memiliki mental dan moral yang teguh dan kokoh, sebab akidah pada hakikatnya membentuk manusia membebaskan diri dari tirani hawa nafsu yang selama ini boleh jadi menjadi “agama baru” di dalam kehidupannya. Akidah fungsional mendidik manusia tentang kesadaran ilahiyah, yaitu sebuah kesadaran akan ”hadirnya” Tuhan di setiap ruang dan waktu. Kesadaran ini sejatinya menumbuhkan sifat kejujuran, kesabaran, kedisiplinan dan kepekaan sosial. Syariah fungsional mewakili dimensi kognitif (ilmu) yang mendorong manusia melahirkan karya dan kreativitas, sehingga tidak lagi larut dan terjebak pada persoalan furu’iyah yang cukup menghabiskan energi untuk selalu berdebat dan saling menyalahkan. Sedangkan muamalah fungsional mewakili dimensi psikomotorik agar manusia cerdas dalam kehidupan bersama dan bersesama. Perbedaan suku, agama, ras, bahasa dan warna kulit tidak lagi dipandang sebagai perbedaan yang membawa kepada perpecahan, tetapi sebuah keniscayaan keragaman yang menghantarkan masyarakat Indonesia kepada persatuan. Karena itu, perayaan tahun baru hijriah 1432 kali ini seharusnya dijadikan sebagai momen untuk berhijrah dari kehidupan yang tidak baik kepada kehidupan yang lebih lebih baik. 10 Etika sebagai basis Berteologi Dalam kehidupan beragama, yang perlu ditonjolkan bukan klaim kebenaran tunggal, siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah? Siapa yang berhak mendapat surga dan siapa yang harus dilempar ke neraka? Bukan siapa yang menjadi cicak atau buaya, bukan pula siapa yang menjadi kanker dan tubuh, tetapi yang dibutuhkan adalah tekad dan komitmen untuk membangun sebuah peradaban unggul yang berbasis pada semangat kebersamaan dan persaudaraan sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui negara Madinahnya. Saatnya kita memikirkan secara seksama, sudah berapa banyak kesalehan sosial yang kita lakukan untuk berloma-lomba berbuat kebajikan ( Q.S. Al-Maidah/5: 48 ) Meneror, menyerang dan membakar rumah ibadah kelompok minoritas keagamaan yang ada di negeri ini bukanlah perbuatan terpuji. Melakukan sebuah amar ma’ruf nahi munkar dengan sebuah kemunkaran juga adalah kejahatan. Syafi’i Ma’arif (Mantan pimpinan PP Muhammadiyah) menyatakan kekecewaannya atas tindakan brutal dan sewenang-wenang sekelompok orang yang merasa paling ”berislam” dan merasa paling benar dengan menampilkan wajah Islam yang seram dan keras dalam beragama. (Fajar K. , Teologi Kenabian; 5) Dalam perspektif agama, akidah atau keyakinan terhadap doktrin agama yang dianut memang menjadi satu hal yang paling sakral, bahkan bisa jadi lebih sakral dari agama itu sendiri. Ketika keyakinan itu diusik, atau hanya karena ada kelompok lain yang berbeda dengan paham yang dianut, maka muncul persoalan dan melahirkan benturan antar kelompok yang menjurus kepada kekerasan bahkan stigma pengafiran. Padahal Allah berfiman dalam QS. al-Nisā: (4): 94: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengatakan “salam” (lailahaillallah) kepadamu, ”kamu bukan seorang yang beriman. Demikian juga Nabi mengingatkan dalam beberapa hadisnya, di antaranya: Barangsiapa yang shalat seperti shalat kita, berkiblat seperti kiblat kita, dan memakan sembelihan kita, maka ia adalah orang muslim yang mempunyai jaminan dari Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu mengecoh Allah dalam hal jaminanNya. (H.R. Bukhari: 167). Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan saudaranya kafir, (jika tidak benar) maka kekafiran itu kembali kepada dirinya. Sudah saatnya masyarakat harus memiliki kearifan teologis dan mampu mendefinisikan diri di tengah paham orang lain yang berbeda dengan pahamnya. Permusuhan, kebencian, pertikaian dan saling menghina di antara umat Islam akibat perbedaan paham itu merupakan kanker-kanker ganas yang akan mengganggu bahkan mematikan ”tubuh” Islam. Fenomena kekerasan dalam berteologi, khususnya seperti yang dialami oleh penganut Syiah Sampang Madura mengisyaratkan bahwa sensitivitas keberagamaan di tengah masyarakat modern dan demokratis ini masih menjadi bahaya laten bagi munculnya konflik berpaham di tengah masyarakat. Meski berada dalam sebuah rumah yang sama dan diatur oleh rujukan teks suci yang sama, akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa konflik horisontal bernuansa perbedaan mazhab teologi ini masih saja terjadi dan bahkan menjadi ancaman kehidupan 11 beragama. Alasan teologis dijadikan alasan dasar untuk meneror, membantai dan menghabisi kelompok lain yang tidak sepaham atau tidak sama dalam berteologi. Untuk mengatasi konflik berteologi ini diperlukan sebuah upaya dialogis untuk menghadirkan kesadaran teologis di kalangan masyarakat muslim agar mareka mampu mendefinisikan dirinya di tengah keragaman paham atau mazhab. Seperti diketahui, konflik bernuansa SARA kembali terjadi. Kelompok minoritas Syiah di Sampang diserang oleh warga yang tidak setuju kelompok ini tinggal di sekitar wilayah mereka. Alasannya masih klasik, kelompok Syiah dianggap sesat karena teologinya berbeda dengan masyarakat Sunni. Efek kekerasan ini menelan banyak korban. Sejumlah rumah dan pesantren Syiah habis dibakar, warga Syiah diusir dari kampung halamannya, sementara anakanak mereka mengalami trauma. Konflik Sunni-Syiah sebenarnya berawal dari persoalan politik tentang siapa yang berhak mengganti Nabi setelah wafat. Menurut Syiah, berdasarkan sejumlah indikator, Ali ra mestinya lebih berhak mengganti Nabi saw. Akan tetapi, faktanya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Konflik kemudian berlanjut ketika Ali ra menjadi khalifah. Pada saat itu, Muawiyah bin Abi Sofyan (Gubernur Damaskus) mendesak Ali menuntaskan kasus pembunuhan Usman. Dianggap tidak mampu, Muawiyah memberontak. Akibatnya, terjadilah perang saudara yang dikenal dengan perang Siffin. Dalam perkembangan selanjutnya, pengikut Ali dan keturunananya disebut sebagai Syiah dan Mu’awiyah dianggap sebagai kelompok Sunni. Dalam perspektif teologis, kelompok Sunni menjadikan mazhab Asyariyah dan Maturidiyah (ahl al-Sunnah wa al-Jamaah) sebagai landasan teologisnya dan berkembang menjadi sebuah kekuatan teologi mainstream hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas muslimnya termasuk di Indonesia, sedangkan Islam syiah lebih mengadopasi teologi Mu’tazilah dan mengukuhkan dirinya di Iran sebagai pusat kekuatan spiritualitas syiah. Jika hari ini kita menyaksikan sejumlah konflik antara Sunni dan Syiah di sejumlah negara, hal ini tidak lain merupakan kelanjutan luka dan ”dendam” lama yang tidak pernah pudar di hati masing-masing, dan sepertinya terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Hanya saja, isu konflik bukan lagi persoalan politik, tetapi memasuki wilayah teologi (keyakinan). Orang Syiah dianggap memiliki keyakinan (rukun iman) yang berbeda dengan kebanyakan Islam sunni lainnya, karenanya dipandang sesat. Fenomena perbedaan rumusan ini tampak pada bangunan rukun iman Syi’ah. Mazhab teologi ini memiliki lima rukun iman yang sedikit berbeda dengan mazhab teologi sunni, yaitu: (a) tauhid, (b) nubuwah, (c) al-ma’ad, (d) al-adl, dan (e) imamah. Dalam hal ini, tampaknya Syi’ah tidak menyebut butir-butir kepercayaan kepada para malaikat, kitab dan qad}a-qadar seperti yang terdapat dalam prinsip keimanan masyarakat Sunni. Quraish Shihab menyatakan hanya terdapat tiga prinsip dasar akidah Syi’ah yaitu (a) tauhid, (b) kenabian, dan (c) hari akhir. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak percaya kepada malaikat atau kitab-kitab, tetapi komponen itu bukan sistematika yang dirumuskan menjadi prinsip rukun iman tersebut. Ini berarti, secara prinsipil tidak terdapat perbedaan akidah yang mendasar antara Sunni dan Syiah. 12 Upaya menyatukan Sunni-Syiah sebenarnya sudah pernah digagas. Muktamar tokoh Sunni-Syiah yang menghadirkan delapan negara Islam, 21 Oktober 2006 menghasilkan apa yang disebut ”Deklarasi Mekkah” yang berisi antara lain; (a) kedua mazhab ini sepakat untuk saling mengakui dan saling memuliakan, (b) melarang saling memanggil kafir, karena muslim berarti siapa saja yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusanNya, (c) tidak boleh menghancurkan rumah ibadah atau fasilitas lainnya, (d) menghindari provokasi yang dapat menyulut konflik, (e) Sunni-Syiah bersatu dalam menentang kezaliman, penjajahan dan ketidakadilan. Demikian pula konferensi internasional pemimpin Islam, 3-4 April 2007 di Bogor sempat membicarakan tentang rekonsiliasi Sunni-Syiah sekaitan dengan konflik Irak. Salah seorang mufti Suriah yang beraliran Sunni bahkan berkata: ”Jika syiah bermakna penantangan terhadap arogansi Amerika, maka kita semua adalah syiah, dan jika sunni bermakna menentang kezaliman Israel atas Palestina, maka kita semua adalah sunni”. Dari ungkapan ini dipahami bahwa kedua mazhab teologi ini sesungguhnya memiliki misi yang sama. Hanya saja Deklarasi dan konferensi ini tampaknya belum dijadikan rujukan bagi pengikut keduanya, sehingga konflik masih tetap berlanjut hingga hari ini. Kondisi ini tentu sangat bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Islam merupakan agama yang sangat menghargai keragaman, baik paham maupun budaya. Penghargaan Islam yang demikian menyebabkan Islam tampil dengan bermacam-macam wajah keluhurannya yang bercorak lokal, terutama di Indonesia. Para tokoh agama dari semua mazhab teologi harus memberikan penyadaran kepada masyarakat pentingnya saling menyapa dan bersesama. Sudah saatnya kedua pengikut mazhab ini melupakan luka sejarah masa lalu. Indonesia khususnya harus menjadi model keberagamaan yang baik yang dapat dicontoh oleh negara lain. Karena itu, kesadaran berteologi melalui pendekatan pemahaman yang pluralis-dialogal menjadi sangat penting, agar kedua mazhab besar ini (Sunni-Syiah) dapat hidup bersama dan saling bergandengan tangan. Di era postmodernisme, setiap hari semakin dirasakan betapa intensnya pertemuan antar agama dan paham keagamaan. Di saat masyarakat masuk ke dalam alam demokrasi, informasi dan globalisasi doktrin-doktrin agama yang selama ini begitu kuat dianut mulai digugat. Munculnya persoalan kontroversial menyangkut teologi pluralisme, liberalisme dan aliran-aliran keagaamn lainnya sebagai bentuk jawaan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap paham yang ada, merupakan bukti nyata dari fenomena postmodernisme tersebut. Dengan demikian, era post modernisme merupakan suatu fase yang mengharuskan manusia mampu membawa diri dan paham keagamannya di tengah agama dan paham orang lain, tanpa harus memberikan sebuah klaim bahwa paham atau agama orang lain adalah sesat dan menyesatkan. Etika berpaham, beragama dan bermazhab harus menjadi poin pentin untuk merajut kebersamaan dalam kehidupan bersama dan bersesama. Di era postmodernisme ini, kontroversi teologis yang paling banyak diwacanakan adalah pluralisme agama, yaitu suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama bersumber dari sumber yang sama. Karena kebenaran agama bersifat relatif , maka tidak ada satupun agama yang boleh mengklaim hanya agamanya yang benar sedangkan agama lain sesat. Wacana pluralisme agama menjadi polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Ada kelompok yang mendukung dan ada yang menentang konsep pluralisme agama ini. Kedua kelompok sama-sama memiliki 13 argumen yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Pluralisme agama merupakan fakta sosial yang selalu ada dan telah menghidupi tradisi agama-agama. Walau demikian, dalam menghadapi dan menanggapi kenyataan adanya berbagai agama yang demikian pluralistik itu, agaknya setiap umat beragama tidaklah monolitik. Mereka cenderung menempuh cara dan tanggapan yang berbedabeda, yang jika dikategorisasikan terbelah menjadi dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Pertama, kelompok yang menolak secara mutlak gagasan pluralisme agama. Mereka biasanya disebut sebagai kelompok eksklusivis. Dalam memandang agama orang lain, kelompok ini sering kali menggunakan standar-standar penilaian yang dibuatnya sendiri untuk memberikan vonis dan menghakimi agama lain. Secara teologis, misalnya, mereka beranggapan bahwa hanya agamanyalah yang paling otentik berasal dari Tuhan, sementara agama yang lain tak lebih dari sebuah konstruksi manusia, atau mungkin juga berasal dari Tuhan tapi telah mengalami perombakan dan pemalsuan oleh umatnya sendiri. Mereka memiliki kecenderungan membenarkan agamanya, sambil menyalahkan yang lain. Memuji agama diri sendiri seraya menjelekkan agama yang lain. Agama orang lain dipandang bukan sebagai jalan keselamatan paripurna. Mereka mendasarkan pandangan-pandangannya itu pada sejumlah ayat di dalam Alquran, Misalnya, QS Ali Imran (3): 85, QS Ali Imran (3): 19 , QS Al-Maidah (5): 3. , QS An-Nisa (4): 144. Bahkan di dalam agama Islam sendiri, terdapat juga kelompok yang tidak mengakui adanya pluralisme di dalam paham Islam sendiri. Kelompok ekslusif seperti ini menganggap hanya paham kelompoknya yang paling benar sedangkan lain salah. Menurut mereka dalam perspektif teologis kelompok merekalah yang paling benar sementara yang lain salah. Mereka menganggap hanya golongannya yang berhak masuk surga sementara yang lain tidak berhak. Oleh karena itu ungkapan "kafir" yang ditujukan kepada kelompok tertentu bukan sesuatu hal yang aneh di abad postmodernisme ini. Kedua, kelompok yang menerima pluralisme agama sebagai sebuah kenyataan yang tak terhindarkan. Kelompok ini biasanya berpandangan bahwa agama semua nabi adalah satu. Mereka menganut pandangan tentang adanya titik-titik persamaan sebagai benang merah yang mempersambungkan seluruh ketentuan doktrinal yang dibawa oleh setiap nabi. Bagi kelompok kedua ini cukup jelas bahwa yang membedakan ajaran masing-masing adalah dimensidimensi yang bersifat teknis-operasional bukan yang substansial-esensial, seperti tentang mekanisme atau tata cara ritus peribadatan dan sebagainya. Pandangan kelompok pluralis ini juga merujuk kepada sejumlah ayat al-Quran. Misalnya, QS Al-Kafirun (109): 6, QS Al-Baqarah (2): 256, QS Al-Maidah (5): 69, QS Al-An'am (6): 108. al-Hajj (22) : 17. Hasibullah Satrawi (Alumnus al-Azhar Kairo) menyatakan terdapat kurang lebih 255 ayat yang berkenaan langsung dengan pluralisme ini. Ayat, bahkan menurutnya Muhammad Imarah (1997) pemikir Mesir menyatakan bahwa pluralisme tidak hanya menjadi ajaran atau spirit Islam, tetapi lebih dari itu ia menjelma sebagai bentuk formal berbagai disiplin keilmuan. Lihat Hasibullah Sastrawi, Menyelami lautan Pluralisme Islam (Republika, Jum'at 22 Desember 2006) Berdasarkan ayat-ayat al-Quran kaum pluralis berkeyakinan bahwa semua pemeluk agama memiliki peluang yang sama untuk memperoleh keselamatan dan rahmat Allah, sebab rahmat Allah sangat luas melebihi luasnya alam jahad raya, kasih sayang Allah melebihi seluruh akumulasi kasih saying ibu kepada anak-anaknya. 14 Kontradiksi nyata antara beberapa ayat al-Quran yang mengakui sumber-sumber penyelamatan otentik lainnya di satu sisi dan ayat-ayat lain yang menyatakan Islam sebagai satu-satunya sumber penyelamatan di sisi lain harus diatasi untuk memungkinkan tegaknya sebuah tata kehidupan berdampingan secara damai dengan umat agama lain. Dalam kenyataannya sayang sekali tidak banyak para ulama dan cendekiawan muslim yang memiliki perhatian utama untuk mencoba menyelesaikan ayat-ayat kontradiktif tersebut, baik dengan cara memperbarui penafsiran maupun dengan menyusun sebuah metodologi tafsir yang baru. Hingga sekarang, sekelompok pemikir Islam yang concern pada gagasan pluralisme agama biasanya hanya mengutip satu-dua ayat yang mendukung pluralisme agama dan sering kali melakukan pengabaian bahkan terkesan “lari” dari ayat-ayat yang menghambat jalan pendaratan pluralisme agama. Demikian juga sebaliknya sembari merayakan ayat-ayat yang problematis dari sudut pluralisme agama, para ulama eksklusif kerap menafikan ayat-ayat yang secara literal jelas-jelas mendukung pluralisme agama. Oleh karena tidak ada penyelesaian metodologis dari kedua kubu ini, maka di satu ada sejumlah yang mengafirkan pluralisme, tetapi di sisi lain terdapat pula ulama yang membela pluralisme agama. Atas dasar pertimbangan ini, maka pendidikan etika Islam di semua lini harus menjadi perhatian serius. Etika Islam harus masuk dan menjadi bagian penting dalam aspek ibadah, muamalah, social dan politik, sebab jika tidak, maka peradaban yang diharapkan tidak akan tercapai dengan baik, sebab bangunan fondasi peradaban hanya didasarkan atas epistimologi intelektualitas yang rapuh, tidak menggandenga aspek etika dalam mengunstruksi sebuah sejarah peradaban. Belajarlah ke masa lalu….bukankah kehancuran sebuah bangsa bukan karena rendahnya kadar intelektualitas yang dimiliki, tetapi rendah dan bobroknya nilai-nilai etika yang dimiliki sehingga Tuhan sebagai sumber etis mendatangkan bencana kepada mereka sebagai efek berpalingnya mereka dari Tuhan. 15 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Islam merupakan salah satu agama samawi yang meletakan nilai-nilai kemanusia atau hubungan personal, interpersonal dan masyarakat secara agung dan luhur, tidak ada perbedaan satu sama lain, keadilan, relevansi, kedamaian yang mengikat semua aspek manusia. Islam yang berakar pada kata “salima” dapat diartikan sebagai sebuah kedamaian yang hadir dalam diri manusia dan itu sifatnya fitrah. Kedamaian akan hadir, jika manuia itu sendiri menggunakan dorongan diri (drive) ke arah bagaimana memanusiakan manusia dan atau memosisikan dirinya sebagai makhluk ciptaaan Tuhan yang bukan saja unik, tapi juga sempurna, namun jika sebaliknya manusia mengikuti nafsu dan tidak berjalan seiring fitrah, maka janji Tuhan adzab dan kehinaan akan datang. Fitrah kemanusiaan yang merupakan pemberian Tuhan (Given) memang tidak dapat ditawar, dia hadir seiring tiupan roh dalam janin manusia dan begitu manusia lahir dalam bentuk “manusia” punya mata, telinga, tangan, kaki dan anggota tubuh lainnya sangat tergantung pada wilayah, tempat, lingkungan dimana manusia itu dilahirkan. Anak yang dilahirkan dalam keluarga dan lingkungan muslim sudah barang tentu secara akidah akan mempunyai persepsi ketuhanan (iman) yang sama, begitu pun Nasrani dan lain sebagainya. Inilah yang sering dikatakan sebagai sudut lahirnya keberagamanaan seorang manusia yang akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam wacana studi agama sering dikatakan bahwa fenomena keberagamaan manusia tidak hanya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang normativitas melainkan juga dilihat dari historisitas.1 Keberagamaan dalam Islam tentu saja harus dipandang secara konprehenshif dan seyogyanya harus diposisikan sbagai sebuah perspektif tanpa menapikan yang lain. Keberagamaan yang berbeda (deferensial) antara satu dengan yang lainnya merupakan salah satu nilai luhur kemanusiaan itu sendiri. Islam lahir dengan pondasi keimanan, syariat, muamalat dan ihsan. Keimanan adalah inti pemahaman manusia tehadap Sang Pencipta, syariat adalah jalan menuju penghambaan manusia kepada tuhannya, sedangkan muamalat dan ihsan adalah keutamaan manusia memandang dirinya dan diri orang lain sebagai sebuah hubungan harmonis yang bermuara pada kesalehan sosial. Etika dalam Islam adalah salah satu bidang yang menjadi perhatian utama. Dalam setiap masyarakat terdapat sosok ulama yang terus membina anggotanya agar akhlak atau etika tetap hidup di tengah-tengah mereka. Bahkan ajaran tentang etika telah banyak dituangkan ke dalam bentuk karya tulis. Di samping internal ummat Islam, di wilayah eksternal Islam pun marak dilakukan kajian tentang tema yang sama. Berbagai teori telah dihasilkan, mulai dari yang berbasis agama, hingga yang menafikannya, dari yang berbasis ego, hingga dari mereka yang berusaha mematikannya. A. Pengertian Etika Untuk memahami etika, terutama sebagai pembahasan persoalan tentang kebaikan manusiawi, kebahagian dan pencapaiannya, kita perlu lebih fokus pada penetapan landasan dan pembentukan landasan kriteria untuk mengevaluasi (jenis-jenis) tindakan tertentu, ketimbang apa yang diperlukan untuk membangun kehidupan manusia 1 Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas dan Historitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. V. 1 yang terbaik. Atau barangkali kita lebih banyak menggarap pembahasan metateoritis tentang sifat dasar diskursus etis dari pada perkembangan kecenderungan etis atau pandangan moral tertentu. Secara umum, kita dapat memandang bahwa etika lebih sebagai usaha teoretis ketimbang usaha praktis. Dengan demikian, kita tidak lagi memandang etika dalam cara klasik.2 Menurut bahasa (etimologi) istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang dalam bentuk jamak (ta etha) yang berarti adat kebiasaan.3 Arti ini menjadi bentuk penjelasan etika yang oleh Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukan istilah etika. Kata etos dalam bahasa Indonesia ternyata juga cukup banyak dipakai, misalnya dalam kombinasi etos kerja, etos profesi, etos imajinasi, etos dedikasi, etos kinerja, dan masih banyak istilah lainya.4 Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubunganya dengan baik dan buruk.5 Adapun etika apabila ditinjau dari segi terminologi, telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Ahmad Amin misalnya mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, manyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa seharusnya diperbuat.6 Menurut Sunoto, etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika Deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Contohnya sejarah etika. Adapun etika normatif sudah memberikan penilaian yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan dan yang tidak. Etika normatif dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum, seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati, dan sebagaimnya. Etika khusus adalah pelaksanaan prinsip-prinsip umum, seperti etika pergauulan, etika dalam pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan sebagainya.7 Selain pendapat di atas penulis juga mengutip pendapat Frans Magnis Suseno yang menyebutkan bahwa etika dapat dibagi ke dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubunganya dengan kewajiban, manusia dalam berbagai lingkungan kehidupanya.8 2 Sayyed Hussein Nasr dan Oliver Leaman, (Ed)., History of Islamic Philosophy, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Mizan dengan judul, Ensiklopedi Filsafat Islam, Jilid II. (Cet. I; Bandung: Mizan, 2003), h. 1277. 3 Donny Grahal Adrian, Menyoal Objektifitas Ilmu Pengetahuan: Dari David Hume Sampai Thomas Kuhn, (Cet. I; Jakarta: TERAJU, 2002), h. 173. 4 M. Yatim Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2006), h. 4. 5 Surajio, Filasafat Ilmu dan Perkembanganya di Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 146. Lihat juga Donny Grahal Adrian, op. cit., h. 167. Lihat juga Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan: Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan, (Cet. I; Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2005), h. 165. 6 Ahmad Amin, al-Akhlak, diterjemahkan oleh Farid Ma’ruf dengan judul Etika (Ilmu Akhlak). (Cet. III; Jakarta: Bulang Bintang, 1983), h. 3. 7 Sunnoto, Bunga Rampai Filsafat, (Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Fak. Filsafat UGM; 1982), h. 1. 8 Frans Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 1. 2 Dalam tradisi filsafat istilah “etika” lazim dipahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Persolan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat mulai ditinjau kembali secara kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang konkrit sedangkan etika bekerja dalam level teori. Nilai-nilai etis yang dipahami, diyakini, dan berusaha diwujudkan dalam kehidupan nyata kadangkala disebut ethos. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan manjadi dua: obyektivisme dan subyektivisme. Yang pertama berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat obyektif, terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Paham ini melahirkan apa yang disebut paham rasionalisme dalam etika. Suatu tindakan disebut baik, kata paham ini, bukan karena kita senang melakukannya, atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat begitu. Tokoh utama pendukung aliran ini ialah Immanuel Kant, sedangkan dalam Islam –pada batas tertentu– ialah aliran Mu’tazilah. Aliran kedua ialah subyektifisme, berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subyek tertentu. Subyek di sini bisa saja berupa subyektifisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subyek Tuhan. Paham subyektifisme etika ini terbagi kedalam beberapa aliran, sejak dari etika hedonismenya Thomas Hobbes sampai ke paham tradisionalismenya Asy’ariyah. Menurut paham Asy’ariyah, nilai kebaikan suatu tindakan bukannya terletak pada obyektivitas nilainya, melainkan pada ketaatannya pada kehendak Tuhan. Asy’ariyah berpandangan bahwa menusia itu bagaikan ‘anak kecil’ yang harus senantiasa dibimbing oleh wahyu karena tanpa wahyu manusia tidak mampu memahami mana yang baik dan mana yang buruk.9 B. Etika dalam Pandangan Islam Kalau kita sepakati bahwa etika ialah suatu kajian kritis rasional mengenai yang baik dan yang buruk, bagaimana halnya dengan teori etika dalam Islam. Sedangkan telah disebutkan di muka, kita menemukan dua paham, yaitu paham rasionalisme yang diwakili oleh Mu’tazilah dan paham tradisionalisme yang diwakili oleh Asy’ariyah. Munculnya perbedaan itu memang sulit diingkari baik karena pengaruh Filsafat Yunani ke dalam dunia Islam maupun karena narasi ayat-ayat al-Qur’an sendiri yang mendorong lahirnya perbedaan penafsiran. Di dalam alQur’an pesan etis selalu saja terselubungi oleh isyarat-isyarat yang menuntut penafsiran dan perenungan oleh manusia. Etika Islam memiliki antisipasi jauh ke depan dengan dua ciri utama. Pertama, etika Islam tidak menentang fitrah manusia. Kedua, etika Islam amat rasionalistik. Sekadar sebagai perbandingan baiklah akan saya kutipkan pendapat Alex Inkeles mengenai sikap-sikap modern. Setelah melakukan kajian terhadap berbagai teori dan definisi mengenai modernisasi, Inkeles membuat rangkuman mengenai sikap-sikap modern sabagai berikut, yaitu: kegandrungan menerima gagasan-gagasan baru dan mencoba metode-metode baru; kesediaan buat menyatakan pendapat; kepekaan pada waktu dan lebih mementingkan waktu kini dan mendatang ketimbang waktu yang telah lampau; rasa ketepatan waktu yang lebih baik; keprihatinan yang lebih besar untuk merencanakan organisasi dan 9 Komarudin Hidayat, Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern Studi Kasus Di Turki, (Jakarta: Paramadina), dalam kumpulan artikel Yayasan Paramadina, www.paramadina.com download tanggal 10 Januari 2008. 3 efisiensi; kecenderungan memandang dunia sebagai suatu yang bisa dihitung; menghargai kekuatan ilmu dan teknologi; dan keyakinan pada keadilan yang bisa diratakan. Rasanya tidak perlu lagi dikemukakan di sini bahwa apa yang dikemukakan Inkeles dan diklaim sebagai sikap modern itu memang sejalan dengan etika al-Qur'an. Dalam diskusi tentang hubungan antara etika dan moral, problem yang seringkali muncul ialah bagaimana melihat peristiwa moral yang bersifat partikular dan individual dalam perspektif teori etika yang bersifat rasional dan universal. Islam yang mempunyai klaim universal ketika dihayati dan direalisasikan cenderung menjadi peristiwa partikular dan individual. Pendeknya, tindakan moral adalah tindakan konkrit yang bersifat pribadi dan subyektif. Tindakan moral ini akan menjadi pelik ketika dalam waktu dan subyek yang sama terjadi konflik nilai. Misalnya saja, nilai solidaritas kadangkala berbenturan dengan nilai keadilan dan kejujuran. Di sinilah letaknya kebebasan, kesadaran moral serta rasionalitas menjadi amat penting. Yakni bagaimana mempertanggungjawabkan suatu tindakan subyektif dalam kerangka nilai-nilai etika obyektif, tindakan mikro dalam kerangka etika makro, tindakan lahiriah dalam acuan sikap batin. Dalam persfektif psikologi, manusia terdiri atas tiga unsur penting yaitu, Id, Ego, dan Superego, sedangkan dalam pandangan Islam ketiganya sering dipadankan dengan nafs amarah, nafs lawwamah, dan nafs mutmaninah. Ketiganya merupakan unsur hidup yang ada dalam manusia yang akan tumbuh berkembang seiring perjalanan dan pengalaman hidup manusia. Maka untuk menjaga agar ketiganya berjalan dengan baik, diperlukan edukasi yang diberikan orang tua kepada anaknya dalam bentuk pemberian muatan etika yang menjadi ujung tombak dari ketiga unsur di atas.10 C. Objek Kajian Etika Islam dan Argumen Teologisnya Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika, jika etika dibatasi pada sopan santun antarsesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah saja. Akhlak lebih luas maknanya daripada etika. Misalnya yang berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. Akhlak diniah (agama) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tidak bernyawa).11 Berikut ini adalah upaya pemaparan secara singkat beberapa sasaran akhlak Islamiyah. Pertama, akhlak terhadap Allah, titik tolak akhlak terhadap Allah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji; demikian agung sifat itu, yang jangankan manusia, malaikat pun tidak akan mampu menjangkau hakekat-Nya. Sebagaimana ungkapan para penyair sebgai berikut: ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ رﺑﻨﺎ ﻻ ﻧﺤﺼﻰ ﺛﻨﺎء ﻋﻠﯿﻚ اﻧﺖ ﻛﻤﺎ اﺛﻨﯿﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ “Mahasuci engkau–Wahai Allah–kami tidak mampu memuji-Mu; pujian atas-Mu, adalah yang engkau pujikan kepada diri-Mu”.12 10 Ahmad Mudlor, Etika Dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, t.th), h. 155. 11 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Ummat, (Cet. VI; Bandung : Mizan, 1997), h. 261. 12 Ibid., h. 262. 4 Itulah sebabnya mengapa al-Qur’an mengajarkan kepada manusia untuk memujinya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah sebagai berikut: ٩٣ َﺳﯿُﺮِﯾﻜُﻢۡ ءَا َٰﯾﺘِ ِﮫۦ ﻓَﺘَﻌۡ ِﺮﻓ ُﻮﻧَ َﮭ ۚﺎ َوﻣَﺎ َرﺑﱡ َﻚ ﺑِ َٰﻐﻔِ ٍﻞ َﻋﻤﱠﺎ ﺗَﻌۡ َﻤﻠ ُﻮن َ ِ َوﻗُ ِﻞ ٱﻟۡ ﺤَ ﻤۡ ُﺪ ِ ﱠ Artinya: “Dan katakanlah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhan tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan”.13 ١٦٠ َ إ ﱠِﻻ ِﻋﺒَﺎ َد ٱ ﱠ ِ ٱﻟۡ ﻤ ُۡﺨﻠَﺼِﯿﻦ١٥٩ َﺼﻔ ُﻮن ِ َﺳُﺒۡ ﺤَٰ ﻦَ ٱ ﱠ ِ َﻋﻤﱠﺎ ﯾ Artinya: “Mahasuci Allah dari segala sifat yang mereka sifatkan kepada-Nya, kecialai (dari) hamba-hamba Allah yang Terpilih”.14 Kedua, akhlak terhadap sesama manusia, banyak sekali rincian yang dikemukakan oleh al-Qur’an berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang di belakangnya kepada orang lain tidak perduli aib itu benar atau salah. Firman Allah: ٢٦٣ ٞﺻ َﺪﻗَﺔٖ ﯾَﺘۡ ﺒَﻌُ َﮭﺎٓ أَذٗ ىۗ وَٱ ﱠ ُ َﻏﻨِ ﱞﻲ ﺣَ ﻠِﯿﻢ َ ۡﺮ ﻣﱢﻦٞ ُوف َوﻣَﻐۡ ﻔِ َﺮةٌ ﺧَ ﯿ ٞ ﻣﱠﻌۡ ﺮٞ۞ﻗ َۡﻮل Artinya: “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari pada sedekah yang disertai dengan sessuati yang menyakitkan (perasaan si penerima)’.15 Di sisi lain al-Qur’an menerangkan bahwa setiap orang hendaknya didudukkan secara wajar. Nabi Muhammad saw – misalnya – dinyatakan sebagai manusia seperti manusia yang lain, namun dinyatakan pula bahwa Nabi Muhammad saw adalah Rasul yang memperoleh wahyu dari Allah. Atas dasar itulah Nabi Muhammad saw berhak memperoleh penghormatan melebihi manusia lain. Karena itu al-Qu’an berpesan kepada orang-orang mukmin: ٢ َﺾ أَن ﺗ َۡﺤﺒَﻂَ أَﻋۡ َٰﻤﻠُﻜُﻢۡ َوأَﻧﺘُﻢۡ َﻻ ﺗَﺸۡ ُﻌﺮُون ٍ ۡﻀﻜُﻢۡ ﻟِﺒَﻌ ِ ۡت ٱﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ َو َﻻ ﺗ َۡﺠ َﮭﺮُو ْا ﻟَ ۥﮫ ُ ﺑِﭑﻟۡ ﻘ َۡﻮ ِل ﻛَﺠَ ﮭۡ ِﺮ ﺑَﻌ ِ ق ﺻ َۡﻮ َ َﺻ َٰﻮﺗَﻜُﻢۡ ﻓ َۡﻮ ۡ ٰ ٓﯾَﺄَﯾﱡﮭَﺎ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَا َﻣﻨ ُﻮ ْا َﻻ ﺗ َۡﺮﻓَﻌُﻮٓ ْا أ Artinya: “Jangan meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi (saat berdialog), dan jangan pula mengeraskan suaramu (di hadapannya saat Nabi diam) sebagaimana (kerasnya) suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain….”. 16 .... ﻀ ۚﺎ ٗ ۡﻀﻜُﻢ ﺑَﻌ ِ ۡﱠﻻ ﺗ َۡﺠ َﻌﻠ ُﻮ ْا ُد َﻋﺎٓ َء ٱﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ِل ﺑَﯿۡ ﻨَﻜُﻢۡ َﻛ ُﺪ َﻋﺎٓ ِء ﺑَﻌ Artinya: “Janganlah kamu jadikan panggilan (nama ) Rasul di antara kamu, seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain)”.17 13 Q.S. al-Naml (27): 93. 14 Q. S. al-Shaffat (37): 159-160. 15 Q.S. al- Baqarah (2): 263. 16 Q.S. al- Hujrat (49): 2. 17 Q.S. al- Nur (24): 63. 5 Dari uraian di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Dalam tradisi filsafat istilah “etika” lazim dipahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Persolan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat mulai ditinjau kembali secara kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang konkrit sedangkan etika bekerja dalam level teori. Nilai-nilai etis yang dipahami, diyakini, dan berusaha diwujudkan dalam kehidupan nyata kadangkala disebut ethos. b. Etika dalam Islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan agung yang bukan saja beriskan sikap, perilaku secara normatif, yaitu dalam bentuk hubungan manusia dengan tuhan (iman), melainkan wujud dari hubungan manusia terhadap Tuhan, Manusia dan alam semesta dari sudut pangan historisitas. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagamaan seseorang. Maka Islam menganjurkan kepada manusia untuk menjungjung etika sebagai fitrah dengan menghadirkan kedamaian, kejujuran, dan keadilan. Etika dalam islam akan melahirkan konsep ihsan, yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan social hanya dan untuk mengabdi pada Tuhan, buka ada pamrih di dalamnya. Di sinilah pesan orang tua dalam memberikan muatan moral kepada anak agar mampu memahami hidup dan menyikapinya dengan bijak dan damai sebagaimana Islam lahir ke bumi membawa kedamaian untuk semesta (rahmatan lilalamain). 6 BAB II ETIKA, MORAL, NILAI DAN ESTETIKA Pergolakan wacana terus bergulir dan senantiasa berbanding lurus dengan kematangan kemampuan daya nalar manusia, banyak persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak tersingkap, tapi kemudian kini harus berhadapan dengan ketajaman rasio, tak mengenal apakah hal tersebut rill atau abstrak sifatnya, bagai air yang terus bergoliat untuk mencari celah guna samapi ke muarah. Satu hal yang dari dahulu dan bahkan hingga sekarang terus menjadi objek perdebatan ialah etika, moral, nilai dan estetika. Keruwetan persoalan ini bukan hanya karena sisi keabstrakannya, lebih dari pada itu karena hal tersebut terkesan memiliki pengertian yang sangat dekat hingga tidak jarang mengecoh intelektulaitas lalu kemudian terjerembab ke dalam kekeliruan penarikan kesimpulan. Tema ini terus bergurita dan memompakan gairah dan kehangatan bagi para pengkaji, wajar jika banyak tokoh yang berusaha tampil kepermukaan untuk memberikan konstribusi, tak ada maksud lain kecuali untuk menyingkap awan tebal yang menyelimuti hakikatnya. Akhirnya sah jika kemudian lontaran diskursus ini terwarnai dengan ragam pendapat, karena memang konteks yang demikian pulalah kerap jadi pemicu bagi lahirnya tokoh-tokoh baru, khususnya yang terkait dengan diktum ini. Melalui makalah singkat ini, penulis berupaya menyingkap pengertian dari keempat persoalan ini hingga batas kemampuan yang penulis miliki. Meski demikian, dalam pemaparannya kelak penulis membatasi fokus hanya pada persoalan pengertian baik secara istilah dan sekaligus mengurai perbedaan mendasar diantaranya. A. Pengertian Etika, Moral, Nilai dan Estetika 1. Pengertian Etika Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Dalam bentuk tunggal ethos berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan cara berpikir. Sementara dalam bentuk jamak, ta etha berarti adat kebiasaan. Filsafat sering mengistilahkan etika dengan apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaa.1 Etika merupakan kata lain dari bahasa Arab, khulq, jamaknya adalah akhlak. khulq merupakan kata yang bersal dari khalaqa yang berarti penciptaan, yaitu perilaku atau kelakukan-kelakukan yang berasal dari seseorang, masyarakat atau dalam hati nurani.2 Etika dalam hal ini juga senanitasa diasosiasikan dengan tabiat manusia, itulah sebabnya sehingga akhlak selalu dikaitkan dengan perbuatan baik atau buruk manusia itu sendiri. Pada posisi ini etika menjadi sebuah ilmu instrumen yang bertugas melakukan penyelidikan dan penilaian terhadap setiap perbuatan manusia. Oleh karena perbuatan manusia itu beragam, maka yang menjadi objek penelitiannya ialah nilainya. 3 Pertanyaannya kemudian 1 Muhammad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi, (Cet. I; Jakarta Kencana, 2009), h. 173. 2 Majid Fakhri, Etika dalam Islam, (Cet. I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 12. 3 Elga Sarapung, Sejarah, Teologi dan Etika Agama-Agama, (Cet. I; Yogyakarta : Dian/Interfidei, 2003), h. 288. 7 adalah, apakah manusia itu berkuasa atas perbuatannya, ataukah ada campur tangan pihak lain? Jika ada campur tangan yang lain, maka dimana dan sejauh apa batas kebebasan mausia dalam berbuat, serta bagaimana menilai jika itu bukan atas kehendaknya? Kenyataan inilah yang banyak mengundang perdebatan dalam aliran-aliran teologi Islam, terutama Qadariah dan Jabariah. Darji Darmodiharjo menegaskan bahwa sifat dasar etika ialah : a. Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku (mengkaji aturan main yang tertetapkan atau disepakati secara konfensional dalam suatu masyarakat). b. Mengajukan pertanyaan tentang legitimasi perbuatan, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya. c. Mempersoalkan hak seperti orang tua, sekolah, negara dan agama untuk mengambil sikap rasional. d. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang ambingkan oleh norma yang ada.4 Etika merupakan cabang filsafat yang berupaya mengupas tindakan manusia kaitannya dengan tujuan hidupnya. Etika membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, sekaligus menyorot kewajiban-kewajiban manusia. Dan secara substansial, etika mempersoalkan tentang bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak, ini pula yang sering diistilahkan dengan etika normatif, sedangkan gambaran dari gejala kesadaran, konsep dan norma disebut dengan etika deskritptif. Menurut Muliyadi Kartanegara bahwa etika ialah seni hidup yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang baik dalam arti memiliki perangai dan tingkah laku yang terpuji.5 2. Moral Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral sebagaimana ide-ide yang umum diterima ialah tindakan manusia terkait dengan yang baik dan yang wajar.6 Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan, namun ada pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu.7 Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai baik atau buruk perbutan manusia menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam pembicaran moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan 4 Muhammad Mufid , Op.cit., h. 174. 5 Mulyadi Kartanegara, Menembus Batas Waktu; Fanorama Filsafat Islam, (Cet. II; Bandung : IKAPI, 2005), h. 6 Fakhri Madjid, Etika dalam Islam, (Cet. I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 7. 7 Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Cet. II; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 19. 68. 8 berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dari sini kita bisa melihat asumsi moralitas Immanuel Kant sebagai sebuah parameter tindakan bahwa manusia dalam berbuat pada intinya hanya terikat dua hal, yaitu tindakan yang sesuai dengan kewajiban (moral) dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban.8 Istilah moral senantiasa mengacu kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia, ia dominan digunakan sebagai parameter untuk menetapkan betul atau salahnya tindakan manusia terkait dengan sesuatu hal. Seorang peribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kadiah dan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap bermoral, tapi jika sebaliknya maka pribadi tersebut dihakimi tidak bermoral. Oleh karena itu, moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji dan mulia. Ia juga dapat diasosiasikan dengan kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehiudpan.9 3. Nilai Kata “nilai” dapat didefinisikan sebagai perasaan tentang apa yang baik atau apa yang buruk, apa yang di inginkan atau apa yang tidak di inginkan, apa yang harus atau apa yang tidak boleh. Nilai berhubungan dengan pilihan, dan pilihan itu merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan. Seorang berusaha mencapai segala sesuatu yang menurut sudut pandangannya mempunyai nilai. Robin Williams membicarakan “nilai sosial”, yaitu nilai yang dijunjung tinggi orang banyak.10 Ada juga “nilai etika atau moral”, yakni ketentuan-ketentuan atau cita-cita dari apa yang dinilai baik atau benar oleh masyarakat. Satu lagi, “nilai budaya” yakni konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat, mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup.11 Menurut Murtadha Muthahari bahwa setiap sesuatu pada intinya bernilai, karena setiap sesuatu adalah merupakan sebuah tingkatan dari wujud, dan wujud adalah merupakan nilai itu sendiri.12 Meminjam istilah filosof bahwa wujud itu sama dengan kebaikan. Munculnya istilah tidak bernilai, itu disebabkan oleh kecenderungan untuk menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, mungkin karena sesuatu tersebut tidak mendatangkan kebaikan, atau bisa juga karena menimbulkan efek negatif, dan lain-lain. Pada posisi inilah menurut Muthahari nilai dikatakan relatif, yaitu nilai sesuatu bagi sesuatu yang lain. Ilustrasi yang menurut penulis sangat menarik terkait dengan pembahasan ini ialah analogi ‘uang’. Uang dikatakan bernilai karena ia memberikan manfaat bagi manusia, akan tetapi manakala uang dibandingkan dengan kesehatan, kemuliaan atau harga diri, maka uang akan kehilangan nilainya dan akan menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Oleh karena itu, jika sesorang menyukai uang, dan pada saat yang sama dia juga orang yang memiliki 8 Budi Hardiman, Filsafat Moderen, (Cet. II; Jakarta : IKAPI, 2007), h. 146. 9 Syed Hussein Mohammad Jafri, Political and Moral Vision of Islam. terj. Ilyas Hasan, Moralitas Politik Islam, (Cet. I; Jakarta : Pustaka Zahra, 2003), h. 123. 10 11 www. pemahaman-nilai-filosofi-etika-dan-estetika.com. diakses pada tanggal 23 September 2011. R.M Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 1981), h. 17. 12 Murtadha Muthahari, Bis Guftor. terj. Ahmad Subandi, Ceramah-Ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan Kehidupan, (Cet. VI; Jakarta : Lentera, 2000), h. 100. 9 kemuliaan dan kehormatan diri, maka dia akan berusaha mencari uang sampai batas-batas dimana kemuliaan dan harga dirinya tetap terjaga. Disisi lain, kita bisa melihat asumsi keterikatan nilai dan moral sebagaimana yang dikemukakan oleh Taqi Misbah Yazdi bahwa predikat nilai dapat dilihat pada dua hal, yaitu obligatif dan evaluatif. Maksudnya bahwa evaluatif adalah sekumpulan konsep yang memuat nilai dan keutamaan seperti konsep baik, buruk, benar dan salah. Sedangkan obligatif ialah konsep yang membawa tuntunan dan pembebanan, seperti konsep harus dan mesti. 13 Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa cerminan nilai sesuatu dapat diukur dengan dua pendekatan ini. 4. Estetika Estetika (estetis) adalah cabang filsafat yang mempersoalkan seni (art) dan keindahan (beauty). Istilah estetika berasal dari kata Yunani “aesthesis”, yang berarti pencerapan indrawi, pemahaman intelektual, atau bisa juga berarti pengamatan spiritual. Istilah art (seni) berarti keindahan, keterampilan, ilmu, atau kecakapan. Keindahan atau estetika merupakan bagian dari filsafat yang mengkaji tentang keindahan sesuatu.14 Batasan keindahan sulit dirumuskan, hal ini disebabkan karena keabstrakan keindahan itu sendiri. Maka dari itu, bisa dikata bahwa batas keindahan adalah pada sesuatu yang indah, dan bukannya pada “keindahan itu sendiri”. Dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa pada intinya estetika erat kaitannya dengan nilai yang terkandung dibalik sesuatu. Pada persoalan inilah Oliver Leman menegaskan bahwa manusia dalam menciptakan karya selalu terilhami dengan pengetahuannya tentang nilai, semakin peka seseorang terhadap realitas (nilai sesuatu) maka akan semakin indah cara dia mengungkapkan realitas itu sendiri. Disisi lain, ketergantungan manusia pada estetika dapat dilacak dari proses keterlibatan aktifnya dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu, sekalipun pada saat itu ia tidak memiliki pengetahuan tentang asal usul sesuatu tersebut.15 Orang boleh saja tidak berpikir bahwa karya seni itu adalah ciptaan Tuhan, atau ciptaan siapa pun, tetapi tetap saja manusia selalu terusik untuk membahas rancangan dan struktur yang menyerta di dalamnya. Jelas paparan tersebut mengafirmasikan sebuah konsep mendasar bahwa manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya pada intinya tidak dapat dipisahkan dengan persoalan estetika. B. Perbedaan Mendasar antara Etika, Moral, Nilai dan Estetika Sekalipun keempat pokok persoalan di atas memiliki relasi/keterkaitan, dan bahkan bisa dikata tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, namun tetap saja terdapat perbedaan mendasar yang bisa mengantarkan pemahaman kita untuk tidak salah kaprah dalam penggunaan dan penempatannya. Berikut adalah perbedaan yang dimaksudkan : 1. Etika memiliki ciri sebagai berikut : 13 Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Falsafeh ye Akhlaq, terj. Ammar Fausi Heriyadi, Meniru Tuhan, antara yang terjadi dan yang mesti terjadi, (Cet. I; Jakarta : Al-Huda, 2006), h. 199. 14 Elly M. Setiadi, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Cet. V; Jakarta : Kencana, 2009), h. 166. 15 Oliver Leman, Islamic Aesthetics. terj. Irfan Abu Bakar, Menafsirkan Seni dan Keindahan Estetika Islam, (Cet. I; Bandung : Mizan, 2005), h. 38. 10 a. Ia menyangkut cara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu. b. Memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. c. Terkait dengan hukum ya atau tidak dari suatu tindakan atau perbuatan. d. Sifatnya mutlak, universal dan tidak berlaku proses tawar menawar di dalamnya. e. Menyangkut aspek internal manusia itu sendiri.16 2. Moral pada intinya memiliki dua kaidah dasar, yaitu : a. Kaidah sikap baik, maksudnya bahwa manusia mesti bersikap baik terhadap apa saja (diri, alam, lingkungan, sesama manusia, dan lain-lain). b. Kaidah Keadilan, yaitu penyeseuian tindakan baik dengan kadar kemampuan yang dimiliki.17 3. Nilai pada hakikatnya bertingkat-tingkat, yaitu : a. Nilai abstrak, seperti : demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, kedamaian dan kemajuan sosial, serta perwujudan dan penentuan diri. b. Nilai tingkat menengah, seperti : kualitas keberfungsian manusia/pribadi, keluarga yang baik, pertumubuhan, dan masyarakat yang baik. c. Nilai tingkat ketiga adalah merupakan nilai instrumental atau operasional yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial. d. Nilai yang telah diinternalisasikan ke dalam diri individu, akan menjadi kerangka refrensi individu tersebut, sebagai prinsip-prinsip etik.18 4. Esensialitas Estetika dapat digambarkan sebagai berikut : a. Mempermasalahkan seni atau keindahan yang diproduksi oleh manusia. b. Menjelaskan dan melukiskan fenomena pengalaman keindahan (deskriptif) serta menyelidiki hakikat, dasar dan ukuran pengalaman keindahan (normatif). c. Berkaitan dengan imitasi atau ekspresi personal atas suatu realtas.19 Pembahasan tersebut di atas mengantarkan suatu pemahaman bawha antara keempat persoalan tersebut di atas menempati ciri/esensi dan wilayah kerja yang berbeda, namun tetap memiliki titik persinggungan antara yang satu dengan yang lain. 16 Muhammad Mufid , Op.cit., h. 177-178. 17 Ibid., h. 180-181. 18 Ibid., h. 176. 19 Ibid., h. 178. 11 Setelah mengamati pembahasan tersebut di atas, maka pada poin penutup ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Etika pada intinya bersifat teoritis, yaitu memandang tingkah laku manusia secara universal, sedangkan moral lebih pada sikap praktis sehingga ia pun sarat denga ukuran-ukuran. Adapun nilai ialah sesuatu yang inklud dengan setiap wujud, sehingga setiap sesuatu dengan kaca mata ini sejatinya adalah memiliki nilai, sementara estetika merupakan cabang ilmu yang lebih menitik beratkan pengkajian pada aspek keindahan setiap maujud. 2. Perbedaan antara keempat hal tesebut ialah lebih pada cara pandang dan kerangka yang ditawarkannya sehingga sekalipun objek kajian hanya terdiri dari satu pokok persoalan, namun tetap saja ia bisa dibedakan dari sisi wilayah kerjanya masing-masing. 12 BAB III HUBUNGAN ETIKA DAN AGAMA Arus rasionalisasi demikian cepat melanda dunia Islam abad modern telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ilmu-ilmu keislaman.Sejalan dengan berkembangnya kajian-kajian rasional keislaman, kajian tentang pemikiran etika pun terangkat ke permukaan, bahkan menjadi topik kajian menarik dalam konteks kekinian dan kemodernan, karena etika merupakan salahsatu persoalan esensial dalam kajian keagamaan. Begitupun sebagian para ilmuan pada masa lalu berpandangan bahwa keberadaan agama secara perlahan akan ditelan oleh perkembangan zaman. Pandangan tersebut bertolak dari pemikiran bahwa perkembangan modernisasi dan sekularisasi menuntut sebuah peradaban yang mendasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan rasional, sedangkan perkembangan agama lebih mendasarkan pada keyakinan yang bersifat spekulatif dan tidak ilmiah.Tetapi dalam kenyataan hingga saat ini pandangan tersebut tidak terbukti, paling kurang hingga abad 21 ini. Tidak ada tanda-tanda yang meyakinkan bahwa agama akan ditinggalkan oleh para penganutnya. Hingga sekarang, sebagaimana yang kita saksikan, agama tetap berkembang di berbagai negara dan justru berperan penting dalam kehidupan sosial dan politik.1 Etika dan agama merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Meskipun manusia dilahirkan terpisah dari individu lain. Namun ia tidak dapat hidup sendiri terlepas dari yang lain, melainkan selalu hidup bersama dalam kelompok atau masyarakat yang oleh para filosof diartikan sebagai al-Insanu Madaniyyun bi athThab’i (zoon politicon.)2 Di dalam masyarakatlah manusia mengembangkan hidupnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan membangun peradaban. Itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain manusia saling memerlukan satu sama lain, apapun status dan keadaannya.3Untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bersama tersebut, di dalam masyarakat terdapat aturan, norma atau kaidah sosial sebagai sarana untuk mengatur roda pergaulan antar warga masyarakat. Itu sebabnya, selain ada agama, hukum, adat istiadat, juga ada akhlak, moral4 dan etika. A. Hubungan Etika dan Agama Etika berasal dari bahasa Yunani ethikos, ethos (adat, kebiasaan, praktek).5 Artinya sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari sebuah sistem nilai atau normayang diambil dari gejala-gejala 1 Imam Tholkhah, Fanani Suprianto, Gerakan Islam Klasik dan Kontradiksi Faham Keagamaan (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2002), h. 1. 2 Lihat Osman Raliby, Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 153. 3 H. Nursid Sumatmadjl , Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 1998), h. 34. 4 H. De Vos, Inleiding Ethick, Terj. Soejono, Pengantar Etika (Jakarta: Tiara Wacana, 1987), h. 42. 5 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Cet. III; Jakarta: Gramedia, 2002), h. 217. 13 alamiah masyarakat atau kelompok tersebut.6 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu: 1. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat 7 K. Bertens mengatakan etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, arti ini disebut juga sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya, etika orang Jawa.Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral yang biasa disebut kode etik.Kemudian etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik dan buruk. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral.8 Amsal Bakhtiar mengemukakan bahwa etika dipakai dalam dua bentuk arti: pertama, etika merupakan suatu kumpulan mengenai pengetahuan, mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia yang lain.9 Secara spesifik Ahmad Amin mengatakan etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apayang seharusnya dilakukan oleh sebagian orang kepada lainnya, mengatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.10 Berdasarkan pemahaman di atas, etika merupakan ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia, sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran dan hati nurani manusia. Agama adalah suatu realitas yang eksis di kalangan masyarakat, sejak dulu ketika manusia masih berada dalam fase primitif, agama sudah dikenal oleh mereka.Meskipun hanya dalam taraf yang sangat sederhana sesuai dengan tingkat kesederhanaan masyarakat waktu itu.Dari masyarakat yang paling sederhana sampai kepada tingkat masyarakat yang modern, agama tetap dikenal dan dianut dengan variasi yang berbeda.Dengan demikian agama tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, kapan dan dimanapun. Agama berasal dari bahasa sansekerta yang artinya tidak kacau, diambil dari suku kata a berarti tidak dan gama berarti kacau. Secara lengkapnya, agama adalah peraturan yang mengatur manusia agar tidak kacau.Menurut maknanya, kata agama dapat disamakan dengan kata religion (Inggris), religie (Belanda), atau berasal dari bahasa Latin 6 Zakiah Daradjat, dkk.,Dasar-dasar Agama Islam (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), h. 264. 7 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 25. 8 K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 2. 9 Amsal Bahtiar, Filsafat Ilmu (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 165. 10 Ahmad Amin, Al Akhlak, Terj. K.H. Farud Ma’ruf, Etika (Ilmu Akhlak), (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 3. 14 religio yaitu dari akar kata religare yang berarti mengikat.11Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata “dien”.Yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan.12 Mahmud Syaltut menyatakan bahwa “agama adalah ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untk menjadi pedoman hidup manusia”.13 Sementara itu, Syaikh Muhammad Abdullah Bardan berupaya menjelaskan arti agama dengan merujuk pada al Qur’an dengan melalui pendekatan kebahasaan. Emmanuel Kant mengatakan bahwa agama adalah perasaan tentang wajibnya melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Harun Nasution berpandanggan agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan sebagai suatu kekuatan gaib yang memengaruhi kehidupan manusia sehingga melahirkan cara hidup tertentu. Sejalan dengan itu, Endang Saifuddin Ansari mengatakan agama adalah sistem kredo (tata ritus, tata peribadatan), sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya berdasarkan sistem keimanan dan sistem peribadatan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa agama adalah kebiasaan atau tingkah laku manusia yang didasarkan pada jalan peraturan atau hukum Tuhan yang setimpal atau adil berupa pahala. Dan apabila tidak ditaati ia akan memperoleh balasan yang setimpal atau adil pula berupa azab atau hukuman dari Tuhan. Relasi antara etika dengan agama sangat erat kaitannya yakni adanya saling isi mengisi dan tunjang menunjang.Keduanya terdapat persamaan dasar, yakni sama-sama menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia.Etika mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan akal pikiran dan hati nurani.Sedangkan agama mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan wahyu (kitab suci) yang kebenarannya absolut (mutlak) dan dapat diuji dengan akal pikiran. B. Fungsi Etika dan Agama dalam Kehidupan Sosial Para pemikir Islam maupun pemikir barat kontemporer sama-sama menyadari bahwa manusia saat ini berada pada puncak krisis yang akut, dimana kehadiran sains dan teknologi modern telah mereduksi eksistensi kemanusiaan sebagai potensi ideal dan kekuatan dalam mendesain peradaban modern.Jauh sebelum Karl Marx merasakan adanya fenomena penindasan oleh berjuis dan kapitalis alat dan modal yang telah meredekreditkan dimensi kemanusiaa,14sehingga zaman modern adalah zaman dimana manusia benar-benar hidup secara real dan harfiah dalam bumi yang satu.15Dalam menyikapi keadaan tersebut, dibutuhkan sikap yang lebih apresiatif dan aktif dalam memfungsikan nilai-nilai etika dan agama dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. 11 Dadang Ahmad, Metode Perbandingan Agama (Perspektif Ilmu Perbandingan Agama), (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 21. 12 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2001), h. 21. 13 Quraisy Shihab, Membumikan Al Qur’an: Peran Wahyu dalam Kehiduan Masyarakat (Cet. XXV; Bandung: Mizan, 2003), h. 209. 14 M. Uhaib As’ad Dalam Y.B. Mangun Wijaya, Spritualitas Baru Agama dan Aspirasi Rakyat (Cet. I; Jakarta: Interfedei, 1994), h. 277. 15 Th. Sumartana,et. al, Reformasi Politik Kebangkitan Agama dan Konsumerisme (Cet. I; Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 99. 15 Berbicara masalah etika dan agama tidak terlepas dari masalah kehidupan manusia itu sendiri.Olehnya itu etika dan agama menjadi suatu kebutuhan hidup yang memiliki fungsi.Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu yang berfungsi mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk, etika mengatur dan mengarahkan citra manusia kejenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Etika menuntut orang agar bersikap rasional terhadap semua norma. Sehingga etika akhirnya membantu manusia menjadi lebih otonom. Etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis yang dapat membedakan antara yang sah dan tidak sah, apa yang benar dan apa yang tidak benar.16Etika memberi kemungkinan kepada kita untuk mengambil sikap sendiri serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Sedangkan agama yang kebenarannya absolut (mutlak) berfungsi sebagai petunjuk, pegangan serta pedoman hidup bagi manusia dalam menempuh kehidupannya dengan harapan penuh keamanan, kedamaian, sejahtera lahir dan batin.17Agama sebagai sistem kepercayaan, agama sebagai suatu sistem ibadah, agama sebagai sistem kemasyarakatan.Agama merupakan kekuatan yang pokok dalam perkembangan umat manusia.18Agama sebagai kontrol moral.Sebagai contoh dalam kehidupan modern yang serba pragmatis dan rasional, manusia menjadi lebih gampang kehilangan keseimbangan, mudah kalap dan brutal serta terjangkiti berbagai penyakit kejiwaan.Akhirnya manusia hidup dalam kehampaan nilai dan makna.Ketika itu agama hadir untuk memberikan makna. Ibarat orang tengah kepanasan ditengah padangSahara. Agama berfungsi sebagai pelindung yang memberikan keteduhan dan kesejukan, serta memiliki ketentraman hidup.19Dengan demikian, ajaran agama mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia (multi dimensional) senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tidak pernah mengenal istlah ketinggalan zaman (out of date). kedua fungsi tersebut tetap berlaku dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Etika mendukung keberadaan agama, dimana etika sanggup membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah.Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional sedangkan agama mendasarkan pada wahyu Tuhan.Dalam agama ada etika dan sebaliknya. Agama merupakan salah satu norma dalam etika.20 16 Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika, Ed. I (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2005), h. 59-60. 17 Burhanuddin Salam, Pengantar Filsafat (Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 176. 18 Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam (Cet. I; Bandung: Mizan, 1991), h. 53. 19 Haidar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 1999), h. 41. 20 Muhammad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 180. 16 Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hubungan antara etika dengan agama sangat erat kaitannya, yakni adanya saling isi mengisi dan tunjang menunjang. Keduanya terdapat persamaan dasar, yakni sama-sama menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Etika mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan akal pikiran dan hati nurani sedangkan agama mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan wahyu (kitab suci) yang kebenarannya absolut (mutlak) dan dapat diuji dengan akal pikiran. 2. Fungsi etika dan agama dalam kehidupan sosial tetap berlaku dan dibutuhkan dalam suatu masyarakat, keduanya berfungsi menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Etika mengukur seseorang dengan argumen rasional sedangkan agama mengukur seseorang dengan berdasarkan wahyu Tuhan dan ajaran agama. Dalam agama ada etika dan sebaliknya agama merupakan salah satu norma dalam etika. 17 BAB IV KEBAIKAN DAN KEBURUKAN, KEBENARAN DAN KESALAHAN, PAHALA DAN DOSA Islam merupakan salah satu agama samawi yang meletakan nilai-nilai kemanusiaan atau hubungan personal, interpersonal dan masyarakat secara agung dan luhur, tidak ada perbedaan satu sama lain, keadilan, relevansi, kedamaian yang mengikat semua aspek manusia. Karena Islam yang berakar pada kata “salima” dapat diartikan sebagai sebuah kedamaian yang hadir dalam diri manusia dan itu sifatnya fitrah. Kedamaian akan hadir, jika manuia itu sendiri menggunakan dorongan diri ke arah memanusiakan manusia dan atau memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaaan Tuhan yang sempurna. Fitrah kemanusiaan yang merupakan pemberian Tuhan (Given) memang tidak dapat ditawar, dia hadir seiring tiupan ruh dalam janin manusia dan begitu manusia lahir dalam bentuk “manusia” punya mata, telinga, tangan, kaki dan anggota tubuh lainnya sangat tergantung pada wilayah, tempat, lingkungan di mana manusia itu dilahirkan. Anak yang dilahirkan dalam keluarga dan lingkungan muslim sudah barang tentu secara akidah akan mempunyai persepsi ketuhanan (iman) yang sama, begitu pun nasrani dan lain sebagainya. Inilah yang sering dikatakan sebagai sudut lahirnya keberagamanaan seorang manusia yang akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam wacana studi agama sering dikatakan bahwa fenomena keberagamaan manusia tidak hanya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang normativitas melainkan juga dilihat dari historisitas.1 Kajian etika merupakan suatu kajian kritis rasional mengenai yang baik dan yang buruk, bagaimana halnya dengan teori etika dalam Islam. Dalam sejarah Islam, ditemukan dua faham, yaitu faham rasionalisme yang diwakili oleh Mu’tazilah dan faham tradisionalisme yang diwakili oleh Asy’ariyah. Munculnya perbedaan itu memang sulit diingkari baik karena pengaruh Filsafat Yunani ke dalam dunia Islam maupun karena narasi ayatayat al-Qur’an sendiri yang mendorong lahirnya perbedaan penafsiran. Di dalam al-Qur’an pesan etis selalu saja terselubungi oleh isyarat-isyarat yang menuntut penafsiran dan perenungan oleh manusia. Kelompok Mu’tazilah yang merupakan salah satu aliran teologi besar dalam sejarah Islam berkeyakinan bahwa perbuatan-perbuatan pada hakikatnya ada yang baik secara esensinya dan adapula yang buruk secara esensinya, dan akal manusia dapat mengetahui kebaikan dan keburukan, dan dari sinilah hukum Islam akan tersingkap, karena hukum Islam tidak mungkin bertentangan dengan akal. Menurut faham Asy’ariyah, nilai kebaikan suatu tindakan bukannya terletak pada obyektivitas nilainya, melainkan pada ketaatannya pada kehendak Tuhan. Asy’ariyah berpandangan bahwa menusia itu bagaikan ‘anak kecil’ yang harus senantiasa dibimbing oleh wahyu karena tanpa wahyu manusia tidak mampu memahami mana yang baik dan mana yang buruk.2 1 Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas dan Historitas (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002) hal. V. 2 Qomarudin Hidayat, Etika Dalam Kitab Suci Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern Studi Kasus Di Turki, (Jakarta : Paramadina), dalam kumpulan artikel Yayasan Paramadina, pada www.paramadina.com. 18 Bab ini membahas salah satu pembahasan yang amat signifikan berkenaan dengan pandangan keagamaan yaitu hakikat kebaikan-kejelekan, dan hubungan antara etika dengan konsep baik-jelek, kebenaran-kesalahan, pahaladosa dalam Islam. A. Hakikat Baik-Buruk dalam Islam Kejahatan adalah satu dari sekian banyak kesulitan yang berkaitan dengan persoalan keadilan Tuhan. Pembahasan ini bukan persoalan ilmiah yang dapat dijawab melalui eksperimen dan observasi, bukan juga masalah praktis yang bisa diselesaikan dengan keputusan dan tindakan. Tetapi, ia lebih merupakan problem filosofis yang menghendaki suatu dalil pemikiran yang dapat menjelaskannya secara proporsional. Begitu fundamentalnya persoalan ini, sehingga hampir semua ajaran yang bersifat keagamaan (teologis) maupun kefilsafatan merasa perlu memberikan tanggapan dengan cara dan metodenya masing-masing. Dalam pandangan Islam, kebaikan dan kejahatan di alam ini bukanlah dua hal yang berbeda dan terpisah satu sama lain, sebagaimana berbedanya benda-benda mati dari tumbuh-tumbuhan, atau tumbuh-tumbuhan dari binatang, yang masing-masing memiliki barisan tertentu. Kita akan melakukan kekeliruan apabila membayangkan bahwa kejahatan memiliki barisan tertentu yang esensinya bersifat “jahat sejati” tanpa sedikit pun kebaikan di dalamnya, dan bahwa kebaikan memiliki barisan tertentu yang berbeda dan esensinya bersifat “baik sejati” tanpa sedikit pun kejahatan di dalamnya. Yang benar adalah bahwa kebaikan dan kejahatan merupakan dua hal yang menyatu tanpa bisa dipisah-pisahkan. Ketika di suatu bagian alam ada kejahatan, di situ pasti ada kebaikan, dan di mana saja ada kebaikan, di situ pasti ada kejahatan. Kebaikan dan kejahatan begitu menyatu dan bersenyawa di alam ini, bukan senyawa kimiawi, melainkan senyawa yang lebih mendalam dan lebih halus, senyawa antara eksistensi dan non-eksistensi (tarkib al-wujud wa al-`adam).3 Dualisme wujud, yakni kejahatan dan kebaikan, pada dataran fenomenalnya memang ada, tetapi pada essensinya hanya ada kebaikan. Pandangan ini merupakan konskuensi dari kenyataan bahwa Tuhan sebagai Wajib alWujud adalah Maha Baik, Maha Adil dan Maha Sempurna, sehingga apa pun yang melimpah dari-Nya mesti mengandung esensi kebaikan. Dalam hal ini Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa pada dataran fenomenal tidak ada “kejahatan sejati” maupun “kebaikan sejati”, sedang pada dataran noumenal hanya ada satu esensi, yakni kebaikan, karena substansi kejahatan benar-benar merupakan ketiadaan murni.4 Dengan demikian, di alam maujud (dunia) sebenarnya tidak ada dualisme, sehingga tidak mengharuskan adanya dua sumber wujud dan nilai. Pandangan ini, di dalam Islam, sejalan dengan ajaran dasar tauhid, bahwa semua yang ada ini berasal dari Satu dan akan kembali kepada Yang Satu. 3 http://mlutfimustofa.com/, “Kejahatan dan Persoalan Teodisi”, diakses pada tanggal 04 Februari 2012. Lihat Muthahhari, Murtadha, Al-`Adl al-Ilahiy, ter. Agus Efendi, Keadilan Ilahi (Bandung: Mizan, 1992). 4 Ibid 19 B. Hubungan Etika Dengan Konsep Kebaikan-Kejelakan, Benar-Salah dan Pahala-Dosa dalam Islam Etika dalam Islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan agung yang bukan saja berisikan sikap, prilaku secara normatif, yaitu dalam bentuk hubungan manusia dengan tuhan (iman), melainkan wujud dari hubungan manusia terhadap Tuhan, Manusia dan alam semesta. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagamaan seseorang. Maka Islam menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung etika sebagai fitrah dengan menghadirkan kedamaian, kejujuran, dan keadilan. Etika dalam Islam akan melahirkan konsep ihsan, yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial hanya dan untuk mengabdi pada Tuhan, buka ada pamrih di dalamnya. Pembahasan hubungan agama dengan akhlak (etika) dapat diobservasi dari dua sudut tinjauan; sudut tinjauan dalam agama dan sudut tinjauan luar agama. Dari sudut tinjauan luar agama, dengan tidak merujuk pada ayat dan riwayat, kontrak-kontrak akhlak terealisasikan dengan jaminan loyalitas terhadap tradisi-tradisi agama; dengan kata lain, keyakinan kepada Tuhan dan pahala serta siksa ukhrawi mempunyai pengaruh kuat dalam terealisaasinya perintah-perintah akhlak. Akan tetapi para pengikut agama dalam level rendah, dengan bantuan keyakinan agama, secara khusus janji pahala dan ancaman siksa, membawa mereka loyal terhadap kontrak-kontrak akhlak dan dalam level yang lebih tinggi, motivasi dekat pada Tuhan, kesempurnaan akhir, dan keyakinan terhadap hubungan takwini antara amal-amal akhlak dan kesempurnaan manusia, berpengaruh dalam terealisasinya perintah-perintah akhlak. Di samping itu, keyakinan-keyakinan agama dalam mendeskripsikan proposisi-proposisi akhlak dan falsafah ketaatan terhadap perintah-perintah akhlak, juga mempunyai pengaruh yang cukup berarti.5 Adapun komprehensi-komprehensi yang digunakan dalam akhlak (etika) seperti “baik”, “buruk”, “harus”, “tidak boleh”, “benar”, “tidak benar”, “tugas”, dan “tanggung jawab”, semuanya merupakan komprehensikomprehensi khusus yang mempunyai makna dan pengertian masing-masing. Pemahaman-pemahaman nilai ini memiliki faedah dalam penggunaannya ketika mempunyai basis dan landasan ontologis, sehingga jika seseorang melanggar nilai-nilai akhlak, ia akan merasakan konsekuensi dari pelanggarannya dalam bentuk penderitaan atau kepedihan hidup serta jauh dari kebahagiaan.6 Merujuk kepada masalah hubungan agama dan akhlak, mempunyai kekhususan, tentu saja perintah-perintah akhlak berpengaruh dalam kebahagiaan kehidupan dunia serta berasaskan prinsip tajassum amaliyah, kebahagiaan akhirat juga lahir dari ketentuan kebahagiaan dunia. Fitrah manusia dan pengajaran yang didapatkannya dari agama, dapat menjadi penjamin atas pengamalan dan perealisasian perbuatan-perbuatan akhlak. Pahala dan balasan, dengan tidak melihat wilayah aktualitasnya, mempunyai dampak atas perealisasian nilainilai akhlak di tengah masyarakat apatah lagi dengan adanya sangksi-sangksi sosial seperti pujian terhadap pelaku akhlak baik dan celaan terhadap para pelaku akhlak buruk. Namun yang paling urgen dalam masalah ini adalah keberadaan Tuhan yang menjadi asumsi dan postulat agama yang dapat menjadi penjamin utama bagi pelaksanaan perbuatan-perbuatan akhlak baik dan pengaman ampuh untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan akhlak buruk. 5 http://www.alhassanain.com. Diakses pada tanggal 15 desember 2011. 6 Ibid 20 Sangat banyak dari komprehensi-komprehensi agama bisa berpengaruh dalam masalah-masalah akhlak. Misalnya, ketika kita mengatakan perbuatan benar adalah perbuatan yang diperintahkan Tuhan, di sini kita membawa keberadaan Tuhan secara langsung dalam masalah akhlak. Tetapi terkadang kita mengatakan perbuatan benar adalah perbuatan yang menjamin kebahagiaan abadi manusia maka di sini tidak berbicara secara langsung tentang Tuhan, tetapi salah satu dari doktrin lain agama; yakni kita menerima postulat tentang kehidupan abadi manusia. Yakni kita menerima secara yakin bahwa manusia setelah mati dan meninggalkan alam materi ini, ia akan melewati kehidupan lain yang abadi dan lestari, dan di sana ia akan mendapatkan pahala kebahagiaan atau balasan kesengsaraan. Berkenaan dengan komprehensi agama dan komprehensi akhlak serta hubungan keduanya, di mana dalam hal ini penentuan ukuran akhlak akan berpengaruh dalam memberi tinjauan dan konklusi tentangnya. Dengan pengertian bahwa jika akhlak berdasarkan prinsip manfaat atau prinsip kelezatan atau berdasarkan prinsip sosial masyarakat atau prinsip akal praktik (‘amali), dalam konteks ini mungkin akhlak dengan agama diasumsikan tidak mempunyai hubungan sama sekali atau hubungan keduanya hanya dalam bentuk pondasi bagi yang lainnya; dan jika parameter permasalahan-permasalahan akhlak adalah kedekatan dengan Tuhan, dengan meninjau ketiadaan pengetahuan kita terhadap “qurbah” dan “maqâm” Tuhan maka hubungan antara akhlak dan agama merupakan hubungan proposisi dan kandungan. Di akhir makalah ini, penulis menyampaikan kesimpulan di antaranya sebagai berikut: 1. Hakikat baik-jelek dalam Islam tidak bersifat dualisme wujud, yakni kejahatan dan kebaikan, pada dataran fenomenalnya memang ada, tetapi pada essensinya hanya ada kebaikan. Pandangan ini merupakan konskuensi dari kenyataan bahwa Tuhan sebagai Wajib al-Wujud adalah Maha Baik, Maha Adil dan Maha Sempurna, sehingga apa pun yang melimpah dari-Nya mesti mengandung esensi kebaikan. 2. Hubungan agama dan akhlak (etika), perintah-perintah akhlak berpengaruh dalam kebahagiaan kehidupan dunia serta berasaskan prinsip tajassum amaliyah, kebahagiaan akhirat juga lahir dari ketentuan kebahagiaan dunia. 3. Pemahaman-pemahaman nilai seperti “baik”, “buruk”, “harus”, “tidak boleh”, “benar”, “tidak benar”, “tugas”, dan “tanggung jawab”, ini memiliki faedah dalam penggunaannya ketika mempunyai basis dan landasan ontologis, sehingga jika seseorang melanggar nilai-nilai akhlak (etika), ia akan merasakan konsekuensi dari pelanggarannya dalam bentuk penderitaan atau kepedihan hidup serta jauh dari kebahagiaan. 21 BAB V ETIKA BERAGAMA, BERMAZHAB DAN PERPAHAM Etika kaitannya dengan pengertian bagaimana seharusnya manusia berbuat dan bertingkah dalam kehidupan ini adalah satu hal yang menempati posisi yang sangat penting, bahkan bisa dikata bahwa jatuh bangunnya suatu tatanan kemasyarakatan sangat bergantung pada bagaimana etika personal dan kolektif itu ditata dan ditaati. Jika hal tersebut berjalan pada alur yang semestinya, maka tentu akan berujung pada kesejahteraan lahir dan batin, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka chaos dalam ragam kehidupanpun akan tak terhindarkan. Kenyataan tersebut dapat dijadikan sebagai flatform paradigma bahwa kejayaan seseorang dan masyarakat itu sangat bergantung pada etika baiknya, mengingat karena hal tersebut merupakan juru kunci bagi terwujudnya keamanan, ketenangan dan ketenteraman. Indikasi paling utama yang dapat dijadikan paramter bagi hal tersebut ialah terlaksananya kewjiban-kewajiban dan terpenuhinya hak-hak, baik secara individu maupun masyarakat sebagaimana mestinya, baik itu kaitannya dengan diri pribadi (individu), masyarakat (sosial), alam (ekosistem), dan lain-lain. Pada posisi ini, agama memainkan peran yang sangat fital, sebab hanya agama (dalam pengertian din) yang dapat menuntun manusia untuk memperoleh petunjuk jalur lurus dan mengarahkan manusia untuk samapi ke tujuan idealnya (kebahagiaan). Maka dari itu, posisi iman dan ilmu kaitannya dengan din adalah dua hal yang menjadi soko guru bagi hal tersebut. Itulah sebabnya sehingga menarik kiranya untuk membahas lebih jauh perspektif Islam kaitannya dengan etika beragama, berfaham dan bermazhab, sebab Islam pada intinya memuat ajaran tersebut sebagaimana yang dicontohkan dan sekaligus menjadi misi utama dari diutusnya Rasulullah Saw di tengah-tengah kehidupan umat manusia. A. Etika Beragama dalam Perspektif Islam Agama (lebih khusus Islam) tampil dengan membawa misi kemanusiaan, bahkan bisa dikata bahwa hal tersebut yang paling mendasar. Simak saja misalnya nilai ajaran yang dikandungnya, totalitas orientasinya senantiasa bermuara pada kesempurnaan/kesejatian manusia itu sendiri. Seluk beluk kehidupan manusia yang begitu kompleks, tak satupun yang terbebas dari pantauannya, bahkan bisa dikata bahwa inilah salah satu alasan kenapa agama hingga kini tetap menjadi jalur utama bagi setiap pencari ketenangan. Sekalipun demikian, tetap saja kita tidak bisa menutup diri dari fakta sejarah bahwa agama juga kadang menjadi pemicu bagi lahirnya konflik sosial, lebih dari itu menurut para rasionalis Abad Pencerahan Eropa bahwa agama akan memperburuk atau membatasi ruang lingkup peribadi.1 Asumsi-asumsi ini boleh saja kita tidak sepakati, tapi tidak berarti kenyataan sejarah harus ditutupi atau bahkan dimanipulasi. Ironisnya kemudian ialah, terkadang Islam sebagai agama terakhir pun sering turut ambil andil dalam pertentangan tersebut. Pertanyaan tentu muncul, apakah agama (tanpa terkecuali) memang melanggengkan konflik dan permusuhan, ataukah justru dari semuanya mengharapkan kehidupan yang dipenuhi cinta kasih dan kerukunan antar sesama? 1 Nurcholis Madjid, dkk, Passing Over; Melintasi Batas Agama, (Cet. II; Jakarta : PT.SUN, 2001), h. 176. 22 Jika berangkat dari pernyataan awal (agama dan misi kemanusiaan) maka penulis lebih bersepakat bahwa sebab terjadinya konflik teologis lebih disebabkan karena adanya sisi dari nilai ke-agama-an yang tidak terimplementasi secara maksimal dalam kehidupan praksis penganutnya, dalam hal ini ialah etika atau akhlak beragama. Penekanan yang dimaksudkan disini sebagaimana yang diasumsikan oleh Hasan Hanafi ialah kemestian membangung penguatan Islam dari unsur progresif-transformatif yang sarat dengan nilai pembebasan.2 Kenyataan ini menurutnya telah dicerminkan oleh para Nabi yang merupakan ruh bagi pergerakan Islam itu sendiri, lihat saja misalnya gerakan Ibrahim yang merefresentasikan revolusi akal (pembangunan dan pengembangan intelektual) dalam melawan tradisi-tradisi buta (tauhid versus berhala), Musa merekomendasikan dalam ruh gerakannya pembebasan melawan otoritarianisme penguasa yang semena-mena dengan kekuasaannya, Isa jadi contoh atas pergerakan revolusi ruh (spiritualitas) dari dominasi materialisme (kecenderungan hedonis), sedangkan Muhammad menjadi refresentasi gerakan kemanusiaan dalam melawan Bal’amisme (kaum intelektual yang menggadaikan kecakapannya untuk kepentingan peribadinya), Qarunisme (para pemilik modal yang rakus dengan harta kekayaannya tanpa mempedulikan nasib orang-orang lemah yang ada disekitarnya), serta Fir’aunisme (penguasa yang tidak menjadikan kekuasaanya untuk membangun kesejahteraan masyarakat). Bahkan Muhammad memberi teladan kaum miskin dan komunitas tertindas dalam perjuangan menegakkan masyarakat bebas dan penuh persaudaraan. Gagasan mutahkir menstimulasi keadaan tersebut dengan istilah toleransi, yakni konsep yang menggambarkan sikap saling menghormati antar sesama tanpa memperdulikan ras, suku dan agama sebagai difrensia sosial. Islam dalam hal ini punya konsep yang sangat jelas, yakni “tidak ada paksaan dalam beragama” serta “bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami”.3 Dalil ini kemudian semestinya menjadi refleksi perjuangan guna membangun penghargaan dan penghormatan terhadap sesama, sebab memang demikianlah sejatinya dimana penghargaan atas nilai kemanusiaan jauh lebih tinggi ketimbang pemaksaan paradigma tertentu yang dikemas dengan pola anarkisme dan sektarianisme. Fakta historis juga menunjukkan tentang bagaimana sikap saling pengertian dan saling menghargai antara sesama (baik pada tataran teologis maupun sosiologis) ditunjukkan oleh Rasulullah Saw melalui Piagam Madinah, ini adalah suatu contoh akan prinsip kemerdekaan yang salah satu butirnya yakni sikap saling menghormati di antara agama yang ada dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi antara yang satu dengan yang lainnya. 4 Kenytaan tersebut menggambarkan bawha Islam menghendaki adanya hidup toleran sebagai basis etika kehidupan sosial, kenyataan ini seyogyanya terbawa seumur hidup. Meski demikian, berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas, tidak berarti membuang prinsip hidup (beragama) yang diyakini, karena kenyataan itu justru akan melemahkan prinsip hidup (keagamaan) yang ada. Segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip yang kita yakini. Kita 2 Hassan Hanafi, From Faith to Revolution, (Spanyol: Cordova Press, 1985), h. 231. 3 Mohamad Natsir, Keragaman Hidup antar Beragama, (Cet. II; Jakarta : Hudaya, 1970), h. 17. 4 Syeikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Toleransi Islam Menurut menurut Pandangan Alquran, terj. Abu Abdillah Mohammad Afifuddin As-Sidawi, (Cet. I; Misra : Maktabah Salafy Press, t.t), h. 31. 23 bebas dengan keyakinan kita, sedangkan pihak yang berbeda (yang memusuhi sekalipun) kita bebaskan terhadap sikap dan keyakinannya. Itulah sentuhan prinsip tegas yang diteladankan oleh Rasulullah Saw kepada kita, dan kita wajib meneladaninya. Karena itu, meneladani biasanya berkaitan dengan perilaku yang baik pada diri seseorang yang sejatinya dimiliki oleh orang yang meneladaninya. Keteladanan menurut Sondang P Siagian adalah melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, baik karena keterikatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun karena limitasi yang ditentukan oleh nilai-nilai moral, etika, dan sosial.5 Oleh karena itu, keteladanan diartikan sebagai hal-hal yang patut ditiru pada diri seseorang, baik ucapan maupun perbuatan. Prinsip ideal tersebut seyogyanya memicu lahirnya refleksi orientasi baru, khsusnya bagi kaum agamawan bahwa terdapat tujuan ideal dari agama itu sendiri, bahwa semua perintah-perintah yang sifatnya mu’amalah substansinya ialah penyelamatan diri (manusia) dan alam, yang dalam prinsip ke-Islam-an dikenal dengan istilah Rahmatan Lil ‘Alamin. B. Etika Berfaham dalam Perspektif Islam Fakta historis menunjukkan keaneka ragaman faham yang menyertai perjalanan manusia (baik secara individual maupun kelompok/masyarakat), hal tersebut merupakan efek dari perbedaan cara pandang (kerangka epistemologis) dalam melihat kompleksitas persoalan hidup. Perbedaan ini tak jarang berujung pada komplik laten yang menelan banyak korban, dan kenyataan seperti ini tentu saja bukan merupakan harapan ideal dari setiap orang. Maka dari itu menarik kiranya mengupas pandangan Islam terkait dengan perbedaan faham seperti ini, bahwa betulkan Islam melihat perbedaan faham tersebut merupakan hal niscaya dalam kehidupan? Jika sekiranya demikian adanya maka bagaimana membangun sikap terhadap hal yang dimaksudkan? Nurholis Madjid dalam mengupas persoalan ini merujuk pada Alquran surah Yunus : 10 yang berbunyi : ٩٩ َض ُﻛﻠﱡﮭُﻢۡ ﺟَ ﻤِﯿ ًﻌ ۚﺎ أَﻓَﺄ َﻧﺖَ ﺗُﻜۡ ِﺮهُ ٱﻟﻨ ﱠﺎسَ ﺣَ ﺘﱠﻰٰ ﯾَﻜُﻮﻧُﻮ ْا ﻣ ُۡﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ ِ ﺷﺎٓ َء َرﺑﱡ َﻚ َ ٓﻷﻣَﻦَ ﻣَﻦ ﻓِﻲ ۡٱﻷ َۡر َ َوﻟ َۡﻮ Terjemahannya : Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? Nurcholis menegaskan bahwa ayat tersebut mengarah pada konsep kemajemukan faham yang semestinya mengantarkan setiap manusia untuk bertarung dalam memperoleh dan melakukan kebaikan, bukan malah menjadikan perbedaan paradigma sebagai pemciu bagi perpecahan dan konflik.6 Bahkan menurut penulis bahwa, dengan tegas ayat tersebut mengilustrasikan bahwa perbedaan itu merupakan bagian dari sunnatullah, dalam kata artian telah menjadi bagian dari prinsip penciptaan. Kenyataan ini pantas untuk direnungkan, bahwa sikap memaksa 5 Sondang P Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Cet. I; Jakarta : Rineka Cipta, 1987), h. 105. 6 Nurcholis Madjid, dkk, Passing Over; Melintasi Batas Agama, (Cet. II; Jakarta : PT.SUN, 2001), h. 174-175. 24 (apalagi dengan cara-cara anarkis) sama sekali tidak dibenarkan, lebih jauh dari itu ayat tergambar secara substansial bahwa soal keberimanan dan kekafiran sesorang adalah bagian rahasiah Tuhan. Tugas manusia secara umum ialah menyampaikan risalah sebagaimana adanya, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Disisi lain, gagasan ideal (pandangan dunia) yang sarat dengan tatanan nilai, jelas membutuhkan medium budaya agar keberadaannya membumi dalam kehidupan manusia, dan sekaligus diharapkan menjadi institusi bagi pengalaman iman kepada Sang Khaliq. Pada posisi ini, sebuah faham diniscayakan menawarkan suatu agenda penyelamatan universal yang memuat kesadaran makna dan legitimasi tindakan bagi pengusungnya, dimana dalam interaksi sosial banyak mengalami perbedaan hermeneutik sehingga sering memicu konflik. Pluralitas paradigma disatu sisi dan hiterogenitas realitas sosial disisi lain, yang kesemuanya membutuhkan kearifan diantara kelompok kepentingan dan kalangan pemeluk paham. Kenyataan ini juga tergambar dengan tegas dari pandangan Ali Syari’ati bahwa gagasan pandangan dunia religius humanistik yang berorintasi pada penemuan keesaan yang orisinil dalam rangka membangun kesadaran sebagai wakil atau khalifah Tuhan di muka bumi. Endingnya ialah terbentukan kesadaran manusia sebagai makhluk merdeka dan memiliki potensialitas tanpa batas untuk menentukan nasibnya sendiri dan bukan ditentukan oleh kekuatan eksternal.7 Pada posisi ini, Syari’ati memahami agama bukan sebagai kumpulan doktrin yang lebih berdimensi ritual saja, jauh dari itu bahwa agama adalah sumber lahirnya kesadaran (awareness), landasan etik (morality), tanggungjawab (responsibility) dan kehendak bebas (free will) yang mampu menggerakkan pemeluknya menjadi kekuatan pembebas dari determinasi ideologi-ideologi dehumanis. C. Etika Bermazhab dalam Perspektif Islam Bermazhab pada umumnya selalu dipandang atau dipahami identik dengan taqlid sehingga pemikiran ulama masa lalu selalu diposisikan sebagai doktrin dan bahkan dogma agama sehingga tabu (berdosa) jika melakukan kritik terhadapnya. Wajar jika kemudian pengertian bermazhab secara harfiah seperti ini mengantarkan umat beragama pada stagnasi pemahaman/intelektual akibat dari sikap penerimaan fatwah sebagai barang matang tanpa lebih jauh menyentuh aspek metodologis dari hal tersebut. Pemahaman seperti ini dengan sendirinya akan sulit membuat terobosan terhadap permasalahan aktual yang bermunculan kepermukaan. Pada posisi ini, perlu kiranya melakukan sebuah terobosan untuk meredefenisi asumsi kemazhaban agar tidak terjebak pada kejumudan paradigma teologis dengan cara mengkerdilkan kemampuan rasionalitas dari setiap mukallid. Berijetihan hendaknya menjadi sebuah formulasi metodologis yang dapat dibentuk dari hasil kajian kritis terhadap konsep teologis yang dipadukan dengan tuntutan zaman dan pertanggung jawaban tradisi akademis. Ijtihad dengan kerangka seperti ini merupakan cara untuk memperoleh landasan, pedoman, petunjuk dan sekaligus legitimasi dalam hidup dan kehidupan. Umat islam ditantang untuk menjadi umat yang terbaik, sebagaimana dalam QS. Ali Imran : 110 : 7 Ali Syari’ati, Man In Islam. terj. M. Amin Rais, Tugas Cendekiawan Muslim, (Cet.II; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 25 25 ﺐ ﻟَﻜَﺎنَ ﺧَ ۡﯿ ٗﺮا ﻟﱠﮭُﻢۚ ﻣﱢﻨۡ ُﮭ ُﻢ ٱﻟۡ ﻤ ُۡﺆ ِﻣﻨ ُﻮنَ َوأَﻛۡ ﺜَ ُﺮ ُھ ُﻢ ِ س ﺗَ ۡﺄ ُﻣﺮُونَ ﺑِﭑﻟۡ ﻤَﻌۡ ﺮُوفِ َوﺗَﻨۡ ﮭ َۡﻮنَ َﻋ ِﻦ ٱﻟۡ ﻤُﻨ َﻜ ِﺮ َوﺗ ُۡﺆ ِﻣﻨُﻮنَ ﺑِﭑ ﱠ ۗ ِ َوﻟ َۡﻮ ءَاﻣَﻦَ أَھۡ ُﻞ ٱﻟۡ ِﻜ َٰﺘ ِ ﻛُﻨﺘُﻢۡ ﺧَ ﯿۡ َﺮ أُ ﱠﻣ ٍﺔ أ ُۡﺧﺮِﺟَ ۡﺖ ﻟِﻠﻨ ﱠﺎ ١١٠ َﺴﻘ ُﻮن ِ ٱﻟۡ َٰﻔ Terjemahan : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Menurut hemat penulis bahwa ayat tersebut tidak bisa diposisikan sebagai pemberian cuma-cuma, namun lebih merupakan tantangan bagi setiap kaum muslimin. Oleh karena itu, responnya bukan sikap bermalas-malasan lantaran adanya jaminan, namun harus bekerja keras untuk mampu mewujukan ma’ruf dan menghindari kemungkaran.8 Dengan demikian, bermazhab tidak lagi ditafsirkan sebagai upaya untuk membunuh dan memaksulkan daya kritis, melainkan lebih dari itu harus dijadikan sebagai upaya transformatif untuk menjadikan setiap keputusan agamais menjadi etika sosial kemasyarakatan.9 Perangai seperti ini sekaligus mengcountre anggapan dan kritikan bawah hukum islam selama ini selalu berkutat pada dunia ibadah murni dan kurang menyentuh kehidupan soisal, akibatnya islam kurang maju dalam kehidupan karena ajaran-ajaran idealnya tidak terimplementasi. Adalah sudah seharusnya bahwa nilai-nilai kebersihan, kerja keras, menempati janji, kedisiplinan, tanggung jawab dan sejenisnya harus mendapat legitimasi hukum islam yang mempunyai konsekuensi pahala-dosa di akhirat. Keteladanan (uswah) sebagai salah satu metode pendidikan Islam yang merujukkan perilaku setiap muslim dengan meneladani perilaku Rasulullah seperti tercantum dalam Alquran : ٢١ ٱﻷ ِﺧ َﺮ َو َذ َﻛ َﺮ ٱ ﱠ َ َﻛﺜ ِٗﯿﺮا ٓ ۡ ﻟﱢﻤَﻦ ﻛَﺎنَ ﯾ َۡﺮﺟُ ﻮ ْا ٱ ﱠ َ وَٱﻟۡ ﯿ َۡﻮ َمٞﺴﻨَﺔ َ َﻟﱠﻘَﺪۡ ﻛَﺎنَ ﻟَﻜُﻢۡ ﻓِﻲ َرﺳُﻮ ِل ٱ ﱠ ِ أُﺳۡ َﻮة ٌ ﺣ Terjemahannya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS.Al-Ahzab,33:21). Perasaan tunduk kepada Yang Maha Tinggi, yang disebut iman, atau itikad, yang kemudian berdampak pada adanya rasa suka, takut, hormat dan lain-lain, itulah unsur dasar al-dîn (agama). Al-dîn (agama) adalah aturanaturan atau tata-cara dan/atau etika hidup manusia yang dipercayainya bersumber dari Yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal lain yang tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai mazhab (bahkan agama) yang telah lahir di dunia ini dan membentuk suatu syariat (aturan), tidak lain kecuali untuk mengatur kehidupan manusia dan menunjukkan 8 A. Qadri Azizy, Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani), (Cet. I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h. 103-104. 9 A Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Cet. I; Yogyakarta : Gama Media, 2002), h. 42-44. 26 manusia kepada kebenaran sejati, kebahagiaan hakiki, serta mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bersama.10 Dari hakikat dan fungsi mazhab seperti yang disebutkan itu, maka pemeluk agama-agama yang ada di dunia ini, telah memiliki strategi, metoda dan etika dalam pelaksanaannya masing-masing, yang sudah barang tentu dan sangat boleh jadi terdapat berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Karenanya, setiap pengikut dalam menjalankan aturan main yang doktirn kemazhaban yang diterimahnya, kiranya tidak terjebak dalam perpecahan, apalagi perpecahan itu justru bermotivasikan perbedaan mazhab. D. Konflik akibat Sintemen Paham Keagamaan/Mazhab Masih relevankah agama bagi kehidupan umat manusia saat ini ? Pertanyaan tersebut di ajukan oleh seorang pengusaha muda di daerah, kepada salah seorang cendekiawan muslim H. Moch. Qasim Mathar, MA. Menurut Qasim, jawaban atas pertanyaan tersebut, bisa ia dan bisa tidak. Kalau berpijak pada kondisi dinamika sosial masyarakat di berbagai wilayah di negara kita yang dilanda kerusuhan dan agama dijadikan alasan pembenaran, maka agama yang senantiasa mengajarkan kedamaian dan ketenteraman, sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi, jika ajaran agama itu dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dipahami secara tepat dan tidak dipinggirkan, maka agama untuk saat ini masih relevan. Masih menurut Qasim, ia memulai jawabannya dengan menyatakan: Pertanyaan Anda tidak relevan untuk saya. Pertanyaan seperti itu hanya cocok bagi umat beragama yang lagi bermusuhan dengan menjadikan ajaran agama sebagai alat pembenaran. Mempertanyakan relevansi agama dengan kondisi okjektif kehidupan sosial masyarakat yang tidak stabil, akibat terjadinya konflik horisontal antar umat beragama, sesungguhnya menarik untuk di simak. Mengapa? Ajaran agama, sebagaimana yang termaktub dalam berbagai kitab suci, semuanya mengajarkan agar manusia menciptakan suasana harmoni, suasana damai dalam kehidupan mereka. Agama sangat tidak menyukai perilaku anarkhis. Pemuka agama senantiasa mengingatkan para pemeluk agama agar menyebarkan kedamaian dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika terjadi keadaan umat beragama berbeda dengan ajaran agama yang dianutnya, tentu ada yang kurang beres. Pertanyaan lanjutan dari kondisi tersebut, ialah mengapa terjadi ketidakberesan dalam beragama? Siapa yang menjadi pemicunya? Bertolak dari pendapat Winter, dapat dipahami bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam masyarakat yang memeluk agama, disebabkan ajaran agama tidak diamalkan sebagaimana mestinya. Agama di pinggirkan, demikian H. Abdurrahman A. Basalamah SE, M. Si. Di samping itu, tidak dapat diingkari bahwa ada di antara umat beragama, pemahamannya terhadap agama yang dipeluknya masih sebatas pengakuan semata yang sangat emosional. Pemahaman yang parsial, bahkan menurut Arifuddin Ahmad, sangat ironis sekali jika ada pemeluk agama hanya berpegang pada pendapat orang yang menafsirkan kitab suci, dengan cara yang kurang tepat. “Sungguh suatu 10 Panji Gumilang, Toleransi Akidah dalam Beragama, (Online; http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedia/a/abdussalam/pidata/toleransi.shtml), diakses pada tanggal 7 Oktober 2011. 27 kekonyolan, jika seorang pemeluk agama hanya berpegang pada pendapat penafsiran orang, tetapi keliru dalam memahaminya”. Masyarakat dunia dewasa ini, sementera bergelut dengan sejumlah problema yang ditimbulkan dari pemikiran modernisasi, yaitu semakin menipisnya dan dangkalnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Hal ini, memunculkan problema baru, yakni lahirnya berbagai krisis, di antaranya kemerosotan nilia-nilai moral, berkembangnya gaya hidup korup, menipisnya kekuatan hukum, tidak tegaknya kejujuran dan keadilan serta terkoyaknya perdamaian, kesatuan, dan integrasi sosial. Selain itu, timbul pula sebuah fenomena sosial kehidupan masyarakat yang cenderung memberi perhatian khusus hanya kepada hal-hal yang berorientasi untuk kepentingan material ketimbang pemekaran nyali sprititual. Hal ini berdampak pada rusaknya tatanan dan etos kerja. Mencari solusi yang komprehensif terhadap berbagai problema kehidupan masyarakat yang disebutkan di atas, menurut hemat kami, tidak lain kecuali mengaktualisasikan kembali nilai-nilai moral keagamaan yang terdapat dalam kitab suci, dalam kehidupan masyarakat, kapan dan dimana pun juga di muka bumi ini. Sebab hal ini berlaku secara universal untuk semua bangsa tanpa membedakan bangsa, warna kulit, dan budaya yang mereka miliki. Tempat yang paling tepat untuk merujuk dalam mengaktualisasilkan nilai-niali moral agama tersebut adalah ajaran-ajaran agama itu sendiri yang dibawa oleh para nabi dan rasul, baik menyangkut soal ketuhanan maupun soalsoal moral dan akhlak al-Karimah. Pada prinsipnya semua agama mengakui adanya perbedaan dan polarisasi sosial. Islam sendiri melihat fenomena pluralitas tersebut sebagai sebuah sunnatullah, sebagai hukum alam dan sebagai realitas empiris terhadap dunia manusia (Koentowijoyo, , 1991 ; 296). Kendati demikian, ini bukan berarti agama, dalam hal ini khususnya Islam, mentolerir social inequality (perbedaan sosial) yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Sebaliknya agama memiliki cita-cita sosial untuk secara terus menerus menegakkan egalitarianisme dan keadilan dituntut kepada setiap pemeluknya. Ini dipandang sebagai ibadah yang sangat tinggi di mana manusia harus mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Sebenarya kesempatan berkompetensi secara sehat dalam mempertahankan kehidupan sangat dimungkinkan dalam agama dan terbuka bagi setiap individu. Perjuangan dan keterlibatan individu akan menentukan kualitas masing-masing sebagai khalifah. Namun demikian, dalam kompetesi tersebut agama juga menetapkan batasbatas dalam pemanfatan sumber daya alam dan lapangan kerja. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar dapat menghilangkan eksploitasi suatu kelompok atas kelompok lain dan menyelamatkan manusia dari kemerosotan (Ja’far Syah Idris, 1998; 94). Salah satu wujud kemerosotan itu tercermin dalam fenomena konglomerasi sebagai eskpresi kecemburuan sosial (Mochtar Pabottingi, dalam Kontektualisasi Islam dalam Sejarah, Paramadina, 1994; 619). Dengan demikian, jelas agama melarang terjadinya konsentrasi dan monopoli terhadap kekayaan yang juga termasuk kekuasaan, karena hal itu akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Kekuasaan dapat berubah menjadi alat penindasan, menjadi taghout yang ujung-ujungnya melahirkan konflik sosial mengatasnamakan agama. 28 Islam misalnya, merupakan agama yang sangat jelas menentang terjadinya konflik baik sesamanya maupun dengan orang yang berbeda agama. Kata Islam atau ucapan assalamu’alaiukum merupakan sebuah doa agar orang lain merasakan kedamaian. Agama menutun manusia ke jalan kedamaian. Allah, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan sesuatu berdasarkan kehendakNya. Semua ciptaanNya baik dan serasi, sehingga tidak mungkin kebaikan dan keserasian itu mengantar kepada kekacauan dan pertentangan. Makhluk Tuhan yang diciptakan ini sebenarnya bersumber dari satu sumber (Q.S.al-Anbiya : 92). Firman Allah ٩٢ إِنﱠ َٰھ ِﺬ ِٓهۦ أُ ﱠﻣﺘُﻜُﻢۡ أُﻣﱠﺔٗ َٰو ِﺣﺪَةٗ َوأَﻧَ ۠ﺎ َرﺑﱡﻜُﻢۡ ﻓَﭑﻋۡ ﺒُﺪُو ِن Demikian pula halnya manusia, dia tercipta dari tanah melalui seorang ayah dan ibu. Oleh karenanya manusia hidup bukan saja harus berdampingan harmonis dengan sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan. Bukankah ketika manusia mati, dia kembali lagi ke tanah ? Persoalannya sekarang, apakah memang setiap agama itu harus memandang satu sama lain sebagai musuh yang harus dibenci dan dihancurkan. Tampaknya hal itu sangat tidak sejalan dengan substansi agama. Bukankah agama Islam dan Nashrani (misalnya) memiliki ajaran keselamatan dan cinta kasih. Islam pada dasarnya di samping pengertian lain memuat pesan dan substansi keselamatan. Ketika seorang muslim melakukan shalat, dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri yang berarti dia menebarkan dan memiliki komitmen terhadap keselamatan dan kedamaian. Demikian pula dengan agama nasrani, agama ini memiliki ajaran cinta kasih yang menekankan pentingnya kasih dan damai. Sebab-Sebab Konflik Sosial dalam beragama Dalam berbagai konflik sosial yang terjadi di tanah air, sudah banyak motif konflik tersebut dilandasi atas sintemen agama. Mereka menyatakan bahwa perang antar penduduk atau etnis tersebut merupakan konflik terbuka dalam rangka mempertahankan “agama”. Sebutlah misalnya kasus seperti di Ambon, Poso, Ketapang. Kasus-kasus ini sesungguhnya bermula dari kasus kecil yang kebetulan pelakukanya adalah orang yang berbeda agama satu sama lain. Misalnya di Ambon, kasusnya bermula hanya dari perkelahian antara preman pasar (beragama Islam) dengan sopir angkotan kota (beragama Kristen). Kasus kriminal murni seperti ini melebar kepada kasus konflik antar pemeluk agama. Demikian pula yang terjadi di Medan antara anggota Pemuda Pancasila (mayoritas Islam) dengan anggota Ikatan Pemuda Karya (mayoritas Kristen) yang konfliknya hanya persoalan lahan yang diperebutkan, tetapi implikasinya perkelahian tersebut justeru mengatasnamakan agama. Sepanjang analisis para tokoh, konflik sosial dalam beragama yang tejadi selama ini tidak ada yang dilatarbelakangi oleh doktrin agama, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh kriminal-kriminal murni yang kemudian mengatasnamakan agama. Oleh karena itu Menurut Ridwan Lubis, konflik yang terjadi antara umat beragama selama ini tidak dapat diebut sebagai konflik – dalam pengertian tindakan permusuhan (behavioral Hostility) berupa konfrontasi – yang secara nyata dapat diklasifikasikan sebagai konflik antar umat beragama. Kerusuhan tersebut lebih tepat dikategorikan 29 sebagai konflik sosial yang tidak mengatasnamakan agama tertentu, meski dua kelompok yang bertikai adalah dua penganut agama yang bereda. (Ridwan Lubis, 2001; 40) Jika dicermati sedemikian rupa, konflik-konflik yang terjadi di negara kita selama ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan konflik antar umat beragama. Jika dilihat dari karakteristik pelaku, ternyata mereka adalah oknum penganut agama (warga negara) yang sesungguhnya tidak banyak mengetahui doktrin agama bahkan hampir tidak memiliki perhatian terhadap agamanya. Demikian pula latar belakang kelompok yang terlibat bukanlah dari kelompok organisasi keagamaan. Lebih dari itu ternyata target yang ingin dicapai dari konflik tersebut juga bukan ditujukan untuk agama tertentu, tetapi lebih banyak menyangkut masalah kepentingan ekonomi dan politik. Meskipun demikian, peneliti tidak menyangkal bahwa konflik murni atas dasar agama juga masih ada seperti kasus penyerangan dan pembakaran gereja akibat gereja didirikan tidak seizin dengan warga setempat yang mayoritas beragama Islam. Demikian pula, ada konflik di daerah tertentu, orang Kristen memprotes kerasnya suara sound sistem masjid yang mengganggu ketenangannya. Akan tetapi meski ada riak-riak konflik seperti itu, areal konflik hanya sebatas lingkungan sekitarnya, tidak menyebabkan konflik secara luas dan itupun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan konflik sosial yaitu: a. Pemahaman ajaran agama yang sempit Agama pada dataran pemahaman dan praktik, bukan pada dataran kewahyuan, memang dapat menimbulkan konflik sosial baik bersifat latent maupun manifest. Pada dasarnya agama yang ada di dunia ini menawarkan konsep-konsep bernilai luhur seperti keselamatan, kedamaian dan cinta kasih. Akan tetapi sudah merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa sintemen agama dan simbolnya sangat kental mewarnai kekerasan, penidasan dan kerusuhan yang terjadi. Kenapa agama dapat membawa seorang pemeluknya ke dalam dunia konflik? Hal ini terjadi disebabkan oleh penganut agama tersebut tidak dapat memahami dan mempraktikan agamanya secara baik dan benar. Di dalam pemahaman keagamannya hanya ada konsep eksklusivitas, menganggap dia yang paling baik-benar dan berhak. Akibatnaya di luar dari dirinya semuanya salah. Dia menganggap orang yang tidak sejalan dan seirama dengan kayakinannya sebagai musuhnya. Padahal di dalam agama (Islam) misalnya telah diajarkan tiga konsep status manusia dan peranannya. Pertama, jika ia berhadapan dengan Allah, maka statusnya adalah sebagai hamba Allah dan peranannya adalah menjalankan perintah agama. Kedua, jika ia berhadapan dengan sesama manusia, maka statusnya adalah saudara. Peranannya adalah menyambung, meningkatkan dan memperkuat persaudarannya, baik saudara sebagai anak –cucu Adam, saudara sebangsa dan setanah air meski berbeda warna ; kulit, bahasa dan agama. Ketiga, jika ia berhadapan dengan lingkungan, statusnya adalah sebagai khalifah dan peranannya adalah memakmurkan bumi dan segala isinya. Dengan demikian, sebenarnya jika dipahami ajaran agama secara baik dan benar, maka manusia hidup dalam kerukunan dan ketentraman b. Kesenjangan Sosial-Ekonomi 30 Perbedaan yang terjadi secara individual dalam dataran kehidupan manusia merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Sebagian orang lebih baik dari orang lain dalam hal jasmani, akal, kekayaan, jabatan dan lain-lain merupakan kenyataan yang dimaksud. Akibat perbedaan tersebut, muncullah stratifikasi masyarakat yang terkelompok ke dalam golongannya masing-masing. Ada individu yang mampu menghasilkan lebih atau cukup, ada pula kurang, bahkan ada yang sama sekali tidak mampu menghasilkan apa-apa. (Azhar Basyir, 1993; 186). Kesenjangan sosial yag terjadi saat ini tidak lepas dari adanya strata masyarakat seperti tersebut di atas. Ketimpangan sosial pada mulanya berawal di bidang ekonomi yaitu di bidang pemenuhan materi, akan tetapi lama kelamaan tidak dapat dipungkiri hal ini meluas ke sektor lain yaitu sosial, politik, budaya dan agama (Farid Mas’udi, 1991; 185). Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini kesenjangan sosial tampak sangat kompak, karena tidak lagi dapat dipisahkan antara faktor-faktor yang ada. Faktor tersebut sangat terkait satu sama lain. Kesenjangan ekonomi hampir sulit dipisahkan dengan politik atau lainnya. Realitas sosial objektif di Indonesia saat berupa kesenjangan kaya-miskin, ketidakadilan sosial bahkan ketidak adilan dalam arti distribusi kekuasaan masih begitu mencolok, bahkan ada fenomena kecendrungan kekuasaan berjalan seirama dengan kekayaan. Artinya jika ia menjabat, maka ia menjadi orang kaya. Sebaliknya jika ia orang kaya, tampaknya jabatan dapat dibelinya. Kerusuhan yang terjadi di Makassar tahun 1997 (penyerangan terhadap kelompok Tionghoa), pengusiran warga Madura oleh suku Daya di Kalimantan Tengah, diusirnya kelompok BBM (Bugis, Buton, Makassar) dari Ambon, merupakan contoh-contoh konflik akibat kesenjangan sosial ekonomi. Dalam masyarakat miskin seperti di Indonesia yang terus mengadakan perubahan (pembangunan) seirama dengan masyarakat dunia modern, tidak dapat dihindari adanya disparitas pendapatan dan sosial yang memungkinkan timbulnya kesenjangan yang berakibat konflik, karena ada beberapa kelompok yang belih mampu memanfaatkan kesempatan baru yang diberikan oleh pembangunan tersebut. Dengan demikian ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan dan pada tahap inilah kerusuhan sosial seperti di atas dapat terjadi. c. Provokasi Pihak ke tiga Banyak pihak yang mensinyalir bahwa hampir setiap kerusuhan yang terjadi dipicu oleh adanya intervensi dan provokasi pihak ketiga atau dikenal dengan provokator. Kesimpulan ini diambil atas dasar adanya fenomena keseragaman pola dan waktu terjadinya kerusuhan, seperti peristiwa bom di malam natal, tragedi etnis Tionghoa di bulan Mei 1998. Hanya saja pihak ketiga ini sampai saat ini masih sulit diidentifikasi. d. Fanatisme terhadap Partai Politik Fanatisme kepartaian ternyata juga dapat menyulut konflik antar umat beragama. Hal ini terjadi di Pekalongan pada tahun 1997. Di Pekalongan mayoritas masyarakat mengidolakan PPP sebegai partainya. Akan tetapi Golkar melalui pendekatannya terhadap Kiyai dan birokrasi sanggup mengimbangi arus suara PPP. Ternyata hal ini memicu terjadinya konflik yang tadinya hanya sebatas konflik antara pendukung parti, tetapi akhirnya merembes ke konflik agama (Simuh, 2001; 16) 31 2. Peranan Agama dalam Penyelesaian Konflik Secara substansial, sebenarnya agama tidak pernah mengalami konflik satu sama lain. Yang terjadi saat ini adalah konflik antara pemeluk/umat beragama yang disebabkan oleh faktor-faktor eskternal agama tetapi kadangkala mengatasnamakan agama. Oleh karena yang bertikai adalah para pemeluk agama, maka yang aktif melakukan penyelesaian konflik adalah subjek yang bersangkutan. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain: a. Peningkatan pemahaman keberagamaan Rendahnya kualitas pemahaman terhadap agama dapat memicu konflik akibat pemikiran inklusivisme yang menganggap hanya diri dan keyakinannya saja yang paling benar. Demikian pula sempitnya pemahaman masyarakat terhadap simbol dan term-term agama seperti istilah jihad, dimaknai sebagai sebuah peperangan suci mengantam orang yang berada di luar agamanya. Menurut K. H. A. Khalik Yahya, selama ini pula pesantren yang juga merupakan basis pengembangan Islam hanya mengajarkan agama kepada para santri dengan pola berfikir linier, satu arah, berwawasan sempit, fanatisme dan kurang menerima perbedaan. (Simuh, 2001; 18) Oleh karena itu dalam pemberian materi kegamaan hendaknya diberikan variasi dengan memberikan berbagai pendapat ulama yang akhirnya dapat membentuk sikap toleransi dalam beragama maupun dalam bermazhab. H. M. Quraish Shihab menggambarkan bagaimana sesungguhnya Islam menggambarkan ide dasar kerukunan dan demokrasi. Lebih lanjut dijelaskan, agama – dalam hal ini Islam – diturunkan tidak saja bertujuan mempertahakan eksistensinya sebagai agama tetapi juga mengakui eksistensi agama lainnya dan memberinya hak hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk agama lain. H. M. Quraish Shihab memberikan contoh dengan mengutip beberapa ayat al-Qur’an antara lain : (1).Q.S.al-An’am : 108. ْﺴﺒﱡﻮ ْا ٱ ﱠ َ ﻋَﺪۡ َۢوا ﺑِﻐَﯿۡ ِﺮ ﻋِﻠۡ ٖ ۗﻢ َﻛ َٰﺬﻟِ َﻚ َزﯾﱠﻨﱠﺎ ﻟِ ُﻜ ﱢﻞ أُ ﱠﻣ ٍﺔ َﻋ َﻤﻠَﮭُﻢۡ ﺛُ ﱠﻢ إِﻟ َٰﻰ َرﺑﱢﮭِﻢ ﻣ ۡﱠﺮ ِﺟ ُﻌﮭُﻢۡ ﻓَﯿُﻨَﺒﱢﺌُﮭُﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ُ َﺴﺒﱡﻮ ْا ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﺪۡ ﻋُﻮنَ ﻣِﻦ دُو ِن ٱ ﱠ ِ ﻓَﯿ ُ ََو َﻻ ﺗ ١٠٨ َﯾَﻌۡ َﻤﻠُﻮن Terjemahnya ”Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan” (2) QS. al-Baqarah : 256. ٢٥٦ ﺳﻤِﯿ ٌﻊ َﻋﻠِﯿ ٌﻢ َ ُ ﺼﺎ َم ﻟَ َﮭ ۗﺎ وَٱ ﱠ َ ِﺴ َﻚ ﺑِﭑﻟۡ ﻌ ُۡﺮ َو ِة ٱ ۡﻟﻮُﺛۡ ﻘ َٰﻰ َﻻ ٱﻧﻔ َ ۡت َوﯾ ُۡﺆﻣ ِۢﻦ ﺑِﭑ ﱠ ِ ﻓَﻘَ ِﺪ ٱﺳۡ ﺘَﻤ ِ َ ٓﻻ إِﻛۡ ﺮَاهَ ﻓِﻲ ٱﻟﺪﱢﯾ ِۖﻦ ﻗَﺪ ﺗﱠﺒَﯿﱠﻦَ ٱﻟﺮﱡﺷۡ ُﺪ ﻣِﻦَ ٱﻟۡ َﻐ ﱢۚﻲ ﻓَﻤَﻦ ﯾَﻜۡ ﻔ ُۡﺮ ﺑِﭑﻟ ﱠٰﻄﻐُﻮ Terjemahnya : ”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya 32 ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (3) QS.al-Kafirun: 6. ٦ ﻟَﻜُﻢۡ دِﯾﻨُﻜُﻢۡ َوﻟِ َﻲ دِﯾ ِﻦ Terjemahnya: “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. (4) QS.al-Hajj: 40. ت َو َﻣ َٰﺴ ِﺠ ُﺪ ﯾُﺬۡ َﻛ ُﺮ ﻓِﯿﮭَﺎ ٱﺳۡ ُﻢٞ ﺻﻠَ َٰﻮ َ َوٞﺻ َٰﻮ ِﻣ ُﻊ َوﺑِﯿَﻊ َ ﻀﮭُﻢ ﺑِﺒَﻌۡ ﺾٖ ﻟ ﱠ ُﮭ ﱢﺪﻣ َۡﺖ َ ۡﻖ إ ﱠ ِٓﻻ أَن ﯾَﻘ ُﻮﻟ ُﻮ ْا َرﺑﱡﻨَﺎ ٱ ﱠ ۗ ُ َوﻟ َۡﻮ َﻻ دَﻓۡ ُﻊ ٱ ﱠ ِ ٱﻟﻨﱠﺎسَ ﺑَﻌ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ أ ُۡﺧﺮِﺟُ ﻮاْ ﻣِﻦ ِد َٰﯾ ِﺮھِﻢ ﺑِﻐَﯿۡ ِﺮ ﺣَ ﱟ ٤٠ ي َﻋﺰِﯾ ٌﺰ ﺼ ُﺮ ٓۚۥه ُ إِنﱠ ٱ ﱠ َ ﻟَﻘَ ِﻮ ﱞ ُ ﺼﺮَنﱠ ٱ ﱠ ُ ﻣَﻦ ﯾَﻨ ُ ٱ ﱠ ِ َﻛﺜ ِٗﯿﺮ ۗا َوﻟَﯿَﻨ Terjemahnya : “Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian orang atas sebagian yang lain (tidak mendorong kerjasama antar manusia) nicara rubuhlah biara-biara, gereja-gereja, rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah”. Ayat di atas dijadikan oleh sebagian para ulama sebaga argumen keharusan memelihara tempat ibadah non muslim. (H. M. Quraish Shibah: 1996; 379-380). Jika pemahaman keagamaan yang seperti ini dapat disosialisasikan kepada semua pemeluk agama, di mana intinya setiap agama senantiasa menjunjung tinggi keadilan, kedamaian dan keharmonisan, maka konflik sosial yang mengatasnamakan agama dapat dihindari. Dengan demikian, untuk mengembangkan kerukunan antar umat beragama, maka diperlukan pendekatan pemahaman keagamaan yang pluralis-dialogal. Pendekatan ini akan menghargai dan menempatkan orang lain dalam prespektif saya, dan menempatkan saya dalam kehadiran orang lain. Untuk hal tersebut di atas, maka para tokoh agama dan juru penyeru agama lain perlu memiliki sikap luhur, yaitu : pertama, hilangkan sikap saling curiga dan jangan menanamkan benih-benih permusuhan dan kebencian; kedua, jangan melakukan generalisasi dalam melihat suatu fenomena keagamaan, yakni tindakan atau ucapan seseorang atau kelompok penganut agama tertentu lalu digeneralisasikan sebagai sikap menyeluruh dari penganut agama yang bersangkutan; ketiga, kembangkan suasana positive thinking (berfikir positif) dengan berusaha memahami dan menghargai keyakinan orang lain Agama bisa mengalami krisisi relevansi jika tidak dhayati dan diamalkan dengan baik. Yang dimaksud dengan krisis relevansi adalah ketika masyarakat mencari pemecahan masalah sosial yang tajam, ia tidak menemukan arahanarahan dari paham atau ideologi agama, lalu ia mencari-cari ideologi lain. Demikian pula jika tidak mampu memperjuangkan tauhid sosial, bisa jadi akan muncul di tengah masyarakat suatu ideologi non religion bahkan ideologi anti agama yang akan diikuti oleh banyak orang sebab ideologi baru itu mungkin memberikan tawaran atau solusi alternatif pemecahan masalah kehidupan. Mereka tidak percaya kepada agama, sebab agama hanya mendatangkan konflik sosial, kontroversial, ritualisme semata, tidak ada tauhid sosialnya. Ini sangat berbahaya. 33 Jika tokoh atau pemuka agama tidak mampu merumuskan tauhid sosial, bisa jadi masyarakat yang mengagung-agungkan dan menjunjung tinggi keadilan, pemerataan dan lain-lai tidak menemukannya di dalam agama, justeru mereka temukan di dalam ajaran Marxisme, Leninisme, Trotskisme. Hal ini berakibat fatal terhadap kehidupan umat beragama. Andaikata masalah di atas tidak dipedulikan, secara tidak sengaja kita telah mengizinkan tumbuhnya sekularisme, sebuah faham yang menolak campur tangan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendeknya, ajaran agama harus diwujudnyatakan dalam kehidupan sekaligus digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Ajaran keadilan yang diakui oleh semua agama harus kembali diamalkan dan ditegakkan. b. Dialog-Dialog pemuka Agama Saat ini diperlukan wacana atau dialog para pemimpin atau tokoh agama untuk meredam ketidakpahaman atau emosi arus bawah. Di Indonesia berlaku teori bayang-bayang. Jika substansi aslinya bergerak, maka bayangannya juga turut bergerak. Artinya apa yang terjadi selama ini lapisan bawah sesungguhnya mencerminkan apa yang terjadi di lapisan atas, hanya saja pola dan modelnya yang berbeda akibat perbendaan pendidikan. Harus diakui, dalam komunitas tertentu, tokoh agama merupakan figur sentral dalam masyarakat. Pada umumnya seseorang dianggap sebagai tokoh agama karena kharismanya, memiliki dasar penmgetahuan teologi, komit terhadap ajaran agamanya dan menjadi teladan bagi jemaahnya. Di dalam agama kristen orang seperti ini antara lain ; pendeta, penginjil, penatua, dan deaken. Di dalam Islam dikenal ustadz, imam, kiyai, guru (ngaji), muballigh. Pola hubungan tokoh dengan umatnya adalah top down. Seorang tokoh bagi umatnya merupakan figur sentral yang dikeramatkan karena kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itulah diperlukan hubungan dan dialog yang baik antar para tokoh tersebut untuk mencairkan kebekuan dan meredam konflik antar pemeluk agama. Di desa Sitiarjo, menurut Imam Prayogo kebersamaan umat beragama tampak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ; a. Adanya kunjungan para tokoh agama ke tempat ibadah; b. Kerjasama sosial yang melibatkan semua unsur pemeluk agama, misalnya dalam pembangunan jalan dan jembatan; c. Jika ada seorang warga yang meninggal, maka seluruh masyarakat ikut membantu tanpa melihat dari agama mana ia berasal; d. Tidak adanya pemisahan lokasi pemakana yang mencolok antara umat Islam dan Kristen; Suasana dialogis menggambarkan adanya pergaulan antara pribadi-pribadi yang saling berusaha mengenal pihak lain sebagaimana adanya (D. Hendropuspito, 1994; 172.) Dialog antar umat beragama berarti setiap penganut agama bersedia mengemukakan pengalamanpengalamana keagamaan mereka yang berakar pada tradisi agama masing-masing. Pengertian-pengertian ini menunjukkan bahwa untuk melakukan dialog demi terwujudnya toleransi antar umat beragama diperlukan sikap dasar, seperti : keterbukaan (inklusif), kesediaan bertukar fikiran dengan orang atau kelompok yang jelas-jelas berbeda, saling mempercayai, dan keinginan untuk membangun kehidupan yang membawa rahmat. Kejujuran dalam 34 mengemukakan ide atau fakta akan sangat membantu bagi semua pihak untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagi kepentingan bersama. Sesungguhnya sikap toleransi dan inklusif yang digambarkan diatas, sudah sejak lama dipraktekkan dalam aplikasi dakwah. Dalam hal ini, ajaran Islam sebagai inti pesan-pesan dakwah menghargai kemerdekaan setiap orang untuk memeluk dan mengamalkan suatu agama. Islam mengajarkan bahwa setiap orang yang dilahirkan tidak untuk dirampas kemerdekaannya yang telah diberikan oleh Allah. Mandat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. hanyalah terbatas pada menyampaikan ajaran Islam dan bukan untuk memaksa orang lain untuk memeluk Islam, sebab mandat untuk memberikan hidayah hanya dimiliki oleh Allah semata-mata. Dalam Islam proses dialogis dan toleransi ini sangat jelas. Mislnya dalam sejarah tercatat bahwa masyarakat pendukung Piagam Madinah jelas memperlihatkan karakter masyarakat yang majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, maupun segi budaya dan agama. Di dalamnya terdapat Arab muslim, Yahudi dan Arab non muslim. Dalam Piagam Madinah tersebut terlihat beberapa asas yang dianut: Pertama, asas kebebasan beragama, negara mengakui dan melindungi setiap kelompok untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Landasannya Q.S. al-Kafirun: 6. Kedua, asas persamaan. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seorangpun diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi, bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu. Allah swt berfirman: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. “. (Q.S. al-Maidah/6 : 2). Ketiga, asas kebersamaan. Semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Landasannya adalah Q.S.al-Nisa/5: 59. َي ٰ◌◌ٓ أَﯾﱡﮭَﺎ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَا َﻣﻨ ُﻮٓ ْا أَطِﯿﻌُﻮاْ ٱ ﱠ َ َوأَطِﯿﻌُﻮ ْا ٱﻟ ﱠﺮﺳُﻮ َل َوأ ُوْ ﻟِﻲ ۡٱﻷَﻣۡ ِﺮ ﻣِﻨﻜ ۡ ُۖﻢ ﻓَﺈ ِن ﺗَ َٰﻨﺰَﻋۡ ﺘُﻢۡ ﻓِﻲ ﺷ َۡﻲءٖ ﻓَ ُﺮدﱡوهُ إِﻟَﻰ ٱ ﱠ ِ وَٱﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ِل إِن ﻛُﻨﺘُﻢۡ ﺗ ُۡﺆ ِﻣﻨ ُﻮن َ ٥٩ ِﯾﻼ ً ﺮ َوأ َۡﺣﺴَﻦُ ﺗَ ۡﺄوٞ ۡٱﻷ ِﺧ ِۚﺮ َٰذﻟِ َﻚ ﺧَ ﯿ ٓ ۡ ِﺑِﭑ ﱠ ِ وَٱﻟۡ ﯿ َۡﻮم Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Keempat, asas keadilan. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum harus ditegakkan, siapapun yang melanggarnya harus terkena hukuman. Hak individu diakui. Landasannya adalah Q.S. al-Nisa :58 ٥٨ ِﯿﺮا ٗ س أَن ﺗ َۡﺤ ُﻜﻤُﻮ ْا ﺑِﭑﻟۡ ﻌَﺪۡ ِۚل إِنﱠ ٱ ﱠ َ ﻧِ ِﻌﻤﱠﺎ ﯾَ ِﻌﻈُﻜُﻢ ﺑِ ۗ ِٓﮫۦ إِنﱠ ٱ ﱠ َ ﻛَﺎنَ َﺳﻤِﯿ َۢﻌﺎ ﺑَﺼ ِ ﺖ إِﻟ ٰ َٓﻰ أَھۡ ﻠِﮭَﺎ َوإِذَا َﺣﻜَﻤۡ ﺘُﻢ ﺑَﯿۡ ﻦَ ٱﻟﻨﱠﺎ ِ إِنﱠ ٱ ﱠ َ ﯾَ ۡﺄ ُﻣ ُﺮﻛُﻢۡ أَن ﺗُ َﺆدﱡو ْا ۡٱﻷَ َٰﻣ َٰﻨ 35 ۞ Terjemahnya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kelima, asas perdamaian yang berkeadilan. Landasannya Q.S.al-Baqarah/2 : 256. ٢٥٦ ﻚ ﺑِﭑﻟۡ ﻌ ُۡﺮ َو ِة ٱﻟۡ ﻮُﺛۡ ﻘ َٰﻰ َﻻ ٱﻧﻔِﺼَﺎ َم ﻟَﮭَ ۗﺎ وَٱ ﱠ ُ َﺳﻤِﯿ ٌﻊ َﻋﻠِﯿ ٌﻢ َ ت َوﯾ ُۡﺆﻣ ِۢﻦ ﺑِﭑ ﱠ ِ ﻓَﻘَ ِﺪ ٱﺳۡ ﺘَﻤۡ َﺴ ِ ﻻ إِﻛۡ ﺮَاهَ ﻓِﻲ ٱﻟﺪﱢﯾ ِۖﻦ ﻗَﺪ ﺗﱠﺒَﯿﱠﻦَ ٱﻟﺮﱡ ﺷۡ ُﺪ ﻣِﻦَ ٱﻟۡ َﻐ ﱢۚﻲ ﻓَﻤَﻦ ﯾَﻜۡ ﻔ ُۡﺮ ﺑِﭑﻟ ﱠٰﻄﻐُﻮ َٓ Terjemahnya : “ Tidak ada paksaan (untuk memasuki) agama Islam …… Keenam, asas musyawarah. (38)ََوأَْﻣُﺮُﻫ ْﻢ ﺷُﻮرَى ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ وَﳑِﱠﺎ َرَزﻗْـﻨَﺎ ُﻫ ْﻢ ﻳـُﻨْ ِﻔﻘُﻮن Semua komunitas beragama diwakili oleh tokoh masing-masing harus banyak melakukan dialog untuk mencari titik persamaan dan akar masalah. Alquran sendiri mendesak kepada Muhammad dan umatnya agar mengajak ahli kitab kepada suatu kalimat yang sama (diolog-mufakat) untuk mengingat persaudaraan. ( Nourouzzaman, Jeram; 85-86) Dialog memang perlu diperbanyak. Misalnya, kebanyakan umat Islam biasa resah dengan pendirian gereja yang amat banyak, sementara di lokasi tersebut penganut agama kristen tidak terlalu banyak. Dalam hal ini umat Islam tidak mengerti sehingga marah dan resah. Umat Islam tidak mengerti bahwa pendirian gereja tidak sama dengan mesjid. Mereka menyangka setiap gereja dapat dimasuki oleh umat kristen kapan dan di manapun, padahal tidak demikian. Dalam agama kristen, setiap gereja sudah ditentutan jemaahnya masing-masing. Tidak seperti di dalam Islam, mesjid yang dibangun oleh orang NU atau Muhammadiyah dan organisasi apa saja, atau apapun nama mesjidnya, semua dapat dimasuki dan dijadikan tempat ibadah/sujud bagi orang Islam. 36 BAB VI ETIKA DALAM ISLAM (Kepada Allah, Manusia dan Lingkungan) Sejarah agama menunjukkan bahwa kebehagiaan yang ingin dicapai dengan menjalankan syariah agama itu hanya dapat terlaksana dengan adanya akhlak yang baik. Kepercayaan yang hanya berbentuk pengetahuan tentang keesaan Tuhan, ibadah yang dilakukan hanya sebagai formalitas belaka, muamalah yang hanya merupakan peraturan yang tertuang dalam kitab saja, bukanlah merupakan jaminan untuk tercapainya kebahagiaan tersebut. Timbulnya kesadaran akhlak dan pendirian manusia terhadap-Nya adalah pangkalan yang menetukan corak hidup manusia. Akhlak, atau moral, atau susila adalah pola tindakan yang didasarkan atas nilai mutlak kebaikan. Hidup susila dan tiap-tiap perbuatan susila adalah jawaban yang tepat terhadap kesadaran akhlak, sebaliknya hidup yang tidak bersusila dan tiap-tiap pelanggaran kesusilaan adalah menentang kesadaran itu. Kesadaran akhlak adalah kesadaran manusia tentang dirinya sendiri, dimana manusia melihat atau merasakan diri sendiri sebagai berhadapan dengan baik dan buruk. Disitulah membedakan halal dan haram, hak dan batil, boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dia bisa melakukan. Itulah hal yang khusus manusiawi. Dalam dunia hewan tidak ada hal yang baik dan buruk atau patut tidak patut, karena hanya manusialah yang mengerti dirinya sendiri, hanya manusialah yang sebagai subjek menginsafi bahwa dia berhadapan pada perbuatannya itu, sebelum, selama dan sesudah pekerjaan itu dilakukan. Sehingga sebagai subjek yang mengalami perbuatannya dia bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. A. Etika terhadap Tuhan Sebagaimana telah disebutkan dalam dalam kitab-kitab kalam bahwa salah satu bukti yang paling populer dan yang paling penting atas keniscayaan mengenal Tuhan yaitu bahwa bersyukur kepada pemberi adalah kewajiban. Tuhan adalah pemberi wujud dan kesempurnaan kita serta segala kemungkinan yang kita miliki, maka bersyukur kepada-Nya menurut hukum moral adalah sebuah keharusan. Keharusan mensyukuri Tuhan hanya mungkin dilakukan hanya dengan mengenal Tuhan. Selama kita tidak mengenal Tuhan, maka ketika itu pula kita tidak akan pernah bersyukur kepada-Nya. Dengan demikian, keniscayaan mengenal Tuhan itu dilandasi oleh hukum moral yang menegaskan bahwa “bersyukur kepada pemberi adalah sebuah keharusan.1 Disamping itu, banyak pemikir-pemikir Barat yang mengandalkan argumen moral dalam upaya membuktikan eksistensi Tuhan. Tampaknya filosof yang pertama kali membuktikan eksistensi Tuhan dengan argumen ini adalah Immanuel Kant. Ia menganggap mandul semua argumen akal budi atas eksistensi Tuhan, meyakini bahwa implikasi akal praktis dan undang-undang moral adalah pengakuan atas keberadaan Tuhan dan atas 1Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Falsafeh ye Akhlaq, diterjemahkan oleh Ammar Fuazi Heriyadi dengan judul, Meniru Tuhan: antara Yang Terjadi dan Yang Mesti Terjadi, (Cet. I; Jakarta: AL-Huda, 2006), h. 212. 38 sejumlah dogma-dogma agama seperti keabadian roh. Menurut Kant, iman kepada Tuhan dan kekalan roh (hingga di alam akhirat) bertummpu pada kesadaran moral dan akal praktis.2 Lewat argumen moral, sebahagian pemikir berusaha mengaitkan konstansi dan kemutlakan perintah dan larangan moral dengan adanya pemerintah dan pelarang yang absolut dan eternal yakni Tuhan. Artinya perintah dan larangan moral mengonsekuensikan adanya Zat pemerintah dan pelarang. Zat itu bukanlah orang atau kelompok manusia, tapi satu otoritas metafisik dan adiinsani. Zat itu bernama Tuhan sebagai sumber tuntutan-tuntutan moral. Bahkan ada pula yang berusaha membuktikan eksistensi legeslasi Tuhan lewat hukum-hukum moral. Eksplasi yang cukup populer dari argumen moral yaitu bahwa nilai-nilai moral itu adalah objek-objek kongkrit yang diwujudkan oleh Sang Pencipta. Dia bukanlah wujud material, bukan pula wujud immaterial layaknya roh manusia yang mengalami ketiadaan, sementara prinsip dan nilai moral tetap utuh. Ketetapan dan keutuhan inilah yang menunjukkan bahwa sang pencipta itu adalah satu wujud transendentaal yakni Tuhan.3 Begitu pula dengan penyembahan, bahwa akhlak menuntun manusia untuk menjalankan kewajibankewajiban agama. Bahwa pilar agama tegak di atas ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Namun dengan alasan apakah kita harus menyembah kapada Tuhan? Ya, karena Tuhan adalah pencipta kita, maka Tuhan berhak untuk ditaati dan disembah. Dan manusia sebagai makhluk-Nya, harus memenuhi hak-Nya dan dengan cara pemenuhan hak tersebut adalah ibadah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ali Zainal Abidin, bahwa “hak Allah swt yang paling besar atas umat manusia adalah penyembahann mereka kepada-Nya, seraya tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.4 Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tidak membuat sekutu (syarikat) bagi-Nya. Dia memiliki sifat-sifat terpuji. Demikian agung sifat itu, jangankan manusia, malaikat sekalipun tidak dapat menjangkau hakekat-Nya.5 Akhlak terhadap Allah ini, digambarkan dalam QS. Luqman (31):13. ﻳﺎﺑﲏ ر ﺗﺸﺮك ﺑﺎﷲ إن اﻟﺸﺮك ﻟﻈﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ... Mengakui dengan sesungguhnya, bahwa Allah tidak memiliki sekutu, merupakan akhlak terhadap Allah. Luqman al-Hakim memulai nasehatnya dengan perintah untuk tidak menyekutukan Allah, merupakan penanaman ajaran tauhid yang memiliki implikasi terhadap penanaman sikap dan akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah tidak hanya terbatas dalam hal mengesakan-Nya, tetapi mencakup seluruh perilaku akhlak baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan (ibadah). 2Bertrand Russel, History of Western Philosophy and its Connection With Political and Social Circumstances From The Earliest Times to The Present Day, diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko dkk dengan judul, Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga sekarang, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 926-927. 3Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Falsafeh ye Akhlaq, op. cit., h. 213. 4Ibid., 5M. Quraish Shihab, Wawasan, h. 262. 39 Di dalam al-Qur’an dijelaskan, bahwa akhlak terhadap Allah tidak saja dilakukan manusia, tetapi seluruh makhluk yang ada di alam jagad raya ini. Beberapa ayat al-Qur’an di antaranya yang menggambarkan sikap makhlukNya sebagai suatu sikap akhlak, misalnya firman Allah dalam QS. al-Naml (27):93. وﻗﻞ اﳊﻤﺪ ﷲ ﺳﲑﻳﻜﻢ آﻳﺎﺗﻪ ﻓﺘﻌﺮﻓﻮ ﺎ وﻣﺎ رﺑﻚ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن Terjemahnya: ‘Dan katakanlah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan.’6 Di dalam QS. al-Syura (42):5 Allah berfirman: ... واﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﺴﺒﺤﻮن ﲝﻤﺪ ر ﻢ... Terjemahnya: ‘… Dan para malaikat menyucikan sambil memuji Tuhan mereka …’7 Di dalam QS. al-Ra’d (13):13. وﻳﺴﺒﺢ اﻟﺮﻋﺪ ﲝﻤﺪﻩ واﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﻔﺘﻪ وﻳﺮﺳﻞ اﻟﺼﻮاﻋﻖ ﻓﻴﺼﻴﺐ ﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻫﻢ ﳚﺎدﻟﻮن ﰲ اﷲ وﻫﻮ ﺷﺪﻳﺪ اﶈﺎل Terjemahnya: ‘Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepada-Nya dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang Maha Keras siksa-Nya.’8 Mengomentari ayat-ayat di atas, Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa makhluk tidak dapat mengetahui dengan baik dan benar betapa kesempurnaan dan keterpujian Allah swt. Itulah sebabnya mereka sebelum memuji-Nya, terlebih dahulu bertasbih dalam arti menyucikan-Nya. Jangan sampai pujian yang diucapkan tidak sesuai dengan kebesaran-Nya.9 Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa akhlak terhadap Allah tidak saja berupa pernyataan dan keyakinan tentang keesaan Allah, tapi lebih dari itu implikasi tauhid itu sendiri harus mencerminkan nilai-nilai akhlak tersebut. Keagungan Allah dengan sifat pengasih dan penyayang, serta berbagai macam sifat terpuji lainnya menunjukkan bahwa Allah sangat menyayangi hamba-Nya, apalagi bagi hamba yang senantiasa bersyukur.10 Allah bahkan berjanji menjadi pelindung bagi hamba-Nya dalam QS. al-Muzammil (73):9: 6Departemen 7Ibid., 8Ibid., Agama RI., op. cit., h. 605. h. 783. h. 370. 9Quraish Shihab, Wawasan, h. 623. 10QS. Ibrahim (14):7. Dijelaskan di dalam ayat ini, bahwa hamba yang selalu bersyukur kepada Allah akan mendapat tambahan nikmat Allah, tapi hamba yang kufur nikmat, akan diazab dengan azab yang sangat pedih. 40 رب اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻫﻮ ﻓﺎﲣﺬﻩ وﻛﻴﻼ Terjemahnya: ‘Dialah Tuhan masyriq dan magrib, tiada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Allah sebagai wakil (pelindung).’11 Menjadikan Allah sebagai wakil,12 sesuai dengan maknanya berarti hendak dan bertindak sesuai dengan kehendak manusia yang menyerahkan perwakilan itu kepada-Nya.13 Pernyataan di atas, menurut Quraish Shihab, perlu diperluas penjelasannya, sebab jika tidak akan memberikan pengertian lain. Menurutnya, yang harus diingat adalah bahwa Allah itu Maha Esa, di antaranya esa dalam perbuatan-Nya, sehingga tidak dapat disamakan dengan perbuatan manusia, walaupun penamaannya sama. Allah swt. yang kepada-Nya diwakilkan segala urusan adalah Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Bijaksana dan Penyayang dan semua sifat yang mengandung pujian. Manusia sebaliknya, memiliki keterbatasan dalam segala hal. Dengan demikian “perwakilan-Nya” pun berbeda dengan perwakilan manusia.14 Ketika menjadikan Allah swt. sebagai wakil, manusia dituntut untuk melakukan sesuatu yang berada dalam batas kemampuannya. Dengan demikian, maka menjadikan Allah sebagai wakil (pelindung), dengan penuh penghambaan merupakan wujud dari akhlak seorang hamba terhadap penciptanya. Penghambaan seseorang terhadap Allah dilihat dari intensitas ibadah yang dilakukan, semakin tinggi nilainya semakin baik pula akhlaknya kepada Allah, sebaliknya semakin rendah kualitas atau tidak ada sama sekali ibadahnya kepada Allah, semakin rendah bahkan bisa dikatakan tidak berakhlak kepada-Nya. Ibadah memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan akhlak. Ibadah berkaitan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Perintah Allah berkaitan dengan perbuatan baik, sedangkan larangan Allah berkaitan dengan perbuatan yang tidak baik.15 Ibadah kepada Allah berkaitan erat pula dengan nilai pribadi seorang hamba. Kualitas pribadi (akhlak) yang baik memiliki nilai lebih di sisi Allah, sebaliknya ibadah yang tidak disertai dengan nilai kualitas akhlak tidak memiliki implikasi etis di hadapan Allah, sebab segala tindakan ibadahnya tidak disertai dengan akhlak. Dengan kata lain, akhlak terhadap Allah dalam segala bentuk ibadah sangat penting dan memiliki nilai di sisi-Nya. Pentingnya akhlak (ketundukan pribadi) kepada Allah dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw. dengan sabdanya: Agama RI., op. cit., h. 989. wakil terambil dari kata wakala, yakilu, berarti menyerahkan urusan kepada yang lain dan dijadikannya sebagai wakil. Lihat al-Asfihani, op. cit., h. 569. 11Departemen 12Kata 13M. Quraish Shihab, Wawasan, h. 263. 14Ibid., h. 264. 15Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung: Mizan, 1995), h. 57. 41 ﻋﻦ اﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ﳑﻦ ﻳﺪﻋﻲ اﻹﺳﻼم ﻫﺬا ﻣﻦ اﻫﻞ...ﺑﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺘﺎل ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﻗﺘﺎﻻ ﺷﺪﻳﺪا ﻓﺄﺻﺎﺑﺘﻪ ﺟﺮاﺣﺔ ﻓﻘﻴﻞ ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ اﻟﺬي ﻗﻠﺖ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ.اﻟﻨﺎر ﻓﺒﻴﻨﻤﺎﻫﻢ، ﻗﺎل ﻓﻜﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ان ﻳﺮﺗﺎب. ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﱄ اﻟﻨﺎر.ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻴﻮم ﻗﺘﺎﻻ ﺷﺪﻳﺪا وﻗﺪ ﻣﺎت ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﱂ ﻳﺼﱪ ﻋﻠﻲ اﳉﺮاح ﻓﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﺧﱪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ.ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ إذ ﻗﻴﻞ اﻧﻪ ﱂ ﳝﺖ وﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﰒ اﻣﺮ ﺑﻼﻻ ﻓﻨﺎدي ﻟﻨﺎس اﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ اﻻ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﻠﻤﺔ.اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎل اﷲ اﻛﱪ اﺷﻬﺪ اﱐ ﻋﺒﺪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ 16 .وان اﷲ ﻟﻴﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﺎﺟﺮ Terjemahnya: ‘… Abu Hurairah berkata: Kami bersama Rasulullah saw. berada (dalam perang) khaibar. Rasulullah saw bersabda terhadap seseorang yang mengaku muslim: “Orang ini ahli neraka”. Ketika peperangan itu terjadi, orang itu berperang dengan gigih sampai menderita luka-luka. Informasi sampai kepada Rasulullah saw. orang yang tadi anda katakan ahli neraka, hari ini telah berperang gigih sekali dan telah wafat. Rasul Allah bersabda: “Dia ke neraka”. Abu Hurairah berkata pula: Sebagian orang hampir saja tidak percaya. Dalam kondisi seperti itu diinformasikan pula orang itu belum meninggal, tetapi menderita banyak luka, lalu bunuh diri. Informasi itu pun sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda: “Maha Besar Allah, aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya”. Kemudian beliau menginstruksikan kepada Bilal untuk menyampaikan kepada orang banyak: “Hanya sesungguhnya pribadi yang tunduk yang akan masuk surga, dan sesungguhnya Allah akan memperkuat agama (Islam) ini dengan seorang fajir (yang imannya tidak benar).17 Hadis di atas mengandung makna, bahwa orang yang ternyata tidak memiliki akhlak kepada Allah, dalam arti dia melakukan ibadah hanya karena sesuatu, bukan karena Allah, maka orang itu tidak bermakna di sisi Allah. Segala usahanya hanya sia-sia. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa penghambaan yang setulus-tulusnya kepada Tuhan memberikan implikasi yang resiprocal (timbal balik). Menurut Harun Nasution, kaum sufi memiliki akhlak yang sangat tinggi kepada Allah. Dalam istilah sufi disebut al-takhalluq bi akhlaq Allah (memiliki akhlak Tuhan), al-ittisaf bi sifat Allah.18 Dengan akhlak seperti itu, kaum sufi menyatakan penghambaan kepada Allah dengan kesungguhan hati dan keikhlasan. 16al-Bukhariy, op. cit., jilid II, h. 1197. Lihat juga Imam Muslim, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy, jilid I (Indonesia: Maktabat Dahlan, t. th.), h. 105-106; Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, jilid II, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1398 H/1978 M), h. 309; Abu Muhammad ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahran al-Darimiy, Sunan al-Darimiy, jilid II (Indonesia: Maktabat Dahlan, t. th.), h. 240-241. 17Terjemahan penulis. 18Harun Nasution, Islam Rasional, h. 59. 42 B. Etika Terhadap Manusia Setelah mencermati kondisi realitas sosial tentunya tidak terlepas dari pembicaraan menggenai masalah kehidupan (problem of life). Tentu kita mengetahui bahwa adalah masalah dan tujuan hidup adalah mempertahankan hidup untuk kehidupan selanjutnya dan salah satu jalan untuk mempertahankan hidup dengan mengatasi masalah hidup itu sendiri. Kehidupan tidak pernah membatasi hak ataupun kemerdekaan seseorang untuk bebas berekspresi, berkarya dan lain sebagainya dalam menjalani hidup.19 Sejatinya kehidupan adalah saling memiliki ketergantungan antara sesame manusia dan dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari aturan-aturan, baik yang bersumber dari kesepakatan antara sesame maupun normanorma agama, karena hanya dengan norma hidup kita akan lebih jauh memahami akhlak natara sesame manusia dan makhluk lainnya dalam mengarungi kehidupan. Manusia tentu saja merupakan hasil dari evolusi terkhir dan karena itu, sebagai makhluk, manusia memiliki karakter atau sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan dan makhluk-makhluk yang lebih rendah dari manusia. Sekalipun hewan dikatakan memiliki kesadaran dan nafsu, tapi kesadaran hewan tentang dunia fisik hanyalah kesadaran indrawi, tidak bisa menjangkau ke kedalaman dan antarhubungan batin benda-benda. Kesadaran indrawi hanyalah pada objek-objek yang bersifat individual dan partikular dan tidak bisa menjangkau yang bersifat universal dan general.20 Berbeda dengan kesadaran hewani, kesadaran manusia bisa menjangkau apa-apa yang tidak bisa dijangkau oleh kesadaran hewani. Kesadaran manusia tidak tetap terpenjara dalam batas lokal atau ruang, ia juga tidak terbelenggu pada waktu tertentu. Kesadaran manusia justru bisa melakukan pengembaraan menembus ruang dan waktu. Namun selain dari itu, yang benar-benar membedakan antara manusia dengan hewan adalah “ilmu dan iman”. Inilah perbedan utama manusia dari hewan. Oleh karena itu, sains dan iman adalah dua hal yang harus diperoleh dan dikembangkan oleh manusia untuk mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaannya.21 Manusia menikmati kemuliaan dan keagungan yang khusus di antara makhluk-makhluk lain dan memiliki peran khusus sebagai wakil Tuhan dan misi khusus sebagai pengelola alam. Namun manusia (dengan kebebasan memilihnya) bertanggungjawab terhadap evolusi dan pertumbuhan serta pendidikannya begitu pula dengan perbaikan masyarakatnya. Alam semesta merupakan sekolah bagi manusia dan Tuhan akan memberi pahala pada setiap diri manusia sesuai dengan niat baik dan usahanhya yang tulus. Sifat kebebasan yang dimiliki manusia sehingga ia menjadi makhluk moral yang bisa diberi sifat baik dan buruk, tergantung perbuatan mana yang dipilihnya secara sadar. Sebagai makhluk moral senantiasa berinteraksi 19 Franz Magniz Suseno, Etika Dasar – Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 30. 20Mulyadhi Kartanegara, Nalar Relegius: Memahami Hakekat Tuhan, Alam dan Manusia, (Jakarta: Erlannga, 2007), h. 102. 21Murtadha Muthahhari, Man and Universe, diterjemahkan oleh Ilys Hasan dengan judul, Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagad Raya, (Cet. V; Jakarta: Lentara, 2008), h. 1 43 untuk mencapai kebahagian sebagai tujuan puncak dari etika, karena tak seorang pun yang tidak mau menggapai kebahagiaan dan bahwa etika adalah ilmu yang menunjukkan jalan kebahagiaan.22 Bagaimanakah etika bisa membawa kebahagiaan, padahal etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah? Etika ingin agar manusia menjadi baik, karena hanya dengan menjadi baik maka seseorang akan menjadi bahagia. Alasannya adalah bahwa orang yang baik adalah orang yang sehat mentalnya dan orang yang sehat mentalnya akan mampu mengecap berbagai macam kebahagiaan rohani, sebagaimana orang yang sehat fisiknya bisa mengecap segala macam kesenangan jasmaninya. Misalnya ketika seseorang terkena penyakit flu dan sejenisnya, kita terkadang mengalami “mati rasa” ketikatidak bisa membedakan rasa manis, asin atau pahit. Ini terjadi ketika fisisk kita sakit, namun jika fisik kita sehat, kita bukan saja mampu membedakan aneka rasa, tapi juga dapat mengenali perbedaan dalam tingkatan rasa, seperti kemanisan, kurang manis atau bahkan tidak manis sama sekali.23 Demikian pula dengan seseorang yang terkena penyakit jiwa, misalnya ketika ia mengidap penyakit iri (dengki). Dia akan senantiasa gelisah dan resah dan tidak bisa tenang dikarenakan penyakitnya tersebut telah membuat mentalya sedemikian sakit sehinggan ia tidak lagi mampu untuk menikmati kebahagiaan yang dianugrahkan Tuhan kapadanya.24 Islam juga sangat menekankan pentingnya akhlaj terhadap orang tua (kedua ibu dan bapak) sebagai orang tua yang mengandung, melahirkan dan membesarkan. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam QS. Luqman (31):14-15: وإن ﺟﺎﻫﺪاك ﻋﻠﻲ أن.ووﺻﻴﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ ﲪﻠﺘﻪ أﻣﻪ وﻫﻨﺎ ﻋﻠﻲ وﻫﻦ وﻓﺼﺎﻟﻪ ﰲ ﻋﺎﻣﲔ أن اﺷﻜﺮﱄ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻚ إﱄ اﳌﺼﲑ ﺗﺸﺮك ﰊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻼ ﺗﻄﻌﻬﻤﺎ وﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺎ واﺗﺒﻊ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ أﻧﺎب إﱄ ﰒ إﱄ ﻣﺮﺟﻌﻜﻢ ﻓﺄﻧﺒﺌﻜﻢ ﲟﺎ .ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن Terjemahnya: ‘Dan kamu perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua ibu-bapakmu, hanya kepada-Kulah kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan-Ku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.’25 22Murtadha Muthahhari, Falsafe Akhlaq, diterjemahkkan oleh Faruq bin Dhiya’ dengan judul, Falsafah Akhlak: Kritik Atas Konsep Moralitas Barat, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 198. 23Mulyadhi Kartanegara, Nalar Relegius......, op. cit., h. 117-118. 24Mulyadhi Kartanegara, Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam, (Cet. II; Bandung: Mizan, 2005), h. 69. Agama RI., op. cit., h. 654-655. 25Departemen 44 Ayat di atas mengisyaratkan pentingnya akhlak terhadap orang tua, sebab ayat di atas memerintahkan manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Merekalah yang mengandung dengan susah payah, lemah dan begitu berat.26 Berbuat baik sebagai suatu sikap akhlak dapat diwujudkan dengan cara memeliharanya,27 dalam arti memberikan perhatian sebagai wujud syukur terhadap keduanya. Sebab Allah memerintahkanmanusia untuk berbuat baik kepada orang tua, baik ketika mereka masih kuat, apalagi jika umur mereka sudah tua. Tidak diperkenangkan seorang anak membentak atau berkata-kata kasar terhadap keduanya.28 Menurut Hasan Khan, perkataan ( )أن اﺷﻜﺮﱄdiikuti dengan perkataan ( )وﻟﻮاﻟﺪﻳﻚmenunjukkan bahwa hak-hak orang tua untuk dihormati dan disyukuri oleh anaknya dan merupakan hak yang paling besar wajib diberikan kepada mereka.29 Adalah wajar dan suatu kewajiban jika manusia diperintahkan berbakti kepada orang tua, sebab orang tua mengandungnya di dalam perut yang setiap hari bertambah besar dan berat, kondisinya menjadi lemah dan sulit. Sufyan pernah berkata, ‘Uyaynah, bahwa siapa yang melakukan (mendirikan) shalat lima waktu, maka ia bersyukur pada Allah dan siapa yang mendoakan keduanya ketika shalat lima waktu, maka ia bersyukur kepada orang tua.30 Dengan demikian, berbuat baik kepada orang tua sebagai suatu akhlak, tidak saja dalam bentuk pelayanan fisik (perbuatan) atau perkataan, tetapi juga dalam bentuk doa kapada Allah agar mereka diberi rahmat. Ada satu hal yang perlu juga direnungkan bahwa keberadaan manusia di dunia ini justru karena orang tua. Orang tua pula yang memberikan pendidikan.31 Mereka juga membesarkan dengan air susu, hingga dua tahun lamanya. Betapa penting berbuat baik kepada orang tua, sampai-sampai Allah meletakkan posisi ini setelah firmanNya tentang larangan menyekutukan Allah (perintah bertauhid). Dalam konteks ini al-Nisaburi mengatakan dalam tafsirnya, bahwa berbuat baik kepada orang tua itu disebutkan setelah bertauhid dan menyembah Allah, dilihat dari berbagai segi yaitu: 1) Orang tua telah menjadi sebab kehadiran anak dan telah mendidiknya, sehingga tidak ada pemberian yang lebih baik daripada pemberian mereka (tentunya setelah pemberian Allah). 2) Pemberian keduanya terhadap anak, seperti pemberian Allah terhadap makhluk-Nya yang tidak mengharapkan pujian dan balasan. 26Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Tabariy, Tafsir al-Tabariy, jilid VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M/1398 H), h. 44. 27al-Alusiy 28QS. al-Isra’ (17):23-24. 29Sadiq 30Ibid. al-Bagdadiy, op. cit., h. 129. Hasan Khan, op. cit., h. 283. 31Ahmad Mustafa al-Maragiy, Tafsir al-Maragiy, juz XIX (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 83. 45 3) Allah swt. tidak pernah jemu memberikan nikmat kepada makhluk-Nya meskipun mereka (sebagiannya) melakukan dosa besar. Demikian pula orang mereka tetap sayang kepada anaknya, meskipun anak itu nakal. 4) Tidak ada kesempurnaan dalam bentuk apapun yang dimiliki seorang anak, kecuali orang tua selalu mencari dan menginginkannya untuk kepentingan anaknya dan mereka tidak pernah berhenti memperjuangkannya. Puncak kebaikan mereka adalah mereka tidak pernah hasud atau iri dan dengki jika anaknya lebih baik dari mereka.32 Dan hal akhlak terhadap orang tua ini, Rasul Allah swt. Telah bersabda: . اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻲ وﻗﺘﻬﺎ: ﻗﺎل ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل. ان رﺟﻼ ﻗﺎل ﻻﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أي اﻟﻌﻤﻞ اﻓﻀﻞ... 33 ... ﻗﺎل اﳉﻬﺎد ﰱ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ. ﻗﺎل وﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻗﻠﺖ وﻣﺎذا ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ،ﻗﻠﺖ وﻣﺎذا ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ Terjemahnya: ‘… Seseorang bertanya kepada Ibn Mas’ud: Amal mana yang paling utama. Ia lalu berkata: Aku telah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal itu. Rasulullah menjawab, mendirikan shalat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian perbuatan apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbuat baik kepada ibu-bapak. Aku bertanya lagi. Kemudian apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab: berjuang di jalan Allah.34 Dari hadis tersebut dapat dimengerti bahwa kedudukan shalat wajib berada di atas kedudukan berbuat baik terhadap orang tua, dan kedudukan berbuat baik terhadap orang tua berada di atas kedudukan jihad. Apa yang disampaikan Rasulullah itu sangat tepat dan sesuai dengan firman Allah swt. berkenaan dengan perintah berbuat baik kepada mereka. Ayat-ayat tersebut selalu didahului dengan perintah untuk beribadat kepada Allah, kemudian diiringi dengan perintah berbuat baik kepada orang tua.35 Berbuat baik kepada orang tua lebih utama daripada berjihad. Hal ini dijelaskan oleh Nabi dalam sabdanya. . ﻗﺎل ﻧﻌﻢ، أﺣﻲ واﻟﺪك: ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل ﺟﺎء رﺟﻞ اﱄ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺴﺘﺄذﻧﻪ ﰲ اﳉﻬﺎد ﻓﻘﺎل... 36 . ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻓﺠﺎﻫﺪ:ﻗﺎل Terjemahnya: ‘… Abd Allah ibn ‘Amr ibn Ash r.a., meriwayatkan, bahwa telah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. memohon izin untuk berjuang. Rasulullah saw. bersabda, “Masih adakah kedua ibu-bapakmu?”, 32Disadur dari Nizam al-Din al-Hasan Muhammad al-Qummiy al-Naisaburiy, Tafsir Gara’ib al-Qur’an wa Gara’ib alFurqan, Hamisy di dalam al-Tabariy, Tafsir al-Tabariy, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M/1398 H), h. 323. 33Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurat al-Turmuziy, Sunan al-Turmuziy, jilid I (Indonesia: Maktabat Dahlan, t. th.), h. 112. 34Terjemahan 35QS. penulis. al-Baqarah (2):36. al-Nisa’ (4):36 dan QS. al-Isra’ (17):23. 36Muslim, op. cit., juz II, h. 418. 46 orang itu menjawab, “Mereka masih hidup”. Rasulullah saw. bersabda, “Kalau demikian berjuanglah engkau dalam berbuat baik kepada ibu bapakmu.”37 Al-Khattabiy menjelaskan bahwa jika seseorang secara ikut berjuang di jalan Allah, maka hal itu hendaknya seizin orang tuanya. Tetapi jika keduanya kafir tidak diharuskan meminta izin.38 Ibn Hajar al-Asqalaniy juga menyatakan bahwa sebagian besar ulama berpendapat bahwa seseorang dilarang ikut berjuang di jalan Allah kecuali keduanya, atau salah satu di antaranya memberikan izin, dan orang tuanya tetap beragama Islam. Berbuat baik kepada orang tua hukumnya wajib (fard ‘ain), sedangkan berjuang hukumnya fard kifayah. Tetapi jika pada suatu saat berjuang itu menjadi wajib hukumnya (fard ‘ain), maka tidak ada keharusan lagi meminta izin kepada orang tua sebab keadaan darurat.39 Lebih jauh al-‘Asqalaniy menyatakan bahwa kedudukan berbuat baik kepada orang tua berada di atas kewajiban berjihad di jalan Allah. Apalagi dalam hal bepergian biasa, maka wajib memohon izin kepada keduanya.40 Beberapa hadis di atas telah menjelaskan bahwa akhlak terhadap orang tua sangat penting, sebab terlalu besar dan banyak jasa orang tua terhadap anak. Hasan Ayyub menyatakan: Tak ada seorang manusia pun yang mampu menghitung dan mengira-ngira mengenai hak-hak ayah dan ibu atas anaknya. Seandainya anak-anak dapat menghitung apa yang dirasakan dan dialami orang tuanya, mereka pasti dapat menghitung dan menentukan apa-apa yang menjadi hak-hak mereka, yang berupa perbuatan baik dan pemuliaannya. Akan tetapi, menghitung dan menentukan serta memperkirakan jasa orang tua terhadap anaknya merupakan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan, terutama jasa ibunya ketika mengandung, melahirkan, menyusui, menjaga dan memeliharanya. Hanya ibu dengan keibuannya dan tak seorang pun yang tidak memerlukannya.41 Jika akhlak yang paling puncak terhadap Allah adalah tidak menyekutukan-Nya, maka puncak akhlak kepada ibu bapak adalah tidak mendurhakai mereka. Perintah bersyukur kepada orang tua datang setelah perintah bersyukur kepada Allah, sementara perintah untuk tidak durhaka kepada ibu bapak datang setelah perintah untuk tidak berbuat syirik kepada Allah. Hal ini dijelaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya: 37Terjemahan penulis. 38Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-‘Azimabadiy, ‘Aun al-Ma’bud, juz VII (t. tp.: al-Maktabat al-Salafiyyah, 1979), h. 203. al-Din Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalaniy, Fath al-Baribi Syarh Sahih al-Bukhariy, juz VI (Beirut: Dar alMa’rifah, t.th.), h. 140-141. Lihat juga Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud ibn Ahmad al-‘Ainiy, ‘Umdat al-Qari Syarh Sahih alBukhariy, juz XIV (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 250. 39Syihab loc. cit. Ayyub, al-Suluk al-Ijtima’iy fi al-Islam, alih bahasa Tarmana Ahmad Qasim dkk., dengan judul Etika Islam (Bandung: Trigenda Karya, 1994), h. 320. 40al-‘Asqalaniy, 41Hasan 47 ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻛﱪ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻻﺷﺮاك ﺑﺎﷲ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﰉ ﺑﻜﺮة ﻋﻦ اﺑﻴﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل... 42 . ﻓﻤﺎ زال ﻳﻜﺮرﻫﺎ ﺣﱵ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻴﺘﻪ ﺳﻜﺖ.وﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ﺛﻼث او ﻗﻮل اﻟﺰور Terjemahnya: ‘… diriwatkan dari Abi Bakrah dari ayahnya ia berkata: Nabi saw. bersabda: Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua, serta bersumpah palsu [yang diulangi mengucapkannya] tiga kali; atau beliau mengatakan berkata bohong. Beliau terus mengulanginya, sampai kami berkata: semoga beliau mau diam.’43 Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. menempatkan aspek durhaka kepada ayah dan ibu pada urutan kedua setelah mempersekutukan Allah. Hal itu menunjukkan besarnya dosa durhaka kepada orang tua. 1. Akhlak terhadap Sesama Manusia Firman Allah swt. Dalam QS. Luqman (31):18-19: وﻻ ﺗﺼﻌﺮ ﺧﺪك ﻟﻠﻨﺎس وﻻ ﲤﺶ ﰱ اﻷرض ﻣﺮﺣﺎ إن اﷲ ﻻ ﳛﺐ ﻛﻞ ﳐﺘﺎل ﻓﺨﻮر واﻗﺼﺪ ﰱ ﻣﺸﻴﻚ واﻏﻀﺾ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻚ إن أﻧﻜﺮ اﻷﺻﻮات ﻟﺼﻮت اﳊﻤﲑ Ayat di atas merupakan dasar moral bagi pergaulan sesama manusia, bagaimana seharusnya manusia berkomunikasi dan bersikap satu dengan yang lainnya. Tidak berakhlak terhadap sesama seperti sombong, angkuh, menyakiti orang lain, merupakan suatu sikap yang tidak disenangi oleh Allah. Menurut al-Syanqiti, pernyataan وﻻ ﺗﺼﻌﺮ ﺧﺪكmengindikasikan adanya larangan bersikap sombong terhadap manusia. Hal ini sesuai pula dengan QS. al-A’raf (7):13, yang menunjukkan perintah menghilangkan sifat sombong (tidak berakhlak) sesama manusia, karena akibat sombong (tidak berakhlak) itu akan menimbulkan kejahatan.44 Bersifat sombong saja telah dilarang Allah, apalagi melakukan hal-hal yang merusak orang lain, seperti membunuh, merampok dan menyakiti hati orang lain dengan menceritakan aib seseorang di belakangnya, tidak perduli aib itu benar atau salah. Allah telah mengatur sedemikian rupa, bagaimana seharusnya manusia memiliki akhlak terhadap sesamanya. Akhlak terhadap manusia itu mencakup perbuatan dan perkataan. Dalam hal perkataan, dijelaskan pula di dalam QS. Luqman (31):19, bahwa manusia hendaknya melunakkan suara dalam arti baik dan indah dalam bertutur, sebab perkataan yang jelek itu sama dengan suara keledai. 42al-Bukhariy, op. cit., juz IV, h. 2765; lihat juga Imam Muslim, Sahih Muslim, juz I (Bandung: Dahlan, t. th.), h. 51. 43Terjemahan penulis. al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jakni al-Syanqiti, Adwa’ al-Bayan fi Indah al-Qur’an bi al-Qur’an, juz VII (t. tp.: Sihab al-Samawi al-Malakiy al-Amin Abd al-Azis, 1983 M/1403 H), h. 497. 44Muhammad 48 al-Tabataba’iy dalam menafsirkan ayat 19 ini, mengutip pernyataan Abu ‘Abd Allah yang menyatakan bahwa أﻧﻜﺮ اﻷﺻﻮاتitu adalah seperti bersin yang keras dan sangat jelek.45 Berkata dan bertutur yang baik, nilainya lebih baik daripada bersedekah yang diiringi dengan sesuatu menyakitkan.46 Karena itu Allah mengatur bagaimana jika manusia bertemu dengan sesamanya. Allah menyatakan bahwa jika manusia diberi salam (dihormati) oleh orang lain, maka hendaknya ia menjawab salam (penghormatan) itu dengan penghormatan yang serupa atau lebih baik.47 Jika ada orang lain yang diberi gelar gentlemen, yakni orang yang memiliki harga diri, berkata benar dan bersikap lemah lembut, maka seorang muslim yang mengikuti perintah Allah (akhlak al-Qur’an), tidak hanya pantas bergelar demikian, tapi juga mendapat gelar al-muhsin.48 Dengan demikian, berakhlak terhadap sesama manusia akan menciptakan suasana kedamaian, saling harga menghargai, sehingga terwujud suatu suasana yang kondusif dan bersahabat di antara sesama. C. Etika Terhadap Lingkungan (alam) Ketika berbicara tentang alam, kebanyakan dari kita yang hidup di abad modern ini cenderung melihatnya dari aspek fisiknya saja, mengabaikan apa yang bagi para sufi merupakan aspek-aspek esensialnya: simbolis dan spiritual. Tentu tidak diragukan lagi bahwa pandangan sekuler tentang alam telah menghasilkan kemajuan-kemajuan ilmiah dan teknologis yang dan membuat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti bagi kemakmuran manusia. Namun, kini kita menyadari semua bahwa betapa pandangan tersebut telah menciptakan berbagai masalah dalam hubungan kita dengan alam dan gangguan-gangguan atas tatanan alam yang mengarah pada apa yang kita sebut sebagai “krisis ekologis”. Manusia modern semakin teralienasi dari alam, setelah mereka menciptakan jurangjurang yang tidak terjembatani antara keduanya: manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek. Dengan memandang alam semata-semata sebagai objek, nafsu mereka (manusia modern) melalui sains dan teknologinya akan mendominasi alam dan mengeksploitasinya secara agak kasar untuk memenuhi tuntutan mereka yang terus menerus meningkat. Akibatnya alam sekarang dalam proses kehilangan kemampuannya untuk memberikan sumber dayanya yang dermawan dan kaya untuk mempertahankan keseimbangan ekologisnya. Bencana alam seperti banjir, erosi, longsor, efek rumah kaca, pemanasan global, polusi udara dan air dan kebakaran hutan yang telah memusnahkan jutaan tumbuhan dan hewan-hewan yang tidak ternilai harganya –beserta habitat-habitat tempat tinggal mereka– hanyalah beberapa contoh dari betapa banyaknya kerusakan yang telah manusia lakukan terhadap alam hingga merendahkan kualitas dan nilai-nilai kemanusiaan mereka sendiri. Secara simbolis, semua itu menunjukkan betapa alam telah “marah” kepada kita atas immoral kita atasnya. 49 45Al-Tabataba’iy, 46QS. 47QS. 48M. op.cit., jilid XVI, h. 221. al-Baqarah (2):263. al-Nisa’ (4):86. Quraish Shihab, Wawasan, h. 269. 49Mulyadhi Kartanegara, Mengislamkan Nalar: Sebuah Respon Terhadap Modernitas, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 156. 49 Masalah lingkungan hidup menjadi masalah etika karena manusia seringkali “lupa” dan kehilangan orientasi dalam memperlakukan alam. Karena “lupa” dan kehilangan orientasi itulah, manusia lantas memperlakukan alam secara tidak bertanggungjawab. Dalam keadaan seperti itu, mereka juga tidak lagi menjadi kritis. Oleh karena itulah pendekatan etis dalam menyikapi masalah lingkungan hidup sungguh sangat diperlukan. Pendekatan tersebut pertama-tama dimaksudkan untuk menentukan sikap, tindakan dan perspektif etis serta manejemen perawatan lingkungan hidup dan seluruh anggota ekosistem di dalamnya dengan tepat. Maka, sudah sewajarnyalah jika saat ini dikembangkan etika lingkungan hidup dengan opsi “ramah” terhadap lingkungan hidup. Teori etika lingkungan hidup sendiri secara singkat dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk membangun dasar-dasar rasional bagi sebuah sistem prinsip-prinsip moral yang dapat dipakai sebagai panduan bagi upaya manusia untuk memperlakukan ekosistem alam dan lingkungan sekitarnya. Paling tidak pendekatan etika lingkungan hidup dapat dikategorikan dalam dua tipe yaitu tipe pendekatan human-centered (berpusat pada manusia atau antroposentris) dan tipe pendekatan life-centered (berpusat pada kehidupan atau biosentris).50 Teori etika human-centered mendukung kewajiban moral manusia untuk menghargai alam karena didasarkan atas kewajiban untuk menghargai sesama sebagai manusia. Sedangkan teori etika life-centered adalah teori etika yang berpendapat bahwa kewajiban manusia terhadap alam tidak berasal dari kewajiban yang dimiliki terhadap manusia. Dengan kata lain, etika lingkungan hidup bukanlah subdivisi dari etika human-centered.51 Pada umumnya, paling tidak semenjak zaman modern, orang lebih suka menggunakan pendekatan etika human-centered dalam memperlakukan lingkungan hidup. Melalui pendekatan etika ini, terjadilah ketidakseimbangan relasi antara manusia dan lingkungan hidup. Dalam kegiatan praktis, alam kemudian dijadikan “obyek” yang dapat dieksploitasi sedemikian rupa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan manusia. Sangat disayangkan bahwa pendekatan etika tersebut tidak diimbangi dengan usaha-usaha yang memadai untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup dan makhluk-makhluk lain yang ada di dalamnya. Dengan latar belakang seperti itulah kerusakan lingkungan hidup terus-menerus terjadi hingga saat ini. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pendekatan etika human-centered tersebut tetap masih relevan diterapkan untuk jaman ini? Menghadapi realitas kerusakan lingkungan hidup yang terus terjadi, rasanya pendekatan etika human-centered tidak lagi memadai untuk terus dipraktikkan. Artinya, kita perlu menentukan pendekatan etis lain yang lebih sesuai dan lebih “ramah” terhadap lingkungan hidup. Jenis pendekatan etika yang kiranya memungkinkan adalah pendekatan etika life-centered yang tadi sudah kita sebutkan. Pendekatan etika ini dianggap lebih memadai sebab dalam praksisnya tidak menjadikan lingkungan hidup dan makhluk-makhluk yang terdapat di dalamnya sebagai obyek yang begitu saja dapat dieksploitasi. Sebaliknya, pendekatan etika ini justru sungguh menghargai mereka sebagai “subyek” yang memiliki nilai pada dirinya. Mereka memiliki nilai tersendiri sebagai anggota komunitas kehidupan di bumi. Nilai mereka tidak ditentukan dari sejauh mana mereka memiliki kegunaan bagi manusia. Mereka memiliki nilai 50Borrong, 51 Robert, Etika Bumi Baru, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1999), h. 34. William Chang, Moral Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 20. 50 kebaikan tersendiri seperti manusia juga memilikinya, oleh karena itu mereka juga layak diperlakukan dengan respect seperti kita melakukanya terhadap manusia.52 Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa.53 Dalam bahasa Arab lingkungan disebut al-muhit yang berarti mengelilingi.54 Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris adalah environment yaitu hal atau kondisi sekeliling khususnya, yang mempengaruhi eksistensi seseorang atau sesuatu,55 atau keadaan yang dikelilingi oleh kondisi sekitar atau semua kondisi yang mempengaruhi perkembangan suatu organisme atau sekelompok organisme. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan serta makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Di dalam QS. Luqman (31):18, dijelaskan bahwa berbuat kerusakan di muka bumi ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang Allah. Karena itu, Luqman al-Hakim memerintahkan anaknya untuk tidak berbuat demikian. al-Zamakhsyariy dalam menafsirkan ayat tersebut di atas menyatakan bahwa tujuan berjalan di muka bumi ini jangan dijadikan tujuan untuk berbuat kebatilan dan kejahatan, sebagaimana kebanyakan orang melakukan demikian, bukan untuk kepentingan agama atau duniawi.56 Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya QS. al-Anfal (8):47: .وﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ ﺑﻄﺮ ورﺋﺎء اﻟﻨﺎس وﻳﺼﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ واﷲ ﲟﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﳏﻴﻂ Terjemahnya: ‘Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. (Dan ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan.’57 Berjalan di bumi (hidup di dunia) dengan maksud berbuat kebatilan dan kejahatan, berarti telah merusak lingkungan, dan ini sama halnya tidak memiliki akhlak terhadap lingkungan. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan al-Qur’an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan serta bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.58 Seseorang manusia yang bersifat sombong, angkuh dan bersifat merusak, sebagaimana dijelaskan dalam surah Luqman (31):18, tentu tidak bisa mengolah alam sebagaimana mestinya, sebab akhlak terhadap alam dan lingkungan tidak dimiliki. 52Borrong, Robert, Etika Bumi….. op. cit., h. 35. 53Ibid., h. 270. 54Ilyas Anthon Ilyas, Qamus Ilyas al-‘Asriy (Mesir: Syarikah Dar Ilyas al-‘Asriyyah, 1979), h. 249. 55Webster’s Encyclopedie Unabridge Dictionary of The English Language (New York: Porland House, 1989), h, 477. al-Qasim Jar Allah Mahmud ibn ‘Umar al-Zamakhsyariy, al-Kasysyaf ‘an Haqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil, juz III (Mesir: Syirkat Maktabat Mustafa al-Babiy al-Halabiy, t. th.), h. 234. 56Abu 57Departemen 58M. Agama RI., op. cit., h. 269. Quraish Shihab, Wawasan, h. 269. 51 Binatang, tumbuhan dan benda materi lainnya, diciptakan oleh Allah swt. dan menjadi milik-Nya, serta semuanya memiliki ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan itu mengantarkan seseorang untuk menyadari bahwa semua itu, adalah “umat” Allah yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. 59 Lingkungan habitat, seperti burung, binatang melata, tumbuhan dan lain-lain, sama halnya juga dengan manusia, sehingga semuanya tidak boleh diperlakukan secara aniaya.60 Kesadaran bahwa semua yang ada di alam ini adalah milik Allah memunculkan suatu sikap akhlak yang terpuji terhadap lingkungan, sehingga tidak ada niat untuk berbuat kerusakan di alam ini. Al-Qurtubiy memberikan penafsiran terhadap ayat ... وﻻ ﲤﺶ ﰲ اﻷرض ﻣﺮﺣﺎ... dengan menyatakan bahwa, ayat ini mengandung makna segala kegiatan ()اﻟﻨﺸﺎط.61 Jadi apa saja kegiatan yang dilakukan, bila sifatnya merusak, maka kegiatan itu termasuk akhlak yang tidak baik. Pendidikan akhlak terhadap lingkungan ini tentu sangat penting ditanamkan kepada anak, agar memiliki kesadaran terhadap pemeliharaan lingkungan, sebab jika tidak demikian, maka kerusakan alam akibat manusia akan terjadi di mana-mana. Al-Qur’an sangat menekankan pentingnya pemeliharaan terhadap alam. Dalam situasi apapun lingkungan harus dijaga. Jangankan dalam masa damai, dalam saat peperangan pun terdapat petunjuk al-Qur’an yang melarang melakukan penganiayaan, baik terhadap manusia, binatang maupun pepohonan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Firman Allah dalam QS. al-Hasyr (59):5: .ﻣﺎﻗﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﻨﺔ أو ﺗﺮﻛﺘﻤﻮﻫﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺻﻮﳍﺎ ﻓﺒﺈذن اﷲ وﻟﻴﺨﺰي اﻟﻔﺎﺳﻘﲔ Terjemahnya: ‘Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma atau kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah atas izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang fasik.’62 Ayat di atas mengajarkan bagaimana seharusnya manusia berakhlak terhadap lingkungan, sebab Allah telah memperuntukkan semua yang ada di bumi dan di langit untuk manusia. Orang yang berakhlak baik terhadap apa saja atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan masuk ke dalam surga, sebagaimana hadis Nabi: . ﺗﻘﻮي اﷲ وﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ: ﻗﺎل،وﺳﻠﻢ ﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎس اﳉﻨﺔ ﺳﺌﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻋﻦ اﰉ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل.. . 63 . اﻟﻔﻢ واﻟﻔﺮج: ﻗﺎل،وﺳﺌﻞ ﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎس اﻟﻨﺎر Terjemahnya: ‘Dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi ditanya tentang penyebab kebanyakan orang masuk surga, Nabi menjawab, “Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik”. Lalu Nabi ditanya tentang penyebab orang masuk neraka, Nabi menjawab. “Mulut dan kemaluan.”64 59Ibid. 60QS. al-An’am (6):38. op. cit., h. 71. Agama RI., op. cit., h. 916. 61al-Qurtubiy, 62Departemen 63al-Turmuziy, 64Terjemahan op .cit., juz III, h. 245. penulis. 52 Itulah beberapa materi dan sasaran akhlak yang telah diajarkan Luqman al-Hakim terhadap anaknya, sebagaimana digambarkan oleh Allah melalui firman-Nya. Di samping itu, beliau juga banyak memberikan nasehatnasehat kepada anaknya sebagai pembentukan akhlak.65 Beberapa nasehat beliau itu adalah sebagai berikut:66 (1) Ia menyatakan bahwa, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam, banyak manusia yang karam ke dalamnya. Bila ingin selamat, layarilah lautan itu dengan sampan takwa dan isinya adalah iman, layarnya adalah tawakkal. (2) Orang yang senantiasa menyediakan dirinya untuk menerima nasehat, maka dirinya akan mendapat penjagaan dari Allah. Orang yang insaf dan sadar setelah menerima nasehat orang lain, akan menerima kemuliaan dari Allah. (3) Ia mengingatkan bahwa, orang yang merasa dirinya hina dan rendah di dalam beribadah dan taat kepada Allah, dia akan lebih dekat kepada Allah dan selalu berusaha menghindarkan maksiat. (4) Ia mendidik anaknya agar berbuat baik kepada orang tua dan ia menyatakan apabila orang tua marah (karena kesalahan anak), maka marahnya orang tua itu bagaikan pupuk bagi tanam-tanaman. (5) Ia juga memberi nasehat agar anaknya menjauhi hutang, karena sesungguhnya hal itu bisa membuat hina di waktu siang dan gelisah di waktu malam. (6) Ia menyuruh anaknya agar selalu berharap kepada Allah tentang sesuatu yang menyebabkan tidak mendurhakai Allah. Bertakwa kepada Allah dengan senbenarnya, sebab takwa melepaskan diri dari sifat keputus asaan. (7) Ia juga meminta anaknya agar jangan berdusta, sebab seorang pendusta akan lekas hilang air mukanya karena tidak dipercayai orang, dan orang yang bejat akhlaknya senantiasa banyak melamunkan hal-hal yang tidak benar. Ia mengibaratkan memindahkan batu yang besar lebih mudah daripada memberi pengertian kepada orang yang tidak mau mengerti. (8) Ia juga melarang anaknya menjadi pendusta, sebab berdusta itu mengakibatkan bahaya yang besar. (9) Ia meminta anaknyaagar bersikap hati-hati dan selektif jangan menelan begitu saja karena manisnya barang dan jangan langsung memuntahkan karena pahitnya. Karena yang manis itu belum tentu baik dan yang pahit itu belum tentu menimbulkan kegetiran. (10) Ia menasehati anaknya agar selalu mengamalkan ilmu sebab, bukan suatu kebaikan namanya bila selalu mencari ilmu tapi tidak pernah diamalkan. Hal itu tidak ubahnya seperti orang yang mencari kayu bakar, setelah banyak terkumpul, ia tidak kuat memikulnya, padahal ia masih mau menambahnya. (11) Ia menyuruh anaknya, untuk memperhalus tutur kata dan budi bahasa, karena orang akan menyenangi melebihi sukanya orang terhadap orang lain yang pernah memberikan barang berharga. (12) Ia meminta anaknya untuk bersikap rendah hati, tidak menerima pujian atau sanjungan orang lain, karena motivasi ria itu menimbulkan cela. (13) Ia menganjurkan anaknya agar berkata-kata baik, tidak mengeluarkan kata-kata kotor serta kasar, karena lebih selamat jika berdiam diri. (14) Ia mendidik anaknya agar berkata dan tertawa seperlunya sesuai dengan kondisi, dia juga menyuruh anaknya untuk tidak menyia-nyiakan harta, ada gunanya bagimu dan jangan menyia-nyiakan harta. (15) Ia berkata bahwa: barang siapa yang bersifat penyayang, tentu dia akan akan disayang, siapa yang pendiam (menjaga kata-kata kotor) dia akan selamat dan siapa yang tidak bisa menjaga lidah, maka dia akan menyesal. Nasehat yang terkandung di dalam surah Luqman, maupun nasehat Luqman al-Hakim seperti diuraikan oleh ulama, memiliki ruang lingkup yang dimensional, luas dan amat dalam terutama berkenaan dengan akhlak, baik dalam hal ubidiyah, maupun mu’amalah. 65Nasehat Luqman ada yang jelas tertera di dalam al-Qur’an sebagaimana di dalam surah Luqman, ada pula beberapa nasehat Luqman yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi dan para mufassir. 66Masih banyak nasehat Luqman al-Hakim, berupa pendidikan akhlak terhadap anaknya. Lebih lanjut lihat al-Alusy alBagdadiy, op. cit., h. 126-127; Ibn Kasir, op. cit., h. 540; al-Suyutiy, op. cit., h. 509-523; dan al-Qurtubiy, op .cit., h. 66-67, di mana ia mencantumkan nama para ulama dan sahabat yang menguraikan nasehat Luqman al-Hakim. 53 Dari beberapa uraian di atas disimpulkan bahwa Tuhan adalah pemberi wujud dan kesempurnaan kita serta segala kemungkinan yang kita miliki, maka bersyukur kepada-Nya menurut hukum moral adalah sebuah keharusan. Keharusan mensyukuri Tuhan hanya mungkin dilakukan hanya dengan mengenal Tuhan. Selama kita tidak mengenal Tuhan, maka ketika itu pula kita tidak akan pernah bersyukur kepada-Nya. Dengan demikian, keniscayaan mengenal Tuhan itu dilandasi oleh hukum moral yang menegaskan bahwa “bersyukur kepada pemberi adalah sebuah keharusan. Manusia tentu saja merupakan hasil dari evolusi terkhir dan karena itu, sebagai makhluk, manusia memiliki karakter atau sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan dan makhluk-makhluk yang lebih rendah dari manusia. Sekalipun hewan dikatakan memiliki kesadaran dan nafsu, tapi kesadaran hewan tentang dunia fisik hanyalah kesadaran indrawi, tidak bisa menjangkau ke kedalaman dan antarhubungan batin benda-benda. Kesadaran indrawi hanyalah pada objek-objek yang bersifat individual dan partikular dan tidak bisa menjangkau yang bersifat universal dan general. Sifat kebebasan yang dimiliki manusia sehingga ia menjadi makhluk moral yang bisa diberi sifat baik dan buruk, tergantung perbuatan mana yang dipilihnya secara sadar. Sebagai makhluk moral senantiasa berinteraksi untuk mencapai kebahagian sebagai tujuan puncak dari etika, karena tak seorang pun yang tidak mau menggapai kebahagiaan dan bahwa etika adalah ilmu yang menunjukkan jalan kebahagiaan. Ketika berbicara tentang alam, kebanyakan dari kita yang hidup di abad modern ini cenderung melihatnya dari aspek fisiknya saja, mengabaikan apa yang bagi para sufi merupakan aspek-aspek esensialnya: simbolis dan spiritual. Tentu tidak diragukan lagi bahwa pandangan sekuler tentang alam telah menghasilkan kemajuan-kemajuan ilmiah dan teknologis yang dan membuat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti bagi kemakmuran manusia. Namun, kini kita menyadari semua bahwa betapa pandangan tersebut telah menciptakan berbagai masalah dalam hubungan kita dengan alam dan gangguan-gangguan atas tatanan alam yang mengarah pada apa yang kita sebut sebagai “krisis ekologis”. Manusia modern semakin teralienasi dari alam, setelah mereka menciptakan jurang-jurang yang tidak terjembatani antara keduanya: manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek. 54 BAB VII KRITIK ISLAM TERHADAP ETIKA BARAT Islam dengan segala dimensinya, memiliki ciri khas yang sekaligus menjadi pembeda dengan yang lain. Basis nilainya yang didasarkan pada kerangka ke-Tauhid-an menjadi spirit utama dalam ruh pergerakannya, dan itu pula yang menjadi penyebab kenapa kemudian hingga kini islam sangat anti terhadap pemujaan-pemujaan semu (palsu) yang mengarah pada alienasi spiritualitas dan kehancuran moralitas (dekadensi moral). Islam dalam hal ini getol membangun propaganda kemanusiaan sejati, dan menjadikan para nabi sebagai teladan sejati, Alquran sebagai panduan hakiki, insan kamil adalah misi pasti. Kenyataan ini mengantarkan Islam terus mendapat tekanan dari berbagai pihak yang memiliki tujuan dan target yang berbeda (materialisme). Tapi sebagai pegangan suci, Islam memiliki nalar dan logikanya sendiri sehingga ia mampu membangun kritik terhadap berbagai hal yang dianggapa bisa membelokkan manusia dari tujuan sejatinya. Kita lihat misalnya bagaimana kompleksitas hidup yang tak satu pun luput dari pantauannya, sehingga kepekaan terhadap hal-hal yang bisa mengantar hidup manusia pada ketimpangan membuatnya pro aktif tampil untuk memberi countre hegemonik, termasuk dalam hal ini propaganda etika kehidupan yang ditawarkan dan dikemas oleh Barat. Maka dari itu, menarik kiranya untuk mengupas lebih jauh bagaimana kritik Islam terhadap konsep dan gagasan Etika Barat, yang tentunya melibatkan unsur word view dan ideologi sebagai bagian dari variabel terpenting, mengingat karena hal tersebut merupakan akar bagi lahirnya gagasan etis dan estetis serta berbagai perangkap sosial kultural lainnya. A. Konsepsi Etika Barat Satu hal yang penulis harus ketengahkan kaitannya dengan sub tema ini bahwa etika Barat yang dimaksudkan disini ialah yang terusung dari beberapa tokoh pemikir Barat yang cenderung pada epistemologi rasonalisme empiris yang berpandangan bahwa manusia hanya sebatas makhluk biologis yang tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lebih asasi (metafisis). Pandangan seperti ini merupakan akibat dari word view (pandangan dunia) materialisme yang menganggap bahwa alam ini tak lain dari entitas materi murni. Paradigma ini berakibat langsung pada konstruk gagasan etisnya hanya berpangkal pada asumsi-asumsi sosio-materialis ketimbang filosofis-metafisis. Itulah sebeabnya sehingga para pengusung gagasan etika seperti ini cenderung mengabaikan agama sebagai aspek penting dalam kehidupan, lihat saja misalnya asumsi para rasionalis Abad Pencerahan Eropa bahwa agama akan memperburuk atau membatasi ruang lingkup peribadi.1 Dilain sisi bahwa, jika sekiranya ada tokoh yang mengandaikan agama sebagai bagian penting dari gagasan etikanya, maka yang terbangun dari hal tersebut hanya sebatas dogma yang tidak memiliki akar argumentasi yang kuat. Maka dari itu, kaitannya dengan kedua hal tersebut, penulis bermaksud mengurai dua pandangan moralitas tokoh barat yang menurut hemat penulis mewakili kedua klan tersebut. 1 Nurcholis Madjid, dkk, Passing Over; Melintasi Batas Agama, (Cet. II; Jakarta : PT.SUN, 2001), h. 176. 55 1. Immanuel Kant dengan asumsi moralitasnya bahwa, tidak ada hal baik secara mutlak kecuali “kehendak baik”. Kehendak baik yang dimaksudkan disini ialah kehendak pada dirinya sendiri (an sich) dan tidak bergantung pada yang lain (harapan akan pamrih).2 Satu-satunya cara bagi manusia untuk mengantar perbuatannya menjadi etis ialah dengan menunaikan kewajiban, sebab dengan penunaian kewajiban tersebut manusia akan terbebas dari harapan akan pamrih. Lebih jelasnya hal ini kita lihat bagaimana Kant membedakan antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Tindakan yang sesuai dengan kewajiban adalah tindakan yang tidak berharga secara moral (legalitas), sedangkan yang kedua bernilai moral dan disebut moralitas. Titik penekanannya bahwa semakin sedikit harapan manusia akan pamrih untuk menunaikan kewajiban, maka semakin tinggi pula nilai moral tindakannya.3 Dari penjelasan tersebut, jelas kiranya bahwa ukuran moralitas bagi Kant ialah kewajiban (kepatuhan terhadap hukum universal). 2. Nietzche, yang justru menganggap moralitas sebagai hiroglif (tanda yang menyembunyikan rahasia kegelapan) dimana rahasia tersebut bisa dibuka dengan penafsiran genealogi. Jadi moralitas bagi Nietszche adalah bahasa isyarat dari emosi-emosi.4 Pada intinya, Nietszche membagi moralitas manusia ke dalam dua bahagian, yaitu moralitas tuan (herrenmoral) dan moralitas budak (herdenmoral). Moralitas tuan adalah ungkapan hormat dan penghargaan terhadap diri mereka sendiri, jadi baik dan buruknya sebuah tindakan bukan dilihat pada tindakan itu sendiri, melainkan pada pribadi yang melakukannya. Sementara moralitas budak adalah moralitas yang tunduk pada perintah, sebab bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri sama dengan penyangkalan terhadap kodratnya.5 Jadi pada intinya nilai moralitas budak adalah terletak pada kepatuhan atas tuannya dengan cara mengurung kemerdekaan individualnya, itulah sebabnya sehingga jenis moralitas ini bersifat reaktif, yakni bersumber dari ketakutan, meski demikian ia tetap hendak menguasi tuannya namun kenyataan berlakunya hanya pada dunia fiktif dengan menghakimi tuannya dengan stigma jahat. Penjelasan tersebut mengantar penulis untuk menarik kesimpulan sementara bahwa pada intinya terdapat kesamaan paradigma moralitas antara Kant dengan Nietszche. Bagi Kant bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewajiban adalah tindakan yang tidak bermoral karena masih mengharapkan pamrih sama dengan moralitas tuan ala Nietsche, dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban sama dengan moralitas budak ala Nietszche. B. Kritik Islam terhadap Etika Barat Islam pada intinya menjadikan setiap perbuatan dan tingkah laku sebagai sesuatu yang bersyarat, yakni tidak terlepas dari visi ketuahanan (keilahian), sebab hanya dengan seperti itulah perbuatan manusia dikatakan 2 F. Budi Hardiman, Filsafat Moderen; Dari Machiavelli sampai Nietzche, (Cet. II; Jakarta : IKAPI, 2007), h. 145. 3 Ibid., h. 146. 4 Ibid., h. 268. 5 Ibid., h. 269. 56 berniali. Berbeda dengan Immanuel Kant yang justru mengusung gagasan moralitas dengan kerangka kewajiban, yang dalam pandangan Islam bahwa hukum tersebut dimaksudkan agar perbuatan manusia bernilai, dan karenanya ia pun tidak bisa dipisahkan dengan motifnya selama hal tersebut dimaksudkan sebagai wujud pengabdian dan penyembahan sebagai konsekuensi logis dari eksistensinya sebagai makhluk yang menerima keistimewaan maujud dibandingakan dengan makhluk-makluk yang lain. Menurut Ali Maksum bahwa kegagalan Barat dan masyarakat moderen menempatkan agama pada posisi yang semestinya menyebabkan mereka kehilangan visi ke-Ilahian-nya.6 Dilain sisi Nasr menegaskan bahwa penyebab paling mendasar atas krisisi kemanusiaan yang terjadi bagi manusia moderen ialah penolakannya terhadap hakekat ruh dari kehidupan manusia sehingga mereka pun memandang alam sekelilingnya tidak lebih dari sekedar sumber daya yang harus dimanfaatkan dan dieskploitasi semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. 7 Pada hal sejatinya bahwa manusia adalah hamba-Nya yang harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya di muka bumi ini karena ia oleh Allah diposisikan sebagai Khalifah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, yakni membunuh Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Nietszche. Semangat yang sama dapat disimak dari pribadi al-Gazali yang mengusung gagasan etikanya dengan kerangka wahyu, stressingnya bahwa kebahagiaan adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Keutamaan-keutamaan merupakan pertolongan Tuhan yang niscaya sifatnya terhadap jiwa. Tidak ada keutamaan lain yang dapat dicapai tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan, al-Ghazali menegaskan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, usaha manusia sendiri dalam mencari keutamaan sia-sia, dan dapat membawa kepada sesuatu yang salah dan dosa.8 Pada posisi ini al-Gazali hendak menegaskan bagaimana sifat niscaya ketergantungan manusia kepada Tuhannya dalam setiap tindakan dan perbuatannya, sehingga ia tidak melakukan suatu perbuatan karena hal tersebut diwajibkan, atau meninggalkan suatu perbuatan karena adanya hukum haram dan kesia-siaan yang mengikatnya, melainkan kesemua tindakan harus ditundukkan dalam kepasrahan kepada Tuhan melalui ketaatan kepada hukum-hukum yang ditetapkan-Nya. Ali Syari’ati yang juga sebagai salah seroang pemikir muslim pun memberikan kritik yang sangat tajam kepada etika hidup Barat yang didasarkan pada cara pandang mereka yang positivistik, dimana melalui proyek sekularisasi ilmu pengetahuan dipisahkan dari konteks kemanusiaan.9 Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi justru melahirkan alienasi manusia dari nilai kemanusiaannya sendiri. Peranan kesejarahan manusia dalam menjalani hidup di dunia ini kata Syariati adalah bergerak pada dua kutub yang saling berhadapan. Kutub pertama merupakan kutub negatif yang diwakili oleh mereka yang menghambat kemajuan dengan melakukan kejahatan-kejahatan, dekadensi, penindasan, memperbudak, menegakkan tirani atas 6 Ali Maksum, Tasawuf sebagai Pembebesan Manusia Moderen; Telaah Signifikansi Konsep Tradisional Islam Sayyed Hossen Nasr, (Cet. I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h. 71. 7 Sayyed Hossen Nasr, Man and Nature; The Spiritual Crisis of Moderen Man, (London : Allen and Unwin, 1967), 8 K Bertens, Etika, (Cet. I; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1993), h. 13. h. 18. 9 Robert Heck and Dawud Reznik, ”The Islamic Thought of Ali Shari’ati and Sayyid Qutb,” Mod ern Islamic Thought (May, 2007): 2. 57 rakyat, dan sebagainya. Kutub kedua adalah kutub positif kemanusiaan yang menentang tirani dan ketidakadilan demi tegaknya perdamaian, keadilan dan persaudaraan. Kedua kutub tersebut selalu berebut ruang dominasi dalam mengisi ruang sejarah umat manusia.10 Pembeberan fakta dan kritik Syariati tersebut mengantarnya untuk mengusung tugas dan tanggung jawab kaum intelektual muslim. Sejatinya para cendekiawan dan ulama tidak menjebak diri pada komuntias eksklusif yang hidup di sangkar emas dan di menara gading tanpa bisa memahami keadaan rakyat mereka. Ali Syari’ati mengkritik para cendekiawan Muslim yang jauh dari komunitas rakyat.11 Mereka seharusnya terus berupaya melakukan transformasi sosial dengan cara terus mencetak kaum intelektual yang tercerahkan dan sadar akan tanggungjawab sosialnya, serta mempunyai misi sosial.12 Asumsi inilah yang mempertegas bagaimana ketidak sepakatan Syariati terhadap Barat, khususnya kaum Kafitalis yang selalu sibuk dengan urusan-urusan material (modal) tanpa memperdulikan nasib sesama (etika sosial). Lain halnya dengan Murtadha Muthahari yang melihat perbuatan etis didasarkan pada asumsi rasionalfilsoofis mengenai fitrah manusia, meskipun demikian nilai dan manfaat yang didapat dari perbuatan etis terkadang tidak bisa dicerap oleh akal manusia.13 Menurut Muthahhari, kecenderungan manusia untuk melakukan perbuatanperbuatan akhlaki bersifat fitrah,14 sebagaimana fitrah manusia yang lain seperti fitrah bertuhan dan beragama. Perbuatan akhlaki/etis merupakan perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh seorang manusia, karena untuk melaksanakan perbuatan tersebut memestikan upaya dan ikhtiyar yang sungguh-sungguh dan ikhlas untuk mengalahkan egoisme dan hawa nafsu yang membelenggu. Muthahhari menyebutkan perbuatan akhlak sebagai perbuatan ksatria yang memiliki nilai lebih tinggi dari perbuatan biasa.15 Perbuatan akhlaki selain didasarkan pada asumsi rasionalitas, juga didasarkan pada kesadaran intuitif (spiritual). Mengutip Immanuel Kant, Muthahhari menyebutkan perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang mendapatkan sinaran cahaya Ilahi. Dan hal tersebut tidak mungkin terealisasi tanpa didasari oleh keimanan yang paripurna kepada Allah swt.16 Pengetahuan tentang akhlak sangat tergantung bagaimana seseorang mengenali dirinya, bahwa dengan mengenal diri, seseorang dapat pula mengenal Allah SWT, yang merupakan masalah pemikiran manusia dan rahasia alam semesta. Kemudian dengan mengenal diri, dapat mengetahui apa yang mesti dilakukan dalam hidup dan bagaimana harus bersikap (akhlak dan perbuatan). Jika seseorang tidak mengenal dirinya niscaya tidak akan pernah 10 Ali Syari’ati, Tugas Cendekiawan Muslim, Op.cit., h. 37-44. Juga dapat dilihat Kritik Ali Shari’ati terkait dengan kegagalan humanisme Barat dalam memposisikan manusia dalam bukunya, Marxism and Other Western Fallacies , translated by. R. Campbell (Berkeley: Mizan Press, 1980), pp. 15-26. 11 Ali Syari’ati, ”What is To Be Done: The Enlightened Thinkers and Islamic Renaissance.” terj. Rahmani Astuti, Membangun Masa Depan Islam (Bandung: Mizan, 1993), h. 25-26. 12 Ibid., h. 29. 13 Murtadha Muthahhari, Falsafa-ye Akhlake, Diterjemahkan oleh Muhammad Babul Ulum dan Eddy Hendri dengan Judul Filsafat Moral Islam, (Cet, I ; Jakarta : al-Huda Islamic Centre, 2004), h. 21. 14 Murtadha Muthahhari, al-Fitrah, Diterjemahkan oleh Afif muhammad dengan Judul Fitrah, (Cet, II ; Jakarta : Lentera Basritama, 1999), h. 55. 15 Murtadha Muthahhari, iFalsafaye Akhlake, op, cit., h. 23. 16 Murtadha Muthahhari, Tarbiyatul Islam, Diterjemahkan oleh Muhammad Baharuddin dengan Judul Konsep Pendidikan Islam, (Cet, I ; Depok : Iqra Kurnia Gumilang, 2005), h. 117. 58 mengenal atau mengetahui bagaimana seharusnya akhlak dan perbuatan dalam hidup di dunia ini. Untuk mengetahui rahasia terbesar alam semesta dan masalah teoritis (Allah SWT), tiada jalan lain kecuali melaui pengenalan terhadap diri. Juga untuk mengetahui masalah amaliah atau praktis terpenting bagi manusia (etika) harus mengetahui atau mengenal diri.17 Dilain sisi, kita bisa lihat bagaimana fakta historis menunjukkan tentang sikap Rasulullah melalui Piagam Madinah, ini adalah suatu contoh akan prinsip moralitas yang salah satu butirnya yakni sikap saling menghormati dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi antara yang satu dengan yang lainnya.18 Tidak sebagaimana fakta moralitas yang diusung oleh Nietszche yang hanya melihat sebagian sisi dari kenyataan hidup manusia, atau dengan kata lain hanya berpijak pada kenyataan yang ia amati dan karenanya pula menurut hemat penulis hal tersebut adalah kasuistis. Dilain sisi, kita melihat bagaimana realitas islam yang justru tampil untuk membangun kesamaan derajat kemanusiaan dengan cara menghapus eksistensi tuan dan budak dalam kanca pergolakan kehidupan dunia (egalitarianisme). Berpijak dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Konsepsi etika barat sebagaimana yang diusung oleh dua tokoh pemikir, yakni Immanuel Kant justru berujung pada kekaburan paradigma, sebab ia sama sekali tidak menjelaskan secara detail asas epistemik kaitannya dengan mengapa manusia harus menundukkan perbuatannya pada hukum-hukum universal dan mengebiri pengharapan akan asas manfaat dari perbuatan moralitas itu sendiri. Sementara Nietszche terjebak pada arus paradigma fenomenologi sosial sehingga gagasan moralitasnya pun bersifat dualism (moralitas tuan dan moralitas budak), sementara yang disebutkan tersebut substansinya sama-sama sebagai manusia. 2. Kritik islam terhadap gagasan etika barat tersebut di atas karena dilepaskannya unsur metafisis (visi ketuhanan) sebagai hal penting dari perbuatan manusia itu sendiri, pada hal sejatinya hal tersebut menjadi spirit utama dari setiap tingkah laku manusia sebagai konsekuensi logis atas kehambaan dan kekahlifaannya. 17 Murtadha Muthahhari, Falsafah Akhlak, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hhidayah, 1995), h. 210. Syeikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Toleransi Islam Menurut menurut Pandangan Alquran, terj. Abu Abdillah Mohammad Afifuddin As-Sidawi, (Cet. I; Misra : Maktabah Salafy Press, t.t), h. 31. 18 59 BAB VIII TASAUF ; MEMBANGUN SPIRITUALITAS MANUSIA Istilah tasawuf dalam bahasa Inggris disebut mistisisme (mysticism). Kata mistisisme (mysticism), misteri (mystery), dan mitos (myth) berasal dari satu kata dalam bahasa Yunani mystheon, yang artinya menutup mulut. Karena itu, mistisisme, misteri, dan mitos adalah sesuatu yang disampaikan sambil tutup mulut. Akan tetapi kata tasawuf tidak berasal dari mistisisme. Ada banyak teori tentang asal usul kata tasawuf, sebagian mengatakan berasal dari kata shuf yang artinya baju bulu atau wol yang dulu dipakai orang fakir. Ada yang mengatakan berasal dari kata shafa yang artinya membersihkan diri. Ada juga yang mengatakan berasal dari bahasa Yunani, theos dan sophos yang artinya kearifan ilahi, karena tasawuf ditegakkan di atas pengetahuan tentang Tuhan.1 Secara sederhana tasawuf merupakan salah satu cabang keilmuan Islam yang menggambarkan pengembaraan spiritual seorang hamba dalam menuju Tuhannya. Ajaran praktik dari tasawuf juga disebut rencana perjalanan rohani (sayr wa suluk; artinya perjalanan dan bepergian) yang ingin mencapai puncak keagungan kemanusiaan, yakni tauhid, dengan menempuh tahap-tahap, stasiun-stasiun yang harus dilewati dengan situasi dan kondisi yang akan dialaminya.2 Dalam pengembaraan tersebut, para pengamal tasawuf melakukan riyadhah dan tazkiyah nafs, latihanlatihan spiritual dan penyucian jiwa, sebab “wajah” Tuhan yang sakral hanya bisa didekati dengan hati yang suci pula. Sehingga praktik tasawuf seolah-olah lebih menekankan aspek rohaninya ketimbang aspek jasmaninya, lebih menekankan aspek esoterik ketimbang eksoterik, dan lebih menekankan penafsiran batiniah ketimbang penafsiran lahiriah. Dengan alasan ini, tasawuf dianggap telah menjadi ritual individualistik dan formalistik yang tidak menyentuh realitas sosial, sehingga banyak pemikir kontemporer mengkritik tasawuf yang mengakibatkan stagnasi dan kecenderungan manusia bersikap apatis-negatif serta menjadi wacana keagamaan yang hanya memiliki satu wajah: kesalehan individual. Menjawab asumsi bahwa tasawuf menciptakan kevakuman, stagnasi, kemunduran, ketaatan pribadi dan melalaikan ketaatan sosial, oleh karena itu makalah ini membahas hakikat tasawuf dan beberapa perannya secara umum dalam menghadapi aneka problematika masyarakat kontemporer dalam sebuah tema berjudul “Tasawuf sebagai revolusi spiritual-moralitas dan sikap atas modernitas.” A. Tasawuf dan Spiritual-Moralitas Manusia Masyarakat global dewasa ini mengalami kehampaan spiritual karena begitu mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan material semata. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan filsafat rasionalisme ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok manusia berupa aspek nilai-nilai transenden, sebuah kedahagaan ontologis yang hanya bisa digali dari sumber wahyu Ilahi. Dengan alasan ini, dapat dimengerti jika masyarakat kontemporer kehilangan pandangan dunia spiritual mereka, sehingga menimbulkan kegersangan spiritual. 1 Jalaluddin Rakhmat, Jalan Rahmat; Mengetuk Pintu Tuhan (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 2011), h. 4. 2 Murtadha Muthahhari, Introduction To Irfan, terj. Mukhsin Ali, Mengenal Tasawuf; Pengantar Menuju Dunia Irfan (Cet. I; Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 9-10. 60 Melihat fenomena kegersangan spiritual manusia dewasa ini, maka banyak ulama yang menawarkan alternatif terapi agar mereka mendalami dan mengamalkan tasawuf. Dalam konteks kehidupan modern, menurut Abul Hasan Fusyanji bahwa tasawuf seakan menjadi nama tanpa realitas, padahal dahulu tasawuf adalah realitas tanpa nama. Kata Hujwiri, pada zaman para sahabat Rasulullah dan para khalifahnya, nama tasawuf tidak ada, tetapi realitasnya ada pada diri setiap orang.3 Beberapa peran tasawuf secara umum dalam menghadapi aneka problematika masyarakat kontemporer. Pertama, tanggung jawab spiritual. Seyyed Hossein Nasr, dalam karya tasawuf terbarunya, The Garden of Truth, menegaskan kembali bahwa kehampaan eksistensial masyarakat kontemporer mesti diterapi melalui wejanganwejangan tasawuf. Sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban intrinsik terhadap kebutuhan spiritual mereka.4 Kedua, tanggung jawab etik atau moral. Sebagai akibat modernisasi dan industrialisasi, banyak manusia mengalami degradasi moral yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya. Wajah kehidupan kontemporer cenderung menampilkan al-hirsh, yakni keinginan yang berlebih-lebihan terhadap materi, sehingga menyebabkan banyak penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, manipulasi dan tidak peduli kepada kaum lemah. Sebagian cendekiawan menawarkan konsep zuhud terhadap persoalan etika tersebut. sejumlah besar masyarakat modern sudah terjebak dalam budaya konsumerisme kontemporer, harus ada kekuatan moralitas yang resisten seperti moralitas zuhud. Agama dalam aspek asketisnya mesti tampil sebagai ideologi sosial dengan mengartikuliasikan wacana-wacana moralitas tasawuf sehingga mampu melakukan counter the consumer society, masyarakat konsumtif yang berwatak hedonistik. Sehingga secara moral keagamaan, orang akan merasa bersalah kalau melakukan konsumsi dengan rakus, sementara di sekitarnya banyak orang hidup dengan kekurangan.5 Ketiga, tasawuf berperan sebagai kritik sosial. Secara historis-sosiologis peran ini cukup signifikan dimainkan oleh tokoh-tokoh sufi. Pada era sahabat, Abu Dzar dengan kezuhudannya mengkritik dengan tajam penguasa yang hidup mewah, Utsman bin Affan, Muawiyah dan para aristokrat yang tidak peduli dengan kaum papa.6 Keempat, peran intelektual. Tasawuf sering diklaim penyebab kevakuman, stagnasi, dan kemunduran umat Islam. Akan tetapi, bila dikaji para tokoh-tokoh besar Islam sejak era klasik hingga kontemporer, banyak di antara mereka pengamal tasawuf. Al-Farabi, raksasa ilmu dan filsafat itu, adalah seorang sufi; Ibn Sina, ahli filsafat dan kedokteran, adalah pengamal tasawuf juga; Sultan Akbar yang menyatukan India dalam kedamaian dan kemakmuran, adalah penguasa sufi; Ibn Arabi menulis lebih dari 250 buku, dan Imam Khomeini, pemimpin revolusi Iran yang menggemparkan itu, dikenal sebagai sufi zaman akhir. Bahkan berkat aliran-aliran sufi, berpuluh-puluh bangsa Chechen memelihara Islam dalam cengkeraman komunisme dan melawan Rusia sendirian.7 Spiritualitas Islam atau tasawuf nampaknya mempunyai signifikansi yang kuat bagi masyarakat Barat modern yang mulai merasakan kekeringan batin dan kini upaya pemenuhannya kian mendesak. Mereka mencari3 Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif; Ceramah-ceramah di Kampus (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2004), h. 261. 4 http://cetak.bangkapos.com,, “Peran Sosial Tasawuf “, diakses pada tanggal 29 Oktober 2011. 5 Ibid 6 Ibid 7 Ibid,. Lihat Jalaluddin Rakhmat, Reformasi Sufistik (Cet. III; Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 167. 61 cari, baik terhadap ajaran Kristen maupun Budha atau sekedar berpetualang kembali kepada alam sebagai 'uzlah' dari kebosanan karena lilitan masyarakat ilmiah-teknologis. Dalam situasi kebingunan seperti itu, Islam masih belum dipandang sebagai alternatif pencarian, karena Islam dipandang dari sisinya yang legalistis-formalistis dan banyak membentuk kewajiban bagi pemeluknya serta tidak memiliki kekayaan spiritual. Atau karena Islam di Barat bercitra negatif karena kesalahan orientalis dalam memandang Islam lewat literatur dan media massa. Akibatnya, Islam dipandang sebelah mata oleh masyarakat Barat. Barat juga masih amat asing kalau Muhammad ditempatkan sebagai tokoh spiritual, dan Islam memiliki kekayaan rohani yang sesungguhnya amat mereka rindukan. Citra idola seorang tokok spiritual menurut mereka hanyalah berkisar pada Budha Gautama yang meninggalkan kemewahan hidup kerajaan, atau Kristus sang penebus dosa anak cucu Adam, atau pada Gandhi yang hidupnya begitu sederhana meski pribadinya amat besar. Sementara Nabi Muhammad Saw, lebih dikenal sebagai panglima perang yang terlalu sibuk dengan penaklukkan wilayah dan membangun kekuasaan duniawi. Islam sebagai agama samawi paling akhir diturunkan, merupakan agama yang menghendaki kebersihan lahiriah sekaligus batiniah. Hal ini tampak misalnya melalui keterkaitan erat antara niat (aspek esoterik) dengan beragam praktek peribadatan seperti wudhu, shalat dan ritual lainnya (aspek eksoterik). Faktor yang paling penting dalam membangun dan membuat identitas muslim masa kini adalah sistem pendidikan Islam tradisional, seperti yang diteladankan kaum sufi.8 Indonesia mencatat betapa besar pengaruh tasawuf kedalam dunia pendidikan sebelum masa kemerdekaan. Pengaruh tasawuf sudah sejak lama memasuki lembaga-lembaga pendidikan seperti Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Jami’at Khair, Madrasah al-Khaerat, Nahdhatul Ulama dan Pesantren.9 Kini saatnya Lembaga Pendidikan Islam mensosialisasikan dan menginternasikan dimensi batiniah Islam kepada peserta didik (murîd, thâlib) sebagai alternatif. Islam perlu disosialisasikan pada mereka, setidak-tidaknya ada tiga tujuan utama: Pertama, turut serta berbagi peran dalam menyelamatkan kemanusiaan dari kondisi kebingungan sebagai akibat dari hilangnya nila-nilai spiritual. Kedua, memperkenalkan literatur atau pemahaman tentang aspek esoteris Islam, terhadap masyarakat Barat modern. Ketiga, untuk memberikan penegasan kembali bahwa sesungguhnya aspek esoteris Islam, yakni tasawuf, adalah jantung ajaran Islam, sehingga bila wilayah ini kering dan tidak lagi berdenyut, maka keringlah aspek-aspek lain ajaran Islam. B. Ajaran Tasawuf dan Sikap Terhadap Modernitas Beberapa ciri yang dikemukakan Magnis Suseno mengenai masyarakat modern yang merupakan tantangan yang dihadapi masyarakat Islam sekarang yaitu rasionalisme. Implikasi pertama rasionalisme ialah antitradisionalisme. Modernisasi akan mendorong orang mempertanyakan keabsahan tradisi-tradisi. Implikasi kedua rasionalisme adalah sekularisasi. Sekularisasi menurut Larry Shiner, paling tidak menunjukkan lima hal: mundurnya pengaruh agama, sekadar kompromi dengan dunia, demistifikasi atau desakralisasi dunia, 8 John L. Esposito, Agama dan Perubahan Sosial Politik, terj., (Cet. I; Aksara Persadara Press, 1985), h. 15. 9 Alwi Shihab, Islam Sufistik (Bandung: Mizan, 2001), h. 214-224. 62 ketidakterikatan kepada masyarakat, dan pemindahan kepercayaan/iman dan pola-pola perilaku dari suasana keagamaan ke suasana sekuler. Implikasi terakhir rasionalisme ialah positivisme dalam filsafat ilmu.10 Manusia modern juga dihadapkan pada sebuah kenyataan, bahwa agama yang selama ini diharapkan mampu memberikan solusi terbaik terhadap persoalan-persoalan modernitas juga mengalami persoalan internal yang cukup rumit. Di antaranya adalah persoalan krisis indentitas yang sejak awal sudah mempertanyakan mampukah agama secara realitas memberikan alternatif pemecahan bagi krisis yang dialami oleh ideologi kapitalisme dan sosialisme. Persoalan lain dari permasalahan keagamaan yang akhir-akhir ini menggejala adalah kekerasan atas nama agama. Sebagian manusia yang beragama berubah menjadi manusia yang brutal, saling menerkam, membunuh dan menghancurkan. Perilaku manusia beragama yang semula religius berubah dalam waktu yang singkat menjadi seperti binatang. Perayaan agama yang begitu meriah tidak mampu membawa perubahan perilaku. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul, dikarenakan ada persoalan mengenai cara beragama yang selama ini dilakukan. Permasalahan itu adalah adanya keterjebakan keberagamaan manusia dalam bahasa simbol yang masih kaku. Hal ini dalam realitas nantinya akan mengarah pada keterjebakan formalisasi agama. Apabila hal ini terjadi maka agama justru menjadi terasing dengan persoalan kehidupan manusia, karena fungsi agama menjadi kabur. Agama yang seharusnya menjadi pembebas akan terperosok dan terjebak pada aspek romantisme formal. Dari deskripsi ini jelas, bahwa beragama tidak cukup hanya bersifat ritual. Ritualisme keliru karena berhenti pada ritus. Pada ritualisme, agama tampak hanya sebagai serangkaian upacara formal yang kering dan tidak bermakna. Eksoterisme sama satu sisinya dengan esoterisme, seorang muslim harus menjalankan dimensi keberagamaan yang lahir dan yang batin sekaligus.11 Adanya kenyataan bahwa, manusia modern mengalami krisis modernitas di satu sisi dan sisi lain agama yang diharapkan memberikan pencerahan ternyata terjebak pada aspek formalisasi ajaran dan fenomena kekerasan yang bercorak agama maka diperlukan pemikiran ulang secara terus menerus untuk lebih mengarahkan agama supaya efektif dalam memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Tuduhan ajaran sufi menjadi penyebab utama lemahnya etos sosial, ekonomi dan politik sehingga mayoritas pemeluk Islam tergolong miskin dan berpendidikan rendah adalah akibat kesalahpahaman memaknai ajaran-ajaran sufi, yang jelas-jelas bersumber kepada Kitabullah dan al-Sunnah. Ajaran sufi bisa menjadi basis etik dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik kebangsaan yang humanis dan berkeadilan dalam dunia global, jika dimaknai sebagai praksis kemanusiaan. Akar etik sufi ialah kesediaan manusia menempatkan dinamika kebendaan dan duniawi (sosial, ekonomi, politik) sebagai wahana pencapaian tahapan kehidupan (maqam) lebih tinggi dan bermutu. Bagi kaum sufi, kehidupan sosial, ekonomi dan politik bukanlah tujuan final, tapi tangga bagi kehidupan lebih luhur. Inilah maksud ajaran suluk sebagai jalan mencapai ma’rifat. Realisasi doktrin sufistik bukanlah dengan menjauhi, menolak dan menghindari pergulatan bendawi, melainkan melampaui dan menerobos batas-batas dinamika bendawi yang materialistik. Tasawuf yang dianggap meninggalkan dunia dan anti ilmu pengetahuan bukanlah tasawuf yang sebenarnya, melainkan pseudosufisme. Sebagian orang hanya mengambil bagian-bagian tasawuf tertentu untuk 10 Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif., op. cit., h. 175-177. 11 Jalaluddin Rakhmat, Reformasi Sufistik, op. cit., h. 227-228. 63 kepentingan dirinya seperti zikir dan doa saja. Menurut Haeri tasawuf bukanlah mirip seperti datang ke toko obat agar sembuh dari sakit, tasawuf yang sebenarnya adalah perlu merubah gaya hidup meliputi sikap, pandangan, dan tingkah laku.12 Perilaku dan pola hidup sufistik merupakan teknik pembebasan manusia dari perangkap materil ketika melakukan tindakan sosial, ekonomi dan politik, juga dalam kegiatan ritual keagamaan. Itulah basis etik setiap laku sufi yang seharusnya meresap kedalam setiap tindakan manusia di dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta berbagai kegiatan ilmiah. Inti ajaran sufi demikian itu mudah kita kenali di semua ajaran agamaagama samawi. Berbasis etika sufistik seseorang bersedia membantu meringankan penderitaan orang lain, walaupun diri sendiri menghadapi kesulitan dan penderitaan. Prestasi kehidupan sosial, ekonomi dan politik penganut sufi, selalu terarah bagi capaian kualitas spiritual, bukan semata bagi status sosial, penumpukan harta dan kuasa pribadi. Problem hedonisme menjadi altar kemunculan dan pertumbuhan tasawuf. Dalam perkembangan selanjutnya tasawuf menjadi suatu pendekatan keagamaan yang diminati mayoritas umat Islam. Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, fenomena ketertarikan masyarakat terhadap pengajian-pengajian yang bernuansa tasawuf mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat untuk mengatasi problem alienasi yang diakibatkan oleh modernitas. Modernitas memang memberikan kemudahan hidup namun tidak selalu memberikan kebahagiaan. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa beberapa peran tasawuf secara umum dalam menghadapi aneka problematika masyarakat kontemporer. Pertama, tanggung jawab spiritual. Kedua, etik atau moral. Ketiga, sebagai kritik sosial. Keempat, peran intelektual. Modernitas yang merupakan tantangan yang dihadapi masyarakat Islam dengan bercirikan rasionalisme yang berimplikasi pada antitradisi, sekularisasi, pola pikir positivistik. Kecenderungan hidup yang pragmatis, materialistik dan hedonistik, serta kondisi masyarakat yang hampa akan spiritualitas karena sangat mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan material semata. Tasawuf menawarkan sebuah alternatif nilai, sikap, dan pola hidup dengan nilai-nilai transenden untuk melepaskan kedahagaan ontologis. 12 Ibid., h. 167-168. 64 BAB IX TASAUF SEBAGAI ETIKA PEMBEBASAN Kegalauan kehidupan spiritual manusia telah menjadi persoalan besar yang perlu diatasi. Tidak terbilang jumlah manusia yang kini menyadari betul pentingnya memenuhi kebutuhan spiritual yang selama ini terabaikan akibat pandangan keliru yang ditebarkan oleh paham materialisme. Ketimpangan akibat kemiskinan spiritual telah merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia sebagaimana terlihat secara jelas pada kemerosotan bahkan kebangkrutan moral. Akibatnya, terjadilah sejumlah krisis yang berakibat pada rapuhnya sendi-sendi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Islam, sesungguhnya memiliki pandangan yang memosisikan manusia sebagai entitas material sekaligus spiritual. Artinya manusia terbentuk dari unsur material dan spiritual yang terpadu secara harmonis. Pengabaian terhadap dimensi spiritual manusia berakibat pada kesengsaraan manusia itu sendiri, demikian pula sebaliknya. Karena itulah, Islam mengajarkan keharusan bagi setiap orang untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik material maupun spiritual secara berimbang. Sayangnya, kebanyakan manusia lebih tertarik memenuhi kebutuhan materialnya dibanding kebutuhan spiritualnya. Berdasarkan kenyataan inilah, tasawuf merupakan aspek ajaran etika maupun moral dalam Islam dapat memberikan solusi atas problem spiritualitas dan moralitas manusia dalam kehidupan modernitas. Karena itulah, pendekatan sufistik dalam menghadapi persoalan kehidupan ini sangat penting dipertimbangkan. A. Tasawuf Sebagai Etika Pembebasan Awal mula timbulnya ajaran tasawuf bersamaan dengan agama Islam itu sendiri yaitu semenjak Muhammad saw, diutus menjadi rasul untuk segenap umat manusia dan seluruh alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum Muhammad diangkat menjadi rasul telah berulang kali melakukan Tahannuts dan khalwat1 di Gua Hira. Disamping untuk mengasingkan diri dari masyarakat Mekah yang mabuk memperturutkan nafsu keduniaan. Juga Muhammad mencari jalan untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa dari noda-noda yang dihinggapi masyarakat pada waktu itu. Mereka ingin lebih dekat dengan Tuhan. Jalan itu diberikan oleh tasawuf.2 Tasawuf adalah usaha seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat mungkin 3 dengan melalui penyucian diri dan memperbanyak ibadah di bawah bimbingan guru/syekh.4 Muhammad Ali berpendapat bahwa 1 Abu Qasim Al Qusyairy an Naisabury, Ar-Risalatul Qusyairiyah fi ‘Ilmi At-Tashawwufi, Terj. Muhammad Lukman Hakim, Risalatul Qusyairiyyah, Induk Ilmu Tasawuf (Cet. IV; Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 92. 2 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pres), 2002), h. 68 3 Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 367. 4 Sahabuddin, Metode Mempelajari Ilmu Tasawuf (Menurut Ulama Sufi) (Cet. 2; Surabaya: Media Varia Ilmu, 1996), h. 26. 65 tasawuf adalah sifat yang baik. Orang yang memiliki sifat itu adalah sifat yang diperintahkan oleh Allah swt.5 Menurut Zakariah al Anzhari, tasawuf adalah cara menyucikan jiwa, tentang cara pembinaan kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.6 Sejalan dengan itu, Hamka mengatakan pada hakikatnya tasawuf adalah kehendak memperbaiki budi dan membersihkan batin.7 Oleh karena itu, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya adalah orang yang mendekatkan diri kepada-Nya. Kembali pada persoalan dewasa ini, usaha manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, bencana dan malapetaka duniawi tidak menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian yang diharapkan. Sebaliknya, justru berakibat semakin parahnya nestapa yang diderita. Sebab, setiap penyelesaian masalah justru semakin menjauhkan manusia dari kemanusiaan, juga semakin jauh dari ketuhanan. Hampir seluruh jalan perbaikan hanya mengutamakan bidang material dengan mengabaikan dimensi spiritual dari manusia yang merupakan roh dari peradaban, yaitu tasawuf.8 Malapetaka kemanusian itu melanda masyarakat Islam secara luas karena tanpa seleksi masyarakat Islam menggunakan paradigma pemikiran yang materialistik, positivistik dan sekularistik. Dengan demikian, tidak sedikit masyarakat Islam yang mengakibatkan ajaran tasawuf sebagai etika pembebasan yang bersumber dari zat yang Maha Suci, penuntun dan penyejuk hati manusia.9 Tasawuf bukanlah sesuatu bentuk eskapisme atau melarikan diri dari kehidupan dunia, melainkan sebuah kezuhudan (asketisme) melepaskan diri dari belenggu duniawi. Sebagai contoh, Syaikh Junaidi Al Baghdadi, seorang sufi besar adalah seorang saudagar kaya. Demikian pula Syaikh Abu Hasan Asy-Syadzili, seorang rohaniawan sekaligus petani yang berhasil. Demikian juga Ibnu Hayyan, berhenti melakukan eksprimen-eksprimen fisika guna memenuhi kebutuhan manusia.10 Di situlah tasawuf tampil sebagai kritik sosial dan juga spirit kemajuan sekaligus mengandung nilai-nilai etika pembebasan. Ketika menawarkan tasawuf dalam kehidupan modern bukan sebuah tawaran untuk meninggalkan kehidupan dunia yang praktis, melainkan bagaimana kehidupan dunia yang fana’ dan praktis itu ditujukan sebagai sarana untuk mencapai ridha dan pengabdian pada Ilahi sehingga yang fana’ itu memiliki nilai keabadian, yang keduniawiaan itu memilih dimensi keakhiratan. Inilah urgensi pendekatan sufi agar kegalauan dunia ini bisa diatasi, ketika moralitas memperoleh pijakan dalam kehidupan sehingga bisa ditegakkan dan diamalkan dalam kenyataan. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan tasawuf merupakan tawaran yang perlu dipertimbangkan di abad modern ini lebih menekankan kepada rekonstruksi sosio moral masyarakat sehingga penekanannya lebih intens pada 5 Mir Valiuddin, Tasawuf dalam Al Qur’an (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 5. 6 Musthafa, Akhlak Tasawuf (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 207. 7 Hamka, Tasawuf Modern (Cet. 20; Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), h. 3. 8 Hamzah Ya’qub, Tashawwuf dan Taqarrub Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin (Cet. III; Bandung: Pustaka Madya, 1987), h. 13. 9 Syamsun Ni’am, Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari (Cet. I; Jogyakarta: Ar Ruzz Media), h. 7. 10 Ibid., h. 14-15. 66 penguatan iman sesuai dengan prinsip-prinsip aqidah Islam dan penilaian terhadap kehidupan duniawi sama pentingnya dengan kehidupan ukhrawi. B. Islam sebagai Agama Moralitas Islam, pada hakikatya adalah aturan atau undang-undang Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah rasul-Nya yang meliputi perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia guna kehidupan di dunia dan akhirat.11 Secara garis besar, ruang lingkup ajaran Islam meliputi tiga hal pokok, yaitu akidah, syariah dan akhlak (tasawuf). Sejarah telah membuktikan, bahwa sejak pertama kali dakwah Islam diperkenalkan, dikumandangkan dan disyiarkan maka Islam dari hari ke hari terus merambah, menjelajah, mengembang dan meluas ke seantero dunia. Lantaran kelahiran, Islam memang semata-mata ditujukan untuk seluruh umat manusia agar mereka dapat mewujudkan perdamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki, di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, Islam bukan hanya untuk kaum Quraisy atau orang Arab saja. Namun dipersiapkan, dirancang dan dipersembahkan bagi seluruh umat manusia semesta alam, sepanjang masa sampai hari kiamat. 12 Islam merupakan ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan. Agama Islam merupakan kekuatan yang pokok dalam perkembangan umat manusia, termasuk perkembangan moral dan etika manusia hingga dewasa ini.13 Itulah sebabnya dimensi moral atau akhlak merupakan hal yang sangat penting dan menjadi perhatian orang dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju, berkembang maupun yang terbelakang. Karena kerusakan moral atau akhlak dapat mengganggu diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara serta agama. Olehnya itu, kesempurnaan seseorang dalam beragama terletak pada kemampuannya memahami ajaran Islam secara mendalam sehingga dia bersifat arif dalam menjalankan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, ajaran Islam merupakan agama moralitas berfungsi sebagai pelindung yang memberikan keteduhan dan kesejukan serta memiliki ketentraman hidup.14 Dengan demikian, ajaran agama Islam mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia (multi dimensional) senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tidak pernah mengenal istilah ketinggalan zaman. Jadi moralitas Islamiyah mengatur prikehidupan manusia semasa di dunia untuk hidupnya di dunia maupun persiapan ke alam akhirat. Perwujudan nilai moralitas oleh Islam disebut amal shaleh.15 11 Wahyu Pramono, dkk, Etika Membangun Masyarakat Islam Modern (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2007), h. 7. 12 Imanuddin Khalil, Khaula Intisyaril Islam Waqoo’i WaMulaa Khadhoat, Ter. Ahmad Sukarno, Islam dari Masa ke Masa (Cet. I; Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h. 15. 13 Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam (Cet. 5; Bandung: Mizan, 1991), h. 53. 14 Haidar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 41. 15 Mudlor Achmad, Etika Islam (Surabaya: Al Ikhlas), h. 125 67 Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa tasawuf bukanlah sesuatu bentuk eskapisme atau melarikan diri dari kehidupan dunia, melainkan sebuah kezuhudan (asketisme) melepaskan diri dari belenggu duniawi. Tasawuf tampil sebagai kritik sosial dan juga spirit kemajuan sekaligus mengandung nilai-nilai etika pembebasan. Dengan demikian, pendekatan sufistik merupakan tawaran yang perlu dipertimbangkan di abad modern ini lebih menekankan rekonstruksi sosiomoral masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip akidah Islam. Ajaran Islam yang merupakan agama moralitas berfungsi sebagai pelindung yang memberikan keteduhan dan kesejukan serta memiliki ketentraman hidup. Islam mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia (multi dimensional) senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tidak mengenal ketinggalan zaman. Perwujudan moralitas Islamiyah adalah amal shaleh. 68 DAFTAR PUSTAKA Achmad, Mudlor. Etika Islam. Surabaya: Al Ikhlas. Ali, Mukti. Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam. Bandung: Mizan, 1991. Hamka. Tasawuf Modern. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001. Khalil, Imanuddin. Khaula Intisyaril Islam Waqoo’i WaMulaa Khadhoat, Ter. Ahmad Sukarno, Islam dari Masa ke Masa. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992. Musthafa.Akhlak Tasawuf. Bandung: Pustaka Setia, 1999. An Naisabury, Abu Qasim Al Qusyairy.Ar-Risalatul Qusyairiyah fi ‘Ilmi At-Tashawwufi, Terj. Muhammad Lukman Hakim, Risalatul Qusyairiyyah, Induk Ilmu Tasawuf. Surabaya: Risalah Gusti, 2000. Nashir, Haidar.Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. ------------. Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. Bandung: Mizan, 1996. Nasution, Harun.Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.Jilid II. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pres), 2002. Ni’am, Syamsun. Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari. Jogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011. Pramono, Wahyu, dkk.Etika Membangun Masyarakat Islam Modern. Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2007. Sahabuddin. Metode Mempelajari Ilmu Tasawuf (Menurut Ulama Sufi). Surabaya: Media Varia Ilmu, 1996. Valiuddin, Mir.Tasawuf dalam Al Qur’an. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993. Ya’qub, Hamzah. Tashawwuf dan Taqarrub Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin. Bandung: Pustaka Madya, 1987. 69 BAB X ASMAUL HUSNA SEBAGAI SUMBER ETIKA Islam pada hakikatnya merupakan aturan atau undang-undang Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunah rasul-Nya yang meliputi perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia guna kehidupan di dunia dan akhirat.1 Secara garis besar, ruang lingkup ajaran Islam meliputi tiga hal pokok, yaitu akidah, syariah dan akhlak (tasawuf). Akhlak (Etika Islam) merupakan gambaran jiwa yang tersembunyi. Oleh karenanya dapatlah disebutkan bahwa akhlak itu adalah nafsiah (bersifat kejiwaan) atau maknawiyah (bersifat abstrak) dan bentuknya yang kelihatan dinamakan muamalah (tindakan) atau perilaku maka akhlak adalah sumber dan perilaku adalah bentuknya atau dapat dikatakan bahwa akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan. Pokok persoalan etika adalah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtihar dan sengaja dan ia dapat mengetahui waktu melakukan apa yang ia perbuat. Inilah yang dapat diberi hukum baik dan buruk demikian juga segala perbuatan yang timbul tidak dengan kehendak, tetapi dapat diikhtiharkan penjagaan waktu sadar.2 Akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situsional tetapi akhlak yang benar-banar memiliki nilai mutlak. Nilai-nilai baik dan buruk, terpuji dan tercela berlaku kapan dan dimana saja dalam segala aspek kehidupan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ajaran akhlak dalam Islam, sesuai dengan fitrah manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki bila bila mengikuti nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh al Qur’an dan sunah, dua sumber akhlak Islam. Akhlak Islam benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat, sesuai dengan fitrahnya itu.3 Dengan demikian Islam sangat memperhatikan nilai-nilai etika. Salah satu aspek ajaran Islam yang paling fundamental sebagai sumber nilai etika adalah asmaul husna (nama-nama Allah yang paling indah).4 1 Wahyudi pramono,dkk, Etika Membangun Masyarakat Islam Modern ( Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 7. 2 Ahmad Amin, al Akhlaq, terj. Farid ma’ruf, Etika Islam (Ilmu Akhlak) (Cet. VIII; Jakarta: Bulan bintang, 1993), h. 5. 3 Murtadha Muthahhari, al Fithrah, terj. H. Afif Muhammad, Fitrah ( Cet. 2; Jakarta: Lentera Basritama, 1999 ), h. 1. 4 Ahmad Bahjat, Allah fi al ‘Aqidah al Islamiyyah : Risalah Jadidah fi at-Tawhid, terj. Muhammad Abdul Ghoffar E.M., Mengenal Allah Risalah Baru Tentang Tauhid ( Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h.313. 70 A. Asmaul Husna Sebagai Sumber Etika Islam. Upaya mengenal dan memahami Allah adalah bagian fitrah manusia, berbagai cara telah ditempuh manusia dengan bantuan intuisi dan nalarnya untuk mencapai tujuan ini. Allah sendiri melalui al Qur’an memperkenalkan diriNya dengan asmaul husna (nama-nama terbaik Allah). Dalam agama Islam, asmaul husna merupakan nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi asmaul husna adalah nama-nama Allah yang baik lagi indah. Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan namanama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna dan penafsirannya. Tetapi yang jelas adalah tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah. Selain perbedaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama, terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, 1000 bahkan 4000. Namun menurut mereka yang paling terpenting adalah hakikat dzat Allah swt yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad saw. Asmaul husna5 secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatNya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Para ulama menekankan bahwa Allah adalah sebuah nama kepada dzat yang pasti ada namanya. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) padaNya. Dengan demikian Allah yang memiliki Maha Tinggi tapi juga Allah yang memiliki Maha Kuasa dan juga Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kata-kata asmaul husna berkali-kali disebutkan dalam al Qur’an dan Hadis Nabi. Itu menunjukkan betapa pentingnya untuk memahami , mengerti dan menghayatinya. Terdapat tiga golongan dalam kalangan umat Islam yang memegang ajaran asmaul husna, yaitu: pertama, golongan mubtadi (pemula) ialah golongan yang terbatas pengertiannya, pemahamannya dan penghayatannya terdapat isi tercantum dalam asmaul husna. Kedua, golongan mutawassith (menengah) ialah golongan yang mengerti dan paham atas segala isinya namun belum sampai kepada tingkat “Kesadaran makrifat” atau” penghayatan sepenuhnya” terdapat makna hakiki yang terkandung dalam setiap asma-asma itu. Ketiga, golongan muntahi (puncak) ialah golongan yang mencapai tingkat kesadaran tertinggi, sempurna makrifatnya, menghayati benar dalam arti hakiki atas segala nama-nama Tuhan yang tercantum dalam asmaul husna. Meskipun terdapat penggolongan tersebut dengan segala tingkatnya selama mereka bersikap yang tidak bertentangan dengan makna yang terkandung di dalam asma-asma tersebut maka dapat dipastikan untuk merekalah seperti yang dijanjikan.6 Asmaul husna sebagai sumber moral atau etika dan pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria baik dan buruknya sesuatu perbuatan adalah al Qur’an dan sunah Rasulullah saw. kedua dasar itulah yang menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan 5 Amatullah Amstrong, Sufi Terminology (Al Qamus Al Sufi ): The Mystical Language of Islam, terj. M.S Nashrullah dan Ahmad Baiquni, Khazanah Istilah Sufi: Kunci Memasuki Dunia Tasawuf (Cet. II; Bandung: Mizan, 1998), h. 38. 6 KH. Haderanie. HN, Asmaul Husna Sumber Ajaran Tauhid/ Tasawuf ( Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu),h. 2-3. 71 buruk.7Asmaul husna yang terdapat dalam ajaran Islam sebagai sistem hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan mempunyai makna yang luas dan komprehensif, yaitu mengatur dan menyatakan pandangannya terhadap segala urusan kehidupan serta meletakan aturan-aturan yang bijak dan teliti. Dengan aturan itu, Islam selalu dinamis dan aktif menghadapi persoalan kehidupan manusia di dunia dalam membangun peradaban yang menjadi misi outentiknya. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa asmaul husna sebagai sumber etika Islam merupakan doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam al Qur’an dan sunah Nabi, di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji.8 Nilai-nilai yang tercakup dalam etika Islam, seperti halnya: sifat terpuji (mahmudah), antara lain berlaku jujur, berbakti kepada kedua orang tua, memelihara kesucian , kasih sayang, berlaku hemat, menerima apa adanya, berbuat baik (ihsan) dan lain-lain. B. Implementasi Asmaul Husna dalam Kehidupan. Allah swt adalah Dzat Yang Maha Perkasa, keperkasaan Allah tiada bandingannya, tidak terbatas dan bersifat kekal. Allah swt menciptakan alam, Allah tidak pernah meminta bantuan terhadap makhluk lain. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah hendaknya selalu memuliakanNya. Kemampuan Allah dengan cara selalu mentati segala yang telah diperintahkannya dan menjauhinya. Kemampuan Allah dalam menciptakan alam beserta isinya merupakan menifestasi dari asmaul husna. Nama-nama tersebut telah disebutkan dalam al Qur’an bahwa adanya asmaul husna sebagai bukti bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Untuk itu wajib mengamalkan asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui asmaul husna dengan cara memahaminya dengan benar merupakan metode yang sah dan akurat. Dikarenakan Allah sendiri yang memperkenalkan diri-Nya dengannya. Sesungguhnya tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali diri-Nya sendiri. Dengan mengenal asmanya yang mulia dan indah, dzatNya yang Ghaib akan semakin jelas dan dekat. Apabila diikuti dengan pengamalan dalam beribadah kepadaNya sesuai dengan petunjuk rasulNya , hal itu menjadi penguat iman yang paling besar. Semakin mendalam pemamahaman seseorang tentang asmaul husna, semakin kuatlah imannya kepadaNya. Semakin sering ia mengamalkannya dalam berdoa dan beribadah, semakin dekatlah ia kepadNya. Itulah sebabnya asmaul husna sangat dikenal sekali dikalangan umat Islam. Karena Allah dan rasulNya menganjurkan dan memberikan suatu harapan yang nyata, bagi orang-orang yang dapat menjaganya dengan memasukkan ke Syurga. 9 Rasulullah saw bersabda ” Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh semibilan asma’,Siapa saja yang menghafal dan mengamalkannya, pasti ia masuk Syurga.” (HR. Al Bukhari dan Muslim). Adapun mamfaat membaca asmaul husna, membuat hati orang yang membacanya menjadi tenang dan terarah, berpikiran jernih dan mengendalikan hawa nafsu untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah dan sebagainya. 7 Hamzah Ya’qub, Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah ( Suatu Pengantar) ( Cet. II; Bandung: Diponegoro, 1983), h. 49-51. 8 Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja ( Cet. 3; Jakarta : Rineka Cipta, 1993),h. 41. 9 Mulyadi, Asmaul Husna Dalam Konteks Al Qur’an (Yogyakarta: Nur Insani, 2003 ), h. III-IV. 72 Ulama-ulama terdahulu untuk menambahkan kebersihan hatinya mereka selalu menzikirkan asmaul husna tersebut, bukti nyatanya, ilmu-ilmu yang mereka sampaikan dapat bermamfaat sampai sekarang dan dapat menyelesaikan perkara-perkara yang menyulitkan umatdengan sarana doa dan zikirnya. Asmaul husna adalah nama-nama baik yang dimilik oleh Allah, harus dapat direalisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya umat Islam dapat mengendalikan jati dirinya ke dalam akidah yang murni, menyembah dan beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya serta mengendalikannya dari tipu daya kehidupan dunia. Jika saja umat Islam dapat merenungi, berpikir dan mengenalkan nama-nama ini, insya Allah, jayalah Islam di bumi ini. Karena asmaul husna mempunyai cakupan yang luas sekali, bila dipahami benar-benar. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: 1. Salah satu aspek ajaran Islam yang paling fundamental sebagai sumber etika Islam adalah asmaul husna. Asmaul husna adalah nama-nama Allah yang paling baik dan indah. Asmaul husna sebagai sumberetika Islam merupakan doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam al Qur’an dan Sunah Nabi, di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji 2. Mengetahui asmaul husna dengan cara memahaminya dengan benar merupakan metode yang sah dan akurat.Asmaul husna dapat menjadi penguat iman yang paling besar. Semakin mendalam pemahaman seseorang tentang asmaul husna, semakin kuatlah imannya kepadaNya. Semakin sering ia mengamalkan dalam berdoa dan beribadah, semakin dekatlah ia kepadaNya. Olehnya itu, asmaul husna adalah nama-nama Allah yang paling baik dan indah harus dapat direalisasikan dan diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya umat Islam. 73 BAB I PEMIKIRAN ETIKA MULLA SHADRA Dalam pemikiran Islam (Islamic thouhgt), muncul studi-studi tentang moral atau etika yang dilakukan oleh para pemikir dan filosof Islam seperti Ibn Bajah, al-Ghazali, Ibn Maskawaih, Mulla Shadra, Murtadha Muthahhari, Muhammad Taqi Mishbah Yazdi dan lain-lain. Perkembangan pemikiran manusia selalu menarik untuk dikaji. Manusia yang berfikir adalah manusia dinamis, yang akan berevolusi menuju puncak kesempurnaannya sebagai makhluk Tuhan. Berfikir adalah sebuah aktivitas awal yang menggerakkan seluruh aktivitas kemanusiaan. Para filosof adalah manusia-manusia pilihan yang mengabdikan dirinya pada pergulatan keilmuan dan pemikiran yang tiada henti. Kehadiran para filosof telah memberikan warna tersendiri bagi kehidupan di dunia ini. Setidaknya mereka mampu mengabstraksikan realitas yang dilihat utamanya dalam konsep-konsepnya tentang etika. Dalam pandangan Mulyadhi Kartanegara bahwa pengkajian di bidang etika dirasakan semakin urgen dikarenakan pelbagai persoalan moral muncul dengan sangat memalukan. Etika menurut para pemikir Muslim, tiada lain adalah ilmu pengobatan rohani yang sangat dibutuhkan manusia, di mana saja dan kapan saja, lebih-lebih dalam keadaan yang serba tidak menentu seperti sekarang ini. Terdapat banyak karya agung perihal etika yang isu-isu moralnya cukup menarik untuk diperbincangkan, misalnya perihal kebahagiaan, pembinaan karakter, pelbagai keutamaan dan penyakit moral, serta pelbagai solusi bagi pelbagai masalah yang timbul. Seperti Tahdzîb al-Ahklâq karya Ibn Miskawaih, Nashirian Ethics karya Nashîr al-Dîn Thûsî, al-Akhlâq wa al-Siyâr karya Ibn Hazm, Akhlâq-I Jalâlî karya Jalâl al-Dîn al-Dawwânî, serta karya-karya filosof Muslim kontemporer seperti Falsafe Akhlâq karya Murtadla Muthahhari.1 Perkembangan filsafat Islam kontemporer dan modern, atau yang lebih dikenal sebagai filsafat pasca Ibn Rusyd. Banyak sekali filosof Muslim yang telah menyumbangkan karya-karya orisinil mereka di bidang filsafat pasca Ibn Rusyd, namun sayang perhatian kita masih sangat minim. Seperti Suhrawardi, Quthb al-Din Syirazi, Nashir alDin Thusi, Syam al-Din Lahiji, Mulla Shadra, ‘Abd al-Razzaq Lahiji, Muhsin Faydl Kasyani, dan lain-lain. Mereka adalah para tokoh baru yang namanya terdengar samar-samar. Beberapa tokoh yang hidup pada abad kedua puluh seperti Astiyani, Thabathaba’i, Murtadha Muthahhari, dan Mehdi Ha’iri Yazdi, adalah para tokoh yang mesti dikaji secara intensif dan serius. Karena, dalam karya mereka tercermin bagaimana reaksi para fiolsof Muslim terhadap perkembangan filsafat Barat.2 Salah seorang filosof besar yakni Mulla Shadra sangat memiliki peran penting bagi dunia intelektual Islam setelah Ibnu Sina, Al Ghazali, Ibn Rusyd dan Suhrawardi. Pada era Mulla Shadra ini, telah melahirkan sebuah nuansa filsafat baru yang dipelajari secara intensif dengan berbagai analisis serta memberikan sintesis dan integrasi dari 1 Mulyadhi Kartanegara, Membangun Kerangka Keilmuan IAIN Perspektif Filosofis, di http://www.ditpertais.net, pada tanggal 18 Nopember 2011. 2 Ibid 74 filsafat-filsafat sebelumnya. Pola pemikiran Mulla Shadra, seperti halnya para filosof dan sufi yang mengembangkan pemikiran sebelumnya, baik dari guru maupun tokoh yang berpengaruh pada waktu itu. A. Biografi Mulla Shadra Nama lengkap Mulla Shadra adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Syirazi, dan diberi gelar “Shadr al-Din, lebih popular dengan sebutan Mulla Shadra atau Shadr al-Muta’allihin.3 Mulla Shadra adalah salah seorang filosof Muslim terbesar. Dia dilahirkan di Syiraz sekitar tahun 979-80 H/ 1571-72 M dalam sebuah keluarga yang cukup berpengaruh dan terkenal, yaitu keluarga Qawam. Ayahnya adalah Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Syirazy salah seorang yang berilmu dan saleh, dan dikatakan pernah menjabat sebagai Gubernur Propinsi Fars. Secara sosial-politik, ia memiliki kekuasaan yang istimewa di kota asalnya, Syiraz.4 Mulla Shadra mendapatkan pelajaran pertama di kota Syiraz. Selain dibimbing oleh keluarganya yang juga berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar, ia juga mendapatkan pelajaran dari sekolah dasar di kota tersebut.5 Mulla Shadra adalah murid pertama dari Syaikh Al-Baha’i dan kemudian murid dari Mir Damad, pendiri mazhab filsafat Islam Isfahan. Di bawah asuhan keduanya Mulla Shadra memiliki keunggulan ilmu di bidang filsafat, tafsir, hadis, dan irfan.6 Mulla Shadra selama empat belas tahun berdiam di Kahak, sebuah desa di Qum untuk melakukan uzlah akibat tuduhan sebagai murtad oleh para seterunya. Pada saat itu, ia mencurahkan seluruh hidupnya untuk membaca dan menulis buku. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, dia diminta untuk mengajar di Madrasah-ye Khan.7 Para sejarahwan membagi kehidupan Mulla Shadra ke dalam tiga periode: periode pertama, pendidikan formalnya berlangsung di bawah asuhan guru-guru terbaik pada zaman itu, ia menerima pendidikan dalam tradisi Syiah: fiqih Ja’fari, ilmu hadis, tafsir, dan syarah al-Qur’an di bawah asuhan Baha’ al-Din al-Amili, yang meletakkan dasar dari fiqih baru Syiah. Pada tahap berikutnya, dia mempelajari ilmu-ilmu filosofis di bawah asuhan Mir Damad.8 Setelah Mulla Shadra merampungkan pendidikan formalnya, ia terpaksa meninggalkan Isfahan, karena kritik sengit terhadap pandangan-pandangannya dari kaum Syiah dogmatis. Dan dalam periode kedua, dia menarik diri dari khalayak dan menjalani uzlah di sebuah desa kecil dekat Qum. Selama periode ini pengetahuan yang pernah diperolehnya mengalami kristalisasi yang semakin utuh, dan kreativitasnya menemukan tempat penyalurannya. Dalam periode ketiga, dia kembali sebagai pengajar di Syiraz, dan menolak tawaran untuk mengajar atau menduduki jabatan resmi di Isfahan. Semua karya pentingnya dilahirkan dalam periode ini, dia menghidupkan semangat kontemplatifnya dan melakukan praktek asketis, beberapa argument filosofisnya diperoleh melalui pengalaman-pengalaman mukasyafah.9 3 Syaifan Nur, Filsafat Wujud Mulla Sadra (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 42-43. 4 Ibid 5 Ibid., h. 44. 6 Murtadha Muthahhari, Filsafat Hikmah; Pengantar Pemikiran Shadra (Mizan: Bandung), h. 13. 7 Ibid 8 Ibid., h. 14. 9 Ibid 75 Karya-karyanya meliputi hampir lima puluh tentang pelbagai persoalan di hampir setiap disiplin ilmu-ilmu tradisional Islam, di antaranya: Al-Hikmah al-Arsyiyyah, Al-Hikmah al-Muta’alliyah fi al-Asfar al-‘aqliyyah al-Arba’ah, AlLama’ah al-Masyriqiyyah fi al-Funun al-Mantiqiyyah, Al-Mabda’ wa al-Ma’ad, Al-Masya’ir, Al-Mazahir al-Ilahiyyah fi al-Asrar al-‘Ulum al-Kamaliyyah, Al-Syawahid al-Rububiyyah fi al-Manahij al-Sulukiyyah, Al-Tasawwur wa al-Tasdiq, dan masih banyak lainnya.10 Mulla Shadra membangun mazhab baru filsafat dengan semangat untuk mempertemukan berbagai aliran pemikiran yang berkembang di kalangan Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Suhrawardi, Ibn ‘Arabi, serta tradisi klasik kalam (teologi dialektis) melalui Nashiruddin al-Thusi. Tidak hanya itu, di samping itu juga mendalami ilmu tentang al-Qur’an dan hadis.11 Mulla Shadra telah menghabiskan hidupnya di beberapa tempat, selain di Syiraz, Qaswin, Isfahan, Qum dan desa Kahak, terdapat beberapa catatan yang menunjukkan bahwa Mulla Shadra juga pernah ke beberapa kota suci di Irak, selain ke kota suci Makkah yang dilakukannya dengan jalan kaki, dia juga ke Masyhad, dan akhirnya dalam perjalanan hajinya yang ketujuh dengan jalan kaki, Mulla Shadra jatuh sakit di kota Basrah, Irak. Tidak lama berselang dalam sakit yang dideritanya Mulla Shadra akhirnya kembali kepada Allah pada tahun 1640 M (1050 H), atau dalam sumber lain dikatakan tahun 1636 M (1045 H) atau 1637 M. Mulla Shadra dimakamkan di kota Najaf, tempat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dimakamkan.12 B. Pemikiran Etika Mulla Shadra Era modern di satu sisi menawarkan manusia kemudahan hidup dalam segala hal. Namun di sisi lainnya, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat dunia secara umum tengah mengalami krisis multidimensional, termasuk moral dan spiritual. Sehingga pada akhirnya menggiring umat manusia ke arah kehampaan nilai-nilai untuk kemudian terasingkan dari poros eksistensi. Beberapa contoh kasus ekstrem yang mewarnai dunia, orang yang bergelimang harta kekayaan materi namun memilih bunuh diri karena kehampaan dalam hidupnya, juga orang-orang yang demi kepentingan pribadi atau golongannya mengabaikan nilai moral dengan melakukan kezaliman, kekerasan dan peperangan (dalam skala yang lebih besar). Semua ini menunjukkan kurangnya kearifan & kebijaksanaan dalam memaknai kehidupan. Salah satu penyebabnya adalah akibat cara pandang dunia (world view) yang dianggap sudah mapan akan tetapi tanpa disadari telah mengesampingkan aspek penting lainnya, yakni cara pandang filosofis yang mengusung nilai-nilai spiritualisme. Paradigma modern di satu sisi berhasil mengembangkan sains dan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia, namun di sisi lainnya telah mereduksi kekayaan kehidupan manusia itu sendiri. Termasuk juga telah mereduksi nilai-nilai filosofis dan spiritual. Untuk itu dibutuhkan suatu paradigm baru yang lebih holistik, yakni 10 Mustamin Al-Mandary (ed), Menuju Kesempurnaan; Persepsi dalam Pemikiran Mulla Shadra (Cet. I; Makassar: Safinah, 2003), h. 11-12. 11 Murtadha Muthahhari, op.cit 12 Mustamin Al-Mandary, op.cit., h. 6. 76 sebuah pandangan dunia baru yang menyeluruh dalam mempersepsi realitas. Hal ini dapat ditemukan dalam filsafat hikmah yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan spiritualisme. Melalui pandangan yang lebih filosofis dan holistik, diharapkan ada interaksi yang erat antara filsafat (dalam hal ini filsafat hikmah) dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya, apalagi ilmu filsafat pernah diterima secara luas sebagai “mother of science”. Pandangan ini mengharapkan suatu pencapaian integrasi ilmu, meskipun dengan berbagai sumber fakultas yang berbeda namun terintegrasi dengan harmonis. Karena manusia telah dianugerahi secara komplit, berbagai macam sumber fakultas untuk mencerap nilai dan pengetahuan untuk memaknai kehidupannya. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan dikotomi antara ilmu agama yang bersumber dari wahyu ilahi dan yang non agama, dikotomi antara ilmu sains yang bersumber dari pengamatan empiris (melalui indera) dengan ilmu filsafat yang bersumber dari pemikiran rasional (melalui akal), juga dikotomi antara ilmu filsafat dan ilmu tasawuf/irfan yang bersumber dari pengalaman spiritual (melalui dzauq/ intuisi kalbu). Dalam hal ini, seorang filosof Muslim bernama Mulla Shadra, dengan pemikiran-pemikirannya dalam filsafat hikmah yang brilian dan orisinil mampu menjawab semua tantangan itu. Filsafat hikmah merupakan evolusi dari filsafat Islam yang bagi sebagian besar orang, dianggap telah berakhir hanya sampai masa Ibn Rusyd, dan diikuti dengan menurunnya Peradaban Islam. Namun di bagian wilayah lain, filsafat Islam tetap bertahan dan berkembang menjadi filsafat hikmah yang diperkenalkan Mulla Shadra. Filsafatnya bukan hanya didasarkan pada pengalaman trans-intelektual dan gnostik, tetapi juga berupa sistem rasional yang solid. Ia berjasa dalam menunjukkan dan menawarkan cara pandang holistik menuju paradigma keilmuan yang islami, karena beliau mampu menjembatani filsafat sebagai “mother of science” dengan ilmu agama/teologi dan tasawuf/irfan secara harmonis. Pemikiran beliau juga unik, dibingkai dengan nilai spiritualitas sebagai suatu perjalanan yaitu: 1) Dari Mahkluk menuju Tuhannya (min al-khalq ila al-Haqq), 2) Dengan Tuhan dalam Tuhan (bi al-Haqq fi al-Haqq), 3) Dari dan dengan Tuhan menuju makhluk (min al-Haqq ila al-khalq), dan 4) Dalam makhluk dengan Tuhan (bi al-Haqq fi alkhalq).13 Etika, bersama politik dan ekonomi, dalam khazanah pemikiran Islam biasa dimasukkan dalam apa yang disebut sebagai filsafat praktis (al-hikmah al-‘amaliyah). Filsafat praktis berbicara tentang segala sesuatu sebagaimana seharusnya. Namun demikian tetap harus didasarkan pada filsafat teoretis (al-hikmah al-nazhariyyah), yakni pembahasa sesuatu sebagaimana adanya, termasuk di dalamnya metafisika.14 Dalam pandangan berbagai pemikir dan filosof Muslim, ada beberapa prinsip utama etika Islam di antaranya, pertama, etika bersifat universal dan fitri, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw bahwa perbuatan baik adalah yang membuat hatimu tenteram, sedangkan perbuatan buruk adalah yang membuat hatimu gelisah. Dalam pandangan atau teori etika dari filosof Yunani klasik, Sokrates yang dipromosikan oleh Plato, menyatakan bahwa moralitas itu bersifat fitri, yaitu pengetahuan baik buruk atau dorongan untuk berbuat baik sesungguhnya telah ada pada sifat alami 13 Lihat Ibid., h. 178. 14 Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam (Cet. I; Bandung: Arasy Mizan Pustaka, 2005), h. 193. 77 pembawaan manusia (fitrah/innate nature).15 Kedua, moralitas dalam Islam didasarkan kepada keadilan. Ketiga, tindakan etis pada puncaknya akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya_bagi Aristoteles bahwa pada puncaknya tujuan dari tindakan-tindakan etis adalah kebahagiaan yang bersifat intelektual. Berkaitan dengan kebahagiaan ini, Mulla Shadra menyatakan sangat bergantung kepada kesempurnaan jiwa dalam proses inteleksi (ta’aqqul). Lebih lanjut Shadra mengatakan bahwa pengetahuan dapat mengalih bentuk orang yang tahu dalam proses trans-substansi (harkah jauhariyah-nya) menuju kesempurnaan. Ada tiga akar (kejahatan) yang dapat merusak jiwa, dari ketiga tersebut muncul akar-akar kejahatan yang lain. Akar yang pertama adalah kebodohan tentang pengetahuan diri yang merupakan realitas manusia. Yang kedua adalah keinginan terhadap kedudukan, uang serta kecenderungan kepada hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah godaan jiwa yang memerintah (nafs al-ammarah) yang menunjukkan keburukan sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai keburukan.16 Menurut Mulla Shadra, bahwa berfilsafat sama maknanya dengan hikmah, ia mendefinisikan filsafat sebagai kesempurnaan jiwa manusia melalui pengetahuan terhadap realitas segala sesuatu yang ada sebagaimana adanya, dan pembenaran terhadap keberadaan mereka yang dibangun berdasarkan bukti-bukti yang jelas, bukan atas dasar persangkaan dan sekedar mengikuti pendapat orang lain, sebatas kemampuan yang ada pada manusia dalam rangka mencapai keserupaan dengan Tuhan.17 Mulla Shadra memandang hikmah ada dua aspek, yaitu teoritis dan praktis atau pengetahuan dan tindakan. Secara teoritis, tujuan hikmah atau pengetahuan adalah mewarnai jiwa dengan gambaran realitas sebagai dunia yang bisa dimengerti, yang menyerupai dunia objektif. Buah dari pengetahuan (hikmah) menurut Mulla Shadra adalah perbuatan baik, dengan tujuan agar tercapai superioritas jiwa terhadap badan dan badan tunduk kepada jiwa, sebagaimana diisyaratkan Nabi Saw bahwa berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Dengan pengetahuan bisa menjadi sarana yang membebaskan manusia dari keterikatan terhadap hal-hal yang bersifat material dan duniawi, dan mengantarkannya kembali kepada asal usul penciptaannya yaitu alam ketuhanan. Ketika Mulla Shadra menafsirkan firman Allah, “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.” Menurutnya, yang dimaksudkan dengan bentuk yang sebaik-baiknya adalah bagian jiwa manusia yang bersifat spiritual, sedangkan tempat yang serendah-rendahnya menunjukkan bagian manusia yang bersifat material. Adapun orang-orang beriman merupakan isyarat bagi hikmah teoritis, sedangkan amal shaleh mengacu kepada hikmah praktis.18 Di samping mengusung gagasan-gagasan filsafat dalam school of thought filsafat hikmah, para pemerhati filsafat Shadrian, berpandangan bahwa Mulla Shadra juga mengusung gagasan-gagasan pemerintahan dalam filsafat hikmah. 15 Ibid., h. 195. 16 Mustamin Al-Mandary, op.cit 17 Syaifan Nur, op.cit., h. 103-104. 18 Ibid., h. 105. 78 Pendeknya, kata mereka, filsafat hikmah mengajarkan dan mempropagandakan politik hikmah. Menurut Ayatullah Jawadi Amuli bahwa setiap pandangan dunia disertai dengan filsafat praktis dalam kehidupannya.19 Hikmah adalah kebijaksanaan (wisdom) yang diperoleh lewat pencerahan ruhaniyah atau intuisi intelektual dan disajikan dalam bentuk yang rasional dengan menggunakan argumen-argumen yang rasional. Hikmah ini bukan hanya memberikan pencerahan kognitif, tetapi juga realisasi, yang mengubah wujud penerima pencerahan itu merealisasikan pengetahuan sehingga terjadinya transformasi wujud hanya dapat dicapai dengan mengikuti syariat.20 Filsafat hikmah tidak hanya merupakan sebuah madrasah filsafat dengan teori-teorinya, namun juga merupakan pandangan dunia yang harus dibumikan dalam lakon sehari-hari. Mulla Shadra menuturkan, tujuan eksistensi manusia adalah menjadi penghuni (bumi) dan dalam pergerakan makrifatullah serta menanjak menuju kepada-Nya. Ia memiliki sisi pendaran cahaya dari pancaran-pancaran sinar Ilahi. Manusia lebur dalam cahaya tersebut dan maksud ini tidak akan tercapai kecuali melalui kehidupan di dunia, lantaran nafs (jiwa) pada awal pembentukannya adalah tidak sempurna dan masih berupa potensi. Proses menanjak dari kondisi tidak sempurna kepada kondisi sempurna, tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan gerakan (harâkat), zaman dan materi penerima yang merupakan tipologi-tipologi kosmos alam empirik.21 Sesuai dengan hukum eksistensial Shadra, gerakan dari kosmos potensial (quwwah) menuju kosmos aktual (fi'il), dari huduts (kebaruan) jasmani kepada baqâ (kekekalan) ruhani, maka mau tidak mau manusia harus berinteraksi dengan majemuk (katsrat/manusia lainnya dan alam semesta) untuk dapat mewujud. Tanpa perhatian terhadap dimensi somatik entitas manusia dan tanpa adanya interaksi sosial maka kesempurnaan hakiki dalam filsafat Shadrian merupakan sesuatu yang mustahil.22 Dalam filsafat politik Shadra, manusia dengan ikhtiarnya harus memilih ketika berdiri pada tapal batas material dan spiritual, sisi ruhani dan jasmani. Manusia senantiasa berada di antara majemuk materi (katsrat maddah) dan kesatuan non-materi (wahdat ruhani), sehingga keniscayaan harus bersikap seimbang (ta'âdul) dan berposisi ekuilibrium. Di antara pelbagai kontingen-kontingen material, ia harus memilih kontingen-kontingen (imkân) yang tidak menjadi penghalang perhatiannya kepada lokus non-materi dan perintang kehadiran (hudhur) pada kesatuanNya. Dalam konteks pemilihan sebagaimana kaitan nafs (jiwa) dan fakultas jiwa yang memajemuk, manusia senantiasa berada pada tataran "wahdat dan katsrat" (tunggal dan majemuk) dan "katsrat dan wahdat" (majemuk dan tunggal). Contoh sempurna penggabung ini adalah pribadi unggul Nabi Saw yang ketika pandangannya tertuju pada katsrat (urusan kebendaan dan sosial politik) maka pada saat yang sama perhatiannya tetap tertuju pada maqam wahdat (tunggal). Manusia sebagai salik (pejalan) perjalanan spiritual sepanjang hidupnya dengan memilih antara tarik 19 http://www.alhassanain.com, “Filsafat Hikmah dan Politik Hikmah,” diaskes pada tanggal 18 Nopember 2011. 20 Jalaluddin Rakhmat, “Pengantar” dalam Mulla Shadra, Kearifan Puncak (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 21 Ibid 22 Ibid XV. 79 ulur jasmani dan pelbagai konflik politik sosial maka ia senantiasa berada pada kondisi memilih di antara jamak dan tunggal.23 Pemerintahan ideal Sadrian merupakan media untuk moral transendental dan moral transendental Sadrian adalah media untuk terealisirnya politik transendental. Politik transendental merupakan jenis pemerintahan dan aturan-aturan politik sosial dalam Madinah Fâdhilah. Politik transendental ini berada pada poros aturan-aturan yang berlaku bagi kematangan dan kemenjulangan manusia serta moral fadhilah. Persoalan politik adalah politik legal yang memiliki kelayakan segala pra syarat untuk mengaktualisasikan pelbagai kesempurnaan potensial setiap orang. Penyediaan syarat-syarat seperti ini termasuk di dalamnya adalah urusan eskatologi dan keseharian manusia. Pemisahan kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan ruhani merupakan suatu hal yang mustahil; sebagaimana dalam definisi esensi manusia dalam filsafat Sadrian, pemisahan dua dimensi jasmani dan ruhani merupakan hal yang mustahil.24 Sistem politik ideal dalam Madinah Fâdhilah ala Mulla Shadra adalah sebuah sistem di mana pada saat yang sama menyediakan pelbagai kebutuhan manusia pada dua sisi, jasmani dan ruhani, material dan spiritual. Konsep kebahagiaan, keadilan, kebebasan, dan legalitas politik Sadrian ditentukan dan didefinisikan dengan konsep-konsep ini. Dalam Madinah Fâdhilah Sadrian, umat memiliki dua tipologi khas. Pertama, memiliki cita rasa esensial dan murni kepada kesempurnaan eksistensial, termasuk pelbagai kesempurnaan praktis dan teoritis. Setinggi-tingginya keutamaan dalam masyarakat seperti ini adalah mereka yang mampu menggondol derajat tertinggi keilmuan dan berbusana dengan pakaian-pakaian moral serta bentuk-bentuk pelbagai perbuatan baik, menghindar dari perbuatan sia-sia, batil dan sifat-sifat tercela. Kedua, gerakan dan perhatian totalitas kepada tujuan tertinggi yaitu sampai dan perjumpaan dengan Allah Swt. Dalam masyarakat yang menjadikan Tuhan sebagai sentral seperti ini, tentu saja secara natural aturan-aturan Ilahi juga yang berkuasa dan syariat berfungsi sebagaimana ruh bagi seluruh aturan-aturan manusia dan politik yang bermakna modern.25 Mulla Shadra juga dalam beberapa disposisi, mengingatkan akan kemestian adanya syariat, wahyu dan intervensi insan kamil sebagai “wali” dalam urusan politik dan sosial sembari menetapkan bagaimana kondisi politik dan kehendak urusan keseharian masyarakat apabila diatur oleh orang-orang yang tidak mengenal hakikat-hakikat spiritual maka umat akan digiring kepada sebuah masyarakat mati dan tanpa ruh serta penuh dengan kerusakan dan destruksi.26 Di setiap ruang dan waktu, di setiap tempat dan masa, di setiap masyarakat yang bercita-cita adilhung mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan diperlukan seorang yang menjadi insan paripurna yang membimbing dan mengejawantahkan nilai-nilai kesempurnaan dalam kehidupan masyarakat. 23 Ibid 24 Ibid 25 Ibid 26 Ibid 80 Kajian filsafat politik_sebagaimana juga etika_merupakan wilayah/domain filsafat praktis (al-Hikmah al‘Amali). Ini sesuai dengan karateristif filsafat Islam, yang tidak dapat terlepas dari kajian ontologis maupun epistemologis (al-Hikmah al-Nazari/filsafat teoritik) sebagai satu kesatuan sistemik-integratif dari filsafat Islam. Di akhir makalah ini, penulis menyampaikan kesimpulan di antaranya sebagai berikut: 1. Nama lengkap Mulla Shadra adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Syirazi, dan diberi gelar “Shadr al-Din, lebih popular dengan sebutan Mulla Shadra atau Shadr al-Muta’allihin. Dia adalah salah seorang filosof Muslim terbesar. Dia dilahirkan di Syiraz sekitar tahun 979-80 H/ 1571-72 M. 2. Buah dari pengetahuan (hikmah) menurut Mulla Shadra adalah perbuatan baik, dengan tujuan agar tercapai superioritas jiwa terhadap badan dan badan tunduk kepada jiwa, sebagaimana diisyaratkan Nabi Saw bahwa berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Dengan pengetahuan bisa menjadi sarana yang membebaskan manusia dari keterikatan terhadap hal-hal yang bersifat material dan duniawi, dan mengantarkannya kembali kepada asal usul penciptaannya yaitu alam ketuhanan. 81 BAB XII PEMIKIRAN ETIKA IBN MASKAWAIH Pada hakikatnya manusia itu bersifat etis, ia mempunyai potensi untuk menjadi bermoral, yaitu hidup dengan tatanan nilai dan norma. Etika merefleksikan bagaimana manusia harus hidup, membawa diri dan menangani hidupnya secara bertanggung jawab agar berhasil sebagai manusia dan mancapai potensialitanya yang tertinggi sehingga hidupnya lebih bermutu. Dengan demikan tujuan etika tidak sekadar hanya mengetahui pandangan atau teori, ilmu, tetapi juga memengaruhi dan mendorong manusia supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan serta memberi mamfaat kepada sesama manusia. Dengan kata lain etika mendorong kehendak agar berbuat baik.1 Etika pada dasarnya memiliki visi yang universal dan berlaku bagi segenap manusia di setiap tempat dan waktu. Namun ada kesukaran untuk merealisasikannya karena ukuran baik dan buruk menurut anggapan orang sangatlah relatif. Hal ini tentu berbeda dengan ajaran Islam dan etika Islam yang kriterianya telah ditentukan secara gamblang dalam al Qur’an dan al hadis. Etika merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Meskipun manusia dilahirkan terpisah dari individu lain. Namun ia tidak dapat hidup sendiri terlepas dari yang lain melainkan selalu hidup bersama dalam kelompok atau masyarakat. itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain manusia saling memerlukan satu sama lain, apapun status dan keadaannya. 2 Dengan demikian Islam sangat memerhatikan etika. Dalam sejarah filsafat Islam, upaya perumusan etika dilakukan oleh berbagai pemikir, termasuk di dalamnya ulama hukum, para teolog, mistikus dan filosof. Hal ini dikarenakan etika atau akhlak dalam Islam merupakan salah satu inti ajaran Islam. Etika dalam Islam didasarkan pada empat prinsip, yaitu pertama, Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat universal dan fitri. Kedua, moralitas dalam Islam didasarkan pada keadilan. Ketiga, tindakan etis dipercaya pada puncaknya akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya. Keempat, tindakan etis bersifat rasional.3 Berdasarkan hal tersebut di atas, menarik untuk dikaji pemikiran etika dari salah satu tokoh filosof muslim yang terkenal, yaitu Ibnu Miskawaih sebagai bapak etika Islam. 1 Ahmad Amin, Al Akhlak, Terj. Farid Ma’ruf, Etika: Ilmu Akhlak ( Cet. 5; Jakarta: Bulan Bintang, 1993 ), h. 6-7. 2 H. Nursid Sumatmadja, Manusia dalam konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup (Cet.I ; Bandung: Arasy, 2005), h. 203-210. 3 Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam ( Cet.I; Bandung: Arasy, 2005 ), h. 203-210. 92 A. Biografi Ibnu Miskawaih Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ya’kub Ibn Miskawaih. 4 Ia lahir pada tahun 320 H/932 M. di Ray dan meninggal di Isfahan pada tanggal 9 Shafar tahun 412 H/16 Pebruari 1030 M. Perihal kemajusiaannya, sebelum Islam,banyak dipersoalkan oleh pengarang, Jurji Zaidan, misalnya ada pendapat bahwa ia adalah Majusi, lalu memeluk Islam.5 Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa neneknyalah yang majusi, kemudian memeluk Islam. Artinya Ibnu Miskawaih sendiri lahir dalam keluarga Islam. Sebagai terlihat dari nama bapaknya. Muhammad. Ibnu Miskawaih hidup pada masa pemerintahan Dinasiti Buwaihi( 320-450 H/932-450 M) yang sebagian besar pemukanya bermazhab Syi’ah Ibnu Miskawaih terkenal sebagai ahli sejarah dan filsafat. Di samping itu, ia juga seorang dokter, moralis, penyair, ahli bahasa serta banyak mempelajari kimia. Ia belajar sejarah, terutama Tarikh al tabari ( Sejarah yang ditulis at Tabari), pada Abu Bakar Ahmad bin Kamil al Qadi pada tahun 350 H/960M, sementara filsafat ia pelajari melalui guru yang bernama Ibnu Khamar, seorang mufasir ( juru tafsir) kenamaan karya-karya Aristoteles. Abu at Tayyib ar Razi adalah gurunya di bidang kimia. Dalam bidang pekerjaan, tercatat bahwa pekerjaan utama Ibnu Miskawaih adalah bendaharawan, sekretaris, pustakawan dan pendidik anak para pemuka dinasti Buwaihi. Selain akrab dengan penguasa, ia juga banyak bergaul dengan para ilmuwan seperti Abu Hayyan at Tauhidi, Yahya Ibn Adi dan Ibnu Sina.6 Ibnu Miskawaih mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang penting dan penguasa dizamannya. Ia pernah mengabdi pada abu fadl al amid sebagai pustakawannya. Setelah Abu Fadl meninggal, ia mengabdi pada putranya, Abu al Fath Ali Bin Muhammad al Amid. Kedua tokoh yang disebut terakhir adalah menteri pada masa dinasti Buwaihi. Ibnu Miskawaih mempunyai pengaruh besa di daerah Rayy. Ia mencurahkan tahun-tahun terakhir dari hidupnya untuk studi dan menulis. Kendatipun disiplin ilmunya meliputi kedokteran, bahasa, sejarah dan filsafat, tetapi ia lebih popular sebagai filsuf akhlak ketimbang sebagai filsuf ketuhanan. Agaknya ini dimo tivasi oleh situasi masyarakat yang kacau di masanya sebagai akibat minuman keras, perzinahan, hidup glamour,dan lain-lain. Itulah sebabnya tertarik untuk menitikberatkan perhatiannya pada bidang etika. Ibnu Miskawaih terkenal sebagai pemikir Muslim yang produktif, ia telah menghasilkan banyak karya tulis tetapi hanya sebagian kecil yang sekarang masih ada, antara lain: al Fauz al Akbar (kemenangan besar ), al Fauz al Asgar ( kemenangan kecil), Tajarib al Uman (pengalaman bangsa-bangsa; sebuah sejarah tentang banjir besar yang ditulis pada tahun 369 H/979 M), Uns al Farid (kesenangan yang tiada taranya; kumpulan anekdot, syair, peribahasa dan kata-kata mutiara),Tartib as Sa’adah (tentang ahlak dan politik), al Mustaufa (yang Terpilih; syair-syair pilihan), 4 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, jilid 2 (Cet. 4; Jakarta: Ich Baru Van Hoeve, 1997), H. 162. 5 Muhammad Yusuf Musa, Falsafah al Akhlak fi al Islam (Kairo: Muassat al Khaniji, 1963), h. 74. 6 Hasan Tamin” al Muqaddimah” dalam Tahzib al Akhlaq wa Tathbir al A’raq (Cet. II; Beirut: Mansyurat Dar al Hayat, 1398 H), h.5-8. 93 Jawidan khirad (kumpulan ungkapan bijak), al Jami’ (tentang jamaah), as Siyar (tentang aturan hidup), kitab al Asyribah (tentang minuman) dan Tahzibal Akhlak (pembinaan akhlak), On the Simple Drugs (tentang Kedokteran), On the Composition of the Bajats (seni memasak), Risalah fi al Lazzah wa al Alam fi Jauhar al Nafs; Ajwibah wa As’ilah fi al Nafs wa al Aql; al Jawab fi al Masa’il al Tsalats; Risalah fi al Jawab fi Su’al Ali Ibn Muhammad Abu Hayyan al Shufi fi Haqiqahh al Aq; dan Thaharahal Nafs.7 B. Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih Bagian terpenting dari pemikiran filosof Ibnu Miskawaih ditujukan pada etika atau moral. Ia seorang moralis dalam arti sesungguhnya. Masalah moral inilah ia bicarakan dalam tiga bukunya: Tartib as Sa’ada, Tahzib al Akhlaq dan Jawidan Khirat. Dalam bidang inilah miskawaih banyak disorot dikarenakan langkahnya filosof Islam yang membahas bidang ini. Secara praktek sudah berkembang di dunia Islam, terutama karena Islam sendiri sarat berisi ajaran tentang akhlak. Bahkan tujuan diutusnya Nabi Muhammad saw adalah menyempurnakan akhlak manusia. Ibnu Miskawaih mencoba menaikan taraf bagian etika dari praktis ke teoritis-fiosofis, namun ia tidak sepenuhnya meninggalkan aspek praktis. Ibnu Miskawih dalam pemikirannya mengenai etika, ia memulainya dengan menyelami jiwa manusia. Ia memandang bahwa ilmu jiwa memiliki keutamaan sendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Manusia tidak mampu untuk meraih suatu ilmu kecuali telah mengetahui ilmu jiwa sebelumnya. Kapan seseorang memahami ilmu jiwa maka hal itu menjadi bantuan baginya untuk memperoleh ilmu yang lain. Mengetahui tentang keadaan-keadaan jiwa (ahwal an Nafs) merupakan pondasi untuk ilmu-ilmu yang lain seperti teologi, etika, logika. Karena mengetahui jiwa, seseorang memiliki senjata untuk melihat yang benar dan batil dalam masalah keyakinan dan antara kebaikan dankeburukan.8 Oleh karena itu, pemikiran etika miskawaih dibangun atas pandangannya terhadap jiwa. Ibnu Miskawaih dalam pengamatannya terhadap jiwa, ia berkesimpulan bahwa jiwa (an nafs) bukan jism dan ardh dan bukan bagian dari jism, ia berbeda dengan jism dan lebih mulia darinya. Jiwa adalah jauhar yang tak tertangkap oleh panca indra. Bagi Ibnu Miskawaih, jiwa tidak berubah dan hancur sebagaimana jism berubah dan hancur. Jiwa menerima semua bentuk yang pasangkan padanya, berbeda dengan jism, apabila telah mengambil sebuah bentuk maka ia tidak bisa lagi mengambil bentuk lain. Sebagai misal, apabila jism telah mengambil bentuk segitiga, maka ia tidak dapat menerima bentuk segi empat dan lainnya kecuali sebelumnya melepasakan bentuk segi tiga tersebut.9 Jiwa senantiasa rindu kepada pengetahuan tentang Tuhan dan jiwa merasa bahagia dengan pengetahuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa jiwa bukan bagian dari jism yang selalu merindukan kenikmatan materialis. Ibnu Miskawaih membagi kekuatan (Potensi) jiwa kepada tiga tingkatan, yaitu: pertama, kekuatan berpikir (al quwwah an natiqah), yaitu kekuatan untuk berpikir dan memebedakan hakikat sesuatu. Dan kekuatan ini dinamakan dengan al Mulkiah dan tempatnya berada di otak. Kedua, al quwwah al ghadabiah ), yaitu kekuatan untuk marah. Menolong, keberaniaan, cenderung untuk menguasai dan keinginan untuk selalu dihormati.kekuatan ini 7 Hasyimsyah nasution, filsafat islam (Cet. 4; Jakarta: Gaya Media Pratama, 199), 57-58. 8 Ahmad Amin, Dhuhr al- Islam, Jus II ( Beirut: Dar Al Kitab Al Araby, 1969), h. 177. 9 Ibnu Miskawaih, Tandzib al Akhlaq (Beirut: American Univ. Press, 1966), h. 3-4. 94 dinamamakan dengan as suba’iyyah dan tempatnya berada di hati. Ketiga, kekuatan syahwatal quwwah al syahwatiyah, yaitu kekuatan syahwat yang selalu meminta makananan dan cengderun kepada kenikmatan makanan, minuman. Menkah. Kekuatan ini dinamakan dengan al bahamiyyah dan tempatnya berada di jantung (al kabid). Ibnu Miskawaih memandang bahwa ketiga kekuatan jiwa tersebut di atas terdapat tingkatan-tingkatan. Tingkatan terendah adalah jiwa al bahimiyah, pertengahan adalah al syahwatiyah dan tertinggi adalah jiwa an nathiqah. Manusia dianggap manusia karena memiliki jiwa yang terbaik atau al nathiqah. Sehingga kemuliaan seseorang dinilai dari besar kekuatan berfikirnya. Apabila kekuatan ini dikuasai oleh kekuatan yang lain maka derajatnya pun menjadi rendah. Ibnu Miskawaih mengatakan” lihatlah di mana tempatmu. Di mana kamu suka tempat diantara tempat-tempat yang telah disediakan oleh Allah bagi makhluknya. Semua ini diberikan padamu dan kembali kepada pilihanmu, jika kamu ingin, ambillah tempat binatang, kamu akan bersamanya. Dan jika kamu ini, ambilah tempat assuba’. Jika kamu ingin, ambilah tempat para malaikat dan jadilah bagian dari mereka”.10 Etika menurut ibnu miskawaih adalah keadaan jiwa yang melahirkan perbuatan tanpa pikiran dan perenungan. Sikap mental tersebut terbagi dua, yaitu yang berasal dari watak dan yang berasal dari kebiasaankebiasaan dan latihan-latihan.11 Akhlak yang berasal dari watak jarang menghasilkan akhlak yang terpuji; kebanyakan akhlak yang jelek. Sedangkan latihan dan pembiasaan lebih dapat menghasilkan akhlak yang terpuji. Karena itu Ibnu Miskawaih sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk akhlak yang baik. Ia memberikan penting pada masa kanak-kanak yang menurutnya merupakan mata rantai antara jiwa hewan dan jiwa manusia. Etika dalam pandangan Ibnu Miskawaih dapat dikembalikan dalam dua bagian, yaitu pertama kepada tabiat atau fitrah dan kedua dengan jalan usaha (iktisab) kemudian berubah menjadi kebiasaan. Namun Ibnu Miskawaih lebih cenderung kepada yang kedua, yaitu seluruh etika semuanya adalah hasil usaha (muktasabah). Ia memandang bahwa manusia memiliki potensi untuk beretika apa saja, apakah prosesnya lambat atau cepat.Ibnu Miskawaih menetapkan kemungkinan manusia mengalami perubahan akhlak. Dari segi inilah diperlukan adanya aturan syariat, nasihat-nasihat dan berbagai macam ajaran tentang adab sopan santun. Masalah pokok yang dibicarakan dalam kajian akhlak adalah kebaikan (al Khair), kebahagiaan (al sa’adah) dan keutamaan (al fadhilah). Kebaikan adalah suatu keadaan dimana telah sampai kepada batas akhir dan kesempurnaan wujud. Kebaikan ada dua, yaitu kebaikan umum dan kebaikan khusus. kebaikan umum adalah adalah kebaikan bagi seluruh manusia dalam kedudukannya sebagai manusia atau dengan kata lain, ukuran-ukuran kebaikan yang disepakati oleh seluruh manusia. Kebaikan khusus adalah kebaikan bagi seseorang secara pribadi.12 Kebaikan yang kedua inilah yang disebut kebahagiaan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa kebahagiaan itu berbeda-beda bagi setiap orang. 10 Ibnu Miskawaih. Ibid.,h. 46. 11 Fathi Muhammad al Zugby, Falsafah al Akhlaq ‘Inda Maskawaih, Juz II( Tanta, Mesir: Maktabah Asywal, 1995),h. 301. 12 Husain Ahmad Amin, al Mi’ah al ‘Azham fi Tarikh al Islam, Terj. Baharuddin Fannani, Seratus Tokoh dalam Sejarah al Islam ( Cet. III; Remaja Rosdakarya, 1999 ), h. 155. 95 Ada dua pandangan pokok tentang kebahagiaan. Yang pertama diwakili oleh Plato yang mengatakan bahwa hanya jiwalah yang mengalami kebahagiaan. Karena itu selama manusia masih berhubungan dengan badan ia tidak akan memperoleh kebahagiaan. Pandangan kedua dipelopori oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa kebahagiaan dapat dinikmati di dunia walaupun jiwanya masih terkait dengan badan. Ibnu Miskawaih mencobah mengompromikan kedua pandangan yang berlawanan itu. Menurutnya, karena pada diri manusia ada dua unsur, yaitu jiwa dan badan. Maka kebahagiaan meliputi keduanya. Hanya kebahagian badan lebih rendah tingkatnya dan tidak abadi sifatnya jika dibandingkan dengan kebahagiaan jiwa. Kebahagiaan yang bersifat benda mengandung kebahagiaan dan penyesalan serta menghambat perkembangan jiwanya menuju kehadirat Allah. Kebahagian jiwa merupakan kebahagiaan yang sempurna dan mampu mengantar manusia menuju berderajat malaikat. Tentang keutamaan Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa asas dari keutamaan adalah kecintaan manusia kepada semua manusia. Tampa kecintaan, suatu masyarakat tidak mungkin ditegakkan. Manusia tidak dapat mencapai jati dirinya, kecuali ia hidup bersama-sama jenisnya dan saling memberikan pertolongan. Ibnu Miskawaih memandang sikap uzlah (memecilkan diri dari masyarakat) sebagai mementingkan diri sendiri. Uzlah tidak dapat mengubah masyarakat menjadi baik walaupun orang yang uzlah itu baik. Karena itu dapat dikatakan bahwa pandangan Ibnu Miskawaih tentang akhlak adalah akhlak manusia dalam konteks masyarakat. Ibnu Miskawaih juga mengemukakan tentang penyakit-penyakit moral. Di antaranya adalah rasa takut dan rasa sedih. kedua penyakit itu paling baik jika diobati dengan filsafat. Ajaran etika Ibnu Miskawaih berpangkal pada teori Jalan tengah (Nadzar Aus’at) yang dirumuskannya. Inti teori ini menyebutkan bahwa keutamaan akhlak secara umum diartikan sebagai posisi tengah ekstrem kelebihan dan ekstrem kekurangan masing-masing jiwa manusia. Posisi tengah daya bernafsu adalah iffah( menjaga kesucian diri) yang terletak antara mengumbar nafsu (al syrarah) dan mengabaikan nafsu (khumud al syahwah). Posisi tengah daya berani adalah syaja’ah (Keberanian) yang terletak antara pengecut (al jubm) dan nekad (al tahawwur). Posisi tengah daya berpikir adalah al hikma (kebijaksanaan) yang terletak antara kebodohan (al safih) dan kedunguan (al balah). Kombinasi dari tiga keutamaan membuahkan sebuah keutamaan yang berupa keadilan (al adalah). Keadilan ini merupakan posisi tengah antara berbuat aniaya dan teraniaya. Menurut Ibnu Miskawaih,setiap keutamaan mempunyai dua eksterm.Yang tengah adalah yang terpuji dan yang ekstrem adalah tercelah. Posisi tengah di sini adalah suatu standar atau prinsip umum yang berlaku bagi manusia. Posisi tengah yang sebenarnya (al wasath al haqiqi) adalah satu, yaituk eutamaan (al fadilah). Yang satu ini disebut juga garis lurus (al khath al mustaqim). Al-Iffah ( menjaga kesucian diri ) adalah keutamaan jiwa al bahimiyyah. Keutamaan ini akan muncul pada manusia apabila nafsunya dikendalikan oleh pikirannya. Artinya mampu menyesuaikan pilihan yang benar sehingga bebas, tidak dikuasai dan tidak diperbudak oleh nafsunya. Sifat ini merupakan antara rakus (al syarah) dengan dingin hati (khumud al syahwat). Yang dimaksud dengan al syarah adalah tenggelam dalam kenikmatan dan melampaui batas. Sedangkan khumud al syahwat adalah tidak mau berusaha untuk memperoleh kenikmatan yang baik sebatas yang diperlukan oleh tubuh sesuai yang diizinkan syariat dan akal. 96 as Syaja’ah (keberanian) merupakan keutamaan dari jiwa al ghadabiyyah. Keutamaan ini muncul pada manusia sewaktu nafsunya dibimbing oleh jiwa dan nathiqah. Artinya ia tidak takut terhadap hak-hak besar jika pelakasanaanya membawa kebaikan dan mempertahankannya merupaakan hal yang terpuji. Sipat ini merupakan pertengahan antara pengecut, al jubn dengan nekad, al tahawwur. Al jubn adalah takut terhadap sesuatu yang seharusnya tidak ditakuti. Sebab itu al jubn digolonkan sebagai ekstrem kekurangan. Adapun al tathawwur digolongkan berani terhadap sesuatu yang seharusnya tidak diperlukan sikap ini. Oleh sebab itu, Al tathawwur digolongkan sebagai ekstrem kelebihan. Al hikmah (kebijaksanaan) adalah keutamaan jiwa rasional (al nafs al nathiqah) yang mengetahui segala maujud (al maujudat), baik hal-hal yang bersifat ketuhanan (al umur al ilahiyyah) maupun hal-hal yang bersifat kemanusiaan (al unsur al insaniyyah). Pengetahuan ini membuahkan pengetahuaan rasional (al maqulah) yang mampu memberi keputusan antara yang wajib yang dilaksanakan dengan yang wajib ditinggalkan.Di samping itu Ibnu Miskawaih mengatakan kebijaksanaan adalah pertengahan (al wasath) antara kelancangan (al safh) dan kebodohan (al balah). Kelancangan yang dimaksud adalah penggunaan daya pikir yang tidak tepat. Sedangkan kebodohan adalah membekukan dan mengesampingkan daya pikir walau sebetulnya mempunyai kemampuan. Dengan demikian yang menjadi tekanan Ibnu Miskawaih di sini bukan pada sisi kualitas daya pikir itu melainkan pada sisi kemauan untuk menggunakannya. Al adalah (keadilan) merupakan gabungan dari ketiga keutamaan al nafs. Dikatakan demikian karena seseorang tidak dapat disebut sebagai kesatria jika ia tidak adil. Demikian pula seseorang tidak dapat disebut pemberani jika tidak mengetahui keadilan jiwa atau dirinya dan mengarahkan semua indranya untuk tidak mencapai tingkat nekad (al tathawwur) maupun pengecut (al jubn). al Hakim tidak akan memperoleh al hikmah jika ia tidak menegakkan keadilan dalam berbagai pengetahuannya dan tidak menjauhkan diri dari sifat kelancangan (al safah) kebodohan (al balah). Dengan demikian manusia tidak akan dikatan adil jika ia tidak mengetahui cara mengharmonisasikan al hikmah, al syaja’at dan al iffah. Menurut Ibnu Miskawaih keadilan diterjemahkan sebagai pertengahan antara al zhulm dan al Inzhilam. Al Zhulum berarti memperoleh hak milik dari sumber dan cara yang tidak semestinya (berbuat aniaya). Adapun al inzhilam adalah menyerahkan hak milik kepada yang tidak semestinyA atau dengan cara yang tidak semestinya pula (teraniaya). Pengertian keadilan di sini disepakati oleh para filosof bukan sebagai sebuah keutamaan tersendiri melainkan keutamaan secara menyeluruh. Keadilan ini merupakan gabungan dari semua keutamaan, karenanya ia hanya akan tercapai jika setiap jiwa mewujudkan masing-masing keutamaan. Keempat keutamaan akhlak tersebut merupakan pokok atau induk akhlak yang mulia.13 Akhlak-akhlak mulia lainnya seperti jujur, ikhlas, kasih sayang, hemat dan sebagainya merupakan cabang dari induk akhlak tersebut. Cabang dari keempat pokok keutamaan itu amat banyak jumlahnya, bahkan tidak terhitung. Bedasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kontribusi pemikiran Ibnu Miskawaih dalam dunia pemikiran Islam pada khususnya dan dunia pada umumnya sangat besar peranan dan pengaruhnya. 13 H. Abuddin Nata, Pemikiran para Tokoh Pendidikan Islam, ed. 1 (Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001 ), h. 9. 97 Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Ibnu Miskawaih lahir pada tahun 320 H/932 M di Rayy dan meninggal di Isfahan pada tanggal 9 Shafar tahun 412 H/16 Februari 1030 M.nama lengkapnya abu alin ibnu Muhammad ibn ya’kubnibn miskawaih. Ia hidup pada masa pemerintahan dinasti Buwaihi (320-450 H/132-450 M) yang sebagian besar bermadzhab Syi’ah. Ibnu Miskawaih terkenal sebagai ahli sejarah, filosof, dokter, moralis, penyair, ahli bahasa serta banyak mempelajari kimia. Karya-karya yang telah dihasilkan oleh miskawaih dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang yang lihai dalam masalah etika sehingga dijuluki sebagai bapak etika Islam. Ia telah mampu merumuskan dasar-dasar etika di dalam kitabnya Tahdzib al Akhlaq wa Thathir al A‘raq ( Pendidikan Budi dan Pembersihan Akhlak ). Sementara sumber filsafat etika ibnu Miskawaih berasal dari fisafat Yunani, peradaban Persia, ajaran syariat Islam dan pengalaman pribadi. 2. Ibnu Miskawaih dalam pemikirannya mengenai etika, ia memulainya dengan menyelami jiwa manusia,. Ia memandang bahwa ilmu jiwa memiliki keutamaan sendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu jiwa lainnya. Etika menurut Ibnu Miskawaih adalah keadaan jiwa yang melakukan perbuatan tanpa pikiran dan perenungan. Sikap mental tersebut terbagi dua yaitu yang berasal dari watak dan kebiasaan serta latihanlatihan. Ajaran etika miskawaih berpangkal pada teori jalang tengah. Intinya menyebutkan bahwa keutamaan akhlak secara umum diartikan sebagai posisi tengah ekstrem kelebihan dan ekstrem kekurangan masingmasing jiwa manusia. Dengan demikian, menurut Ibnu Miskawaih bahwa akhlak merupakan perikeadaan jiwa yang mengajak sesorang untuk melakukan perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya sehingga dapat dijadikan fitrah manusia maupun hasil dari latihan-latihan yang dilakukan hingga menjadi sifat diri yang melahirkakn akh;ak yang baik. 98 BAB I PEMIKIRAN ETIKA IBN BAJAH Di dunia Islam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan didorong oleh ajaran al-Qur’an dan hadis yang menganjurkan kepada umatnya supaya menghargai kekuatan akal dan mencari ilmu pengetahuan dimanapun. Filsafat Islam di bagian Timur dunia Islam (Masyriqi) berbeda dengan filsafat Islam di Maghribi (bagian Barat dunia Islam). Di Timur terdapat tiga orang filosof terkemuka, al-Kindi, al-Farabi dan Ibnu Sina, di Barat juga terdapat tiga orang filosof kenamaan, Ibn Bajjah, Ibn Thufail dan Ibn Rusyd. Filsafat Islam lebih dulu muncul di Timur sebelum di Barat, sebagai akibat adanya peradaban yang berpusat di Syam dan Persia setelah sebelumnya berpusat di Athena dan Iskandariyah. Munculnya filsafat di kawasan Maghribi terlambat dua abad lamanya dibanding dengan kehadira filasafat di kawasan Masyriqi, setelah pemerintahan Bani Umayyah berdiri mantap, tidaklah sukar bagi orang Arab menerjemahkan buku filsafat, kegiatan ini di lakukan orang Suryan atas dorongan para khalifah dan para penguasa Arab. Pada pertengahan abad ke-4 H, beberapa orang Andalus pergi ke kawasan Masyriqi untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena kebutuhan pembangunan di Andalus, orang mulai banyak menuntut ilmu matematika dan ilmu falak. Keadaan seperti itu tetap berlangsung selama dua abad, makin lama kebutuhan akan buku-buku filsafat terasa semakin mendesak, di samping kebutuhan akan buku-buku ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka lahirlah pemikir-pemikir filsafat. Dalam suasana perkembangan ilmu seperti tersebut di atas muncullah seorang filosof Andalus bernama Abu Bakar Muhammad bin Yahya ibn Bajjah. Filsafat Ibnu Bajjah banyak terpengaruh oleh pemikiran Islam dari kawasan di timur, seperti al-Farabi dan Ibnu Sina. Hal ini di sebabkan kawasan Islam di Timur lebih dahulu melakukan penelitian ilmiah dan kajian filsafat dari kawasan Islam di Barat (Andalus). Dan inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji bagaimana sosok Ibn Bajjah dalam memberikan perhatian dan kontribusi yang sangat besar terhadap dunia filsafat Khususnya di Spanyol. A. Riwayat Hidup Ibnu Bajjah Ibnu Bajjah adalah filosof muslim yang pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalus. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Yahya ibnu al-Sha’igh, yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Bajjah. Orang Barat menyebutnya Avenpace. Ia dilahirkan di Saragossa (Spanyol) pada akhir abad ke-5 H/abad ke-11 M.1 Riwayat hidup Ibnu Bajjah secara rinci tidak banyak diketahui orang. Begitu juga mengenai pendidikan yang ditempuhnya dan guru yang mengasuhnya, tidak terdapat informasi yang jelas.2 Selain sebagai seorang filsuf, Ibnu Bajjah juga dikenal sebagai penyair, komponis, bahkan sewaktu Saragossa berada di bawah kekuasaan Abu Bakar Ibnu Ibrahim al-Shahrawi dari Daulah al-Murabithun, Ibnu Bajjah dipercayakan sebagai Wazir. 1 Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam (Ringkas), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) h. 148. 2 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1991), h. 157. 89 Pada tahun 512 H Saragossa jatuh ke tangan raja Alfonso I dari Arogan, Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke Sevilla. Di kota ini ia bekerja sebagai dokter. Kemudian ia pindah ke Granada, dan dari sana ia pindah ke Afrika Utara, yang menjadi pusat dinasti Murabithun. Malang bagi Ibnu Bajjah setibanya di kota Syatibah ia ditangkap oleh Amir Abu Ishak Ibrahim Ibnu Yusuf Ibnu Tasifin yang menuduhnya sebagai murtad dan pembawa bid’ah, karena pikiran-pikiran filsafatnya yang asing bagi masyarakat Islam di Maghribi yang sangat kental dengan paham sunni ortodoks. Atas jasa Ibnu Rusyd, yang pernah menjadi muridnya, Ibnu Bajjah kemudian dilepaskan. Ibnu Bajjah melanjutkan karirnya sebagai ilmuwan di bawah perlindungan penguasa Murabithun.3 Pada tahun 533 H/1138 M, Ibnu Bajjah meninggal di Fez dan dimakamkan di samping makam Ibn ’Arabi. Menurut salah satu riwayat, Ibnu Bajjah meninggal karena diracuni oleh seorang dokter bernama Abu al-A’la ibn Zuhri yang iri hati terhadap kecerdasan, ilmu, dan ketenarannya.4 B. Karya-karya Ibnu Bajjah Menurut Ibnu Thufail bahwa sebuah kelompok baru para sarjana yang lebih ahli dalam bidang filsafat abstrak, muncul ke atas panggung dan Ibnu Bajjah berada di barisan terdepan kelompok ini. Oleh karena itu ia dapat diketegorikan sebagai tokoh utama dalam sejarah fisafat Arab Spanyol. Sebagai seorang imuwan, Ibnu Bajjah juga banyak menulis buku sebagai berikut: 1. Kitab Tadbīr al-Mutawahhid, ini adalah kitab yang paling popular dan terpenting dari seluruh karya tulisnya. Kitab ini diberisikan akhlak dan politik serta usaha-usaha individu menjauhkan diri dari segala macam keburukan-keburukan dalam masyarakat negara, yang disebutnya sebagai Insān Muwahhid (manusia penyendiri). 2. Risalāt al-Wadā’, risalah ini membahas penggerak pertama (Tuhan), manusia, alam, dan kedokteran. 3. Risalāt al-Ittishā, risalah ini menguraikan tentang hubungan manusia dengan akal fa’al. 4. Kitab al-Nafsh, kitab ini menjelaskan tentang jiwa.5 5. Tardiyyah, berisi tentang syair pujian. 6. Risalah-risalah Ibnu Bajjah yang berisi tentang penjelasan-penjelasan atas risalah-risalah al-Farabi dalam masalah logika. Majālah al-Majama’ al-’Ilm al-’Arabī.6 C. Pemikiran Etika Ibnu Bajjah I. Teori Etika Perbuatan manusia, menurut Ibnu Bajjah, dapat dibagi menjadi perbuatan yang sukarela (voluntary) dan tidak sukarela (involuntary). Yang disebut belakangan ialah tindakan yang terjadi akibat impuls yang ada pada segenap manusia dan binatang, sedangkan yang pertama ialah tindakan yang terjadi akibat pertimbangan akal dan pilihan bebas yang hanya ada pada manusia. 3 Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 152. 4 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004), h. 185. 5 A. Mustofa, Filsafat Islam, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2004), h. 258. 6 Sirajuddin zar, Filsafat Islam…., op. cit., h. 191. 90 Di negara-negara korup, semua tindakan bersifat involunter dan impulsive; tidak berpijak pada pertimbangan akal sehat, tetapi berpijak pada hasrat untuk memenuhi hajat hidup (seperti yang disebutkan al-Farabi tentang “kota darurat”) atau hasrat untuk memuaskan hawa nafsu (pada “kota tercela”) atau hasrat untuk menaklukkan (pada “kota tiran”).7 Sifat akali yang berasal dari ruhani yang menggerakkan manusia pada kesusilaan membuat manusia mengenal akhlak. Sifat akali manusia yang menjadi pangkal ilmu mereka adalah sifat kesempurnaan yang mutlak dapat mengatasi sifat-sifat hewani pada diri manusia. Antara lain sifat manusia yang dianalogikan seperti sifat berani dari singa, sifat sombong dari merak, sifat malu dan sebagainya.8 Ibnu Bajjah membagi pertumbuhan-pertumbuhan manusia kepada dua bagian. Bagian pertama, ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat maupun jauh. Bagian kedua ialah pebuatan yang timbul dari pemikiran yang harus dan kemauan yang bersih dan tinggi. Bagian ini yang oleh Ibnu Bajjah disebut sebagai “perbuatan-perbuatan manusia”. Pangkal perbedaan kedua bagian tersebut bagi Ibnu Bajjah bukan pada perbuatan itu sendiri melainkan terletak pada motifnya. Untuk menjelaskan kedua macam perbuatan tersebut, Ibnu Bajjah mengemukakannya dengan memakai contoh pada seorang yang terantuk (tersandung) batu kemudian luka, lalu ia melemparkan batu itu. Kalau ia melemparkannya karena batu itu telah melukianya, maka ini adalah perbuatan yang hewani yang didorong oleh naluri hewani yang telah mendiktekan kepadanya untuk memusnahkan setiap perkara yang telah mengganggunya. Kalau melemparkan batu itu agar tidak mengganggu orang lain bukan karena kepentingan dirinya, maka perbuatan itu adalah pekerjan manusia, dan pekerjaan itu bisa dinilai dalam lapangan akhlak.9 Menurut Ibnu Bajjah hanya perbuatan yang dibawah pengaruh pikiran dan keadilan semata dan tidak ada hubungannya dengan segi hewani padanya, dan itu bisa disebut dengan perbuatan manusia. Setiap orang yang akan menundukan segi hewani pada dirinya, maka tidak cara lain yakni, ia harus memulai dengan melaksanakan atau mengaktualkan segi-segi kemanusiaannya. Dengan demikian segi hewani pada dirinya dapat ditundukkan kepada ketinggian segi kemanusiaan dan seseorang bisa menjadi manusia dengan tidak ada kekurangannya, karena kekurangan itu timbul disebabkan ketundukannya pada naluri. II. Perbuatan Manusia dan Etikanya Setiap perbuatan yang dilakukan tentunya adalah untuk tujuan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup di bumi. Namun perbuatan manusia yang didasarkan pada kebutuhan hidup yang bercampur dengan keinginan dan hawa nafsu kadang kala membuat ketidaksesuaian dan kesenjangan dalam komunitas maupun lingkungan. Ketidaksesuaian perilaku itu membuat terklasifikasinya perbuatan manusia dalam pandangan para filosof. Menurut Mahmud Shaghir dalam Ibnu Bajjah yang dikutip oleh Zaharuddin Zar, bahwa perbuatan manusia terbagi menjadi dua yaitu perbuatan hewani dan manusiawi.10 7 Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam, Edisi Revisi (Cet. II; Bandung: Mizan, 2006), h. 209. 8 Tim Penyusun, Ensiklopedi….., op. cit., h. 153. 9 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam…., op. cit., h. 159. 10 Ibid., 91 Perbuatan hewani didasarkan atas dorongan naluri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan hawa nafsu. Sementara perbuatan manusia adalah perbuatan yang didasarkan atas pertimbangan rasio dan kemauan yang bersih dan luhur. Zaharuddin Zar memberikan contoh, perbuatan makan bisa dikategorikan perbuatan hewani dan bisa pula menjadi perbuatan manusiawi. Apabila perbuatan makan tersebut dilakukan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu, perbuatan ini jatuh pada perbuatan hewani. Namun jika perbuatan makan tersebut dilakukan bertujuan untuk memelihara kehidupan dalam mencapai keutamaan hidup, perbuatan itu jatuh pada perbuatan manusiawi. Perbedaan antara kedua perbuatan ini tergantung pada motivasi pelakunya, bukan pada perbuatannya.11 Perbuatan yang bermotifkan pada hawa nafsu, tergolong pada jenis perbuatan hewani dan perbuatan yang bermotifkan rasio atau dengan akal (rasio) maka dinamakan perbuatan manusiawi. Kalau didorong oleh nafsu hewani berarti perbuatan hewan, tetapi kalau perbuatannya itu didasarkan akal budi, maka hal itu adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia adakalanya didorong oleh naluri yang juga tidak berbeda dengan yang terdapat pada hewan. Selain itu, manusia memiliki kelebihan dengan adanya naluri insani yang tidak terdapat pada hewan. Manusia dapat melakukan aktivitas berdasarkan pertimbangan akalnya, bebas dari rangsangan naluri hewani. Manusia apabila didasarkan pada pemuasan akal (rasio) semata, perbuatan ini mirip dengan perbuatan Ilahi daripada perbuatan manusiawi. Hal ini merupakan keutamaan jiwa telah dapat menekan keinginan hewani yang selalu menentang akal. Pada dasarnya manusia bebas melakukan perbuatannya sesuai dengan iradah yang diberikan Tuhan. Namun dengan pertimbangan akal dan wahyu yang menuntun manusia untuk berpijak pada adat-adat kebenaran yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran sesuai derngan pertimbangan akal dan nurani. Secara ringkas Ibnu Bajjah membagi tujuan perbuatan manusia menjadi tiga tingkatan sebagai berikut: 1) Tujuan jasmaniah, dilakukan atas dasar kepuasan rohaniah. Pada tujuan ini manusia sama derajatnya dengan hewan. 2) Tujuan rohaniah khusus, dilakukan atas dasar kepuasan ruhaniah. Tujuan ini akan melahirkan keutamaan akhlaqiyah dan aqliyah. 3) Tujua ruhaniah umum (rasio), dilakukan atas dasar kepuasan pemikiran untuk dapat berhubungan dengan Allah. Inilah tingkat manusia yang sempurna dan taraf inilah yang ingin dicapai manusia penyendiri (Insān al-Muwahhid). Keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk lain terletak pada daya pikir (akal) yang manjadi sumber perbuatannya. Perbuatan dan tingkah laku yang didasarkan atas akal sehat disebut perbuatan ikhtiariah. Kalau perbuatan manusia hanya didasarkan atas pikiran demi kebenaran, maka perbuatannya itu lebih merupakan perbuatan Ilahiyah dari perbuatan manusiawi. Sehingga kalau akal sudah memutuskan sesuatu, tidak dapat ditentang oleh jiwa hewani. Pada dasarnya jiwa hewani tunduk pada akal, keculi pada manusia yang menyeleweng dari sifatsifat kemanusiaanya, sehingga kelakuannya menyerupai binatang.12 Untuk menundukkan sifat hewani pada diri manusia guna mencapai tujuan yang lebih tinggi, ia harus memulai dengan melaksanakan segi-segi kemanusiaannya. Kemurnian akal yang selau diikuti dengan realisasi dalam bentuk perbuatan dan penuh pertimbangan akal membawa manusia jauh dari sifat hewani menuju sifat Ilahi. Namun jika perbuatan yang hanya mengikuti keinginan hawa nafsu maka inilah yang dikatakan perbuatan hewani. 11 A. Mustofa, Filsafat Islam….., op. cit., h. 259. 12 http://bulanpurnama.blogdrive.com/ diakses pada tanggal 18 – 11 2011. 92 Karakteristik utama manusia dan tindakannya yang patut adalah akal budi, maka jelaslah bahwa manusia merupakan salah satu “bentuk intelektual” atau “spiritual” yang merupakan bagian tertinggi dari skala besar wujud. Ibnu Bajjah menentukan posisi manusia sepanjang skala “bentuk-bentuk spiritual” dalam hirarki universal dari wujud yang telah dipopulerkan oleh kaum Neo-Platonis Muslim. Jika nalar manusia yang selaras dengan pertimbangan adalah sensi manusia, bukannya dorongan-dorongan impulsif, manusia sebenarnya adalah makhluk dan berbentuk (form) spiritual yang banyak diperbincangkan oleh kaum noe-platonis dan mistis.13 Bagi Ibnu Bajjah, ada empat tipe makhluk spiritual, yakni: 1) Bentuk-bentuk dari benda langit (forms of the heavenly bodies) yang sama sekali bersifat immaterial. Tipe ini disepadankan dengan akal-akal terpisah (sparate intelligences) yang dalam kosmologi Aristotelian dan Islam diyakini sebagai penggerak benda-benda langit itu sendiri; 2) Akal-akal capaian (mustafad) atau akal aktif yang juga bersifat immaterial; 3) Bentuk-bentuk immaterial yang diabstraksikan dari materi; 4) Bentuk-bentuk atau representasi-representasi yang tersimpan dalam tiga daya jiwa; sensus communis, imajinasi, dan memori. Seperti bentuk-bentuk material, bentuk-bentuk ini dinaikkan ke tingkat spiritual melalui fungsi abstraktif yang terdapat pada jiwa manusia. Puncak dari fungsi abstraktif ini ialah pemikiran rasional. Kategori yang pertama bersifat sama sekali immaterial, sementara yang kedua, sekalipun pada hakikatnya immaterial, tetapi mempunyai hubungan tertentu dengan materi. Karena intelek itu merupakan ma’qulat material sesuai dengan kemampuan pencapaiannya, atau menjadikan mereka sesuai dengan kapasitas aktifnya. Yang ketiga mempunyai suatu hubungan tertentu dengan materi, sejauh bentuk-bentuk seperti itu dipisahkan dari substarata materi mereka. Sementara yang keempat berada di tengah-tengah, antara bentuk-bentuk material dan spiritual.14 III. Manusia Menyendiri (Insān al-Muwahhid). Filsafat Ibnu Bajjah yang paling populer ialah manusia penyendiri (Insān al-Muwahhid). Dalam menjelaskan manusia penyendiri ini, Ibnu Bajjah terlebih dahulu memaparkan pengertian Tadbīr al-Mutawahhid. Kata tadbīr, berasal dari bahasa Arab, mengandung pengertian yang banyak, namun pengertian yang diinginkan oleh Ibnu Bajjah ialah mengatur perbuatan untuk mencapai tujuan yang di inginkan, dengan kata lain aturan yang sempurna.15 Jika tadbīr dimaksudkan sebagai pengaturan yang baik untuk mencapai tujuan tertentu, maka tadbīr tentu hanya khusus bagi manusia. Sebab pengertian itu hanya dapat dilakukan dengan perantaraan akal, dan akal hanya terdapat pada manusia. Dan juga perbuatan manusia berdasarkan ikhtiar. Hal inilah yang membedakan manusia dari makhluk hewan. Lebih lanjut Ibnu Bajjah menjelaskan tentang tadbīr bahwa kata ini mencakup pengertian umum dan khusus. Tadbir dalam pengertian umum, seperti disebutkan diatas, adalah segala bentuk perbuatan manusia. Sementara itu tadbīr dalam pengertian khusus adalah pengaturan negara dalam pencapaian tertentu, yakni 13 http://pandidikan.blogspot.com/2010/03/filsafat-ibn-bajjah.html diakses pada tanggal 16 – 11 – 2011. 14 http://iirmakalahtarbiyah.blogspot.com/2010/11/makalah-filsafat-islam-filsafat-al.html diakses pada tanggal 16 – 11 – 2011. 15 A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsafat Islam, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 245. 93 kebahagian. Filosof pertama spanyol ini menghubungkan istilah tadbīr pada Tuhan yakni Maha Pengatur, yang disebut al-Mutadabbir.16 Tuhan telah mengatur alam semesta sedemikian rapi dan teratur tanpa cacat. Pemakaian kata ini kepada Allah hanya untuk penyerupaan semata. Akan tetapi, pendapat Ibnu Bajjah ini memang ada benarnya. Tadbīr yang akan dilaksanakan manusia mestinya mencontoh kepada tadbirnya Allah SWT terhadap alam semesta. Selain itu, tadbīr hanya bisa dilaksanakan dengan akal dan ikhtiar manusia. Pengertian ini mencakup manusia yang memiliki akal dan Allah yang dalam filsafat disebut dengan ‘Aql.17 Adapun yang disebut degan istilah al-Mutwahhid adalah manusia penyendiri. Degan kata lain, seorang atau beberapa orang yang mengasingkan diri secara sendiri-sendiri, tidak berhubungan dengan orang lain, mereka harus mengasingkan diri dari sikap dan perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak baik.18 Mereka hanya berhubungan dengan ulama atau ilmuwan, apabila para filosof tidak melakukan hal demikian, mereka tidak akan mungkin berhubungan dengan akal af’al karena pemikiran mereka akan merosot dan tidak pernah mencapai tingkat akal mustafad, yakni akal yang dapat berhubungan dengan akal af’al. itulah sebabnya Ibnu Bajjah menyebutkan bahwa manusia penyendiri bagaikan tumbuhan. Jika ia tidak menyendiri dalam menghadapi kondisi seperti itu maka ia akan layu, artinya pemikiran filsafatnya mengalami kemunduran. Jika inin terjadi, filosof yang di maksud tidak akan pernah mencapai kebahagiaan (al-Sa’ādah).19 Ibnu Bajjah dalam filsafatnya ini dapat di kelompokkan ke dalam filosof yang mengutamakan amal untuk mencapai derajat manusia yang sempurna. Pada pihak lain, filsafat manusia penyendiri Ibnu Bajjah cocok dengan zaman modern ini. Manusia apabila hidup dalam masyarakat yang bergelimang dalam kemaksiatan dan kebobrokan atau dalam masyarakat materialistis harus membatasi pergaulanya dalam masyarakat dan ia hanya berhubungan dengan masyarakat ketika memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya semata.20 Dari uraian diatas disimpulkan bahwa Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia menjadi perbuatan hewani dan manusiawi. Perbuatan didasarkan atas dorongan naluri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan hawa nafsu. Sementara, perbuatan manusiawi adalah perbuatan yang didasarkan atas pertimbangan rasio dan kemauan yang bersih lagi luhur. Perbedaan antara kedua ini tergantung pada motivasi pelakunya, bukan pada perbuatannya. Perbuatan yang bermotifkan hawa nafsu tergolong pada jenis perbuatan hewani dan perbuatan bermotifkan rasio (akal) maka dinamakan perbuatan manusiawi. Manusia, menurut Ibnu Bajjah, apabila perbuatannya dilakukan demi memuaskan akal semata, perbuatannya ini mirip dengan perbuatan Ilahi dari pada perbuatan manusiawi. Hal ini merupakan keutamaan karena jiwa telah dapat menekan keinginan jiwa hewani yang selalu menentangnya. Perbuatan seperti inilah yang dikehendaki oleh Ibnu Bajjahbagi warga masyarakat yang hidup dalam negara utama. Adapun tujuan manusia hidup di dunia ini, 16 Ibid., h. 246. 17 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat…….op. cit., h. 159. 18 Tim Penyusun, Ensiklopedi….., op. cit., h. 154. 19 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat…….op. cit., h. 160. 20 Ibid., 94 adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Untuk itu, diperlukan usaha yang bersumber pada kemauan bebas dan pertimbangan akal dan jauh dari nafsu hewani. Watak sejati manusia pada hakikatnya bersifat Intelektual, yang merupakan karakteristik semua bentuk spiritual. Dan hanya “manusia spiritual” inilah yang benar-benar dapat merasakan kebahagiaan. Ibnu Bajjah menyatakan bahwa kemajuan intelektual bukanlah semata-mata atas usaha manusia, tetapi disempurnakan oleh Tuhan dengan memasukkan cahaya ke dalam hati. 95 BAB XIV PEMIKIRAN ETIKA AL-GAZALI Sejarah telah mencatat bahwa pada abad ke-4 hijriah, semangat intelektual para ulama Islam mulai melemah. Mereka lebih tertarik untuk mengikuti alur-alur pikiran pada imam terdahulu yang mereka pandang memiliki kelebihan ilmu dari pada mereka.1 Inilah masa dimana rasionalitas dalam dunia ke-Islam-an tergantikan dengan semangat taqli d yang justru mematikan atau setidak-tidaknya telah mengkaburkan ruh syariah Islam. akibatnya ialah, kompleksnya masalah dalam masyarakat yang tak dapat dihadapi, sehingga bagi yang tidak dapat melihat pokok permasalahan secara jernih semena-mena melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya terhadap syariah Islam itu sendiri.2 Menurut Asaf. A. A Fysee, zaman itu dikatakan adalah zaman dimana segi (syariah, hukum, fikih) Islam mengalami kemunduran umum.3 Demikian pula menurut Anwar Harjono, menamakannya dengan zaman “kelesuan” karena bagaimanapun juga keadaan syariah Islam terus hidup, hanya saja ia tampil dengan semangat kelesuan karena tidak mampu menghadapi keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. 4 Kondisi seperti itulah diperlukan filosof, fakih, sufi, dan ahli tasawuf untuk meluruskan pandangan keliru tadi, dan mampu mendamaikan antara syariah dan tasawuf, dan pada gilirannya, muncullah al-Gaza li (1058-1111 M), seorang ulama yang berpengaruh dan mampu meluruskan pemikiran para ulama yang selama ini keliru. Al-Gaza li menghimbau mereka untuk kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah serta kembali menghidupkan akal dengan memfatwahkan bahwa pintu Ijtihad tidak pernah tertutup.5 Juga al-Gaza li sebagai tokoh tasawuf yang terkenal dengan konsep ma’rifahnya menghimbau agar antara syariah dan tasawuf direkonsiliasi, dipadukan, diparalelkan untuk sejalan bersama-sama. Apa yang dilakukan al-Gaza li menyebabkan dirinya mendapat gelar hujjah al-Islam (bukti kebenaran Islam).6 1. A. Biografi Singkat Imam Al-Gazali Sejak kecil al-Gaza li7 bernama Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, sesudah berumah tangga dan mendapat seorang putra laki-laki yang bernama “Hamid”, maka dia dipanggil “Abu Hamid” (bapak si Hamid)8 1 Situasi ini memunculkan fanatic mazhab, kemudian memunculkan percekcokan antara penganut mazhab dengan yang lainnya, situasi ini muncul semboyan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Lihat Muhammad Ibnu Abi alSyaukani, Irsyadi al-Fuhu l Ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilmu al-Ushu l (Bairu t Da r al-Fikr, t. th), h. 253 2 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya (Cet II: Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 82 3 Asaf. A. A Fysee, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Tirtamas 1960), h. 38 4 Anwar Harjono, loc.cit., h. 89. 5 John. L. Esposito (ed) ensiklopedi Oxford, Dunia islam Modern, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2003), h. 112. 6 M. M Syarif (ed), Para Filosof Muslim (Cet. I; Bandung: Mizan, t. th), h. 102. Penulisan nama al-Gaza li ada dua macam yaitu: (1) Al-Gaza li (dengan satu “z”), nama ini berasal dimana desa tempat ia lahir, yaitu “Gazala”; (2) Al-Gazza li (dengan dua “z”) terambil dari istilah nama pekerjaan orang tuanya 7 106 Selanjutnya karena kefasihan dalam berbicara, dan pengetahuannya yang dalam tentang berbagai studi keilmuan (termasuk dalam hal ini adalah seni berdebat dan berargumentasi) mengantarnya jadi tokoh masyhur di zamannya dan bahkan hingga sekarang, akibatnya Ia pun mendapat gelar tambahan sebagai “Hujjatul Islam”. kesemuanya itu dipadukan untuk membentuk nama lengkap al-Gaza li, yakni Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid al-Gaza li Hujjatul Islam. Al-Gaza li lahir di Ghaza li, suatu desa dekat Thus9 di daerah Khurasan (Persia), Iran sekarang pada tahun 450 H/1058 M.10 Dia berasal dari keluarga miskin namun agamis. Bapaknya bekerja sebagai penenun wol. Semenjak kecil al-Gaza li telah menjadi yatim, sebelum orang tuanya meninggal, ia dan saudaranya dititipkan kepada seorang sufi sahabat ayahnya untuk dipelihara dan dididik.11 Oleh sahabat ayahnya, Ahmad bin Muhammad alRazikani di Thus, al-Gaza li mendapatkan ilmu dibidang fikih secara mendalam dan kemudian mempelajari tasawuf dari Yusuf al-Nassay seorang sufi terkenal. Selanjutnya meninggalkan Thus menuju Jurjan untuk mendalami pengetahuan bahasa Arab dan Persia sambil belajar pengetahuan agama pada gurunya yang terkenal dengan sebutan Imam Abu Nashar al-Ismai’li.12 Pada tahun 470 H, al-Gaza li mengembara menuju Nishopur (Naisa bur) untuk belajar di sekolah tinggi “Niza miyah”, disinilah Ia bertemu dengan Abu al-Ma’a li Dhiuddin al-Juwaeni (Imam Haramany).13 Dengan bimbingan al-Juwaeni, al-Gaza li menjadi ilmuwan besar, ia menerima ilmu pengetahuan di sekolah tinggi ini, yaitu hukum Islam, sufisme, logika dan ilmu-ilmu alam serta filsafat.14 Dalam menuntut ilmu, al-Gaza li termasuk murid yang pandai, mampu mempelajari bahkan menghapal berbagai materi yang tidak dapat dilakukan oleh murid lain yang seangkatan dengannya. Naishabur merupakan batu loncatan pengembaraan bagi al-Gaza li untuk menaiki tangga kemajuan dan kemasyhuran namanya, sambil belajar dia diangkat menjadi asisten dari Imam Haramain di usia 25 tahun. Setelah gurunya Imam Haramain meninggal pada tahun 478 H/1085 M, al-Gaza li dikenal murid yang hebat dan cerdas sehingga menarik perhatian Nizha m al-Mulk (Perdana Menteri Kerajaan Abbasiah), maka dia diundang dan yakni ghazzal (pemintal dan penjual wol). Lihat Zainal Abidin Ahmad, Riwayat Hidup imam al-Gaza li (Cet. I; Jakarta; Bulan Bintang, 1975), h. 28 8 Ibid., h. 27 Thus adalah salah satu kota di Khura san yang penduduknya sangat heterogen, baik dari segi faham keagamaan maupun dari segi suku bangsa. Lihat al-Subki, Tabaqa t al-Syafi’iyah al-Kubra, juz IV (Mesir: Mushtha fa alBa b al-Halabi, t.th), h. 102 9 Badawy Thabanah, al-Tasnawwuf al-Isla my wa Dira sat Tahli liyat li al-Syakhshiyat al-Ghaza li wa Falsafatuhu fi al-Ihya ‘, Muqaddimah Kita b al-Gaza li, Ihya Ulum al-Di n (Cet. I; Semarang: Maktabat wa Mathba’ah Toha Putra, t. th), h. 7. 10 11 Zainal Abidin Ahmad, op. cit., h. 30. 12 Lihat Ensiklopedi Islam (Jakarta: ikhtiar Baru, Van Hoeve), h. 25. 13 Imam Haramain ialah gelar kehormatan yang diberikan kepada al-Juwaini setelah baliau melawat ke tanah suci Mekkah dan Madinah sebagai ulama besar yang diakui mengajar dan memberi fatwa hampir empat tahun. Itulah sebabnya digelar sebagai Imam Haramain (Imam dari dua kota suci Mekkah dan Madinah) dan diminta oleh perdana Menteri Niza mul Mulk menjadi Rektor di Universitas al-Niza miyah. Lihat Zainal Abidin Ahmad, op. cit., h. 33 14 Abd. al-Rahman Badawi, Muallafa t al-Gaza li (Damaskus: al-Majelis al-A’la li Ri’yat al-Funu n, 1961), h. 19 107 diangkat menjadi pimpinan Universitas Baghdad yang menjadi pusat dari seluruh Universitas Niza miyah di masa itu.15 Selama masa ini, ia telah melahirkan sejumlah karya dalam bentuk buku, baik dalam bidang fikih, teologi dan filsafat.16 Tahun 1090, Nizha m al-Mulk, negarawan ini mengakui keahlian al-Gaza li yang kemudian mengangkatnya menjadi guru besar (Professor) dalam ilmu hukum di Universitas Nizhamiyah Baghdad. Al-Gaza li bertambah tinggi kehormatannya dan kekuasaannya dalam Negara, melebihi umara dan penasehat khali fah.17 Selama proses pengembaraannya terhadap penguasaan berbagai ilmu pengetahuan, al-Gaza li pernah mengalami pergolakan batin, di dalam dirinya tumbuh keraguan, ia meragukan pengetahuan yang diperolehnya yang akhirnya menimbulkan penyakit psikis yakni tidak bisa berbicara.18 Pergolakan batin tersebut menyebabkan dirinya berobat secara medis dan kejiwaan kepada beberapa orang dokter ahli, namun tidak berhasil. Menurutnya ia memperoleh nu r (cahaya) yang dipancarkan Allah SWT. Sehingga terbukalah ma’rifah untuk menghilangkan keraguan dalam hatinya dengan jalan menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Dengan demikian, ia meninggalkan Baghdad kemudian mengembara ke Damaskus selama 2 tahun untuk beribadah, beri’tikaf di Mesjid kota itu. Selanjutnya ke Bayt al-Maqdis dengan maksud yang sama, lalu melanjutkan pengembaraan ke Mesir untuk mendapatkan ketenangan, setelah itu Ia akhirnya ke Mekkah menunaikan ibadah haji dan selanjutnya ke Madinah.19 Dengan hati yang puas, menurut pengakuannya kurang lebih 10 tahun masa berkhalwat, dia mengalami pergolakan batin yang kuat, dan dalam keadaan demikian terbuka segala soal yang tidak terhitung banyaknya lewat ilmu dari Allah SWT, maka pada tahun 1108 M, ia kembali ke Naisha bur memenuhi permintaan Fakhr al-Mulu k (anak Nizha m al-Muluk) untuk mengajar di Nizha miyah. Namun tidak berapa lama mengajar, tanpa alasan yang jelas ia memutuskan untuk berhenti dan pulang ke kampung halamannya (Thus). Ia sempat mendirikan madrasah untuk para penuntut ilmu dan tempat berkhalwat, dan akhirnya pada hari senin 14 Jumadil akhir 505 H (18 desember 1111 M), al-Ghaza li wafat dalam usia 55 tahun.20 B. Karya-Karya Imam al-Gaza li Sepeninggal al-Gaza li, dia mewariskan beberapa karya yang terkenal antara lain; Maqa shid al-falsifah; Taha fut al-Fala sifah; al-Ma’a rif al-‘Aqliyah wa al-Hikmah al-Ilahiyah; Mi’yar al-‘Ilm; Jam al-Haqa iq fi Tajra d al-A’laiq; Ihya ‘Ulu m al-Di n; al-Basi t; al-Wasi t; al-Waji z; al-Khula sha t; al- Iqtisha l; al-Risa lah al-Qudsiah; Ilm al-Kalam; Haqa iq al-‘Ulu m; Maqa syifah al-Qulu b al-Matrahba Ila ‘Alla m al- Ghuyu b; Miha q al-Nazhr; ma’a rij al-Quds fi Muda rij Ma’rifah al-Nafs. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah 15 Lihat al-Gaza li, Munqiz al-Dhala l (Beiru t: al-Ma’ktabat al-Sa’biyyah, t. th), h. 35-37 Buku-bukunya yang terbit dalam bidang fikih antara lain: al-Basi t, al-Wasi t, al-Waji z dan alKhula sha t. Dalam bidang ilmu kalam antara lain: al-Iqtisha l, al-Risa lah, al-Qudsiah, Ilm al-Kalam. Dalam bidang filsafat ialah Maqa shid al-Falsifah dan Tha fut al-Fala sifah, serta selainnya. Lihat ibid., h. 57 16 17 Zainal Abidin Ahmad, op. cit., h. 40 18 Al-Gaza li, Munqiz, op. cit., h. 31 19 Ibid., 20 Al-Gaza li, Muka syofat al-Qulu b al-muqarrab min ‘Alam al-Ghuyu b (Kairo: Da r al-Sya’b, t. th), h. 8 108 karya-karya al-Gaza li. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 228 buah. Hanya saja, sebagian karya-karyanya adalah kitab Ihya Ulumuddin (menghidupkan kembali ilmu agama). Karyanya ini, menjadi koleksi bacaan yang sangat digandrungi oleh banyak kalangan umat Islam. C. Konsepsi Etika Imam Al-Gazali Al-Ghazali merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam memadukan sufisme dengan syariah, yah tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah bagian dari efek atas ketertarikannya terhadap sufisme sejak berusia masih belia. Ia juga tercatat sebagai sufi pertama yang menyajikan deskripsi sufisme formal dalam karyakaryanya.21 Al-Gazali adalah salah satu tokoh Asy’ariyah yang banyak mengembangkan teori etika di dunia Islam. Gagasan etikanya dibangun melalui perhubungan paradigma wahyu dengan tindakan moral, stressingnya bahwa kebahagiaan adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Keutamaan-keutamaan merupakan pertolongan Tuhan yang niscaya sifatnya terhadap jiwa. Tidak ada keutamaan lain yang dapat dicapai tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan, alGhazali menegaskan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, usaha mandiri manusia dalam mencari keutamaan akan sia-sia dan bahkan dapat membawa kepada sesuatu yang salah dan dosa.22 Penegasan tersebut membuktikan bahwa al-Ghazali bermaksud menyamakan pengertian etika atau moralitas sama halnya dalam teologi Islam. Menurut Amin Abdullah, al-Ghazali jatuh pada “reduksionisme teologis”. Artinya, al-Ghazali menempatkan wahyu Alquran menjadi petunjuk utama atau bahkan satu-satunya dalam tindakan etis, dan dengan keras menghindari intervensi rasio dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar universal tentang petunjuk ajaran Alquran bagi kehidupan manusia (etika mistis lawan dari etika rasional spekulatif).23 Menurut al-Ghazâlî akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan di mana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka secara spontan Ia menolongnya tanpa memikirkan resiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka.24 Etika atau akhlak menurut pandangan al-Ghazali bukanlah pengetahuan (ma’rifah) tentang baik dan buruk, bukan pula pengamalan (fi’il) yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap. Al-Ghazali berpendapat sama dengan Ibn Miskawaih bahwa penyelidikan etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan-kekuatan dan sifat-sifatnya. Tentang klasifikasi jiwa manusia pun al-Ghazali membaginya ke dalam tiga bahagian; daya nafsu, daya berani, dan daya berfikir, sama dengan Ibn Miskawaih.25 Dida Darul Ulum, “Filsafat Etika antara Ibn Miskwaih dan Al-Ghozali”, dalam http://www.darululum.blogspot.com-2006-12-filsafat-etika-antara-ibn-miskawaih dan al-gazali.htm. diakses pada tanggal 27 November 2011. 21 22 23 24 25 K Bertens, Etika, (Cet. I; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1993), h. 13. M. Amin Abdullah, Filsafat Etika Islam: Antara al-Ghazâlî & Kant, (Cet. II; Bandung : Mizan 2002), h. 11. Komaruddin Hidayat, Kontekstualisasi Islam dalam Sejarah, (Cet. I; Jakarta : Paramadina, 1996), h. 22. Dida Darul Ulum, op.cit., 109 Menurut al-Ghazali bahwa watak manusia pada dasarnya ada dalam keadaan seimbang dan yang memperburuk itu adalah lingkungan dan pendidikan. Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu tercantum dalam syariah dan pengetahuan akhlak. Tentang teori Jalan Tengah Ibn Miskawaih, al-Ghazali menyamakannya dengan konsep Jalan Lurus (al-Shirât al-Mustaqîm) yang disebut dalam Alquran dan dinyatakan lebih halus dari pada sehelai rambut dan lebih tajam dari pada mata pisau. Untuk mencapai ini manusia harus memohon petunjuk Allah agar mampu melawan keburukan dan kejahatan dalam hidup ini.26 Al-Ghazali untuk pertama kalinya menghancurkan otoritas Aristoteles dan pada saat yang sama menabur bibit-bibit filsafat mekanika, fondasi metafisika untuk sains modern. Maka kontribusinya itu tidak hanya destruktif, tetapi juga konstruktif. Alih-alih menghambat perkembangan sains, al-Ghazãli adalah seorang agen dalam memfasilitasi kemajuan yang lebih jauh. Sebagai seorang individu, ia telah mencapai untuk pertama kalinya antara tahun 1094 dan 1108 hal-hal yang sama seperti apa dicapai orang-orang Eropa selama lima abad, yaitu akhir abad ke12 hingga abad 17. Dengan demikian, ia mensimbolisasikan individualism (suatu pemikiran yang bernilai pada zaman Renaissance) dalam cara yang paling baik, dan menyerang atau menghancurkan ide-ide bid’ah Aristoteles dan Aristotelianisme dalam tiga tahun, yaitu tahun 1092 hingga 1095. Perlu dicatat bahwa al-Ghazali berbicara pada tataran tinjauan teologi Islam sementara kebanyakan pemikir etika Barat sedikit banyaknya mengambil manfaat dari ide-ide al-Ghazãli. Selain itu, berdasarkan pandangan teologis, dia menolak gagasan kausalitas dalam tindakan etis. Dia tidak dapat membenarkan hubungan kausal antara sanksi dan pahala karena tidak bersifat rasional. Dari pemahaman dasar ini, dia menyatakan bahwa kebaikan dan kejahatan hanya dapat diketahui melalui wahyu dan menolak bahwa perintah-perintah Tuhan dalam Alquran memiliki tujuan tertentu. Akhlak seseorang, di samping bermodal pembawaan sejak lahir, juga dibentuk oleh lingkungan dan perjalanan hidupnya. Nilai-nilai akhlak Islam yang universal bersumber dari wahyu, disebut al-khayr, sementara nilai akhlak regional bersumber dari budaya setempat dan disebut al-ma`rûf, atau sesuatu yang secara umum diketahui masyarakat sebagai kebaikan dan kepatutan.27 Sedangkan akhlak yang bersifat lahir disebut adab, tatakrama, sopan santun atau etika. Selain itu juga terdapat akhlak universal yang berlaku untuk seluruh manusia sepanjang zaman, dan hal tersebut berjalan sesuai dengan keragaman manusia. Dilain sisi, juga dikenal ada akhlak yang spesifik, misalnya akhlak anak kepada orang tua dan sebaliknya, akhlak murid kepada guru dan sebaliknya, akhlak pemimpin kepada yang dipimpin dan sebagainya. Seseorang dapat menjadi pemimpin (al-imâm) dari orang banyak manakala ia memiliki (a) kelebihan dibanding yang lain, yang oleh karena itu ia bisa memberi (b) memiliki keberanian dalam memutuskan sesuatu, dan (c) memiliki kejelian dalam memandang masalah sehingga ia bisa bertindak arif bijaksana. Secara sosial seorang pemimpin adalah penguasa, karena ia memiliki otoritas dalam memutuskan sesuatu yang mengikat orang banyak yang dipimpinnya.28 26 27 28 Ibid., Mahjuddin. Kuliah Akhlaq-Tasawuf . (Cet. II; Jakarta: Kalam Mulian, 1994), h. 21. Pudjowijatno. Etika, Filsafat Tingkah Laku . (Cet. II; Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 35. 110 Menurut etika keagamaan, seorang pemimpin pada hakekatnya adalah pelayan dari orang banyak yang dipimpinnya (Sayyid al-Qawmi Khâdimuhum). Pemimpin yang akhlaknya rendah pada umumnya lebih menekankan dirinya sebagai penguasa, sementara pemimpin yang berakhlak baik lebih menekankan dirinya sebagai pelayan masyarakatnya. Dampak dari keputusan seorang pemimpin akan sangat besar implikasinya pada rakyat yang dipimpin. Jika keputusannya tepat maka kebaikan akan merata kepada rakyatnya, tetapi jika keliru maka rakyat banyak akan menanggung derita karenanya. Oleh karena itu, pemimpin yang baik disebut oleh Nabi dengan sebutan pemimpin yang adil (imâmun `âdil) sementara pemimpin yang buruk digambarkan Alquran dan juga al-Hadîst sebagai pemimpin yang zalim (imâmun zhâlim). Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan sebaliknya zalim artinya menempatkansesuatutidakpada-tempatnya. Kisah dalam Alquran yang menyebut Nabi (Raja) Sulaiman yang memperhatikan suara semut mengandung pelajaran bahwa betapa pun seseorang menjadi pemimpin besar dari negeri besar, tetapi ia tidak boleh melupakan rakyat kecil yang dimisalkan semut itu (Q/27:16). Meneladani kepemimpinan Rasulullah meniscayakan keteladanan yang baik (uswatun hasanah), terutama dalam kehidupan pribadi, seperti; hidup bersih, sederhana dan mengutamakan orang lain. Ini merupakan sebuah alasan yang mengantarkan al-Ghazâlî dianggap sebagai seorang filsuf walaupun dia tidak suka disebut sebagai seorang filsuf. Berpijak dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka pada poin penutup ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berkut : 1. Imam al-Gazali adalah salah seorang tokoh muslim yang lahir di Ghaza li pada tahun 450 H/1058 M, suatu desa dekat Thus di daerah Khurasan (Persia), sekarang dikenal Iran. 2. Kehebatan al-Gazali dibuktikan melalui lahirnya gagasan orisinil yang diterbitkan melalui beberapa kitab karangannya sendiri. 3. Konsep etika al-Gazali berasas pada Alquran dan Sunnah, sedangkan akal/rasionalitas hanya dipandang sebagai instrument argumentatif turunan dari kedua asas tersebut. 111 BAB XV PEMIKIRAN ETIKA MURTADA MUTTAHHARI Etika dalam Islam adalah salah satu bidang yang menjadi perhatian utama. Dalam setiap masyarakat terdapat sosok ulama yang terus membina anggotanya agar akhlak atau etika tetap hidup di tengah-tengah mereka. Bahkan ajaran tentang etika telah banyak dituangkan ke dalam bentuk karya tulis. Di samping internal ummat Islam, di wilayah eksternal Islam pun marak dilakukan kajian tentang tema yang sama. Berbagai teori telah dihasilkan, mulai dari yang berbasis agama, hingga yang menafikannya, dari yang berbasis ego, hingga dari mereka yang berusaha mematikannya. Perbincangan tentang tema etika ini cukup beralasan, sebab setiap manusia pada prinsipnya mengakui berbagai nilai-nilai etis yang ada, seperti; kejujuran, keadilan dan lain-lain. Sehingga dengan alasan tersebut, kita sering mendapatkan ungkapan bahwa seorang pembohong sekalipun pada dasarnya tidak mau dibohongi. Perbedaan pandangan (teori-teori etika) para penganut mazhab-mazhab etika tersebut, akhirnya banyak tergiring ke wilayah hubungan dialogis yang lebih maju. Di sana kita akan disuguhkan sesuatu yang membedakan antara etika yang berlandaskan agama dengan etika yang berbasis teori-teori non Ilāhī, tentang keuniversalannya dan hal-hal lain yang berakaitan dengannya. Salah satu tokoh pemikir Islam yang terkenal, yaitu Murtadā Mutahharī adalah tokoh yang banyak melakukan kajian kritis terhadap berbagai teori etika yang ada. Tidak jarang kita temui dalam karyanya kritik tajam yang dilakukan, penolakan bahkan pelurusan dari berbagai kekeliruan yang terungkap dari teori-teori yang ada di dalam hasil kajiannya tentang etika. A. Biograpi singkat Murtadhā Muthahharī Al-Syahīd Ayātullāh Murtadhā Muthahharī1 adalah seorang filosof, ulama, sufi Syi‘ah kontemporer, serta salah seorang dari ideolog revolusi Islam Iran, yang mempunyai hubungan dekat dengan dua tokoh besar Syi‘ah, yaitu Ayātullāh Rūhullāh Khumainī dan Ayātullāh Muhammad Husain Thabathaba’ī. Murtadhā Muthahharī lahir pada tanggal 2 Pebruari 1920 M, bertepatan dengan tahun 1338 H di desa Fariman, dekat kota Masyhad, Iran. Ayahnya adalah Muhammad Husain Muthahharī, seorang ulama yang cukup terkemuka di kalangan muslim Syi‘ah Iran, yang sekaligus menjadi guru pertamanya.2 Murtadhā Muthahharī memulai sekolah formalnya dengan belajar ilmu-ilmu agama pada usia 12 tahun di hauzah (pesantren) kota Masyhad. Inti studi agamanya adalah bidang fikih. Namun di tempat ini ia menunjukkan kecintaan yang tinggi pada filsafat, irfān (tasawuf), dan teolog, sesuatu yang kemudian ia pelihara sepanjang 1 Untuk selanjutnya ditulis Murtadhā Muthahharī. 2 Murtadhā Muthahharī, The Causes Responsible For Materialist Tendencies in The West, diterjemahkan oleh Akmal Kamil dengan judul, Kritik Islam terhadap Materialisme (Cet. I; Jakarta: Al-Huda Islamic Center, 2005), h. 9. 102 hidupnya.3 Untuk mempelajari materi tersebut, ia dibimbing oleh ahli utamanya Mirza Mehdi Syahidi Razawi. Setelah pembimbingnya wafat, ia kemudian pindah ke Qum pada tahun 1973. Di Qum ia berguru kepada dua tokoh besar Syi‘ah, yaitu Ayātullāh Rūhullāh Khumainī, yang masyhur dengan kuliah-kuliah etikanya yang bernuansa mistis, begitupun dengan hubungan yang ia bangun dengan Ayātullāh Muhammad Husain Thabathaba’ī, seorang mufassir dan filosof.4 Pada tahun 1952, Murtadhā Muthahharī meninggalkan Qum menuju Teheran, tempat ia memulai mengajar logika, filsafat, fiqhi dan ilmu kalam di Madrasah-yi Marvi, dua tahun kemudian ia menjadi dosen di Fakultas Teologi Universitas Teheran, bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Jurusan Filsafat di Universitas tersebut.5 Murtadhā Muthahharī juga bergabung dengan organisasi-organisasi Islam, di antaranya adalah Husainiyah-yi Irsyād yang didirikan pada tahun 1965. Banyak kuliah-kuliahnya yang ia sampaikan lewat organisasi ini, dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku-buku.6 Di samping kesibukannya dalam bidang keilmuan, Murtadhā Muthahharī juga aktif pada kegiatan politik melawan rezim Syah Pahlevi yang dikenal diktator. Ia dikenal sebagai salah satu ideolog dan propagandis gerakan revolusi Islam Iran di bawah kepemimpinan Ayātullāh Rūhullāh Khumainī pada tahun 1979. Murtadhā Muthahharī menunjukkan secara serius dan terbuka sebagai seorang pengikut Imam Khumaini (Pemimpin Spiritual Syi‘ah dua belas), baik secara politis maupun intelektual. ia tampil menyebarkan seruan-seruan politik Imām Khumainī dan mendesak masyarakat Iran untuk mendukungnya dalam setiap khutbah yang beliau sampaikan. 7 Dalam pergerakan politiknya, Murtadhā Muthahharī aktif di berbagai organisasi politik, di antaranya Persatuan Ulama Militan (Jāmi‘ah-yi Ruhaniyāt-i Mubāriz), organisasi yang menghimpun ulama-ulama Syi‘ah Iran yang bertujuan untuk mendukung seruan Revolusi Islam Imam Khumaini dan menggulingkan Syah Reza Pahlevi. Satu bulan menjelang terjadinya revolusi Islam Iran, tepatnya pada tanggal 12 Januari 1979, Murtadhā Muthahharī ditunjuk sebagai ketua Dewan Revolusi (Syurā-yi Inqilāb-i Islāmī) bersama beberapa ulama Syi‘ah lainnya, seperti Ayātullāh Javad Bahonar dan Ayātullāh Husein Behesyti.8 Akhirnya, tiga bulan setelah Revolusi Islam Iran, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1979, setelah memimpin rapat dewan revolusi di kediaman Dr. Tadullāh Shahābi. sebutir peluru yang ditembakkan oleh kelompok furqānī 9 bersarang tepat di kepalanya dengan menembus kelopak matanya. Murtadhā Muthahharī pun mengakhiri aktivitas 3 Hamid Algar, “Hidup dan karya Murtadhā Muthahharī” Pendahuluan dalam Murtadhā Muthahharī, Filsafah alHikmah, diterjemahkan oleh Tim Penerbit Mizan dengan judul, Filsafat Hikmah; Pengantar Pemikiran Shadra (Cet. I; Bandung: Mizan, 2002), h. 30. 4 Muhsin Labib, Para Filosof Sebelum dan Sesudah Shadra (Cet. I; Jakarta: Al-Huda Islamic Center, 2005), h. 278. 5 Murtadhā Muthahharī, Intoduction to Kalam, diterjemahkan oleh Muhammad Ilyas Hasan dengan judul, Mengenal Ilmu Kalam (Cet. I; Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 7. 6 John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, diterjemahkan oleh Eva Y.N. et. All. dengan judul, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Jilid 4 (Cet. II; Bandung: Mizan, 2002), h. 138. 7 Murtadā Mutahharī, The Causes…, op. cit., h. 10. 8 Ibid., h. 10-11. 9 Kelompok furqānī adalah kelompok yang menyebarkan reinterpretasi doktrin Syi’ah secara modern, radikal dan anti ulama. Ia memandang Murtadhā Muthahharī sebagai lawan intelektual yang terberat. Lihat John L. Esposito, loc. cit., 103 politiknya yang mengantarkan ia pada kesyahidan. Ia kemudian dimakamkan di Qum. Imām Khumainī dalam sambutan perkabungannya tak kuasa menahan kesedihan, ia dengan terbata-bata dan berlinang air mata menyatakan “Murtadhā Muthahharī adalah bagian dari dagingku”.10 Perjalanan hidup al-Syahīd Ayātullāh Murtadhā Muthahharī dapat disingkat “Ia lahir, ia berjihad dan ia syāhid”.11 Walaupun Revolusi Islam Iran telah memberi kelayakan bagi Murtadhā Muthahharī sebagai seorang figur politik, tulisan-tulisannyalah yang dengan penuh semangat dipromosikan oleh otoritas revolusioner, yang menjadi warisan utamanya. Karya Murtadhā Muthahharī yang diterbitkan baik dari hasil ceramah maupun tulisannya mencakup lebih dari 200 judul dalam berbagai bidang ilmu, seperti; filsafat, kalām, sejarah, sosiologi, antropologi, etika (akhlāq), usul fiqhi dan fiqhi, ‘irfān (tasawwuf), politik serta ekonomi.12 B. Pemikiran Etika Murtadhā Muthahharī Menurut Murtadhā Muthahharī, perbuatan manusia dapat dibedakan antara perbuatan alami (biasa) dan perbuatan akhlāqī. Perbuatan alami adalah perbuatan yang tidak menjadikan pelakunya menjadi layak puji, misalnya; seorang yang lapar akan makan, yang haus akan minum, yang lelah akan istirahat dan lain-lain. Jenis perbuatan alami ini juga diperbuat oleh binatang.13 Sedang perbuatan akhlāqī adalah perbuatan yang layak untuk dipuji atau disanjung, perbuatan yang identik dengan usaha (ikhtiar). Dalam artian manusia mengakui akan nilai agung suatu perbuatan akhlāqī. Nilai yang dimaksud tidaklah sama dengan harga yang dapat disandingkan atau disejajarkan dengan materi seperti uang atau barang lainnya, sebesar apapun materi tersebut. Nilai yang dimaksud berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam diri manusia.14 Perbuatan akhlāqī tersebut berbeda dan jauh lebih mulia dibanding perbuatan alami di atas. Perbuatan akhlāqī inilah yang biasa juga disebut perbuatan manusiawi, yang lebih bernilai dari sekedar perbuatan alami atau hewani. Di dalamnya terdapat kemerdekaan, salah satu nilai yang melampaui aspek hewani manusia dan nilai materil. Olehnya itu akan kita jumpai manusia yang lebih memilih jalan hidup sulit dengan alasan yang penting ia merdeka dan tidak diperbudak.15 Hadirnya perbuatan akhlāqī tersebut disebabkan karena manusia adalah maujud yang memiliki dua sisi, ia berada di alam materi dan metafisik, memiliki ruh dan jasad. Di satu sisi manusia sangatlah tinggi, di sisi lain ia mempunyai kesamaan dengan binatang dan maujud lainnya yang bergantung pada petunjuk ilham (naluri, fitrah). Olehnya itu manusia memiliki potensi lebih besar untuk mencapai kesempurnaan di banding hewan. Mereka yang 10 Ibid., 11 Murtadhā Muthahharī, Manusia dan Agama; Membumikan Kitab Suci (Cet. I; Bandung: Mizan 2007), h. 44. 12 Muhsin Labib, op. cit., h. 280. 13 Murtadhā Muthahharī, Falsafe Akhlāq, diterjemahkan oleh Faruq bin Dhiya’ dengan judul, Filsafat Akhlak (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 30. Dalam buku tersebut istilah etika dan akhlak disamakan oleh Murtadā Mutahharī. 14 Ibid., h. 12. 15 Murtadhā Muthahharī, Falsafe Akhlāq, ibid., h. 30. Murtadhā Muthahharī, Perfect Man, diterjemahkan oleh M. Hashem dengan judul, Manusia Sempurna; Pandangan Islam tentang Hakikat Manusia (Cet. II; Jakarta: Lentera, 1994), h. 37. 104 lebih sempurna adalah yang lebih banyak bergantung pada petunjuk daya fikir dan akal (yang dimaksud adalah akal dan hati).16 Lewat potensi internal manusia yang telah Allah anugerahkan menjadikan manusia harus memilih sendiri sistem pendidikan dan moralitas yang dianggapnya perlu. Para pembimbing (para Nabi dan Rasul) didatangkan kepada mereka untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada fitrah alamiahnya. Dalam istilah Mullā Shadrā, Tuhan telah memberi manusia bukti-bukti kebenaran lewat dua jalur, yaitu jalur internal berupa akal (akal yang dimaksud adalah gabungan antara rasio dan hati) dan eksternal berupa kehadiran para Rasul dan Nabi. 17 Dalam hadis Nabi saw. bersabda: ﺑﻌﺜﺖ ﻻﺗﻤﻢ ﺣﺴﻦ اﻻﺧﻼق: ﻗﺎل.وﺣﺪﺛﻨﻰ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﮫ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﮫ ان رﺳﻮل ﷲ ﺻﻌﻢ Artinya: “Dan telah memberitakan kepadaku dari Malik, sungguh ia telah menyampaikannya bahwa sanya Rasulullah saw. bersabda “Aku diutus untuk menyempurnakan kabaikan akhlak”.18 Maksudnya pada mulanya manusia diciptakan dalam keadaan tidak sempurna, kemudian didatangkanlah sistem akhlāqī untuk menghilangkan kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada fitrah dasar manusia tersebut, sehingga manusia dapat mencapai kesempurnaan dengan kekuatan berfikir dan kehendak sendirinya.19 Menurut Murtadā Mutahharī, kemanusiaan dan akhlak tidak akan memiliki arti apabila tidak dibarengi dengan pengenalan terhadap Tuhan (ma‘rifat Allāh). Artinya, tauhīd dalam pandangannya adalah akar dari prinsip akhlak orang beriman yang tidak akan dapat dicabut oleh kekuatan manapun. Bukan karena alasan bertaklid, didikte, terhipnotis ataupun alasan lainnya, karena semuanya sangat mudah terbantahkan sekaligus mempunyai akibat yang sangat berbahaya bagi kelangsungan akhlak manusia.20 Allah berfirman: َﻀﺮِبُ ٱ ﱠ ُ ۡٱﻷَﻣۡ ﺜَﺎ َل ۡ ﺗ ُۡﺆﺗِﻲٓ أُ ُﻛﻠَﮭَﺎ ُﻛ ﱠﻞ ﺣِﯿ ِۢﻦ ﺑِﺈ ِذۡ ِن َرﺑﱢ َﮭ ۗﺎ َوﯾ٢٤ ﺴ َﻤﺎٓ ِء ِﺖ َوﻓ َۡﺮ ُﻋﮭَﺎ ﻓِﻲ ٱﻟ ﱠٞ َﺻﻠُﮭَﺎ ﺛَﺎﺑ ۡ ﺿﺮَبَ ٱ ﱠ ُ َﻣﺜ َٗﻼ َﻛﻠِﻤَﺔٗ طَﯿﱢﺒَﺔٗ َﻛﺸَﺠَ ﺮَةٖ طَﯿﱢﺒَ ٍﺔ أ َ َأَﻟَﻢۡ ﺗَ َﺮ ﻛَﯿۡ ﻒ ﺖ ﻓِﻲ ِ ِ ﯾُﺜَﺒﱢﺖُ ٱ ﱠ ُ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَا َﻣﻨُﻮ ْا ﺑِﭑﻟۡ ﻘ َۡﻮ ِل ٱﻟﺜ ﱠﺎﺑ٢٦ ٖض ﻣَﺎ ﻟَﮭَﺎ ﻣِﻦ ﻗَﺮَار ِ ق ۡٱﻷ َۡر ِ َو َﻣﺜَ ُﻞ َﻛﻠِ َﻤ ٍﺔ ﺧَ ﺒِﯿﺜَﺔٖ َﻛﺸَﺠَ َﺮ ٍة ﺧَ ﺒِﯿﺜَ ٍﺔ ۡٱﺟﺘُﺜ ۡﱠﺖ ﻣِﻦ ﻓ َۡﻮ٢٥ َس ﻟَ َﻌﻠﱠﮭُﻢۡ ﯾَﺘَ َﺬ ﱠﻛﺮُون ِ ﻟِﻠﻨ ﱠﺎ ٢٧ ﺸﺎٓ ُء َ َﻀ ﱡﻞ ٱ ﱠ ُ ٱﻟ ﱠٰﻈﻠِﻤِﯿﻦَۚ َوﯾَﻔۡ َﻌ ُﻞ ٱ ﱠ ُ ﻣَﺎ ﯾ ِ ُ ٱﻷ ِﺧ َﺮ ۖ ِة َوﯾ ٓ ۡ ٱﻟۡ ﺤَ ﯿَﻮٰ ِة ٱﻟ ﱡﺪ ۡﻧﯿَﺎ َوﻓِﻲ Terjemahnya: “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang Telah dicabut dengan akarakarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang 16 Murtadhā Muthahharī, Falsafe Akhlāq, op. cit., h. 54. Murtadhā Muthahharī, Khatemiat, diterjemahkan oleh Muhammad Jawad Bafaqih dengan judul, Kenabian Terakhir (Cet. V; Jakarta: Lentera, 1991), h. 61. 17 Agus Efendi, “Mengenal Mullā Shadrā” dalam Sukardi (ed.), Kuliah-Kuliah Tasawwuf (Cet. I; Bandung, Pustaka Hidayah, 2000), h. 199. 18 Imam Malik, Muatta’ Mālik, (Kitāb al-jāmi‘, Mausū‘ah al-hadīs al-syarīf) 19 Murtadhā Muthahharī, Falsafe Akhlāq, op. cit., h. 54. 20 Ibid., h. 58. 105 beriman dengan Ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orangorang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki”. (QS. Ibrahim (14): 24-27).21 Bahaya yang mengancam kelanggengan akhlak manusia tersebut disebabkan oleh masalah ego di dalam akhlak yang tidak terkelola dengan baik, ego yang meyakini adanya pembatasan dan penyempitan. Sedang manusia yang egois adalah manusia yang mengakui batasan dan selalu menghendaki apa yang ada di luar batasan dikorbankan untuk yang ada dalam batasan. Pandangan Nitsche dan kaum komunis misalnya, pokok akhlak mereka tidak lebih dari satu, yaitu memelihara kehidupan individualisme yang berdasar pada ego. Sementara sistem akhlak dan pendidikan di dunia mempunyai istilah keluhuran akhlak, keadilan, kejujuran, amanah dan lainnya yang bertentangan dengan egoisme individual, yaitu sejenis perlawanan terhadap ego.22 Menurut Murtadhā Muthahharī, ego dapat diklasifikasi ke dalam tiga jenis sebagai berikut: 1. Ego individualisme. Sebagian manusia itu egois dan angkuh, mereka benar-benar hidup sendirian. Efek yang ditimbulkan adalah perlakuan keji, moral yang rusak, perampasan hak orang lain dan kezaliman lainnya. 2. Ego kekeluargaan atau kelompok. Ego dalam wilayah ini terkesan tampil sebagai orang yang adil di lingkungan keluarga atau kelompoknya, namun di luar wilayah tersebut anda akan menyaksikan tindakannya yang melampaui batas. Misalnya, di antara sesama anggota perampok, mereka mampu menampakkan sifat saling mengasihi, lemah lembut, jujur, berbuat adil, saling memberi informasi yang benar dan lain-lain. 3. Ego kebangsaan. Ego ini lebih luas dari dua ego sebelumnya. Pada bangsanya ia dapat bersikap jujur, ia bukan pencuri, penipu, pembunuh, dan pelaku perbuatan zalim lainnya. Tetapi seiring semua itu, akan kita dapati suatu bangsa yang menzalimi bangsa lain. Semua keluhuran budi, kejujuran, perdamaian, kasih sayang, keadilan dan melindungi Negara-negara lemah hanya didasarkan pada alasan apabila menguntungkan Negara adikuasa.23 Untuk melawan ego tersebut, terdapat dua pilihan yang biasa ditempuh oleh manusia; pertama, melemahkan ego seperti yang dilakukan oleh penganut Hindu, Budha ataupun beberapa orang dari kelompok Islam sendiri. Kedua, memperluas batasan ego hingga mencakup seluruh maujud alam, tanpa batas. Bagi Muthahharī, Islam hanya dibolehkan menempuh cara yang kedua, sehingga di satu sisi Islam mewajibkan ummatnya untuk melawan ego, sekaligus mewajibkan agar mempertahankan hak dan kehormatan dirinya. Dengan demikian wilayah akhlāqī tidaklah terbatas pada individu atau daerah tertentu, tetapi meliputi seluruhnya, termasuk di dalamnya muslim dan non muslim. Hal ini dapat kita perhatikan pada ajarannya yang membolehkan membalas orang yang menzalimi kita, tetapi hanyalah sebatas kejahatan yang mereka lakukan. Islam melarang melakukan pembalasan yang melampaui batas.24 21 Depertemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, op. cit., h. 258. 22 Murtadā Mutahharī, Falsafe Akhlāq, op. cit., h. 55. 23 Ibid., h. 59-62. 24 Ibid., h. 64-65. 106 Olehnya itu, Murtadhā Muthahharī menolak keras pandangan yang menyatakan bahwa akhlak dapat digapai dan diwujudkan begitupun ego dapat dibantah meskipun tanpa bersandar pada prinsip tauhīd (iman dan ma‘rifat Allāh).25 Menurutnya teori yang paling pas bagi akhlak adalah teori penyembahan. Pilihan “teori penyembahan” Murtadhā Muthahharī di atas yang tidak memisahkan antara akhlak dan agama adalah hasil perolehan dari studi kritis yang ia lakukan –antara lain– atas teori-teori akhlak yang memisahkan maupun yang membuka peluang pemisahan pada keduanya, misalnya:26 a. Pandangan orang yang beranggapan bahwa panggilan intuitiflah sebagai taklif yang bersumber dari dalam internal manusia, bukan sesuatu yang yang eksternal. Menurut Murtadhā Muthahharī, di samping jiwa mengetahui taklif, ia juga mengetahui mukallif, yang ke semuanya berujung pada pengenalan Allah (kesadaran akan ketauhīdan). Intuisi tidak hanya memerintah, tetapi juga mengetahui siapa yang memerintah.27 b. Pandangan mazhab estetisme, yaitu mazhab yang berpandangan bahwa akhlak termasuk dalam kategori estetik, keindahan. Menurut Murtadhā Muthahharī, manusia secara sadar memahami sumber mata air keindahan (yaitu Allah), sehingga manusia pun pada gilirannya akan melihat dari sudut pandang-Nya bahwa semua kehendak dan keridhaan mata air keindahan itu adalah indah pula.28 c. Pandangan orang yang menyatakan bahwa akhlak merupakan kategori cinta. Menurut Murtadhā Muthahharī, bagaimana mungkin manusia akan mencintai sesuatu atau seseorang yang secara keseluruhan berbeda dengan dirinya, yang tidak memiliki keterikatan atau hubungan apapun? Mencintai sesuatu sama dengan kecintaannya pada diri sendiri merupakan kejadian yang didasari oleh logika Ilāhiyah, yang dinamakan taklif Ilāhiyah. Manusia dengan mata batinnya merasakan bahwa “Kekasih Sejatinya” menginginkan perbuatan tertentu, dan Allah menyukai perbuatan-perbuatan tersebut. Argumen Murtadhā Muthahharī di atas menunjukkan bahwa perwujudan semua kejadian di alam ini merupakan perwujudan dari keagungan, keindahan dan kemuliaan Allah. Segala sesuatu berasal dari-Nya, begitupun akan kembali kepada-Nya (Allah adalah wujud, sedang makhluk adalah maujud).29 25 Muhammad Abduh, Syarh Nahj al-Balāgah, diterjemahkan oleh Muhammad Bagir dengan judul, Mutiara Nahj al-Balāgah: Wacana dan Surat-surat Imam Ali, (Cet. III; Bandung: Mizan, 2003), h. 22. 26 Teori-teori akhlak yang ada tidak penulis tampilkan secara utuh karena yang penulis tekankan adalah inti pelurusan yang dilakukan Muthahharī atas teori-teori tersebut. 27 Ibid, h. 143. 28 Murtadā Mutahharī, Falsafe Akhlāq, op. cit., h. 145. 29 Di wilayah inilah para filosof muslim memperbincangkan tentang teori emanasi (al-faud), kebaikan dan keburukan serta segala yang berkaitan dengannya. Agar tidak menyimpang dari prinsip tauhid (tidak syirik), poin-poin penting tentang konsep wujud - dalam pandangan Mulla Sadra dan para filosof muslim sebelumnya - patut diperhatikan, yaitu; a) hakikat ada adalah ada, b) ada bukan tiada, c) ada dan tidak ada tidak mungkin bertemu, d) hakikat ada adalah wajib ada, e) hakikat tiada adalah tiada dan tidak mungkin bertemu ada, f) keterbatasan (ketidaksempurnaan) ditimbulkan oleh adanya yang berposisi sebagai akibat g) akibat yang ditimbulkan oleh sebab yang juga merupakan sebab, akan tidak sempurna dibanding sebabnya yang juga tidak sempurna. Untuk penjelasannya lihat Hasan Abu Ammar, Akidah Syi‘ah Seri Tauhid Rasionalisme dan Alam Pemikiran Filsafat Islam (Cet. II; Jakarta: Yayasan Mulla Shadra, 2002), h. 199. Lihat juga Murtadhā Muthahharī, Filsafah al-Hikmah, op. cit. Murtadhā Muthahharī, Muhammad Husain Thabathabā’i, 107 Menurutnya setiap perbuatan akhlāqī adalah sejenis tindakan ibadah atau penyembahan yang berada di alam bawah sadar, di mana setiap manusia mengenal Tuhannya melalui fitrahnya. Secara fitrah manusia mengangap mulia perbuatan akhlāqī, sekalipun bertentangan dengan logika alami dan logika akal praktisnya yang mengajarkan manusia agar memelihara kepentingan individualnya.30 Menurut Murtadhā Muthahharī, manakala perasaan alam bawah sadar yang berubah menjadi alam sadar, maka semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai perbuatan akhlāqī. Ketika program hidup manusia berjalan atas dasar taklif dan keridhaan Allah, maka manusia telah menjadi manusia yang berakhlak lagi suci.31 Orang beriman adalah orang yang tidak membeda-bedakan antara keluarga, kelompok, agama dan seluruh makhluk dalam melaksanakan keluhuran akhlak. Segala sesuatu baginya adalah milik Allah. Di mana saja gagasan keagaman selalu memberikan nilai kesucian padanya. Segala perbuatannya tercermin dalam ungkapan ayat berikut: ١٦٢ َي َو َﻣﻤَﺎﺗِﻲ ِ ﱠ ِ َربﱢ ٱﻟۡ َٰﻌﻠَﻤِﯿﻦ َ ﺴﻜِﻲ َوﻣ َۡﺤﯿَﺎ ُ ُﺻ َﻼﺗِﻲ َوﻧ َ ﻗُﻞۡ إِنﱠ Terjemahnya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (QS. al-An‘am (6): 162).32 Manusia yang memanusiakan dirinya dengan perbuatan akhlāqī dengan landasan tauhīd seperti kandungan ayat di atas adalah manusia teladan, unggul lagi luhur, manusia yang sempurna dalam keimanannya. Dalam istilah Muhyiddīn ‘Arabī al-Andalusī Tā’ī (Ibnu Arabi) disebut sebagai manusia sempurna (insān kāmil).33 Pribadi inilah yang tercermin dalam pribadi luhur Nabi Muhammad saw. dan ahl al-baīt (keluarga spiritual) Nabi yang disucikan sesuci-sucinya,34 begitupun dua belas Imam yang ma’sūm35 dari keturunan Nabi, sebagaimana yang diyakini oleh Mazhab Syi’ah dua belas (Isnā ‘Asyariyah). Imam Ali misalnya, di siang hari ia bergabung dan bergembira dengan para sahabatnya, bahkan terkadang bersenda gurau, sementara pada malam hari ia berlinang air mata dalam ibadahnya di mihrab. Di antara kalimat dari rintihan doa yang cukup panjang Imam Ali – yang dikenal dengan sebutan doa Kumail- sebagai berikut: ھﺒﻨﻲ ﯾﺎ اﻟﮭﻲ ﺻﺒﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﺬﺑﻚ ﻓﻜﯿﻒ اﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﻗﻚ. ھﺒﻨﻲ ﯾﺎ اﻟﮭﻲ ﺻﺒﺮت ﻋﻠﻰ ﺣﺮ ﻧﺎرك ﻓﻜﯿﻒ اﺻﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻛﺮاﻣﺘﻚ. Ayātullāh Khumainī, Light Within Me, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan dengan judul, Menggapai Gemerlap Cahaya Ilahi (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2008), h. 251. Dan buku-buku filsafat Islam lainnya. 30 Murtadhā Muthahharī, Falsafe Akhlāq, op. cit. h. 139. 31 Dalam Alquran dijelaskan bahwa seluruh alam ini merupakan maifestasi (tajalli) Tuhan. Dunia eksternal sebagai ayat dan dunia internal disebutnya sebagai jiwa. Lihat Murtadā Mutahharī, Manusia dan Agama, op. cit., h. 125. Di antara ayatnya adalah sebagai berikut: Terjemahnya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (Q.S. al-Fussilat (41): 53). 32 Depertemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, op. cit., h. 1. 33 Murtadhā Muthahharī, Perfect Man, op. cit., h. 22. 34 Dalam Al-Qur’ān Allah Berfiman. Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahl al-baīt dan membersihkan kamu sesuci-sucinya”. (Q.S. Al-Ahzab (33): 33). 35 Istilah ma’sūm dalam pandangan Syi‘ah tidak terlepas dari ikhtiar manusia, bukan sesuatu yang determinis. Lihat misalnya dalam Murtadhā Muthahharī, Khatemiat, op. cit. 108 Artinya: “Tuhanku! seandainya aku dapat bersabar menerima siksa-Mu, bagaimana mungkin aku dapat bersabar memikul derita berpisah dengan-Mu”?. “Tuhanku Sekiranya aku mampu bertahan dari jilatan api Neraka-Mu yang tidak terbayang panasnya, namun bagaimanakah aku dapat bersabar memikul derita bila tidak memandang kemuliaan-Mu”?36 ﯾﺎ ﻣﻦ اﺳﻤﮫ دواء وذﻛﺮه ﺷﻔﺎء وطﺎﻋﺘﮫ ﻏﻨﺎء. ارﺣﻢ ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﮫ اﻟﺮﺟﺎء و ﺳﻼﺣﮫ اﻟﺒﻜﺎء. Artinya: “Wahai yang nama-Nya adalah obat, mengingat-Nya adalah penyembuh dan ketaatan kepada-Nya adalah kekayaan! Kasihanilah hamba yang modal utamanya adalah harapan, dan senjatanya hanyalah tangisan”.37 Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Al-Syahīd Ayātullāh Murtadhā Muthahharī lahir di desa Fariman, tanggal 2 Pebruari 1920 M/ 1338 H dan wafat sebagai syāhid’ pada tanggal 1 Mei 1979. Inti studi agamanya adalah bidang fikih, namun ia menunjukkan kecintaan yang tinggi pada filsafat, irfan (tasawuf), dan teolog, sesuatu yang kemudian ia pelihara sepanjang hidupnya. Menurut Murtadhā Muthahharī, perbuatan manusia dapat dibedakan antara perbuatan alami (biasa) dan perbuatan akhlāqī. Perbuatan alami adalah perbuatan yang tidak menjadikan pelakunya menjadi layak puji, jenis perbuatan alami ini juga diperbuat oleh binatang. Sedang perbuatan akhlāqī adalah perbuatan yang layak untuk dipuji atau disanjung, perbuatan yang identik dengan usaha (ikhtiar). Dalam artian manusia mengakui akan nilai agung suatu perbuatan akhlāqī yang tidak dapat diukur dengan materi; b. Hadirnya perbuatan akhlāqī disebabkan karena manusia adalah maujud yang memiliki dua sisi, ia berada di alam materi dan metafisik, memiliki ruh dan jasad. Olehnya itu menurut “teori penyembahan” Murtadhā Muthahharī, akhlak tidak akan memiliki arti apabila tidak dibarengi dengan pengenalan Tuhan (ma‘rifat Allāh). Artinya, tauhīd dalam pandangannya adalah akar dari prinsip akhlak orang beriman yang tidak akan dapat dicabut oleh kekuatan manapun; c. Manakala perasaan alam bawah sadar yang berubah menjadi alam sadar, maka semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai perbuatan akhlāqī. Itulah yang tercermin pada pribadi manusia-manusia suci. 36 Syaikh ‘Abbas al-Qummi, Mafātih al-Jinān (t.c.; Jakarta: Al-Huda, 2008), h. 221-222. 37 Ibid., h. 227. 109