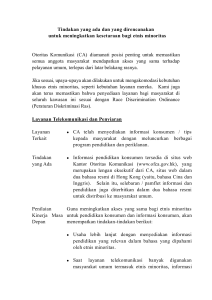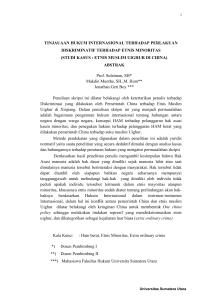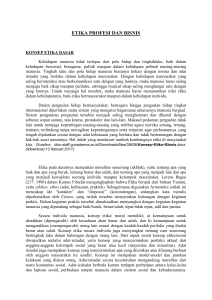BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam studi hak asasi
advertisement

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam studi hak asasi manusia (HAM), negara diletakkan pada posisi sebagai pengemban (duty bearer) tanggung jawab dan kewajiban pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM. Dalam konteks demokrasi, isu minoritas dapat diletakkan dalam dua persoalan utama; pertama, relasi mayoritasminoritas yang berkecenderungan meletakkan mayoritas sebagai tiran1; kedua, relasi minoritas dengan negara dimana sistem di dalamnya cenderung mengeksklusi kelompok minoritas2, baik secara disengaja maupun tidak. Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah yang kedua, yaitu bagaimana Jemaah Syiah, sebagai minoritas yang rentan terhadap eksklusi, mengambil pilihan-pilihan politik untuk memperjuangkan representasi mereka dalam sistem demokrasi di Indonesia. Representasi merupakan salah satu isu utama dalam studi politik dan demokrasi. Telah banyak penelitian dan analisis mengenai representasi di dalam demokrasi. Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan oleh para ahli untuk menjawab isu-isu keterwakilan (representativeness) mulai dari representasi melalui individu anggota legislatif, oleh partai politik, serta oleh pemerintahan. 1 Beberapa pemikir besar memberikan sinyalemen sekaligus kritik (beberapa mengkhawatirkan) bahwa demokrasi kemudian menjadi arena bagi tirani mayoritas. Plato dalam Politea dan Republic menyebut “tyrannical majoritarianism” sebagai salah satu masalah radikal demokrasi. Demikian juga Tocqueville, dia menyebut tirani minoritas terjadi di dalam demokrasi jika majority rule tidak bersanding dengan minority rights. John Adams, Hegel, Hannah Arendt, dan beberapa pemikir lain menyebut tirani mayoritas sebagai masalah pokok demokrasi. Lihat Barker, Tragedy and Citizenship: Conflict, Reconciliation, and Democracy from Haemon to Hegel (New York: State University of New York Press, 2009), hlm. 50. Juga Boni Hargens, “Tirani Popularitas”, KOMPAS, 1 Agustus 2013. Selengkapnya baca juga Boesche, Theories of Tyranny: From Plato to Arendt (Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 1996). 2 Seperti pandangan Tocqueville, negara demokratis yang tidak bisa menjembatani hak-hak individual (individual rights) seluruh warga negara dalam majority rule akan melanggar hakhak minoritas. Tocqueville, Democracy in America (Chicago: University of Chicago Press, 2000), ch. XV, book 1. 1 Atas isu epistemik representasi, terdapat tiga penjelasan yang coba diajukan oleh beberapa ahli melalui beberapa fokus studi yang berbeda. Pada fase pertama, studi awal representasi Michigan yang mengaitkan antara konstituen dan perwakilan/representatifnya. Studi ini kelanjutan dari perdebatan lama atas model perwakilan wali-delegasi dalam sistem Pemilu Single Majority Member. Penelitian ini membandingkan pendapat konstituen dengan para legislator terpilih dari distrik-distrik, dan menghasilkan hasil empiris campuran, terutama dalam kasus-kasus partai-partai di Eropa.3 Pada fase kedua studi tentang representasi, penelitian-penelitian yang ada menggeser fokus lebih pada hubungan antara pemilik suara dengan partaipartai yang mereka pilih, bukan dengan anggota legislatif secara individual. Penelitian tersebut menggambarkan teori the ruling party yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam representasi politik.4 Model pemerintahan partai ini tampaknya lebih relevan untuk sistem parlementer dengan partai-partai politik yang kuat.5 Di negara-negara dengan sistem parlementer ini, partai merupakan aktor politik utama, bukan kandidat. Dalam model pemerintahan partai ini dibangun kesepakatan antara pemilih dan partai yang dipilih mereka. Calon-calon dipilih oleh elit partai, bukan melalui pilihan terbuka. Dengan demikian para calon itu merupakan wakil partai. Model pemerintahan dengan tanggung partai ini mengasumsikan bahwa para anggota sebuah partai yang menjadi delegasi di parlemen bertindak secara serempak.6 Suara partai di dalam parlemen maujud sebagai satu blok, meskipun barangkali dalam Miller, W., dan Stokes, D. 1963. “Constituency influence in Congress”. American Political Science Review 57: 45-56. Lihat juga McAllister, I. 1991. “Party elites, voters and political attitudes: Testing three explanations for mass-elite differences”. Canadian Journal of Political Science 24: 237-268. 4 Beberapa di antaranya dilakukan oleh Rose (1974), antara lain melalui publikasinya yang berjudul Problems of Party Government. London: Macmillan. Juga Castles, F., and Wildenmann, R. (Eds.), “Visions and Realities of Party Government”, (Berlin: Walter de Gruyter and Co., 1986) 5 Thomassen (1976), Dalton (1985), Holmberg (1989), Esaiasson dan Holmberg (1996); Matthews dan Valen (1999). Lihat Russell J. Dalton, David M. Farrell dan Ian McAllister, “The Dynamics of Political Representation” (Amsterdam: Pallas Publications-Amsterdam University Press, Amsterdam, 2011), hlm. 21-38 6 Bowler, S., Farrell, D., and Katz R., Party Discipline and Parliamentary Government, (Columbus, OH: Ohio State University Press, 1999). 3 2 proses internal partai tersebut sebelumnya terjadi perdebatan sengit sebelum akhirnya pilihan partai diputuskan. Partai melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan melalui kontrol partai di lembaga legislatif tingkat nasional. Singkatnya, partai menyediakan pilihan kepada pemilik kontrol langsung atas tindakan para legislator dan urusan-urusan pemerintahan, dan tidak menyediakan representasi berbasis pilihan-pilihan konstituen. Analog dengan itu, Sartori (1968) menegaskan sebuah highlight bahwa representasi warga negara oleh dan melalui partai dalam demokrasi Barat merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari.7 Pada fase ketiga, studi tentang representasi tidak lagi berfokus pada representasi berbasis konstituensi dan representasi melalui partai politik, namun juga di dalam pemerintahan. Singkatnya, representasi tidak hanya soal bagaimana legislator mewakili konstituennya dan bagaimana partai politik merepresentasi pemilihnya. Akan tetapi, fokus penelitan-penelitian mengenai representasi kemudian diperluas, yaitu berangkat dari pertanyaan dasar bagaimana dan sejauh mana pemerintah merepresentasikan warga yang memilih dan memberikan mandat kepada mereka.8 Salah satu penelitian tentang representasi pada fase ini dilakukan oleh Przeworski, et.al. (1999). Di antara yang disoal oleh Przeworski adalah pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah pemilih mendapati pemerintahan yang menurut mereka sebangun dengan pilihan-pilihan kebijakan yang mereka inginkan? Apakah representasi berfungsi melalui pertimbanganpertimbangan prospektif atau menilai dengan pertimbangan-pertimbangan Sartori, G. 1968. “Representational systems”. International Encyclopedia of the Social Sciences 13: 470-475. 8 Powell ( 2000; juga Huber dan Powell 1994) adalah peneliti pertama yang membandingkan posisi Kiri - Kanan pemilih (dari survei opini publik) dengan posisi Kiri - Kanan partai-partai koalisi (dari survei ahli) di negara-negara demokrasi Barat. Dia menemukan tingkat kesesuaian yang bervariasi antara “posisi” pemilih dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Sejak itu beberapa penelitian telah menggunakan data-data kuantitatif untuk membandingkan kesesuaian antara warga dengan pemerintah, seperti Klingemann et al (1994). McDonald dan Budge (2005). Lihat Russell J. Dalton, David M. Farrell dan Ian McAllister. Op.cit, hlm. 21-38 7 3 retrospektif dan kemudian meminta pertanggungjawaban mereka pada saat pemilu?9 Perkembangan studi representasi lebih banyak memberikan tekanan fokus pada pihak yang mewakili (representatives) dan tidak pada yang diwakili. Tekanannya, apakah pihak-pihak yang mewakili, entah namanya legislator, partai politik, atau pemerintah, mengambil pilihan-pilihan kebijakan yang kongruen dengan kehendak dan kepentingan rakyatnya. Kata kunci pokok sebagai momen sentral dari representasi politik tersebut adalah pemilihan umum.10 Pemilihan umum merupakan starting point untuk mengukur representasi politik tersebut, baik pada aspek yang mewakili maupun yang diwakili.11 Perkembangan studi politik mengenai representasi tersebut memberikan ruang bagi studi mengenai ekspresi pilihan-pilihan warga negara dalam representasi politik sebagai proses yang terus berlangsung (ongoing process), dan bukan even tunggal yang sekali selesai. Dalam konteks Indonesia, salah satu persoalan paling serius yang dicatat oleh studi Demos dalam rangka melihat bagaimana demokrasi dan demokrasi bekerja adalah masalah representasi politik.12 Representasi politik yang dinilai paling parah kualitasnya adalah representasi melalui partai politik, dan pada ujungnya juga berimplikasi pada rendahnya kualitas pemilu dari kaca mata representasi popular. Partai politik peserta pemilu memang tumbuh dan bekerja, namun parpol tidak merepresentasikan kepentingan-kepentingan konstituen dan isu-isu vital masyarakat. Pemilu memang dilaksanakan secara 9 Przeworski, A., Stokes, S., and Manin, B. (Eds.), Democracy, Accountability, and Representation, (New York: Cambridge University Press, 1999). 10 Hal ini tentu saja disandarkan pada realitas faktual dan teoretik bahwa pemilu merupakan aspek esensial demokrasi, yang menjadi saluran untuk, paling tidak, regularitas pemilihan pemimpin oleh warga negara serta hak pilih untuk seluruh warga negara (universal sufferage). 11 Dalam konteks ini, beberapa pemikir menyebut representasi politik demikian sebagai responsiveness atau policy congruence, lihat antara lain Powell (2000). Titik tekannya pada apakah pilihan-pilihan kebijakan yang diinginkan oleh warga negara tergambar dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, atau lebih lanjut, apakah ada kesebangunan kebijakan antara warga negara dengan pemerintah negara. Aspek ini dipandang sebagai indikator utama untuk menilai kualitas sebuah demokrasi. Lihat Diamond and Morlino (2005). 12 Di samping masalah representasi, juga mengemuka: masalah jaminan kebebasan dan hak-hak dasar khususnya ekonomi, sosial dan budaya, masalah oligarki demokrasi, masalah agen perubahan yang mengambang, masalah lokalisasi politik yang tidak menyatukan, dan masalah fragmentasi agen-agen gerakan demokrasi. 4 regular dan menghasilkan keterpilihan wakil-wakil yang duduk di lembaga legislatif, khususnya. Namun, kenyataannya wakil-wakil tersebut sangat minim dalam merepresentasikan kepentingan-kepentingan publik dan lebih dominan didorong oleh kepentingan-kepentingan personal dan elitis. Situasi representasi politik demikian dicatat sebagai defisit demokrasi Indonesia yang paling serius.13 Salah satu isu utama representasi politik di Indonesia adalah representasi kelompok-kelompok minoritas, dimana mereka tidak saja tereksklusi dari politik Indonesia yang lebih banyak bekerja dalam logika mayoritarianisme, namun bahkan menjadi objek dari tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi, seperti minoritas Syi’ah di Sampang yang menjadi korban penyerangan, pembakaran tempat tinggal dan rumah ibadah, dan penyerbuan yang berakibat pada hilangnya nyawa. Dengan spektrum paradigmatik yang similar dengan studi-studi tentang representasi tersebut, peneliti melihat bahwa persoalan diskriminasi, persekusi, intoleransi, dan pelanggaran atas hak-hak dasar kelompok minoritas agama/keyakinan, khususnya Jemaah Syi’ah Sampang, dapat dilihat dari perspektif representasi politik untuk memastikan terjaminnya hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Dalam konteks studi ini, representasi politik tidak hanya merujuk pada bagaimana lembaga-lembaga politik bekerja dan berfungsi mewakili kepentingan-kepentingan kelompok minoritas, namun lebih dari itu mengacu pada bagaimana kelompok minoritas menggiatkan civic engagement, baik secara individual maupun secara kolektif, dalam saluran-saluran politik yang ada, khususnya partai politik, untuk memperjuangkan representasi politik untuk menjamin hak-hak dan memenuhi kepentingan-kepentingan mereka. Untuk itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Jemaah Syiah di Indonesia memperjuangkan politik inklusi demokratis bekerja untuk menjamin representasi politik mereka, dan pada gilirannya menjamin pemenuhan hak-hak dasar dan kepentingan-kepentingan 13 Lihat Otto Adi Yulianto, “Representasi Semu”, dalam AE Priyono, et.al. Op.cit, hal 69-102. 5 kelompok minoritas Jemaah Syi’ah pasca Kasus Sampang. Pada akhirnya studi ini akan melihat bagaimana politik inklusi demokratis dioptimalkan oleh Jema’ah Syi’ah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar dan kepentingan-kepentingan minoritas mereka pasca Kasus Sampang. Penelitian mengenai Syi’ah dengan menggunakan kacamata representasi politik merupakan sesuatu yang baru dan penting untuk dilakukan, paling tidak karena dua alasan. Pertama, studi-studi ilmiah yang ada tentang Syi’ah selama ini lebih banyak mengambil perspektif yang makro tentang Syi’ah baik teologis maupun kultural serta perjuangan Syi’ah di berbagai bidang. Kedua, Syi’ah merupakan bagian integral dari Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, memahami Syi’ah dengan lebih baik dari kacamata politik akan membuka ruang bagi hidup setiap manusia, makhluk politik (zoon politicon), secara peaceful co-existence. B. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian (research question) dapat dinyatakan dalam pertanyaan: Bagaimana pilihan-pilihan Jemaah syi’ah Sampang dalam memperjuangkan representasi politik mereka dalam politik inklusi demokratis? C. Tujuan Penelitian Dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengungkap sikap-sikap politik Jemaah Syi’ah dalam memperjuangkan mekanisme dan sistem yang merepresentasikan aspirasi dan kepentingankepentingan mereka, dan 2) menganalisis tindakan-tindakan mereka dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi, hak-hak dasar dan kepentingan- kepentingan Jemaah Syi’ah pasca Kasus Sampang, di dalam kerangka demokrasi. Dengan dua tujuan partikular tersebut, penelitian ini secara umum akan menganalisis perjuangan Jemaah Syi’ah sebagai kelompok minoritas sekaligus tidak diuntungkan (minority and disadvantaged groups), terutama 6 pasca Kasus Sampang, untuk mewujudkan representasi politik mereka dalam perspektif politik inklusi demokratis. D. Kajian Teori Untuk mengerangkai pengumpulan dan analisis data penelitian ini sekaligus untuk menyajikan temuan-temuan baru (findings) penelitian ini, maka peneliti akan mengulas dua kajian teoretik utama, yaitu minoritas dan demokrasi, serta representasi dalam politik inklusi demokratis. 1. Minoritas dan Demokrasi Secara literal, istilah minoritas sebenarnya belum terlalu jelas. Sebab label minoritas ini dikonstruk secara akademik dan historikal14, sehingga dimensinya sangat kompleks. Namun demikian, klaritas konseptual dapat kita telusuri melalui beberapa pandangan, antara lain Louis Wirth (1941), Marvin C Harris (1959), Francesco Capotorti (1991), dan Jules Deschênes (2008). Wirth menyatakan bahwa konsep minoritas digunakan untuk menyebut mereka yang mendapatkan perlakuan yang berbeda atau diri mereka sendiri dipisahkan dari sebuah masyarakat, hanya karena mereka memiliki perbedaan fisik, social, dan kultural. Beberapa kelompok itu tidak saja posisi obektifnya tidak diuntungkan (disadvantageous objective position), bahkan cenderung berkembang konsepsi bahwa mereka itu inferior, alien (tercerabut dari masyarakatnya), dan kelompok teraniaya (persecuted groups), yang pada akhirnya berdampak secara signifikan terhadap peran-peran mereka dalam urusan publik dan bangsa.15 Selanjutnya, Harris menyatakan bahwa minoritas adalah subkelompok dari masyarakat yang lebih besar dan anggota dari subkelompok tersebut Preece, Jennifer Jackson. 2005. “Understanding the Problem of Minorities”, dalam Minority Rights (Cambridge: Polity), hlm. 3 15 Situasi ini selain menunjukkan bahwa ada aspek dalam diri minoritas yang harus dilindungi, juga menggambarkan bahwa masyarakat kita secara faktual belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Lihat Louis Wirth, “Morale and Minority Groups”, American Journal of Sociology, Vol. 47, No. 3 (November 1941), diterbitkan oleh The University of Chicago Press, hlm. 415-433 14 7 menjadi subjek ketidakberdayaan (diasabilities) dalam berbagai bentuk prasangka, diskriminasi, segregasi, atau persekusi yang dilakukan oleh subkelompok lainnya yang biasanya disebut mayoritas.16 Menurut Capotorti, minoritas adalah: … a group, numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members-being nationals of the State- possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language.17 Sedangkan Deschênes menyatakan, minoritas merupakan: … a group of citizens of a State, constituting a numerical minority and in a non-dominant position in that State, endowed with ethnic, religious or linguistic characteristics which differ from those of the majority of the population, having a sense of solidarity with one another, motivated, if only implicitly, by a collective will to survive and whose aim is to achieve equality with the majority in fact and in law”.18 Terhadap beberapa definisi tersebut dapat diajukan beberapa catatan. Pertama, basis pengkategorian minoritas, di antaranya, bersifat numerik— terkait jumlah. Menurut peneliti, identifikasi minoritas berdasarkan jumlah mengandung bias tersendiri. Mendekati minoritas dari kalkulasi numerikal cenderung tidak dapat merangkum berbagai fakta diskriminasi terhadap minoritas. Satu contoh unik yang dapat diajukan adalah kasus Afrika Selatan. Rezim apartheid Afrika Selatan sebelum ditumbangkan oleh Nelson Mandela melakukan diskriminasi rasial atas warga Afsel yang secara numerikal sangat besar. Kedua, secara politis, minoritas memiliki status yang khas. Dalam lingkup sebuah negara, mereka menempati posisi yang tidak dominan. Harris, Marvin, “Race, Class, and Minority”, Social Forces, Vol. 37, No. 3 (Mar., 1959), yang diterbitkan oleh Oxford University Press, hlm. 248-254 17 “Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.” UN Document E/CN.4/Sub.2/384/Add.1-7 (1977). Diakses melalui http://www.minorityrights.org/docs/mn_defs.htm, pada tanggal 3 November 2008. 18 Proposal Concerning a Definition of the Term 'Minority'. UN Document E/CN.4/Sub.2/1985/31 (1985). Diakses melalui http://www.minority-rights.org/docs/mn_defs.htm, pada tanggal 3 November 2008. 16 8 Ketiga, minoritas memiliki karakter distingtif. Mereka memiliki ciri etnik, religi, dan linguistik yang berbeda dengan mayoritas penduduk di sebuah negara. Keempat, terdapat rasa solidaritas yang tinggi di antara mereka untuk bertahan dengan budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka. Pemikir yang lain, Jackson Preece, melihat persoalan minoritas dari perspektif politik. Sebab, menurutnya, persoalan-persoalan minoritas hadir dalam upaya untuk membedakan mereka yang memiliki komunitas politik tertentu dan siapa yang tidak memiliki komunitas politik tersebut.19 Preece, berpijak pada pandangan Hannah Arendt (1972), menyatakan bahwa kehidupan politik menyisakan asumsi bahwa kita dapat memproduksi kesetaraan melalui pengaturan, sebab manusia dapat bertindak di dalam, mengubah, dan membangun sebuah dunia bersama. Tata politik (political order) merupakan buatan manusia. Ia lebih sebagai akibat tindakan manusia daripada bagian dari dunia fisik dan alamiah. Apa yang dinyatakan Arendt kira-kira tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Thomas Hobbes (1988). Tanpa rekayasa (politik) manusia, tidak ada tempat untuk industri, tidak ada seni, tidak ada huruf, dan tidak ada masyarakat. Di sisi yang buruk, tidak ada ketakutan yang terus-menerus, tidak ada bahaya kematian dengan kekerasan, tidak ada pengungkungan, kemiskinan, kekejian, dan kekejaman. Minoritas, menurut Preece, adalah identitas yang lebih tepat dibaca dari konstruksi politis. Minoritas merujuk pada kelompok yang dikeluarkan secara politis (political outsiders) dari tatanan politik yang dominan. Identitas minoritas memiliki sejarah latar politis yang panjang. Katolik abad pertengahan melabeli orang-orang yang memiliki kepercayaan tapi tidak berhubungan dengan Gereja Katolik sebagai minoritas. Di negara-negara dinasti, label minoritas disematkan kepada mereka yang tidak mentaati paham keagamaan yang dipercayai oleh pangeran yang berdaulat. Dalam kekaisaran Eropa, minoritas adalah mereka yang tidak memiliki ciri nyata peradaban Eropa. 19 Preece, Jennifer Jackson, 2005, “Understanding the Problem of Minorities”, dalam Minority Rights, (Cambridge: Polity), hlm. 6 9 Identifikasi minoritas dari perspektif dominasi politik, menurut peneliti, memiliki basis argumentasi yang kuat dengan kekayaan fakta di lapangan. Meskipun perspektif numerikal kadang menjadi subkarakter minoritas, akan tetapi yang dominan mendistingsi sebenarnya adalah konstruksi dan kategorisasi politis. Fakta politik kontemporer menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap mereka yang dilabeli minoritas seringkali dilakukan oleh kelompok yang dominan secara politis dan memiliki kekuasaan untuk menyatakan bahwa di luar mereka merupakan kelompok yang lemah, yang harus disantuni secara positif, atau secara negatif harus diwaspadai sebagai kelompok yang merusak ketertiban politik. Jadi minoritas yang dimaksudkan dalam penelitian ini tidak dibangun dari perspektif numerik—paling tidak bukan pertimbangan mayor. Keminoran yang dibahas didasarkan pada pertimbangan utama bahwa dalam suatu situasi dan keadaan politis tertentu dimana minoritas dijadikan sebagai objek alienasi, diskriminasi, segregasi, inferiorisasi, dan bahkan persekusi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hak-hak mereka? Pada masa yang lalu pengaturan khusus mengenai minoritas dan keadaan-keadaan yang memungkinkan mereka bertahan digambarkan sebagai “jaminan” dan bukan “hak”.20 Hal itu tampak dalam perlakuan yang terjadi pada abad ke-17 sampai 19-an. Pada masa Liga Bangsa-Bangsa, misalnya, ada pengaturan bernama League of Nation Systems of Minority Guarantees, yang diadopsi sebagai upaya ntuk memelihara Perkampungan 1919 di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Perbedaan semantik ini jelas memiliki makna yang signifikan dan menjelaskan bagaimana pengaturan kepada mereka dilakukan. Kata “jaminan” menunjukkan bahwa arrangement merupakan kewajiban yang secara sukarela atau karena budi baik yang diberikan oleh negara-negara besar terhadap negara-negara baru atau negara-negara kecil. Setelah diskursus HAM menguat pasca Perang Dunia II, perlindungan terhadap eksistensi minoritas diekspresikan dalam bentuk hak dan bukan 20 Ibid, hlm. 13 10 jaminan. Apa perbedaan keduanya memang tidak benar-benar secara jelas ditegaskan dalam pemahaman kontemporer. Vincent (1986), sebagaimana dikutip Preece, memberikan penjelasan bahwa kata hak menunjukkan perilaku yang seseorang dapat menuntutnya, baik secara legal maupun moral, yang mensyaratkan keadaan-keadaan normatif yang dilekatkan kepada privilege, atau kekebalan, atau otoritas untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. Vincent selanjutnya menjabarkan bahwa hak terdiri dari lima element; subjek hak, objek hak, penggunaan hak, pemangku kewajiban korelatif, dan justifikasi hak. Dalam Konvensi Hak Minoritas 1992, pengaturan atas eksistensi dan survivalitas minoritas digambarkan dalam dua sisi sekaligus; hak internal minoritas dan jaminan eksternal dari negara. Hak-hak minoritas dinyatakan secara gamblang pada Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam Pasal 2 ayat 1, misalnya, dinyatakan mengenai hak untuk menikmati kebudayaan, meyakini dan melaksanakan agama, dan menggunakan bahasa mereka sendiri, baik di ruang publik maupun privat, secara bebas tanpa gangguan dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Jaminan perlindungan sebagai obligasi negara dinyatakan dalam jumlah pasal yang lebih banyak, antara lain Pada pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Dalam Pasal 1 ayat 1, misalnya, dinyatakan bahwa negara wajib melindungi identitas nasional atau etnik, budaya, agama, dan bahasa minoritas yang terdapat dalam wilayahnya dan mengembangkan keadaankeadaan yang memungkinkan pemajuan identitas tersebut. Hak-hak minoritas (minority rights) merupakan wacana komplementer dalam narasi besar Hak Asasi Manusia (HAM) kontemporer. Secara formal masyarakat dunia baru memberikan penekanan afirmatif atas hak-hak minoritas pada akhir abad ke-20, dengan diadopsinya Declaration on Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1992. Secara akademik, hak-hak minoritas sebenarnya sudah lama dibicarakan, terutama sejak secara sangat umum pasal 27 International 11 Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa: “Di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri”. Sebagai turunan dari Pasal 27 ICCPR,21 Deklarasi Minoritas 1992 di atas mengakomodasi rumusan-rusumusan hak minoritas yang lebih detil22, yaitu: 1) Perlindungan, oleh Negara mengenai keberadaan mereka dan identitas suku bangsa, atau etnik, budaya, agama, dan bahasa,23 2) Hak untuk menikmati budaya mereka, untuk mengimani dan melaksanakan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka dalam urusan pribadi dan di masyarakat,24 3) Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan umum,25 4) Hak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka pada tingkat nasional dan daerah,26 5) Hak untuk membentuk dan mempertahankan perserikatan mereka sendiri,27 6) Hak untuk membentuk dan mempertahankan hubungan damai dengan anggota masyarakat lain dalam kelompok mereka dan 21 Hal itu dinyatakan secara eksplisit pada bagian Preamble Deklarasi PBB tentang Minoritas Di sisi yang berbeda, hak-hak tersebut berimplikasi pada kewajiban dan tanggungjawab negara. Dalam kerangka itu negara juga dituntut untuk mengambil langkah-langkah positif dalam rangka melindungi minoritas, tidak saja di bidang sipil dan politik sebagaimana yang dikehendaki ICCPR, akan tetapi juga untuk mendukung dan memelihara minoritas secara kultural. Lihat Steven Wheatly, Democracy, Minorities and International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 7 23 Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Minoritas 24 Pasal 2 (1) Deklarasi PBB tentang Minoritas 25 Pasal 2 (2) Deklarasi PBB tentang Minoritas 26 Pasal 2 (3) Deklarasi PBB tentang Minoritas 27 Pasal 2 (4) Deklarasi PBB tentang Minoritas 22 12 dengan orang dari kelompok minoritas lain, baik di dalam negara mereka sendiri atau di luar batas-batas negara,28 7) Kebebasan untuk melaksanakan hak-hak mereka, secara individu dan juga di dalam masyarakat dengan anggota lain dari kelompok mereka tanpa adanya diskriminasi.29 Kemudian bagaimana hak-hak minoritas itu dijamin oleh negara demokrasi? Demokrasi model apa yang lebih memungkinkan pemenuhan hak-hak minoritas tersebut? Demokrasi secara konseptual merupakan sistem yang memungkinkan jaminan eksistensial bagi minoritas, di samping mekanisme untuk pengambilan keputusan bersama melalui otoritas negara berdasarkan aspirasi mayoritas. Demokrasi menyediakan ruang bahkan mekanisme perlindungan hak-hak dasar bagi seluruh warga melalui saluran-saluran demokratis. Maka, dalam sistem demokratis tersebut hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara, dari kelompok minoritas sekalipun, mendapatkan jaminan perlindungan dalam konstitusi negara. Ideal tersebut berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah. David T Canon (2005) menyatakan bahwa tantangan pokok demokrasi perwakilan (representative democracy) adalah bagaimana menyediakan ruang suara bagi kepentingan minoritas dalam sistem yang didominasi oleh suara mayoritas. Karenanya, legitimasi dan stabilitas sebuah demokrasi terutama ditentukan oleh kemampuannya untuk mengatasi kerumitan persoalan relasi mayoritas dengan minoritas dalam penyediaan ruang politik yang setara bagi keduanya.30 Secara faktual seringkali terjadi anomali dalam ranah politik dimana demokrasi dijadikan alat untuk mendiskriminasi atau mempersekusi minoritas. Instrumentasi prosedur-prosedur demokrasi untuk mendiskriminasi 28 Pasal 2 (5) Deklarasi PBB tentang Minoritas Pasal 3 Deklarasi PBB tentang Minoritas 30 David T Canon, “The representation of Minority Interest in The U.S. Congress”, dalam Christina Wolbrecht dan Rodney E Hero, The Politics of Democratic Inclusion (Philadelphia: Temple University Press, 2005), hlm. 281 29 13 minoritas terjadi dalam berbagai wajah. Untuk memperluas spektrum ilustrasi dapat kita cermati referendum demokratis yang diselenggarakan di swiss dalam rangka menolak rencana minoritas muslim disana untuk membangun menara masjid kelima. Kepentingan minoritas yang relatif sederhana, membangun menara masjid—sementara masjidnya sudah ada, terbentur dengan mekanisme dan prosedur demokratis yang digunakan oleh mayoritas. Referendum sebagai instrumen demokrasi untuk menegaskan aspirasi dan kehendak mayoritas dijadikan sebagai kendaraan (means) untuk menegasikan akomodasi dan toleransi atas kepentingan minoritas.31 Berkaca dari pengalaman kasus “menara kelima” di Swiss, demokrasi yang diidealkan sebagai the only of game in town,32 justru dijadikan sebagai the game of majority untuk mendiskriminasikan minoritas di negara itu. Tidak saja begitu, demokrasi di banyak negara bahkan seringkali dijadikan sebagai tool of revenge atas minoritas. Momentum pasca otoriter seringkali diinstrumentasi sebagai pintu masuk bagi mayoritas untuk mengambil tindakan menumpahkan kemarahan mayoritas kepada minoritas, terutama kelompok-kelompok yang dalam pemerintahan otoriter sebelumnya mendapat keuntungan-keuntungan.33 31 Di Swiss terdapat sekitar 400.000 orang warga muslim, atau kira-kira 4% dari jumlah total penduduk. Sebagai tempat ibadah bagi mereka, terdapat sekitar 150 masjid di seluruh Swiss. Hanya 4 masjid yang memiliki menara. Muncul inisiatif untuk membangun menara ke-5. Aktivis partai politik sayap kanan menolak pembangunan menara kelima itu dan menilai hal itu sebagai “simbol politik fundamentalis dan simbol islamisas. Mereka lalu menjadi inisiator untuk mengajukan referendum demokratis untuk menjajaki aspirasi mereka, apakah sebagian besar rakyat menerima atau menolak rencana pembangunan menara kelima tersebut.. Referendum akhirnya dimenangkan oleh kubu yang menolak pembangunan dengan total suara 57,5%. Sementara masyarakat yang mendukung “hanya” 42,5%. Dengan demikian dilaranglah pembangunan menara kelima tersebut. Robertus Robet, “Demokrasi versus Toleransi”, dalam Bonar Tigor Maipospos dan Ismail Hasani (eds.), Beragama, Berkeyakinan, dan Berkonstitusi (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2009), hlm. 2-3 32 Demokrasi diidealkan sebagai bentuk pemerintahan terbaik. Sejak era Aristoteles demokrasi diidentifikasi sebagai sistem politik yang mengandung kebaikan paling sedikit dibandingkan sistem lain yang banyak keburukannya. Dalam pandangan Linz, disebut sebagai “the only game in town” (satu-satunya aturan main yang berlaku”. Juan J Linz, “Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation”, dalam R William Liddle, Crafting Indonesian Democracy (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 27 33 Diinspirasi oleh Amy Chua (2010), I Wibowo memberikan aneka contoh cukup komprehensif mengenai bagaimana demokrasi pasca otoriter dijadikan momentum bagi mayoritas untuk menekan bahkan meminggirkan minoritas yang sebelumnya mendapat keuntungan. Dalam kasus-kasus yang dielaborasi oleh I Wibowo adalah mereka yang mendapatkan keuntungan- 14 Dalam konteks Indonesia, tampilan relasi mayoritas minoritas di alam demokrasi lebih mengerikan. Kelompok-kelompok minoritas seringkali mendapatkan tindakan diskriminasi, persekusi, dan marjinalisasi dari anasir mayoritas dengan menggunakan instrumen-instrumen non demokratis, seperti kekerasan, intimidasi, serta berbagai tindakan langsung seperti sweeping dan lain sebagainya. Penggunaan instrumen-instrumen non demokratis tersebut berdampak pada hilangnya berbagai hak dasar minoritas, sebagai individu maupun sebagai kesatuan kelompok, seperti hak atas properti, kebebasan berserikat, kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan keyakinan, bahkan hak-hak yang sangat fundamental seperti hak hidup serta hak atas kebebasan dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan. Korban terbesar dalam terjadinya berbagai tindakan kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi lainnya terhadap minoritas adalah kelompok minoritas agama/keyakinan. SETARA Institute mencatat sepanjang tahun 2012 telah terjadi peningkatan intoleransi dan diskriminasi kebebasan beragama/berkeyakinan, pelanggaran atas sejumlah kebebasan 264 peristiwa dan beragama/berkeyakinan 371 tindakan sebagai hak konstitusional yang dinaungi dan dijamin oleh konstitusi negara. Angka tersebut menunjukkan peningkatan situasi minor secara signifikan dalam kebebasan beragama/berkeyakinan dibandingkan tahun lalu, dimana masingmasing “hanya” berjumlah 244 peristiwa dan 299 tindakan.34 keuntungan ekonomi, yang dalam pandangan Chua disebut “market-dominant minorities”. “Balas dendam” tersebut terjadi di Zimbabwe begitu Mugabe terpilih secara demokratis melalui Pemilu pada tahun 1980. Juga di Venezuela setelah Hugo Chaves terpilih sebagai presiden melalui pemilu demokratis pada 1998. Lihat I Wibowo, Negara dan Bandit Demokrasi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001). Juga Amy Chua, World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, (New York: Anchor Books, 2010). Untuk kasus Indonesia, kasus pembakaran dan perkosaan atas minoritas China dalam huru-hara politik di awal reformasi Indonesia sampai tingkatan tertentu dapat dikatagorikan sebagai contoh serupa, hanya dengan saluran di luar demokrasi. 34 Dalam enam tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan secara signifikan sejak tahun 2007. Lihat Halili, dkk., Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Situasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Tahun 2012 (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 31 dan hlm. 53. Data yang tidak jauh berbeda juga dirilis oleh The Wahid Institute, yang secara umum menggambarkan tingginya tampilan diskriminasi dan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan akhir-akhir ini. 15 Salah satu kelompok minoritas yang hingga kini masih terus berada dalam situasi anomali negara demokratis adalah Jemaah Syi’’ah Kabupaten Sampang. Mereka menjadi korban teror, intimidasi, penyerangan, perampasan, serta pembakaran tempat tinggal, harta benda, dan tempat ibadah, bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Jemaah Syi’ah Sampang kini terusir dari tanah kelahiran mereka dan tercerabut dari akar natural dan sosio-kultur mereka.35 Padahal jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kerangka demokrasi konstitusional Indonesia sangatlah cukup bahkan lebih dari memadai. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 (UUD 1945) terdapat beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga negara maupun bukan. Jaminan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 28 E dan Pasal 28 I.36 Tersedianya jaminan dan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan menunjukkan rekognisi bahwa hak beragama atau pemelukan suatu agama oleh seseorang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat esensial.37 35 Ibid, hlm. 75-97. Pasal 28 E ayat (1) berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Sedangkan Pasal 28 I ayat (1) berbunyi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” 37 Bahkan ada yang menyebut hak beragama merupakan hak asasi yang paling esensial dibandingkan hak-hak asasi lainnya. Lihat Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi), (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 286. 36 16 Dengan kedudukan yang demikian signifikan, maka hak beragama— sejalan dengan norma universal hak asasi manusia—ditempatkan sebagai non derogable rights sebagaimana dinyatakan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebagai hak yang terkategori non derogable rights, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.38 Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/ berkeyakinan sebagai non derogable rights, UUD 1945 juga mengatur mengenai jaminan negara terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan, yang ditegaskan dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Mandat jaminan konstitusional yang diturunkan dari filosofi dasar negara demokratis diperkuat dengan berbagai instrumen hukum derivatnya dalam bentuk undang-undang. Beberapa Undang-Undang yang dapat diidentifikasi dalam kerangka utamanya adalah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian jaminan konstitusional in book bagi kelompok minoritas agama/keyakinan sangatlah kuat. Namun in action, jaminan konstitusi demokratis tersebut tidak menyelamatkan kelompok minoritas agama/keyakinan dari berbagai tindakan-tindakan non demokratis atas kebebasan dan hak dasar yang dijamin oleh kerangka dasar demokrasi negara. Jadi jika dipantulkan dengan cermin faktual, maka demokrasi, sampai di tingkatan ini, tidak terlalu bermakna bagi mereka.39 38 39 Ibid, hlm. 293. Meminjam perspektif Demos yang melihat demokrasi di era pasca otoritarianisme Orde Baru— dengan berbagai problemnya, mulai dari representasi semu hingga pembajakan politik oleh elit—tidak cukup bermakna sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit untuk membuat dan memastikan demokrasi menjadi lebih bermakna. Lihat AE Priyono, dkk, Making Democracy Meaningful: Problems and Options in Indonesia atau dalam versi Indonesia berjudul Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan di Indonesia (Jakarta: Demos, 2004) 17 Bagaimana alternatif untuk membuat agar demokrasi bekerja lebih baik dalam mengakomodasi kepentingan minoritas? Secara teoretis beberapa opsi telah ditawarkan oleh berbagai ahli, pengamat, dan peneliti, berbasis pada beberapa riset relevan dengan berbagai perspektif. Menurut Lawrence Surendra, gejala formalisasi demokrasi—dimana prosedur-prosedur demokrasi tampak bekerja secara normal namun hanya di tataran formal, misalnya regulasi dan pemilihan umum secara reguler— merupakan salah satu masalah pokok demokratisasi di beberapa negara postotoritarian, khususnya di Asia. Untuk merespons masalah tersebut diperlukan langkah substansialisasi demokrasi. Inti (substance) dari demokrasi dan demokrasi substantif sejatinya berkaitan dengan pertanyaan seberapa inklusif demokrasi tersebut. Sehubungan dengan hal itu, untuk membuat demokrasi yang lebih inklusif, maka harus diupayakan agar representasi politik yang berlangsung di negara demokrasi dikembangkan agar lebih mengarah kepada politik inklusi.40 Tesis Surendra membayangkan bahwa semakin luas dan substantif tingkat dan coverage representasi di sebuah sistem demokratis maka akan semakin terakomodasi kepentingan-kepentingan seluruh kelompok di dalam sistem, khususnya kelompok-kelompok minoritas. Jika hal itu terjadi maka bekerjanya demokrasi akan semakin substantif bagi publik dan warga negara. Berkaitan dengan perspektif tersebut, melalui studi cukup komprehensif dari pengalaman Amerika Serikat, Rodney E. Hero dan Christina Wolbrecht melihat bahwa politik inklusi demokratis merupakan sesuatu yang sentral untuk memahami sekaligus mengukur kualitas sebuah demokrasi.41 Penggunaan standar-standar politik kesetaraan dan kedaulatan rakyat (popular sovereignty) akan berdampak pada meluas dan mendalamnya representasi warga yang diperintah. Pro kontra terkait dengan penggunaan Lawrence Surendra, “Democratizing Democracy-Beyond Representative Politics to The Politics of Inclusion”, dalam Hee Yeon Cho, Lawrence Surendra, and Eunhong park (eds.), States of Democracy: Oligarchic Democracy and Asian Democratization (Mumbai: Earthworm Books, 2008), hlm. 23-40. 41 Dalam hal ini tentu yang dimaksud oleh Studi Hero dan Wolbrecht adalah kualitas demokrasi Amerika Serikat. Lihat Wolbrecht dan Hero. Op.cit, hlm. 1 40 18 standar-standar politik kesetaraan dan kedaulatan popular, khususnya mengenai sampai di tingkatan mana standar itu digunakan, selalu berkembang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang secara tradisional tidak diuntungkan (disadvantaged groups), seperti perempuan, minoritas etnik dan ras, serta para imigran. Dalam rangka itu, seperti diurai secara analitik dengan basis empirik yang memadai oleh Wolbrecht dan Hero, perluasan dan pendalaman representasi (dalam definisi yang lebih luas) dilakukan dalam demokrasi Amerika, paling tidak di tiga lapisan. Pertama, diversitas dalam dan antar kelompok. Misalnya, bagaimana memahami relasi dan struktur etnik dan ras di AS, bagaimana membangkitkan kesadaran kelompok-kelompok masyarakat, dan kemudian membawa kesadaran tersebut dari luar ke dalam kelompok atau dari dalam ke luar kelompok. Kedua, mediasi lembagalembaga demokrasi, misalnya, bagaimana menjadikan gerakan social sebagai mekanisme politik inklusi, bagaimana menjadikan partai politik dan lembagalembaga demokrasi mewadahi minoritas dan sebagainya. Ketiga, pengaturan lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Misalnya, bagaimana mengekstensifikasi representasi di Kongres, pemanfaatan Pengadilan Federal untuk memperjuangkan demokrasi inklusif, hingga penataan kepresidenan. Beberapa hal itu memungkinkan perbaikan kualitas inklusi demokratis di AS. Salah satu ilustrasi sederhana dari bekerjanya politik inklusi demokratis tersebut adalah terpilihnya seorang Afro-Amerika, Barack Obama, sebagai presiden, yang dalam dinamika politik AS di masa yang lalu tampaknya dipandang sebagai sesuatu yang hampir mustahil. Berkaca dari pengalaman berbagai negara Eropa khususnya di sekitar semenanjung Balkan seperti Romania, Kroasia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Montenegro, dan Albania, Florian Bieber (2008) mencatat bahwa salah satu mekanisme mengakomodasi demokratik yang kepentingan-kepentingan dapat digunakan minoritas adalah untuk dengan memperluas partisipasi politik minoritas. Partisipasi politik minoritas 19 merupakan alternatif demokratis untuk mengakomodasi dan memenuhi hakhak minoritas.42 Demokrasi dalam konteks pemenuhan hak-hak minoritas dapat didudukkan dalam spektrum pembahasan demokrasi dan keadilan. Demokrasi merupakan bentuk politik terbaik untuk mewujudkan keadilan.43 Demokrasi memungkinkan dikendalikannya para penyelenggara negara dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang secara faktual merupakan godaan yang sulit dielakkan. Dalam iklim politik demokratis, individuindividu dan gerakan sosial dapat secara terus menerus menuntut pemerintah untuk mewujudkan keadilan, mencegah warga negara dari menderita ketidakadilan, menolak rencana program yang akan memproduksi ketidakadilan, dan memerangi ketidakadilan. Mereka juga dapat berharap publik dan pemerintah demokratis untuk memperbaiki dan memberikan ganti rugi atas ketidakadilan yang terjadi.44 Young menyebut model demokrasi yang lebih functioning untuk mengcover dan mewujudkan keadilan adalah model demokrasi deliberatif— pendalaman dari model demokrasi yang hanya berfokus pada prosedur dan mekanisme, yaitu apa yang dia sebut sebagai model demokrasi aggregatif.45 Secara substansial, demokrasi deliberatif mengoperasionalkan demokrasi di wilayah yang lebih dalam dari demokrasi aggregatif. Banyak pemikir dan para teoris yang mengusulkan demokrasi model ini, yang dinilai sebagai 42 Meskipun secara umum hak-hak minoritas tersebut secara umum belum didefinisikan secara jelas, sementara standar internasional juga kabur (vague) dan cenderung mengelak (evasive), paling tidak dengan ketersedian saluran partisipasi akan melindungi minoritas dari berbagai tindakan diskriminasi. Lihat Florian Bieber, “Introduction: Minority Participation and Political parties”, dalam Bieber, et.al., Political parties and Minority Participation (Skopje: Friedrich Ebert Stiftung, 2008), hlm. 1-30. 43 Iris Marion Young, Inclusion and Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2002, hlm. 17 44 Tugas utama bentuk politik demokratis adalah memajukan keadilan. Bahkan Ian Saphiro menyebut demokrasi sebagai “subordinated good”, dan ordinatnya adalah keadilan. Lihat Saphiro, Democratic Justice, New Heaven, Yale University Press, 1999, atau Philips van Parijs, “Justice and Democracy: Are They Incompatible?”, Journal of Political Philosophy, 4/2 (June 1996), 17-101. 45 Iris Marion Young. Op.cit. 19-25 20 demokrasi yang “dalam” (deep democracy), sekaligus sebagai kritik atas demokrasi aggregatif.46 Model aggregatif menginterpretasikan demokrasi sebagai proses aggregasi pilihan-pilihan warga negara dalam menentukan pejabat dan kebijakan-kebijakan publik. Dalam hal itu, tujuan dari penentuan kebijakan demokratis adalah untuk menentukan apa yang paling mengaitkan antara pemimpin, aturan, dan kebijakan dengan pilihan-pilihan yang telah dibuat oleh warga negara. Demokrasi dalam model ini membayangkan bahwa setiap orang dalam sebuah masyarakat politik memiliki pilihan-pilihan yang berbeda tentang apa yang mereka inginkan untuk dilakukan pemerintah. Mereka juga tahu bahwa orang lain dalam komunitas politik yang sama memiliki pilihanpilihan yang berbeda yang bisa jadi tidak match dengan pilihan mereka. Nah, demokrasi dalam situasi demikian merupakan proses kompetitif dimana partai politik dan para kandidat berusaha untuk menawarkan platforms mereka dan memuaskan sebanyak-banyaknya orang. Warga negara dengan pilihan yang serupa berusaha untuk mengorganisasi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi perilaku partai politik dan politisi pembuat kebijakan yang telah mereka pilih. Pada akhirnya, Pemilu dan proses pembuatan legislasi menggambarkan agregasi yang terkuat dalam populasi.47 Model aggregatif dalam pandangan Young memiliki beberapa kelemahan. Pertama, model aggregatif menempatkan pilihan-pilihan individu 46 Beberapa ilmuwan yang disebut Young sebagai penganjur demokrasi deliberatif antara lain: 1) Joshua Cohen, “Deliberation and Democratic Legitimacy”, dalam Alan Hamlin dan Philip Pettit (eds.), The Good polity (Blackwell, London, 1989), 2) Spragens, Reason and Democracy, 3) Barber, Strong Democracy, 4) Cass R. Sunstein, The Partial Constitution (Cambridge, Massachusset: Harvard University Press, 1993), 5) Frank Michelman, “Traces of Self-Government”, Harvard Law Review, 100 (1986), 4-77, 6) Jane Mansbridge, “A Deliberative Theory of Interest Representation”, dalam Mark P Patracca (ed.), The Politics of Interest: Interest Group Transformed (Boulder, Colorado: Westview Press, 1992), 7) Dryzek, Discoursive Democracy, 8) James Bohman, Public Deliberation (Cambridge, Massachusset: MIT Press, 1996), 9) James Fishkin, The Voice of The People, 10) Jurgen Habbermas, Between Facts and Norms (Cambridge, Massachusset: MIT Press, 1996), 11) Amy Gutmann dan Dennis Thompson, Democracy and Disagreement (Cambridge, Massachusset: Harvard University Press, 1996) 47 Young. Ibid. 19-20. 21 sebagai sebagai sesuatu yang given. Tidak penting apa pertimbangan di balik pilihan tersebut. Kedua, model ini merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengagregasi kepentingan warga negara untuk melihat mana pilihan yang berasal dari jumlah terbanyak atau dengan intensitas terkuat. Karenanya para individu itu tidak perlu meninggalkan pilihan individual kepentingan mereka dan berinteraksi dengan pilihan-pilihan lain yang berbeda. Maka demokrasi aggregatif dengan demikian menghilangkan potensi interaksi diantara warga negara yang sudah barang tentu berbeda, dan meniadakan argumentasi dan motivasi mengapa sebuh keputusan diambil. Ketiga, model ini juga mendorong terwujudnya rasionalitas yang sangat tipis dan individualistik. Para politisi barangkali mengungkapkan alasan atau argumen dalam engagement politik mereka, tapi keputusan yang keluar sesungguhnya tidak butuh rasionalitas dan bisa saja sama sekali tidak pernah sampai pada proses rasionalisasi. Keempat, model aggregatif bersifat skeptis tentang kemungkinan objektivitas normatif dan evaluatif. Model aggregatif hanya memberikan ruang kepada perorangan untuk bertahan pada pilihan subjektifnya, bukan dengan reasons kenapa pilihan itu dianggap baik. Meskipun terhadap hasil kebijakan disediakan cara untuk mengkritisi, tapi dengan tidak adanya kesempatan untuk mengevalusi rasio normatif dalam prosesnya, maka patut dipersoalkan legitimasi moral dari substansi sebuah kebijakan politik. Sebaliknya, Young mencatat beberapa kelebihan model deliberative sehingga hal itu dipandang lebih feasible untuk mewujudkan keadilan melalui politik demokrasi. Dalam model delliberatif, demokrasi merupakan bentuk dari akal budi praktis (practical reason). Para partisipan dalam proses-proses demokratik mendapat ruang untuk menawarkan tawaran-tawaran program bagaimana mengambil cara terbaik untuk mengatasi sebuah persoalan tertentu, mereka juga menyampaikan argumentasi untuk mempersuasi yang lain agar menerima tawaran mereka. Proses demokrasi utama dalam demokrasi deliberative adalah mendiskusikan masalah, konflik, kepentingan, 22 atau klaim tentang kebutuhan tertentu. Berbagai kelompok dan liyan menguji tawaran-tawaran program dan argumentasinya. Keputusan akhir diambil bukan karena sebuah pilihan didukung oleh sebagian besar orang secara numerik, tapi ditentukan oleh apakah sebuah tawaran program disertai dengan reasoning terbaik. Model deliberatif48, dengan demikian, mengandung berbagai nilai utama, yang berbeda secara fundamental dengan model agregatif. Beberapa ideal normatif dalam relasi para pihak yang berdeliberasi (deliberating parties) adalah: inklusi, kesetaraan poltik, reasonableness, dan publicity. 2. Representasi dalam Politik Inklusi Demokratis Seperti dinyatakan di bagian latar belakang penelitian ini, kualitas demokrasi ditentukan antara lain oleh derajat inklusivitasnya. Semakin inklusif sebuah politik demokratis, semakin baik kualitas demokrasi tersebut.49 Inklusi bukanlah konsep yang asing dalam politik, terutama politik identitas. Basis argumentasi sederhananya pada mulanya sederhana, yaitu moralitas tentang solidaritas universal dan tanggunggjawab sesama (responsibility of each for all).50 Habermas menegaskan bahwa respek yang setara terhadap setiap orang tidak terbatas pada mereka yang seragam dengan kita (who are like us), tetapi diperluas kepada orang lain yang tetap dalam “kelainannya” (otherness). Dalam kerangka itu, solidaritas atas orang lain sebagai bagian dari kita merujuk pada kelenturan “kita” dalam sebuah komunitas, yang menolak semua determinasi substantif dan memperluas batas-batas berpori lebih jauh lagi. Artinya, meskipun batas komunitas itu 48 Jika dikontekstualisasi ke Indonesia, menurut peneliti, ideal demokrasi deliberatif sessungguhnya sebangun dengan demokrasi yang ingin diletakkan sebagai model demokrasi Indonesia, yaitu Demokrasi Permusyawaratan (juga perwakilan), sebagaimana tertuang dalam Sila ke-4 Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. 49 Secara teoretis, kualitas tertinggi demokrasi dikonseptualisasi sebagai demokrasi substantif atau demokrasi maksimalis, tahap yang dipandang lebih tinggi dari sekedar demokrasi minimalis, demokrasi elektoral, atau demokrasi prosedural. 50 Seperti yang sering dibela dan diperjuangkan oleh Jurgen Habermas. Lihat antara lain The Inclusion of the Other, ed. Ciaran Cronin dan Pablo De Greiff (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1998), hlm. xxxi-xxxvii 23 ada, orang-orang yang berbeda dari kalangan yang lebih luas dimungkinkan untuk masuk. “Komunitas moral” tersebut menegakkan dirinya semata-mata melalui jalan menghapuskan diskriminasi dan tindakan membahayakan lainnya dan dengan memperluas relasi berdasarkan rekognisi mutual yang meliputi orang-orang yang terpinggirkan. Komunitas tersebut tidak dibangun sebagai sebuah kolektif untuk memaksakan homogenitas anggotanya sebagai upaya untuk menegaskan kekhasan komunitas tersebut. Jadi, inklusi dalam konteks ini cenderung bermakna bahwa batas-batas sebuah komunitas bersifat terbuka untuk semua, juga untuk liyan (the other) dan khususnya kepada orang-orang yang “asing” bagi yang lain dan ingin bertahan dengan “keasingan”-nya. Sebab berkaitan dengan relasi mayoritas-minoritas, inklusi juga merupakan salah satu isu penting dalam spektrum studi demokrasi, sebagaimana juga studi dan teori keadilan. Salah satu masalah serius yang terjadi di tengah-tengah masyarakat demokratis, dalam pandangan Habermas, adalah dimana sebuah kelompok yang dominan secara politis, yaitu kultur mayoritas, memaksakan jalan hidupnya kepada minoritas yang kemudian berdampak kepada pengabaian kesetaraan hak yang efektif kepada warga negara lain dari latar belakang kultural yang berbeda.51 Masalah tersebut berkaitan dengan isu politik yang melahirkan self understanding secara etis dan sekaligus juga identitas rakyat pada umumnya. Dalam konteks ini, minoritas tidak bisa semata-mata sebagai subjek yang dikalahkan dalam pemilu oleh mayoritas. Pemerintahan mayoritas pada akhirnya bekerja dalam keterbatasan komposisi kewargaan yang dibayangkan akan menghasilkan sesuatu yang tampaknya dinilai sebagai prosedur yang netral. Padahal sesungguhnya prinsip mayoritas sendiri tergantung pada asumsi mereka sebelumnya mengenai kesatuan komunitas— atau unit politik, dalam bahasa Robert Dahl. Dengan demikian mayoritas akan kesulitan untuk berbuat adil, apalagi kepada minoritas. Perilaku adil 51 Ibid. 143-146 24 bagi kesatuan masyarakat secara keseluruhan sejatinya terletak di atas prinsip mayoritas tersebut. Dalam kacamata Habermas, secara umum diskriminasi terhadap minoritas dapat dieliminasi melalui proses inklusi yang memiliki sensitivitas yang memadai terhadap latar belakang kultural individu dan kelompok yang secara spesifik memiliki perbedaan-perbedaan.52 Demokrasi idealnya bisa men-setup proses inklusi tersebut. Persoalan minoritas sebagai mana kita tahu merupakan proplem endemik di masyarakat pluralistik, dan cenderung menjadi lebih akut di masyarakat multikultural.53 Namun pada perkembangan selanjutnya negara-negara demokrasi konstitusional menyediakan berbagai rute untuk mewujudkan sebuah impian yang tidak mudah, yaitu inklusi yang sensitif perbedaan, seperti delegasi kekuasaan di negara federal, desentralisasi atau transfer fungsional kompetensi negara, jaminan otonomi kultural, hakhak kelompok masyarakat dengan kekhasan tertentu, kebijakan-kebijakan kompensatori, dan mekanisme-mekanisme lain untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi kelompok minoritas.54 Prinsip moral-filosofis inklusi kemudian di-breakdown lebih lanjut oleh para pemikir ke dalam pengaturan politik demokrasi. Young, sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, merekomendasikan model demokrasi deliberatif sebagai demokrasi yang kompatibel dengan impian perwujudan ide keadilan untuk semua melalui politik inklusi. Inklusi merupakan ideal normatif tertinggi dalam demokrasi. Dalam cara pandang demokratisasi, berbasis pada pengalaman negaranegara Asia, Surendra menyebutkan bahwa politik inklusi merupakan tantangan terbesar demokratisasi. Politik inklusi merupakan upaya untuk 52 Ibid. Masyarakat pluralistik merujuk pada masyarakat dengan keragaman dan perbedaan-perbedaan di lapisan-lapisan besarnya, seperti ras dan agama. Sedangkan masyarakat multikultural merujuk pada keberagaman di level yang lebih minor, seperti pola sosialisasi, busana, atau bahkan mindset atau hal-hal yang tercakup dalam subcultural diversity, perspectival diversity, dan communal diversity. Lihat, antara lain, Lihat Bikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory (Cambridge, Massachusset: Harvard University Press, 2000), juga Hairus Salim dan Suhadi, Membangun Pluralisme dari Bawah (Jogjakarta: LKIS, 2007), hlm. 103-106. 54 Habermas, Op.cit. 53 25 memastikan bahwa demokrasi betul-betul maujud sebagai format sistem untuk mengatasi persoalan sehari-hari. Politik inklusi memungkinkan penghormatan atas bahasa dan diskursus seputar hak-hak dasar dan tanggungjawab dan seterusnya. Namun, demokratisasi yang berlangsung belakangan (di Asia secara umum) menunjukkan gejala demokrasi sebagai eksklusi, bagaimana mengeksklusi, dan kelompok-kelompok mana yang akan dieksklusi.55 Dengan cara pandang tersebut, maka politik inklusi demokratis merupakan agenda penting dalam demokratisasi. Pertanyaannya, apa itu politik inklusi demokratis? Meminjam Wolbrecht dan Hero, inklusi demokratis merupakan inkorporasi, pengaruh, dan representasi berbagai kelompok sosial yang tidak diuntungkan ke dalam institusi-institusi demokrasi.56 Dengan demikian, politik inklusi demokratis berkaitan dengan penyediaan saluran (channel) dan ruang (space) untuk melakukan inkorporasi, memberikan ruang mempengaruhi, dan mewadahi representasi kelompok minoritas melalui institusi-instisusi politik demokratis. Untuk mewujudkan politik inklusi demokratis, beberapa variasi bentuk ditawarkan. Beberapa benchmarks diajukan oleh Schmidt et al (2002) untuk mengakomodasi inklusi dalam lembaga-lembaga politik demokratis: 1) akses pernuh untuk partisipasi, 2) representasi dalam institusi-institusi dan prosesproses pembuatan kebijakan penting, 3) pengaruh atau kekuasaan dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan, 4) adopsi kebijakan-kebijakan publik yang menampung kepentingan dan concern kelompok-kelompok tidak diuntungkan, 5) paritas sosial ekonomi.57 Benchmarks inklusi yang disampaikan oleh Schmidt dkk. mengidealkan inkorporasi dalam derajat yang sangat luas atau penuh. Dalam kerangka penelitian ini elemen inklusi politik demokratis disederhanakan oleh peneliti menjadi dua benchmark umum, yaitu partisipasi politik dan representasi politik. Jika disandingkan dengan benchmarks Schmidt dkk, elemen partisipasi dapat meliputi benchmark 1 dan 3, 55 Surendra, Op.cit, hlm. 31 Wolbrecht dan Hero, Op.cit, Hlm. 4 57 Ronald Schmidt Sr, et.al (2002) sebagaimana dikutip Hero dan Wolbrecht, Op.cit, hlm. 4 56 26 sedangkan elemen representasi politik meliputi benchmark 2 dan 4. Penelitian ini pada operasionalisasinya mengacu kepada satu elemen inklusi politik demokratis. Bagaimana memahami dan mengevaluasi benchmark partisipasi politik? Urgensi partisipasi politik minoritas dapat dipahami dan dijelaskan dari dua perspektif: 1) perspektif hak-hak minoritas dan 2) argumen stabilitas demokrasi.58 Dalam perspektif hak-hak minoritas, asummsi dasarnya adalah bahwa hak-hak minoritas tidak mungkin dapat terpenuhi kecuali minoritas itu sendiri ambil bagian dalam proses-proses pengambilan kebijakan politik yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak minoritas. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang stabilitas demokrasi, tanpa tindakan protektif tertentu dalam melalui prosedur, mekanisme, dan institusi demokratis tertentu, hampir dapat dipastikan bahwa minoritas akan selalu berhadapan dengan resiko tereksklusi dari sistem. Di samping itu, ketiadaan partisipasi minoritas dalam sistem akan semakin mengukuhkan ketidakadilan demokrasi prosedural. Dengan demikian, demokrasi akan menjadi domain eksklusif mayoritas yang pelan-pelan akan kehilangan legitimasinya. Inefektivitas pemerintahan sangat mungkin terjadi dalam situasi ini. Hal tersebut pasti akan berdampak pada stabilitas demokrasi itu sendiri. Partisipasi itu sendiri dapat dipahami dalam spektrum pemahaman yang luas. Berangkat dari pengalaman Eropa, partisipasi politik dapat dipahami dalam tiga level partisipasi. Pertama, dalam proses konsultatif. Dalam proses konsultatif tersebut, kelompok minoritas menyuarakan pendapatnya tentang hukum atau peraturan tertentu, di sisi lain lembaga pemerintah harus mengkomunikasikan kebijakan terkait kepada minoritas. Di tahap ini tidak ada jaminan bahwa suara minoritas akan didengarkan. Kedua, pembuatan kebijakan bersama. Di level ini, minoritas terlibat sebagai bagian dari lembaga eksekutif, parlemen, atau lembaga-lembaga negara lainnya. Tingkat partisipasi demikian memungkinkan suara mereka untuk lebih didengarkan atau dipertimbangkan. Namun demikian praktek mengajarkan bahwa mereka 58 Bieber, Op.cit, hlm. 6 27 sering diabaikan dalam co-decision making, karena representasi mereka yang terbatas. Ketiga, pembuatan kebijakan penuh. Dalam tahap ini, Negara menyediakan lembaga minoritas khusus atau perwakilan dalam pemerintahan yang memberikan jaminan partisipasi mereka membuat keputusan dapat dilakukan secara penuh dan otonom.59 Sedangkan representasi, secara teoretik, dapat dieksplorasi sekaligus diuji secara empiris dengan dua model pokok: 1) representasi deskriptif, dan 2) representasi substantif.60 Representasi deskriptif61 merupakan sebuah bentuk representasi yang titik tekannya pada diri politisi yang dipilih untuk mewakili. Apakah orang yang dipercaya menduduki jabatan politik tertentu “tampak seperti” konsituennya. Jadi representasi disini dibayangkan melalui tampilan eksistensial, formal, bahkan numerikal. Dalam konteks Indonesia misalnya, apakah warga Muhammadiyah sudah terwakili dengan keberadaan political appointee dari Muhammadiyah dalam kabinet atau kementerian? Atau apakah warga Nahdlatul Ulama’ (NU) sudah terwakili dengan adanya legislator berlatarbelakang NU? Atau apakah penduduk dari Indonesia Bagian Timur sudah terwakili dengan keberadaan pejabat dari Indonesia Timur dalam jabatan-jabatan politik tertentu? Atau dalam konteks penelitian ini, apakah warga Syi’ah sudah terepresentasi dengan keberadaan politisi dengan latar belakang Syi’ah dalam jabatan politik tertentu? Meskipun tampak sederhana, representasi model ini merupakan sesuatu yang positif dalam demokrasi. Hal itu terutama jika terdapat komunikasi antara yang diwakili (constituents) dengan yang mewakili (representatives) dihalangi oleh kendala ketidakpercayaan, atau ketika kepentingan- 59 Ibid, hlm. 8-9 Canon, Op.cit, hlm. 282-285 61 Representasi deskriptif kerap juga dipanggil sebagai representasi simbolik, atau representasi deskriptif-simbolik. Lihat Robert C Smith, “Recent Elections and Black Politics: The Maturation or Death of Black Politics?”, PS: Political Science and Politics, 23:160-62. Juga disebut sebagai representasi kehadiran (representation of presence). Lihat Anne Phillips, Politics of Presence (New York: Clarendon Press/Oxford University Press, 1995). Atau disebut juga representasi cermin (mirror representation). Lihat Hanna Pitkin, The Concept of Representation, (Berkeley: University of California Press, 1971), hlm. 90 60 28 kepentingan penting dari kelompok deskriptif belum atau tidak terkristal, atau ketika kelompok-kelompok konstituen tidak diuntungkan atau memencar.62 Sementara representasi substantif merujuk pada perwakilan yang lebih dalam, tidak saja semata secara formal atau numeriko-eksistensial. Representasi model ini bergeser dari sekedar keterwakilan tampilan kepada keterwakilan kepentingan-kepentingan konstituen. Dalam model ini, tidak terlalu penting kehadiran representatif yang “tampak seperti” konstituen yang diwakili. Dalam konteks Indonesia, representasi substantif akan terjadi jika kebijakan-kebijakan pembangunan di Papua ditujukan untuk dan berdasarkan pada kepentingan orang-orang Papua, meskipun pengambil kebijakan politik tersebut bukan orang Papua. Atau dalam konteks penelitian ini, representasi substantif dipandang maujud jika kepentingan-kepentingan warga Syi’ah di lembaga legislatif dijadikan dasar dan tujuan meskipun tidak ada satupun di antara legislator disana yang berlatar mashab Syi’ah. Representasi dalam model ini lebih didasarkan pada ide63 dan tindakan64. Elemen pokok terwujudnya representasi ini adalah responsivitas perilaku dari para representatif. Namun juga dipengaruhi oleh tuntutan, pengawasan, dan penilaian konstituen atas perilaku representatifnya. Secara lebih spesifik, Young mendiskusikan representasi khusus untuk kelompok-kelompok yang termarginalkan, seperti perempuan, kaum miskin, minoritas, dan sebagainya. Dengan asumsi dasar bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan politik hanya bisa diatasi dengan perluasan inklusi (inclusion of) dan pengaruh (influence for) dan semakin pluralis representasi semakin substantif demokrasi itu dalam mewujudkan keadilan, Young merekomendasikan satu langkah penting yaitu melalui ketersediaan lembagalembaga assosiasional, di samping juga institusi-institusi politik untuk merepresentasi kelompok-kelompok yang dimarjinalkan tersebut, termasuk minoritas. Melalui rekayasa institusi politik kita harus memastikan bahwa 62 William T Bianco, Trust: Representatives and Constituents (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994) 63 Phillips, Op.cit 64 Hanna Pitkin (1967), dikutip oleh Canon, Op.cit, Hlm. 284 29 representasi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan menjadi semakin baik. Selain itu, representasi kelompok juga dapat dilakukan melalui gerakan sosial, berbagai macam komisi dan dewan, lembaga-lembaga swasta, sebagaimana juga lembaga-lembaga pemerintahan.65 Perluasan ruang dan saluran lembaga politik dan assosiasional akan semakin memperluas representasi kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalisasi. Perbaikan representasi secara politis dan assosiasional akan memugkinkan representasi minoritas pada tiga bagian penting, yaitu kepentingan (interest), pendapat (opinion), dan cara pandang (perspective) minoritas.66 Ketiga aspek tersebut menyiratkan, tidak saja kepentingan kelompok sebagai satu kesatuan, akan tetapi juga orang per orang dalam kelompok minoritas tersebut. Dengan demikian Young dengan sangat intensif mengajukan teori representasi yang berbasis pada rekayasa dan institusionalisasi politik dan assosiasional. Young membaca bahwa inekualitas (ketidaksetaraan) ekonomi dan sosial telah nyata-nyata memproduksi ketidaksetaraan politik dan secara relatif juga menghasilkan eksklusi dari diskusi-diskusi politik yang menentukan, terutama nasib semua orang, terutama kelompok minoritas yang terpinggirkan itu. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial telah menciptakan sistem dan fakta objektif bahwa kelas miskin dan pekerja tidak terepresentasi kepentingan dan perspektifnya, jika dibandingkan dengan kelas menengah atau kelas kaya misalnya. Sehingga hal itu harus mendapatkan koreksi melalui pelibatan kelompok tersebut dalam desain besar kelembagaan demokrasi inklusif pada level politis dan assosiasional yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi diskusi-diskusi dan proses-proses politik yang menentukan kepentingan dan perspektif dan, pada akhirnya, nasib mereka. Hal itu tentu saja sangat ditentukan oleh komitmen demokratis bersama, artinya komitmen bahwa saluran-saluran demokrasi yang tersedia adalah untuk menghimpun semua elemen dalam demokrasi, tidak hanya kelas atas 65 66 Young, Op.cit. Hal 141-145 Ibid. 140 30 akan tetapi juga kelas bawah, tidak cuma mereka yang secara jumlah sangat besar, namun juga kelompok minoritas. Dalam pengalaman Indonesia, kita pernah memiliki fase dimana komitmen demokrasi demikian sangat rendah. Demokrasi hanya dipahami sebagai mekanisme politik elektoral-prosedural untuk mengamankan kepentingan-kepentingan kelas-kelas atas dalam berbagai aspek demokrasi serta kelompok-kelompok mayoritas dalam sebuah inkorporasi politik yang menguntungkan mereka di satu sisi, akan tetapi mengeksklusi, bahkan sampai derajat tertentu merepresi, kelas bawah, minoritas, dan terpinggirkan. Kata kunci untuk mengatasi situasi tersebut adalah komitmen demokratik, yang hal itu kemudian dituntut oleh rakyat sepanjang Reformasi 1998, sehingga memungkinkan perbaikan level inklusi dalam demokrasi kita. Rekayasa sosial dan ekonomi untuk mengatasi inekualitas barangkali bisa dilakukan, akan tetapi hal itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi dalam situasi dimana hambatan-hambatan ekonomi—seperti lemahnya kondisi makro ekonomi, melemahnya pertumbuhan, melebarnya kesenjangan, dan lebih-lebih, rendahnya kemandirian ekonomi—masih terjadi. Rekayasa sosial juga merupakan cara intervensi untuk mengatasi inekualitas dengan prasyarat-prasyarat yang relatif compleks dan multiaspek. Belum lagi kalau menghitung seberapa besar tingkat mempengaruhi dari rekayasa tersebut. Rekayasa institusional politik dan assosiasional lebih memberikan pengaruh (influencing) dan “hanya” tergantung pada seberapa besar komitmen demokrasi, sebagaimana ditekankan Young di muka. Artinya, seberapa demokrasi akan dibuka untuk representasi politik sebanyakbanyak orang akan menentukan seberapa besar inekualitas bisa dikurangi. Dalam bahasa Florian Bieber, representasi politik secara substantif dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, ia merupakan bagian dari hak dasar minoritas—baik sebagai perorangan maupun kelompok, sedangkan di sisi lain 31 itu merupakan a broader tool to advance democratic governance in the country.67 Pertanyaannya kemudian bagaimana minoritas direpresentasi dalam demokrasi yang inklusif dengan basis institusi politis dan ssosiasional tersebut? Berbasis pengalaman Eropa, representasi politik bagi minoritas menurut Bieber dilakukan dalam empat bentuk.68 Pertama, asosiasi minoritas diberikan ruang agar memiliki peran formal dalam merepresentasi kepentingan-kepentingan minotitas. Dengan komitmen yang kuat pada demokrasi, sistem politik memberikan ruang kepada minoritas untuk ikut menentukan kebijakan yang berkenaan dengan kepentingan dan perspektif mereka sendiri. Dengan demikian, memberikan ruang kepada asosiasi minoritas tidak saja menutup ruang eksklusi kepada minoritas, akan tetapi lebih dari itu memberikan saluran politik melalui asosiasi-asosiasi tersebut untuk bisa menentukan, atau paling tidak mempengaruhi, kebijakan yang berkaitan dengan dirinya. Berkaitan dengan perspektif HAM, yang juga menjadi titik tekan penelitian ini, membuka ruang-ruang formal bagi asiosiasi minoritas, sesungguhnya berkaitan dengan salah satu hak dasar setiap orang, termasuk minoritas, yaitu hak universal untuk menentukan nasib sendiri self determination. Dalam konteks relasi antara politik dan hak asasi manusia, politik pada akhirnya tidak hanya berpihak pada (stand for) hak asasi manusia, akan tetapi secara lebih formal mempengaruhi (influence for) pemenuhan hak-hak asasi manusia. Jika mengacu pada teori representasi Pitkin, tampak bahwa format representasi politik melalui asosiasi minoritas sesungguhnya memberikan ruang bagi representasi substantif. Minoritas tetap diberikan ruang untuk memberikan dukungan dan atau aspirasi untuk terakomodasinya kepentingan, opini, dan perspektif minoritas, meskipun para pengambil kebijakan dalam suprastruktur politik formal tidak berasal dari kelompok minoritas. 67 68 Bieber, Op.cit, hlm. 8 Bieber, Op.cit, hlm. 11 32 Dalam konteks keterbukaan politik di Indonesia pasca 1998, ruangruang untuk pembentukan dan beroperasinya institusi-institusi assosiasional ini tersedia cukup lebar. Sehingga dapat kita cermati kemudian bagaimana Syi’ah di Indonesia melakukan utilisasi atas ruang dan saluran assosional yang disediakan oleh mekanisme demokrasi tersebut. Kedua, minoritas direpresentasi melalui sebuah institusi khusus yang dibentuk untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka. Institusi-institusi ini di negara-negara Balkan diwujudkan dalam bentuk dewan minoritas (minority council), dewan minoritas dan otonomi kultural (cultural autonomy and minority council), dan sebagainya. Repsentasi deskriptif atau representasi cermin Pitkinian sangat terbuka melalui format repsentasi melalui saluran ini. Dalam pengalaman Eropa Timur, masalah utama yang dihadapi oleh institusi-institusi minoritas ini adalah soal bagaimana pemilihan anggotaanggota dewan tersebut. Dua bentuk pemilihan sama-sama memiliki masalahnya sendiri. Jika pemilihan dewan ini dilakukan secara langsung akan banyak masalah yang muncul, misalnya siapa saja minoritas yang berhak memilih, siapa yang menentukan siapa yang berhak memilih, dan jika dua pertanyaan tersebut tak terjawab oleh prosedur formal yang memadai, maka terbuka peluang bagi terjadinya diskriminasi. Sebaliknya jika pemilihan tersebut dilakukan dengan cara pemilihan tidak langsung atau dengan penunjukan maka hal itu dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendiskriminasi yang lain, baik dalam relasi mayoritasminoritas maupun minoritas-minoritas. Menurut pandangan peneliti, saluran dan ruang yang kedua ini sulit untuk direplikasi dalam konteks kebhinnekaan dan komplikasi politik Indonesia. Selain itu, secara konstitusional belum tersedia fundamen/fondasi untuk diadopsinya saluran atau ruang bagi pembentukan dewan minoritas. Untuk itu, dalam konteks penelitian ini, salah satu saluran representasi dalam pengalaman Eropa ini tidak digunakan oleh peneliti untuk membaca pilihanpilihan representasi politik Jema’ah Syi’ah di Indonesia. 33 Ketiga, kepentingan minoritas diartikulasi oleh parpol atau lembaga negara yang tidak secara khusus merepresentasikan minoritas, namun untuk konstituensi yang lebih luas, yang tercakup di dalamnya kelompok minoritas. Jika meminjam perspektif Pitkin, maka saluran ini sesungguhnya membuka peluang besar bagi terwujudnya representasi substantif dan deskriptif sekaligus. Dalam teori politik modern, partai politik merupakan arena politik resmi seluruh warga negara untuk aggregasi dan artikulasi kepentingan mereka dalam arena negara demokrasi. Sebagaimana doktrin Macridisian, tidak ada demokrasi modern tanpa partai politik. Dalam teori, partai politik sebagai sebuah format inklusif dalam demokrasi harus menghindari penekanan yang berlebihan terhadap perbedaan-perbedaan primordial dan fisik, seperti agama dan etnisitas. Namun demikian, dalam kenyataannya partai politik hampir selalu mempersoalkan numerik, sehingga keberpihakan kepada yang besar secara numerik merupakan fenomena objektif, dan dalam sudut pandang yang lain dapat dikatakan bahwa selalu ada potensi bagi yang kecil secara numerikal untuk diabaikan. Dalam perspektif inklusi, partai politik merupakan ruang dan saluran politik yang sangat memadai bagi minoritas di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan politik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan, opini, dan perspektif mereka. Partai politik juga dapat dipandang dalam kacamata minoritas sebagai arena untuk mengkontestasi kepentingan dan aspirasi dalam kompetisi demokratik. Untuk konteks Indonesia, partai politik merupakan saluran yang sangat potensial bagi minoritas jika dilihat dari wataknya yang catch-all dan nyaris tanpa pembeda secara ideologis antara satu partai politik dengan partai politik yang lain. Hampir seluruh partai politik, termasuk partai agama dengan basis kanan Islam yang dalam teori politik aliran kerapkali dibedakan dengan partai nasionalis, memilih untuk berkumpul di “tengah” sebagai partai moderat dan 34 terbuka.69 Hal ini memberikan peluang bagi Syi’ah di Indonesia untuk menjadikan afiliasi dengan partai-partai politik sebagai saluran representasi politik. Keempat, minoritas direpresentasi secara khusus oleh sistem politik dalam sebuah partai tertentu untuk golongan minoritas. Dalam perspektif Pitkin, saluran yang keempat ini akan menginstitusionalisasi representasi cermin atau representasi deskriptif. Dalam pengalaman negara-negara Balkan, partai-partai politik yang secara khusus dibentuk untuk menjadi wadah politik minoritas merupakan hal fenomenal politik disana. Konfigurasi sistem kepartaian yang membuka ruang bagi etnik minoritas di negara-negara Balkan sebagian besar sebagai konsekuensi dari ketidakmauan mayoritas untuk secara serius melakukan inkorporasi atas urusan-urusan minoritas. Mengingat segregasi etnik yang sangat tajam, parpol lebih takut untuk kehilangan sentiment mayoritas dibandingkan dengan ideal mengakomodasi minoritas. Konsekuensi logisnya, minoritas akan selalu potensial teralienasi dari concern mayoritas dalam parpol, maka taka da pilihan lain selain mendirikan partai politik yang berdiri sendiri. Di Indonesia, dalam sistem kepartaian Indonesia modern atau pasca kemerdekaan, tidak pernah muncul partai politik yang secara ideologis muncul sebagai konsekuensi dari relasi mayoritas-minoritas yang mmeminggirkan minoritas. Partai-partai kecil yang tumbuh menjamur terutama pada Pemilu 1955, Pemilu 1999, dan Pemilu 2004 merupakan implikasi dari liberalisasi politik yang sedang berlangsung sesuai dengan konteks temporal masing-masing Pemilu. Partai-partai agama yang pernah muncul di Indonesia lebih tampak sebagai ekspresi politik keagamaan (atau sampai derajat tertentu dapat kita sebut politik aliran), bukan sebagai ekspresi dari keinginan untuk melepaskan diri dari alienasi minoritas oleh mayoritas dalam dinamika internal partai politik. 69 Beberapa pakar dan pengamat politik bahkan menandai situasi partai politik yang demikian sebagai matinya ideologi partai politik. 35 Namun demikian basis konstitusional dan demokrasi yang established di Indonesia hingga kini memungkinkan ruang pendirian partai politik atas dasar apapun. UU Parpol memberikan peluang bagi sekumpulan warga negara, atas dasar apapun, untuk mendirikan partai politik. Bagi Syi’ah sendiri, eksperimentasi pendirian parpol bahkan negara, seperti negara, merupakan hal yang tidak asing. Syi’ah dalam aneka sistem kepartaian di Timur Tengah memberikan referensi tentang berdirinya partai politik, meskipun dengan basis argumentasi yang khas Timur Tengah, dalam konteks itu, relasi Syi’ah dan Sunni di Iran, Irak, Suriah, Kuwait dan sebagainya, serta relasi Islam dengan zionisme seperti Hizbullah di Lebanon. Dengan perspektif teoretik tersebut, pilihan-pilihan representasi politik Jemaah Syi’ah dapat dijelaskan dengan beberapa kerangka: Pertama, pilihan Jemaah Syi’ah untuk memperjuangkan representasi dalam politik inklusi demokratis dilakukan melalui asosiasi-asosiasi masyarakat sipil. Kedua, representasi Jemaah Syi’ah diperjuangkan secara lebih formal melalui afiliasi dengan partai-partai politik kontestan Pemilihan Umum. Ketiga, representasi politik Jemaah Syi’ah diperjuangkan melalui asosiasi-asosiasi sipil demokratis yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Keempat, representasi politik Jemaah Syi’ah melalui pembentukan partai politik ideologis. Dengan kerangka teoretik yang ditawarkan oleh Young dan Bieber tentang representasi berbasis institusi politik dan assosiasional tersebut, dapat diajukan beberapa pertanyaan kunci sekaligus indikator-indikator untuk dijawab secara faktual melalui penelitian ini: Pertama, berkaitan dengan sikap Syi’ah terhadap representasi politik Jema’ah Syi’ah dalam demokrasi politik di Indonesia; 1. Apa dan bagaimana Syi’ah memandang politik? 2. Apa dan bagaimana sikap Syi’ah mengenai negara? 3. Bagaimana sikap mereka mengenai representasi politik dalam negara Indonesia? 36 Kedua, berhubungan dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memperjuangkan representasi politik mereka dalam kerangka inklusi politik demokratis; 1. Bagaimana Syi’ah memanfaatkan saluran-saluran institusi politik untuk merepresentasi kepentingan (interest), pendapat (opinion), dan cara pandang (perspective) Jema’ah Syi’ah di Indonesia? 2. Bagaimana mereka mengoptimalkan ruang dan saluran institusi assosiasional untuk representasi politik tersebut dalam kerangkan demokrasi yang lebih inklusif? 3. Apa dan bagaimana peluang, kendala, dan persoalan mendasar yang mereka hadapi dalam kerangka representasi politik tersebut? E. Metode Penelitian 1. Jenis, Pendekatan, dan Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif.70 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik, 71 Penelitian ini akan mengkombinasikan dua metode, yaitu field-study dan desk-study. Secara operasional metode field-study digunakan untuk pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi/pengamatan. Sedangkan metode desk-study secara teknis digunakan untuk melakukan pengumpulan data sekunder dan analisis data penelitian. 70 Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan atau analisis untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, gejala atau perilaku yang diamati. Lihat Moleong, 1998, Metodologi Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 3 71 Dengan pendekatan ini, peneliti bersifat aktif dalam melakukan interaksi dengan subjek penelitian dalam situasi apa adanya tanpa adanya rekayasa, sehingga data diperoleh dari fenomenanya yang bersifat asli dan natural. Lihat Indah Sulistyo Arty, 2006, “Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik”, Makalah, disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 2627 Desember 2006, hlm. 1 37 Dalam relasi konseptual-faktual penelitian ini, metode field-study lebih banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua mengenai bagaimana tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memperjuangkan representasi politik mereka dalam kerangka inklusi politik demokratis. Meskipun demikian, dalam beberapa isu digunakan untuk mengkonfirmasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama. Sedangkan metode desk-study lebih ditekankan penggunaannya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama tentang bagaimana sikap Syi’ah terhadap representasi politik Jema’ah Syi’ah dalam demokrasi politik di Indonesi. Walaupun begitu, dalam beberapa isu spesifik metode ini juga digunakan untuk mengkonfirmasi beberapa data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua. 2. Sumber Data dan Subjek Penelitian Sumber data penelitian ini berupa person dan paper.72 Penentuan subjek penelitian berupa person dilakukan dengan teknik purposif. Dengan teknik ini, ditetapkan kriteria-kriteria informan sesuai dengan tujuan penelitian, sebagai berikut: a. Warga Jemaah Syi’ah atau di luar Syi’ah, b. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan Jemaah Syi’ah sebagai baik secara individual maupun institusional, c. Memiliki informasi mengenai perjuangan politik Jemaah Syi’ah untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut, maka informan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: a. Tajul Muluk, Pemimpin Pondok Pesantren Syi’ah “Misbahul Huda” b. Ahmad Hidayat, Sekjen Ahlulbayt Indonesia (ABI) 72 Yang dimaksud dengan sumber data disini adalah subjek dari mana data diperoleh. Suharsimi Arikunto mengklasifikasi sumber data menjadi tiga jenis ; a. person, yaitu sumber data (informan) berupa orang. b. place, yaitu sumber data berupa tempat, dan c. paper, yaitu sumber data berupa simbol. Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107 38 c. Syafinuddin Al-Mandari, Wakil Sekjen Ahlulbayt Indonesia (ABI) d. Husnul Yaqin, Ketua DPD Ahlul Bayt Indonesia (ABI) Sumatera Selatan e. Ghufron Buchori, Mantan Ketua Umum Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) f. Alexander Lagobar, Pengurus IJABI Makassar g. Safwan, Pimpinan Rausyan Fikr Institute Yogyakarta h. RS, intelektual Syi’ah, kandidat doktor dari Tilburg University Belanda Pengumpulan data dari mereka dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview) yang dilaksanakan dengan berpedoman pada panduan wawancara (interview guide). Panduan tersebut tidak sepenuhnya mengikat proses wawancara secara kaku, sebaliknya wawancara dapat berkembang sesuai dengan situasi masyarakat dan khususnya informan atau subjek penelitian. Meski demikian, peneliti tetap berupaya untuk menggunakan strategi teknis secara jeli agar hasil wawancara dapat memeberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan penelitian. Sedangkan sumber data berupa paper dimanfaatkan untuk data collecting dengan dua teknik dua teknik: 1) studi kepustakaan; yaitu dengan memanfaatkan buku-buku pokok yang memuat data-data penting mengenai Jemaah Syi’ah sesuai dengan tujudan penelitian. 2) Studi dokumen, yaitu pengkajian atas berbagai dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal; bersifat internal dalam artian pengkajian langsung atas dokumen, sedangkan yang bersifat eksternal berupa sumber-sumber yang mendukung pengkajian atas dokumen. Dokumen internal yang menjadi sumber data penelitian ini antara lain data demografi Kabupaten Sampang, data anggota atau pengikut Jemaah Syi’ah Sampang, dan sebagainya. 39 3. Pengujian Keabsahan Data Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi.73 Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu teknik pengecekan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari person dengan paper (hasil wawancara mendalam dengan studi pustaka dan dokumentasi) atau paper dengan paper, atau person dengan person lainnya. 4. Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif.74 Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, meliputi reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi.75 73 Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Lihat Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 178 74 Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data. Lihat Moleong, Metodologi Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hal 205 75 1) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan penyaringan data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. 2) Display data yang dilakukan berupa penyajian secara deskriptif atau naratif data yang telah direduksi dalam bentuk laporan yang sistematis. 3) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.Pengambilan kesimpulan dan verifikasi adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Lihat Sayekti Pujosuwarno, Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta, 1992), hlm. 19 40