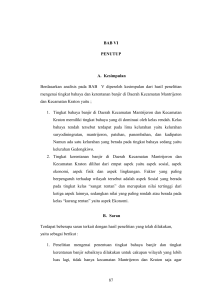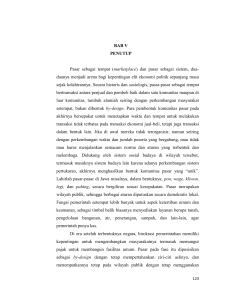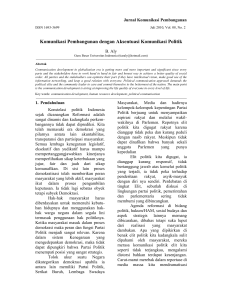BAB I Menggulirkan Wacana Pembatasan Kepemilikan
advertisement

BAB I Menggulirkan Wacana Pembatasan Kepemilikan Tanah bagi Warga Keturunan China di Yogyakarta A. Latar Belakang Penelitian ini hendak mencari tahu upaya warga keturunan China di Yogyakarta dalam mengakses haknya atas tanah. Daerah Istimewa Yogyakarta memberlakukan pelarangan hak atas tanah berupa Hak Milik bagi warga keturunan China. Hal ini berdasarkan pada Surat Instruksi Gubernur No. K.898/I/A/1975. Dengan instruksi tersebut Pemerintah Daerah ingin melindungi hak warga pribumi atas tanah dari penguasaan besar-besaran oleh non-pribumi yang dianggap lebih kuat secara finansial. Mereka hanya berhak atas Hak Guna Bangunan yang dapat diperpanjang setiap 20 tahun sekali. Biarpun hanya berupa Instruksi Gubernur, nyatanya aturan pembatasan kepemilikan tanah bagi warga keturunan China tersebut masih berlaku dan memiliki daya ikat. Padahal melalui Undang-undang Pokok Agraria 1960 hak setiap warga negara atas tanah telah dijamin sepenuhnya tanpa membedakan ras atau kesukuan. Begitu juga dengan Undang-undang Kewarganegaraan 2006 yang telah menghapuskan dikotomi pribumi dan bukan pribumi. Dilihat dari kacamata hukum, Instruksi Gubernur 1975 seharusnya batal demi hukum. Posisinya sangat lemah bila dibandingkan dengan aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pertanahan. 1 Urusan pertanahan menjadi salah satu hal istimewa yang (turut) disahkan dalam Undang-undang Keistimewaan DIY 2012. UUK memberi ketegasan posisi Kraton sebagai badan hukum yang berhak mengatur hal-hal keistimewaannya. UUK mengembalikan “kedaulatan” DIY. Kini DIY berhak mengatur perihal keistimewaannya secara penuh dan lengkap. Pun mengatur kepemilikan hak atas tanah bagi warga keturunan yang menghuni Kota Budaya ini. Sebagai yang istimewa, Yogyakarta merasa perlu melindungi hak-hak pribumi atas tanah dari penguasaan masif oleh warga keturunan yang dianggap lebih kuat secara finansial. Tetapi konsep melindungi itu perlu kembali ditinjau ketika beberapa kasus pertanahan mulai muncul ke permukaan. Berbekal UUK Kraton sedang giat menginventarisir kembali semua pertanahan di Yogyakarta. Menurutnya, semua tanah-tanah tidak bersertifikat (tidak bertuan) adalah milik Kraton. Masyarakat petani pesisir Kulon Progo masih terus mencangkul dengan perasaan cemas. Bagaimana tidak? Tanah pasir yang selama puluhan tahun secara turun–temurun diolahnya menjadi lahan produktif penghasil hortikultura, hendak diambil pemerintah atas nama Kraton dan Pakualaman. Mereka sangat berminat menambang kandungan mineral pasir besi yang terkandung sejak mengetahuinya. Masyarakat petani melakukan perlawanannya dengan terus bertanam, biarpun UUK semakin menguatkan posisi Kraton dan Pakualaman atas tanah. Medio 2013 juga pernah memotret pengusiran warga pribumi di tanah magersari. Mereka terdiri dari lima keluarga yang diusir dari pemukimannya selama ini karena tidak mengantongi ijin meminjam dari Kraton. Bekas 2 pemukiman yang mereka tinggali kini dipinjamkan kepada pengusaha keturunan China oleh Kraton melalui Panitikismo. Melihat kedua realitas di atas, masihkah instruksi 1975 relevan disebut sebagai pelindung hak-hak pribumi atas tanah di Yogyakarta? Ataukah tersebut justru sebuah indikasi bahwa warga keturunan hanya dijadikan buffer politik atas elit dalam menguasai dan mengelola pertanahan di Yogyakarta? Maka, persoalan agraria hendaknya dikelola secara tepat. Terlebih lagi di wilayah ini karena masyarakat masih mengakui eksistensi Kraton dan Pakualaman. Sejak status kepemilikannya, penguasaan, dan pengelolaan, urusan tanah bukanlah perkara mudah. Mengingat semua kehidupan terjadi di atasnya dan semua makhluk pasti menggantungkan kehidupan dari kekayaan yang terkandung dalam tanah. Bahasan agraria tidak akan pernah selesai dimakan zaman. Agraria adalah persoalan hidup dan mati bagi siapapun yang tinggal di atasnya. Meskipun hanya tanah, benda ini tidak berarti apa-apa tanpa aktivitas kerja manusia di atasnya. Tetapi luasnya tidak pernah menjangkau hasrat manusia untuk memiliki, justru sebaliknya. Demi tanah, jamak kita saksikan air mata bahkan nyawa menjadi taruhannya. Maka itu penguasaannya selalu merupakan hal yang rumit karena menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, demografi, hukum, politik, dan sosial (Wiradi : 2008). Aspek ekonomi menyebut tanah sebagai faktor produksi yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Namun perbandingannya tidak pernah setara dengan pertambahan jumlah penduduk, sedangkan luasnya tetap; tidak bertambah, maka membawanya pada persoalan demografi. Sedangkan pengaturan 3 kepemilikan, penguasaan, dan pengusahaannya membutuhkan aspek hukum yang membuatkan kerangka hak dan kewajiban penduduk atas keberadaan tanah tersebut. Lalu untuk memastikan semua berjalan dengan baik sesuai hak dan kewajibannya, di sini diperlukan kehadiran aspek politik yang memiliki daya paksa (wewenang) untuk mengatur semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Lantas terjadilah hubungan sosial antara manusia-manusia yang mengambil manfaat dan kelompok-kelompok yang mengatur pertanahan. Persinggungan itulah yang akan menjelaskan makna sosial dalam hal ini (Wiradi : 2008). Pembatasan hak memiliki tanah tersebut sebetulnya diberlakukan bagi semua warga keturunan baik China, India, atau Arab yang bermukim dan mencari penghidupan di Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini hanya akan mengulik pergulatan warga keturunan etnis China atas tanah. Dibandingkan etnis lainnya, etnis China lebih menunjukkan proses adaptasi yang unik, alot, canggih, hingga kadang serba salah. Menurut Schwartz (1994) dalam Ubed Abdilah, etnis China hanya merupakan sebagian kecil saja (4%) dari total penduduk Indonesia namun mampu menguasai sekitar 70% aktivitas ekonomi Indonesia. Jumlahnya minoritas namun mampu menguasai perekonomian Indonesia hingga memicu kecemburuan sosial. Pada periode 1998 Indonesia mengalami fase transisi rezim dari Orde Baru yang bergaya diktator beralih pada reformasi. Banyak kerusuhan mewarnai pergantian rezim saat itu. Di Jakarta, etnis China menjadi sasaran amukan massa sebagai pelampiasan amarah terhadap Orde Baru yang dianggap menganakemaskan golongan China (di sektor perekonomian). Sikap istimewa ini berawal 4 dari pemberian hak-hak istimewa berupa penyediaan barang-barang kebutuhan tentara oleh Soeharto kepada rekannya seorang China, Liem Sioe Liong (Abdilah. S. : 2002). Bahkan kerusuhan serupa juga terjadi sampai di Solo. Hebatnya, kerusuhan itu tidak menjalar hingga Yogyakarta. Padahal jarak keduanya berdekatan. Hal ini disebut-sebut ada campur tangan Sultan Hamengku Buwono X dalam melindungi seluruh masyarakatnya. Hubungan Kraton dengan warga etnis China boleh dibilang harmonis. Sebelum masa kemerdekaan warga etnis China pernah menganugerahi sebuah prasasti untuk Kraton atas pengayoman kepada masyarakatnya yang juga dirasakan mereka saat itu. Tindakan itu merupakan ungkapan terima kasih kepada Sultan yang telah mengayomi mereka di perantauan ini. Oleh kebijakan Sultan mereka diberi tempat permukiman yang sekarang kita kenal sebagai kampungkampung pecinan Yogyakarta, antara lain Ketandan Malioboro dan Jalan Solo. Tanah-tanah Kraton banyak dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan menyelenggarakan pemerintahan nasional. Pembangunan Gedung Agung, Benteng Vredeburg, kantor-kantor pemerintahan, dan beberapa universitas di Yogyakarta misalnya, dibangun di atas tanah Kraton. Setiap bangunan tersebut boleh berada di tanah-tanah milik Sultan karena kegiatannya bertujuan untuk kemajuan sosial, pengembangan ilmu, dan kemaslahatan umat. Bila melihat kondisi wilayah geografisnya, Yogyakarta cukup kering akan sumber daya alam. Tapi sejauh ini masyarakatnya berada dalam kehidupan yang ayem. Jarang terjadi perselisihan antarwarga karena memperebutkan sesuatu hal. Selama ini tempat wisata bersejarah, pendidikan, dan kuliner menjadi daya tarik 5 utama bagi Yogyakarta yang menyandang Kota Budaya dan Pelajar. Namun, komoditi itu tidak menjadi persoalan besar bagi masyarakat. Seolah-olah masyarakat sudah paham hak bagian masing-masing. Ketentraman yang muncul tentu tak luput dari peran Sultan sebagai pengayom dan yang disegani masyarakat. Tanah sebagai modal utama produksi telah dipegang oleh Sultan sehingga masyarakat terjaga kepemilikannya. Oleh karena itu penelitian ini tidak akan memisahkan kekuasaan Gubernur dan Sultan sebagai pemegang kuasa politis dari lembaga budaya sekaligus pemerintahan di Yogyakarta. Memisahkan kedudukan kedua posisi politik ini bukanlah perkara mudah atau bahkan hal yang mustahil. Begitupun memisahkan kepentingan di balik motif keluarnya instruksi tersebut. Meskipun kedua jabatan yang melekat pada satu subjek ini mampu dipisahkan secara seksama dalam keterkaitannya dengan tanah maka penulis mengira tetap akan terjadi satu keberpihakan yang sama atas penguasaan tanah, yakni milik Raja (Kraton). Penguasaan tanah di sini sangat erat hubungannya dengan pengaturan tanah oleh Kraton, mengingat perolehannya pada masa dahulu yang merupakan milik Raja (Kraton) atas hasil perang. Sebelumnya, penelitian terkait pembatasan kepemilikan tanah bagi warga keturunan China di Yogyakarta pernah dilakukan oleh Satrio Yudharianto, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UGM 2010. Penelitian itu melihat konstruksi hukum Instruksi 1975 dengan aturan perundangan lainnya yakni Undang-undang Pokok Agraria 1960 dan Undang-undang Kewarganegaraan 2006. Dalam tesisnya Ia menyimpulkan bahwa bila dilihat dari konstruksi hukum, 6 instruksi 1975 selayaknya tidak lagi diberlakukan karena menyalahi azas hukum (lex superiori derogat legi inferiori) peraturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkan peraturan hukum yang lebih rendah. Keberlangsungan instruksi 1975 hingga saat ini dianggap sebagai bentuk kearifan lokal Pemerintah Daerah dan Kraton. Keduanya bermaksud melindungi hak warga pribumi atas tanah dari penguasaan oleh warga keturunan China yang dianggap lebih kuat secara finansial. UUK mungkin saja merupakan potret Yogyakarta yang bergejolak menuntut penegasan identitas “ke-akuan” yang ingin kembali dimiliki daerah kecil ini. Tahta istimewa yang pernah diberikan kepada rakyatnya ingin kembali diraih bersama meluasnya konsep Otonomi Daerah. Melihat realitas di atas, penelitian ini menjanjikan paparan tulisan menarik terkait usaha warga keturunan China dalam memenuhi haknya atas tanah di Yogyakarta. Sebelumnya akan sedikit dicari tahu bagaimana etnis China diposisikan sebagai buffer politik dari setiap rezim pemerintahan Indonesia. Selain karena ketertarikan penulis terhadap tempat kelahirannya yang ternyata menyimpan teka-teki bagi tetangganya yang “lain.” Oleh karena semua itu, topik ini diangkat. B. Rumusan Masalah Dari paparan latar belakang diambilah sebuah rumusan masalah seperti berikut ini: 7 “Bagaimana siasat yang dilakukan warga keturunan China dalam memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik di Yogyakarta?” C. Tujuan Penelitian 1) Mengetahui bagaimana warga keturunan China mengakses haknya atas tanah di Kota Yogyakarta. 2) Mengetahui kuasa Kraton atas tanah-tanah di Yogyakarta melalui kebijakan pertanahan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. 3) Mengetahui sebab dibatasinya hak warga keturunan atas tanah di Kota Yogyakarta. D. Kerangka Teori D.1. Kraton dan Elit Kraton dalam Konsep Berbangsa Negara Republik Indonesia Kraton merupakan entitas lengkap bagi masyarakat Yogyakarta. Sebelum bergabung dengan NKRI, Yogyakarta merupakan kerajaan lengkap dengan atributnya. Setelah bergabung dengan NKRI lembaga ini masih eksis karena penghormatan masyarakatnya, terlebih lagi masyarakat yang fanatik terhadap Kraton. UUK resmi disahkan pada 2012. Yogyakarta kini memiliki legitimasi atas keistimewaan yang seperti dibayangkan. Ada beberapa hal yang menjadi bagian keistimewaan Yogyakarta, diantaranya urusan pertanahan. Pada Bab X dinyatakan bahwa “kembali” Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman memiliki hak milik atas 8 tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten dengan dikukuhkannya keduanya menjadi badan hukum (subjek hak milik) atas tanah. Bila kita menengok Kepres Tahun 1984 yang memberlakukan UUPA 1960 sepenuhnya di Yogyakarta, maka sudah sepatutnya kedua jenis tanah SG dan PAG lebur menjadi tanah negara. Segala aturan pertanahan di Yogyakarta sewajarnya pun mengikuti aturan nasional (dengan UUPA). Seperti disebutkan dalam Diktum UUPA huruf A bahwa “Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.” Munculnya Kepres Tahun 1984 tidak lain adalah inisiatif Sultan HB IX yang saat itu juga kontroversial, karena dianggap menyerahkan kedaulatan kerajaan pada negara yang bahkan baru lahir. Namun juga hal tersebut yang menimbulkan simpati masyarakat dan sejumlah negarawan lainnya yang menganggap hal itu merupakan suatu kebijaksanaan Sultan HB IX demi kesejahteraan rakyatnya. Dengan inisiatif Sultan HB IX maka kebijaksanaannya ditanggapi baik oleh Pemerintah Pusat untuk segera memberlakukan UUPA sepenuhnya di Yogyakarta. Menyerahkan kewenangan pertanahan yang semula merupakan urusan otonomi melalui payung hukum UU DIY 1950 menjadi urusan dekonsentrasi mengikuti aturan pertanahan nasional. Adalah Sultan HB X sebagai raja yang sedang berkuasa beserta keluarga memainkan peran sebagai elit. Posisi ini sudah secara alamiah didapatnya sebagai penerus sah tahta keturunan Mataram. Demikian pula dengan anggota 9 keluarganya, baik keluarga inti maupun batih semua menduduki strata sosial yang tidak dapat dimiliki secara bebas oleh orang kebanyakan. Terlebih lagi adalah karena Sultan HB X menduduki dua jabatan politis yakni sebagai Kepala Daerah (Gubernur DIY) sekaligus merupakan seorang Sultan (Raja) dari Kraton yang masih eksis. Eksistensi Kraton setelah bergabungnya dengan Republik Indonesia memang tidak luntur. Kraton masih menjadi simbol atas lembaga budaya yang diakui persis oleh masyarakatnya. Tidak jarang kita saksikan masyarakat Yogyakarta bahkan dari luar Yogyakarta yang sangat menyambut dengan antusias dan mempercayai perhelatan ritual yang diadakan Kraton (mis: Jamasan, Gunungan Maulud Nabi). Bagi masyarakat yang fanatik terhadap Kraton, Sutoro Eko dalam Membongkar Mitos Keistimewaan, menyebutnya sebagai golongan konservatif. “Golongan ini terbelenggu pada basis kekuasaan feodalistik dan sangat dipengaruhi oleh paradigma klientelisme. Haluan ini cukup puas pada mempunyai pola kepemimpinan kharismatik-benevolent, serta visi mempertahankan status formal keistimewaan Yogyakarta yang sudah ada, sesuai dengan kekhasan budaya Yogya, aturan hukum yang ada serta pengalaman sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu, terutama pengorbanan Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII terhadap rakyat dan republik Indonesia, selalu digunakan sebagai justifikasi kaum konservatif untuk mempertahankan matimatian status formal keistimewaan Yogyakarta. dengan justifikasi ini pula, haluan konservatif menegaskan bahwa Kraton dan provinsi 10 harus disatukan, serta menegaskan bahwa Sultan dan Paku Alam secara otomatis merangkap sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.” Memaknai elit, seperti dikutip Schoorl dari Lipset dan Solari dalam Kuasa Elit (Haryanto: 2005) menyebutkan bahwa elit adalah posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas. Senada dengan pengertian dalam KBBI yang mengutarakan elit sebagai suatu kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi seperti bangsawan dan cendekiawan. Kedua pengertian tersebut sepakat pada kesamaan mengenai elit, bercirikan sejumlah kecil orang dengan kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Orang-orang yang menduduki posisi elit itu merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keunggulan lain (atau juga lebih) dari orang kebanyakan lainnya–superioritas. Orang-orang yang menduduki posisi elit menguasai kelebihan tidak di semua lini kehidupan, melainkan hanya pada beberapa saja. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa elit juga memiliki kelebihan pada beberapa aspek kehidupan. Maka elit adalah orang-orang dengan keunggulan tertentu daripada orang lainnya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki elit tersebut membuatnya menjadi berbeda dan memiliki pengaruh atas kebijakan-kebijakan yang mungkin diambil ketika mereka terlibat dalam suatu lingkungan. 11 Kemunculan elit secara alamiah akan menempatkannya sebagai pemimpin atas kebanyakan orang lain (massa). Bila dilihat dari kuantitasnya, elit selalu berjumlah lebih sedikit daripada massa. Namun elit memiliki keunggulan lebih daripada massa. Penguasaannya terhadap sesuatu yang tidak dikuasai massa ini membuat elit tampak lebih unggul. Maka, dengan keunggulan yang dimiliki elit akan mendaulatnya menjadi pemimpin atas kebanyakan orang lainnya (massa) dalam sebuah lingkungan. Robert Michels mengutarakan bahwa tidak akan ada masyarakat tanpa suatu kelas “dominan” atau kelas politik. Orang-orang dengan keunggulan lebih inilah yang menempati kelas dominan (elit). Maka kelompok minoritas ini yang memberlakukan “tatanan legal” yang merupakan hasil dominasi dan eksploitasi terhadap massa. Kelompok minoritas tidak pernah benarbenar mewakili golongan mayoritas. Stratifikasi politik semacam ini menegaskan bahwa orang-orang dalam posisi massa tidak memiliki kuasa sebanyak yang dimiliki elit. Sedangkan elit dengan kelebihannya akan mampu menggenggam dan menjalankan kekuasaan (terlibat dalam pembuatan-pembuatan kebijakan). Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa semakin ke atas posisi seseorang atau sekelompok orang dalam stratifikasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kekuasaan yang semakin besar; demikian pula sebaliknya semakin ke bawah posisi seseorang atau sekelompok orang mengandung arti bahwa yang bersangkutan memiliki kekuasaan yang semakin kecil atau bahkan tidak memilikinya sama sekali.1 1 Haryanto, Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar (Yogyakarta: Program Pascasarjana PLOD UGM, 2005), hlm. 78-79. 12 Kraton lahir sebagai sebuah kerajaan baru pecahan dari Mataram akibat Giyanti 1755. Pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Sultan. Sedangkan pergantian tampuk kekuasaan akan selalu berdasarkan keturunan rajaraja terdahulu, bukan diperoleh karena persaingan demokratis. Begitulah tradisi pergantian tampuk kekuasaan dalam Kraton yang menduduki posisi Raja. Sebagai lembaga budaya, Kraton juga tetap melestarikan paugeran yang menyangkut banyak hal, seperti misalnya proses pergantian pemimpin (Raja), upacara-upacara jumenengan maupun Maulud Nabi hingga jamasan benda-benda pusaka. Bahkan, masyarakat sangat mempercayai adanya nilai magis yang dimunculkan pada setiap event budaya yang digelar Kraton. Sedangkan Robert van Niel (1984) secara lugas mengungkapkan elit adalah kaum priyayi atau kaum apapun yang menempati strata lebih tinggi daripada rakyat jelata. Di Indonesia ini menjadi fenomena gamblang, di mana keberadaan priyayi masih ditentukan (merujuk) pada keluarga kerajaan. Terlebih lagi di Yogyakarta. Kraton masih eksis dan keluarga besarnya adalah elit dari rakyat kebanyakan yang tidak memiliki kuasa apa-apa, sedangkan Kraton adalah pusat kebudayaan dan politik bagi masyarakat. Masih menurut van Daniel, orang Indonesia secara besar terpetakan menjadi dua golongan, adalah masyarakat tidak berkuasa atau kelompok petani, orang desa dan kampung yang dinamai rakyat jelata dan kelompok administratur, pegawai pemerintah, dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan baik di desa maupun di kota menempati urutan lebih tinggi kemudian disebut dengan elit atau priyayi. 13 Harold Laswell mengungkapkan bahwa pergeseran elit sangat mungkin terjadi di antara elit itu sendiri atau juga dari luar. Untuk mempertahankan kedudukannya sebagai elit yang berpengaruh, elit perlu melakukan tindakantindakan yang mendukung langgengnya kekuasaan. Mereka perlu melakukan inovasi atau pun sekadar penyegaran yang memberi penegasan kepada masyarakat (massa yang dipimpinnya) bahwa mereka masih ada (eksis). Menurut Laswell ada upaya-upaya yang lazim dilakukan elit untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaannya, yakni kemampuan untuk meyakinkan dan memanipulasi, sampai dengan kemampuan untuk melakukan pemaksaan baik dengan kekerasan ataupun tidak.2 Ia menambahkan bahwa hanyalah elit dengan tingkat kecakapan dan memiliki nilai-nilai (values) terbanyaklah yang akan berhasil menduduki posisi elit, bahkan untuk mempertahankan. Dengan demikian, cakupan elit politik relatif mudah ditentukan: elit politik akan mencakup anggota-anggota pemerintahan dan pejabat tinggi, para pemimpin militer, dan dalam beberapa kasus, keluarga-keluarga aristokrat dan kerajaan yang secara politis berpengaruh dan para pemimpin usaha-usaha ekonomi yang kuat.3 D.2. Konsep Feodalisme dalam Sistem Kepemilikan Pengelolaan Pertanahan Yogyakarta Feodalisme merupakan suatu sistem pemerintahan yang utamanya erat berkaitan dengan sistem sosial ekonomi lingkungan sekitarnya. Sistem feodal memang sangat melekat dengan kepemimpinan raja (kerajaan). Hal ini sangat erat kaitannya karena pada waktu pemerintahan itu berlangsung, kuasa raja adalah 2 3 Ibid., hlm. 128. T.B. Bottomore, Elite dan Masyarakat (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006), hlm. 12. 14 mutlak, baik tanah maupun segala yang tinggal di atasnya. It is a method of government in which the essential relation is not that between ruler and subject, nor state and citizen, but between lord and vassal (Strayer and Coulborn 4:1956). Feodalisme mencerminkan adanya hubungan penguasa dan jelata (budak) yang dipekerjakan untuk mengambil manfaat atas budak dengan biaya yang minimal. Hubungan yang terjalin antara budak dengan penguasa diperantarai oleh orang-orang kepercayaan penguasa yang menguasai suatu wilayah tertentu. Orang-orang kepercayaan penguasa ini menunjuk dan menjalin hubungan dengan para pekerja di bawahnya. Di sini komunikasi antara kedua pihak tersebut sangat penting, sehingga hubungan yang dekat dan mudah perlu dicapai. Intensitas komunikasi diperlukan sebagai upaya controlling dari atasan pada budaknya (vassal). Feodalisme pun mendelegasikan kewenangan/ kekuatan politik juga terdapat pada kaki tangan penguasa yang berada di daerah-daerah. Lebih lanjut, F. Lot dan M. Bloch (Strayer and Coulborn 6:1956) meringkas feodalisme sebagai suatu hubungan antara penguasa dan pekerja, yang dalam hal ini yang disebut penguasa adalah penguasa tanah dan vassal yang dimaksud pun adalah budak/tenaga pekerja di tanah-tanah penguasa. Para pekerja/budak bergantung pada tanah-tanah yang dimiliki raja sedangkan kerajaan pun memerlukan materi untuk tetap menjaga keberlangsungan kerajaannya. Para kaki tangan pun membutuhkan tenaga yang murah untuk mengelola tanah-tanah yang dikuasainya agar menghasilkan upeti bagi keberlangsungan kerajaan. Oleh karena itu, sebagai kaki tangan raja, penguasa memiliki kuasa untuk menentukan segala yang terkait dengan pengelolaan tanah. Bahkan, pada masa feodalisme 15 masuk ke Eropa Utara, penguasa berhak menentukan harga dan memberi pajak pada hasil olahan tanah. Adalah tanah merupakan kue kekuasaan yang sangat penting dan utama bagi keberlangsungan sistem feodalisme ini. Oleh karena kekuasaan kerajaan saat itu bersifat mutlak, sehingga pengelolaan tanah adalah hal penting. Tanah-tanah yang luas itu dipercayakan oleh raja pengelolaannya kepada kaki tangan raja tersebut. Setiap kaki tangannya memiliki kuasa atas suatu wilayah tanah. Para kaki tangan raja memiliki orang-orang yang bekerja mengolah tanah-tanah itu dengan ketentuan harus mengumpulkan upeti untuk kerajaan. Setelah menunjuk Kraton sebagai daerah swapraja yang menempati posisi elit seperti di atas, lebih lanjut akan diutarakan perihal bagaimana elit – Kraton menggunakan dan menjaga kekuasaannya. Meminjam pendekatan feodalisme, konsep ini menerangkan pentingnya keberadaan tanah untuk mendukung keberlangsungan sebuah kerajaan. Feodalisme digambarkan sebagai suatu sistem politik di mana kerajaan mendelegasikan kewenangan – melakukan kerjasama pengaturan tanah pada pemimpin-pemimpin lokal. Strayer dan Coulborn menyimpulkan feodalisme adalah suatu metode pemerintahan. Sebagai sebuah kerajaan, keberadaan tanah menjadi urusan sangat penting. Luasan tanah menentukan seberapa besar tanah tersebut dapat memberi hasil bumi. Sedangkan pada waktu itu pengurusan tanah didelegasikan kepada Bekel yang membawahi sejumlah cacah. Bekel merupakan Kepala Desa yang ditunjuk Kraton untuk mengelola dan mengawasi kinerja cacah. Semakin banyak cacah yang dimiliki akan terkumpul banyak pajak yang harus disetor pada Kraton. 16 Sebagai kepercayaan kerajaan, setiap bekel yang membawahi beberapa cacah diupah dengan sistem bagi hasil pula dengan cacah dan kerajaan. Sistem feodal berhubungan erat dengan eksistensi kerajaan mengingat sifat kekuasaan raja adalah mutlak, baik pada wilayahnya dan juga pada semua yang tinggal di wilayahnya (SDM dan SDA). Hal ini berkaitan pula dengan mayoritas mata pencarian masyarakat Yogyakarta yang berkutat pada dunia agraris dan perdagangan hasil pertanian. Salah satu ciri feodalisme adalah adanya lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas ditempati oleh para penguasa dan pemilik tanah. Sedangkan lapisan bawah merupakan tenaga-tenaga penggarap yang umumnya hanya mengolah lahan milik para tuan tanah. Para penggarap masih pula diharuskan menyetor pajak yang dalam pemahaman Jawa dianggap sebagai rasa terima kasih pada raja yang sudah meminjamkan tanahnya untuk diolah dan diambil manfaatnya. Berjalannya waktu kemudian membawa perubahan pula pada sistem pertanahan di atas. Keberadaan cacah mungkin tidak lagi signifikan (tidak lagi digunakan). Namun, pengaturan pertanahan yang sudah sejak lama digunakan, dipertahankan, tentu membawa kebiasaan kontrol bagi Kraton atas pertanahan yang dimiliki. Kraton memiliki kontrol atas kuasa sumber daya utama yang dimilikinya. Senada dengan Nur Aini Setiawati dalam Lembaran Sejarah Vol. 4 No. 1 2001 menyebutkan bahwa sampai pada awal abad XX, masyarakat kota Yogyakarta masih berbudaya feodal. Strafikasinya mendasarkan pada beberapa lapisan masyarakat terbagi menjadi empat golongan berdasarkan hak atas tanah 17 serta kewajibannya.4 Pertama adalah Sultan yang menempati posisi sebagai penguasa wilayah dan tinggal di Kraton. Kedua, kerabat Kraton atau bangsawan keturunan Raja dan pejabat tinggi kerajaan yang mendapat tanah apanage. Kedua lapisan ini disebut wong gede. Ketiga, golongan menengah yang terdiri atas abdi dalem atau priyayi. Golongan ini mendapat kewajiban memelihara wilayah Kraton dan umumnya menumpang di tanah raja (magersari). Keempat adalah wong cilik atau rakyat jelata. Golongan ini yang terbesar di antara golongan lainnya dan merupakan golongan yang diperintah. Memiliki tanah dan memperoleh nilai manfaat atasnya memang merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun tidak mudah mengaturnya biarpun dalam Undang-undang hal tersebut telah jelas dibenarkan, diatur, dan dibela haknya bagi tiap-tiap warga negara. Tetap saja itu bukan urusan sepele. Setidaknya akan ada persaingan-persaingan (perebutan penguasaan sumbersumber produksi) yang terjadi antara sesama warga negara, warga negara dengan negaranya, atau bisa juga terjadi pada warga negara dengan negara yang diboncengi kepentingan korporasi baik lokal maupun asing. Telaah Kartodirjo dan Suryo (1991) dalam Kus Sri Antoro tentang perkebunan menunjukkan bahwa di Indonesia, relasi kekuasaan antara modal dan negara untuk mengukuhkan ekonomi politik kapitalisme sudah dimulai sejak jaman kolonial, sebagai bukti: negara merupakan instrumen dalam penetrasi, akumulasi, dan ekspansi modal berbasis sumberdaya alam. Akibatnya, terbentuk dua kutub kekuatan, 1) korporasi dan negara yang hendak menempatkan kapitalisme sebagai satu-satunya kekuatan 4 Nur Aini Setiawati, Lembaran Sejarah Vol. 4 No. 1 2001 hlm. 107. 18 ekonomi politik dan 2) kekuatan sosial yang dirugikan oleh kapitalisme. Kedua kekuatan itu bertemu dalam perebutan 1) ruang dan alat produksi secara material; 2) arena kekuasaan di ranah kebijakan; dan 3) wacana untuk legitimasi sosial.” Di Indonesia kita mengenal sistem “land tenure” (tenurial sistem) yang diadopsi dari konsep feodal Inggris sebelum berhasil diduki bangsa Normandia pada 1066. Secara harafiah, seperti diungkapkan Gunawan Wiradi,5 bahwa kata land sudah jelas berarti tanah. Sedangkan tenure berasal dari bahasa Latin tenere yang mencakup arti memelihara, memegang, memiliki. Karena itu kata land tenure memperoleh arti hak atas tanah atau penguasaan tanah. Istilah ini biasanya dipakai untuk menguraikan masalah-masalah pokok, umumnya status hukum penguasaan tanah semisal hak milik, pacht, gadai, bagi hasil, sewa-menyewa, dan juga kedudukan buruh tani. Menurut Bruce (1998), sistem land tenure adalah keseluruhan sistem dari pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional, maupun oleh sistem lokal. Sebuah sistem land tenure sulit dimengerti kecuali dikaitkan dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Gunawan Wiradi di atas, bahwa membaca kepemilikan (penguasaan) atas tanah tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek keilmuan yang lain. Sistem land tenure sudah lama dipakai pegiat agraria dalam memperjuangkan hak warga desa atas kepemilikan tanah adat dan atau juga hutan adat. Land tenure merupakan istilah baku yang mengakui adanya hak kepemilikan (memiliki) tanah, bukan sekadar fakta menguasai tanah. Hal ini 5 Gunawan Wiradi, “Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria”, dalam Tjondronegoro, Sediono. M.P dan Gunawan Wiradi (ed.), Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta: Yayasan Obor, 1984,. Hlm. 290-291. 19 dipakai untuk menghindari kerancuan atas adanya pemakai tanah dengan pemilik, yang mana masing-masing tentu mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula. Land tenure memisahkan antara hak milik dan hak guna yang mungkin saling tumpang tindih dalam sebuah objek tanah yang sama. Oleh karena itulah land tenure hadir menjawab. Konsep land tenure mengenal hak-hak yang melekat pada status hukum seperti tersebut, yakni:6 1. Subjek hak, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan. Subjek hak bervariasi bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial-ekonomi bahkan lembaga politik setingkat negara. 2. Objek hak, yang berupa persil tanah atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah. Objek hak termaksud harus bisa dibedakan dengan alat tertentu, dengan objek lainnya. Untuk objek hak berupa suatu persil tanah, batas-batasnya biasanya diberi suatu simbol. Objek hak bisa bersifat total bisa juga parsial. Misalnya, seseorang yang mempunyai hak atas pohon sagu tertentu, tidak dengan sendirinya mempunyai hak atas tanah dimana pohon sagu itu berdiri. 3. Jenis haknya, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakannya dengan hak lainnya. Untuk jenis-jenis hak merentang dari hak milik, hak pakai, hak sewa, dll. Setiap jenis hak ini memiliki hubungan khusus dengan kewajiban tertentu yang dilekatkan 6 Emilia dan Suwito, Memahami Terminologi Tenure, 2006, hlm. 7. 20 oleh pihak lain (mulai dari individu lain hingga negara) dan keberlakuannya dalam suatu kurun waktu tertentu. Di sini, warga keturunan etnis China adalah subjek hak yang menempati objek hak berupa tanah yang tidak boleh diklaim sebagai hak milik, pengusahaannya hanya sebatas pada hak guna bangunan yang bisa diperpanjang secara berkala. Akibatnya akses warga keturunan etnis China semakin terhalang karena pengesahan Kraton sebagai badan hukum, yang berarti penguasa sah atas tanah. Sebagai pemegang hak guna, warga keturunan etnis China jelas berkurang (mengurangi) haknya untuk menguasai sepenuhnya tanah yang ditempati, apalagi untuk berinvestasi tanah, mengembangkan perekonomiannya. Tentulah hak mereka terbatas hanya pada penggunaan tanah saja, bukan sampai pada pemilikan. Padahal, aktivitas yang tercipta dari manusia dengan tanah adalah pengusahaannya. Perihal bagaimana pemilik memanfaatkan lahannya untuk mencapai kemakmuran. Hal ini ditilik dari pandangan ekonomi yang melihat tanah sebagai faktor produksi, sedangkan warga keturunan etnis China disebutsebut sebagai golongan yang cakap dalam urusan ekonomi. Oleh karena itu bagi mereka keberadaan tanah menjadi faktor yang semakin penting. Perbedaan kepentingan inilah yang akan membawa kita pada hakikat masalah pertanahan, yakni perihal pembagiannya. Ada tiga media yang dipakai untuk mengklaim suatu sumber daya adalah milik seseorang:7 7 Surayya Afif Tinjauan Atas Konsep “Tenure Security” Dengan Beberapa Rujukan Pada Kasus Kasus di Indonesia. 21 1. Peta dimanfaatkan sebagai alat untuk melegitimasi suatu klaim umumnya banyak digunakan oleh negara dan perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin dari pemerintah yang berkuasa. 2. Cerita masyarakat awam di banyak tempat yang umumnya tidak mempunyai bukti-bukti tertulis selalu mengandalkan cerita (misalnya tentang sejarah asal usul, silsilah, lokasi-lokasi keramat) untuk mendukung legitimasi mereka atas kepemilikan dan penguasaan tanah. 3. Tanda-tanda alam dan bukti fisik ini mendukung cerita yang diwacanakan pada suatu masyarakat. Pada zaman dahulu misalnya, bukti-bukti suatu kepemilikan tanah hanya ditandai dengan batasan pepohonan yang ditanam di atas tanah tersebut. Sistem tenurial mengenal dua sistem kepemilikan atas hak, pertama tenurial yang diakui dalam hukum-hukum negara, sementara kelompok kedua adalah sistem tenurial yang dikenali dan bahkan diatur secara lokal dan terkait dengan praktik-praktik tradisional.8 Konsep ini memungkinkan memberi kelonggaran atas kepemilikan-penguasaan yang bukan hanya terletak pada satu subjek hak, melainkan bisa berbagi dengan subjek hak lainnya. Seseorang yang secara de facto memiliki suatu lahan (pemukiman), belum tentu seseorang tersebut juga memiliki hak untuk menguasai lahan. Sebagai jaminan keamanan atas kepemilikan tanah atau sumber daya alam, tenure sistem mengenal tenure security yang memiliki berbagai cara seperti yang sudah banyak dilakukan di beberapa negara lainnya. Untuk membaca kondisi ini, 8 Cromweel dalam Memahami Terminologi Tenure, 2006. Hlm. 7. 22 hanya akan dipakai satu dari empat aliran yang diutarakan oleh Ellsworth (2004). Adalah property rights, suatu sistem keamanan yang kepemilikannya terletak pada individu–privat. Kepemilikan dengan sistem ini berangkat atas filosofi politik dan ekonomi yang sangat mendukung individu. Kepemilikan ini akan jelas mengantongi sertifikat kepemilikan secara hukum yang akan memberi perlindungan kepemilikan secara penuh bagi individu. Dengan legitimasi hukum itulah individu akan bebas dari gangguan pihak lain. Juga akan memudahkan individu dan orang lain melakukan transaksi atas sumber daya yang dimiliki. Jual beli di sini sangat membuka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik, yang dikenal dengan paham Pareto Optimality.9 Sistem ini mengandaikan bahwa semakin tingginya tingkat pertumbuhan maka sejalan pula dengan kebutuhan atas sumber daya. Maka semua pemangku kepentingan di sebuah daerah dan negara perlu mendorong kemajuan ini agar meningkatkan produksi. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat dimiliki oleh orang per-orang maka hendaknya sumber daya itu dimiliki oleh negara demi tercapainya kemakmuran hajat hidup orang banyak. Sistem property rights hanya mereduksi makna keamanan kepemilikan sumber daya dengan sertifikasi tanah. Dengan legitimasi hukum ini tidak akan ada pihak lain yang berhak mengganggu kekayaan orang lain. Individu pemegang hak atas sumber daya juga lebih leluasa mengeksplorasi kekayaannya. Memahami definisi elit di atas, maka tepat bila Kraton ditempatkan pada posisi elit. Mengingat definisi elit merupakan golongan orang dengan kelebihan 9 Lynn Ellsworth, A Place in the World: A Review of the Global Debate on Tenure Security. (Ford Foundation, 2004), hlm.10. 23 yang tidak dimiliki orang kebanyakan, dengan berbekal kelebihan itulah elit mampu memimpin (menguasai) massa. Terlebih lagi adalah elit mengantongi legitimasi dari masyarakat yang dipimpinnya, sehingga elit mendapatkan kepercayaan penuh untuk memimpin masyarakatnya (massa). Sebagai kerajaan yang masih eksis keberadaannya, pun dengan telah disahkannya Kraton sebagai badan hukum, jelas Kraton memiliki kewenangan penuh mengatur sendiri urusan rumah tangganya yakni pertanahan. Kontrol Kraton atas pemilikan tanah-tanah di seluruh Yogyakarta bersifat penuh. Pemilikan tanah di Yogyakarta harus melewati persetujuan pihak Kraton yang melibatkan BPN untuk memastikan bahwa tanah yang digunakan seseorang sudah sesuai dengan haknya yang bisa diberikan oleh Kraton dan Pemerintah. E. Definisi Konseptual E.1. Sistem Elit Elit merupakan segolongan orang yang memiliki kelebihan dibandingkan orang kebanyakan. Kelebihan ini berupa nilai-nilai (values) yang penting dan diakui dalam suatu masyarakat. Berbekal dengan kelebihan inilah elit mampu berperan sebagai pemimpin atas massa yang tidak memiliki kelebihan sepertinya. Berbekal kelebihan yang dimiliki juga membantu elit dalam melanggengkan kekuasaan. E.2. Sistem Pengaturan Tanah ala Feodal Sistem ini mengklaim kepemilikan semua tanah adalah milik Raja. Sedangkan pengelolaannya bukan berdasarkan luas lahan, melainkan pada jumlah 24 yang dimiliki. Raja sangat berwenang dalam mengatur pola kepemilikan pertanahan di wilayahnya. Meminjam sistem tenure, Raja melakukan klasifikasi pemakaian pertanahan yang dimilikinya untuk dipergunakan, disewakan, dipinjamkan kepada yang berkenan. Ada berbagai status kepemilikan misalnya hak pakai dan hak guna bagi yang menempati tanah-tanah Raja. Pemegang status hak milik pada wilayah selain milik Raja lebih aman dan kuat daripada hak guna ataupun hak pakai. sedangkan pemegang hak pakai di atas tanah Raja akan lebih rentan karena sewaktu-waktu harus menyerahkan tanah yang dipinjam ketika Raja menitakan. F. Definisi Operasional F.1. Elit Penelitian ini utamanya menempatkan Kraton sebagai elit, yang akan dilihat dengan indikator sebagai berikut: 1) Elit berjumlah terbatas. Dalam hal ini menyoroti posisi Sultan dan atau Gubernur, keluarga Sultan yang sedang memerintah, dan Kraton pada umumnya. 2) Kedudukan politik antara Sultan dan Gubernur yang rangkap, memperkokoh kuasa salah satu (kedua) predikat yang melekat pada satu subjek individu. F.2. Sistem Feodal Pengelolaan tanah dengan sistem feodal akan tampak pada kuasa Kraton dalam memetakan penggunaan tanah untuk apa, oleh siapa, dan 25 seberapa menguntungkan. Dibantu dengan sistem tenure, feodalisme akan dilihat dari dengan indikator: 1) Jenis-jenis kepemilikan tanah seperti hak guna, hak pakai, maupun hak milik. 2) Jaminan keamanan kepemilikan tanah G. Metode Penelitian G.1. Jenis Penelitian Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif studi kasus untuk mengetahui gejala sosial seperti tersebut di atas. Dengan teknik ini penulis dibantu untuk menjawab bagaimana upaya yang dilakukan warga keturunan China dalam memperoleh haknya atas tanah. Penulis juga sangat ingin mengetahui mengapa mereka dibatasi haknya atas kepemilikan tanah. Kedua kata tanya ini memudahkan penulis untuk mendedah fakta di balik pertanyaan tersebut. Berangkat dari kata tanya itulah penulis menelusuri sejumlah responden yang langsung berkaitan dengan instruksi pembatasan tanah bagi warga keturunan China. Studi kasus menuntun penulis dalam mengeksplorasi realitas secara intens dan detil. Pun metode ini memerlukan kemampuan interpretasi penulis terhadap fakta-fakta yang ditemui. Hal itu disebabkan bertumpuknya (layered) informasi yang diperoleh. juga diharuskan untuk menentukan keberpihakan atas data yang diperoleh. menentukan keberpihakan pada salah satu data yang diperoleh penting dilakukan untuk membangun argumen yang kuat dan jelas dalam penelitian ini. Sekali lagi hal tersebut dikarenakan banyaknya informasi dari berbagai persepsi 26 aktor/subjek penelitian. Karena banyaknya informasi yang diperoleh, maka penulis juga melakukan telaah melalui triangulasi dari semua data yang dipunyai. Penulis melakukan pemilahan data yang mendukung dan mengesampingkan data yang tidak mendukung penulisan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas warga etnis Cina atas kepemilikan tanah di Yogyakarta. Utamanya, melihat upaya mereka yang minoritas dalam memenuhi hak milik atas tanah. Lebih lanjut juga baik diketahui perihal sebab kemunculan larangan tersebut di Yogyakarta. Analisis untuk memahami realitas tersebut akan dilihat pada kepentingan dibalik aturan kepemilikan lahan tersebut. Proses penelitian dilakukan dengan mengcross-check data dari berbagai pihak untuk memperoleh gambaran jelas perihal realitas yang terjadi. Setelah itu analisis dilakukan untuk membaca data yang diperoleh di lapangan. G.2. Fokus Analisa Penelitian ini utamanya mencoba menerka makna pentingnya pertanahan di Yogyakarta bagi Kraton selaku pusat budaya, sosial, politik, dan bahkan agama bagi masyarakatnya. Hal itu akan dilihat dengan sebuah instruksi perlindungan pertanahan bagi pribumi yang mengesampingkan warga non-pribumi. Mulanya akan diungkap terlebih dahulu bagaimana upaya warga keturunan China dalam memperoleh haknya atas tanah, yakni hak milik. Menyajikan berbagai data proses kepemilikan hak atas tanah yang terjadi di Yogyakarta akan menjadi jalan masuk bagi penulis untuk membaca arti pentingnya tanah di sini. Dibantu dengan data- 27 data sekunder terkait penggunaan tanah-tanah Kraton akan lebih memudahkan penulis dalam mengerucutkan kesimpulan penelitian. G.3. Teknik Pengumpulan Data a. Teknik Observasi Teknik ini digunakan penulis untuk melihat secara empiris realitas yang tampak. Khususnya digunakan pada narasumber warga keturunan China yang diwawancara di tempat (rumah). Kegiatan ini menguntungkan penulis karena dapat melihat langsung realitas yang diungkapkan narasumber. Terlebih lagi dapat melihat besar-kecilnya usaha yang mereka bangun. b. Teknik Wawancara Dalam mengumpulkan realitas penulis menggunakan wawancara untuk mencapai keterangan langsung dari semua narasumber terpilih. Wawancara yang dilakukan bersifat open ended dimana semua pertanyaan berkelanjutan yang juga bermanfaat untuk membantu penulis dalam meng-cross-check data yang diperoleh dari semua narasumber. Sedangkan teknik wawancara dilakukan dengan snowballing effect, di mana keterangan yang diperoleh seorang narasumber akan digulirkan pada narasumber lain yang saling mengait dengan fokus penelitian. Beberapa narasumber yang terkait seperti berikut ini: a. warga keturunan China baik yang menepati haknya berdasar ketentuan instruksi 1975 atau tidak. Narasumber ini adalah yang pernah bersinggungan dengan penulis, ada di antaranya menjalin hubungan baik sebagai pelanggan. 28 b. Notaris dan pihak Kraton adalah mereka yang dijejaringkan oleh orang yang dekat dengan keduanya, sehingga penulis tidak mengalami kendala apapun dalam mengakses keterangan sedalam-dalamnya kepada keduanya. c. Pihak Kantor Pertanahan Yogyakarta diakses melalui surat izin penelitian yang sudah disetujui oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. d. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang ditemui penulis sudah cukup dikenal penulis lewat beberapa hubungan pers mahasiswa dengan public defender. e. Pemakai tanah dengan hak magersari adalah keluarga teman lama yang sangat terbuka menanggapi pertanyaan yang digulirkan penulis. Penulis sangat mencoba untuk seimbang dalam mengkaji penelitian ini dengan upaya mengcross-check yang diperolehnya dengan data-data sekunder. Selain itu berdiskusi dengan teman-teman komunitas, kampus, dan akademisi sangat membantu penulis untuk standing position. Data-data sekunder yang turut dipergunakan berupa jurnal, artikel ilmiah, buku, media massa baik daring maupun cetak. G.4. Teknik Analisa Data Penulis hanya memilah data yang berguna bagi penelitian untuk selanjutnya diorganisir dalam per-bab penulisan. Teknik ini sangat membantu penulis untuk menyikapi temuan lapangan agar menjadi sebuah data komprehensif yang memiliki makna. Tentunya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif karena mensyaratkan pentingnya menganalisis data dengan interpretasi yang sesuai perspektif peneliti dan tujuan yang dilakukan. Proses 29 peneliti menjawab rumusan pertanyaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kemudian menganalisanya sehingga menghasilkan data yang bermanfaat dan solid. H. Sistematika Bab Bab I sudah menyajikan latar belakang penelitian ini diangkat serta deskripsi singkat perihal penelitian seperti apa yang hendak dikerjakan. Pada Bab II penulis ingin terlebih dahulu menyampaikan pembabagan konteks China diposisikan di berbagai rezim yang berkuasa di Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru hingga kini memasuki pasca-reformasi. Untuk melihat secara spesifik, penulis juga menyertakan secuil potret realitas kehidupan warga keturunan Cina yang bermukim di kota ini. Pun akan diungkapkan latar belakang munculnya Instruksi 1975. Sedangkan pergulatan warga keturunan China untuk memperoleh haknya atas tanah disampaikan secara menarik pada Bab III. Pembaca akan banyak menemui fakta terkait upaya mereka dengan beberapa pihak terkait dalam mengakses hak atas tanah berupa hak milik. Barulah pada Bab IV penulis mulai menguraikan pentingnya pertanahan di Yogyakarta bagi elit yang berkuasa (Kraton). Sebagai penutup, Bab V memberikan ikhtisar atas semua tulisan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Di sini juga hendak diutarakan saran akademis untuk kebijakan yang sudah berlangsung selama ini. 30