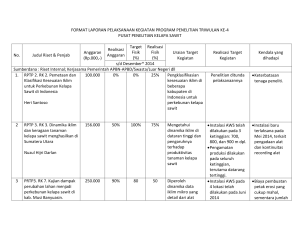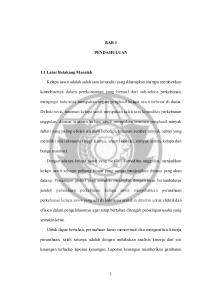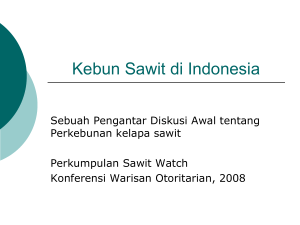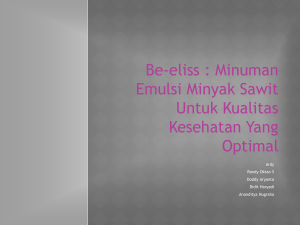Buruh-Sawit-Susah-Makan-Malam-Liputan-Jurnalis
advertisement
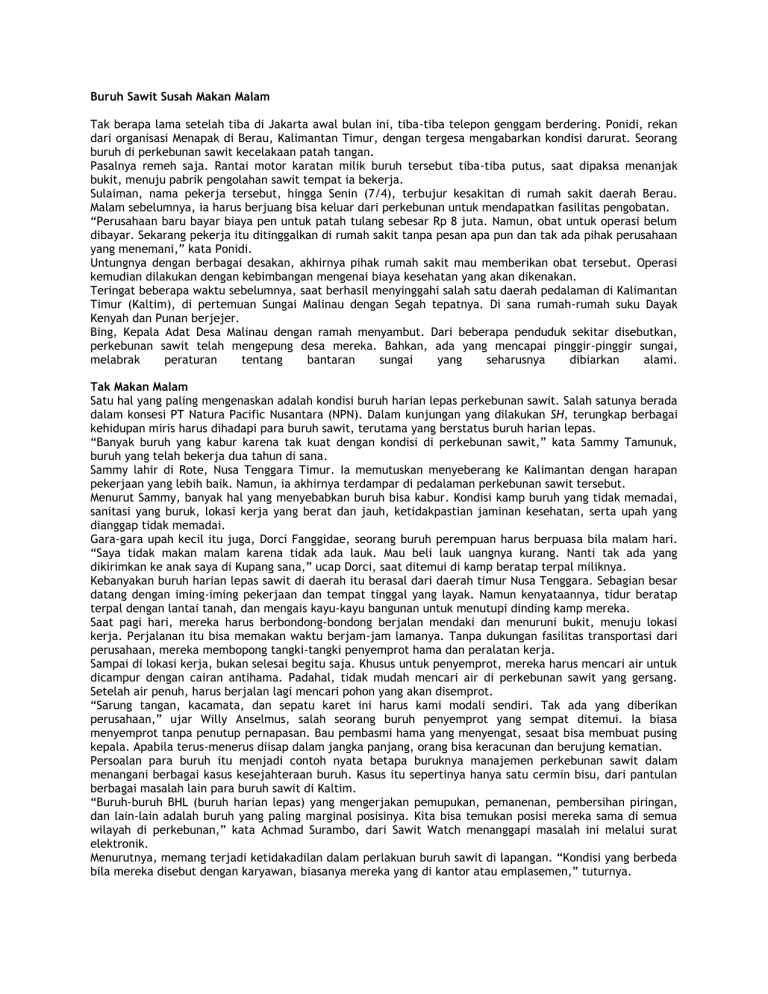
Buruh Sawit Susah Makan Malam Tak berapa lama setelah tiba di Jakarta awal bulan ini, tiba-tiba telepon genggam berdering. Ponidi, rekan dari organisasi Menapak di Berau, Kalimantan Timur, dengan tergesa mengabarkan kondisi darurat. Seorang buruh di perkebunan sawit kecelakaan patah tangan. Pasalnya remeh saja. Rantai motor karatan milik buruh tersebut tiba-tiba putus, saat dipaksa menanjak bukit, menuju pabrik pengolahan sawit tempat ia bekerja. Sulaiman, nama pekerja tersebut, hingga Senin (7/4), terbujur kesakitan di rumah sakit daerah Berau. Malam sebelumnya, ia harus berjuang bisa keluar dari perkebunan untuk mendapatkan fasilitas pengobatan. “Perusahaan baru bayar biaya pen untuk patah tulang sebesar Rp 8 juta. Namun, obat untuk operasi belum dibayar. Sekarang pekerja itu ditinggalkan di rumah sakit tanpa pesan apa pun dan tak ada pihak perusahaan yang menemani,” kata Ponidi. Untungnya dengan berbagai desakan, akhirnya pihak rumah sakit mau memberikan obat tersebut. Operasi kemudian dilakukan dengan kebimbangan mengenai biaya kesehatan yang akan dikenakan. Teringat beberapa waktu sebelumnya, saat berhasil menyinggahi salah satu daerah pedalaman di Kalimantan Timur (Kaltim), di pertemuan Sungai Malinau dengan Segah tepatnya. Di sana rumah-rumah suku Dayak Kenyah dan Punan berjejer. Bing, Kepala Adat Desa Malinau dengan ramah menyambut. Dari beberapa penduduk sekitar disebutkan, perkebunan sawit telah mengepung desa mereka. Bahkan, ada yang mencapai pinggir-pinggir sungai, melabrak peraturan tentang bantaran sungai yang seharusnya dibiarkan alami. Tak Makan Malam Satu hal yang paling mengenaskan adalah kondisi buruh harian lepas perkebunan sawit. Salah satunya berada dalam konsesi PT Natura Pacific Nusantara (NPN). Dalam kunjungan yang dilakukan SH, terungkap berbagai kehidupan miris harus dihadapi para buruh sawit, terutama yang berstatus buruh harian lepas. “Banyak buruh yang kabur karena tak kuat dengan kondisi di perkebunan sawit,” kata Sammy Tamunuk, buruh yang telah bekerja dua tahun di sana. Sammy lahir di Rote, Nusa Tenggara Timur. Ia memutuskan menyeberang ke Kalimantan dengan harapan pekerjaan yang lebih baik. Namun, ia akhirnya terdampar di pedalaman perkebunan sawit tersebut. Menurut Sammy, banyak hal yang menyebabkan buruh bisa kabur. Kondisi kamp buruh yang tidak memadai, sanitasi yang buruk, lokasi kerja yang berat dan jauh, ketidakpastian jaminan kesehatan, serta upah yang dianggap tidak memadai. Gara-gara upah kecil itu juga, Dorci Fanggidae, seorang buruh perempuan harus berpuasa bila malam hari. “Saya tidak makan malam karena tidak ada lauk. Mau beli lauk uangnya kurang. Nanti tak ada yang dikirimkan ke anak saya di Kupang sana,” ucap Dorci, saat ditemui di kamp beratap terpal miliknya. Kebanyakan buruh harian lepas sawit di daerah itu berasal dari daerah timur Nusa Tenggara. Sebagian besar datang dengan iming-iming pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Namun kenyataannya, tidur beratap terpal dengan lantai tanah, dan mengais kayu-kayu bangunan untuk menutupi dinding kamp mereka. Saat pagi hari, mereka harus berbondong-bondong berjalan mendaki dan menuruni bukit, menuju lokasi kerja. Perjalanan itu bisa memakan waktu berjam-jam lamanya. Tanpa dukungan fasilitas transportasi dari perusahaan, mereka membopong tangki-tangki penyemprot hama dan peralatan kerja. Sampai di lokasi kerja, bukan selesai begitu saja. Khusus untuk penyemprot, mereka harus mencari air untuk dicampur dengan cairan antihama. Padahal, tidak mudah mencari air di perkebunan sawit yang gersang. Setelah air penuh, harus berjalan lagi mencari pohon yang akan disemprot. “Sarung tangan, kacamata, dan sepatu karet ini harus kami modali sendiri. Tak ada yang diberikan perusahaan,” ujar Willy Anselmus, salah seorang buruh penyemprot yang sempat ditemui. Ia biasa menyemprot tanpa penutup pernapasan. Bau pembasmi hama yang menyengat, sesaat bisa membuat pusing kepala. Apabila terus-menerus diisap dalam jangka panjang, orang bisa keracunan dan berujung kematian. Persoalan para buruh itu menjadi contoh nyata betapa buruknya manajemen perkebunan sawit dalam menangani berbagai kasus kesejahteraan buruh. Kasus itu sepertinya hanya satu cermin bisu, dari pantulan berbagai masalah lain para buruh sawit di Kaltim. “Buruh-buruh BHL (buruh harian lepas) yang mengerjakan pemupukan, pemanenan, pembersihan piringan, dan lain-lain adalah buruh yang paling marginal posisinya. Kita bisa temukan posisi mereka sama di semua wilayah di perkebunan,” kata Achmad Surambo, dari Sawit Watch menanggapi masalah ini melalui surat elektronik. Menurutnya, memang terjadi ketidakadilan dalam perlakuan buruh sawit di lapangan. “Kondisi yang berbeda bila mereka disebut dengan karyawan, biasanya mereka yang di kantor atau emplasemen,” tuturnya. Setengah-setengah Bila ditilik secara kondisi riil, sepertinya masalah buruh dan lingkungan perkebunan sawit, berpotensi besar terjadi pada perusahaan menengah dan kecil. Dalam perbincangan dengan para pakar industri kelapa sawit, ditemukan adanya indikasi perusahaan menengah dan kecil paling berpotensi membakar hutan untuk minimalkan biaya produksi, membayar buruh dengan murah, serta tak menutupi berbagai jaminan karyawan. “Untuk menjalankan perkebunan sawit memang tidak bisa setengah-setengah. Banyak biaya yang harus dikeluarkan. Sebaiknya perusahaan sawit kecil dan menengah bergabung menjadi satu agar banyak masalah tidak berkembang dan merugikan perusahaan,” ujar Basuki Sumawinata, pakar ilmu tanah dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Basuki, yang ditemui saat lokakarya “Pengelolaan Bisnis dan Dampak Lingkungan pada Perkebunan Sawit” di Denpasar, Bali (28/3), juga menjelaskan perhitungan biaya mahal perkebunan sawit bisa terlihat dari pengelolaan tanah perkebunan. Perkebunan di lahan gambut, misalnya saja, memerlukan biaya besar karena gambut tak bisa didiamkan begitu saja tanpa dirangsang untuk melakukan dekomposisi. “Gambut itu miskin, bakteri dan jamur sedikit, hanya hidup di permukaan. Dekomposisi sulit terjadi,” katanya. Minimnya dekomposisi akan memengaruhi kesuburan lahan. Bila hal tersebut terus didiamkan, produksi perusahaan akan terkena dampak karena pohon sawit tidak berbuah biji sesuai yang diharapkan. Namun, Joko Supriyono, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), membantah kondisi hidup miris yang dialami buruh petani sawit. Menurutnya, kini ada peraturan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia (ISPO). Dalam peraturan tersebut, termaktub parameter-parameter bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh karyawan. “Setahu saya tak ada anggota Gapki yang masih menggaji karyawan di bawah standar gaji UMR daerah,” ucap Joko. Ia mengatakan, jika ada perusahaan kelapa sawit yang masih menggaji buruh di bawah UMR, Gapki bisa memberikan peringatan. Bahkan, perusahaan tersebut juga bisa dikeluarkan dari keanggotaan Gapki. Sementara itu, seperti yang tertera pada keterangan daftar anggota di situs daring Gapki, PT NPN tidak masuk sebagai anggota Gapki. Sumber : Sinar Harapan