MAQASHID AL-SYARI`AH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM Oleh:
advertisement

Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM Oleh: Sri Lum’atus Sa’adah Dosen Tetap Fakultas Syari’ah IAIN Jember Email: [email protected] Abstrak Tak terpungkiri lagi, bahwa mashlahah merupakan kata kunci dalam upaya merumuskan secara filosofis, kaitan teks wahyu dengan realitas konteks kehidupan umat beragama sehari-hari. Hukum Allah pasti mempunyai tendensi kemaslahatan. Secara etimologis, mashlahah mempunyai makna identik dengan manfaat, yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu. Namun, pada tataran substansinya, boleh dibilang sampai pada titik penyimpulan bahwa mashlahah adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (madlarat). Berkaitan dengan hukum kewarisan islam,jika dikaitkan dengan konsep mashlahah, maka mashlahah yang ingin dilindungi adalah perlindungan akan eksistensi agama (hifdh al-din), keturunan (hifdh al-nasl) dan juga perlindungan harta(hifdhla-mal) yang semuanya berada pada peringkat sekunder (hajiyyat) atau tersier (tahsiniyyat). Kata Kunci: Maqashid la-Syari’ah, Mashlahah, Kewarisan Islam Pendahuluan Al-mashlahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Secara etimologis, maqashid merupakan bentuk jama’ dari al maqshudyang berarti tujuan, sehingga al maqashid al-syari’ahdapat diartikan sebagai tujuan dari syari’at.1Ulama ushul fikih Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir :Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),112 1 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 125 Sri Lum’atus Sa’adah mendefinisikanmaqashid al-syari’ah dengan “makna dan tujuan yang dikehendaki syara‘ dalam mensyariatkan hukum bagi hambanya (manusia). Setiap hukum yang diciptakan syari‘ pasti mengandung kemaslahatan bagi hamba Allah, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.Oleh karena itu, setiap mujtahid ketika akan mengistimbatkan hukum harus berpatokan pada tujuan-tujuan syari‘dalam mensyari’atkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai kemaslahatan umat manusia.2 Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa tujuan utama dari pensyari’atan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat primer (dlaruriyyat), kebutuhan sekunder(hajiyyat), maupun kebutuhan tersier (tahsiniyyatt).3 Tak terpungkiri lagi, bahwa mashlahahmerupakan kata kunci dalam upaya merumuskan secara filosofis, kaitan teks wahyu dengan realitas konteks kehidupan umat beragama seharihari. Secara etimologis, mashlahah mempunyai makna identik dengan manfaat, yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu.4 Namun, pada tataran substansinya, boleh dibilang sampai pada titik penyimpulan bahwa mashlahah adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (madlarat). Sebagai kata kunci, kajian tentang mashlahahdapat memberikan kepastian akademik bagi penyelesaian alotnya perdebatan para juris Islam di seputar ta’lil alahkam: apakah hukum-hukum Tuhan mempunyai hubungan kausalitas dengan Abdul Aziz Dahlan et. al (ed), EnsiklopediHukumIslam 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),1008 3 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Kuwait:Dar al-Millah, 1978), 197 4 Said Ramadhan al Buthi, Dlawabith al mashlahah, (Beirut:Muassasah alRisalah, tt), 27. 2 126 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam kepentingan hamba?, apakah hukum-hukum yang tidak disebutkan secara tersurat oleh teks wahyu, dapat dianalogikan pada teks lain yang mempunyai ‘illat (reason) hukum sama?; dan apakah seorang mujtahid boleh memberikan simpulan hukum karena pertimbangan mashlahah tanpa pijakan teks? Kaitan hukum Tuhan dengan konteks mashlahah ini, kemudian memiliki momentum ketika berhadapan dengan gagasan institusionalisasi hukum Islam dan formalisasi agama. Kalangan formalis, selalu berupaya menaklukkan setiap perubahan yang terjadi di bawah otoritas hukum Tuhan. Sementara, kalangan substansialis menawarkan performa egaliter dengan memaknai hukum Tuhan secara lebih luas menyangkut perwajahan Islam secara kaffahdanrahmatan li al ‘alamin.Untuk mengetahui lebih jelas lagi pendapat para ulama (juris Islam) tentang mashlahah, dan boleh tidaknya mashlahahdigunakan sebagai hujjah atau patokan dalam penetapan hukum, di bawah ini diuraikan pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi dan al Thufi5 tentangmashlahah. Dalam bentangan sejarah hukum Islam, tepatnya sejak alSyafi’i(w. 204 H.) menulis kitab al-Risalah, ushul al-fiqh disepakati sebagai seperangkat metodologis dalam legislasi hukum Islam. Salah satu tema yang banyak diperdebatkan di kalangan ulama Penulis memilih tiga tokoh tersebut dengan pertimbangan: pertama, alGhazali (w. 505 H.), al-Syatibi (w. 790 H.), dan al-Thufi (w. 716 H.) berlatar belakang madzhab fiqih yang berbeda, yakni al-Ghazali (w. 505 H.) berlatang belakang Syafi’iyyah yang dalam ijtihadnya menekankan ada konsep qiyas, sedangkan al-Syatibi (w. 790 H.) berlatar belakang Malikiyyah yang menjadikan mashlahah mursalah sebagai dalil terdepan setelah alQur’an dan al-Hadits, sementara al-Thufi (w. 716 H.) adalah bermadzhab Hanbali yang menekankan pada pemahaman leteral teks al-Qur`an dan alHadits serta mendahulukan atsar al-Shahabah dari pada qiyas dan dalil hukum lainnya dalam penggalian hukum Islam. Karakter madzhab Hanbali tetap terlihat dalam pandangan al-Thufi (w. 716 H.) tentang mashlahah dalam ranah ibadah dan muqaddarat. Sedangkan dalam ranah mu’amalah, al-Thufi (w. 716 H.) mencukupkan mashlahah sebagai dalil hukum andalannya; Selain itu, elabora dari pemikiran tokoh tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis pelaksanaan hukum kewarisan Islam. 5 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 127 Sri Lum’atus Sa’adah ushul, adalah pembahasan tentang mashlahah, apakah termasuk dalam perangkat istinbath al-hukm atau tidak. Kontroversi tersebut terjadi karena mereka berbeda dalam melihat sejauh mana akal (ra’yu) ditolerir ikut bermain dalam memahami pesan teks. Al-Syafi’i (w. 204 H.) adalah ulama yang paling keras menolak penggunaan nalar dalam berbagai bentuknya, baik melalui istihsan atau mashlahah mursalah dalam penggalian hukum Islam. Pendapat tersebut diikuti oleh ulama sesudahnya seperti alJuwaini (w. 478H.) dan al-Ghazali (w.505 H.). Namun demikian, dua tokoh tersebut mengembangkan sedemikian rupa konsep mashlahah. Al-Juwaini (w. 478 H.) disinyalir sebagai bapak maqashid pertama. Dialah tokoh yang melahirkan konsep ta’lil dalam tiga kategori: dlaruriyyat, hajat dan mahasin. Konsep al-Juwaini (w. 478 H.) inilah yang memberikan inspirasi al-Ghazali dalam mengemas mashlahah dengan wajah baru yaitu maqashid al-syari’ah dalam bingkai al-ushul al-khamsah (lima hal pokok), yakni pemeliharaan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, walaupun cara aplikasinya masih “nyantol” dengan teori ijtihad andalan Syafi’iyan, yaitu qiyas. Berbeda dengan al-Ghazali (w. 505 H.) yang bermadzhab Syafi’iyyah, al-Syatibi (w. 790 H.) memformulasikan sedemikian rupa konsep mashlahah yang dirintis al-Juwaini (w. 478 H.) dan alGhazali, dan menjadikannya sebagai sebuah metode istinbath hukum Malikiyyah, yakni metode mashlahah mursalah, yang sejatinya tingkat keterikatannnya dengan teks masih begitu kental.6 Mirip dengan al-Ghazali (w. 505 H.), al-Syatibi (w. 790 H.) menegaskan bahwa maqashid al-mukallaftidak boleh menabrak rambu-rambu maqashid al-syari’, keduanya harus sesuai, dan apabila terjadi pertentangn antara keduanya, maka yang harus rela mengalah adalah maqashid al-mukallaf.7 Pasca al-Syatibi, dalam rentan waktu tidak kurang dari enam abad, hadir tokoh maqashid baru, Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur (w. 1393 H) dengan kitabnya yang terkenal, Maqashid al6Ibid.,65 7Ibid. 128 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam Syari‘ah al-Islamiyyah, dan dalam waktu yang hampir bersamaan juga hadir tokoh lain, yakni ‘Alal al-Fasi (w. 1394 H.) dengan kitabnya yang bernama Maqashid al-Syari‘ah wa Makanatuha. Kemudian muncullah para pengkaji mashlahah seperti Muhammad Sa’id Ramadlan al-Buthi, dengan kitabnya, Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, Musthafa Zaid, dengan bukunyaal-Mashlahah fi al-Tasyri’ al-Islami, Musthafa Syalabi, dengan kitabnya, Ta’lil al-Ahkam, Husain Hamid Hassan, dengan kitabnya, Nadhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami. 8 Konsep mashlahah juga dikembangkan oleh al-Thufi (w. 716), seorang ulama yang bermadzhab Hanbali, sebuah madzhab yang secara tegas dan keras menolak campur tangan nalar dalam istinbathhukum. Bagi al-Thufi, mashlahah adalah dalil hukum terdepan dan terkuat, khususnya dalam ranah mu’amalah. Dalil apapun yang berlawanan dengan semangat mashlahah harus ditolak, karena hukum bukan untuk kemaslahatan Tuhan, tetapi semata-mata untuk menghantarkan manusia dalam menggapai mashlahah, yaitu memperoleh kebaikan dan sekaligus terhindar dari bahaya, baik di kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Ahmad al-Raisuni, Nadhariyat al-Maqashid, 68-69. Ibid, hlm, 68-69 8 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 129 Sri Lum’atus Sa’adah Al-Mashlahah Menurut Sudut Pandang Beberapa Pemikir Mashlahah al-Ghazali9 (450 H - 505 H/1058 M-1111 M) Menurut pandangan al-Ghazali, hukum Allah (syari’at) yang ada dalam al-Qur’an dan al-Haditsmengandung suatu tujuan (maqashid). Melalui maqashid, ide pokok Tuhan yang tersembunyi di balik firman-firman tertulisnya dapat dijadikan landasan untuk memahami apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari setiap aturan yang ditetapkan untuk makhluk-Nya. Ia memandang suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syari’, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Dengan demikian,mashlahah yang dijadikan pertimbangan hukum adalah tujuan atau mashlahah menurut pandangan Tuhan, bukan semata mashlahah dalam persepsi manusia. Kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat kelak10. Menurut al-Ghazali, tujuan Syara’yang digunakan untuk menciptakan kemaslahatan manusia tersebut adalah mewujudkan pemeliharaan terhadap lima prinsip dasar: agama (din), jiwa (nafs), 9Imam al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi al-Syafi’i lahir pada tahun 450 H / 1058 M di sebuah kota kecil di Khurasan (Iran) bertepatan dengan setelah tiga tahun kaum Saljuk berkuasa di Baghdad. Orang tua al-Ghazali adalah seorang pemintal benang dari bulu dan dikenal sebagai orang yang saleh dan hidup sederhana. al-Ghazali menimba ilmu pada Ahmad bin Muhammad alRazikani. Kemudian dia mengembara ke Nisabur untuk belajar di Madrasah Nidhamiyah yang dipimpin oleh al-Haramayn al-Juwaini al-Syafi’i (478 H.). Di madrasah ini al-Ghazali mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti tasawuf, fiqh, tauhid, filsafat dan logika. Kecerdasan dan kedalaman ilmu pengetahuan al-Ghazali, menghantarkannya untuk mendapatkan kepercayaan sebagai tenaga pengajar di Madrasah Nidhamiyah pada tahun 484 H. Dan lima tahun kemudian al-Ghazali diangkat menjadi kepala madrasah tersebut. Al-Ghazali meninggal dunia pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriyah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus, tempat al-Ghazali dilahirkan, dan dikebumikan di tanah kelahirannya juga. Lihat, Abdul Aziz Dahlan et al (ed), Ensikopedi Hukum Islam 4, (Jakarta:Ichtiar van Hoeve), 1147 10Ibid, 287. 130 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam akal (‘aql), keturunan (nasab) dan harta (mal). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya memelihara kelima aspek tersebut, maka perbuatannya tersebut dinamakan mashlahah. Begitu pula upaya untuk menolak terhadap hal menimbulkan kemadharatan juga disebut mashlahah. Sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya terhadap perlindungan kelima hal tersebut disebut mafsadat.11Lima prinsip di atas oleh al-Ghazali dibedakan menjadi tiga peringkat, aldlarurat, al-hajat dan al-tahsinat12. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Maqashid aldlaruriyyat (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total13. Maqashid al-hajiyyat (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam katagori dlaruriyyat14. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer tersebut, maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan (sebagai terjemahan harfiah dari hajiyyat), bukan niscaya (sebagai terjemahan langsung dari dlaruriyyat). Artinya, Jika hal-hal hajiyyat tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurang-sempurnaan, bahkan kesulitan.15 Sementara maqashid al-tahsiniyyat (tujuan-tujuan tersier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan harfiah dari kata tahsiniyyat) proses perwujudan kepentingan dlaruriyyat dan hajiyyat.16 Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun 11Ibid., 287. 12Ibid.,289. 13Ibid., 290 14Ibid.,291 15Ibid.,230 16Ibid., 292. Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 131 Sri Lum’atus Sa’adah mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Al-Ghazali juga mengklasifikasikan mashlahah dari aspek adanya legalitas atau tidaknya dari Syari’ (Allah dan Rasul) dalam tiga katagori: mashlahahmu’aththirah, yaitu kemaslahatan yang yang dijelaskan secara langsung dalam teks; mashlahah mulghah (sia-sia) dan gharibah (asing), yaitu kemaslahatan yang keberadaanya ditolak oleh teks; dan mashlahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak dinyatakan dalam teks secara langsung namun memilki kesesuaian spirit dengan mashlahah yang dijelaskan dalam teks17. Satu hal yang perlu ditegaskan di sini, menurut al-Ghazali, bahwa mashlahah hajiyyah (sekunder) dan mashlahah tahsiniyyah (tersier) tidak dapat dijadikan landasan hukum kecuali bila diperkuat oleh ashl (sesuatu yang hukumnya dijelaskan oleh teks). Dengan demikian, cara kerja mashlahahala alGhazali adalah cara kerja qiyas, sebab bila tidak didukung oleh syara’ , maka sama saja dengan istihsan.18 Sedangkan mashlahah dlaruriyyah (kepentingan primer, mendesak) bagi al-Ghazali dapat dijadikan pijakan hukum, apabila memenuhi syarat-syarat berikut: Pertama, tidak bertentangan dengan nash qath’i. Bagi al-Ghazali, nash qath’i lebih kuat dari mashlahah mursalah. Sementara pertentangan (ta’arudl) yang terjadi antara mashlahah dengan nashdhanni, maka yang diprioritaskan adalah mashlahah, tanpa menafikan teks sama sekali. Dengan kata lain, yang berlaku dalam kasus ini adalah mashlahahmen-takhshish keumuman teks; Kedua, mashlahah yang bersifat universal (kulliyat), bukan mashlahah yang bersifat juziyyat; Ketiga, diyakini atau diduga kuat akan benar-benar mencerminkan kemaslahatan, bukan mashlahah utopis, praduga atau sangkaan belaka19. 17Ibid., 310-311. A. Halil Tahir, Pakaian Perempuan Menurut Muhammad Shahrur: Pendekatan Maqas{id al Shari’ah, (Disertasi IAIN Sunan Ampel, 2012), 74-75. 19 Ibid 75. 18 132 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam Mashlahahal-Syatibi20 (w. 790 H /1388 H.) Secara geneologis rancang bangun pemikiran maqashid bukanlah temuan hal yang baru. Maqashid bukanlah hasil capaian ulama kontemporer, karena dalam tradisi ushul fiqh klasik, kendati term maqashid secara eksplisit belum ditemukan dalam kitab-kitab “anggitan” para ulama klasik, hal itu sudah banyak terangkum dalam pembahasan di term-tern lain misalnya tentang qiyas.Namun, pembahasannya belum sistematis sebagaimana yang telah disajikan oleh al-Syatibi. Dalam pembahasannya tentang mashlahah al-Syatibi lebih sistematis, tertata sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Menurut al-Syatibi, Allah menurunkan syari’at (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalb al- mashalih wa dar’ al- mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang telah ditentukan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia dan akhirat sekaligus.21 Kemaslahatan tersebut dapat terwujud, apabila lima unsur pokok berikut terpenuhi, yakni:pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.22 20Nama lengkap al-Shatibi adalah Abu Ishaq bin Musa al-Gharnathi, dan dikenal dengan sebutan al-Syathibi. Nama al-Syatibi berasal dari nama negeri keluarganya, Syatibah (Xativa atau Jativa).Al-Syatibi dilahirkan di Granada. Menurut Hamka Haq, sampai saat ini, tanggal kelahiran al-Syatibi masih mesterius. Pada umumnya orang banyak menyebut tahun wafatnya, yakni 790 H./1388 M. Namun demikian, dapat diduga kuat, al-Syatibi lahir dan menghabiskan hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yusuf Abu al-Hajjaj (1333-1354 M.) dan Sultan Muhammad IV (1354-1391). Nama Syatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syathibah), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247M, keluarga Imam al-Syatibi mengungsi ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M. Periksa Abdul Aziz Dahlan et.al (ed),Ensiklopedi Hukum Islam 5, 1699. 21Ibid. 22 Urutan kelima dlaruriyyat ini bersifat ijtihadi bukan naqly. Artinya. Ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara istiqra’ (induktif). Dalam merangkai kelima dlaruriyyat ini (al- Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 133 Sri Lum’atus Sa’adah Dengan demikian dapat dipahami, bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan Allah dalam syari’ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi baik dan menghindarkannya dari segala yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akherat. Kata kunci yang kemudian kerap disebut oleh para sarjana muslim adalah mashlahah. Untuk menjaga yang lima sebagaimana yang telah dirinci al Ghazali tersebut diatas dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: a. Dari segi adanya (min nahiyyat al-wujud), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. b. Dari segi tidak adanya (min nahiyyat al-‘adam), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.23 Urutan kelima dlaruriyyat ini bersifat ijtihadi bukan naqli. Artinya, ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap kulliyat al khams) terkadang ada yang yang mendahulukan al nasl dari pada al-aql, atau ada yang mengakhirkan al-din, dsb. Bagi al- Zarkasyi, urutannya adalah; al nafs, al mal, al nasab,al din dan al aql.22Sedangkan menurut alAmidi urutannya dalah; al-din, al-nafs, al-nasl, al-aql dan al-mal. Dan menutut al- Qarafi, urutannya: al-nufus, al-adyan, al- ‘uqul, al-amwal, dan ala’radh. Sementara al- Ghazali urutannya, al-din, al-nafs, al-‘aql al-nasl dan almal. Namun urutan yang dikemukakan al- Ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama ushul fiqh berikutnya. Cara kerja kelima dlaruriyyat tersebut harus sesuai dengan urutannya. Periksa,alZarkasyi, al-Bahr al-Muhith, (Kuwait:Wizarat al Auqaf wa al Syu’un al Islamiyyah, 1993 juz VI), 612, al- Amidi, Al Ahkanm fi Ushul al Ahkam, (Muassasah al Halaby,1991 Juz IV), 252,Al -Qarafi, Syarh Tanqih al Fushul, (Maktabah al Kulliyah al Azhariyah, tt), 391, al- Ghazali, al-Mustashfa, (Beirut: Dar al-Fikr,1997 Juz I), 258 23 Contoh penerapannya sebagai berikut: menjaga agama dari segi al-wujud, misalnya shalat, zakat. Menjaga dari segi al-‘adam misalnya jihad dan hukuman bagi pemurtad. Menjaga jiwa dari segi al- wujud, contohnya makan dan minum, dari segi al -‘adam qishas dan diyat. Menjaga aqal dari segial-wujud contohnya mencari ilmu, dari segi al-‘adam contonya had bagi peminum khamar. Menjaga nasl dari segi al-wujud contohnya,nikah, dari segi al-‘adam contohnyahadbagipezinadanmuqadzif. Menjaga harta dari segi al- wujud contohnya jual beli dan mencari rezeki, dari segi al- ‘adam misalnya dilarang riba, had potong tangan bagi pencuri. 134 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam nash yang diambil dengan cara istiqra’ (induktif). Dalam merangkai kelima dlaruriyyatini (al kulliyat al-khams) terkadang ada yang mendahulukan al- nasl dari pada al-aql, atau ada yang mengakhirkan al-din, dsb. Bagi al Zarkasyi, urutannya adalah; alnafs, al- mal, al-nasab,al-din dan al-aql. Sedangkan menurut alAmidi24 urutannya adalah; al- din, al- nafs, al-nasl, al-aql dan al-mal. Menurut al Qarafi25, urutannya: al-nufus, al- adyan, al-‘uqul, alamwal, dan al a’radh. Sementara menurut al Ghazali26 urutannya, al din, al nafs, al-‘aql, al-nasl dan al-mal. Urutan yang dikemukakan al Ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama ushul fiqh berikutnya. Cara kerja kelima dlaruriyyat tersebut harus sesuai dengan urutannya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah mengurut lima hal pokok (al-ushul al-khamsah) dengan urutan sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian harta. Sementara ulama Hanafiyyah mengurutnya dengan urutan: agama, jiwa, keturunan, akal, kemudian harta27. Dalam usaha merealisaikan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqashid, yaitu28: a. al-maqashid al-dlaruriyyat (primer, pokok) b. al-maqashid al-hajiyyat (sekunder, kebutuhan) c. al-maqashid al-tahsiniyyat (tersier, keindahan). Klasifikasi mashlahah seperti tersebut di atas dapat memudahkan pengkaji hukum Islam dalam menganalisis kasus hukum yang di dalamnya terdapat pertentangan antara beberapa mashlahah. Ketika yang bertentangan adalah mashlahah yang samasama dalam peringkat dlaruriyyat , maka penyelesaiannya adalah dengan mendahulukan urutan yang paling tinggi dalam lima Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam IV, (Muassasah al Halaby,1991 ), 252. Al-Qarafi,Syarh Tanqih al- Fushul, (Maktabah al Kulliyah al Azhariyah, tt),391 26 Al-Ghazali, al-Mustashfa I,(Beirut: Dar al- Fikr,1997 ), 258 27 Periksa, Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Vol. 2, (Bairut: Dar alFikr, 1986), 752-753. 28 Al-Syathibi, al-Muwafaqat, Vol. 2…, 6 24 25 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 135 Sri Lum’atus Sa’adah unsur pokok (al-ushul al-khamsah), dimana peringkat tertinggi adalah agama, kemudian secara berurutan diikuti dengan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mashlahah al-Thufi (675 H/1276 M-. 716 H/ 1316 M.) Nama lengkap al-Thufiadalah Najm al-Din Abu al-Rabi’ Sulaiman bin Abd al-Qawi bin Abd al-Karim bin Sa’id al-ThufialSarsari al-Baghdadi al-Hanbali, yang kemudian dikenal dengan alThufi29. Al-Thufi nisbat pada Tawfa, nama desa yang terletak di daerah Sarsar Irak, dan di desa itulah tokoh ini dilahirkan. Disamping tokoh tersebut terkenal dengan namaal-Thufi, juga popular dengan nama Ibn Abi ‘Abbas.Al-Thufi lahir pada tahun 673 H (1274 M) dan meninggal pada tahun 716 H (1316 M) di Palestina.30 Al-Thufi mempunyai karya tulis yang banyak sekali. Dari sekian banyaknya karya al-Thufi, yang paling menonjol dan menjadi kontroversi adalah tentang konsep mashlahah, yang terdapat dalamKitab al-Ta’yin fi Syarh al-Arba’in, sebuah kitab syarh (penjelasan makna kata dan dan kalimat berikut kandungan) terhadap kitab Al-Hadits al-Arba’in al-Nawawiyyah. Dalam kitab tersebut, tepatnya pada penjelasan hadis ke 32, yakni hadisla dlarara wala d}irara (tidak boleh ada bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh pula ada bahaya pada orang lain),alThufi menulis gagasannya tentang mashlahah sebagai dalil mustaqil (berdiri sendiri) dalam penggalian hukum Islam. Mashlahah merupakan hujjah yang terkuat yang secara mandiri dapat digunakan sebagai landasan hukum. Menurutnya, ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu-Nya dan sunnah Rasulullah SAW pada intinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, dalam segala aspek persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan 29Ibn al-‘Imad, Syadzarat al-Dhahab fi Akhbai Man Dhahab, Vol. 5, (Bairut: alMaktabah al-Tijari, t.th.), 39. 30 Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah, Terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983), 37-38 136 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam pertimbangan adalah kemaslahatan. Apabila pekerjaan itu sesuai dengan kemaslahatan, maka harus dikerjakan oleh manusia,31 sebagaimana yang dijelaskan dalam tulisan ini. Pada dasarnya, sebelum al-Thufi, tidak ada seorang ulamapun yang menerima mashlahah sebagai dalil hukum independen (mustaqil), baik para imam madzhab besar, yakni Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit (w. 150 H/767 M), Malik bin Anas (w. 179 H/795 M), Muhammad bin Idris al-Syafi’i (w.204 H/819 M), dan Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M), maupun para ulama pengikut empat madzhab tersebut. Pandangan al-Thufi tentang mashlahah sebagaimana penulis dikemukakan adalah berasal dari pembahasan (syarh}) hadis nomor 32 dari kitabhadisal-Arba’in al-Nawawiyyah.hadis dimaksud berbunyi: ال ضرر وال ضرار “Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas kerugian dengan kerugian yang lain”.32 Tanpa memperdulikan kuat atau lemahnya rangkaian periwayatan (sanad) atau otentik tidaknya penisbatan pada Nabi, al-Thufi memandangnya sebagai representasi yang valid dari tujuanal-Qur’an untuk melindungi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Al-Thufi membangun pemikirannya tentang mashlahah tersebut berdasarkan atas empat prinsip33: a. Akal semata, tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. Hanya saja kemandirian akal untuk 31M. al Husain al Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al din Al T}ufi, terj. Abdul Basir (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2004),49 32Al-Thufi, Kitab al-Ta’yin, 234. Al-Hadits tersebut terdapat dalam alMuwaththa` nomor 1234, Sunan Ibn Majah nomor 2331 dan 2332. Periksa, Malik bin Anas, al-Muwaththa`, Vol. 5, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th.), 37. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Vol. 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 143. 33 Ibrahim Hosen, “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam”, dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof.Dr.H. Munawir Sjadzali (Jakarta:IPHI dan Paramadina, 1995), 254-257. Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 137 Sri Lum’atus Sa’adah mengetahui baik dan buruk terbatas dalam ranah mu’amalah dan adat istiadat; b. Sebagai kelanjutan pendapatnya yang pertama di atas, ia berpendapat bahwa mashlahah merupakan dalil syar’i mandiri yang kehujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi tergantung pada akal semata. Bagi al-Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu mashlahah adalah atas dasar adatistiadat dan eksperimen, tanpa memerlukan petunjuk nash; c. Sebagaimana disebutkan sebelumnya,mashlahah} menjadi dalil syar’i hanya dalam bidang mu’amalat (hubungan sosial) dan adat-istiadat. Sedangkan dalam bidang ibadat dan muqaddarat (sesuatu yang ukurannya telah ditentukan dalam nash, mashlahah} tidak dapat dijadikan dalil. Dalam kedua hal ini, nash danijma’-lah yang harus diikuti. d. Bagi al-Thufi, secara mutlakmashlahah merupakan dalil syara’ yang paling kuat. Baginya, mashlahah bukan hanya hujjah semata ketika tidak terdapat nash dan ijma’, melainkan ia harus didahulukan atas nash dan ijma’ ketika terjadi pertentangan antara keduanya dengan cara takhshish dan bayan. Mengutamakan dan mendahulukan mashlahah atas nash berlaku dalam seluruh karakteristiknya; baik qath’i dalam sanad dan matan-nya ataupun dhanni. Berdasarkan keempat asas ini, al-Thufi menyusun tiga argument dalam mendahulukan mashlahah atas nash dan ijma’ sebagaimana berikut:34 a. Kedudukan ijma’ sebagai dalil hukum diperselisihkan di kalangan ulama’. Sementara mashlahah telah disepakati, termasuk oleh mereka yang menentang ijma’. Ini berarti bahwa mendahulukan sesuatu yang disepakati (mashlahah) atas hal yang diperselisihkan (ijma’) adalah lebih utama35. b. Nash mengandung banyak pertentangan, dan hal inilah salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Sedangkan memelihara mashlahah merupakan sesuatu yang disepakati; 34Ibid. 35Ibid. 138 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam c. Terdapat nash dalam Sunnah yang ditentang oleh mashlahah, seperti sikap sahabat Umar yang melarang menyampaikan alHadits Nabi tentang “garansi” masuk surga bagi orang yang mengucapkan kalimah tauhid. Larangan itu didasarkan pada kemaslahatan umat Islam, yaitu kekhawatiran sahabat Umar terhadap sikap bermalas-malas untuk beramal dengan dasar al-Hadits tersebut.36 Sementara dalam ranah mu’amalah, menurut al-Thufi, yang dijadikan pedoman istidlal adalah mashlahah. Mashlahahdan dalil-dalil hukum yang lain seperti nash, ijma’ dan qiyas, dalam melihat hukum sesuatu ada dua kemungkinan: sama atau berbeda. Dalam mengaplikasikan dua kemungkinan ini al-Thufi menawarkan langkah-langkah istidlal sebagaimana berikut37: Jika mashlahah dan dalil-dalil hukum yang lain sama dalam menetapkan hukum, maka tidak ada masalah dan baik sekali, seperti sepakatnya nash, ijma’ dan mashlahah dalam menetapkan lima hukum yang bersifat mendesak (dlaruri), yakni: qisas terhadap pembunuh, membunuh orang murtad, memotong tangan pencuri, had penuduh zina (qadzif), dan had terhadap peminum khamar.38 Apabila mashlahah dan dalil hukum lainnya berbeda, maka diupayakan untuk mengkompromikan antara keduanya (al-jam’u bainahuma), misalnya dengan membawa sebagian dalil pada sebagian hukum, tidak pada yang lain, selagi tidak menabrak mashlahah dan tidak mempermainkan dalil. Tetapi apabila melakukan kompromi tidak memungkinkan, maka yang harus didahulukan dari dalil lain adalah mashlahah, sebagaimana pesan Nabi dalam haditsnya: la dlarara wa la dlirara. Makna al-Hadits ini, menurut al-Thufi, khusus dimaksudkan untuk menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan memelihara mashlahah yang menjadi tujuan utama syara’. Sedangkan dalil-dalil lainnya tidak ubahnya sebagaimana sarana (wasail). Oleh karena itu, tujuan harus 36Ibid. 37 Ibrahim Hosen, Beberapa Catatan Reaktualisasi, 277. 227 38Ibid., Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 139 Sri Lum’atus Sa’adah diutamakan dari pada sarana.39 Bila langkah kompromi tidak memungkinkan, maka yang diprioritaskan adalah mashlahah yang paling urgen, atau dengan cara diundi apabila dari sekian mashlahah sama-sama pentingnya40. Suatu kasus hukum yang di dalamnya hanya ada unsur mafsadat, maka mafsadat tersebut dihindari, dan membuang seluruh mafsadat kalau memang terdapat beberapa mafsadat dan memungkinkan untuk menghindari semuanya. Bila langkah tersebut tidak mungkin dilakukan, maka cukup mengerjakan yang mungkin saja. Ketika tingkat mafsadat-nya tidak sama, maka yang dihindari adalah mafsadat yang lebih berat (irtikab akhaf aldlararayn). Tapi bila kadar mafsadah-nya sama, makaharus memilih salah satu atau dengan cara diundi untuk menghindari tuhmah (prasangka buruk)41. Maqashid al-syari‘ah Dalam Hukum Kewarisan Islam Sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan maqashid alsyari‘ah, bahwa pada dasarnya ajaran Islam,tentu juga tentang pembagian warisdimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan dalam maqashid al-syari‘ah mencakup lima hal pokok (al-ushul al-khamsah), yakni: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masing-masing dari lima hal pokok tersebut mempunyai peringkat dlaruriyyat (primer, pokok), hajiyyat (sekunder, kebutuhan), dan tahsiniyyat (tersier, keindahan).42 39Ibid. 40Ibid. 41Ibid., 279. Pembagian mashlahah dengan tiga katagori: dlaruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat dalam lima hal pokok tersebut adalah perspektif al-Ghazali dan al-Syatibi. Sedangkan bagi al-Thufi, mashlahah bersifat mutlak, tanpa batas. Kekuatannya berkisar pada katagori: rajih/qawiy dan arjah/aqwa, dan mencakup masalahah dunyawiyyah dan mashlahah ukhrawiyyah 42 140 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam Sejauh penelusuran penulis dalam beberapa literatur, belum didapati pembahasan maqashid al-syari‘ah pembagian warisyang sistematika pembahasannya mengikuti sistematika maqashid al-syari‘ah al-Ghazali dan al-Syatibi, khususnya dalam mengklasifikasikan mashlahah pada tiga ranah dlaruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Namun demikian, penjelasan tentang maqashid alsyari‘ah tentang pembagian waris tersebut masih dapat dicarikanrujukan dalam ranah perlindungan lima hal pokok (alushul al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta., melalui hikmah dari pembagian waris Islam. Hikmah pembagian waris berdasarkan hukum Islam adalah: a. Islam mendudukkan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam sistem kewarisan di luar Islam, orang tua dimungkinkan mendapat hak warisan kalau pewaris meninggal dengan tidak meninggalkan keturunan. Suami istri mendapat hak saling mewarisi. Hal ini bertentangan dengan tradisi Arab jahiliyah yang menjadikan istri sebagai harta warisan. b. Memelihara keutuhan keluarga. Pembagian warisan berkaitan langsung dengan harta benda, apabila tidak diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Hal ini dikarenakan secara fitrah manusia itu sangat senang terhadap harta. c. Sebagai sarana untuk mencegah kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Hal ini terlihat bahwa dalam sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin kepada ahli waris dan kerabat.Harta warisan bukan saja terhadap anak-anak pewaris, tetapi orang tua, suami-istri, saudarasaudara, cucu bahkan kakek dan nenek. d. Sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaaan pada seseorang. Dengan dirincinya aturan tentang pembagian waris, diharapkan tiap ahli waris mendapatkan hak yang semestinya secara proporsional. Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 141 Sri Lum’atus Sa’adah e. Mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dikarenakan pembagian waris dalam Islam tidak hanya ditunjukkan kepada seseorang tertentu dari keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga lain dan tidak pula diserahkan kepada Negara.43 Berdasarkan hikmah pembagian waris tersebut, dapat ditarik ke ranah maqashid al-syari‘ah sebagai berikut: a. Untuk menjalankan syari’at Islam. Dengan melaksanakan ketentuan Allah tentang pembagian waris merupakan simbol ketundukan seorang hamba terhadap Tuhannya. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam QS al-Nisa ayat 13, artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”. b. Untuk memelihara keutuhan dan kerukunan keluarga. Dengan membagi harta peninggalan dengan sistem kewarisan Islam, diharapkan tidak lagi ada perpecahan antara keluarga dikarenakan memperebutkan bagian-bagiannya. Hal ini secara rinci telah disebutkan dalam al-Qur’an khususnya surat al-Nisa ayat 11 dan 12. c. Memberi jaminan terhadap ahli waris, dapat hidup berkecukupan, setelah ditinggalkan oleh si pewaris. d. Untuk memelihara harta, khususnya berkaitan dengan pendistribusian harta. Dengan sistem waris Islam, diharapkan tidak ada penimbunan harta bagi sesorang. Harta dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh ahli waris. Mencermati fungsi atau hikmah pembagian waris tersebut di atas, maka maqashid al-syari‘ahpembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (hifdh al-nasl) dari 43Muhammad Syah Ismail, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), 235. 142 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam pada perlindungan terhadap harta (hifdh al-mal), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat dlaruriyyat (primer), melainkan semuan berada pada peringkat hajiyyat (sekunder) atau tahsiniyyat (tersier). Hal ini seperti yang digambarkan dalam tabel fungsi pembagian waris kaitannya dengan maqashid al-syari‘ah berikut ini: Tabel 3.4 Pembagian Waris Islam Dan Kaitannya Dengan maqashid al-syari‘ah No. 1 2 3 Fungsi/hikmah pembagian waris Aspek Mas}lah}ah yang Dilindungi Peringkat Mas}lah}ah Simbol ketundukan Hifdh al-din (perlindungan kepada Allah terhadap agama) Hajiyyat/ dalam pelaksanaan Tahsiniyyat hukum waris Sebagai sarana Perlindungan terhadap menjaga keutuhan keturunan (hifdh al keluarga nasl) ______ Sebagai sarana Perlindungan terhadap pendistribusian harta (hifdh al mal) harta secara adil Uraian tentang hikmah pembagian waris di atas, dapat kita pahami bahwa mashlahah yang ingin dilindungi adalah perlindungan akan eksistensi agama (hifdh al-din),keturunan (hifdh al-nasl) dan juga perlindungan harta(hifdh al mal) yang semuanya berada pada peringkat sekunder (hajiyyat) atau tersier(tahsiniyyat). Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 143 Sri Lum’atus Sa’adah Kesimpulan Dari paparan singkat di atas dapat disimpulkan beberapa hal: 1. Tujuan utama dari pensyari’atan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat primer (dlaruriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), maupun kebutuhan tersier (tahsiniyyatt). 2. Tujuan utama, fungsi,dan hikmah pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (hifdh al-nasl) dari pada perlindungan terhadap harta (hifdh al-mal), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat dlaruriyyat (primer), melainkan semuanyaberada pada peringkat hajiyyat (sekunder) atau tahsiniyyat (tersier). 144 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Kewarisan Islam Daftar Pustaka Al-Amidi, Al- Ahkam fi Ushul al Ahkam, (Muassasah al Halaby,1991). Al-Amiri, M. al Husain, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al- Thufi, terj. Abdul Basir (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2004). Al-Buthi, Said Ramadhan, Dlawabith alMashlahah,(Beirut:Muassasah al Risalah, tt). Al-Ghazali, al- Mustashfa I,i(Beirut: Dar al- Fikr,1997). Al-Qarafi, Syarh Tanqih al Fushul, (Maktabah al Kulliyah al Azhariyah, tt). Al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhith, (Kuwait:Wizarat al Auqaf wa al Syu’un al Islamiyyah, 1993). Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Vol. 2, (Bairut: Dar alFikr, 1986). Anas, Malik bin, al-Muwaththa`, Vol. 5, (Bairut: Dar al-Kitab al‘Arabi, t.th). Dahlan, Abdul Aziz et. al ed , EnsiklopediHukumIslam 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001). Hosen, Ibrahim, “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam”, dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof.Dr.H. Munawir Sjadzali (Jakarta:IPHI dan Paramadina, 1995). Ibn al-‘Imad, Syadzrat al-Dzahab fi Akhbai Man Dzahab, Vol. 5, (Bairut: al-Maktabah al-Tijari, t.th). Ismail,Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1992). Khalaf ,Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, (Kuwait:Dar Al Millah, 1978). Khan, Qamaruddin, Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah, Terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983). Majah, Ibn, Sunan Ibn Majah, Vol. 7, (Bairut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyyah, t.th). Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015 145 Sri Lum’atus Sa’adah Munawwir, Ahmad Warson, Al Munawwir:Kamus ArabIndonesia,(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Tahir, A. Halil, Pakaian Perempuan Menurut Muhammad Shahrur: Pendekatan Maqas{id al Shari’ah, (Disertasi IAIN Sunan Ampel, 2012). 146 Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 April 2015


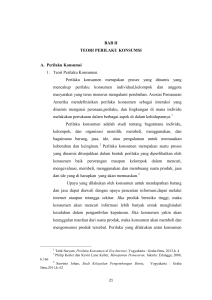

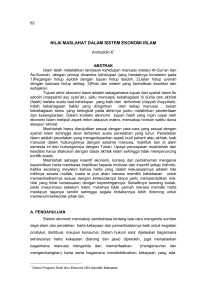
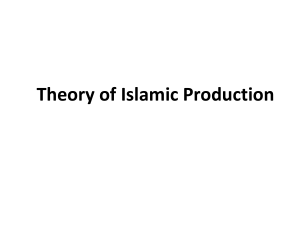
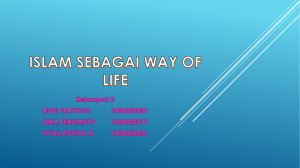

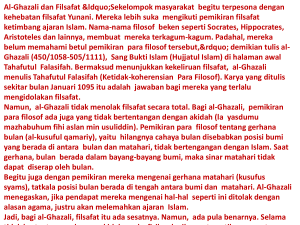
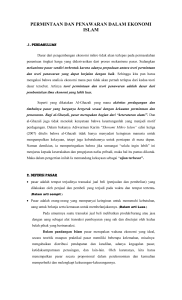
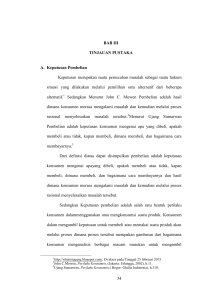
![Modul Pendidikan Agama Islam [TM10].](http://s1.studylibid.com/store/data/000354932_1-b2362430d3e553f2c681d230e3130c68-300x300.png)