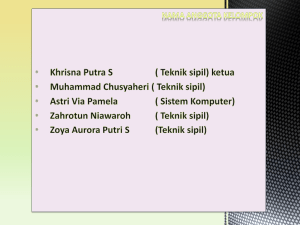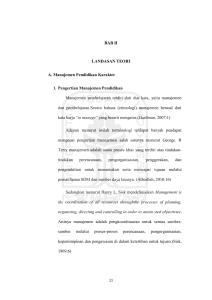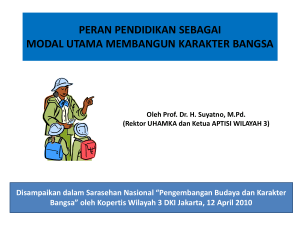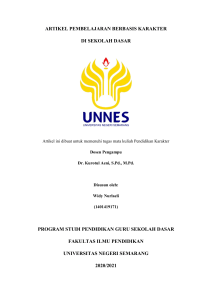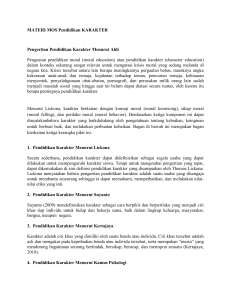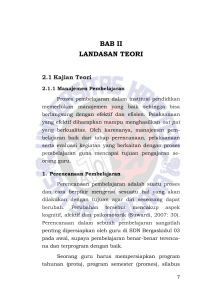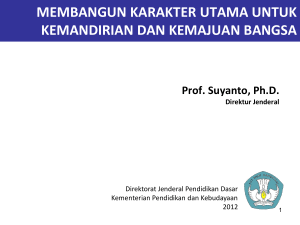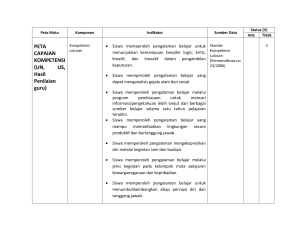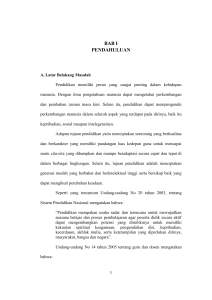MEMBUMIKAN PENDIDIKAN KARAKTER
advertisement
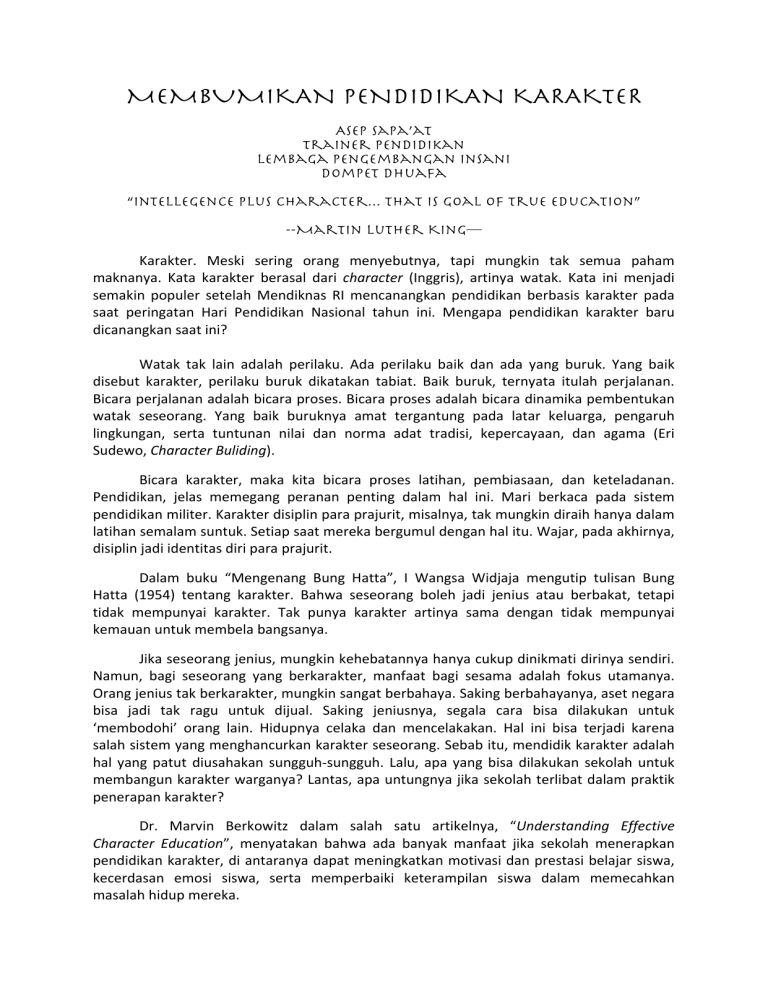
MEMBUMIKAN PENDIDIKAN KARAKTER Asep Sapa’at Trainer Pendidikan Lembaga Pengembangan Insani Dompet Dhuafa “Intellegence plus character... that is goal of true education” --Martin Luther King— Karakter. Meski sering orang menyebutnya, tapi mungkin tak semua paham maknanya. Kata karakter berasal dari character (Inggris), artinya watak. Kata ini menjadi semakin populer setelah Mendiknas RI mencanangkan pendidikan berbasis karakter pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Mengapa pendidikan karakter baru dicanangkan saat ini? Watak tak lain adalah perilaku. Ada perilaku baik dan ada yang buruk. Yang baik disebut karakter, perilaku buruk dikatakan tabiat. Baik buruk, ternyata itulah perjalanan. Bicara perjalanan adalah bicara proses. Bicara proses adalah bicara dinamika pembentukan watak seseorang. Yang baik buruknya amat tergantung pada latar keluarga, pengaruh lingkungan, serta tuntunan nilai dan norma adat tradisi, kepercayaan, dan agama (Eri Sudewo, Character Buliding). Bicara karakter, maka kita bicara proses latihan, pembiasaan, dan keteladanan. Pendidikan, jelas memegang peranan penting dalam hal ini. Mari berkaca pada sistem pendidikan militer. Karakter disiplin para prajurit, misalnya, tak mungkin diraih hanya dalam latihan semalam suntuk. Setiap saat mereka bergumul dengan hal itu. Wajar, pada akhirnya, disiplin jadi identitas diri para prajurit. Dalam buku “Mengenang Bung Hatta”, I Wangsa Widjaja mengutip tulisan Bung Hatta (1954) tentang karakter. Bahwa seseorang boleh jadi jenius atau berbakat, tetapi tidak mempunyai karakter. Tak punya karakter artinya sama dengan tidak mempunyai kemauan untuk membela bangsanya. Jika seseorang jenius, mungkin kehebatannya hanya cukup dinikmati dirinya sendiri. Namun, bagi seseorang yang berkarakter, manfaat bagi sesama adalah fokus utamanya. Orang jenius tak berkarakter, mungkin sangat berbahaya. Saking berbahayanya, aset negara bisa jadi tak ragu untuk dijual. Saking jeniusnya, segala cara bisa dilakukan untuk ‘membodohi’ orang lain. Hidupnya celaka dan mencelakakan. Hal ini bisa terjadi karena salah sistem yang menghancurkan karakter seseorang. Sebab itu, mendidik karakter adalah hal yang patut diusahakan sungguh‐sungguh. Lalu, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk membangun karakter warganya? Lantas, apa untungnya jika sekolah terlibat dalam praktik penerapan karakter? Dr. Marvin Berkowitz dalam salah satu artikelnya, “Understanding Effective Character Education”, menyatakan bahwa ada banyak manfaat jika sekolah menerapkan pendidikan karakter, di antaranya dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, kecerdasan emosi siswa, serta memperbaiki keterampilan siswa dalam memecahkan masalah hidup mereka. The Leader in Me (2008), buku terjemahan yang berkisah tentang praktik penerapan The 7 Habits of Highly Effective People di sekolah‐sekolah di beberapa negara, bisa dijadikan rujukan penerapan karakter di sekolah. Sulit dibayangkan, seorang Walter Vozzo, siswa kelas lima di sekolah A. B. Combs, mampu berpidato dengan tenang dan percaya diri dihadapan 700 orang di sebuah ruangan olahraga. Hal ini bisa terjadi karena Vozzo dan teman‐teman sekelasnya sudah dilatih untuk berbicara di depan kelas, di setiap awal memulai pelajaran sekolah. Aktivitas ini pun sudah dirancang secara sistematis dan berkelanjutan oleh pihak sekolah. Buah dari proses pembiasaan tersistematis, menghasilkan siswa yang percaya diri sekaligus mampu menguasai kemampuan public speaking. Masih di A. B. Combs, sekolah mengembangkan budaya kepemimpinan (leadership) di kalangan siswa. Setiap tahun, para ketua kelas dipilih oleh rekan‐rekannya untuk melakukan temu wicara dan diskusi dengan kepala sekolah, khusus untuk memberikan masukan dalam upaya pengembangan sekolah. Ada juga siswa yang memiliki reputasi sebagai pewawancara paling cerdas dan tajam, diberi kepercayaan penuh untuk menjadi pewawancara dalam seleksi guru baru di sekolah mereka. Karena biasanya, dia lebih pandai memilih guru baru yang menyukai anak‐anak. Sesuatu yang kadang sulit dinilai orang dewasa. Jika siswa tersebut memutuskan untuk menolak guru baru tersebut, maka pihak sekolah mendukung penuh keputusan itu. Apa mungkin sekolah‐sekolah di Indonesia berani mempraktikan hal‐hal seperti ini? Berkaca dari kisah di atas, penerapan karakter hanya akan terwujud jika ada komitmen, partisipasi, proses pembiasaan, dan keteladanan dari pemimpin sekolah. Sulit mengharapkan siswa berkarakter jujur, jika praktik pendidikan sekolah masih berpihak pada ketidakjujuran. Siswa tak pernah bisa disiplin, jika guru dan kepala sekolah masih setia pada jam karet. Tak ada pembiasaan dan keteladanan, maka takkan pernah ada karakter. Lebih jauh lagi, kita bisa mengatakan, karakter tak cukup diajarkan sebatas pengetahuan. Di sekolah kita sudah ada pelajaran PPKN, mengapa tawuran pelajaran masih marak di jalanan? Pelajaran agama sudah dikonsumsi sejak di bangku SD, mengapa narkoba dan seks bebas jadi pilihan sebagian pelajar kita? Akhirnya, karakter hanyalah isap jempol saja jika pendidikan bangsa ini dibangun atas dasar prinsip Tut Wuri Nggerogoti (Di Belakang Mengegerogoti), Ing Madya Ngangkut Banda (Di Tengah Mengangkut Harta), Ing Ngarsa Terus Ngapusi (Di Depan Selalu Menipu). Apalagi jika prinsip ini fasih dipraktikkan para pemimpin kita. Akan jadi apa bangsa kita ini?