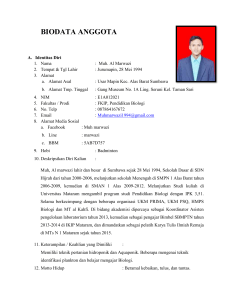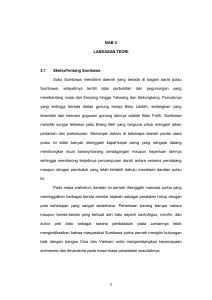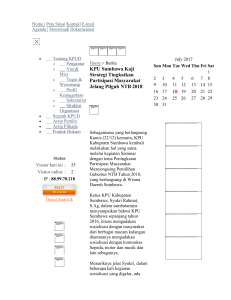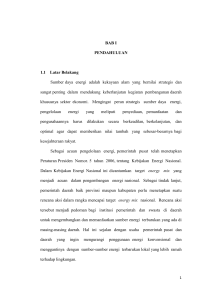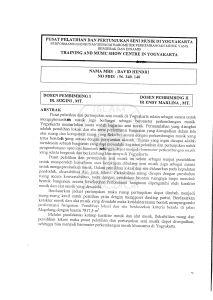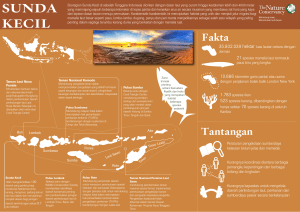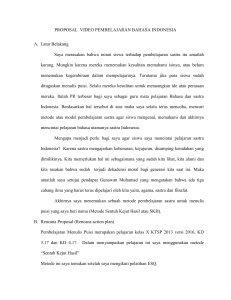BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
advertisement
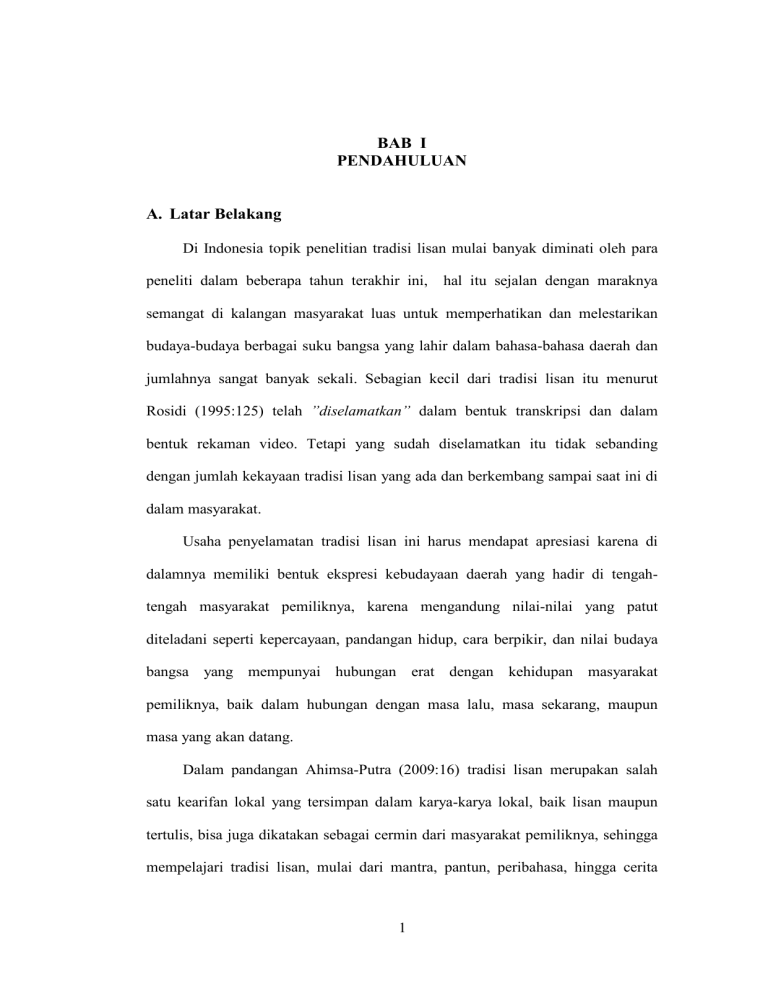
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di Indonesia topik penelitian tradisi lisan mulai banyak diminati oleh para peneliti dalam beberapa tahun terakhir ini, hal itu sejalan dengan maraknya semangat di kalangan masyarakat luas untuk memperhatikan dan melestarikan budaya-budaya berbagai suku bangsa yang lahir dalam bahasa-bahasa daerah dan jumlahnya sangat banyak sekali. Sebagian kecil dari tradisi lisan itu menurut Rosidi (1995:125) telah ”diselamatkan” dalam bentuk transkripsi dan dalam bentuk rekaman video. Tetapi yang sudah diselamatkan itu tidak sebanding dengan jumlah kekayaan tradisi lisan yang ada dan berkembang sampai saat ini di dalam masyarakat. Usaha penyelamatan tradisi lisan ini harus mendapat apresiasi karena di dalamnya memiliki bentuk ekspresi kebudayaan daerah yang hadir di tengahtengah masyarakat pemiliknya, karena mengandung nilai-nilai yang patut diteladani seperti kepercayaan, pandangan hidup, cara berpikir, dan nilai budaya bangsa yang mempunyai hubungan erat dengan kehidupan masyarakat pemiliknya, baik dalam hubungan dengan masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Dalam pandangan Ahimsa-Putra (2009:16) tradisi lisan merupakan salah satu kearifan lokal yang tersimpan dalam karya-karya lokal, baik lisan maupun tertulis, bisa juga dikatakan sebagai cermin dari masyarakat pemiliknya, sehingga mempelajari tradisi lisan, mulai dari mantra, pantun, peribahasa, hingga cerita 1 rakyat akan sangat membantu memahami pola pikir atau berbagai kejadian dalam kehidupan masyarakat. Terdapat hubungan antara tradisi lisan dengan kebudayaan, sebab tradisi lisan merupakan salah satu unsur kebudayaan, sehingga tradisi lisan bagi para ahli antropologi dapat dipahami sebagai data kebudayaan yang mengandung berbagai informasi tentang kebudayaan. Sebagai salah satu data kebudayaan lebih lanjut Ahimsa-Putra (2003:78) menjelaskankan bahwa tradisi lisan dapat dipandang sebagai ”pintu masuk” untuk memahami kebudayaan itu sendiri. Maka posisi tradisi lisan dapat menjadi unsur-unsur kebudayaan seperti sistem nilai, sistem politik, sistem kepercayaan, sistem mata pencaharian, dan sebagainya. Ekspresi tradisi lisan perlu diungkapkan kalau ingin mendapatkan gambaran tentang kekayaan budaya, seperti orang Sumbawa (tau Samawa)1 mempunyai 1 Kata Tau Samawa (Tau= orang/penduduk Samawa, Samawa=Sumbawa) maksudnya: (a) semua orang/penduduk asli/kelahiran/berasal dari/berdomisili sejak lama di Tanaq Samawa (Daerah Sumbawa). (b) Khusus mereka yang menjadi penduduk kota Sumbawa Besar. (c) Istilah tau Samawa kadang dimaksudkan untuk membedakan tipologi masyarakat kota dan desa yakni mereka yang menjadi penduduk kota Sumbawa (Samawa) dan dianggap mempunyai ciri-ciri sebagai orang kota (tau desa rea= orang kota) disebut tau Samawa. Mereka yang menjadi penduduk desa dan dianggap mempuyai ciri-ciri sebagai orang desa disebut tau desa ode. Bahasa Samawa: Tau= orang, desa=kampung. Ode=kecil, orang dusun. Lebih lanjut perkataan Samawa sebagai sebuah nama seperti dimaksudkan diatas. Samawa berasal dari perkataan dalam bahasa daerah Sumbawa sendiri, yaitu Samawa terdiri dari kata dasar mawa yang berarti beban, yang dibawa, barang bawaan, atau oleh-oleh. Diberi awalan sa yang diikuti dengan tekanan bunyi pada suku kata akhir kata dasar (dalam hal ini suku kata wa) yang mempunyai fungsi/arti awalan me dan akhiran kan dalam bahasa Indonesia. Samawa berarti membebankan, memberi beban, membawakan, memberikan untuk di bawa, mengamanatkan, mengharapkan disampaikan pada alamatnya. Kata dasar “mawa” adalah kata benda yang artinya seperti tersebut di atas, berbeda dengan kata dasar “bawa” (kata kerja) yang bentuk dan artinya sama dengan kata dasar “bawa” dalam bahasa Indonesia. Jika kata dasar “bawa” diberi awalan “sa” juga akan berubah menjadi “samawa” (bukan “sabawa”) yang berarti membawakan. Baik kata dasar “mawa” maupun kata dasar “bawa” yang masing-masing berarti “barang yang di bawa” dan “membawakan”, sama berkisar pada pengertian “bawa” . kemudian mendapat awalan “sa” menjadi sa-bawa; sa-bawa (samawa), karena perubahan fonem menjadi “sama bawa” – “sambawa” seterusnya “Sumbawa” jadi sebutan “Sumbawa” sekarang mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian yang terkandung dalam nama aslinya “SAMAWA” (Masnirah,1988:40). 2 seni tradisi lisan (oral tradition) yang masih bertahan sampai sekarang yaitu lawas2 yang dilisankan dengan berbagai macam cara pewarisannya, ada yang dilagukan sendiri-sendiri, ada pula secara berpasangan atau beramai-ramai. Dalam kaitan dengan penelitian ini, akan fokus pada seni tradisi lisan sakeco yang merupakan salah satu bentuk penyampaiannya melalui unsur kelisanan yang paling digemari oleh masyarakat Sumbawa. Seni tradisi lisan ini dimainkan oleh dua orang dengan cara melantunkan lawas sambil memukul 2 buah alat rebana kecil (ode) sebagai alat musik pengiring ketika penutur menyelesaikan satu alinea cerita kemudian dilanjutkan ke bait cerita berikutnya. Lawas-lawas yang dilantunkan dalam seni tradisi lisan sakeco berisi tentang cinta kasih muda-mudi, nasehat agama (akherat), kepatriotan, perjuangan yang penuh heroik di masa lalu, politik, perkawinan, dan nilai gotong royong yang berazaskan kekeluargaan. Pertunjukan tradisi lisan sakeco sampai saat ini masih tetap bertahan dalam masyarakat pemiliknya. Bagi orang Sumbawa (tau Samawa) seni ini digunakan untuk memeriahkan upacara adat3 ramai mesaq4, sunatan (khitanan), tokal basai5, 2 Lawas adalah sejenis puisi traditional khas Sumbawa, umumnya terdiri dari tiga baris per bait, setiap baris terdiri dari delapan suku kata dan biasanya dilisankan secara resmi pada upacaraupacara tertentu (Sumarsono, 1985:75). 3 Kata adat artinya wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, normanorma, hukum serta aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem yaitu sistem budaya. Kalau dikaitkan dengan kata adat istiadat berarti aturan yang kuat dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan (Koentjaraningrat, 1984). 4 Ramai Mesaq (ramai sendirian) dulunya hanya dilakukan di rumah calon pengantin laki dengan menggunakan pakaian adat, tanpa dihadiri oleh calon pengantin wanita dengan menanggap seni tradisi lisan sakeco dan ratib rebana ode (syalawatan) sebagai media hiburan (Zulkarnain, 2011:201).Tradisi ramai mesaq dalam pandangan orang Sumbawa saat ini adalah pra-resepsi perkawinan. Tradisi ini dilakukan pada malam hari setelah dilakukan kegiatan aqad nikah. Adat ini dilakukan di rumah calon pengantin laki-laki sebagai bentuk hiburan untuk melepaskan kepergiannya ke rumah calon pengantin wanita. Akan tetapi seni tradisi lisan sakeco dilakukan 3 peresmian lembaga, peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) Kabupaten Sumbawa, kampanye partai politik, dan upacara adat lainnya. Sakeco is played to celebrate the wedding party, the moriterious but not obligatory prophet or other ritual ceremony. Tanpa sakeco dalam acara tersebut ada sesuatu yang hilang bagi keluarga penyelenggara hajatan sebelum menanggap seni pertunjukan tradisi lisan sakeco. Data etnografi awal yang peneliti observasi pada tanggal 21 Februari 2012 dari penyelenggaraan adat ramai mesaq yang ingin dikemukakan sebagai titik awal pada bagian latar belakang ini ada seorang mantan PNS (Pegawai Negeri Sipil) bernama Suharno berdomisili di Desa Tengah Kecamatan Utan-Sumbawa. Ia berasal dari Kabupaten Klaten-Jawa Tengah dengan profesinya sekarang sebagai petani. Dalam sebuah hajatan perkawinan anaknya yang bernama Rika Putri Nora, Suharno tidak mau ketinggalan dalam merayakan perkawinan dengan sangat meriah menurut ukuran orang di desa tersebut. Dalam perkawinan itu, adat ramai mesaq tetap digelar dengan menanggap seni tradisi lisan sakeco sebagai sajian hiburan bagi para keluarga yang datang dari kejauhan, dan menjadi daya tarik masyarakat sekitarnya karena orang berbondong-bondong menuju halaman rumah pak Suharno untuk menyaksikan seni ini meskipun mereka tidak diundang. pula di rumah pengantin perempuan sebagai bentuk hiburan penyambutan kedatangan pengantin laki-laki (nginring). 5 Tokal Basai artinya duduk bersanding dalam acara resepsi perkawinan. Dalam tradisi Sumbawa para pengiring dalam arakan bersama seluruh warga masyarakat wajib menikmati acara makan malam bersama pengantin. Lebih-lebih kepada para tamu undangan yang telah tiba dari kejauhan diharuskan untuk makan malam pula. Para tamu yang datang dari luar telah disediakan akomodasi dirumah-rumah penduduk, yang secara moral tuan rumah juga mempersiapkan segala sesuatunya termasuk makan dan tempat tidurnya, karena para tamu akan sepanjang malam berada dirumah pengantin sambil menikmati pertunjukkan seni tradisi lisan sakeco. 4 Apa yang dilakukan oleh Suharno ini mengundang minat peneliti untuk melakukan penelitian dalam perspektif fungsional-struktur. Peristiwa perayaan perkawinan secara meriah menurut ukuran desa Tengah Kecamatan Utan memacu tanda tanya, bagaimana mungkin pak Suharno mau menyelenggarakan perkawinan anaknya secara besar-besaran dengan menanggap seni tradisi lisan sakeco, sementara pak Suharno bukan asli orang Sumbawa atau sebagai bagian dari warga masyarakat desa. Apakah penyelenggaraan adat ramai mesaq bagi anaknya merupakan upaya untuk membuktikan bahwa walaupun bukan orang asli Sumbawa tetapi ia adalah warga desa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga-warga lainnya. Hal itu semua menimbulkan daya tarik bagi peneliti karena pak Suharno dalam perayaan perkawinan anaknya menanggap seni tradisi lisan sakeco bukan dangdutan. B. Rumusan Masalah Dari paparan latar belakang di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi seni pertunjukan tradisi lisan sakeco dalam masyarakat dan para pemain sakeco (tau sakeco) yang memiliki arti penting bagi kehidupannya, terutama menyangkut perannya sebagai pelaku seni pertunjukan tradisi lisan sakeco. Apalagi dalam masyarakat pemiliknya menjadikan genre seni sakeco ini sangat mengakar dan menjadi milik masyarakat setempat. Dari hal itu menimbulkan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara ilmiah; (1) Apa ciri-ciri seni pertunjukan tradisi lisan sakeco Sumbawa ? (2) Mengapa seni 5 pertunjukan tradisi lisan sakeco Sumbawa sampai sekarang masih tetap bertahan dalam masyarakat ? . C. Tujuan Penelitian Secara umum, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk memahami ciri-ciri dan fungsi seni pertunjukan tradisi lisan sakeco bagi masyarakat Sumbawa sebagai nilai sosial budaya di kalangan masyarakat; (2) untuk memahami tentang seni pertunjukan tradisi lisan sakeco dalam masyarakat Sumbawa sampai sekarang ini tetap bertahan. Pemahaman ini diletakan dalam konteks masyarakat Sumbawa yang menglobal bersama kehendak tuntutan zaman. Secara khusus ada beberapa hal yang ingin diketahui dan dipahami melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui tentang ciri-ciri seni tradisi lisan sakeco Samawa sebagai genre pertunjukan yang masih bertahan dalam masyarakat sampai saat ini dalam adat ramai mesaq, khitanan, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa atau kemerdekaan RI dan lain-lainnya masih menjadi pilihan masyarakat setempat, dan sangat banyak penonton yang menggemarinya, padahal masih banyak jenis seni lain yang mengalami krisis penonton; (2) Memperoleh penjelasan mengenai fungsi seni pertunjukan sakeco bagi masyarakat Sumbawa dilihat dari fungsi budaya, sosial, politik dan ekonomi. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini mendeskripsikan seni pertunjukan tradisi lisan sakeco Sumbawa yang diharapkan dapat memberi beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini: (a) dapat memberikan manfaat 6 sebagai informasi lanjut, menambah khazanah kepustakaan bagi pengembangan ilmu di bidang seni tradisi lisan, dan kajian antropologi budaya yang secara khusus bagi masyarakat Sumbawa, dan secara universal bagi masyarakat Indonesia. Kesemua itu digunakan oleh generasi selanjutnya sebagai blue print dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapinya; (b) Sebagai referensi bagi pengkaji tradisi lisan, antropologi dan sebagai perwujudan dari pandangan hidup masyarakat pemiliknya, sehingga dapat dijadikan studi perbandingan dengan daerah lainnya. Adapun manfaat secara praktis diharapkan dapat berguna untuk berbagai hal: (1) penelitian ini diharapkan bagi masyarakat pembaca betapa banyak hal yang bisa dipelajari secara tersurat dan tersirat dari kearifan lokal seperti seni tradisi lisan sakeco Sumbawa. Dengan memahami maksud yang terkandung didalamnya dapat mengetahui fungsi sakeco bagi masyarakat Sumbawa; (2) bagi masyarakat Sumbawa dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai upaya mengangkat nilai-nilai lokal tradisi lisan Sumbawa untuk dijadikan pedoman dalam bermasyarakat, sebagai bahan pertimbangan informasi bagi para penentu kebijakan di Sumbawa, dalam merumuskan aneka kebijakan publik di bidang budaya, sosial, politik dan ekonomi, terutama menyangkut eksistensi tradisi lisan; (3) dapat menjadi pedoman bagi kelompok pertunjukan sakeco yang ingin mengembangkan kemasan seni pertunjukannya; (4) disamping itu juga akan bermanfaat bagi para pengelolah seni pertunjukkan sebagai salah satu model pedoman kerja. Adapun bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini akan menambah bacaan dan wawasan yang sangat beragam dalam bidang seni 7 pertunjukan yang kelak dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut atau dapat memotivasi peneliti lain untuk mengadakan suatu penelitian yang lebih mendalam terutama hal-hal yang belum dapat dijangkau dalam penelitian ini. E. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka ini akan dipaparkan beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Tulisan-tulisan yang dimaksud akan dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu kelompok pertama akan dipaparkan kajian tentang tradisi lisan, kedua akan dijelaskan studi sakeco itu sendiri. 1. Tradisi Lisan Informasi mengenai tradisi lisan ada beberapa tulisan yang telah melakukan penelitian di Indonesia dari disiplin ilmu yang berbeda-beda.6 Menurut Dananjaya (1991:9-10) apa yang dilakukan merupakan sebagian kecil dari bahan tradisi lisan Indonesia yang sangat banyak itu. Kebanyakan mereka itu adalah orang Eropa, terutama berkebangsaan Belanda. Hasil karya dapat dibaca dalam buku Raymond Kennedy yang berjudul Bibliography of Indonesian People and 6 Penelitian itu dengan paradigma yang berbeda misalnya dari filologi G.A.J. Hazeu (1897), J.Kats (1923), H.Kern (1887), R.M.Ng Poerbatjaraka (1940), Tjan Tjoe Siem (1941), J. Hooykaas (1956), dan Th.Pigeaud (1929). Dari musikologi antara lain Jaap Kunst (1959), A. Brandts Buys (Van Zijp) (1926), Colin McPhee (1966), Suryabrata (dahulu bernama Bernard Ijzerdraad), dan Mantle Hood (1958). Dari antropologi antara lain B.J.O Schrieke (1921 dan 1922), WH.Rassers (1959), J.PB. de Josselin de Jong (1929), Jane Belo (1960), Gregory Bateson dan Margaret Mead (1942), Koentjaraningrat (1961), Clifford Geertz (1964), dan James Peacock (1968), I Gusti Ngurah Bagus (1971). Dari teologi antara lain C.Poesen (1870), J.Kreemer (1888), P.J. Zoetmulder (1939), Roelof Goris (1937), A.C.Kruyt (1940), dan N. Adriani (1930). Dari ilmu Tari antara lain K.E.Mershon (1971) dan Made Bandem (1972), dan dari senin rupa Walter Spies (1939) dan (Dananjaya, 1991). 8 Cultures (1962), atau buku J. Danandjaya yang berjudul An Annotated Bibliography of Javanese Folklore (1972). Pada masa itu penelitian tradisi lisan Indonesia baru pada masa awal, baik dalam hal pengumpulan data maupun analisa. Walaupun demikian kita merasa bangga atas usaha para sarjana dimasa itu, karena mereka menerapkan teori yang telah dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan sosial dan budaya. George Alexander Wilken (1912) telah menerapkan paradigma evolusi religi dalam menganalisa kepercayaan rakyat Indonesia. Kesimpulannya bahwa kepercayaan orang Jawa tentang padi mempunyai jiwa dan adat memanggur gigi adalah bekas peninggalan yang tetap masih hidup (survival) dari zaman animisme dulu. W.H. Rassers dan J.P.B. de Josselin de Jong (1922) telah menggunakan paradigma struktur sosial dalam menganalisis tradisi lisan Indonesia. Hasilnya adalah ada kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari legenda, upacara, dan struktur sosial Jawa. Khusus tentang puisi lisan H. Van der Veen (1924) mengkaji puisi tentang kematian Toraja Selatan, WL Steinhart (1934) dan Lageman (1983) mengkaji puisi dari cerita rakyat Nias, Dunnebier (1938) mengkaji puisi lisan di Sulawesi Utara, Schrer (1966) mengkaji puisi lisan Dayak Ngaju, dan Fox (1971) mengkaji puisi lisan masyarakat pulau roti. Bahkan puisi-puisi itu oleh Fox pada secara khusus menemukan gejala paralelisme pada puisi lisan di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan menurut Fox (1971) gejala paralelisme puisi lisan bini pada masyarakat pulau Roti dibandingkan puisi lisan karya Homer di Yugoslavia 9 mempunyai struktur yang berbeda. Bini dilantunkan atau kadang-kadang dibaca dalam bahasa ritual dan disusun dalam bentuk paralelisme. Bini dapat mengekspresikan kisah apa saja, tetapi biasanya berhubungan dengan mitologi masyarakat roti, misalnya asal usul api, hubungan zaman purba dengan dewadewa langit/laut dan keturunannya. Dengan tema tertentu, bini dapat juga dilantunkan dalam upacara kematian. Tema puisi lisan bini lebih terbuka karena mengisahkan pengalaman hidup dan kejadian sehari-hari yang dialami seorang tokoh lantunan. Tradisi lisan bini menggunakan kata-kata yang berpasangan yang sifatnya dyadic, yaitu pasangan kata yang di pakai menunjukkan kesejajaran semantik misalnya, matahari/bulan, kepala/ekor, jantan/betina, tinggi/pendek, besar/kecil, tua/muda, dll (Fox, 1986). Pasangan-pasangan kata seperti ini sifatnya tetap (fixed pairs) yang telah disiapkan adat. Paralelisme seperti ini dipengaruhi oleh konsep kosmologi dualis masyarakat Roti. Pada prinsipnya, dalam puisi bini terdapat kesejajaran antara dua baris yang mengandung kata yang ada pasangannya disejajarkan dengan baris lain dengan menggunakan kata pasangan itu sehingga bentuknya menyerupai dyadic sets. Disamping itu pula Fox tidak hanya membahas struktur bini, tetapi juga menggali fungsi bini bagi masyarakat Roti. Mengenai tradisi lisan rakyat lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelantunan dalam proses penciptaan karya, pencipta hanya mengingat kelompok kata dan formula sesuai dengan keinginannya secara kreatif maka tentu menggunakan pandangan Lord (1981) yang meneliti epik Homer dengan ciri- 10 cirinya yaitu panjang (puluhan ribu baris), naratif, oral, bertema kepahlawanan, tradisional, menggunakan repetisi dan paralelisme, berpola sama, dan menggunakan stereotyped phrase. Karakteristik repetisi, paralelisme, dan stereotyped phrase muncul secara dominan pada baris-baris lantunan sehingga karya Homer disebut formulaic epic (Yektiningtyas (2008:14). Bagi Lord puisi epik lebih bersifat narrative oral poetry, tema lantunan lebih bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan perasaan seseorang pelantun ketika melantunkan lantunannya. Finnegan (1977) berargumentasi bahwa generalisasi formulaic style yang ditemukan Lord masih perlu ditinjau kembali. Lord mengatakan bahwa puisi lisan ditandai dengan formula dan formulaik serta puisi yang berformula dan formulaik adalah lisan masih dapat diperdebatkan. Finnegan menekankan bahwa signifikansi formula dan formulaik cenderung untuk memberikan kesempatan bagi pelantun untuk mengekspresikan puisi lisan secara unik dan membuat lantunannya berbeda dari lantunan yang lain. Walaupun demikian A. Teeuw (2003) menggarisbawahi bahwa formula dan formulaik yang ditemukan Lord sangat berarti bagi dunia folklore lisan. Hasil penelitian Lord memberikan dorongan bagi para peneliti selanjutnya untuk meneliti puisi lisan dari daerah lain serta mengembangkan konsep teori yang sesuai. Hasil penelitian Parry-Lord menurut Abdullah (1988) juga mendorong para ahli untuk mengujinya lewat berbagai penelitian terhadap karya-karya klasik maupun cerita rakyat yang ternyata banyak memberikan kesesuaian, sehingga mengantarkan pada kesimpulan bahwa gaya formulaik puisi lisan (oral formulaik 11 style) merupakan pangkal tolak yang membedakan puisi lisan dengan puisi tulis. Sweeney (1973) telah meneliti puisi lisan melayu yang membuktikan bahwa tiap kali tukang cerita membawakan ceritanya, merupakan penciptaan kembali, bukan penghafalan. Setiap penyampaian berbagai pilihan katanya dan sering juga sekuen (sequence)-nya, sedangkan isi ceritanya dapat dikatakan tidak berubah. Unsurunsur perulangan, kesejajaran, selipan bunyi-bunyi kosong (filler, balancing words), dan ceritapun di rakit dari persediaan unsur-unsur bahasa dan unsur puitik yang siap pakai (stock-in-trade) (Teeuw, 1984, Abdullah, 1988). Untuk memperkuat hasil penelitian Sweeney di atas, khusus tentang puisi lisan Melayu, Piah (1989) melakukan penelitian dan memberikan pandangan tentang puisi rakyat yang memiliki ciri-ciri umum yaitu formula atau bentuknya terikat oleh konvensi-konvensi tertentu yang seterusnya memberikan bentuk dan struktur dalam puisinya. Misalnya puisi melayu tradisional tersusun atas barisbaris atau aturan-aturan kata yang berulang-ulang dalam kedudukan yang sejajar. Menurut Mat Piah (1989), kesejajaran pada pantun misalnya lebih jelas terlihat dengan adanya baris-baris yang berpasangan (symmetrical), yaitu suatu bagian yang secara fisik mempunyai ciri yang sama dengan yang lain. Sesuai dengan skema rima akhir (a-b-a-b), baris pertama berpasangan dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris ke empat. Dengan demikian, sebuah pantun yang baik akan mempunyai pasangan-pasangan yang sempurna, bukan saja dari segi rima dan jumlah suku katanya, melainkan juga kata-kata yang mungkin berpasangan. Huizinga (1990) berpendapat bahwa pantun melayu yang terdiri dari empat baris itu (a-b-a-b) dua barisnya yang pertama dinamakan sampiran untuk 12 menyatakan suatu fakta, sedangkan dua baris terakhir yang dinamakan isinya mengandung suatu sindiran. Bahkan menurut Piah puisi melayu tradisional masih digunakan dalam kegiatan kesenian rakyat yang merupakan sebagian dari budaya rakyat (folklore) yang dipersembahkan, disampaikan, dan disebarkan dalam bentuk lisan. Hampir semua nyayian daerah atau senandung rakyat, nyayian-nyayian yang mengiringi tarian, ungkapan-ungkapan dalam istiadat-istiadat sosial dan keagamaan, zikir yang dilagukan atau yang mengiringi perlakuan yang bersifat magis, dipersembahkan dan diabadikan dalam bentuk puisi (Abror, 2009). Hal ini terbukti dengan hasil penelitian Soetaryo (1979) tentang Kesenian Angguk di Desa Garongan tentang pantun yang mereka tampilkan tidak saja mengungkapkan hal-hal yang profan, melainkan juga bersifat sakral (magis) sehingga pemain dalam aktraksi tersebut mengalami ndadi (trance). Banyak peneliti menaruh perhatian terhadap puisi lisan tradisonal misalnya Yektiningtyas (2008) meneliti Helaehili dan Ehabla sebuah bentuk puisi lisan masyarakat Sentani Papua yang ditembangkan secara spontan dengan hafalan. Lantunan dibangun dengan formula untuk memudahkan dalam melantunkannya yaitu kata/frasa paralel yang diciptakan sendiri atau yang telah disiapkan adat (ready-made phrase). Dan melalui penelitiannya ditemukan bahwa lantunan helaehili dan ehabla mempunyai fungsi sebagai; (1) media pendidikan, (2) pencerminan angan-angan masyarakat sentani, (3) alat pengesah pranata adat dan lembaga kebudayaan, (4) pemaksa dan pengawas norma sosial dan adat, (5) penguat emosi keagamaan, (6) media sosialisasi masyarakat, (7) media hiburan. 13 Termasuk tradisi lisan macapat dalam ungkapan orang madura disebut mamanca sebagai salah satu unsur seni pertunjukan yang pernah di teliti oleh Helene Bouvier (1994). Mamanca ini termasuk puisi lisan Jawa yang dinyayikan lalu dituturkan suatu cerita (careta) dalam tembang (tembhang), sambil menambah penjelasan (tegghes). Acara mamanca diselenggarakan pada arisan, upacara pembawa berkat di makam keramat (rokat bhuju), di rumah pribadi (rokat bengko), upacara sunat (sonnat), perkawinan (panganten), pangur gigi (mamapar), nazar untuk memiliki sejumlah sapi (niyat sape), hari raya islam dan nujum. Telah banyak kajian tentang macapat sebagai sastra lisan seperti I Wayan Senen (2001) Komparasi Tembang Macapat Jawa dan Bali, Laginem, et.al. (1996) Macapat Tradisional Dalam Bahasa Jawa, Hadisubroto (tt) Serat Kesusatraan Djawi, Ciptowiyono (1988) Tuntunan Sekar Macapat, Darmacarita (tt) Macapat Pancasila, Karsono H. Saputra (1992) Pengantar Sekar Macapat, Marwoto (1992) Tuntunan Sekar Macapat, Sardjana HA (1968) Tembang Macapat, Soewarno (1989) Macapat, Yohanes Mardimin Sekitar tembang Macapat, Zawimah (1985) Macapatan, Soedarjanto (1989) Macapat Dalam Bahasa Jawa, Sri Nardiati ( tt ) Pedhotan Tembang Macapat dan Asmoro Achmadi (1998) Nilai-Nilai Subtansial Dalam Macapat. Peneliti-peneliti di atas menyebutkan bahwa tembang macapat ada sebelas macam, yaitu Pucung, Dhandhanggula, pangkur, sinom, kinanthi, durma, mijil, maskumambang, asmaradana, megatruh, dan gambuh. Semua tembang macapat susunannya diatur oleh aturan yang ketat. Berbagai aturan dalam menyusun sekar 14 macapat selalu diikat oleh pupuh yang didalamnya terdapat podo (unit yang kecil dari lirik/suku kata) dan setiap akhir dari lirik diatur bunyi tertentu. Sekar macapat juga sarat dengan nilai-nilai luhur yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batín. Berbagai nilai moral itu diharapkan dapat membawa kearah kebaikan hidup manusia, karena ajaran itu bersumber pada nilai-nilai luhur (kebaikan). Sekar macapat juga mengandung nilai-nilai edukatif (etik eudemonisme) agar manusia memiliki sifat-sifat rendah hati, susila, bijaksana, dan sopan. Menurut Soedarsono (1994:2) macapat sebagai puisi Jawa tradisional memiliki kaitan dengan seni suara dan merupakan bagian dari seni pertunjukan. Banyak peneliti fokus pada kajian ini seperti Benard Arps (1922) di Banyuwangi yang yang meneliti tentang Tembang in Two Traditions: Performance and Interpretation of Javanese Literarure. Sebagai karya sastra Arps melihat macapat sebagai seni resitasi yang membahas unsur-unsur yang diperlukan oleh penyanyi (singer) misalnya mengenai tone, laras, pedhotan, dan watak tembang macapat. Dan bahkan I Made Bandem (1985) yang berjudul Wimba Tembang Macapat Bali mendeskripsikan sejarah tembang macapat, ciri-ciri tembang macapat, laras, dan syarat-syarat penembang atau penyanyi macapat. Heru Djarot Santosa (2001) dalam artikelnya yang berjudul Tradisi Macapat di Kabupaten Boyolali mengatakan bahwa macapat mengandung dua hal yakni seni sastra dan seni pertunjukan. Tradisi macapat berangkat dari tradisi lisan ke tradisi tulisan, dan kembali lagi ke tradisi pelisanan. Tradisi macapat di Kabupaten Boyolali dilaksanakan sebagai kenangan terhadap leluhur dari Kasunanan Surakarta. 15 Demikian pula ahli-ahli sastra Jawa seperti Arintaka (1981) dalam bukunya Sekar Macapat 1 dan 2 memberi tuntunan bagaimana cara menyayikan tembang macapat disertai notasinya untuk masing-masing metrum jenis tembang macapat. R.Hardjowirogo yang berjudul Pathokaning Nyekaraken (1952), Yohanes Bosco Maridja (2005) Macapat Rabu Pahingan yang tidak dapat dipisahkan dengan peziarahan rohani (laku prihatin) yang dilakukan oleh Pastur G.P. Sindhunata, S.J dengan beberapa umat Katholik Pakem. Sebagai seni pertunjukan resitasi kegiatan macapat dilaksanakan setiap malam selasa kliwon berupa tirakan atau wungan dengan menyanyikan metrum-metrum macapat. Setiap malam rabu pahing diadakan kegiatan untuk menghormati Bunda Maria yang dikenal dengan Macapat Rabu Pahingan. Kegiatan tersebut tetap berlangsung sampai sekarang dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan ritual yang tetap memperhatikan tempat, waktu, peserta, dan kebiasaan setempat, serta benda-benda simbolis dengan pemaknaan baru sesuai dengan ajaran gereja. 2. Sakeco Hasil penelitian yang membahas secara khusus mengenai seni tradisi lisan sakeco bagi masyarakat Sumbawa, sampai saat ini belum banyak yang melakukan penelitian secara mendalam yang memuat topik ini. Hanya ada satu hasil penelitian yang diteliti oleh Suyasa (2001) dengan judul ”Seni Balawas Dalam Masyarakat Etnis Samawa”. Hasilnya adalah bahwa seni balawas merupakan bentuk sastra setengah lisan yang disampaikan melalui saketa, langko, gandang, ngumang, sakeco, badede, dan basual. Hal yang membuat orang tidak banyak dan 16 fokus melakukan penelitian tradisi lisan di Sumbawa dikarenakan; (1) posisi Kabupaten Sumbawa di wilayah Timur Indonesia, yang jauh dari gugusan pulau di Nusantara ini sehingga jarang sekali terdengar dalam pentas Nasional dalam kaitan dengan seni tradisi lisan. Jangankan untuk mengenal seni tradisi lisannya, daerah Sumbawa saja selalu diasosiasikan berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), padahal kabupaten Sumbawa berada pada wilayah Nusa Tenggara Barat, (2) di Sumbawa dan Nusa Tenggara Barat (NTB) secara keseluruhan belum ada yang fokus untuk seni tradisi lisan ini. Padahal tradisi lisan ini cukup banyak berserakan dalam masyarakat yang membutuhkan sentuhan para peneliti untuk melakukan research secara mendalam untuk kepentingan sebuah ilmu dan kemasyarakatan. Dalam beberapa buku hanya sekedar menginformasikan tentang adanya seni tradisi lisan sakeco dalam masyarakat Sumbawa tetapi bukan menjadi fokus kajian obyek material maupun formal. Dalam buku Manca (1984:39) yang berjudul Sumbawa Pada Masa Lalu (Suatu Tinjauan Sejarah) menjelaskan terutama orang Belanda bernama Zolinger yang datang ke Sumbawa sebelum ada pemerintahan Belanda, di mana pada waktu itu Belanda sedang berusaha untuk mendaratkan bala tentaranya, sehingga kedatangannya tidak mendapat sambutan baik dari kalangan rakyat. Dalam pandangan Zolinger (1987) secara sentimentil mengatakan bahwa kedatangannya baik, oleh Sultan maupun pembesar-pembesar kerajaan lainnya demikian juga rakyat jelata menerima dengan muka tidak baik. Sehingga lantaran jengkelnya mengatakan bahwa selama berada di Sumbawa Sultan selalu menunjukkan pembawaan tidak sopannya, kemudian Zolinger mengolok dengan mengatakan 17 bahwa orang-orang Sumbawa bukan bangsa periang, jarang mengadakan pesta, dan bahkan menganggap tidak terdapat alat-alat musik dan belum pernah mendengar orang Sumbawa bernyanyi, padahal dari dulunya seni tradisi lisan sudah cukup lama berkembang seiring dengan proses islamisiasi di Sumbawa dan bahkan rebana, lawas yang yang menjadi pesan sakeco digunakan sebagai alat media komunikasi dalam sebuah pertunjukan. Tetapi hasil penelitian team Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (1990) dalam buku Ensiklopedi Musik dan Tari daerah Nusa Tenggara Barat membatah tulisan dan pendapat Zolinger, ternyata orang Sumbawa (tau Samawa) memiliki kegemaran yaitu menembangkan puisi lisan tradisional (balawas). Tradisi ini menurut Muhammad (2011) ada semenjak manusia mengenal bahasa Sumbawa melalui proses pembauran kebudayaan yang menghuni tanah Sumbawa. Awalnya berperan sebagai alat ekspresi suasana batin manusia yang halus, atau suasana batin manusia diliputi rasa haru, sendu, gundah-gulana karena musibah atau datangnya marabahaya yang mengancam hidupnya, maka untuk menghilangkan kondisi itu dicurahkan perasaannya dalam bentuk lawas. Salah satunya adalah lawas bernuansa ajaran islam (pamuji) yang berasal dari ungkapan perasaan yang halus akan cinta (mahabbah) kepada Allah SWT, tempat bercermin dan mengevaluasi diri, melihat realitas kehidupannya, kemudian diwujudkan kedalam sikap dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nilai-nilai inilah yang mempengaruhi secara signifikan dalam perilaku keberagamaannya, memberi makna dan bobot terhadap hidup dan kehidupannya. Kemudian wujud kreatifitas 18 itu dimanifestasikan dalam pola hidup sehingga melahirkan perubahan sikap dalam bermasyarakat. Bahkan Ardhana (1985), meneliti tentang Sastra Lisan Samawa. mengklasifikasikan tradisi lisan Samawa menjadi jenis prosa (fable, mitos, legenda, dongeng, cerita sejarah, kisah asmara, dan fable jenaka), dan puisi berbahasa samawa disebut lawas yang dalam perkembangannya telah menjadi inspirasi masyarakat dalam berkesenian, dan menggunakan lawas sebagai medianya. Muhammad (2007) dalam Lawas) dan Muatan Keagamaannya dan Rayes (2000) Seni dan Sastra menjadi Rohani Kita, menjelaskan bahwa lawas merupakan puisi tradisional yang diwariskan secara turun temurun dengan cara dilantunkan (temung). Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengekspresian isi hati dalam bentuk cinta, sedih, kritik, nasehat, motivasi, nilai ajaran Islam dan sebagainya. Ada berbagai jenis tradisi lisan; (1) tradisi lisan lisan anak-anak (tau ode), yang mengedepankan dunia anak-anak yang penuh kegembiraan, (2) tradisi lisan muda-mudi (taruna-dadara), yang intinya berkisar sekitar perkenalan, percintaan, berkasih-kasihan, perpisahan beriba hati, (3) tradisi lisan orang tua (tau loka) berintikan pendidikan Islam (nasihat agama), bersifat didaktis yang berintikan ajaran agama. Lawas-lawas itu lahir dengan berbagai macam cara. Ada yang dilagukan sendiri-sendiri, ada pula secara berpasangan misalnya: Di iringi dengan rebana kecil (rebana ode) dinamakan sakeco, bila dengan iringan rebana besar (rebana rea) dinamakan malangko. Diiringi dengan seruling (sarune) dinamakan gandang, jika ditambah dengan koor (gero) disebut saketa. Secara beramai-ramai pria dan wanita dengan berbalas lawas (saling siyir) disaat musim panen padi (mengetam) agar panasnya matahari tak terasa di sebut balawas (Manca,1984:40). Apabila melangsungkan upacara 19 perkawinan atau sunat rasul beberapa wanita menembangkan lawas sambil membunyikan kosok kancing (sejenis maracas) dinamakan badede. Seorang pria mengancungkan kedua tangannya di tengah sawah sambil menembangkan lawas (seperti seorang penari) dengan suara merdu sehingga ia menjadi pusat perhatian orang banyak dalam tradisi karapan kerbau (barapan kebo) dinamakan ngumang. Dan ada juga tanya jawab dengan lawas, dimana seseorang mengajukan soal lawas (menyebut sampiran dari sebuah lawas) dan yang mengetahui segera menjawab soal tadi. Jelasnya seorang mengemukakan sampiran lawas dan seorang lagi menjawab dengan isi lawas dinamakan basual. (Gani, 1997: 27-30). Dalam Buku Manca (1984) menjelaskan secara detail tentang cara melagukan lawas tanpa iringan bersyarat pada waktu dan jenis orang yang melagukan. Ada ulan sawai (perempuan) dan ulan salaki (laki-laki). Bila dilakukan pada waktu pagi disebut dengan ulan siyup, pada siang hari disebut ulan tangari, dan pada waktu malam disebut ulan petang. Membawa ulan-lan tersebut harus sesuai dengan waktunya dan akan menjadi tertawaan orang bila membawa ulan itu tidak sesuai dengan waktu dan jenis orang yang membawanya. Demikian pula dapat pula membedakan dimana kita berada setelah kita mendengarkannya. Secara beramai ramai diwaktu mengetam padi wanita dan pria saling siyir (sambut menyambut lawas) begitu mengesankan masing-masing sehingga terik matahari tak terasa. Diwaktu memasang atap rumah pria sesama pria menembangkan lawas (balawas), sedang wanita menanak nasi serta memasak lauk-pauknya untuk suguhan bagi orang memasang atap rumah (selip santek). Lain pula alunan gadis-gadis yang sedang beramai-ramai menumbuk padi (nujaq) pada waktu malam hari. Dengan alunan suaranya yang merdu menyebabkan mereka yang mendengarkannya terharu, tak lama kemudian tempat itu menjadi ramai oleh pemuda-pemuda yang ingin melihat dan mendengarkan secara dekat gadis-gadis yang secara santai dengan lawas (puisi lisan) itu. Di tengah-tengah 20 hutan, para gembala sambil berkuda atau berjalan kaki mengiringi ternak gembalanya, ataukah kebetulan sedang melepas lelah dibawah pohon terdengarlah suara pemuda yang belawas meramaikan dirinya yang sedang mengembalakan hewan ternaknya. Demikian pula di tengah malam, berjejer-jejer di tengah sawah beratapkan jerami terdengarlah suara melengking memecah malam yang sepi untuk menahan mata dari ngantuk. Terkadang terdengar pula saling bergantian dengan bunyi serunai yang dibuat dari batang padi. Selain kegemaran tersebut di atas ada juga yang dinamakan badiya yaitu menembangkan legenda rakyat yang bernama Lalu Diya dan Lala Jinis diiringi dengan genang air. 7 Diya adalah salah satu tradisi lisan Sumbawa yang daya rangsangnya sangat mengesankan seperti tergambar di kalangan masyarakat Sumbawa sebagai berikut: Pengadilan adat di Sumbawa pernah menjatuhi hukuman mati kepada 4 orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan. Pidana kerajaan pada masa itu, berlaku hukum syariat Islam sepenuhnya. Barang siapa yang membunuh, maka pembunuhnya dibunuh pula. Algojo kerajaan (Penggawa Teyar) sudah bersiap-siap untuk menanti perintah pengadilan. Tetapi tentu saja perintah itu tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari Sultan Sumbawa. Rupanya Sultan Sumbawa juga memikirkan, kapan tiba waktunya yang tepat untuk suatu eksekusi. Sultan berfikir bahwa tidak terlalu mudah untuk suatu kerajaan yang kuat seperti Sumbawa membinasakan warganya. Pada suatu hari keempat orang yang tersangkut pidana pembunuhan itu disuruh membersihkan halaman Istana, Begitulah tugas mereka bertahun-tahun. Mereka ternyata mengubah kelakuannya, tingkah sebagai pembunuh kian hari kian berkurang. Kebetulan mereka rupa-rupanya bukan penjahat sungguhan, mereka membunuh karena suatu pembalasan dendam semata. Karena 7 Adapun yang dinamakan genang air yaitu gendang yang dibuat dari seruas bambu yang diberi lubang pada kedua ujungnya. Di atasnya kira-kira 1 ½ jari diratakan sedikit, lalu di tengahnya diberi lubang 4 persegi. Sepanjang tempat yang diratakan itu dicukilkan dengan pisau berupa 4 buah snaar, masing-masing 2 pada sebelah menyebelah. Dua snaar sebelah dalam dihubungkan dengan lidah persegi empat yang dibuat dari hati bambu. Sewaktu menembangkan itu, sebelah tangan memukul pada ujung bambu lalu mengeluarkan suara gendang, sedangkan jari jempol tangan yang disebelahnya mementilkan snaar berganti-ganti dengan beberapa kali pada yang engkel lalu berpindah ke snaar yang berklep (diberi berlidah) yang mengeluarkan suara bass. 21 kelakuannya yang baik, oleh kepercayaan Sultan (Nyaka) keempat pembunuh itu dibolehkan tidur di bawah kolong istana. Pada suatu malam mereka melakukan badiya dengan suara yang sangat merdu. Nyaka-nyaka dan sarian-sarian yang menjaga istana membiarkan saja sambil mendengar diya itu. Tiba-tiba dalam keadaan santai Sultan yang sedang duduk di tiang kuntung yaitu satu dari sekian banyak tiang Istana asyik juga mendengarkan diya keempat calon narapidana mati itu. Lama nian Sultan tertegun setelah mendengarkan alunan lagu diya itu, sehingga beliau lambat sekali masuk ke tempat peristirahatan. Permasalahan yang mencekam pikiran beliau adalah apakah melaksanakan eksekusi hukuman mati ataukah menjaga lagu diya yang ekspresif-melancholis itu dapat dikembangkan dalam seluruh kawasan kerajaan beliau untuk dijadikan santapan rohani kerajaan ataukah membunuh nyawa keempat orang itu. Akhirnya mejelis kerajaan mengambil keputusan terhadap keempat orang tersangkut pembunuhan itu dan karena mereka merupakan orang yang memiliki keahlian, akhirnya kerajaan menghapus hukuman mati dan kepada mereka. Sultan memberikan tugas untuk menembangkan diya di seluruh kerajaan Sumbawa. Tradisi lisan sakeco dijelaskan dalam BUK Samawa bahwa seni ini sesuai dengan latar belakang sejarahnya sudah tidak lagi merupakan pertunjukan yang menjadi milik kelompok tertentu, tetapi sudah menjadi milik kerajaan, sehingga sebagai seni persembahan. Jikalau ada pertunjukan yang diadakan oleh Sultan maka seni tradisi lisan sakeco dan seni lain sering ditanggap untuk menghibur masyarakat dan lingkungan kerajaan Sumbawa yang sudah memeluk Islam, bahkan sakeco menjadi pertunjukan yang mempunyai peran cukup penting dalam kehidupan kaum bangsawan kerajaan. Tetapi menurut Hamim (2011) dalam buku Lawas Samawa Dulu dan Kini tidak ada dokumen di Sumbawa yang dapat memberikan gambaran tentang seni sakeco sehingga sulit menelusuri awal munculnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa istilah Sakeco itu berasal dari nama dua orang ahli pelantun lawas yang bernama Zakaria dengan panggilannya 22 (pendondok) Sake dan Syamsuddin dengan panggilannya Co sehingga menjadi Sakeco perlu ditelusuri secara mendalam atau penelitian lebih lanjut dengan paradigma tertentu. Diperkirakan menurut Amin (2012) dalam buku Apresiasi Tradisi Lisan Sumbawa; Lawas, Ama, Panan dan Tutir dimulai oleh pembantu-pembantu Sultan Sumbawa yang pulang berguru dan belajar agama Islam di Aceh, Semenanjung Melayu, dan Banjar. Mereka mengajak datang ke Sumbawa para ulama dan pujangga penyebar agama Islam termasuk dari kota Lawe (Padang Lawas) Sumatra Utara. Kemudian para pujangga itu membuat syair lawas dalam masyarakat Sumbawa. Kemunculan lawas di masa kerajaan Sumbawa, oleh seorang ulama dan budayawan Sumbawa yaitu H.Muhammad Amin Dea Kadi telah menciptakan lawas lawas akherat (pamuji) yang di tulis dengan huruf Arab Melayu berbahasa Sumbawa (rabasa Samawa) sampai 190 bait saling berkait secara teratur (bariri) tiada putus berangkai menjadi satu. Lawas-lawas pada masa itu dipakai sebagai media pembelajaran dalam memahami agama Islam. Hal penting lain yang terdapat di dalam tulisan ini adalah disebutkan mengenai pertunjukan di Sumbawa memberikan informasi bahwa sakeco pada waktu itu telah berkembang di dalam Pondopo kesultanan maupun di luar Pondopo kesultanan dan menyebar secara luas di masyarakat, baik di kota maupun di desa. Dalam menembangkan sakeco, pemain sakeco (tau sakeco) berkeliling ke desa tempat orang menyelenggarakan hajatan. Informasi mengenai tradisi lisan sakeco inilah yang mendorong Suyasa (2001) melakukan penelitian 23 dan fokuskan pada bentuk seni balawas dengan mennggunakan paradigma Lord (1976) yang meliputi formula dan tema. Dalam proses penciptaan karya tradisi lisan pencipta belajar mengingatkan kelompok kata atau ungkapan-ungkapan dan pola dari pencipta yang lain. Kemudian menggunakan formula itu sesuai dengan keinginannya secara kreatif, dengan analogi. Dalam penyusunan baris dengan formula terjadi proses pergantian, kombinasi, pembentukan model, dan penambahan kata atau ungkapan baru pada pola formula sesuai dengan kebutuhan. Pencipta dapat membuat baris-baris terus menerus sesuai dengan keinginannya dan kreativitasnya. F. Kerangka Teori Seni tradisi lisan sakeco di Sumbawa adalah salah satu khasanah kebudayaan yang ada di Indonesia. Untuk memperkuat argumentasi itu Herkovits (1956:17) mengatakan bahwa kebudayaan adalah buatan manusia dan merupakan bagian dari lingkungannya, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, dan kebudayaan itu dapat dipelajari. Bahkan Janet Wolff (1993) dalam The Social Production of Art mengungkapkan bahwa seni tidak bisa lepas dari masyarakat pendukungnya yang merupakan produk sosial. Pendapat Wolff sepadan dengan pandangan Arnold Hauser (1982) dalam The Sociology of Art dengan bahasan khusus Art as a Product of Society dan Society As The Product of Art mengungkapkan bahwa seni sebagai produk masyarakat tidak lepas dari adanya berbagai faktor sosial budaya, yaitu faktor alamiah dan faktor generasi, yang 24 semuanya memiliki andil bagi perkembangan seni (Wolff, 1993:26, Hauser, 1982:94, Caturwati, 2011:38). Dalam kaitanya dengan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teoritis8 ciri-ciri tradisi lisan, formula dan paradigma fungsional-struktur dalam sebuah pertunjukan: 1. Ciri-Ciri Tradisi Lisan Kebudayaan menurut Clark Wissler (1923) mempunyai unsur-unsur yang disebut dengan cultur universals seperti sistem mata pencaharian hidup (ekonomi), sistem peralatan dan perlengkapan hidup (teknologi), sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan sistem religi. Tradisi lisan (Folklore lisan) juga mempunyai unsur-unsur semacam itu yang disebut dengan genre, atau dapat diterjemah menjadi bentuk (form). Menurut Brunvand (1968) dalam Danandjaja (1991:21) dapat klasifikasikan menjadi tiga bentuk: (1) folklore lisan (verbal folklore), (2) folklore sebagian lisan (partly verbal folklore), dan folklore bukan lisan (non verbal folklore). Dalam kaitannya dengan penelitian ini tentang tradisi lisan maka perlu didefinisikan. Kata tradisi lisan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa 8 Sebelum “paradigma” menjadi konsep yang populer, para ilmuwan sosial-budaya telah menggunakan beberapa konsep lain dengan makna yang kurang lebih sama, yakni: kerangka teoritis (theoretical framework), kerangka konseptual (conceptual framework), kerangka pemikiran (frame of thinking), orientasi teoritis (theoretical orientation), sudut pandang (perspective), atau pendekatan (approach). Kini istilah paradigm sudah mulai banyak digunakan oleh ilmuwan social-budaya. Meskipun demikian, istilah-istilah lama tersebut juga tetap akan digunakan, dengan makna yang kurang-lebih sama dengan paradigma (paradigm) (Ahimsa-Putra, 2011:1) 25 Inggris “oral tradition” yang menurut Finnengan (1989:5) sesutu yang bersifat lisan dan lisan adalah bentuk pewarisan yang khas. “Oral” also implies something expressed in Word (as opposed to sign language, for example, or material cultural); in this sense, stories, songs, or proverbs are distinguished from other cultural behavior by being verbalized” (Levinson, 1996:888). Adapun menurut Ahimsa-Putra (2010:2) oral tradition adalah: “Delivery esp. Oral delivery of information or instruction, transmission of statements, beliefs, rules, customs or the like, esp. By Word of mouth, or by practice without writing. A statement, belief or practice transmitted (esp.orally) from generation to generation“. Tradisi lisan adalah kesaksian verbal yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya atau generasi masa depannya (Vansina, 1973:xiii, Kuper, 2000:719). Dalam pandangan Finnegan (1977:16-17) oral tradition refers to cultural processes and products that, though handed down over time, are not written. Dari beberapa pandangan itu dapat dipahami bahwa tradisi lisan amat luas cakupannya. Tradisi lisan tidak terbatas pada cerita rakyat, mite, dan legenda saja, melainkan berupa sistem kognasi kekerabatan lengkap, hukum adat, praktik hukum, dan pengobatan tradisional. Bahkan tradisi lisan adalah sebuah wadah budaya lisan yang mampu menampung segala aspek warisan kolektif (Endraswara, 2005:3). Berangkat dari definisi itu, maka tradisi lisan sakeco dapat dimasukkan kedalam bentuk folklore lisan (verbal folklore) yang menurut Brunvand (1968) bentuk-bentuknya (genre) meliputi; (a) bahasa rakyat (folk speech) seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan; (b) ungkapan tradisional, seperti pribahasa, pepatah, dan pemeo; (c) pertanyaan tradisional, seperti teka teki; 26 (d) puisi rakyat, seperti pantun, gurindam dan syair; (e) cerita prosa rakyat, seperti mite, legenda, dan dongeng; dan (f) nyayian rakyat (Danandjaja,1991:21-22). Puisi lisan rakyat (genre folklor lisan) seperti tradisi lisan sakeco dalam bentuk lawas-lawasnya tidak berbentuk bebas (free phrase) melainkan berbentuk terikat (fix phrase). Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya, biasanya terdiri dari beberapa deret kalimat, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Menurut Lord (1981:99-102) dalam The Singer of Tales ciri-ciri puisi lisan sebagai berikut: (1) pelantunan bersifat spontan karena dilantunkan langsung di tempat pertunjukan tanpa catatan, (2) pelantun hanya menyiapkan plot dan tema dari rumah, (3) lantunan di dominasi oleh repetisi dan paralelisme, (4) lantunan di perkaya dengan stock epithet, yaitu frasa siap pakai yang telah disediakan adat, (5) lantunan mengandung formula, yaitu kata atau frasa yang digunakan untuk mengisi tempat kosong pada bait-bait selanjutnya yang mempunyai kesejajaran semantik tertentu, (6) ditemukan kesatuan singer-composer-performer dalam pertunjukan, (7) tidak ada istilah original dan varian untuk lantunan karena setiap lantunan adalah asli (selalu diproduksi kembali). Dalam masyarakat Sumbawa, puisi lisan rakyat yang disebut dengan lawas masih berperan, dan mempunyai ciri pengenal utama yang dapat dirumuskan. Menurut Dundes (1972), Dorson, Abrams (1985), Foley (1986), dan Danandjaya (2002), Folklor lisan adalah memiliki ciri-ciri dimana setiap kegiatan budaya masyarakat verbal yang diciptakan masyarakat lama, anonym (unknown 27 authorship), disampaikan dari mulut ke mulut, dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Finnegan (1974:58) Tradisi lisan bercirikan: (a) verbal, berupa kata-kata; (b) tanpa tulisan; (c) milik kolektif rakyat; (d) mengandalkan performance; e) memiliki makna fundamental, ditransmisikan dari generasi ke generasi. Adapun menurut Utley (1965;8) folklor itu bercirikan lisan (oral), ada persebaran (transmission), tradisi (tradition), pelestarian (survival), dan kolektif (comunal). Adapun ciri khusus dari tradisi lisan adalah : (1) Penyebarannya (transmisi) melalui mulut ke mulut, maksudnya ekspresi budaya yang disebarkan secara lisan; (2) lahir didalam masyarakat yang masih bercorak desa, masyarakat di luar kota, atau masyarakat yang belum mengenal huruf; (3)menggambarkan budaya suatu masyarakat, sebab tradisi lisan itu merupakan warisan budaya yang menggambarkan masa lampau, tetapi menyebut pula hal-hal baru (sesuai dengan perubahan sosial). Oleh karena itu, tradisi lisan disebut juga sebagai fosil hidup; (4) anonim, tidak diketahui pengarangnya karena itu menjadi milik masyarakat; (5) bercorak puitis, teratur, dan berulang-ulang. Tujuannya untuk menguat ingatan, dan untuk menjaga keaslian sastra lisan supaya tidak cepat berubah; (6) tidak mementingkan fakta, dan kebenaran. Tradisi lisan lebih menekankan pada aspek khayalan/fantasi yang tidak diterima oleh masyarakat modern, tetapi tradisi lisan itu mempunyai fungsi penting didalam masyarakatnya; (7) terdiri dari berbagai versi; (8) segi bahasa, menggunakan gaya bahasa lisan (bahasa sehari-hari), yang mengandung dialek, dan kadang-kadang diucapkan tidak lengkap (Hutomo,1991:3-4). Dananjaya (1991: 3-5) menjelaskan secara lebih luas dan panjang lebar mengenai ciri-ciri folklor lisan: (a) penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan suatu contoh yang disertai gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat) dari satu generasi kegenarasi berikutnya; (b) Folklor bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan diantara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi); (c) Folklor ada (exist) dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut (lisan), biasanya 28 bukan melalui cetakan atau rekaman, sehingga oleh proses lupa diri manusia atau proses interpolasi (interpolation),9 folklor dengan mudah dapat mengalami perubahan. Walaupun demikian perbedaannya hanya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya dapat tetap bertahan; (d) Folklor bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi; (e) Folklor biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola; (f) Folklor mempunyai kegunaan (function) dalam kehidupan bersama suatu kolektif; (g) Folklor bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi folklor lisan dan sebagian lisan; (h) Folklor menjadi milik bersama (collective) dari kolektif tertentu. Hal ini sudah tentu diakibatkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya; (i) Folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu sopan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa folklor merupakan proyeksi emosi manusia paling jujur manipestasinya. Kalau dipersempit kedalam bentuk puisi lisan tradisional, menurut Piah puisi rakyat memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: (1) Diciptakan dan disebarkan secara lisan dan bersifat kolektif dan fungsional, yaitu tanpa dicantumkan pengarangnya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat; (2) bentuknya terikat oleh konvensi-konvensi tertentu yang seterusnya memberikan bentuk dan struktur dalam puisinya; (3) Sebagai puisi yang bersifat fungsional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebuah genre tertentu digunakan untuk satu kegiatan, misalnya pantun untuk kegiatan seni yang berunsur hiburan dan ritual; (4) puisi tradisional berhubungan erat dengan magis dalam maksud dan pengertian yang luas; (5) Sebagai bahan yang berunsur magis dan ritual, puisi dianggap suci (sacred); (6) Puisi Melayu tradisional juga dapat dikatakan mengandung unsur-unsur musik. Hampir semua pengucapannya disampaikan dalam lagu, irama, atau intonasi yang tipikal; (7) Bahasanya padat, mengandung unsur-unsur perlambang, imaji, kias, dan perbandingan-perbandingan lain yang tepat dengan maksud dan fungsinya (Piah, 1989:5-7, Abror, 2009:80). Sebagai salah satu genre puisi lisan tradisional, menembang lawas dengan menggunakan bahasa Sumbawa merupakan salah satu alat ekspresi kelisanan, dan salah satu aspek budaya sehingga menjadi faktor utama yang tidak dapat 9 Yang dimaksud kata interpolasi menurut Dananjaya (1991;4) adalah penambahan atau pengisian unsur-unsur baru pada bahan folklor. Umpamanya pada waktu memperoleh cerita rakyat yang tidak lengkap, tidak jelas, atau terasa tidak sesuai dengan nilai budaya suku bangsa tertentu. maka biasanya ada kecenderungan bahwa secara tidak sadar terjadi proses tambahan atau penggantian dengan unsur-unsur cerita yang dikenal. 29 dipisahkan dalam seni ini. Dalam Seni tradisi lisan sakeco menggunakan bentuk verbal bahasa Sumbawa dan non verbal alat musik rebana dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat perasaan dan solidaritas kelompok. Teks lawas yang disampaikan menggunakan irama (temung) sebagai penguat ekspresi dalam pertunjukkan seni tradisi lisan sakeco. Oleh karena itu antara lawas, irama (temung) dan rebana merupakan satu kesatuan yang dimainkan oleh tau sakeco dalam satu pertunjukkan. Lawas dibangun berdasarkan formula dan struktur bahasa Sumbawa sehingga bahasa dalam lawas memiliki kekhasan tersendiri yang tidak terikat pada irama (temung), tetapi temung terikat oleh sakeco itu sendiri dalam artian lawas bisa dilagukan dengan menggunakan berbagai jenis irama (temung) sesuai dengan bentuk pertunjukannya. Sementara rebana merupakan suatu bentuk penyelaras yang digunakan tau sakeco (tukang lawas) dalam melantunkan lawas, dan pemberi isyarat bagi pemain pada saat ia melantunkan lawasnya. Misalnya pukulan rebana dijadikan patokan untuk memulai menyampaikan lawas, pindah temung (pilas temung) dan mengakhiri satu satu episode cerita. Dengan membaca teks di atas maka dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu; (1) bagian pembuka yang dimulai dengan pujian kepada Tuhan dan pemberian salam dan maaf kepada penonton, (2) bagian isi penyampaian lawas atau tuter (cerita) yang diambil dari fakta-fakta sosial, sejarah, dan cerita rakyat, dan (3) penutup diakhiri dengan humor (racik) yang di dalamnya bisa berisi teka teki (panan), pantun, dan lainlainnya. 30 2. Formula Kata formula mempunyai arti a set form of words in which something is defined, stated, or declared, or which is prescribed by authority or custom to be used on some ceremonial occasion (The Oxford English Dictionary (1933:466). Dalam Webster’s Third New International Dictionary kata formula diartikan sebagai a set form of words for use in a ceremony or ritual, atau a formal statement of religious doctrine or a written confession of faith (Babcock Gove, 1968:894). Dari beberapa makna diatas maka formula bisa berarti sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari bentuk teks (formula) yang dapat diartikan sebagai susunan/bentuk tetap (Depdikbud, 1989:244) atau penggunaan suatu kaidah, dalil atau prinsip yang diekspresikan dalam bentuk tertentu. Bila dikaitkan dengan tradisi lisan Dananjaya (1991:3) menjelaskan bahwa folklor lisan mempunyai bentuk berumus atau berpola, atau memiliki unsur formula yang kuat yang dapat dibuat sesuai dengan keperluan dalam tradisi lisan. Aspek kelisanan sakeco tentu mempunyai bentuk berumus atau berpola, atau memiliki unsur formula yang dapat dibuat sesuai dengan keperluan dalam tradisi lisan itu sendiri. Dalam hal ini paradigma yang digunakan untuk menganalisis formula tradisi lisan sakeco adalah teorinya Lord (1976) dalam The Singer of Tales berdasarkan hasil penelitiannya terhadap epos-epos Yugoslavia (Epik Homer) oleh para pencerita yang dilantunkan dengan lisan bersandar pada formula. Para pencerita dalam melantunkan ceritanya dengan menciptakan kembali secara spontan dan memakai unsur bahasa (kata, kata majemuk, frasa) 31 yang tersedia baginya (stock-in-trade) yang siap pakai sebagai bentuk variasi yang sesuai dengan tuntutan tata bahasa, matra dan irama puisi yang digunakan. Tradisi lisan memiliki keterkaitan dengan pelantunan dalam proses penciptaan karya, pencipta hanya mengingat kelompok kata dan formula sesuai dengan keinginannya secara kreatif. Menurut Lord (1981) Epik Homer memiliki ciri khas yaitu panjang (puluhan ribu baris), naratif, oral, bertema kepahlawanan, tradisional, menggunakan repetisi dan paralelisme, berpola sama, dan menggunakan stereotyped phrase. Karakteristik repetisi, paralelisme, dan stereotyped phrase muncul secara dominan pada baris-baris lantunan sehingga karya itu disebut formulaic epic (Yektiningtyas (2008:14). Menurut Lord (1976:30) formula adalah ”....a group of words which is regularly employed under the same metrical conditions to express a given essential idea”. Formula juga bisa disebut dengan ”...the study of the repeated phrases by textual analysis, by counting repetitions, classifying similar phrases and thus extracting the technique of composition by formula .....”. Formula itu muncul berkali-kali dan merupakan bentuk matra yang tetap berupa frasa, klausa, dan larik-larik yang secara teratur digunakan oleh seorang pencerita. Untuk menghasilkan pengulangan itu, ada dua cara yang ditempuh oleh pencerita, yakni: (1) mengingat pengulangan itu dan (2) menciptakan melalui analogi dengan pengulangan kata, frasa, klausa dan larik yang telah ada. Sedangkan menurut Sweeney (1980:68) bahwa formula adalah larik atau setengah larik yang digunakan lebih dari sekali dalam bentuk yang sama, sedangkan ekspresi formulaik adalah ungkapan yang dibentuk menurut pola irama yang ada serta 32 mengandung sekurang-kurangnya satu kata yang sama, baik dalam pengulangan maupun sinonim. Sedangkan ungkapan formulaik menurut Lord (1976:4) adalah ”...expression I denote a line or half line constructed on the pattern of the fornulas. By theme I refer to the repeated incidents and descriptive passages in the songs”. Dijelaskan bahwa formulaik sebagai larik atau setengah larik yang disusun sesuai dengan pola formula. Bentuk nyata dari formula adalah berupa ungkapan formulaik, baris baris yang diciptakan secara berurutan menggunakan pola formula sehingga menimbulkan aspek-aspek kepuitisan yang menjadi ciri dari tradisi lisan. Pencerita dalam menyusun cerita memakai formulaik sehingga ada proses pergantian, kombinasi, pembentukan model, dan penambahan katakata atau ungkapan baru pada pola formula, sesuai dengan kebutuhan pencerita. Dalam formula menurut Pudentia (2000:149) ada unsur kreatifitas penutur atau unsur kebaruan yang dibuat oleh penutur dalam mengulang apa yang diingatnya seperti penutur memberlakukan teks sebagai materi yang dihafalkanya sebelum berpentas. Pada tahap selanjutnya ia mampu melepaskan diri dari teks tersebut dan mulai mengingat dialog dengan menandai adegan-adegan, khususnya adegan cerita yang dimainkannya. Dengan demikian, pencerita dapat membangun larik terus menerus, sesuai dengan keinginan dan kreatifitasnya. Oleh karena itu ekspresi formulaik dapat juga membantu terbentuknya wacana ritmis yang merupakan salah satu alat bantu untuk mengingat kembali dengan mudah, cepat, dan tepat cerita yang disampaikan. 33 Cerita rakyat disusun dalam matra yang sangat ketat tuntutannya, yang mutlak dipatuhi oleh sang pencerita. Dalam proses penciptaan karya tradisi lisan pencerita belajar mengingat kelompok kata atau ungkapan-ungkapan yang lain, kemudian ia akan menggunakan formula itu sesuai dengan keinginan secara kreatif (Lord, 1976:37). Bahkan seorang pencerita dapat mempelajari dan mengingatkan dari pendahulunya dan dalam pengalaman waktu ia pun akan menghasilkan formulanya sendiri. Dalam artian ini seperangkat frasa dihasilkan berdasarkan pengalaman, frasa ini dapat menjadi formula setelah secara teratur dimunculkan dan beruralng kali digunakan. Semakin banyak pengalaman seseorang pencerita, baik pengalaman menyaksikan pertunjukan maupun pengalaman untuk mementaskan dendiri, semakin baik baginya untuk merekam formula dalam ingatannya dan menghasilkan formula sendiri (Pudentia (2000:149). Dengan formula sebagai dasar, pencerita dapat menyusun baris-baris dengan rapi dan cepat pada posisi tertentu. Dalam penyusunan baris dengan pola formula ini terjadi proses penggantian, kombinasi, pembentukan model, dan penambahan kata atau ungkapan baru pada pola formula sesuai dengan kebutuhan penceritaan. Pencerita menurut Finnengan (1979:59) dapat membuat baris-baris terus menerus, sesuai dengan keinginan dan kreativitasnya. Kaidah-kaidah ini tidak datang begitu saja kepada pencerita, ia menempu proses tertentu sampai dapat membawakan cerita dengan baik. Menurut Lord (1976) ada tiga tahapan proses penjadian seorang penyair lisan; (1) tahap mendengar dan menyerap berbagai unsur penyajian cerita, kelompok frase yang berulang yang disebut formula. (2) tahap 34 mencoba mengaplikasikan hasil serapan tadi. Ia mulai memantapkan elemen bentuk yang paling utama, rima dan melodi, dan (3) tahap mencoba mengisi katakata ke dalam pola dasar larik (rhythmic pattern) yang dilagukan dalam melodi yang bervariasi (Abdullah, 1988:964). Pencerita dalam menyampaikan puisinya tidak penuh-penuh terikat dengan formula. Teknik formula di kembangkan untuk melayaninya sebagai seniman. Ciri khas tradisi lisan tidak ada wujud formula yang baku mantap, keberadaan tradisi lisan penuh dengan variasi. Karena itulah tidak tertutup kemungkinan akan muncul versi-versi di dalam tradisi lisan. Pencerita dalam proses penciptaan selain mengingat pola formula ia juga memikirkan tema yang disusun dari adeganadegan yang telah ada dalam pikiran pencerita dan digunakan untuk menyusun cerita itu. Menurut Lord (1976:4) tema merupakan peristiwa atau adegan yang diulang dan bagian-bagian yang deskriptif dalam nyayian. Dalam fikiran pencerita tema akan mengalami perkembangan, karena sifat lentur formula yang dipakai dan juga disebabkan oleh pencerita tidak memakai formula yang sama pada setiap penceritaan. Tema bukanlah suatu yang statis, melainkan kreasi yang hidup dan berubah serta dapat disesuaikan dengan situasi. 3. Fungsi Pertunjukan Tradisi Lisan Kata fungsi berasal dari kata functie dalam bahasa Belanda, dan kata function dalam bahasa Inggris yang berarti: (1) one of a group of related action contributing to a larger action, (2) an organization unit performing a group of related acts and processes (Babcock Gove, 1968:920). A.R. RadcliffeBrown (1952:181) mendefinisikan kata fungsi adalah: 35 “….function is the contribution which a partial activity makes to the total activity of which it is a part. The function of a particular social usage is the contribution it makes to the total social life as the functioning of the total social system….” Dalam antropologi, fungsi mencakup pengertian yang luas sehingga dalam ilmu tersebut ada suatu aliran yang mengkhususkan diri pada masalah fungsi, melalui tokoh Malinowski (1939:938) berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat. Dengan kata lain, pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat, memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan yang bersangkutan. Malinowski mengemukakan bahwa fungsi dari satu unsur kebudayaan adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sekunder dari pada warga dari suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 1980:167). Dalam tulisannya yang berjudul A Scientific Theory of Culture and Other Essays mejelaskan: The system of conditions in the human organism, in the cultural setting, and in the relation of both to the natural setting and environment, which are sufficient for the survival of group and organism….Habits and their motivation, the learned responses and the foundations of organisation, must be so arranged as to allow the basic needs to be satisfied (Malinowski, 1944:40, Baal, 1970:51). Sedangkan konsep fungsionalisme A.R. Radcliffe-Brown dalam kajian sosial-budaya menggunakan organisma sebagai modelnya. Masyarakat itu seperti organisma atau kebudayaan itu seperti organisma yang diumpamakan seperti makhluk hidup terbangun dari berbagai macam unsur yang saling berhubungan 36 secara fungsional satu dengan yang lain. Hubungan fungsional antar gejala berarti adanya saling ketergantungan antar gejala tersebut. Konsep fungsi yang diartikan adalah rangkaian hubungan antara unit-unit melalui proses kehidupan yang terjadi. Menurut Radcliffe-Brown (1952: 181): “…The function of a particular social usage is the contribution it makes to the total social syatem. Such a view implies that a social system (the total social structure of a society together with the totality of social usages in which that structure appears and on which it depends for its continued existence) has a certain kind of unity , which we may speak of as a functional unity. We may define it as a condition in which all part of the social system work together with a sufficient degree of harmony or internal consistency, without producing persistent conflicts which can neither be resolved nor regulated. Radcliffe-Brown dalam bukunya yang berjudul The Andaman Islanders (1922) menyarankan untuk memakai istilah fungsi sosial untuk menyatakan efek dari suatu keyakinan, adat atau pranata, kepada integrasi sosial dalam masyarakat “...the social function of the ceremonial customs of the Andaman Islanders is to transmit from one generation to another the emotional dispositions on which the society (as it is constituted ) depends for its existence (Koentjaraningrat, 1987:176). Istilah ini pada dasarnya sama dengan pandangan Malinowski mengenai fungsi, yaitu pengaruh dan efek suatu upacara keagamaan atau suatu dongeng mitologi terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara berintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu (Koentjaraningrat, 1980:177). Timbulnya berbagai aspek perilaku sosial terdorong untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, teori fungsionalisme Radcliffe-Brown ini disebut teori fungsionalisme struktur. 37 Malinowski dipandang sebagai tokoh aliran fungsionalisme murni yang lebih menekankan pada aspek individu, sedangkan Brown dikenal sebagai tokoh fungsinalisme struktural yang lebih menekankan pada aspek sosial. Untuk itu dalam membahas fungsi pertunjukan seni tradisi lisan sakeco dalam adat di Sumbawa digunakan teori fungsionalisme Brown bahwa berbagai aspek perilaku sosial bukan semata-mata berkembang untuk memuaskan kebutuhan individu, tetapi justru timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Pendapat tersebut dapat diasumsikan, bahwa setiap aktivitas yang disumbangkan oleh individu atau unit-unit dalam masyarakat merupakan usaha untuk menjaga dan melestarikan struktur sosial. Pertunjukan sakeco dalam adat dipandang sebagai kegiatan kolektif yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan menjalinkan hubungan dengan sesamanya, sehingga kesatuan sosial dapat dipertahankan. Demikian juga konsep Malinowski (1936:132) yang berasumsi, bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi individu-individu apabila unsur kebudayaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesenian sebagai contoh dari salah satu unsur kebudayaan misalnya, terjadi karena mula-mula manusia ingin memuaskan kebutuhan naluri akan keindahan (Koentjaraningrat, 2007:171). Secara khusus dalam kaitan dengan tradisi lisan Bascom juga mengungkap fungsi folklor lisan dengan memperluas pandangan Malinowski. Inti dari penelitiannya antara lain folklor ritual memiliki fungsi untuk menenteramkan hati (ego-reassurance) (Dorson, 1972:20-21). Secara lebih rinci Bascom 38 menjelaskan bahwa fungsi tradisi lisan adalah: (1) cermin atau proyeksi anganangan pemiliknya; (2) alat pengesah pranata dan lembaga kebudayaan, (it plays in validating culture, in justifying its rituals and institution to those who perform and observe them); (3) alat pendidikan, (it plays in education, as pedagogical device); dan (4) alat penekan atau pemaksa berlakunya tata nilai masyarakat (maintaining conformity to the accepted patterns of behavior, as means of applying social pressure and exercising social control) (Dundes, 1965a: 279-298). Sedangkan Dananjaya (1991:3) menjelaskan bahwa tradisi lisan (folklore) mempunyai fungsi sebagai alat pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam. Dundes (1965:277) menjelaskan secara umum fungsi tradisi lisan adalah sebagai: (1) mempertebal perasaan solidaritas suatu kolektif (promoting a group ‘s feeling of solidarity); (2) membuat suatu kelompok merasa lebih superior daripada kelompok lain (providing socially sanctional ways for individual to act superior to other individuals); (3) sebagai wahana untuk memperotes ketidakadilan (serving a vehicle for social protest); (4) pelarian dari dunia nyata untuk mengubah pekerjaan yang menjemukan menjadi pekerjaan yang menyenangkan (an enjoyable escape from reality and converting dull work into play). Dalam kaitan dengan seni tradisi lisan sakeco merupakan salah satu bentuk pertunjukan rakyat, yang berarti lawas-lawas yang menjadi isi dari sajiannya tentu mengandung fungsi-fungsi dan nilai-nilai pendidikan. Dalam mengungkapkan seni sakeco sebagai fungsi sosial budaya tentu tidak menekankan pada penelitian 39 tekstual semata, namun secara kontektual perlu dilakukan untuk mencermati sakeco dalam kehidupan masyarakat. Marco de Marinis (1993:12) dalam bukunya The Semiotics of Performance menjelaskan bahwa teks dalam seni pertunjukan berbeda dengan teks dalam linguistic. Teks dalam linguistik mempunyai satu lapis (single layer) yaitu bahasa, maka teks seni pertunjukan mempunyai multilapis (multi layers) yaitu semua lapis dari seni pertunjukan misalnya dicontohkan sakeco terdiri dari orang sakeco (tau sakeco), gerak, rebana, rias, busana, tata panggung dan lain-lain. Analisis tekstual untuk mengungkapkan bentuk pertunjukan sakeco menyangkut bentuk visual yang berkaitan dengan ciri-ciri seperti gerak, rebana, rias, busana, panggung, hubungan atau jalinan antara elemen satu dengan yang lain dan system produksi. Adapun analisis kontekstual untuk mengungkapkan antara lain latar belakang diadakan pertunjukan sakeco, bagaimana pertunjukkan itu berlangsung dalam masyarakat pemiliknya. Dalam penerapannya diperlukan teori dan konsep disiplin antropologi, folklore yang relevan untuk menganalisa pertunjukan sakeco dalam adat di Sumbawa yang secara langsung dan tidak langsung ada kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakatnya, karena pertunjukan sakeco merupakan salah satu produk budaya masyarakat tentu saja mempunyai fungsi bagi kehidupan masyarakat. Soedarsono (2002: 122-123) mengatakan: Setiap zaman, setiap kelompok etnis, serta setiap lingkungan masyarakat, mempunyai berbagai bentuk seni pertunjukan yang memiliki fungsi primer dan sekunder yang berbeda. Pembagian fungsi primer menjadi tiga berdasarkan atas ‘siapa’ yang menjadi penikmat seni pertunjukan itu. Hal itu penting diperhatikan, karena seni pertunjukan disebut sebagai seni pertunjukan karena dipertunjukan bagi penikmat. Bila penikmatnya adalah keuatan-kekuatan yang 40 tak kasat mata seperti misalnya dewa atau roh nenek moyang, maka seni pertunjukan berfungsi sebagai sarana ritual. Apabila penikmatnya adalah pelakunya sendiri seperti tau sakeco (orang sakeco) seni pertunjukan berfungsi sebagai sarana hiburan pribadi. Jika penikmat seni pertunjukan itu adalah penonton yang kebanyakan harus membayar, seni pertunjukan itu berfungsi presentasi estetis. Dengan demikian secra garis besar seni pertunjukan memiliki tiga fungsi primer yaitu: (1) sebagai sarana ritual, (2) sebagai ungkapan pribadi yang pada umumnya berupa hiburan pribadi, dan (3) sebagai presentasi estetis. Disamping fungsi primer dimana seni pertunjukan disajikan untuk dinikmati, menurut R.M Soedarsono dalam Widyastutieningrum (2006:46) ada juga fungsi sekunder dimana penyajian seni dimanfaatkan tidak sekedar untuk dinikmati, tetapi juga untuk keperluan yang lain. Seni pertunjukan yang berfungsi sekunder cukup banyak jumlahnya: sebagai legitimasi status sosial seseorang yang menyelenggarakan, pengikat solidaritas kelompok masyarakat (integrasi sosial), terapi sosial bagi masyarakat, sebagai media komunikasi massa, sebagai media propaganda politik, sebagai propaganda program-program pemerintah, dan sebagainya. Pertunjukan sakeco dalam adat di daerah Sumbawa telah berlangsung sangat lama, dan masih dipertahankan sampai sekarang. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa tradisi tersebut telah diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain agar tetap lestari keberadaannya. Usaha ini tidak mungkin dilakukan selama tradisi tersebut tidak berfungsi bagi masyarakat pendukungnya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pertunjukan sakeco yang menyertai adat mempunyai fungsi bagi kehidupan sosial masyarakat pendukungnya. 41 G. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian etnografi yang mempelajari secara mendalam salah satu nilai-nilai budaya yang terjadi dalam masyarakat Sumbawa yaitu tradisi lisan sakeco. Esensi dari penelitian ini adalah memahami secara mendalam tentang ciri-ciri dan fungsi seni sakeco dalam masyarakat Sumbawa. Agar peneliti terhindar dari bias etnosentrisme dan dapat melukiskan dalam thick description maka perlu memperhatikan perspektif emik dan perspektif etik. Perspektif emik adalah deskripsi kebudayaan dari sudut pandang orang yang diteliti, sedangkan perspektif etik mendeskripsikan kebudayaan berdasarkan sudut pandang peneliti dengan konsep-konsep antropologis (Ahimsa-Putra:1995; Wiyata, 2002:23). Dengan demikian, melalui penelitian ini maka akan dapat dilihat secara mendalam nilai-nilai sosial budaya masyarakat Sumbawa. Untuk maksud kegiatan ini, peneliti telah berada di lapangan selama 12 bulan, yaitu sejak bulan Nopember 2012 hingga Oktober 2013. Selama masa itu penulis mengumpulkan data dengan cara menerapkan metode penelitian observasi partisipasi (participant obeservation) secara langsung, yang dilengkapi dengan metode wawancara mendalam. Peneliti memfokuskan pengamatan pada kegiatan tradisi Sumbawa yang menanggap sakeco. selama penelitian di lapangan peneliti membaginya menjadi dua agenda yaitu: (1) dilakukan mulai pada bulan Nopember 2012. Pada bulan ini waktu musim hujan (barat) sudah mulai masuk dan masyarakat sudah mulai persiapan untuk kembali ke sawah sebagai petani. Maka kegiatan adat pada bulan ini dan seterusnya dengan menanggap sakeco sudah mulai berkurang secara 42 drastis. Maka peneliti selama waktu itu kurang maksimal untuk mengobservasi secara langsung kegiatan adat dan pementasan sakeco karena sangat jarang pertunjukan sakeco di gelar. Yang bisa peneliti lakukan adalah wawancara secara mendalam dan sekaligus mengobservasi pola pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh pelaku sakeco sendiri. (2) dilakukan kembali pada bulan Juni-Nopember 2013. Pada saat itu sudah mulai masuk musim kemarau (balit) dan kegiatan masyarakat di sawah sudah sangat berkurang, dan warga masyarakat memfokuskan diri pada agenda perkawinan anaknya (nyukat), khitanan, dan kegiatan-kegiatan adat lainnya, yang selalu menanggap seni tradisi lisan sakeco sebagai hiburan primadona masyarakat setempat. Dalam agenda kegiatan kedua ini peneliti lebih fokus mengamati secara langsung tentang adat sebagai tempat pertunjukan sakeco, gotong royong masyarakat dalam menyiapkan arena pertunjukan dan saat pertunjukan sakeco itu sendiri di gelar. 1. Lokasi Penelitian Meskipun objek penelitian sakeco dapat ditemukan di seluruh wilayah kabupaten Sumbawa, karena alasan dan pertimbangan terutama masalah dana dan waktu, maka kegiatan di lapangan hanya difokuskan pada wilayah tengah kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk tinggal beberapa waktu di desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, selama kegiatan penelitian lapangan berlangsung. Pertimbangan memilih lokasi ini karena di canangkan sebagai desa yang masih memegang teguh tradisi Sumbawa, dan pelaku sakeco cukup banyak sehingga mudah diamati dan diwawancarai sewaktu-waktu. 43 Disamping hal itu ada juga faktor lokasi ini tepat berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Sumbawa, yang mudah untuk dilalui yang menghubungkan mulai dari ujung barat hingga ujung timur Sumbawa. Pertimbangan faktor lokasi ini memiliki arti dalam hal kegiatan operasional di lapangan. Peneliti hampir setiap minggu pergi ke desa lain untuk memburu informasi mengenai pertunjukan sakeco dalam tradisi yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Untuk kepentingan ini, biasanya peneliti harus tinggal beberapa hari di desa-desa tersebut, sehingga pelaksanaan penelitian lapangan menjadi lebih efisien. 2. Proses Pengumpulan Data Proses awal yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data ini adalah melakukan studi pustaka yang berorientasi pada data teoritis yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Data teoritis menurut Ahimsa-Putra (2007:8) adalah fakta-fakta yang berhubungan dengan asumsi-asumsi, model, dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Data teoritis ini biasanya tidak diperoleh dari lapangan, kecuali jika masalah penelitiannya adalah mengenai kerangka teoritis itu sendiri. Data teoritis peneliti peroleh dari berbagai buku, jurnal, makalah, yang berisi uraian-uraian teoritis mengenai masalah yang diteliti, atau yang berisi tentang paradigma-paradigma yang telah digunakan oleh para ahli dalam penelitian mengenai masalah yang sama. Oleh karena itu, data teoritis ini hanya dapat diperoleh lewat penelitian kepustakaan. 44 Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data di lapangan yang dilakukan secara intensif selama satu tahun, sejak bulan Nopember 2012 hingga Oktober tahun berikutnya. Itu sengaja dilakukan untuk melihat ragam aktivitas pelaku seni (tau sakeco) dan pertunjukan sakeco selama satu tahun. Di luar waktu satu tahun tersebut, yaitu tahun 2014-2015 peneliti juga melakukan kunjungan 4 kali ke lapangan, guna melengkapi informasi yang masih dipandang perlu untuk tambahan data. Keseluruhan proses kegiatan lapangan dilakukan sesuai dengan pendekatan yang menekan pada perspektif emik, menempatkan praktik sosial sebagai fokus kajian, dengan menggunakan pengamatan terlibat (participant observation) dan wawancara mendalam (indepth interview) sebagai tehnik pengumpulan data dan analisis data yang berlangsung secara simultan dalam proses penggalian data, dan mengembangkan teori dengan mengacu pada konsep dasar penelitian teori fungsi seni tradisi lisan. Sehubungan dengan itu, berikut ini dijelaskan situasi kegiatan lapangan, termasuk beberapa kendala yang dihadapi. Lokasi penelitian ini di Sumbawa, merupakan daerah asal peneliti, tetapi sudah 23 tahun peneliti meninggalkan daerah itu dan relatif jarang berkunjung kesana. Pada awal penelitian ini perlu belajar banyak untuk mengenal lebih dekat dengan pelaku sakeco. Banyak di antara mereka yang benar-benar tidak peneliti kenal, siapa namanya dan di antara mereka terdapat juga yang tidak begitu mengenal peneliti sendiri. Hal itu merupakan tantangan tersendiri, akhirnya peneliti memutuskan untuk melakukan pengamatan terlibat (participant observation), yaitu melakukan 45 kegiatan observasi dengan ikut melibatkan diri dalam berbagai aktivitas setempat. Selama kegiatan participant observation banyak memperoleh gambaran yang lebih luas tentang kehidupan dan keadaan masyarakat, dan akan terjadi hubungan yang akrab dengan masyarakat. Dalam pandangan Ahimsa-Putra (1998:6) dengan pengamatan terlibat akan dapat mengetahui dengan baik individu-individu di suatu lokasi penelitian, kehidupan pribadi mereka, pola prilaku mereka sehari-hari, sejarah kehidupan mereka, perasaan-perasaan mereka sebagai manusia, jaringan kekerabatan dan persahabatan yang mereka miliki, berbagai konflik dan kerjasama yang telah mereka alami, dan berbagai informasi lainnya, yang semuanya ini akan sangat membantu peneliti dalam memahami kehidupan dan kebudayaan masyarakat yang ditelitinya. Participant observation dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap: (1) mendeskripsikan situasi sosial budaya (broad descriptive situation) untuk mulai mengenali, dan merasakan situasi baru di lokasi penelitian sebelum melakukan kegiatan inti penelitian. Pengamatan sebenarnya hampir sama dengan orientasi medan (transek) agar bisa memperoleh gambaran tentang kondisi lokasi penelitian secara menyeluruh. Kegiatan ini diawali dengan berjalan kaki mengelilingi desa atau wilayah disekitar tempat tinggal selama berada di lapangan dengan memaksimalkan semua panca indera, sebab setiap hal yang ada di sekitar wilayah penelitian adalah data. (2) Mengarah kepada fokus pada pengamatan (focused observation) yang mengarah pada riset, yang berkaitan dengan tradisi lisan sakeco, dimana peneliti akan turut mengalami, merasakan, melihat tempat dan waktu cara mewariskan sakeco secara lisan pada saat latihan, 46 dan kegiatan pertunjukan sakeco dalam adat. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data-data yang menyangkut orang-orang yang terlibat didalamnya, dan melihat secara langsung pengaruhnya yang terjadi dalam masyarakat yang ada. Disamping itu pula pengamatan juga dilakukan secara langsung untuk melihat berbagai aspek kehidupan orang (tau) sakeco dan lingkungannya seperti kondisi tempat tinggalnya, kegiatan dan tindakan tineliti dalam membangun relasi-relasi sosial dalam aktivitas keseharian, serta berbagai peristiwa lainnya yang memiliki relevansi dengan kajian sakeco. Peneliti dalam hal ini akan melukiskan secara tepat seperti apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Sedapat mungkin peneliti melibatkan diri dalam proses pewarisan sakeco secara lisan, hal ini dilakukan peneliti agar dapat merasakan suasana secara mendetail. Mengapa selama proses pengamatan peneliti terlibat secara langsung ada beberapa alasan karena: (1) bisa melihat secara langsung situasi tertentu; (2) kalau hanya mendengar dari informan, informasi yang kita peroleh sudah banyak terdistorsi, dengan melihat langsung bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu; (3) bisa memperoleh pengalaman dengan warga; (4) bisa melihat peristiwaperistiwa melalui sudut pandang emik; (5) mempermudah komparasi dalam kognitif kita, dan (6) mempermudah saat mulai menulis etnografi (Pujiriani dkk, 2010:39). Hal itu peneliti lakukan agar semakin mengenal dan akrab dengan orangorang setempat, disamping untuk dapat mendengar kata-kata atau ungkapan mereka dalam situasi yang sewajar mungkin, juga supaya dapat menyaksikan aktivitas mereka secara lebih wajar, karena tak tampak sedang diamati. Untuk itu, peneliti ikut terlibat dalam kegiatan mereka seperti penyiapan arena pertunjukan, 47 dan persiapan ketika mereka menggelar latihan. Membaur di tengah mereka menonton yang cukup ramai, peneliti juga mendampingi rombongan seni sakeco dari desa Moyo ke Kabupaten Sumbawa tempat dimana mereka ikut kontestasi. Peneliti juga menghadiri acara/atau upacara adat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh ketua adat, dan biasa bergabung dengan orang-orang yang sedang mengikuti resepsi perkawinan (tokal basai) di teras-teras rumah atau di gardu-gardu tempat jaga malam. Pengamatan terlibat berjalan lancar dan cepat, karena ditunjang dengan penggunaan bahasa daerah dalam setiap percakapan dengan penduduk setempat. Dan yang lebih penting lagi, pada diri mereka tampak ada rasa gembira bercampur bangga karena peneliti mengunjungi aktivitas mereka sehingga sangat memperlancar proses kegiatan lapangan. Selama kegiatan lapangan berlangsung, peneliti dibantu oleh dua orang co-researcher, dan keduanya warga masyarakat setempat yaitu Hatta Jamal yang sudah berumur (60 tahun) menjadi seorang petani. Sedangkan yang satunya adalah Hasanuddin yang berumur (50 tahun) berprofesi sebagai pegawai Negeri Sipil dinas Pariwisata Sumbawa. Keduanya tergolong luas pergaulannya seharihari sehingga relatif kaya informasi tentang seluk beluk beserta kehidupan seharihari masyarakat Sumbawa. Mereka teman peneliti berdiskusi memperbincangkan hasil observasi maupun wawancara yang peneliti lakukan sehari-hari. Selain itu peneliti banyak belajar ungkapan dari Faisal (1998:88) dengan istilah tau sarua antap sarua loto (orang setakar kacang hijau setakar beras). Istilah itu dipakai untuk mengomentari seseorang yang dinilai banyak bohong dalam memberikan 48 informasi antara mana yang benar dan mana yang bohong. Hatta Jamal dan Hasanuddin memiliki andil besar ikut mencermati hasil observasi maupun wawancara yang peneliti lakukan selama kegiatan lapangan. Juga tak jarang mereka ikut mengarahkan kemana peneliti harus berburu informasi yang diperlukan. Mereka juga peneliti libatkan dalam proses klarifikasi dan dan penyaringan yang perlu didalami kasusnya untuk masing-masing kategori dari peristiwa sakeco. Sewaktu peneliti tidak berada di lapangan, terutama Hatta Jamal secara aktif menginformasikan sebuah peristiwa atau kejadian penting via Handphone ke peneliti, kemudian nanti dilaporkan secara mendetail ketika peneliti berada kembali di lapangan. Kemanapun peneliti pergi mencari data di lapangan selalu membawa alat perekam (sony recorder) dan sebuah note book berukuran kecil yang dapat peneliti masukkan saku baju atau celana, untuk merekam dan menulis catatancatatan penting yang relevan dengan tujuan penelitian selama kegiatan wawancara mendalam (Indepth interview). Dananjaya (1991:195) dalam hal ini menganjurkan untuk menggunakan wawancara yang terarah (directed) dan yang tidak terarah (non directed). Anjuran itu peneliti gunakan dengan menggunakan wawancara yang tidak terarah pada tahap pertama. Wawancara ini bersifat bebas, santai dan memberi informan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk memberikan keterangan yang ditanyakan. Wawancara ini penting pada tahap pertama penelitian karena dengan memberikan keterangan umum sering kali mereka juga memberikan keterangan-keterangan yang tidak terduga yang takkan dapat peneliti ketahui jika menanyakan dengan cara wawancara terarah. Pada 49 tahap kedua, setelah peneliti mendapatkan gambaran umum bentuk tradisi lisan yang hendak di teliti, peneliti baru menggunakan wawancara yang terarah. Pertanyaan yang akan diajukan sudah tersusun sebelumnya dalam bentuk suatu daftar tertulis. Jawaban yang diharapkan sudah dibatasi dengan yang relevan saja dan diusahakan agar informan tidak melantur kemana-mana. Penggunaan daftar pertanyaan untuk mengumpulkan tradisi lisan, karena hasilnya nanti akan dimasukan ke dalam naskah yang mempunyai format yang sama. Untuk pengujian kebenaran data hasil wawancara, peneliti akan mengecek kepada informan lain dengan daftar pertanyaan yang sama, dan melihat kenyataan berdasarkan pengamatan peneliti sendiri. Adapun syarat orang yang akan dijadikan informan dalam wawancara mendalam ini adalah (a) pelaku sakeco yang sudah pernah memenuhi undangan masyarakat untuk menembangkan tradisi lisan sakeco dalam acara adat ramai mesaq sebelum resepsi perkawinan di laksanakan, atau tradisi lainnya, (b) masyarakat asli Sumbawa yang paham tentang sakeco dan adat istiadat orang (tau) Sumbawa, (c) mengetahui bahasa Sumbawa yang lengkap, (d) mengetahui latar belakang budayanya, (e) mudah diajak bicara, (f) memahami informasi yang dibutuhkan, (g) dengan senang hati mau memberikan informasi, (h) artikulatif (tahu bagaimana cara menceritakan informasi), dan (i) mempunyai cukup waktu dalam memberikan keterangan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam penelitian ini. Ada hal yang menarik dalam kegiatan wawancara yaitu peneliti diketahui selama ini bertugas sebagai staf pengajar di IAIN Mataram, pada suatu waktu 50 peneliti dimintai sebagai pemberi nasehat perkawinan dalam acara resepsi perkawinan di desa Motong Kecamatan Utan misalnya, sebelum acara dimulai di depan halaman rumah terjadi wawancara santai dengan tokoh agama setempat yang bernama H.Sirajuddin Wake, dan didapatkan data sangat berharga berkenaan dengan pandangan hidup masyarakat Sumbawa. Ungkapan-ungkapan itu langsung peneliti catat pada buku kecil dan direkam dengan sony recorder yang sudah di-on-kan. Ketika peneliti sampaikan dalam ceramah nasehat perkawinan, para hadirin ada yang tertawa karena tak mengira ungkapanungkapan lokal masuk buku catatan seorang peneliti, dan bahkan ungkapanungkapan itu peneliti jadikan tema dalam acara tersebut, sambil mengaitkan dengan ungkapan-ungkapan lain yang telah peneliti peroleh selama di lapangan, dan reaksi mereka terlihat sangat antusias. Itu semua karena buku kecil dan sony recorder yang senantiasa dibawakan kemana pun peneliti pergi selama berada di lapangan. Catatan penting dari suatu observasi dan wawancara selanjutnya peneliti tuangkan ke dalam field note yang lebih lengkap, dan hal tersebut dilakukan sesegera mungkin, sewaktu masih segar dalam ingatan. Selain itu, juga membuat kategori, tempat menuliskan pokok-pokok informasi setiap peristiwa. Sewaktu kegiatan lapangan, peneliti juga memanfaatkan sejumlah data sekunder yang terdapat di kabupaten Sumbawa, yang tertuang dalam buku Sumbawa dalam angka 2012 terutama dimaksudkan untuk tujuan deskripsi, baik tentang keadaan umum tentang kabupaten Sumbawa. Ada pelajaran berharga bagi peneliti dalam melaksanakan kegiatan lapangan ini, yang patut dipaparkan di sini, yaitu berkenaan dengan tuntutan penggunaan perspektif emik, tanpa membawa 51 perspektif etik. Perlu juga disebut disini bahwa selama kegiatan lapangan belum melakukan penulisan disertasi. Yang dilakukan hanya sampai ke tingkat menghasilkan draf awal laporan hasil penelitian. Karenanya, peneliti pernah diundang sebagai salah satu pemateri seminar diselenggarakan oleh Pusat Bahasa NTB tanggal 15 Oktober 2014, yang pesertanya para pemerhati budaya se-NTB, akademisi perguruan tinggi se-NTB, dan tokoh-tokoh LSM di Mataram-Lombok. Dalam seminar itu peneliti memanfaatkan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian. Penyusunan draf laporan hasil penelitian tidak dilakukan di lokasi penelitian, ternyata mempunyai akibat buruk pada saat memulai menyusun disertasi. Di kota Yogyakarta tempat memiliki waktu luang yang banyak, apabila terasa ketidaklengkapan data peneliti melakukan kunjungan lagi ke lapangan sebanyak empat kali. Itu semua tidak akan menjadi kendala serius apabila jarak tempat penelitian relatif berdekatan dengan tempat studi peneliti. Tetapi dalam kasus penelitian ini, jarak Yogyakarta-Sumbawa relatif berjauhan, dan itu peneliti rasakan sebagai suatu permasalahan yang cukup serius dan menggunakan pembiayaan yang lumayan besar. H. Analisis Data Semua data hasil observasi dan wawancara sehari-hari dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan sehingga menjadi suatu catatan lapangan atau field notes. Selama dalam pelaksanaan wawancara, semua pembicaraan direkam menggunakan tape recorder. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data 52 ini adalah: (1) Langkah pertama ini adalah membaca secara seksama untuk dapat menghayati dan memahami seluruh sumber data, kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan, (2) Langkah kedua peneliti akan melakukan reduksi data (data reduction), ferivikasi dan displai data (data display). Reduksi data adalah proses penyeleksian data, pemfokusan, dan penyederhanaan data kasar. Ferivikasi merupakan memilih data yang sesuai dengan masalah dan menandai data, Display data merupakan proses dalam mengorganisasi informasi yang ditemukan, (3) Langkah ketiga peneliti merumuskan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian dari data yang sudah diklasifikasikan guna menemukan fungsi sakeco dalam masyarakat Samawa dengan menggunakan analisis: (a) Analisis konteks (sesuai dengan faktor yang diteliti) misalnya pendeskripsikan ini untuk melihat siapa saja yang menjadi partisipannya, topik, latar, saluran yang digunakan, bentuk pesannya, peristiwa yang terjadi, dan tujuan pada setiap sakeco yang ditembangkan. (b) Analisis kategori-kategori; artinya sakeco itu kemudian di klasifikasikan dalam kategori-kategori cara-cara, wilayah, sasaran (pelaku-pelaku), tujuan, dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pemakainya. Dengan sistem kategori-kategori tersebut akan terungkap pengklasifikasian wilayah sakeco, jenis-jenis isi sakeco, alat-alat rabana yang dipakai, musim orang Sumbawa mengundang sakeco, upacara adat. Dengan pengklasifikasian ini akan mengetahui nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh pemilik kebudayaan. (c) Analisis pertunjukan sakeco, maksudnya adalah dimana tempat terjadinya transmisi itu dan hubungan antara guru sakeco dengan kotap 53 (muridnya) dimana dalam hubungan itu tidak hanya dilandasi oleh rasa ikhlas untuk menurunkan dan menerima ilmu sakeco, tetapi ada bentuk-bentuk lain yang dilakukan oleh para murid terhadap gurunya sebagai ungkapan rasa syukur terhadap ilmu yang telah diberikan. (d) Analisis fungsi sakeco, maksudnya adalah melihat sesuatu hubungan antara sakeco dengan tujuan tertentu dalam kehidupan si pemilik budaya. Hal ini disesuaikan dengan fungsi yang disebut langsung oleh informan. Kemudian fungsi itu diklasifikasi sesuai sasaran isi dari sakeco. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang muncul apabila sakeco tersebut ditujukan kepada sasaran yang dimaksud. 54