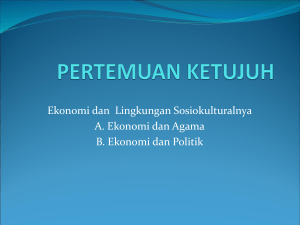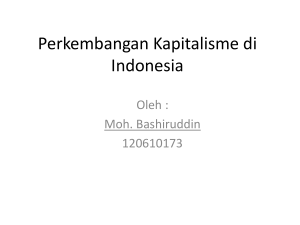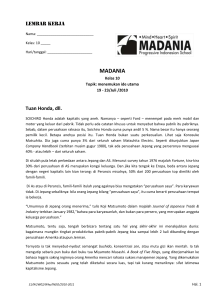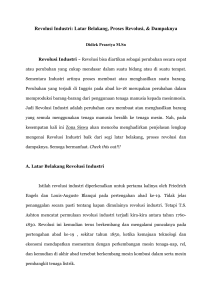Panggilan Tanah Air
advertisement

PANGGILAN TANAH AIR . PANGGILAN TANAH AIR Noer Fauzi Rachman, Ph.D Prakarsa Desa Panggilan Tanah Air Penulis : Noer Fauzi Rachman, Ph.D Penyelaras bahasa : Haslinda Qodariah Tata letak : Prasetyo Desain cover : Yayak Adya Yatmaka Gambar cover : Yayak Adya Yatmaka Prakarsa Desa (Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan, BP2DK) Gedung Permata Kuningan Lt 17 Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C Jakarta Selatan 12910 Jl. Tebet Utara III-H No. 17 Jakarta Selatan 10240 t/f. +6221 8378 9729 m. +62821 2188 5876 e. [email protected] w. www.prakarsadesa.id Cetakan Pertama, 2015 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Noer Fauzi Rachman (penulis) Panggilan Tanah Air Cet. 1—Jakarta: 144 hal., 14 X 20 cm ISBN: 978-602-0873-00-8 © Hak Cipta dilindungi undang-undang All Rights Reserved Pengantar Penerbit Bagaimana nasib desa di masa depan? Apakah setelah terbitnya UU Desa, yakni UU No. 6 tahun 2014, maka akan dengan sendirinya nasib desa berubah, dan akan dengan sendirinya gerak pembangunan menempatkan desa sebagai subyek? Apa dasar dari pandangan tersebut? Jika kita yakin akan kerja undangundang, maka yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah ada dasar dari keyakinan kita tersebut? Bagaimana kondisi desa saat ini? Bagaimana kondisi kampung-kampung dewasa ini? Apakah dalam keadaan ideal? Ataukah desa, kampung dan atau dengan nama lainnya, telah berada dalam suatu situasi yang membuatnya tidak mudah untuk mengubah arah nasibnya? Jika demikian, apa yang harus dilakukan? Naskah ini adalah hasil refleksi panjang Noer Fauzi Rachman, v panggilan tanah air Ph.D., seorang guru pendidikan rakyat, yang telah bekerja demikian lama dalam urusan keagrariaan, pedesaan dan pemberdayaan masyarakat secara luas. Noer Fauzi Rachman, hendak memperlihatkan suatu keadaan “gawat”, yakni keadaan yang dilukiskannya sebagai keadaan porak-poranda, ketika tanah air Indonesia porak-poranda. Tentu saja naskah ini bukan jenis naskah yang mengundang kita untuk bersedih meratapi keadaan. Sebaliknya, naskah ini dimaksudkan untuk mengundang keterlibatan, mengundang agar kita bersedia menjadi pandu tanah air, sebagaimana yang tertuang dalam lagu Indonesia Raya. Mengapa naskah ini terbit, di dalam rute pembangunan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA)? Sebagaimana disebut di atas, bahwa naskah ini dimaksudkan menjadi energi bagi suatu semangat baru. Dengan semangat tersebut, maka sangat diharapkan lahirnya suatu cara pandang baru, sedemikian rupa sehingga SIDEKA tidak diperlakukan hanya sebagai teknologi (aplikasi yang sempit), melainkan menjadi “teknologi pemberdayaan” yang baru, dan karenanya disebut sebagai cara baru menghadirkan negara. Untuk karena itu pula, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terbitnya naskah ini, yang kelak akan ditempatkan sebagai bahan pokok pembelajaran bagi para Pandu Desa yang akan menggerakkan pembangunan SIDEKA. Diucapkan terima kasih kepada Departement of Foreign Affairs and Trade-DFAT Australia, yang memungkinkan penerbitan naskah ini. Pun semua pihak, baik dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas, yang langsung maupun tidak, ikut memberikan vi pengantar penerbit kontribusi bagi terbitnya naskah ini, dan juga penyebarannya. Akhirnya, selamat membaca, merenungi nasib bangsa, dan menjawab panggilan kepanduan: menyelamatkan tanah air, dan membawanya kepada masa depan baru, yang lebih baik dan lebih bermakna, sebagaimana maksud dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jakarta, April 2015. vii . Pengantar Penulis Sebagai pembuka dari apa yang saya uraikan secara panjang lebar dalam buku ini, mari kita bayangkan apa yang masih sering dibicarakan banyak orang mengenai tanah air kita ini. Biarkan diri dan imajinasi kita bersafari pada keindahan kampungkampung halaman yang beragam, apakah itu di pulau-pulau kecil, di pantai-pantai, hutan-hutan, ladang-ladang pertanian, permukiman kaki gunung, di dalam hutan dataran tinggi, maupun sabana-sabana? Kemudian tariklah nafas dalam-dalam sembari memejamkan mata sambil membayangkan semua keindahan keanekaragaman bentang alam itu. Sungguh mempesona dan tiada taranya bukan? Selanjutnya bacalah nyanyian “Rayuan Pulau Kelapa” karya pujangga Ismail Marzuki (1914-1958) berikut ini: ix panggilan tanah air Tanah Airku Indonesia Negeri elok amat kucinta Tanah tumpah darahku yang mulia Yang kupuja sepanjang masa Tanah airku aman dan makmur Pulau kelapa yang amat subur Pulau melati pujaan bangsa Sejak dulu kala Melambai-lambai, nyiur di pantai Berbisik-bisik, raja klana Memuja pulau, nan indah permai Tanah airku, Indonesia Ternyata kita bisa juga membaca sambil menyanyikannya. Bagaimanakah rasa takjub dan imajinasi yang ditimbulkannya? Karya dari Ismail Marzuki yang senada adalah “Indonesia Tanah Air Beta” berikut ini. Indonesia tanah air beta Pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala Tetap dipuja-puja bangsa Di sana tempat lahir beta Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir menutup mata x pengantar penulis Satu lagi, mari kita pelajari lagu “Tanah Airku” karya pujangga lain Saridjah Niung Bintang Soedibio (1908-1993), yang lebih terkenal dengan panggilan Ibu Sud. Tanah airku tidak kulupakan Kan terkenang selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalbu Tanahku yang kucintai Engkau kuhargai Walaupun banyak negeri kujalani yang masyhur permai dikata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku m’rasa senang Tanahku tak kulupakan Engkau kubanggakan Betapa istimewanya bila kita bisa menyanyikan dengan perlahan dan penuh perasaan lagu itu. Lagu Ibu Sud di atas berusaha menggambarkan masyhur dan permainya Indonesia kepada orang yang telah atau sedang berkelana di negeri orang. Mereka yang telah jauh bertualang, menjelajah berbagai negeri dan menyeberangi berbagai lautan, akhirnya sadar bahwa tidak ada negeri yang lebih indah yang bisa ditemukan selain negerinya sendiri: Indonesia. Maka, sekali pun mungkin menetap selamanya di negeri orang, tidak akan hilang tanah air tersebut dari kalbunya, malahan membangga-banggakannya pada siapa pun yang ia temui. xi panggilan tanah air Generasi saya mempelajari lagu-lagu itu melalui mata pelajaran “Seni Suara” semasa kami berada di Sekolah Dasar (SD) di tahun 1970-an, dan melalui acara televisi. Saat itu kami baru mengenal televisi sebagai produk teknologi baru dan menjadi sumber media hiburan yang segera saja populer di kalangan anak-anak. Pada saat itu, menyanyi menjadi salah satu acara idaman kami di Televisi Republik Indonesia (TVRI) dengan pengarah acara A.T. Mahmud dan pengasuh acara Ibu Mul untuk “Lagu Pilihanku” dan Ibu Fat untuk “Ayo Menyanyi”. Kedua acara itu diiringi oleh Ibu Meinar yang memainkan piano. Acara lomba menyanyi pun semarak di Radio Republik Indonesia (RRI) maupun radio-radio swasta. Karena di sekolah, siaran TVRI, RRI maupun radio-radio swasta sering memperdengarkan berbagai nyanyian seperti itu, kami pun menjadi pandai menyanyikannya. Siapakah di antara para orang tua yang bisa ditanyakan situasi dan pengaruh dari pengajaran menyanyi dan siaran-siaran itu? Siapakah kini yang masih sering melantunkan lagu-lagu itu? Atau, di manakah kita masih dapat mendengarkan lagu-lagu itu sekarang? Seolah semuanya sudah hilang dan terlupakan begitu saja. Dimana kita bisa temukan tanda-tanda jejak bahwa kita pernah memiliki imaji bersama tentang apa itu tanah air, sebagaimana tergambar begitu mempesona dalam lagu-lagu di atas. Memulai dengan pembukaan tersebut, naskah buku ini hendak mengangkat tema tanah air sebagai kampung halaman rakyat. Bukan “tanah air” sebagai imaji ideal yang simbolik, umum dan abstrak, yang dijadikan rujukan dalam romantisme atas alam yang xii pengantar penulis indah melalui tamasya. Tanah air yang saya maksudkan di sini adalah tempat nyata dimana rakyat Indonesia benar-benar hidup dan mempertahankannya. Sudah lebih dari seperempat abad saya belajar dan menjadi saksi dari porak-porandanya tanah air melalui “perampasanperampasan tanah” yang nyata di kampung-kampung halaman rakyat di seantero Nusantara. Salah satu tonggak penting yang tidak bisa saya lupakan adalah Lokakarya Advokasi Kasus-Kasus Pertanahan, 8-11 November 1993, yang diselenggarakan secara bersama oleh Yayasan Sintesa - Kisaran, LBH Pos - Bandar Lampung, Lembaga Pengembangan Pendidikan Pedesaan (LPPP) - Bandung, Lembaga Kajian Hak-hak Masyarakat (LEKHAT) Yogyakarta, dan Yayasan Manikaya Kauci - Denpasar. Pertemuan itu dihadiri oleh lebih 100 aktivis agraria dari lebih tujuh puluh (70) kelompok/lembaga, dan menghasilkan sebanyak 27 naskah yang mengungkapkan pengalaman advokasi dan pengorganisasi rakyat di kasus-kasus pertanahan. Naskah-naskah ini kemudian dibukukan dalam Benny K. Harman dkk (1995), dan Noer Fauzi dan Boy Fidro (1998). Hingga kini saya masih terus mempelajari situasi porak-porandanya tanah air rakyat akibat perampasanperampasan tanah. Saat mengedit akhir naskah ini, saya baru saja selesai pulang dari Banda Aceh, setelah bersama pengacara dan paralegal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mempelajari karakteristik empat kasus konflik agraria yang tersebar di empat kabupaten sehubungan dengan perluasan wilayah konsesi perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kasus-kasus itu penting dipelajari dalam konteks provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berstatus wilayah “Otonomi xiii panggilan tanah air Khusus” sebagai hasil dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, 2005. Apakah semaraknya demokrasi politik yang terbuka, dan pengaturan pembagian kewenangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dapat menyelesaikan konflik-konflik agraria dengan mengakui klaim-klaim rakyat dan memulihkan situasi tanah air kampung halamannya yang porak poranda itu. Buku kecil ini hendak mengajak kita semua membuka mata melihat situasi sebagian dari tanah air, kampung halaman tempat hidup rakyat di desa-desa, di seantero Nusantara (nusa – antara, artinya gugusan pulau-pulau). Saya merasa tugas utama buku kecil ini adalah, pertama-tama, menunjukkan perlunya kita memperhatikan bagaimana reorganisasi ruang untuk meluaskan cara/sistem produksi kapitalis yang menghasilkan komoditaskomoditas global. Selanjutnya, naskah ini akan berhasil menjalankan tugasnya, bila pembaca dapat mengidamkan dan membayangkan suatu cara pengabdian untuk memperbaiki situasi tanah air kampung halaman rakyat. Saya menyampaikan terima kasih kepada Gunawan Wiradi, Roem Topatimasang, Mia Siscawati, Hendro Sangkoyo, Hilmar Farid, R. Yando Zakaria, Dadang Juliantara, Haslinda, Yuslam Fikri, Rachmi Diyah Larasati, Sandra Moniaga, Abdon Nababan, Usep Setiawan, Ahmad Nashih Luthf i, Eko Cahyono, Bosman Batubara, Iwan Nurdin, Dewi Kartika, Siti Maimunah, Siti Rachma Herwati, Samuel Pangerapan, Raharja Waluya Jati, Ignatius Kristanto, Yohanes Krisnawan, Isnaini, Paskah Irianto, xiv pengantar penulis Budi Supriatna, Sapei Rusin, dan banyak teman lain yang tertinggal di daftar dan tidak bisa saya masukkan dalam daftar itu, termasuk semua yang telah mengundang saya menyampaikan ceramah/kuliah dan mereka yang menyampaikan pertanyaan, komentar kritis, dan pujian untuk ceramahceramah saya di berbagai tempat dan kesempatan yang berbedabeda. Terima kasih khusus pada Hendro Sangkoyo yang mengijinkan penggunaan karyanya untuk dimuat di bab V, Parakitri T. Simbolon yang mengijinkan pemuatan ringkasan yang dibuatnya atas Tan Malaka, Hatta dan Sukarno untuk Lampiran 1a, 1b, dan 1c. Tidak lupa juga banyak terima kasih untuk Haslinda untuk memeriksa dan memperbaiki tata bahasa dan kalimat naskah buku ini. Istri saya tercinta, Budi Prawitasari, dan kedua putra kami, Tirta Wening dan Lintang Pradipta, berkorban tidak terkira untuk keleluasaan yang saya dapatkan selama ini, termasuk untuk menuliskan naskah ini. Saya tidak tahu cara menyampaikan terima kasih yang layak untuk pengorbanan yang mereka berikan. Pengabdian saya untuk rakyat dan tanah air Indonesia adalah pengabdian kalian juga. Terakhir rasa terima kasih kepada penerbit yang mengusahakan membuat buku ini sampai ke tangan pembaca sekalian. Selamat menikmati. Studio Tanah Air Kita, Bogor, 2015 xv . “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” (Al Quran, surah Ar-Ra’d ayat 11) Daftar Isi Pengantar Penerbit ~~ v Pengantar Penulis ~~ ix I. Pembuka ~~ 1 II. Situasi Umum Tanah Air Kita ~~ 5 III. Reorganisasi Ruang ~~ 15 IV. Merasani “Kutukan Kolonial” ~~ 25 V. VI. Masa Depan Tanah Air, Tanah Air Masa Depan ~~ 39 Penutup: Panggilan Ideologis untuk Pandu ~~ 57 Lampiran-lampiran 0 0 0 Tan Malaka (1925) Naar de “Republiek Indonesia” ~~ 65 Mohammad Hatta (1932) Ke Arah Indonesia Merdeka ~~ 76 Soekarno (1933) ”Mencapai Indonesia Merdeka” ~~ 88 xix panggilan tanah air 0 0 0 0 0 0 Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ~~ 103 Pidato Soekarno Memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ~~ 105 Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia ~~ 107 Lirik Lagu “Indonesia Raya” versi asal (1928) ~~ 110 Lirik Lagu Kebangsaan Indonesia Raya versi Resmi (1958, 2009) ~~ 112 Lirik Lagu Kebangsaan Indonesia Raya versi Resmi (dengan Ejaan Yang Disempurnakan) ~~ 114 Daftar Pustaka ~~ 117 xx -I- Pembuka Naskah ini dibuat dalam situasi di mana banyak orang Indonesia sudah terbiasa dan dibiasakan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui transaksi jual beli. Semua cenderung menganggap transaksi jual-beli itu normal dan alamiah. Lebih dari itu, untuk berhasil memenuhi kepentingan memperoleh pendapatan atau keuntungan, cara jual beli merupakan sesuatu yang sudah lazim ditempuh. Pasar pun dianggap penyedia kesempatan. Di Indonesia sekarang ini kita tidak memiliki rujukan yang otoritatif mengenai batas apa-apa yang boleh atau tidak boleh diperjualbelikan. Bukankah demikian? Berbeda dengan mereka yang menganggap pasar sebagai kesempatan, saya hendak menunjukkan sisi lain dari pasar sebagai mekanisme yang sering dianggap normal, alamiah dan sudah seharusnya demikian itu. Jarang orang memikirkan secara sungguh-sungguh bagaimana pasar pada mulanya dibentuk oleh perusahaan raksasa dan dengan cara bagaimana perusahaanperusahaan raksasa pada mulanya memperoleh modal untuk produksi barang-barang dagangan yang kemudian dipasarkan. 1 panggilan tanah air Naskah ini berangkat dari pengalaman-pengalaman saya, selama hampir tiga puluh tahun, menyaksikan bagaimana rakyat menghadapi operasi-operasi kekerasan, yang dijalankan oleh berbagai kekuatan, dalam rangka menciptakan modal bagi perusahaan-perusahaan raksasa. Terutama perusahaanperusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, kehutanan, dan perkebunan untuk membangun sistem produksi kapitalisme, yang menghasilkan barang dagangan untuk diperjualbelikan di pasar bagi sebesar-besar keuntungan perusahaan. Operasi kekerasan yang dimaksud di atas terutama mencakup pelepasan hubungan kepemilikan rakyat terhadap tanah, sumber daya alam dan wilayah, perubahan secara drastis tata guna dari tanah, sumber daya alam dan wilayah, serta perubahan posisi kelas dari rakyat dalam hubungannya dengan keberadaan sistem produksi baru yang berdiri dan bekerja atas tanah, sumber daya alam dan wilayah itu. Operasi kekerasan itu, selain menghasilkan modal bagi perusahaan-perusahaan untuk pertama kalinya, sesungguhnya di kalangan rakyat melahirkan ketegangan hingga pertengkaran sosial, dislokasi sosial hingga migrasi, bahkan perasaan tercerabut yang dapat melahirkan protes berkelanjutan. Namun sebagian besar rakyat mengalah dan kalah. Mereka menyingkir, atau meninggalkan kampung halamannya, dan tidak lagi bisa mengandalkan hidup dari tanah, sumber daya alam, dan wilayah yang telah dikapling perusahaanperusahaan itu. Ada sedikit saja rakyat yang berhasil mempertahankan diri atau menghalau perusahaan-perusahaan yang mengkapling tanah-tanah mereka itu. 2 pembuka Bagaimana sesungguhnya kita menyikapi semua ini? Pendek kata, naskah ini bermaksud menggugah bagaimana kita bersikap menghadapi porak-porandanya tanah air, kampung halaman rakyat akibat reorganisasi ruang untuk perluasan cara/sistem produksi kapitalisme yang menghasilkan komoditas-komoditas global. Lebih lanjut, saya berharap naskah ini dapat membuat kita mengidamkan, memikirkan, dan merintis usaha-usaha memulihkan rakyat dan alam yang porak-poranda itu. Terbuka kemungkinan rakyat memilih dan menjadikan kampung atau desa (apapun namanya) sebagai tempat berangkat dan sekaligus tujuan pengabdian. Kita berangkat dari apa yang pernah dikemukakan Muhammad Yamin dalam perdebatan pembuatan pasal 18-B UUD 1945, yakni: “... kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya.” 3 . - II - Situasi Umum Tanah Air Kita Masalah agraria dan pengelolaan sumber daya alam bangsa Indonesia secara umum pernah dirumuskan secara sederhana oleh elite pemerintahan nasional di zaman Reformasi melalui Ketetapan MPR RI No. IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sebagai berikut: (i) ketimpangan (terkonsentrasinya) penguasaan tanah dan sumber daya alam di tangan segelintir perusahaan, (ii) konflikkonflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang meletus di sana-sini dan tidak ada penyelesaiannya, dan (iii) kerusakan ekologis yang parah dan membuat layanan alam tidak lagi dapat dinikmati rakyat.1 Tiga golongan masalah ini sayangnya diabaikan oleh banyak pejabat publik dan sama sekali tidak diurus secara serius oleh presiden-presiden, menteri-menteri dan para pejabat yang berhubungan dengan masalah agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta para pejabat pemerintahan daerah. Rakyat Indonesia di desa-desa selayaknya menyambut abad XXI dengan penuh kegembiraan dan optimisme, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Banyak kelompok rakyat miskin 5 panggilan tanah air di banyak desa, di pinggir kota, di dataran tinggi, di pedalaman maupun di pesisir dari pulau-pulau, dilanda rasa risau dan kuatir. Rakyat pedesaan menanggung beban berat secara kolektif sehubungan dengan akses pada tanah pertanian, hutan, dan lingkungan hidupnya semakin hari menyempit, produktivitasnya semakin hari merosot, lingkungan ekosistemnya semakin hari semakin tidak mendukung kehidupan, dan secara relatif kesejahteraannya menurun. Konsentrasi penguasaan tanah, nilai tukar pertanian yang rendah, konversi tanah-tanah pertanian ke non-pertanian, perkembangan teknologi produksi, dan pertumbuhan penduduk miskin, telah membuat akibat yang nyata pada jumlah rumah tangga petani dan luas total pertanian rakyat. Data sensus pertanian 2013 menunjukkan rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 26,13 juta, yang berarti telah terjadi penurunan sebesar 5 juta rumah tangga pertanian, dibandingkan dengan hasil sensus pertanian 2003. Secara retorik, setiap satu menit satu rumah tangga petani hilang, berganti pekerjaan dari pertanian. Bila kita lihat lebih jauh, seperti ditunjukkan oleh Khudori (2014) laju konversi lahan pertanian rakyat mencapai angka 110.000 ha/tahun (pada rentang 19922002), dan bahkan melonjak 145.000 ha/tahun pada periode 2002-2006, serta 200.000 ha/per tahun pada periode 2007-2010. Bila ambil saja rata-rata konversi 129.000 ha/tahun, maka secara retorik setiap menit, sekitar 0,25 hektar tanah pertanian rakyat berubah menjadi lahan non-pertanian. 6 situasi umum tanah air kita Arus pengurangan jumlah petani dimulai sejak pertengahan abad 20 yang lalu, dan diperhebat dalam dekade yang lalu di Indonesia. Secara umum, kesempatan kerja di sektor pertanian semakin sempit dari tahun ke tahun, dibanding dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan. Minat bekerja pada bidang pertanian juga semakin menipis. Banyak sekali lapisan orang miskin di pedesaan, yang mayoritas tidak bertanah dan tidak bisa menikmati sekolah tinggi, harus mengambil risiko dengan memilih pergi ke luar desa untuk mendapatkan pekerjaan melalui kerja migran, di kota-kota provinsi, metropolitan hingga ke luar negeri. Sebagian besar rakyat pekerja migran ini sesungguhnya berhasil memperoleh upah kerja yang lebih baik, mengirimkan pendapatannya ke desa, dan kemudian menjadi daya tarik bagi pemuda-pemudi desa generasi berikutnya untuk mengikuti mereka. Di sana sini, pengalaman pahit hidup kerja sebagai migran, mulai kondisi kerja yang tidak layak, penipuan, diskriminasi hingga kekerasan, umumnya dipersepsi sebagai nasib buruk, yang tidak mampu mencegah rombongan lain untuk pergi. Dunia pertanian dan hidup di desa bukanlah masa depan yang menjanjikan bagi pemuda-pemudi, padahal masa depan pertanian rakyat bergantung pada siapa yang akan bertani (White 2011, 2012). Kaum paling miskin bekerja menjadi kelas terendah dalam sektor informal dan hidup di komunitaskomunitas pondok dalam wilayah-wilayah kumuh dan marjinal di kota-kota (Jellinek 1977). Mereka mudah sekali berpindahpindah menjadi sesuatu yang diistilahkan oleh Jan Breman sebagai footloose labor (Breman 1977). 7 panggilan tanah air Semakin tinggi pendidikan orang desa, semakin kuat pula motivasi dan dorongan untuk mereka meninggalkan desanya. Desa ditinggalkan pemuda-pemudi yang pandai, termasuk untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Mereka inilah yang semakin memenuhi kota-kota kabupaten, provinsi dan metropolitan. Mereka yang berhasil menjadi kelas menengah di kotakota tidak kembali ke desa, menjadi konsumtif, dengan membeli/ menyewa tanah dan rumah untuk tinggal di pinggiran kota, serta motor dan mobil baru untuk transportasi, yang pada gilirannya membuat infrastuktur jalan di kota-kota provinsi dan metropolitan tidak lagi memadai. Di kota-kota metropolitan, terjadi macet di mana-mana setiap pagi pada jam pergi menuju pusat kota dan jam pulang menuju pinggiran kota. Sejarawan terkenal, Eric Hobsbawm dalam karyanya yang terkenal, Age of Extremes, membuat deklarasi bahwa “the most dramatic change in the second half of this century, and the one which cuts us forever from the world of the past, is the death of the peasantry”. Artinya, “perubahan paling dramatis dalam paruh kedua abad (kedua puluh) ini, yang untuk selamanya memisahkan kita dari dunia masa lampau, adalah kematian petani” (Hobsbawm, 1994:288-9). Istilah untuk berkurangnya jumlah orang desa yang bekerja sebagai petani, yang dibuat oleh para sarjana peneliti masalah agraria , adalah depeasantization (Araghi 1995, McMichael 2014). Ini untuk menunjukkan bagaimana berbagai kekuatan ekonomi politik bekerja pada tingkat global sehingga menghasilkan kecenderungan pengurangan jumlah kelas petani di pedesaan, dan semakin kecilnya pengaruh pedesaan pada kehidupan rakyatnya. Lebih 8 situasi umum tanah air kita lanjut, ahli agraria lain membuat istilah deagrarianization (Bryceson 1996) untuk menunjukkan semakin kecilnya andil kerja-kerja dari dunia agraris bagi ekonomi rakyat, perubahan orientasi hidup, identifikasi sosial, dan perubahan lokasi hidup. Tidak dipungkiri bahwa semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan suatu cara hidup baru dengan gaya perkotaan modern (urban modernity), yang banyak dianggap sebagai keniscayaan yang harus ditempuh. Henri Lefebrve (1970/2003) menyebutnya sebagai urban revolution, bahwa masyarakat global sekarang ini sedang mengalami proses urbanisasi dan masyarakat perkotaan sekarang ini terbentuk sebagai hasil proses urbanisasi. Ia memaksudkan bahwa ini bukan sekadar perubahan lokasi hidup di kota-kota, melainkan seluruh cara hidup, berpikir dan bertindak yang berbeda secara total. Kampung halaman rakyat di desa-desa porak-poranda untuk melayani cara hidup masyarakat perkotaan, termasuk kaum elite kaya yang hidup di kota-kota yang berjaringan satu sama lain, termasuk dengan dihubungkan oleh lapangan terbang, mobil dan jaringan jalan highway, hotel, pusat perbelanjaan dan perumahan gated-communities, hingga kantor-kantor perusahaan maupun pemerintahan di pusat kota metropolitan. Elite perkotaan kita ini hidup di metropolitan cities seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar, Medan, hingga Singapura, dan bersama-sama dengan elite perkotaan di negara-negara pasca kolonial lain dalam jaringan dengan kota-kota New York, London, dan Tokyo, dan sebagainya (Sassen 2001, 2005, Roy and Ong 2011). 9 panggilan tanah air Saya bukan akan membahas sisi modernisasi yang mentereng itu. Sisi lain dari cara perluasan sistem-sistem produksi komoditas globallah yang akan kita bahas, khususnya cara perluasan melalui konsesi-konsesi proyek pertambangan, kehutanan, perkebunan, infrastruktur, dll. Produktivitas rakyat yang hidup di lokasi-lokasi sasaran perluasan itu sesungguhnya diabaikan dan sama sekali tidak diperhitungkan, apalagi dihargai. Cerita dan berita mengenai penghancuran kehidupan yang sebelumnya melekat pada tempat sistem-sistem produksi baru itu tidak dimasukkan dan dimuat dalam naskah-naskah resmi di kantor-kantor pemerintah. Sebaliknya, pemerintah menyampaikan keharusan-keharusan bagaimana kebijakan dan fasilitas pemerintah diarahkan untuk mempermudah para perusahaan raksasa (biasa disebut: investor!) bekerja untuk memperbesar kapasitas produksi komoditas-komoditas global, mensirkulasikannya, dan menjualbelikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan dan penumpukan kekayaan. Ketika naskah ini ditulis, saya membaca berita di Koran Kompas edisi 18 April 2015 “Konflik Lahan Adat Meningkat”. Suryati, Sekretaris Pelaksana Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang menjadi narasumber berita itu melaporkan bahwa sejak tahun 2003 hingga 16 April 2015, terdapat setidaknya konflik lahan antara 18 komunitas adat dengan PT Toba Pulp and Paper yang beroperasi di kawasan Toba. “Setidaknya konflik itu melibatkan 3.777 keluarga atau 17.722 jiwa di lahan seluas 26.560,398 hektar di Kabupaten Humbalang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Toba Samosir, 10 situasi umum tanah air kita Dairi, dan Simalungun.” (Kompas “Konflik Lahan Adat Meningkat” 18 April 2015). Perlu diketahui bahwa PT TPL memperoleh lisensi izin pemanfaatan lahan untuk Hutan Tanaman Industri melalui SK Menhut nomor 58/2011 untuk lahan seluas 188.000 hektar. Izin ini merupakan pembaruan atas SK Menhut 493/1992 hektar untuk lahan seluas kurang lebih 269.000 hektar atas nama PT Inti Indorayon Utama (IIU). Kasus konflik lahan di wilayah ini bukan hanya 18 kasus itu. Ke-18 kasus itu adalah mereka yang bertahan hingga saat ini. Banyak komunitas yang sudah kalah dan mengalah terhadap PT TPL atau PT IIU.2 Konflik-konflik lahan di wilayah ini sudah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, semenjak PT IIU bekerja di sana mendapatkan lisensi pembalakan kayu (Hak Pengusahaan Hutan/HPH) dari Menteri Kehutanan seluas 100.000 hektar pada tanggal 23 Oktober 1984 dengan jangka waktu pengusahaan 20 tahun. Baru-baru ini di akhir tahun 2003, saya memiliki satu kesempatan istimewa mengunjungi salah satu dari konflik-konflik lahan itu, yakni yang terjadi di kampung Naga Hulambu, kabupaten Simalungun. Saya bertemu dan mendengar cerita bagaimana seorang ibu (inang) memimpin rakyatnya mempertahankan tanah air mereka dengan cara mengusir kontraktor-kontraktor PT TPL yang telah, sedang, dan akan menghabisi kebun-kebun mereka yang dipenuhi oleh pohon kayu, buah-buahan maupun sayur-sayuran. Secuplik cerita satu kasus konflik agraria ini dimaksudkan untuk 11 panggilan tanah air menunjukkan masalah tanah air rakyat yang kronis. Lebih dari itu, sinyalemen mengenai sebaran konflik agraria di seantero Nusantara sudah menujukkan luasannya di seantero Nusantara (Konsorsium Pembaruan Agraria 2014).3 Di sini saya tidak akan memperpanjang cerita-cerita kasus semacam itu. Di naskah ini, saya akan mengarahkan penjelasan mengenai sebab utama dari porak-porandanya rakyat dan tanah airnya, yang berlangsung secara sistemik, sebagai akibat dari reorganisasi ruang untuk perluasan cara/sistem produksi kapitalisme untuk menghasilkan komoditas-komoditas global. Catatan Akhir 1 Satu mandat utama dari TAP MPR ini adalah penyelesaian pertentangan, tumpang tindih dan tidak sinkronnya berbagai perundang-undangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang berlaku. Ironisnya tidak ada satupun Presiden Republik Indonesia yang menjalankan arah kebijakan dan mandat yang termuat di dalam Ketetapan MPR itu. Semenjak dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 melalui UU Nomor 24/2003 sudah cukup banyak undangundang agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang telah diuji konstitusionalitasnya, dan sebagian telah dibatalkan karena tidak sesuai dengan UUD 1945 yang berlaku. Yang terbanyak diuji adalah Undangundang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Yang baru saja dibatalkan adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Air sebagai sumber daya yang vital tidak boleh diswastakan, dan harus dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2 Pertama kalinya saya membaca satu kasus dari wilayah ini melalui buku Ibrahim Gidrach Zakir (1980) Dari Jenggawah ke Siria-ria: Sebuah Peneguhan Sikap di Hadapan Pengadilan Mahasiswa, yang diterbitkan 12 situasi umum tanah air kita di Bandung oleh Badan kerjasama Pembelaan Mahasiswa Indonesia. Buku ini adalah Pledoi Ibrahim Gidrach Zakir, salah seorang mahasiswa yang dipenjarakan oleh rezim militer Orde Baru karena tuntutan mereka agar Soeharto mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kasus ini telah menjadi perhatian para pekerja hak asasi manusia sejak akhir ahun 1989. Saya membacanya di YLBHI (1990), Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1989. Naskah akademik terbaik mengenai perjuangan agraria di sana, termasuk yang digerakkan oleh ibu-ibu Sugapa, adalah Simbolon, Indira Juditka 1998 Peasant Women and Access to Land; Customary Law, State Law and Gender Based Ideology; The Case of the Toba - Batak (North Sumatra). PhD thesis in Wageningen University. 3 Salah satunya dibuat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang melaporkan bahwa sepanjang tahun 2014 sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan konflik mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK). Data KPA memperlihatkan konflik agraria tertinggi pada tahun ini terjadi pada proyek-proyek infrastruktur, yaitu sebanyak 215 konflik agraria (45,55%) di sektor ini. Selanjutnya ekspansi perluasan perkebunan skala besar menempati posisi kedua yaitu 185 konflik agraria (39,19%), dilanjutkan oleh sektor kehutanan 27 (5,72%), pertanian 20 (4,24%), pertambangan 14 (2,97%), perairan dan kelautan 4 (0,85%), lain-lain 7 konflik (1,48%). Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 103 atau meningkat 27,9% dari tahun 2013. Secara kumulatif selama 10 tahun masa pemerintahan SBY (2004-2014) setidaknya telah terjadi 1.520 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan luasan areal konflik seluas 6.541.951,00 hektar dan melibatkan lebih dari 977.103 kepala keluarga (KK), yang harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Dapatlah dikatakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini rata-rata hampir dua hari sekali terjadi konflik agraria (KPA, 2014). 13 . - III - Reorganisasi Ruang Secara gamblang saya mengajak pembaca melihat sebagian situasi rakyat dan tanah airnya yang porak-poranda itu sebagai bagian akibat dari reorganisasi ruang yang digerakkan oleh kekuatan-kekuatan yang memperluas sistem-sistem produksi kapitalis. Sebagai suatu sistem produksi yang mendasarkan pada pemisahan antara pemilik dan pekerja, serta manajer pengelola produksi, dan yang senantiasa berorientasi untuk pelipatgandaan keuntungan si pemilik, mesin-mesin industrinya harus terus bergerak memproduksi tak henti-henti untuk menghasilkan komoditi atau barang dagangan secara standar dan massal. Barang dagangan atau komoditi itu kemudian disirkulasikan sedemikian rupa sehingga bisa sampai pada konsumen. Seperti diuraikan secara padat oleh Schumpeter (1944/1976:8283), sebagai suatu sistem ekonomi yang khusus, kapitalisme tidak pernah statis tapi sangat dinamis. Perubahan yang dihasilkan oleh kapitalisme bukan hanya dikarenakan fakta bahwa kehidupan ekonomi berlangsung dalam suatu lingkungan sosial 15 panggilan tanah air dan alam yang berubah. Memang penting juga melihat pengaruh kekuatan politik dan segala pergolakan yang timbul dari padanya pada perubahan industrial, akan tetapi semua itu bukanlah penggerak utamanya. Tidak pula hanya karena pengaruh yang begitu rupa dari ilmu dan jumlah modal yang diinvestasikan, atau oleh pengaruh khusus dari sistem-sistem moneter, yang semuanya memang benar berpengaruh. Dorongan pokok yang membentuk dan menggerakkan mesin kapitalis sesungguhnya berasal dari kemampuannya membuat rakyat mengkonsumsi barang-barang yang baru, yang dimungkinkan melalui cara-cara produksi baru, transportasi baru, pasar-pasar baru, dan manajemen organisasi industrial baru. Barang-barang dagangan selalu harus dibeli dan rakyat kita dipacu untuk terus menjadi konsumen belaka. Mekanismemekanisme baru untuk memperbesar konsumsi terus-menerus diperbarui: yang lama diganti dan yang baru diciptakan. Kapitalisme akan mati bila tidak ada yang membeli barang dagangan (komoditi) yang mereka hasilkan. Dari hari ke hari, sistem produksi kapitalis terus-menerus menghasilkan barangbarang baru, termasuk untuk menggantikan barang-barang dagangan yang dihasilkan oleh sistem produksi non-kapitalis. Saat ini, kita lihat kenyataan bahwa selera rakyat dibentuk melalui iklan dan gaya hidup konsumtif yang mampu membangkitkan gairah mengidamkan dan membeli barang-barang baru. Upaya pembiasaan membeli pun digencarkan melalui iklan-iklan TV, radio, billboard hingga penjualan di mall-mall, supermarket di kota-kota hingga minimarket dan toko-toko di kelurahan/desadesa, serta situs-situs maya yang menawarkan secara online. 16 reorganisasi ruang Demikianlah, ekspansi sistem produksi kapitalis memerlukan reorganisasi ruang (spatial reorganization) yang khusus agar cara/sistem produksi kapitalisme bisa meluas secara geografis (geographic expansion). Istilah yang dimaksudkan di sini lebih luas maknanya dari istilah yang disebut oleh pemerintah sebagai “penataan ruang”. Secara umum, yang dimaksudkan dengan istilah ruang dalam “reorganisasi ruang” di sini mencakup: (a) ruang imajinasi dan penggambaran, termasuk perancangan teknokratik yang diistilahkan master plan, grand design, dan sebagainya; (b) ruang material, tempat kita hidup; dan (c) praktikpraktik keruangan dari berbagai pihak dalam membuat ruang, memanfaatkan ruang, memodifikasi ruang, dan melenyapkan ruang, dalam rangka berbagai upaya memenuhi keperluan, termasuk mereka yang berada dalam posisi sebagai bagian negara, atau korporasi, atau rakyat.1 Reorganisasi ruang dilakukan terus-menerus oleh kekuatan yang bermaksud melipatgandakan keuntungan perusahaanperusahaan kapitalis. Keuntungan itu pada dasarnya diperoleh dari privatisasi tanah dan sumber daya alam, pemisahan antara penghasil dan pemilik barang yang dihasilkan, dan eksploitasi tenaga kerja untuk menghasilkan barang dagangan yang bernilai tambah. Komoditas atau barang dagangan yang dihasilkan oleh sistem produksi kapitalis itu ditransportasikan sedemikian rupa mulai dari tempat ia diproduksi hingga diperdagangkan dan dikonsumsi rakyat, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun melayani kebiasaan berbelanja (budaya konsumtif). Saat ini, tidak bisa tidak, kita harus membicarakan kapitalisme, 17 panggilan tanah air dan memahami cara bekerjanya. Sebab, kapitalisme telah menjadi suatu sistem produksi yang menguasai Indonesia dan dunia sekarang ini. Fernand Braudel, sejarawan Perancis dan pemimpin dari Aliran Annales (Annales School) dalam ilmu sejarah, menulis kalimat yang dikutipkan di atas itu dalam salah satu karya klasiknya Civilization and Capitalism 15th – 18th Century Volume II: the Wheels of Commerce: “manakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela.” Ia melanjutkan, “Suka atau tidak, … terdapat suatu bentuk kegiatan ekonomi yang tak bisa dihindari memanggil ingatan kita pada kata ini dan tidak bisa tidak” (Braudel 1979:231). Manusia-manusia yang sepenuhnya menikmati menjadi bagian dari sirkuit produksi-konsumsi komoditas itu terus menyebarluaskan kehebatan dari sistem produksi ini, dan meyakini bahwa kita tidak bisa mengelak kecuali menjadi bagian dari pada kapitalisme. Kita sepenuhnya bisa memahami mereka yang bekerja mengabdikan dirinya secara profesional dengan andalan keahliannya, memperoleh upah, penghargaan, dan jaminan karir yang diatur secara manajemen. Umumnya yang tidak mereka ceritakan adalah cara bagaimana sistem-sistem produksi kapitalis ini wilayah kerjanya semakin meluas melalui operasi-operasi kekerasan, terutama merampas tanah kepunyaan rakyat, dan membatasi bahkan membuat rakyat tidak bisa lagi memanfaatkan tanah dan sumber daya alamnya, mengubah secara drastis dan dramatis tata guna tanah . yang ada, dan menciptakan kelompok-kelompok pekerja yang terpaksa maupun siap sedia untuk didisiplinkan menjadi 18 reorganisasi ruang penggerak sistem produksi kapitalis itu. Saya mengajak kita melihat bagaimana nasib sebagian besar rakyat Indonesia yang melanjutkan hidup di desa-desa dengan cara menguasai dan memanfaatkan tanah dan wilayahnya melalui sistem pertanian keluarga, perladangan suku, wana-tani, penggembalaan suku, kebun-hutan bersama, hingga pengelolaan pesisir dan laut. Ekspansi sistem-sistem produksi kapitalis akan memaksa kehidupan mereka berubah. Keadaan kampung, ladang, sawah, hutan, sungai, dan pantai mereka telah, sedang dan akan terus diubah oleh industri pengerukan (batu bara, timah, nikel, pasir besi, bauksit, emas, semen, marmer, dsb), industri pulp and paper, industri perkebunan kelapa sawit, industri perumahan dan turisme, industri manufaktur, dan lain sebagainya. Semua sistem produksi baru ini perlu dipahami sebagai bagian dalam jaringan produksi internasional/global yang ekspansif. Perusahaan-perusahaan raksasa di bidang industri pertambangan, kehutanan, pekebunan, manufaktur, perumahan dan turisme, infrastruktur, dan lainnya, bekerja berdasarkan lisensi atau surat izin yang diperoleh dari pejabat publik yang berwenang, seperti Menteri Pertambangan yang membuat Kontrak Karya Pertambangan, Menteri Kehutanan yang mengeluarkan izin HPH/HPHTI, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengeluarkan Surat Keputusan HGU, dan lainnya. Lisensi-lisensi itu menjadi alas hukum untuk menyingkirkan dan meminggirkan rakyat agraris (petani, nelayan, masyarakat adat yang mengumpulkan hasil hutan/laut, dsb-nya) 19 panggilan tanah air dari tanah dan wilayah hidupnya, baik oleh perusahaanperusahaan pemegang lisensi itu, maupun aparatur keamanan/ polisi yang bekerja untuk perusahan-perusahaan pemegang lisensi itu. Konsesi-konsesi berupa taman-aman nasional dan kawasan konservasi lainnya, yang dihasilkan oleh keputusankeputusan Menteri Kehutanan, juga menjadi dasar penyingkiran rakyat atas nama biodiversity hotspot,di mana spesies-spesies flora fauna yang langka dan ekosistemnya perlu dikonservasi. Saat ini yang sedang menjadi andalan pemerintah adalah pembangunan berbagai mega proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, lapangan terbang beserta aerocity, kompleks industri pengolahan, dsb. Berbeda dengan yang lain, infrastruktur memiliki fungsi khusus melayani komoditas untuk bersirkulasi, khususnya dengan jalan darat atau kereta api, pelabuhan, atau bandara udara. Komoditas ditransportasikan dari satu tempat ke tempat lainnya hingga sampai ke konsumen. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang masif ini ikut menyumbang juga pada penyingkiran rakyat dari kampung halamannya. Sejak masa kebijakan otonomi daerah dimulai tahun 2000, pemerintah daerah lebih tertarik memburu rente yang dapat diperolehnya, baik dari pembagian keuangan pemerintah pusat, maupun dari pemberian izin-izin. Bertarung dalam pemilu kepala daerah menghabiskan biaya yang sangat mahal, dan itu membuat kepala daerah harus mempunyai cara mendapatkan kompensasi dari pengeluarannya ketika bertanding dalam pemilukada itu. Cara itu menemukan bentuk praktisnya ketika desakan desentralisasi 20 reorganisasi ruang berujung pada kewenangan kabupaten dalam pemberian izin lokasi, izin usaha pertambangan, dan sebagainya. Alih-alih mengurus masalah porak-porandanya tanah air, kampung halaman rakyat, negara memfasilitasi pemenuhan kepentingan akumulasi kekayaan segelintir orang, sebagaimana disinyalir oleh Karl Marx (1948) dalam pamfletnya yang termasyhur The Communist Manifesto bahwa “(t)he executive of the modern state is nothing but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie.” Tentu saja, keberadaan negara yang bersifat melulu instrumental terhadap perluasan sistem kapitalisme ini sesungguhnya bertentangan dengan maksud pembentukan Republik Indonesia, sebagaimana dicita-citakan pada masa pendiriannya. Justru sebaliknya, negara diidamkan sebagai kekuatan pembebas rakyat. Barang-barang yang diperjualbelikan dihasilkan di pabrik-pabrik yang lokasinya jauh dari tempat barang itu dijual. Semua barang itu dimungkinkan hadir melalui rantai komoditas (commodity chain) yang merupakan bagian dari sirkuit produksi-sirkulasikonsumsi. Tontonlah video 20 menit yang diproduksi oleh Annie Leonard, dkk. dari Story of Stuff Project. Mereka menunjukkan bagaimana daya rusak dari sistem produksi kapitalis dan pola konsumsi yang dibentuknya https://www.youtube.com/ watch?v=9GorqroigqM. Dengan menonton film ini dan film-film mereka lainnya (lihat informasinya di http://storyofstuff.org) kita akan tercengang dan terinspirasi! Indonesia menduduki posisi khusus dalam sirkuit ini. Istilahnya, 21 panggilan tanah air terdapat pembagian kerja yang telah diatur secara internasional (international division of labour), di mana posisi dan andil Indonesia dalam tata perekonomian global itu sungguh penting untuk dicermati. Kebijakan industri mengatur kehadiran pabrikpabrik yang menghasilkan barang dagangan sesuai standar dan secara massal. Semua itu diatur dalam perjalanan industrialisasi Indonesia secara nasional, yang telah melintasi beberapa kali periode. Kita telah mengalami suatu pengalaman industrialisasi substitusi impor (ISI) yang dimulai awal tahun 1970-an hingga industrialisasi orientasi ekspor (IOE) pada tengah tahun 1980an. Muaranya adalah pembangunan kawasan-kawasan industri khusus (special economic zone), yang menjadi lokasi pabrik-pabrik, dengan sistem produksi kapitalis yang mendasarkan diri pada cara pabrik model Fordism. Istilah Fordism ini berasal dari nama industrialis Amerika Henry Ford, yang membangun pabrik mobil Ford dengan suatu sistem sosial dan ekonomi modern berbasiskan bentuk produksi massal industri yang memiliki standar. Teknik dalam manajemen industrinya disebut sebagai assembly line dengan alat “ban berjalan” dan tugas buruh yang repetitif. Di akhir tahun 1990-an, setelah Presiden Jenderal Soeharto turun tahta dan rezim otoritarian Orde Baru kehilangan cengkeramannya, sebagai respon manajemen industri terhadap gerakan-gerakan serikat buruh yang semakin menguat, dimulailah mekanisme sub-contracting, tidak memerlukan suatu hubungan industrial yang memberi peran bagi serikat-serikat buruh, terutama dalam kontrak kerja yang mencakup kondisi kerja dan penentuan nilai upah. Lebih dari itu, suatu model manajemen industri baru, yang disebut sebagai post-fordism, 22 reorganisasi ruang yakni suatu sistem manajemen industri untuk produksi barang dagangan yang massal melalui mekanisme yang lebih lentur dalam skala produksi, spesialisasi, lokasi produksi, dan sebagainya, dengan basis penggunaan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi baik dalam rantai pasokan untuk produksi (supply chain) hingga sirkulasi barang dagangan sampai ke konsumen. Model paling akhir dan terbaru adalah yang disebut sebagai “jaringan produksi internasional” (international production network), atau juga disebut sebagai jaringan produksi global (global production network). Jaringan produksi internasional/global berlangsung dalam skala besar dan sedang dilayani oleh negara, termasuk melalui pembangunan berbagai mega proyek infrastruktur dalam kerangka pelaksanaan Comprehensive Asia Development Plan (CADP) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (ERIA 2009, 2010, Pemerintah Indonesia 2011). Pelajarilah apresiasi dan kritik atas rancangan MP3EI sebagai Master Plan untuk mereorganisasi ruang bagi perluasan investasi dan pasar di Asia melalui pembangunan proyek infrastruktur raksasa (Rachman dan Januardi 2014). Konsep-konsep baru, seperti koridor ekonomi, konektivitas, kawasan ekonomi khusus, dan lainnya, diandalkan untuk meyakinkan pembaca mengenai keharusan proyek-proyek infrastruktur raksasa dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah bagi investasi perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan dan mensirkulasikan komoditas global. Pada gilirannya Indonesia hendak dijadikan bagian dari “Pabrik Asia” 23 panggilan tanah air (Asia Factory). Istilah Asia Factory ini dibuat untuk menunjukkan suatu model baru dalam produksi komoditas yang berisi jaringanjaringan produksi tingkat regional yang menghubungkan pabrikpabrik di berbagai wilayah ekonomi Asia yang memproduksi bagian-bagian dan komponen-komponen yang kemudian dirakit, dan produk akhirnya dikirim ke wilayah-wilayah “ekonomi maju” (ADB 2013: 2). Contoh yang terbaik adalah produksi cellphone. Kita tidak bisa lagi mengenali di mana cellphone sesungguhnya diproduksi. Kita tidak bisa lagi percaya tanda-tanda lokasi produksinya pada label barang dagangan itu, seperti “made in Japan”, “made in Korea”, “made in Indonesia”, dsb. Tontonlah suatu film (4 menit, 23 detik) yang dibuat oleh Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO) berjudul Made in The World: https:// www.youtube.com/watch?v=KMkJu8S8ztE.2 Menonton film singkat itu, kita akan terkesan, dan memahami kecenderungan baru yang mengagumkan, sekaligus mengkhawatirkan! Catatan Akhir 1 Rujukan mengenai konsep produksi ruang ini berangkat dari pemikiran Henri Lefebvre (1992). Menurut Lefebvre (1976), kapitalisme akan mati bila tidak memperluas diri dengan melakukan ekspansi geografis ini. Penjelasan lebih terbaru dibuat oleh Harvey (2003, 2005, 2006) 2 Terima kasih untuk Hendro Sangkoyo yang telah menunjukkan video ini. 24 - IV - Merasani “Kutukan Kolonial” Ayolah kita sedikit lebih dalam memahami apakah modal itu, bagaimana mekanisme bekerjanya modal sebagai suatu kekuatan pengubah tanah air rakyat di seantero kepulauan Indonesia, memporak-porandakan cara berproduksi yang ada dalam ruang hidup rakyat berserta seluruh kelangsungan layanan alamnya. Lebih lanjut, marilah kita menyadari betapa pentingnya hadir dan berperan sebagai pejuang tanah air, merintis cara berjuang baru menghadapi konteks perkembangan kapitalisme yang baru, dan menjadi bagian dari perjuangan tanah air itu. Ellen M. Wood (1994, 2002) membedakan market-as-opportunity (pasar-sebagai-kesempatan), dan market-as-imperative (pasar-sebagai-keharusan). Pasar sebagai kesempatan bekerja melalui proses sirkulasi barang dagangan. Kebutuhan manusia pada gilirannya dibentuk agar dapat mengkonsumsi apa-apa yang diproduksi. Sebagai suatu sistem produksi yang khusus, ia mendominasi cara pertukaran komoditas melalui pasar. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan raksasa sanggup membentuk bagaimana cara sektor ekonomi dikelola oleh badan-badan 25 panggilan tanah air pemerintahan hingga pada pemikiran bagaimana ekonomi pasar itu diagung-agungkan. Sementara itu, pasar-sebagai-keharusan dapat dipahami mulai dari karakter sistem produksi kapitalis sebagai yang paling mampu dalam mengakumulasikan keuntungan melalui kemajuan dan pemutakhiran teknologi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja per unit kerja, serta efisiensi hubungan sosial dan pembagian kerja produksi dan sirkulasi barang dagangan. Karena karakter kapitalisme yang progresif inilah kita menyaksikan penggantian pabrik-pabrik yang telah usang, sektor-sektor ekonomi yang tidak kompetitif, hingga penggantian para pekerja yang keterampilannya tidak lagi dapat dipakai. Istilah Joseph Schumpeter yang dibuat terkenal oleh David Harvey adalah creative destruction (Harvey 2006). Maksudnya, sebagai sistem produksi yang khusus, kapitalisme ini memberi tempat hidup dan insentif bagi semua komponen yang efisien, dan menghukum mati atau membiarkan mati halhal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya. Selanjutnya, di atas apa-apa yang telah dihancurleburkan itulah dibangun sesuatu yang baru, yang dapat lebih menjamin penciptaan keuntungan dan keberlangsungan akumulasi modal. Hal ini mencakup juga perubahan hubungan kepemilikan dan tata guna mengenai tanah dan sumber daya alam, tata guna tanah, hutan, pantai, dan sebagainya. Membangun sistem produksi kapitalistik dimulai dengan menghancurkan terlebih dahulu sistem produksi nonkapitalis yang telah terlebih dahulu ada di wilayah yang disasar itu. 26 merasani “kutukan kolonial” Menurut David Harvey (2006), creative destruction itu semakin mencolok saat berbagai praktik dan kebijakan pemerintah didasari oleh paham neoliberalisme. Dalam hal ini neoliberalisme merupakan suatu paham yang menempatkan kebebasan individu untuk berusaha sebagai norma tertingi dan paling baik dilindungi dan dicapai dengan tata kelembagaan ekonomi yang mengandalkan jaminan atas hak kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Paham neoliberalisme tidak anti pada intervensi pemerintah, melainkan justru mendayagunakannya. Aransemen kelembagaan dan kebijakan ekonomi yang diabdikan untuk mengoperasionalisasikan paham ini secara sungguh-sungguh dirancang untuk terwujud, termasuk privatisasi, finansialisasi, dan berbagai formula menghadapi krisis-krisis finansial dan ekonomi. Membicarakan kapitalisme bukanlah sesuatu topik yang baru bagi Indonesia sebagai bangsa. Cara bagaimana kapitalisme ini bekerja memporak-porandakan tanah air Indonesia sudah secara gamblang dulu ditunjukkan oleh Soekarno dalam karyanya Indonesia Menggugat (1930). Lebih lanjut, bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia dimaknai sebagai arus balik menandingi kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme dapat dipelajari pada karya Tan Malaka (1925) Naar de ‘Republiek-Indonesia’ (Menudju Republik Indonesia), Mohammad Hatta (1932) Ke Arah Indonesia Merdeka, Soekarno (1933) Mentjapai Indonesia Merdeka. Siapakah yang sekarang membaca naskah-naskah itu?1 Mereka adalah para pendiri bangsa yang fasih mengkritik kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Karya-karya mereka 27 panggilan tanah air itu sanggup menjadi rujukan utama bagi semua orang Indonesia yang berusaha mencari tahu akar-akar kesengsaraan rakyat Indonesia. Selanjutnya pamflet yang ditulis Tan Malaka, Soekarno dan Mohammad Hatta yang ditulis hampir secara bersamaan mampu menjadi rujukan untuk mengerti mengapa Indonesia Merdeka adalah suatu cita-cita dan sekaligus pembentuk dari cara rakyat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, zonder kapitalisme, dan kolonialisme. Di sini kita musti secara khusus menyebut andil Soekarno dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidato di BPUPKI 1 Juni 1945. Ia dengan jelas dan jenius menunjukkan bagaimana Negara Republik Indonesia musti difungsikan sebagai Ibu Pertiwi yang memangku rakyat sebagai warga negaranya. “Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?” Arah politik agraria Indonesia di masa awal kemerdekaan adalah menghilangkan sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme untuk memberi jalan bagi sistem ekonomi nasional bekerja atas prinsip pasal 33 ayat 3 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” – kalimat yang perumusannya dibuat oleh Drs. Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Meski wacana land reform berhasil menjadi kebijakan nasional, namun dua sistem agraria warisan kolonialisme, yakni 28 merasani “kutukan kolonial” perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan Sumatera dan penguasaan lahan hutan oleh Perhutani di Jawa, berhasil berlanjut hidup dengan menempatkan diri sebagai perusahaanperusahaan milik negara, yang dikerangkakan sebagai bagian dari Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya, kebijakan land reform berfokus pada urusan membatasi penguasaan tanah-tanah pertanian rakyat, melarang penguasaan tanah swapraja dan tanah-tanah guntai, redistribusi tanah-tanah negara dan pengaturan bagi hasil (Fauzi 1999, Rachman 2012). Land reform kemudian bergeser dari agenda bangsa untuk mewujudkan keadilan agraria berubah menjadi isu politik yang membelah pengelompokan sosial-politik dan membuat perebutan tanah menjadi basis dari konflik yang lebih luas di pedesaan Jawa, Bali, sebagian Sumatera dan sebagian Nusa Tenggara. Konflik itu berkulminasi menjadi pembunuhan massal, penangkapan dan pemenjaraan puluhan ribu orang yang digolongkan komunis, pelarangan PKI, ideologi komunis, dan organisasi yang digolongkan dalam underbow-nya. Konflik itu juga berpuncak pada digulingkannya Soekarno melalui suatu cara kudeta merangkak, naiknya jenderal Soeharto sebagai Presiden RI, dan awal mula dari rezim otoritarianisme militer. Seperti ditunjukkan oleh sejarawan Hilmar Farid (2005), suatu kekerasan massal yang berlangsung 1965-1966, merupakan primitive accumulation, bagian dari proses awal kembalinya kapitalisme berkembang di Indonesia. Apa yang terjadi di periode itu terus akan menanti untuk diungkap, dan memerlukan keberanian, sikap kritis, dan moral bijaksana untuk memahami 29 panggilan tanah air yang terjadi dalam babak sejarah itu, termasuk menghubungkannya dengan perkembangan kapitalisme, yang sempat jeda terhenti sepanjang sekitar 23 tahun, yakni 19421945, 1945-1949, 1949-1957, dan 1958-1965. Sekarang kita bisa memandang betapa penting periode ketika Soekarno memimpin 1958-1965 itu. Soekarno telah menegaskan fondasi ideologis untuk menandingi kapitalisme kolonialisme. Selain Soekarno, kita ingat juga Mohammad Hatta dan Mochammad Tauchid yang telah meletakkan dasar-dasar baru pengaturan agraria nasional, yang berdasarkan kritik terhadap cara politik agaria kolonial bekerja. Mohammad Hatta telah meletakkan dasar-dasar yang melarang tanah (dan sumber daya alam) untuk diperlakukan sebagai komoditas (barang dagangan). Kita ingat juga Mochammad Tauchid dalam bukunya Masalah Agraria jilid 1 dan 2 (1952/3), yang memberikan penjelasan paling menyeluruh tentang politik agraria Indonesia, termasuk meletakkan dasar bahwa penyelesaian masalah agraria menentukan kelangsungan hidup bangsa dan rakyat Indonesia. Selain Pancasila yang telah menjadi ideologi negara, Soekarno telah pula melahirkan formula Trisakti (Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan) untuk menginspirasi perjuangan dekolonisasi dalam segala bentuknya, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk perjuangan kemerdekaan negeri-negeri terjajah lainnya, sebagaimana secara fundamental ditegaskan dalam deklarasi “Dasasila Bandung” yang dihasilkan oleh Konferensi Asia-Afrika 1955.2 30 merasani “kutukan kolonial” Namun, selama kepemimpinan langsung Presiden Soekarno (1958-1965), Indonesia belum berhasil mengatasi apa yang saya istilahkan “kutukan kolonial”, yang secara lantang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno pada sidang pleno pertama Dewan Perantjang Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959. Kutukan itu, pertama, “Indonesia mendjadi pasar pendjualan daripada produk-produk negeri pendjadjah atau negeri-negeri luaran di tanah air kita”; kedua, “Indonesia mendjadi tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi industriil kapitalisme di negeri pendjadjah atau negeri-negeri lain”, dan ketiga, “Indonesia mendjadi tempat investasi daripada modalmodal pendjadjah dan modal-modal asing jang lain”. Kutukan kolonial ini menemukan rezim penguasa politik yang mewujudkannya, rezim otoritarian-militer Orde Baru (19661998), yang kembali menjalankan politik agraria kolonial, khususnya dengan mempraktikkan kembali azas domein Negara. Sejarah politik agraria di Hindia-Belanda memberi pelajaran bahwa pemberlakuan azazdomein negara, baik dengan Boschordonantie voor Java en Madoera 1865 (Undang-undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura 1865), dan Agrarische Wet 1870, menyatakan klaim bahwa setiap tanah (hutan) yang tidak dapat dibuktikan adanya hak kepemilikan pribadi (eigendom) di atasnya maka menjadi domain pemerintah. Pemberlakuan pernyataan domein (domein verklaring) ini merupakansuatu cara agar perusahaan-perusahaan dari negara-negara Eropa dapat memperoleh hak-hak pemanfaatan yang eksklusif atas tanah/ wilayah di tanah jajahan, membentuk rezim tenaga kerja kolonial yang khusus, dan menjadi sistem-sistem agraria kehutanan dan 31 panggilan tanah air perkebunan, yang menghasilkan komoditas ekspor (Tauchid 1952/2009:32-90; Peluso 1992:44-67, Simbolon 1995/2007:155-7, Fauzi 1999:33-37). Rezim penguasa Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto yang berkuasa melalui peralihan kekuasaan yang berdarah-darah di tahun 1965-1966, kembali memberlakukan azas domein ini. Melalui sistem perizinan (lisensi) yang serupa dijalankan oleh pemerintah kolonial, badan-badan pemerintahan pusat mengkapling-kapling tanah-air Indonesia untuk konsesi pertambangan, kehutanan dan perkebunan, dan mengeluarkan paksa penduduk yang hidup di dalam konsesi itu. Tiap-tiap rezim kebijakan dari badan pemerintah pusat memiliki instrumen hukum dan birokrasi pemberian lisensi yang berbeda-beda. Nama, definisi, dan bentuk dari lisensi-lisensi itu berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan keperluan perusahaan untuk mengakumulasikan kekayaan, karakteristik sumber daya alam yang disasar, dan rancangan pemerintah untuk mengkomodifikasi atau mengkonservasi sumber daya alam. Untuk menyebut beberapa saja, misalnya, rezim perizinan pertambangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki “Kontak Karya” dan “Kontrak Karya Pertambangan”; rezim perizinan kehutanan di Kementerian Kehutanan3 memiliki “Hak Pengusahaan Hutan” dan “Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri” yang kemudian diganti menjadi nama “Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA)”, dan “Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)”; rezim perizinan kehutanan untuk konservasi memiliki kekhususan bentuk yakni 32 merasani “kutukan kolonial” “Taman Nasional”, “Cagar Alam”, “Taman Wisata Alam”, dll., hingga yang baru adalah “Izin Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-Restorasi Ekosistem)”; dan Badan Pertanahan Nasional memiliki instrumen “Hak Guna Usaha (HGU)” untuk perkebunan-perkebunan. Teritorialisasi yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan, melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1984/5, untuk pertama kalinya menetapkan kawasan hutan negara seluas sekitar 2/3 dari total wilayah daratan Republik Indonesia. TGHK mengatur secara agregat hutan permanen dikategorikan menjadi: (1) hutan produksi seluas 64,3 juta hektar; (2) hutan lindung seluas 30,7 juta hektar; (3) wilayah konservasi dan hutan cagar alam seluas 18,8 juta hektar; dan (4) hutan produksi, yang dapat diubah peruntukannya, seluas 26,6 juta hektar. Luasan masing-masing kategori ini kemudian berubah setelah ada pembaruan data dari Departemen Kehutanan. Kewenangan legal Menteri Kehutanan mengeluarkan lisensi berbentuk surat-surat izin pemanfaatan hutan sesuai dengan kategori-kategori itu. Wilayah-wilayah rakyat yang masuk dalam kawasan hutan negara itu nasibnya bergantung pada kelompok kategori di mana wilayah rakyat itu berada, dan lisensi-lisensi yang dikeluarkan Menteri Kehutanan yang mencakup atau mengenai wilayah rakyat itu. Konflik-konflik agraria struktural muncul ketika rakyat menolak disingkirkan oleh perusahaan pemegang izin, dan melakukan perlawanan secara terus-menerus. Konflik-konflik ini merebak di mana-mana dan menjadi kronis, karena pemerintah terus saja berfungsi melayani dan melindungi kepentingan33 panggilan tanah air kepentingan perusahaan-perusahaan, dan tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang tepat untuk menjamin tercapainya keadilan agraria (Rachman 2013). Hubungan dan cara penduduk menikmati hasil dari tanah airnya telah diputus melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pengkaplingan wilayah secara f isik, hingga penggunaan wacana dan simbol-simbol baru yang menunjukkan status kepemilikan yang bukan lagi dipunyai rakyat. Bila saja sekelompok rakyat melakukan protes dan perlawanan untuk mengklaim dan menguasai kembali tanah dan wilayah yang telah diambil alih oleh pemerintah dan diberikan ke perusahaanperusahaan itu, maka mereka menerima akibat yang sangat nyata, yakni menjadi sasaran tindakan kekerasan secara langsung maupun melalui birokrasi aparatus hukum negara. Pengkapling-kaplingan dan pemutusan hubungan kepemilikan rakyat dengan tanah airnya itu pada intinya adalah penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam tertentu, lalu tanah dan kekayaan alam itu masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapitalistik.4 Jadi, perubahan dari alam menjadi “sumber daya alam” ini berakibat sangat pahit bagi rakyat petani yang harus tersingkir dari tanah airnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/buruh upahan. Ini adalah proses paksa menciptakan orang-orang yang tidak lagi bekerja dan hidup di tanah airnya. Orang-orang ini hanya akan mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya saja, lalu menjadi para pekerja bebas. Sebagian mereka pergi dari tanah mereka di desa-desa ke kota-kota untuk mendapatkan 34 merasani “kutukan kolonial” pekerjaan. Kantung-kantung kemiskinan di kota-kota pasca kolonial, yang dijuluki planet of slums (Davis 2006), banyak dilahirkan oleh proses demikian ini. Betapa ironisnya bahwa sebagian dari wajah Indonesia masih mengidap “kutukan kolonial” setelah hampir 70 tahun berjalan melewati “jembatan emas” kemerdekaan. Sesungguhnya, “kutukan kolonial” itu, oleh Soekarno dikontraskan dengan keperluan untuk secara leluasa “menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi”. Secara jelas hal ini dipidatokan oleh Ir. Soekarno dalam Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan 1 Juni tahun 1945, setelah memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai “jembatan emas”. Kita sudah menyelesaikan revolusi nasional yang menghasilkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, dan perjalanan Indonesia masa lalu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang menyulitkan kita mencapai cita-cita kemerdekaan itu. Mengapa kita mesti leluasa? Karena, dalam memikirkan mengenai masa depan Indonesia, kita tidak boleh dikekang dan dikungkung oleh cara-cara penyelenggaraan pemerintahan yang lalu. Cara-cara yang menggagalkan itu tidak perlu diulang. Indonesia seharusnya tidak lagi berkedudukan yang melanggengkan kedudukan Indonesia sebagai “Een natie van koelies enen koelie onder de naties”, “A nation of coolies and a coolie amongst nations”. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari “kutukan kolonial” ini? 35 panggilan tanah air Catatan Akhir 1 Bagi yang sulit mendapatkan naskah-naskah ini, ikutilah ringkasan karya-karya itu yang dibuat oleh Parakitri T. Simbolon, seorang cendekiawan cum wartawan di Lampiran 1a, Lampiran 1b, dan Lampiran 1c 2 Isi Dasasila Bandung yang dicetuskan dalam Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 menjadi relevan dan mendesak untuk diaktualisasikan. Kita mengingat butir-butir “Dasasila Bandung” yang selengkapnya, yakni: (1) Menghormati hak-hak asasi manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam Perserikatan BangsaBangsa; (2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, (3) Mengakui persamaan semua etnis dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil; (4) Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam masalahmasalah dalam negeri negara lain; (5) Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian maupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB; (6) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, dan tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain; (7) Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu Negara; (8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB; (9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama; dan 36 merasani “kutukan kolonial” (10)Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. 3 Sejak tahun 2014, Presiden Jokowi mengubahnya menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4 Karl Marx dalam Capital (1867) mengembangkan konsep “the socalled primitive accumulation”, yang mendudukkan proses perampasan tanah ini sebagai satu sisi dari mata uang, dan kemudian memasangkannya dengan sisi lainnya, yaitu penciptaan tenaga kerja bebas. Marx mengerjakan kembali temuan Adam Smith (pemikir ekonomi terkenal yang menteorikan mengenai “tangan-tangan tak terlihat” [invisible hands] yang bekerja dalam mengatur bagaimana pasar bekerja), bahwa “akumulasi kekayaan alam harus terjadi dulu sebelum pembagian kerja”, sebagaimana tertulis dalam karya terkenalnya The Weath of Nations (1776, I.3: 277). Michael Perelman memecahkan misteri penggunaan kata “primitive“ dalam “primitive accumulation“. Seperti yang secara tegas tercantum dalam tulisan Marx, kata primitive berasal dari istilah previous accumulation- Adam Smith. Marx yang menulis dalam bahasa Jerman menerjemahkan kata “previous” dari karya Adam Smith menjadi “ursprunglich“, di mana penerjemah bahasa Inggris Das Kapital karya Marx kemudian menerjemahkannya menjadi kata “primitive“ (Perelman 2000:25). Uraian menarik mengenai konsep “original accumulation“ dari Adam Smith dan “primitive accumulation“ dari Karl Marx, dan relevansinya untuk memahami perkembangan kapitalisme dewasa ini, dapat ditemukan dalam Perelman (2000) dan De Angelis (1999, 2007). 37 . -V- Masa Depan Tanah Air, Tanah Air Masa Depan Rezim Orde Baru adalah rezim ekstraktif (extractive regime) (Gellert 2010), yang berhasil melahirkan elite oligarki penguasa ekonomi dan politik Indonesia, dan merupakan mitra kerja perusahaan-perusahaan asing transnasional. Dari waktu ke waktu, kekayaan mereka diperoleh melalui perusahaanperusahaan raksasa pertambangan minyak, gas, emas, batu bara, dsb., perusahaan-perusahaan pembalakan kayu, hingga perusahaan-perusahaan perkebunan untuk kayu lapis, bubur kertas, kelapa sawit, dan sebagainya. Mereka adalah tiang penyangga keberlangsungan rezim Orde Baru. Karenanya, pemerintah perlu memastikan mereka mempunyai konsesikonsesi tanah dan sumber daya alam untuk akumulasi kekayaan mereka itu.1 Konsesi-konsesi itu bisa bekerja bila kekuatan lembaga lokal yang sudah terlebih dahulu menguasai dan mengatur tanah airnya itu dilumpuhkan. Penyeragaman nama, bentuk, susunan, dan kedudukan desa dilakukan oleh rezim Orde Baru, dan dikombinasikan dengan paket-paket insentif politik uang melalui 39 panggilan tanah air berbagai Instruksi Presiden (inpres), berhasil melumpuhkan kekuatan serta menghilangkan kewenangan lembaga-lembaga adat/lokal untuk mengatur tanah airnya.2 Selama Indonesia berada di bawah kekuasaan rezim Orde Baru, desa didudukkan sebagai sasaran pengaturan dan sekaligus kekuatan untuk mengendalikan dan sekaligus memobilisir rakyat. Kepala desa bersama dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) menjadi aparat pengendalian teritorial dan mobilisasi rakyat. Di atas birokrasi pemerintahan desa, terdapat struktur pengendali dan mobilisasi yang terkordinasi dalam Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari camat, Komandan Rayon Militer (Danramil), dan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek).3 Setelah Orde Baru tumbang, DPR RI dan Pemerintah menyadari bahwa penyeragaman nama, bentuk, susunan dan kedudukan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945. Demikian yang ditulis dalam bagian “menimbang” Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Norma dasar yang termuat dalam pasal 18 UUD 1945 diabaikan oleh pemerintahan Orde Baru. Secara khusus, pada penjelasan pasal 18 UUD 1945 itu secara eksplisit dinyatakan bahwa : “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan 40 masa depan tanah air, tanah air masa depan ”Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”. Warisan yang kita dapat saat ini adalah sebagian dari tanah air yang porak-poranda, berada dalam situasi krisis sosial ekologi yang parah. Komponen utama krisis itu, sebagaimana pernah ditunjukkan oleh Hendro Sangkoyo (1999) adalah keselamatan rakyat yang tidak terjamin, produktivitas rakyat yang menurun, layanan alam yang rusak, dan kesejahteraan rakyat merosot. Quo vadis? Mau kemana kita menuju? Pedoman apa yang bisa kita rujuk untuk bisa keluar dari krisis itu, menempuh jalan mencapai cita-cita bersama dengan cara yang baru? Situasi membangun arus balik untuk memperjuangkan tanah air harus berurusan dengan proyek-proyek pembangunan, terutama proyek pembangunan untuk mengatasi kemiskinan. Suatu jenis proyek pembangunan yang penting dalam menata ulang pemerintahan lokal ini diberi nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Di tahun 41 panggilan tanah air 2007 dan seterusnya, PNPM Mandiri menjadi andalan untuk pengentasan kemiskinan, dengan jangkauan 2.827 kecamatan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 3,6 triliun. Pada tahun 2008 jumlah kecamatan yang dijangkau menjadi 3.999 kecamatan dengan anggaran yang disediakan sekitar 13 triliun. Sedangkan pada tahun 2009 diagendakan seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 5.263 kecamatan akan mendapat PNPM Mandiri. Besarnya bantuan langsung pada tahun 2007 antara Rp 750 juta s/d Rp 1,5 miliar per kecamatan, sementara pada tahun 2008 besarnya bantuan per kecamatan sudah ada yang mencapai Rp 3 miliar (Menko Kesra 2008). Sampai akhir kepemimpinan SBY-Boediono di tahun 2014, secara total PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan telah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 74,46 triliun. Sedangkan dana BLM P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) dan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2008 - 2013 sebesar Rp 9,124 triliun dan pada 2014 dana yang dialokasikan sebesar 1,380 triliun. Sampai saat tahun terakhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kedua jenis program tersebut diklaim “telah menghasilkan berbagai dampak positif terhadap peningkatan kapasitas, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat” (Paket Informasi PNPM Mandiri 2014:23). Apa yang sesungguhnya dihasilkan? Selain berhasil membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur skala kecil-kecil, PNPM berhasil membentuk komunitas miskin menjadi 42 masa depan tanah air, tanah air masa depan masyarakat proyek. Struktur administratif program ini membuka persaingan antar kelompok satu dengan lainnya dalam proses penyampaian proposal proyek untuk perolehan dana. Semuanya itu mengandung norma-nilai kewirausahaan, inovasi individual, dan kompetisi pasar bebas. Norma-nilai demikian itu menyertakan prinsip-prinsip, seperti akuntabilitas yang dilaksanakan melalui aturan-aturan maupun prosedur yang mensyaratkan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan hak partisipasi individu yang dilaksanakan melalui aturan maupun prosedur seperti voting, sistem kuota, dan kewajiban konsultasi (Rawski 2006:942). Lebih jauh, melalui proyek-proyek ini pemerintah berhasil “memerintah melalui komunitas” dalam rangka mengatur ulang aspirasi, keyakinan, perilaku, tindakan, dan hal-hal subjektivitas lainnya (Li 2014). Pendek kata, PPK menggunakan teknologi partisipatif sebagai alat pengantar dari norma-nilai yang cocok dan diperlukan mereka agar bisa hidup dalam masyarakat yang didominasi oleh hubungan-hubungan sosial yang kapitalistik (Carrol 2010:86). Babak PNPM berakhir setelah kabinet Jokowi-JK tersusun dan mulai bekerja dengan sembilan agenda utama yang diberi nama “Nawa Cita”, yang salah satunya “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”. Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa menjadi rujukan yang utama dan kesempatan bagi desa untuk diutamakan.4 Dirumuskan bahwa “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 43 panggilan tanah air pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penyebutan desa dan desa adat dapat disesuaikan dengan nama setempat. Tidak mudah bagi elit pemerintah kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/kota untuk membuat pengaturan-pengaturan dengan azas-azas baru yang ditetapkan dalam Undang-Undang Desa tersebut. Para legislator dan eksekutif pembuat aturan perlu memiliki imajinasi yang baru, khususnya karena azas-asas baru dalam UU tentang Desa ini.5 Undang-undang Desa ini tidak bisa dijalankan dengan mentalitas “hanya sekedar melaksanakan sesuai instruksi”. Masalahnya juga, banyak elit pemerintah desa dan juga sebagian anggota masyarakat desa, saat ini sudah terbiasa diposisikan sebagai yang diatur. Desa terbiasa diatur sebagai bawahan dari birokrasi kecamatan (dan bukan sebagai entitas yang memiliki hak asal-usul), sasaran dari berbagai macam proyek yang dipegang oleh badan-badan pemerintah (bukan unit yang mengatur sendiri apa yang menjadi kepentingannya), dan diatur secara seragam (dan bukan mempertimbangkan keanekaragaman geografi dan sejarah masing-masing). Mereka yang terpanggil sebagai pandu, terlepas apapun posisi formalnya, perlu mengembangkan cara pandang baru dengan imajinasi yang baru. Hendro Sangkoyo (1999) mengundang kita untuk memulai dari cara kita memahami apa sesungguhnya 44 masa depan tanah air, tanah air masa depan “pemerintahan” itu. “Pemerintahan” sebagai mitos yang harus diterima sebagai ketentuan bagi rakyat, yang nyaris diterima begitu saja dan dianggap bersifat alami. Dalam mitos yang sekarang masih melekat sebagai wacana publik itu, pemerintahan merupakan sebuah pertunjukan tentang bagaimana mengelola sumber-sumber alam, orang, barang, dan uang, dengan para pengelola negara sebagai pemain panggungnya, dan rakyat sebagai pengamat dan pembayar karcis pertunjukan. Partisipasi rakyat, paling jauh, adalah sebagai komentator atau kritikus pertunjukan. Ajakan pembaruan cara dan agenda pemerintahan dengan demikian bersifat mudah-mudahan, penuh harap pada para pengelola negara yang baru serta pada ketentuan-ketentuan yang dihasilkannya; sebuah koor nyaring dari bawah panggung tentang reformasi, yang tetap takzim pada akar kata itu: perintah. Pengurusan merupakan suatu konsep tandingan yang sangat akrab bagi penutur bahasa Indonesia, dan mengacu kepada konsep pokok yang lebih jitu: urus. Setelah sejarah membuktikan kegagalan dari pengelolaan perubahan tanpa rakyat selama tiga puluh tahun, penggantian orang, perombakan dekorasi panggung dan/atau skenario baru saja mengandung resiko kegagalan yang sama, selama rakyat sendiri tidak aktif dan tidak berkesungguhan mengurus apa yang menjadi persyaratan kehidupannya. Otonomi pemerintahan daerah dari campur tangan 45 panggilan tanah air berlebihan pemerintah pusat di Jakarta, serta besarnya ruang pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada proses pemerintahan daerah pada saat ini, merupakan situasi persimpangan yang genting bagi rakyat: meneruskan tradisi pertunjukan sebagai penonton dalam panggung-panggung yang lebih kecil, atau bersama-sama berperan sebagai pemain, mengurusi apa yang hendak dimainkan bersama. Keputusan yang harus rakyat tentukan pada saat ini bukan saja bergantung pada kehendak sendiri, melainkan juga pada keterdesakan waktu untuk memulihkan kerusakan sosial dan ekologis yang selama lebih dari satu generasi yang lampau telah mengasingkan rakyat dari wilayah hidupnya. Ya, kita musti mengurus secara sungguh-sungguh pemulihan kerusakan sosial dan ekologis yang menjadi syarat-syarat keberlangsungan hidup rakyat. Tidak ada jalan lain! Bagaimana kampung atau desa dapat dijadikan tempat berangkat dan sekaligus sasaran pengabdian? Saya menganjurkan untuk benarbenar mempelajari panduan yang berikut ini diuraikan secara kental oleh Hendro Sangkoyo,6 agar dapat kita dapat bekerja mengenali dan menangani krisis sosial ekologis melalui pemahaman baru atas tiga golongan masalah: (a) keselamatan dan kesejahteraan rakyat, (b) keutuhan fungsi-fungsi faal ruang hidup, dan (c) produktivitas rakyat. A. Keselamatan dan Kesejahteraan Rakyat Keselamatan rakyat, pada skala orang per orang maupun 46 masa depan tanah air, tanah air masa depan rombongan, tidak pernah kita urus sebagai syarat yang harus dipenuhi dan dijaga baik oleh para pengurus negara dan alatalatnya. Hilangnya nyawa, ingatan, tanah halaman, harta benda, nafkah, kesempatan, kehormatan milik rakyat karena proses penyelenggaraan perubahan selama tiga puluh tahun terakhir ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa selama keselamatan rakyat tidak kita persyaratkan sebagai agenda pengurusan masyarakat dan wilayah, akan terus jatuh korban. Keselamatan rakyat sudah saatnya menjadi salah satu agenda inti dari proses pembaruan ketentuan-ketentuan kenegaraan, termasuk pembaruan hukum, dan dari penyelenggaraan fungsi-fungsi politik seperti pengelolaan produksi dan keuangan. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa mengurus keselamatan rakyat harus menjadi tindakan kolektif sehari-hari dari lembagalembaga politik terkecil pada aras desa hingga kabupaten. Kesejahteraan rakyat, meskipun senantiasa menjadi semboyan, program, pos anggaran, dan indikator, tidak pernah kita urus sebagai syarat dari kerja birokrasi negara. Tak terpisahkan dari konsep pokok “keselamatan”, rakyat selama ini “mendapatkan” dua akibat perubahan terencana pada keadaan kesejahteraannya, yang saling bertolak belakang: pelayanan kesejahteraan seperti kesehatan dan pendidikan, sekaligus perampasan kesejahteraan lewat berbagai mekanisme, baik langsung maupun tidak, seperti politik fiskal, perampasan tanah dan tempat tinggal rakyat sebagai syarat investasi produksi, dan politik konstruksi fisik sarana pelayanan umum di pusat-pusat pemukiman. 47 panggilan tanah air Pemenuhan syarat keselamatan dan kesejahteraan rakyat di sini merupakan cara bagi rakyat khususnya pada aras desa untuk ikut menentukan arah dan besaran perubahan yang menyangkut dirinya secara teratur dan terorganisir. Proses pemenuhan persyaratan tersebut di atas menuntut tiga syarat (dua hal dalam syarat pertama dapat dipenuhi langsung pada tingkat kesepakatan bersama): (1) pemetaan berkala mengenai keadaan persyaratan bagi rakyat desa dan agenda tindakan bersama untuk mengoreksi kegagalan pemenuhan; (2) usaha kolektif untuk mengatasi kesulitan rakyat memenuhi syarat keselamatan/kesejahteraannya sendiri; dan (3) pelayanan publik lewat peralatan kenegaraan termasuk dana dan ketentuan hukum; Prioritas utama agenda tindakan pada saat ini adalah perumusan dan penyepakatan persyaratan keselamatan dan kesejahteraan setempat, serta penerapan ketiga proses di atas dalam suatu proses belajar bersama yang harus melibatkan warga desa, legislator daerah (DPRD kabupaten) dan pengurus-pengurus negara di daerah (pemerintah kabupaten). B. Keutuhan Fungsi-fungsi Faal Ruang Hidup Hilangnya sumber-sumber air bersama, gundulnya wilayahwilayah dataran tinggi dan curam yang genting kedudukannya dalam daur tata air setempat, peracunan dan pemiskinan hara tanah karena cara produksi tani yang mementingkan hasil jangka 48 masa depan tanah air, tanah air masa depan pendek, atau karena kegiatan penambangan, pengeruhan dan pendangkalan aliran sungai, hilangnya sumber-sumber hayati perairan pesisir, adalah beberapa contoh tidak terpenuhinya kelangsungan “pelayanan alam” bagi kehidupan yang dikandungnya, yang bersifat mendorong pengawetan bahkan peluasan pemiskinan rakyat khususnya di desa, dan merupakan ancaman jangka panjang terhadap syarat-syarat keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kata “pelayanan alam” sendiri telah mengalami evolusi, dari kondisi material yang memungkinkan berkembang dan terbaruinya kehidupan di sebuah bentang alam (dalam masa hidup kita, dapat disebut sebagai kehidupan simbiotik dari tumbuhan dan hewan, termasuk kehidupan spesies manusia), menjadi “kegiatan produksi nilai”, di mana keberadaan air, hara tanah, oksigen, nitrogen, karbon, biota, bahkan “pemandangan indah”, diperlakukan sebagai sebuah kelas dalam sistem klasifikasi industrial, setara dengan perdagangan grosir, binatu, atau reparasi dan semir sepatu. Lebih jauh, dalam empat dekade terakhir, rasionalitas publik tengah disubversi menjadi logika keberlanjutan produksi nilai, misalnya ketika kendali publik atas daur reproduksi air tawar dipersamakan dengan “monopoli”, dan oleh karenanya harus dihapuskan untuk memungkinkan persaingan bagi perusahaan air pribadi/swasta. “Pelayanan alam” dibubuhi nilai tukar, dan karenanya diperlakukan sebagai barang untuk dijualbelikan. Logika kebutuhan air untuk pertanian pangan hendak disetarakan dengan logika kebutuhan air untuk kapal tanker, pusat belanja atau hotel, untuk memudahkan penentuan harga. Hutan direduksi keberadaan materialnya sebagai 49 panggilan tanah air onggokan zat karbon yang terkandung dalam pohon dan tanahnya, dihitung bobot matinya, dan dibubuhi harganya dalam ukuran kilogram atau ton. Apa-apa yang berharga untuk dilindungi dan apa-apa yang bisa rusak dari bentang-alam hutan beserta penghuninya dicomot sebagian kecilnya saja, yaitu terurainya zat karbon ke atmosfir, seolah-olah kita semua adalah benda mati yang boleh diperlakukan sebagai seonggok zat karbon. Itulah sebabnya, segala sesuatu dalam skema jual-beli dan penciptaan nilai atas nilai-uang dari zat karbon, termasuk dalam program reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi lahan adalah penghinaan terhadap logika kehidupan itu sendiri. Dalam hal ini, apa yang tengah dirusak dengan kecepatan penuh oleh logika neoliberal dari pengurusan publik sekarang bukanlah ketersediaan air, lahan atau bahan-bahan alami, melainkan syarat keberlangsungan fungsi-fungsi faal infrastruktur ekologis dari sebuah ruang hidup, beserta ikatan menyejarahnya dengan masyarakat manusia di situ. Selama empat puluh tahun terakhir, proses penjalaran kerusakan alam setempat maupun pencegahan atau perlindungannya berjalan terlepas dari proses pengurusan keselamatan dan kesejahteraan serta produktivitas rakyat maupun dari proses politik desa. Wilayah-wilayah yang seharusnya dikelola bersama untuk dicegah proses kerusakannya — seperti di wilayah berhutan — telah dijadikan sebagai kompleks-kompleks berpagar dan berpatok kekuasaan negara (tanah negara, hutan negara, dll.) yang bahkan tidak boleh disentuh, apalagi dimanfaatkan oleh rakyat setempat. 50 masa depan tanah air, tanah air masa depan Ketika pencurian besar-besaran terhadap segala yang bersifat ‘milik negara’, menjadi kesepakatan tidak tertulis di antara pengurus negara setempat dan pemilik modal pribadi, untuk berbagai maksud dan tujuan, maka akibatnya wilayah-wilayah perlindungan yang eksklusif pun turut menjadi sasaran utama. Tidak berlakunya konsep ‘kepentingan bersama’ dan ‘milik bersama’ menjadi pelancar penjarahan atas wilayah-wilayah yang seharusnya dimanfaatkan atau dilindungi secara hati-hati. Penanganan dengan kekerasan negara lewat tindakan polisionil dan peradilan, maupun pengerahan dana untuk pemecahan teknis seperti penanaman pohon, telah terbukti tidak mampu menghentikan laju perusakan apalagi menumbuhkan keinginan rakyat untuk memulihkannya. Tandingan terhadap penciptaan wilayah-wilayah negara itu adalah penciptaan wilayah-wilayah kelola bersama. Kepentingan rakyat atas kelangsungan pelayanan alam, serta kebutuhan pemanfaatan bahan terbarui dari hutan, perbukitan dan dataran tinggi, daratan dan perairan pesisir, bukan saja harus diakui secara resmi, tetapi justru harus menjadi tumpuan dari usaha mempertahankan kelangsungan pelayanan alam atau pemulihan wilayah-wilayah rusak yang sering dinamai ‘lahan kritis’ itu. Sampai hari ini, instrumen terpenting dalam operasionalisasi logika ekstraksi nilai dari setiap jengkal bentang alam adalah praktik institusional pembongkaran dan perkiraan nilai komersial atas sumber daya alam, dari tenunan ruang-ruang hidup beserta infrastruktur ekologisnya, menjadi “ruang” sebagai kategori stok kapital. Dalam sistem dan praktik bertutur mengenai ruang 51 panggilan tanah air macam itu, pemilahan fungsi-fungsi sosial-ekologis dari bentang daratan dan perairan digantikan dengan pertimbangan lokasi dalam angan-angan memaksimalkan surplus dari rerantai penciptaan nilai dan rerantai produksi/pasokan/konsumsi barang. Hilangnya imajinasi sosial-ekologis tentang pulau, yang telah nyaris paripurna digantikan dengan sistem kepercayaan pada garis-garis batas juro-politik, bukanlah tanda kurangnya kecerdasan semata, tetapi adalah produk dari pengerahan kepatuhan politik terhadap rezim penataan ruang tanpa asas keselamatan manusia dan kelangsungan ruang-hidupnya. Di setiap pulau di kepulauan Indonesia, bermakna tidaknya agenda pembaruan politik tani sepenuhnya bergantung pada ada tidaknya agenda pembaruan pikiran tentang duduk perkara kota di dalam logika keberlangsungan sosial-ekologis pada skala pulau. Mendesakkan pilihan ini sebagai ketentuan negara atas dasar kesepakatan rakyat adalah prioritas nomor satu bagi badan legislatif di daerah. C. Produktivitas Rakyat Selama tiga puluh tahun terakhir dapat kita nyatakan dengan tegas bahwa produktivitas rakyat, khususnya pekerja tani, tidak pernah beranjak dari kedudukannya yang sangat rendah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraannya sendiri. Bertentangan dengan penjelasan yang menyesatkan bahwa produktivitas kerja adalah cerminan sederhana dari tingkat teknologi dan efisiensi produksi, rendahnya produktivitas pekerja tani merupakan akibat dari penekanan sistematis atas 52 masa depan tanah air, tanah air masa depan nilai tukar produk petani, serentak dengan penyedotan tabungan rakyat lewat pengurangan atau penghapusan subsidi input produksi termasuk penyediaan pengairan dan angkutan rakyat, politik pengembangan wilayah dan sarananya yang diskriminatif terhadap bentuk-bentuk tradisional hak dan kuasa rakyat atas tanah dan wilayah serta terhadap kemampuan lokal untuk menghasilkan bahan pangan. Naiknya produktivitas pertanian pangan maupun pertanian lainnya —karena tambahan input per satuan luas lahan— tidak menjadikan naiknya produktivitas kerja tani, bahkan memperbesar kebutuhan untuk kerja sampingan nontani. Selama politik produktivitas pertanian tidak mendorong naiknya nilai kerja tani dan nilai produk tani, dan selama masing-masing daerah tidak menerapkan syaratsyarat perlindungan pada tanah-tanah rakyat desa dari pembelian atau pengambilalihan untuk berbagai fungsi-fungsi non pertanian seperti pariwisata, rakyat desa khususnya pekerja tani tanpa tanah akan tetap miskin, dan proses pemusatan hak milik dan kuasa atas lahan di desa akan terus merambat luas, tanpa atau dengan pendudukan kembali/reklamasi hak atas tanah-tanah pertanian maupun redistribusi tanah. Produktivitas rakyat desa karenanya harus kembali dipelajari, dibaca, dan ditakar dalam bingkai persoalan setempat (desa atau antar desa). Demikian juga, tindakan sistematis meningkatkan produktivitas rakyat hanya masuk akal apabila tindakan tersebut berguna bagi rakyat desa khususnya pekerja tani untuk memenuhi syarat keselamatan dan kesejahteraannya. Dalam neraca desa, naiknya produksi hasil tani per hektar, begitu pula tersedianya barang-barang indikator kesejahteraan yang biasa 53 panggilan tanah air digunakan (listrik, jalan raya, televisi, dan sebagainya) harus serta merta selalu dikoreksi dengan ada tidaknya penggusuran baru atau perampasan hak yang belum dipulihkan kembali, kemiskinan kronis, ketidakmampuan warga memenuhi syarat keselamatan, kesehatan atau pendidikan yang dibutuhkannya, atau naiknya pengeluaran tunai untuk mencukupi syarat kesehatan maupun pelayanan sosial sehari-hari seperti pendidikan anak. Produktivitas rakyat juga harus dikoreksi pada tingkat abstraksi. Gagasan produktivitas yang mengacu semata pada proses penciptaan nilai pakai atau tukar telah terbukti mengasingkan satu kesatuan ekonomis seperti rumah tangga dari yang lain dan menjadikan desa sebagai wilayah pemusatan pemilikan atau penguasaan tanah. Produktivitas desa dan peningkatannya menjadi identik dengan penguatan golongan terkaya di desa. Sebagai tandingannya, produktivitas seharusnya mengacu pada kemampuan kolektif rakyat di satu wilayah terorganisir/wilayah kelola, untuk menghasilkan syarat-syarat keselamatan dan kesejahteraannya. Efisiensi produksi, perbandingan modal dengan output, dan berbagai takaran produktivitas lain dengan demikian tunduk pada batasan tandingan tersebut di atas. Dalam pengukuran berkala, pembesaran polarisasi kuasa di desa menjadi pembagi dalam fungsi produktivitas setempat; begitu pula kegagalan pemenuhan syarat keselamatan atau kesejahteraan dari warga, atau kegagalan perlindungan alam. Hanya dengan syarat produktivitas sedemikianlah demokratisasi politik desa menjadi kepentingan mendasar bagi rakyat sendiri, bukan pusat-pusat kuasa di ibu kota politik. 54 masa depan tanah air, tanah air masa depan Catatan Akhir 1 Bagaimana dinamika kekuasaan oligarki bekerja dalam periode yang berbeda-beda dapat dipelajari dari karya-karya Robison (1986), Robison dan Hadiz (2004, 2014), dan Winter (2014). 2 Zakaria (2000) menunjukkan perjalanan pengaturan negara mengenai desa sejak kolonial hingga akhir Orde Baru. 3 Struktur pengendali dan mobilisasi rakyat ini serupa dengan yang dilakukan oleh pemerintah balatentara Jepang ketika menguasai Jawa 1942-1945. Aiko Kurosawa (1993) sangat baik menjelaskan apa yang dilakukan pemerintahan balatentara Jepang dengan memperlakukan desa sebagai alat memobilisir dan mengendalikan rakyat. Susunan, kedudukan dan bentuk dari organisasi Rukun Tetangga-Rukun Warga (RT-RW), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Koperasi Unit Desa (KUD), pertahanan sipil (hansip) beserta doktrin Hankamrata dan peraturan “1 x 24 jam harus lapor”, dan sebagainya. 4 Saat ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memulai rekrutmen 16.000 fasilitator desa. Akan banyak kepentingan yang mengarah ke desa, baik untuk suatu politik membangun konstituensi politik, menjadikannya sasaran pengaturan, hingga yang mau meraup keuntungan bisnis melalui pencarian lisensi atau menawarkan jasa. Banyak mantan fasilitator PNPM Mandiri yang diperkirakan akan masuk melamar untuk mendapatkan posisi itu. Ke mana orientasi mereka, dan bagaimana cara kita ikut membentuk mereka menjadi pandu-pandu rakyat dan tanah airnya? 5 Pengaturan-pengaturan mengenai desa itu harus berdasarkan pada 13 (tiga belas) asas, yakni: (1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; (2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa; (3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan 55 panggilan tanah air bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa; (5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa; (6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa; (7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; (8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; (9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; (10) partispasi; (11) kesetaraan; (12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; dan (13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa. 6 Hendro Sangkoyo secara khusus memodifikasi apa yang pernah ditulisnya pada tahun 1999 (Sangkoyo 1999) untuk dimuat untuk naskah buku ini. 56 - VI - Penutup: Panggilan Ideologis untuk Pandu Sudah lama kita hidup dalam situasi di mana “agraria adalah akibat, kapitalisme adalah sebab” (Juliantara 1997). Mari kita buat arus balik, dengan menjadikan situasi tanah air rakyat, menjadi tempat berangkat, yang harus terlebih dahulu dirawat dan diurus untuk dipastikan keberlanjutannya. Karena itu, tanah air rakyat juga sekaligus tempat pengabdian. Kita tidak bisa sekedar berangan-angan, dan menganggap segala sesuatunya bisa dijalankan dengan mudah dan bisa begitu saja sesuai dengan angan-angan. Saya ingat suatu pepatah penting bahwa memang manusia dapat mengubah sejarah, tapi tidak dalam situasi yang kita pilih sendiri. Kita hidup dengan berbagai kebiasaan yang kita terima sebagai warisan.1 Jadi sudah pasti tidak mudah. Soekarno pernah mengingatkan bahwa “kesoelitan-kesoelitan hendaknja tidak mendjadi penghalang daripada tekad kita, tidak mendjadi penghalang daripada kesediaan kita oentoek teroes berdjoang dan teroes bekerdja, bahkan kesoelitan-kesoelitan itu hendaknja mendjadi satoe tjamboekan bagi kita oentoek berdjalan teroes, bekerdja 57 panggilan tanah air teroes oleh karena memang diharapkan daripada kita sekarang ini realisasi daripada penjelenggaraan daripada masjarakat jang adil dan makmoer jang telah lama ditjita-tjitakan oleh rakjat Indonesia”. Lebih lanjut, pada sidang pleno pertama Dewan Perantjang Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia harus “dengan tegas haroes menoedjoe kepada masjarakat adil dan makmoer”, yang pada waktu itu disebutnya sebagai “masjarakat sosialis a la Indonesia”. Upaya merealisasikannya “tidak boleh tidak kita haroes mengadakan planning dan kita haroes mengadakan pimpinan dan haroes kita mengadakan kerahan tenaga. … Tanpa planning, tanpa pimpinan, tanpa pengerahan tenaga tak moengkin masjarakat jang ditjita-tjitakan oleh rakjat Indonesia itoe bisa tertjapai dan terealisasi”. Perencanaan, pengerahan tenaga dan kepemimpinan yang bagaimana? Tentu konteks waktu dan ruang ketika dan di mana Soekarno menyampaikan pesan itu sudah jauh berbeda. Tapi, kita bisa memperlakukannya sebagai rujukan dan inspirasi. Pemimpin dalam semua satuan, termasuk di desa-desa, harus bekerja secara gotong-royong dengan perencanaan yang matang. Adalah tugas kita semua untuk kembali menjadikan perjuangkan tanah air sebagai pijakan, termasuk untuk pemerintah yang selayaknya memposisikan diri dan menjalankan perannya untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan 58 penutup: panggilan ideologis untuk pandu dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (kalimat dari Pembukaan UUD 1945. Lihat Lampiran 2, Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945). Di sini saya menganjurkan kita semua untuk segera menggenapkan tekad dan mengerahkan segala daya upaya untuk merintis arus balik memperjuangkan tanah air, dengan benar-benar menimbang sejarah dan geografi mulai dari masingmasing kampung/desa, lalu kawasan, lalu pulau, hingga mengurus kembali Indonesia sebagai bangsa maritim terbesar di dunia. Penggunaan istilah “arus balik” di atas secara sadar dipakai merujuk pada novel karya Pramoedya Ananta Toer,2 dan juga diinspirasi oleh konsep counter-movement dari Karl Polanyi (1944). Polanyi menulis “selama berabad dinamika masyarakat modern diatur oleh suatu gerakan ganda (double movement): pasar yang terus ekspansi meluaskan diri, tapi gerakan (pasar) ini bertemu dengan suatu gerakan tandingan (countermovement) menghadang ekspansi ini agar jalan ke arah yang berbeda. Membuat arus balik ini adalah ekspresi dari suatu kesadaran kritis dan sekaligus semangat mengubah nasib. Apa yang diutamakan oleh gerakan tandingan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari daya rusak pasar kapitalis. Arus balik atau gerakan tandingan itu sesungguhnya menandingi prinsip “pengaturan diri-sendiri” dari pasar kapitalis (Polanyi 1944:130). Sesungguhnya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Cita-cita Pembentukan Negara Republik Indonesia merupakan keberanian membuat 59 panggilan tanah air suatu arus balik pada zamannya (lihat Lampiran 3, Pidato Soekarno Memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945). Marilah kita, para tetua bapak dan ibu, terutama para pemuda dan pemudi, menjadi pandu tanah air, merintis dan membangun arus balik dengan menjadikan kampung/desa atau apapun namanya sebagai tempat berangkat dan sekaligus tempat kita mengabdi.3 Panggilan menjadi pandu ini adalah panggilan ideologis. Ketahuilah, kepanduan adalah salah satu dari dasar-dasar persatuan Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam “Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia”, 28 Oktober 1928 (lihat Lampiran 4, Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoedi Indonesia) Saya menjadi ingat pada kata-kata utama dalam teks lagu kebangsaan Indonesia Raya versi asal, yang dikenal sebagai karya Wage Rudolf Supratman. Lirik Indonesia Raya untuk pertama kalinya dipublikasi di Koran Sin Po 10 November 1928, kira-kita sebulan setelah W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya itu dengan biola pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928.4 Seluruh lirik lagu itu terdiri dari tiga stanza.5 Perhatikanlah baitbait pertama dari tiap stanza. Karena “Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku”, maka “di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku” (dari bait pertama stanza pertama); Karena “Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya”, maka “di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya” (dari bait pertama stanza kedua); dan karena “Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti”, 60 penutup: panggilan ideologis untuk pandu maka “di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati” (dari bait pertama stanza ketiga). Sebagai penutup, marilah kita hayati panggilan ideologis menjadi pandu, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya versi asal (Lihat Lampiran 5c: Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman). Memang akan terasa panjang karena tiga stanza. Namun, justru karena itu, kita diajak menghayati filosofi yang terkandung di dalam lirik lagunya, khususnya mengenai keniscayaan “berdiri” menjadi “pandu” “untuk selama-lamanya” “menjaga ibu sejati”. Bukankah semua itumerupakan panggilan dari tanah air. Selamat merasa, berpikir, memutuskan, dan bekerja. Catatan Akhir 1 Kalimat terkenal dari Karl Marx (1852): “Manusia membuat sejarahnya sendiri, tapi mereka tidak membuatnya seperti apa yang mereka inginkan dalam situasi yang mereka pilih sendiri, tapi dalam situasi yang langsung dihadapi, ditentukan dan diteruskan dari masa lampau. Tradisi dari semua generasi yang sudah mati membebani bagaikan impian buruk di benak manusia yang hidup.” 2 Menurut Hilmar Farid (2014) “Arus Balik karya Pramoedya Ananta Toer (1985) disebut novel sejarah bukan semata karena latarnya mengambil tempat di Tuban lima ratus tahun yang lalu, tapi karena novel itu menggambarkan sebuah transformasi yang hebat, sebuah arus balik yang hebat, dalam sejarah perairan kita. Sejarah sebagai kritik bertujuan mengenali semua kekuatan yang membentuk transformasi itu. Kesadaran inilah yang akan menjadi landasan bagi transformasi besar di masa mendatang.” 61 panggilan tanah air 3 Cf. Zakaria (2005). 4 Majalah Mingguan Tempo baru-baru ini membuat edisi khusus Hari Kemerdekaan Muhammad Yamin (1903-1962) 18-24 Agustus 2014. Salah satu liputannya adalah mengindikasikan bahwa Muhammad Yamin lah yang menuliskan dan memberikan teks lagu Indonesia Raya itu untuk Wage Rudolf Supratman. 5 Saya berterima kasih pada Gunawan Wiradi (2004) “Lagu Kebangsaan dan Nasionalisme”. https://sajogyoinstitute.wordpress.com/ 2013/09/20/lagu-kebangsaan-dan-nasionalisme/ (unduh terakhir pada 4 April 2015) 62 Lampiran-lampiran . Lampiran 1a Tan Malaka (1925) Naar de “Republiek Indonesia” [Ringkasan dibuat oleh Parakitri T. Simbolon] Ringkasan ini dibuat berdasarkan terjemahan Ongko D. atas karya Tan Malaka, Menudju Republik Indonesia (Jakarta: Yayasan “Massa”, 19 Februari 1986), 82 halaman. Aslinya bahasa Belanda, Naar de “Republiek Indonesia” (Canton: April 1925 untuk cetakan pertama/ Tokyo: Desember 1925 untuk cetakan kedua). Isinya 14 sub-judul dalam cetakan pertama,15 sub-judul cetakan kedua. Ringkasan ini berdasarkan cetakan kedua: tiga pengantar, tiga bab inti, satu penjelasan, dan delapan sisanya merupakan program aksi. Tiga pengantar yaitu INTERUPSI, KETERANGAN PADA CETAKAN KEDUA, dan KATA PENGANTAR. INTERUPSI: mulai dengan epigram “Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan bawaan kelahirannya itu.”; dalam cetakan pertama banyak kesalahan karena kurangnya persediaan huruf latin dan bahasa Belanda yang sudah lama tak digunakan; brosur ditulis singkat mengingat kecilnya minat baca masyarakat yang dituju; yang dituju adalah “golongan terpelajar 65 panggilan tanah air (intelektuil) dari penduduk Indonesia”; brosur ditulis sebagai satu-satunya cara mendekati masyarakat Indonesia akibat pengasingan Tan Malaka oleh Dirk Fock, gubernur-jenderal Hindia Belanda. KETERANGAN PADA CETAKAN KEDUA: permintaan akan brosur ini terus meningkat; kesalahan sudah berkurang tapi masih tetap banyak; tambahan sub-judul baru tentang Majelis Permusyawaratan Indonesia; beberapa penegasan baru seperti dugaan yang terbukti bahwa golongan terpelajar Tiongkok lebih aktif daripada golongan terpelajar Indonesia; sebulan sebelum cetakan kedua terbit, lima juta golongan terpelajar Tiongkok serentak meninggalkan sekolah untuk bergabung dengan perlawanan rakyat; namun demikian perlawanan rakyat Indonesia makin meruncing; perlawanan rakyat makin berkembang ibarat “Padi tumbuh tak berisik ...” KATA PENGANTAR: brosur disusun berdasarkan kesadaran akan pertentangan kelas sosial dan didorong oleh kenyataan berupa “krisis dewasa ini”; beda dengan negeri-negeri terjajah lain, Indonesia tidak punya kelas menengah dan pertentangan kelas berimpit dengan perbedaan rasial; akibatnya sumber pemimpin (golongan terpelajar) buat organisasi revolusioner sangat miskin, dan sumber yang miskin itu pun dibuat putus hubungan dengan rakyat oleh penjajah; krisis dunia sangat mempertajam pertentangan kelas di Indonesia sehingga golongan terpelajar terpaksa menentukan sikap dan memilih pihak; makanya brosur “memberikan tangga kepada saudara [golongan terpelajar], supaya saudara dapat turun kepada rakyat.” 66 lampiran-lampiran *** Tiga bab inti: Bab I SITUASI DUNIA; Bab II SITUASI INDONESIA; Bab III TUJUAN PKI. [PKI – Partai Komunis Indonesia – harap dibaca “Kekuatan Revolusioner”, karena memang demikianlah kenyataannya waktu itu – Pts]. Bab I SITUASI DUNIA: Perang Dunia I (1914-1918) telah memecah dunia antara negara-negara yang kalah dan yang menang perang, namun dua-duanya menderita secara ekonomi. Yang kalah bayar biaya dan pampasan perang, yang menang bayar biaya perang. Karena itu dua-duanya harus ditolong oleh para raja-uang Amerika Serikat seperti J.P. Morgan, melalui organisasi bantuan seperti Rencana Dawes (1924).Dua-duanya juga harus tunduk terhadap kekuatan modal tersebut, yang kalah menjadi negeri setengah-jajahan, yang menang menjadi sekutu yang patuh. Itu berarti kapitalisme bukannya terpukul seperti diharapkan segera setelah Revolusi Rusia (1917-1920), tapi agaknya bakal memperoleh masa damai untuk berkembang. Semua hal itu membuat kekuatan revolusioner menghadapi kesulitan menentukan sikap: bergerak dengan perkiraan kapitalisme segera akan runtuh atau kapitalisme akan berkembang dalam masa damai. Kesulitan ini diatasi dengan tidak memilih perkiraan yang mana pun, tapi membuat kekuatan revolusioner tidak boleh lupa dengan kesadaran pertentangan kelas sosial, yang kini bekerja pada tataran negara. Negaranegara yang menang perang bakal bersaing di bidang modal [kolonialisme dan imperialisme], sedang negara-negara 67 panggilan tanah air setengah jajahan karena kalah perang siap menanti kesempatan yang timbul akibat persaingan itu. Demikianlah Jepang menjadi pesaing besar di Asia, dan Jerman menanti kesempatan di Eropa. Dua-duanya “dapat menimbulkan perang dunia baru”. Sementara Jerman dan Jepang menanti kesempatan baik, pertentangan kelas sosial terus bergolak menuju kehancuran kapitalisme untuk diganti dengan sistem kemasyarakatan yang baru. Ternyata kekuatan revolusioner dunia sekarang jauh lebih terkait satu sama lain, makanya kekuatan revolusioner wajib bergerak sesuai dengan asas pertentangan kelas sosial, ada atau tidak ada peluang akibat persaingan dunia kapitalis. Kekuatan revolusioner patut memusatkan upaya untuk “membentuk di mana-mana Partai Rakyat Pekerja dan memperkuatnya, membawa massa yang menderita di bawah pimpinan kita dan akhirnya memperkuat ikatan dan setia-kawan internasional.” Dengan demikian “Jika nanti waktu untuk bertindak bagi kita telah datang,” kekuatan revolusioner sudah siap. *** Bab II SITUASI INDONESIA: Mengibaratkan kapitalisme sebagai gedung, Indonesia adalah satu di antara tiang yang mendukung gedung itu. Kita tahu, cepat atau lambat, gedung itu pasti runtuh, tapi kita tidak tahu bagaimana runtuhnya. Gelombang politik ekonomi dunia akibat Perang Dunia I telah mematahkan satu tiangnya yang rapuh, kapitalisme Rusia, dan seluruh gedung terancam runtuh. Sayang, “datang budak-budaknya, yaitu kaum Sosial Demokrat” untuk menyelamatkannya. Jadi kita kaum 68 lampiran-lampiran revolusioner Indonesia tidak boleh menunggu gedung itu runtuh baru bertindak, karena kalau “kapitalisme kolonial di Indonesia besok atau lusa jatuh, kita [sudah] harus mampu menciptakan tata-tertib baru yang lebih kuat dan sempurna di Indonesia.” Sementara “[k]apitalisme Eropa dan Amerika didukung [oleh] kaum Sosial Demokrat”, sedang “ [d]i tanah-tanah jajahan seperti: Mesir, India, [...] dan Filipina, imperialisme yang sedang goyah didukung oleh borjuis nasional, [...] di Indonesia tak ada [...] yang mampu menolong [...]. Pertentangan antara rakyat Indonesia dan imperialisme Belanda [terjadi secara langsung, dan] makin lama [...] makin tajam. [...] Suara merdu politik etis [sudah] diganti dengan [...] tongkat karet [...] dan gemerincing pedang.” Pertentangan seperti itulah yang berkobar di Bandung, Sumedang, Ciamis, dan Sidoarjo, utamanya sejak Februari 1925. “Rakyat Indonesia di bawah [...] siksaan di luar batas prikemanusiaan tetap menuntut hak-hak kelahirannya [hak-hak asasi].” Itulah “hak-hak yang semenjak puluhan tahun yang lalu telah diakui di Eropa dan Amerika, tapi oleh imperialisme Belanda dijawab dengan tindakan-tindakan biadab.” Namun demikian, “tongkat karet dan pistol tak akan mampu mengundurkan rakyat yang sedang melangkah maju.” “Politik apakah yang harus kita lakukan pula sekarang?” Jawabannya tergantung pada kemampuan kaum revolusioner untuk melihat kenyataan sosial Indonesia dengan kacamata pertentangan kelas. “ Lebih dari 300 tahun imperialisme Belanda 69 panggilan tanah air melakukan politik ‘gertakan’ dan ‘tindasan’. Belum pernah politik semacam itu oleh rakyat Indonesia [...] disambut dengan terangterangan dan sewajarnya, sebagaimana telah terjadi pada 1 Pebruari [1925].” Sambutan ini berbeda dengan aneka perlawanan sebelumnya seperti Perang Jawa atau Perang Aceh. Perlawanan ini berkobar “karena sumpah, jimat, suara gaib atau segala kegelapan-kegelapan feodal”, sedang perlawanan sejak Februari 1925 “karena hak-hak yang nyata dan wajar sebagai manusia [hak-hak asasi]”. Kini penjajah “berkata kepada diri sendiri ‘Orang Indonesia tak dapat lagi digertak dan ditindas’”. Orang Indonesia menimpali, “’Selamat jalan jiwa-jiwa budak [...] buat selama-lamanya’”. Perlawanan seperti barusan dikemukakan akan membuat imperialisme Belanda menyadari bahwa “lebih dari yang sudahsudah, [...] ucapan Multatuli akan lantang bergema di kupingnya: ‘Jika setiap orang Jawa meludah ke tanah, maka mati tenggelamlah orang-orang Belanda’”. Karena itu “akan dibicarakan cara memperbaiki keadaan ekonomi rakyat” dan “memberikan hak-hak politik lebih banyak kepada golongan orang Indonesia tertentu”. Namun demikian, karena “mengenal susunan sosial-ekonomi Indonesia”, kekuatan revolusioner Indonesia tahu bahwa “pemegang kekuasaan itu tak akan dapat selangkah [pun] keluar dari lingkungan sempit birokrasinya.” Imperialisme Belanda tak akan “[dapat] dengan seketika [...] memperbaiki kesalahankesalahan yang telah berlangsung berabad-abad dengan serentak.” 70 lampiran-lampiran Kesalahan-kesalahan tersebut menjadi jelas dengan perbandingan. Inggris yang menjajah India membiarkan “industri nasional yang kuat” berkembang sehingga “di sana [terdapat] jembatan untuk menghubungkan [...] modal Inggris dengan modal nasional” dan “menghubungkan politik imperialisme dan politik nasional. Tetapi politik imperialisme Belanda sejak semula [sengaja menghancurkan] industri kecil dan perdagangan kecil nasional, teristimewa di Jawa.” Akibatnya “mati jugalah kerajinan dan inisiatif suku Jawa” yang mestinya mampu membangun “industri nasional modern”. Akibat lebih jauh lagi, imperialisme Belanda tidak bisa “mendapatkan titik pertemuan untuk suatu kompromi ekonomi dengan orang-orang Indonesia. Berhubungan dengan itu suatu kompromi dalam politik [akan sulit pula]”. Apa saja yang akan coba dilakukan oleh imperialisme Belanda untuk membuka kompromi itu “akan hanya berarti satu tetes air di atas besi yang membara”. Itu berarti “krisis Indonesia bukan hanya krisis politik, seperti di Mesir, India-Inggris, dan Filipina, akan tetapi juga terutama adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini tak akan dapat disembuhkan dalam beberapa tahun.” Karena itu “[...] imperialisme Belanda tak akan mungkin mendekati rakyat Indonesia dengan memberikan konsesi politik dan ekonomi, ia harus melakukan politik biadab yang lama, warisan dari Oost Indische Compagnie”. “Marx pernah berkata: ‘Proletariat tak akan kehilangan sesuatu miliknya, kecuali belenggu budaknya’. Kalimat ini dapat kita gunakan di Indonesia lebih luas. Di sini anasir-anasir bukan 71 panggilan tanah air proletar berada dalam penderitaan yang sama dengan buruh industri, karena di sini tak ada industri nasional, perdagangan nasional”. *** Bab III TUJUAN PKI. “Tujuan Partai-partai Komunis dunia ialah menggantikan sistem kapitalisme dengan komunisne.” Namun, penggantian ini tidak bisa serta-merta. Perlu suatu masa peralihan yang tidak bisa dipastikan lamanya. “Dalam masa peralihan ini, proletariat melakukan diktatur atas borjuasi. [...]. Sovyet adalah perwujudan diktatur proletariat. Tujuan Sovyet ialah menghapuskan kapitalisme dan mempersiapkan tumbuhnya komunisme.” Selama masa peralihan, diktatur proletariat menasionalisasi industri-industri yang penting, artinya diserahkan kepada negara proletar. Dengan nasionalisasi, hak milik pribadi dihapus. “Dengan demikian akan hapuslah anarchisme dalam produksi, yaitu: menghasilkan barang [...] yang satu sama lain tidak ada sangkut-pautnya [...] Sebagai gantinya diadakanlah rasionalisasi, yaitu menghasilkan barang-barang keperluan hidup menurut kebutuhan masyarakat. Dengan hapusnya hak milik perseorangan dan anarki dalam produksi, persaingan juga akan hapus” dan hilang pulalah semua kelas sosial seperti kelas proletar dan kelas borjuasi. “Dengan hapusnya persaingan, tak akan berlaku lagi politik imperialisme, yaitu politik modal-bank sesuatu negara kapitalis 72 lampiran-lampiran untuk [menjajah] negara-negara [lain guna menampung] kelebihan hasil pabriknya [...]. Sebagai gantinya tersusunlah hak milik bersama, produksi terencana, penukaranproduksi dengan sukarela dan internasionalisme, yaitu: perdamaian, kerjasama dan persaudaraan antara berbagai bangsa di dunia.” Pendeknya terciptalah masyarakat komunis, masyarakat tanpa kelas sosial. “Apa yang diuraikan di atas adalah teori komunis yang bisa menjadi kenyataan jika kapitalisme dunia jatuh serentak, sebagaimana yang hampir-hampir terjadi pada tahun-tahun pertama sesudah revolusi Bosjewiki di Rusia.” Ternyata kapitalisme dunia tidak runtuh serentak, malah tertolong oleh golongan sosial demokrat. Bolsjewiki Rusia pun “mengadakan langkah mundur pada tahun 1921. Langkah mundur ini harus diterima dalam arti ekonomi dan taktik. [...] Negara Sovyet mengijinkan berlakunya kembali hak milik perseorangan kepada petani-petani yang merupakan 80% [...] penduduk Rusia dan kepada borjuis-borjuis kecil di kota-kota.” Perdagangan pun dilakukan “atas dasar kapitalisme”. Pendeknya para petani dan borjuis kecil “dapat ditarik dalam barisan pendukung Negara Buruh”. Inilah yang disebut PEB (Politik Ekonomi Baru). PEB tidak hanya berlaku “khusus di Rusia yang terbelakang”, tapi juga di negeri-negeri kapitalis. Jika demikian halnya, PEB lebih penting lagi berlaku di Indonesia yang kapitalismenya bersifat “kolonial dan tidak tumbuh secara tersusun dari masyarakat Indonesia sendiri [...] Ia dipaksakan dengan kekerasan oleh suatu negeri imperialis Barat dalam masyarakat feodal Timur”. Dirumuskan lain “proletariat Indonesia berada 73 panggilan tanah air lebih rendah daripada proletariat Eropah Barat dan Amerika. Diktator proletariat yang tulen akan dapat membahayakan peri penghidupan ekonomi di Indonesia, terlebih jika revolusi dunia tak kunjung datang. Akibatnya [...] bagian yang terbesar daripada penduduk, yaitu orang-orang yang bukan proletar, sangat mudah dihasut melawan buruh Indonesia yang kecil jumlahnya.” “Untuk menjamin peri penghidupan ekonomi di Indonesia dalam kemerdekaan nasional yang mungkin datang, kepada penduduk yang bukan proletar harus diberikan kesempatan [...] mengusahakan hak milik perseorangan dan perusahaanperusahaan kapitalis. Sudah barang tentu, perusahaanperusahaan besar harus segera dinasionalisir. Dengan demikian kegiatan ekonomi rakyat dapat dikembangkan tanpa kekuatiran akan datangnya [kelas-kelas] lainnya. Dengan demikian perimbangan ekonomi antara proletar dan bukan proletar dapat dicapai dan dipertahankan.” “Memang kita harus selalu ingat bahwa buruh [Indonesia] menurut kualitas dan kuantitasnya ada rendah, sedang orangorang bukan proletar [berjumlah] besar dan revolusioner. [...] Karenanya dalam ‘INDONESIA MERDEKA’ cara bagaimana pun kepada orang-orang bukan proletar harus diberikan kesempatan mengeluarkan suaranya. Akan tepat adanya, jika buruh dalam perang kemerdekaan nasional yang mungkin datang, mewujudkan barisan pelopor [bagi] seluruh rakyat, maka perusahaan-perusahaan besar akan jatuh di tangannya, dan selaras dengan itu kekuasaan politik. Perimbangan politik dengan 74 lampiran-lampiran orang-orang bukan proletar akan mudah ... diciptakan, yang ... sangat penting adanya bagi Indonesia Merdeka.” Perkembangan selanjutnya “tergantung kepada keadaan internasional dan lebih lanjut pada perkembangan industri di Indonesia sendiri.” *** Sembilan sub-judul lain semuanya menyangkut program nasional, strategi dan taktik. Betapa penting pun kesembilan sub-judul ini, semuanya tidak mengubah konsistensi tiga bab inti yang diringkas di atas. Apa yang sekarang ini disebut “visi dan misi” politik sudah tercakup dalam tiga bab inti tersebut. Oleh karena itu kesembilan sub-judul itu tidak diringkas dalam kesempatan ini. % (Parakitri T. Simbolon, 21 Juni 2009) Sumber: http://zamrudkatulistiwa.com/2009/06/21/naar_de_republiek_ indonesia_/ (unduh terakhir pada 5 Mei 2015) 75 Lampiran 1b Mohammad Hatta (1932) Ke Arah Indonesia Merdeka [Ringkasan dibuat oleh Parakitri T. Simbolon] Tulisan tentang “visi-misi” Bung Hatta ini pertama kali terbit pada 1932 berbentuk brosur berisi asas dan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia, kemudian dimuat dalam buku bunga-rampainya, Kumpulan Karangan, jilid I (Djakarta: Balai Buku 1952-53, empat jilid). Ringkasan ini disusun berdasarkan karya yang sama yang dimuat dalam Karya Lengkap Bung Hatta (Buku 1): Kebangsaan dan( Kerakyatan (Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1998) hlm 211- 30. Brosur ini langsung mulai dengan semacam pengantar tanpa sub-judul, lalu seterusnya terdiri dari tiga subjudul: “I. Kebangsaan”; “II. Kerakyatan”; dan “Arti Kedaulatan Rakyat bagi Pergerakan Sekarang”. Pengantar tanpa judul “Pendidikan Nasional Indonesia menuju Indonesia Merdeka! Dan pasal 2 daripada Peraturan Dasar menyebut, bahwa perkumpulan berasas Kebangsaan dan Kerakyatan”. Dua kata ini sering “menjadi buah bibir ... sekarang” tapi sekaligus banyak orang yang “menyangka [...] kedua-dua pengertian itu sekarang tidak laku lagi.” 76 lampiran-lampiran Menurut orang itu yang laku adalah “’semangat internasional’”, dengan Jenewa, Swis, sebagai “pusat ‘pergaulan internasional’”. Lalu mereka berkata: “Tidakkah kita tersesat, kalau kita masih gila dasar kebangsaan? Dan apakah pergerakan kita nanti tidak mundur ke belakang kembali?” Mereka juga bilang: “[B]ukankah orang sudah bosan [dengan] ‘kerakyatan’ dan ‘demokrasi’?” Yang benci terhadap‘kerakyatan’ dan ‘demokrasi’ bukan hanya golongan bangsawan dan fasis tapi juga kaum komunis. “Tidakkah Mustafa Kemal, pemimpin Turki Muda, [malah] kembali dari demokrasi ke diktatur? Jikalau sekarang kaum radikal ... kanan dan ... kiri [di mana-mana] sudah memuntahkan dasar kerakyatan, mestikah kita membangkitkan dan meninggikannya lagi?” Begitulah keberatan banyak orang terhadap “‘kebangsaan’” dan “’kerakyatan’”.Namun, “siapa yang menyelidiki [sejarah] dunia dengan betul” tahu bahwa keberatan banyak orang itu “lemah sekali”. Memang soal kebangsaan dan kerakyatan tidak mudah, apalagi kalau dua-duanya jadi “sepasang” pengertian. Namun, “[j]ika diperhatikan pula sejarah pergerakan kemerdekaan di ... dunia ini dan susunan masyarakat zaman sekarang, maka jelaslah ... bahwa dasar ‘dua sepasang’ itu kuat dan cocok dengan keperluan pergerakan Indonesia di masa sekarang.” “I. Kebangsaan” “Pendidikan Nasional Indonesia bersifat kebangsaan karena ia 77 panggilan tanah air menuju Indonesia Merdeka, yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air. [...] Tidak ada pergerakan kemerdekaan yang terlepas dari semangat kebangsaan.” Jika perdamaian antarbangsa dan manusia itu baik, maka hal itu hanya mungkin terwujud bila lebih dulu “ada kemerdekaan bangsa. Hanya bangsa-bangsa dan manusia yang sama derajat dan sama merdeka [yang] dapat bersaudara. Tuan dan budak [tidak dapat] bersaudara.” “Oleh sebab itu tidak salah langkah Pendidikan Nasional Indonesia, kalau ia berdasar kebangsaan. Ia tidak pula memundurkan kembali pergerakan kita karena itu, malainkan memajukan dan memperkuat rohnya.” T idak hanya itu. “Sejarah dunia memperlihatkan [...][betapa] kuatnya roh kebangsaan itu. [...] Cinta bangsa dan tanah air sudah menjadi nyanyian yang merdu di telinga orang banyak, istimewa bangsa yang tidak merdeka, karena bangsa itu menjadi ukuran manusia dalam pergaulan internasional.” Namun, “kita [juga] insaf” bahwa kebangsaan “dapat dipergunakan oleh satu golongan saja, misalnya kaum majikan, untuk memuaskan hawa nafsunya. Rakyat ... dipakai sebagai perkakas saja.” Harus juga diakui, “rakyat menjadi perkakas [...] sebagian besar tergantung [pada] didikan rakyat. Rakyat yang bersifat ... budak memang sudi mengorbankan diri untuk golongan yang dipertuan [...]. Akan tetapi rakyat yang sadar akan harga dirinya tidak mudah disuruh berbuat demikian, [apalagi] rakyat yang insaf akan kedaulatan dirinya!” Sesungguhnya semangat internasionalisme kalah dengan 78 lampiran-lampiran “semangat kebangsaan”. Ambil Irlandia sebagai contoh sesudah PD I “tatkala [bangsa itu] berjuang melawan Inggris untuk mencapai kemerdekaannya.” Labour Party Irlandia sudah berupaya “menanam bibit internasionalisme dan persaudaraan umum”, tapi usaha itu gagal. Kaum buruh Irlandia tetap “berpihak kepada partai Sinn Fein yang semata-mata berdasar kebangsaan. Pada pemilihan umum untuk parlemen Irlandia, Labour Party hampir tidak dapat suara.” Hal yang sama terjadi di India, Mesir, Tiongkok, dan juga Indonesia sehubungan dengan PKI. “Partai ini memakai dasar internasionalisme dan program serta janji-janjinya sangat menarik hati rakyat .... [Tapi], PKI sendiri tidak sanggup menarik orang banyak ke dalam golongannya. Supaya dapat pengaruh atas rakyat, [PKI] terpaksa mendirikan suatu anak partai, yaitu Sarekat Rakyat, yang tiada berdasar komunisme, melainkan bersifat nasionalisme radikal. Sebagian besar mereka adalah “kaum saudagar-saudagar kecil.” [...] “Kalau ada partai yang menyebut sifatnya ‘internasional’, itu cuma nama saja, batinnya nasional juga!” Kenyataan ini tidak hanya ada di negeri jajahan, tapi juga di Eropa. Dalam Perang Dunia I, “kaum buruh Jerman berbunuhbunuhan dengan kaum buruh Perancis”, padahal dua-duanya berasaskan internasionalisme. Lagipula, kaum buruh Jerman di bawah panji sosial demokrat bersatu dengan “kaum kapitalis untuk membela tanah air Jerman.” “Sebab itu Pendidikan Nasional Indonesia daripada memakai topeng internasional palsu, lebih baik terus terang memakai baju kebangsaan, nasionalisme yang benar!” Kebangsaan yang benar 79 panggilan tanah air perlu ditegaskan karena “[k]ebangsaan ada bermacam-macam menurut rupa dan warna golongan yang memajukannya. Ada kebangsaan cap ningrat, ada kebangsaan cap intelek dan ada pula kebangsaan cap rakyat.” “Jikalau kaum ningrat menyebut Indonesia Merdeka, maka [yang] terbayang di muka mereka [adalah] suatu Indonesia yang terlepas dari tangan Belanda, akan tetapi takluk ke bawah kekuasaan mereka. Dari zaman dulu kala sampai ... sekarang kaum ningrat ... tetap menjadi golongan pemerintah.” Di bawah kerajaan dulu, mereka “menjadi tunjangan raja-raja itu, menjadi tiang kekuasaan otokrasi dan feodalisme.” Demikian juga sekarang di zaman penjajahan Belanda, kaum ningrat, “Inlandsche Hoofden”, dibuat langsung memerintah rakyat demi kekuasaan penjajah. “Bagaimana pula rupa kebangsaan ... cap ... intelek? Menurut paham kaum intelek, kaum terpelajar atau ... cerdik pandai, Indonesia Merdeka haruslah berada di bawah kekuasaan mereka sendiri. Negeri tidak maju dan makmur kalau tidak dikemudikan oleh orang yang berpengetahuan tinggi. Bagi mereka, orang menjadi orang pemerintah bukan karena keturunannya, melainkan karena kecakapan sendiri. Bukan bangsawan karena darah yang mereka akui, melainkan bangsawan karena otak dan kecakapan.” Menurut mereka, karena “miskin dan alpa dan terpaksa pula bekerja keras” untuk bisa hidup, “rakyat tidak mempunyai waktu untuk memikirkan politik dan keselamatan negeri. [Oleh] sebab 80 lampiran-lampiran itu tidak wajib rakyat [...] diberi [hak] suara tentang urusan negeri. [...]. [N]asib rakyat dan urusan negeri ada di tangan kaum intelek. Mereka mengumpamakan diri mereka sebagai dewa orang banyak. [...] Nyatalah bahwa rakyat, [...], tidak lain daripada perkakas kaum intelek saja.” “[B]ukan kebangsaan ningrat dan bukan pula kebangsaan intelek yang dikehendaki oleh Pendidikan Nasional Indonesia, melainkan kebangsaan rakyat! ‘Karena rakyat itu badan dan jiwa bangsa’. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendah derajat kita. [...] Hidup atau matinya Indonesia Merdeka ... tergantung kepada semangat rakyat. [...] [K]aum terpelajar baru ada berarti, kalau di sampingnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya.” “Sebab itu menurut keyakinan Pendidikan Nasional Indonesia, kebangsaan itu haruslah dihinggapi semangat rakyat, jadi berdasar kerakyatan!” “II. Kerakyatan” “Seperti halnya soal kebangsaan, pengertian tentang kerakyatan bermacam-macam pula, menurut sifat golongan yang menganjurkannya. ... Kerakyatan yang dipahamkan oleh Pendidikan Nasional Indonesia sebagai asas yang kedua ... berlainan daripada cita-cita kerakyatan yang biasa, tiruan dari demokrasi Barat. Dalam pasal 2 Peraturan Dasar [Pendidikan Nasional Indonesia] ditulis:” 81 panggilan tanah air Asas Kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht; peraturan-peraturan negri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau [hukum itu berdasarkan] kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi pangakuan oleh segala jenis manusia yang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Agar asas kerakyatan ini terwujud dalam Indonesia Merdeka, “haruslah rakyat insaf akan haknya dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri dan perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul. Pendeknya, cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. [...] [R]akyat itu [adalah] daulat alias raja atas dirinya. Tidak lagi orang seorang atau sekumpulan orang pandai atau satu golongan kecil saja yang memutuskan nasib ... bangsa, melainkan rakyat sendiri. Inilah arti Kedaulatan Rakyat! Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya, [t]idak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan sosial ...; keputusan dengan mufakat rakyat yang banyak.” Asas “kedaulatan rakyat yang menjadi dasar Pendidikan Nasional Indonesia” ini berbeda sekali “dengan demokrasi cara Barat [...]”, yang dikenal juga dengan moderne democratie. Rakyat memerintah diri sendiri dengan perantaraan Badan-badan Perwakilan, yang susunannya dipilih oleh rakyat sendiri. Akan 82 lampiran-lampiran tetapi melakukan asas-asas demokrasi itu berbeda-beda dalam praktek, menurut keperluan golongan masing-masing. Sebab itu ada conservatieve democratie, ada liberale democratie, ada vrijzinnige democratie, dan ada pula sociale democratie. Mana golongan yag kuat atau berpengaruh besar, itulah yang memberi rupa kepada demokrasi tadi.” “[S]usunan demokrasi itu masing-masing” tidak akan dibicarakan. “Cukuplah buat pengetahuan, bahwa di waktu sekarang kaum kapitalis yang berkuasa di benua Barat. Oleh sebab itu demokrasi di sana memakai rupa kapitalistische democratie yang juga dinamai burgerlijke democratie. Dan (cita-cita moderne democratie yang begitu bagus ... tidak berlaku lagi. [...].” Penyimpangan cita-cita demokrasi modern di Barat itu bersumber dalam individualisme yang menjadi dasarnya. Seperti mula-mula dirumuskan oleh filsuf Prancis J.J. Rousseau dalam dasawarsa-dasawarsa pertengahan kedua abad ke-18, individualisme adalah keyakinan bahwa “manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka”. Oleh karena itu, pemerintahan otokrasi yang “ditunjang oleh kaum ningrat [atau] foedalisme” ditentang keras lalu dirobohkan oleh semangat individualisme itu. Dengan demikian semangat individualisme “memberi kemerdekaan kepada orang-orang untuk menentukan nasib sendiri”. Namun, karena sumber daya masih tetap dikuasai oleh segelintir orang, kemerdekaan orang per orang itu tidak menghasilkan “demokrasi enonomi”, tapi hanya “demokrasi politik”. Timbul perpecahan sosial melalui “perjuangan kelas kasta”. 83 panggilan tanah air Revolusi individualisme atau “individueele revolutie” di Prancis dengan serentak ditimpali dengan revolusi industri atau “industrieele revolutie” di Inggris. Maka revolusi ganda itu melahirkan “Kapitalisme Modern”. Jadi, “[s]emangat individualisme memajukan politik liberalisme dan liberalisme memperkuat roh kapitalisme. Dalam politik [...] tiap-tiap manusia lahir merdeka dan hidup merdeka.” Makanya tidak aneh kalau dalam konstitusi pertama Prancis hasil revolusi orang dilarang berserikat. Akibatnya celaka bagi buruh, karena mereka tidak bisa lagi mengandalkan serikat sekerja untuk membela kepentingan sendiri terhadap majikan. Sebaliknya majikan boleh berbuat apa saja, karena “[d]alam ekonomi, semangat individualisme [...] [berarti] laissez faire, laissez passer”, yang berarti boleh berbuat sesuka hati. “Jadinya, demokrasi Barat [...] tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menegakkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu Kedaulatan Rakyat. Harus ada pula demokrasi ekonomi ... [yaitu] bahwa segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga”. Dirumuskan lain “[b]agaimana pemerintahan negeri harus dijalankan dan bagaimana caranya rakyat mesti hidup, semuanya itu harus merupakan hasil keputusan rakyat atas mufakat.” Mufakat ini merupakan “sifat kemasyarakatan (gemeenshap)” bangsa kita “semenjak zaman purbakala”. Itulah sendi “demokrasi asli Indonesia.” Namun, bagaimana pun “bagusnya 84 lampiran-lampiran di masa dahulu, [demokrasi asli kita itu] tidak [lagi] mencukupi di waktu sekarang”. Lagi pula demokrasi asli kita itu “hanya terdapat pada pemerintahan desa saja”, sedang “[p]emerintahan di atas semata-mata berdasarkan otokrasi. Di atas otonomi desa berdiri ‘Daulat Tuanku’ yang [bertindak] sewenang-wenang [...]. Kita harus melanjutkan demokrasi asli menjadi Kedaulatan Rakyat, supaya terdapat peraturan pemerintahan rakyat untuk Indonesia seumumnya. ‘Daulat Tuanku’ (Raja) mesti diganti dengan ‘Daulat Rakyat’!” [...] “Sekarang jelaslah apa yang disebut di atas, bawa Kedaulatan Rakyat yang dimajukan oleh Pendidikan Nasional Indonesia sungguh pun baru, sebenarnya tidak asing bagi rakyat Indonesia, karena tersusun di atas demokrasi tua yang ada di tanah air kita. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang. Sepadan dengan betul dengan semangat demokrasi asli Indonesia, cita-cita Kedaulatan Rakyat paham Pendidikan Nasional Indonesia berdasar pada rasa-bersama, kolektivitas!” “Arti Kedaulatan Rakyat bagi Pergerakan Sekarang” “Sekarang kita maklum, bahwa cita-cita yang di atas hanya dapat dicapai, kalau Indonesia sudah merdeka serta rakyat Indonesia sudah memerintah dirinya sendiri dan kalau hukum dan undangundang negeri cocok dengan perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam sanubari rakyat yang banyak.” 85 panggilan tanah air “Bahwa Indonesia lambat laun mesti merdeka, itu tidak dapat disangkal lagi. Itu sudah Hukum Riwayat [Hukum Sejarah]! Indonesia Merdeka bukan perkara dapat atau tidak, hanya perkara waktu saja.” “Sebab itu apa yang diucapkan oleh Pendidikan Nasional Indonesia tidak tinggal di awang-awang, melainkan berarti pada waktu sekarang, selagi rakyat dalam perjuangan.” “Dari mulai sekarang cita-cita Kedaulatan Rakyat harus ditanam di dalam hati rakyat! Kalau tidak, rakyat tidak akan insaf akan harga dirinya, tidak tahu, bahwa ia raja atas dirinya sendiri, sehingga ia tidak mudah tunduk ke bawah kekuasaan apa dan siapa juga. Dan kalau Indonesia sampai merdeka, ia akan tinggal tertindas, karena kekuasaan tentu jatuh ke dalam tangan kaum ningrat, sebab merekalah yang banyak mempunyai orang cerdik pandai. Dan dalam Indonesia Merdeka yang seperti itu tidak berarti rakyat merdeka!” “[...]”( “Sebab itu Pendidikan Nasional Indonesia mendidik rakyat, supaya insaf akan kedaulatan dirinya dan paham kepada makna dan maksud dasar Kedaulatan Rakyat. [...].” “Jalan yang dipakai oleh Pendidikan Nasional untuk mencapai tujuan itu ialah terutama mendidik rakyat dalam hal-hal politik, ekonomi, dan sosial dengan memperhatikan asas-asas Kedaulatan Rakyat.” “[...]” 86 lampiran-lampiran “Moga-moga Pendidikan Nasional Indonesia lekas mendapat perhatian daripada rakyat jelata, sebagai pohon yang rindang tempat marhaen Indonesia berlindung, dan sebagai langgar umum, tempat rakyat mengasah budi dan pekerti.” % (Parakitri T. Simbolon, 24 Juni 2009) Sumber: http://zamrudkatulistiwa.com/2009/06/24/ke_arah_indonesia_ merdeka/ (unduh terakhir pada 5 Mei 2015) 87 Lampiran 1c Soekarno (1933) ”Mencapai Indonesia Merdeka” [Ringkasan dibuat oleh Parakitri T. Simbolon] Ringkasan “visi-misi” Bung Karno ini berdasarkan “Mencapai Indonesia Merdeka” dalam Ir. Soekarno, Di bawah Bendera Revolusi (Djakarta: Panitya Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, 1964), jilid pertama, cetakan ketiga, hlm. 257-324. Seperti diungkapkan di bagian awal karya ini, Soekarno menuliskannya di Pangalengan pada 30 Maret 1933. Pangalengan, suatu kota kecil pegunungan di sebelah selatan kota Bandung. “[S]ekembali ... dari ... tournée ... ke Jawa Tengah ... membangkitkan Rakyat sedjumlah 89.000 orang,” Soekarno “berpakansi beberapa hari [di sana] melepaskan kelelahan badan.” Ia sendiri menyebut karyanya ini “risalah”, juga “vlugschrift”, yang dua-duanya berarti karangan ringkas, brosur, pamflet. Risalah ini ditujukan kepada “orang yang baru mendjejakkan kaki di gelanggang perjoangan”. Agar tidak “terlalu tebal” dan “terlalu mahal”, “hanya garis-garis besar sahaja” yang dikemukakan. “Mitsalnya fatsal ‘Di Seberang Jembatan Emas’ kurang jelas, sehingga akan dipaparkan lebih rinci dalam karya lain. 88 lampiran-lampiran Di luar pengantar yang tanpa sub-judul, risalah ini terdiri dari 10 sub-judul: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sebab-sebabnya Indonesia Tidak Merdeka Dari Imperialisme-Tua ke Imperialisme-Modern “Indonesia, Tanah Yang Mulya, Tanah Kita Yang Kaya; (Di sanalah kita Berada, untuk Selama-lamanya” ...) “Di Timur Matahari Mulai Bercahaya, Bangun dan Berdiri, Kawan Semua”... Gunanya Ada Partai Indonesia Merdeka Suatu Jembatan Sana Mau ke Sana, Sini Mau ke Sini Machtsvorming, Radikalisme, Massa-Aksi Diseberangnya Jembatan Emas Mencapai Indonesia-Merdeka! 1. Sebab-sebabnya Indonesia Tidak Merdeka Risalah mulai dengan menolak tesis “Professor Veth” bahwa Indonesia “tidak pernah merdeka [...] dari zaman Hindu sampai sekarang [...] Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan: mulamula jajahan Hindu, kemudian jajahan Belanda.” Namun sejarah menunjukkan yang sebaliknya: “[K]aum yang kuasa di dalam zaman Hindu itu [...] tidak terutama sekali kaum penjajah [...]. Mereka bukanlah kaum yang merebut kerajaan, tetapi mereka sendirilah yang mendirikan kerajaan di Indonesia! Mereka menyusun staat Indonesia, yang tahadinya tidak ada staat Indonesia!” Hubungan kerajaan Indonesia itu dengan Hindustan “bukanlah perhubungan kekuasaan, [...] tetapi ialah 89 panggilan tanah air perhubungan peradaban, perhubungan cultuur.” [...] “Negeri Indonesia ketika itu merdeka, – tetapi penduduk Indonesia, Rakyat-jelata Indonesia, Marhaen Indonesia ... tidak pernah merdeka.” Namun begitulah nasib semua rakyat jelata di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Mereka “diperintah oleh raja-rajanya secara feodalisme: Mereka hanyalah menjadi perkakas sahaja dari raja-raja itu dengan segala balakeningratannya ...”. Karena itu sebab-sebabnya Indonesia dijajah, tidak merdeka, harus dicari dalam masa “[t]iga empat ratus tahun yang lalu, di dalam abad keenam belas ketujuh belas ... ketika “feodalisme Eropah” surut dan diganti dengan “vroeg-kapitalisme”, kapitalisme tua, yaitu timbulnya kelas “pertukangan dan perdagangan, yang giat sekali berniaga di seluruh benua EropaBarat.” Kelas kapitalis ini semakin kuat sampai dapat mencapai “kedudukan kecakrawartian”, kuasa pemerintahan. Segera Eropa menjadi sempit bagi kapitalisme tua itu, sehingga “timbullah suatu nafsu, suatu stelsel” untuk menguasai “benuabenua lain, – terutama sekali di benua Timur, di benua Azia!” Itulah “imperialisme”. Sementara itu “... masyarakat Indonesia khususnya, masyarakat Azia umumnya, pada waktu itu kebetulan sakit”, maksudnya “suatu masyarakat ‘in transformatie’ ..., yang sedang asyik ‘berganti bulu’: “[dari] feodalisme-kuno” atau “feodalisme 90 lampiran-lampiran Brahmanisme” ke “feodalisme-baru, feodalismenya ke-Islaman, yang sedikit lebih demokratis ...”. Masa ‘berganti bulu” itu tercermin antara lain dalam “pertempuran antar Demak dan Majapahit, atau Banten dan Pajajaran”. Pertempuranpertempuran itu “membikin badan masyarakat menjadi ‘demam’ dan menjadi ‘kurang-tenaga’, dan lambat-laun dikalahkan oleh kapitalisme-tua Eropa melalui nafsu imperialismenya. 2. Dari Imperialisme-Tua ke Imperialisme-Modern “Tahukah pembaca bagaimana mekarnya imperialisme itu, ... dari imperialisme-kecil menjadi imperialisme raksasa [...,] dari imperialisme-tua menjadi imperialisme modern?” Untuk itu pembaca perlu tahu lebih dulu bahwa “[i]mperialisme adalah anaknya kapitalisme. Imperialisme-tua dilahirkan oleh kapitalisme-tua, imperialisme-modern dilahirkan oleh kapitalisme-modern. [Namun] [w]ataknya kapitalisme-tua adalah berbeda besar dengan wataknya kapitalisme-modern. [...] Maka imperialisme-tua yang dilahirkan oleh kapitalisme-tua itu, – imperialismenya [VOC] dan ... [Tanam Paksa] – ... niscayalah satu watak dengan ‘ibunya’, yakni watak-tua, watak-kolot, watakkuno.” Watak kuno imperialisme-tua itu “menghantam ke kanan dan ke kiri, [menjalankan] stelsel monopoli dengan kekerasan dan kekejaman ... mengadakan sistim paksa ..., membinasakan ribuan jiwa manusia, menghancurkan kerajaan-kerajaan ..., membasmi milliunan tanaman cengkeh dan pala .... Ia melahirkan aturan contingenten [pajak berupa hasil bumi] dan leverantien [hak 91 panggilan tanah air monopoli beli hasil bumi] yang sangat berat dipikulnya oleh Rakyat [...].” “Tetapi lambat-laun di Eropah modern-kapitalisme mengganti vroeg-kapitalisme yang sudah tua-bangka. Paberik-paberik, bingkil-bingkil, bank-bank, pelabuhan-pelabuhan, kota-kota industri timbullah seakan-akan jamur di musim dingin, dan tatkala modern-kapitalisme ini sudah dewasa, maka modalkelebihannya alias surplus kapital-nya lalu ingin dimasukkan di Indonesia ...”. Mereka tidak sabar menunggu di pintu gerbang Indonesia. Mereka memekik dengan semboyan-semboyan seperti kebebasan buruh, kebebasan menyewa tanah, persaingan bebas. “Dan akhirnya, pada kira-kira tahun 1870, dibukalah pintu gerbang itu!” Maka masuklah “modal-partikelir di Indonesia, – mengadakan paberik-paberik gula di mana-mana, kebon-kebon teh di mana-mana, onderneming-onderneming tembakau di mana-mana, dan lain sebagainya ...”. “Cara pengambilan [rezeki dengan jalan monopoli] berobah, sistimnya berobah, wataknya berobah, tetapi banyakkah perobahan bagi Rakyat Indonesia? Banjir harta yang keluar dari Indonesia bukan semakin surut, tetapi malahan makin besar, drainage Indonesia malahan makin [besar].” Maka sejak “adanya opendeur politiek [politik pintu terbuka] di dalam tahun 1905, maka modal yang boleh masuk ke Indonesia dan mencari rezeki di Indonesia bukanlah lagi modal Belanda sahaja, tetapi juga modal Inggeris, juga modal Amerika, juga modal Jepang, juga modal Jerman, juga modal Perancis, juga modal Italia, juga modal lain-lain, sehingga imperialisme di Indonesia kini adalah 92 lampiran-lampiran imperialisme yang internasional karenanya. Raksasa ‘biasa yang dulu ... kini sudah menjadi raksasa Rahwana Dasamuka yang bermulut sepuluh!” Drainase itu digambarkan dengan perbandingan antara ekspor dan impor untuk 1924-1930. Rata-rata jumlah ekspor/tahun f 1.527.799.571, sedang rata-rata jumlah impor/tahun f 875.917.143. Jadi rata-rata rasio ekspor dan impor adalah 174/100, sedang rasio tertinggi 226/100 dan terendah 135/100. “Sedang bandingannya ekspor/impor di negeri-negeri jajahan yang lain-lain ada ‘mendingan’, [dan] bandingan itu di dalam tahun 1924: Afrika Selatan 119/100; Filipina 123/100; India 123/100; Mesir 129/100, Sri Lanka 133/100. “[M]aka buat Indonesia, ia menjadi yang paling celaka [...]”. Sebanyak 75 persen nilai ekspor itu berasal dari “delapan macam hatsil onderneming landbouw” atau hasil pertanian yang sangat dekat dengan kepentingan rakyat. Untung bersih bagi semua onderneming itu rata-rata f 515.000.000/tahun, “lima ratus lima belas milliun rupiah setahun, dan ini adalah 9% á 10% dari mereka punya modal-induk!”, sedang “bagi Marhaen, yang membanting tulang dan berkeluh-kesah mandi keringat bekerja membikinkan untung sebesar itu, ratarata di dalam zaman ‘normal’ [sebelum meleset] ta’ lebih dari delapan sen seorang sehari ...” 3. “Indonesia, Tanah yang Mulya ...” Marhaen dapat “ta’ lebih dari delapan sen seorang sehari. Dan ini pun bukan hisapan-jempol kaum pembohong, bukan 93 panggilan tanah air hasutannya kaum penghasut, bukan agitasinya pemimpin-agitator. [...] Memang hanya orang munafik dan durhaka sahajalah yang tak’ berhenti-henti berkemak-kemik: ‘Indonesia sejahtera. Rakyatnya kenyang-senang.” [...]. Kenyataan ini “ta’ dapat dibantah lagi. Dr Huender telah mengumpulkan angkaangka[nya]. [...] Ia membagi pendapatan Kang Marhaen itu dalam tiga bagian: ... dari padinya, ... dari palawijanya, ... dari perkuliannya bilamana Marhaen tengan ‘vrij’”. [...] “En toch, barangkali risalah ini dibaca oleh fihak ‘twijvelaars’ alias fihak ‘ragu-ragu’ di kalangan kita punya intellectuelen yang karena terlampau kenyang ‘cekokan kolonial’ tidak percaya bahwa Marhaen papa-sengsara?” Cara manjur melenyapkan keraguan mereka itu adalah menganjurkan mereka pergi ke kalangan Marhaen sendiri, lalu melihat dengan mata kepala sendiri. Boleh juga periksa “perkataan Professor Boeke yang berbunyi, bahwa hidupnya bapak tani adalah hidup ‘ellendig’, hidup yang sengsara keliwat sengsara’”. Boleh juga buka “surarsurat chabar [...] dan mengumpulkan ‘syair megatruh’ [...] yang melagukan betapa hidupnya Kang Marhaen yang ... sudah ‘sekarang makan besok tidak’ itu”. [...]( “O, Marhaen, hidupmu sehari-hari morat-marit” tapi “kamu boleh menyanyi: Indonesia,Tanah Yang Mulya/ Tanah Kita Yang Kaya/ Disanalah kita Berada/ Untuk Selama-lamanya.” 94 lampiran-lampiran 4. “Di Timur Matahari Mulai Bercahaya,” “Tetapi hal-hal yang saya ceritakan di atas ini hanyalah kerusakan lahir sahaja. Kerusakan bathin pun ternyata [timbul] di manamana. Stelsel imperialisme yang butuh pada kaum buruh itu, sudah [menyelewengkan] semangat kita menjadi semangat perburuhan ... yang hanya senang jikalau bisa menghamba. Rakyat Indonesia sediakala terkenal sebagai Rakyat yang gagahberani ..., yang perahu-perahunya melintasi lautan dan samodra ..., kini terkenal sebagai ‘het zachtste volk der aarde’, ‘Rakyat yang paling lemah-budi di seluruh muka bumi’. Rakyat Indonesia itu kini menjadi Rakyat yang hilang kepercayaannya pada diri sendiri, hilang keperibadiannya [...]”. Itu pun “belum bencana bathin yang paling besar! Bencana bathin yang paling besar ialah bahwa Rakyat Indonesia itu percaya bahwa ia memang adalah ‘Rakyat-kambing’ yang selamanya harus dipimpin dan dituntun”. Rakyat seperti itu percaya saja semboyan imperialisme bahwa mereka datang di Indonesia bukan untuk cari rezeki, malainkan datang membawa “’maksud suci’ ... ‘missioncacrée’ [untuk mencapai] ‘beschaving’ dan ‘orde en rust’, – ‘[peradaban]’ dan ‘[ketertiban] umum’.” Namun semua itu “hanyalah omong-kosong belaka”, dan kita akan binasa kalau terus percaya omong-kosong tersebut, ‘dan pantas binasa di dalam lumpur penghinaan dan nerakanya kegelapan. [...] Tetapi ... Alhamdulillah, di Timur matahari mulai bercahaya, fajar mulai menyingsing! Obat tidur imperialisme yang berabad-abad kita minum ... perlahan-lahan mlai kurang dayanya. 95 panggilan tanah air [...] Berabad-abad kita sudah lembek hingga seperti kapuk dan agar-agar. Yang [kita] butuhkan kini ialah otot-otot yang kerasnya sebagai baja, urat-urat-syaraf yang kuatnya sebagai besi, kemauan yang kerasnya sebagai batu-hitam ... dan jika perlu, berani terjun ke dasarnya samodra!” Fajar menyingsing itu adalah pergerakan kebangsaan kita. “Pergerakan memang bukan tergantung [pada] seorang pemimpin ..., pergerakan adalah bikinannya nasib kita yang sengsara. [Pergerakan] pada hakekatnya adalah usaha masyarakat sakit yang mengobati diri sendiri. [...] Oleh karena itulah kita harus mempunyai [...] pergerakan yang ... cocok dan sesuai dengan hukum-hukumnya masyarakat dan terus menuju ke arah doelnya masyarakat, ya’ni masyarakat yang selamat dan sempurna. [...]. Haibatkanlah pergerakanmu menjadi pergerakan yang bewust dan insyaf, yang karenanya akan menjadi haibat sebagai tenaganya gempa. Fajar mulai menyingsing. Sambutlah fajar itu dengan kesadaran, dan kamu akan segera melhat matahari terbit.” 5. Gunanya Ada Partai “Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup yang lebih layak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena ‘ideal’ saja ... [tapi] karena ingin perbaikan nasib [di segala bidang].” Namun, perbaikan nasib “hanyalah bisa datang seratus prosen, bilamana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. [...] Oleh karena itu ... pergerakan kita itu ... yang ingin merobah samasekali sifatnya masyarakat ... yang 96 lampiran-lampiran samasekali ingin menggugurkan stelsel imperialisme dan kapitalisme. Pergerakan kita janganlah hanya ... ingin rendahnya pajak, ... tambahnya upah, janganlah hanya ingin perbaikanperbaikan kecil yang bisa tercapai hari sekarang ...”. Perubahan yang begitu besar harus “dibarengi dengan gemuruhnya banjir pergerakan Rakyat-Jelata. [...]. Kita pun harus menggerakkan Rakyat-jelata di dalam suatu pergerakan radikal yang bergelombangan sebagai banjir, menjelmakan pergerakan massa yang tahadinya onbewust dan hanya raba-raba itu menjadi suatu pergerakan massa yang bewust dan radikal, ya’ni massaaksi yang insyaf akan jalan dan maksud-maksudnya.” “Welnu, bagaimanakah kita bisa menjelmakan pergerakan ... yang bewust dan radikal? Dengan suatu partai! Dengan suatu partai yang mendidik Rakyat-jelata itu ke dalam ke-bewest-an dan keradikalan.” [...]. Partai yang demikian ... bukan partai burjuis, bukan partai ningrat, bukan ‘partai-Marhaen’ yang reformistis, bukan pun ‘partai radikal’ yang hanya amuk-amukan sahaja, – tetapi partai-Marhaen yang radikal yang tahu saat menjatuhkan pukulan-pukulannya.” 6. Indonesia Merdeka Suatu Jembatan Dengan partai seperti itulah pergerakan kebangsaan mencapai maksudnya: “suatu masyarakat yang adil dan sempurna, yang tidak ada tindasan dan hisapan, yang tidak ada kapitalisme dan imperialisme. [...]. Dan syarat yang pertama untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme ... ialah: 97 panggilan tanah air k i t a h a r u s m e r d e k a. Kita harus merdeka, agar supaya kita bisa leluasa bercancut-tali-wanda menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Kita harus merdeka, supaya kita bisa leluasa mendirikan suatu masyarakat-baru yang tiada kapitalisme dan imperialisme. [...]. Dapatkah Ramawijaja mengalahkan Rahwana Dasamuka, jikalau Ramawijaya itu [masih] terikat kaki dan tangannya ...?” Syarat kedua, “mengikhtiarkan kemerdekaan nasional”, kaum Marhaen “j u g a h a r u s m e n j a g a j a n g d i d a l a m k e m e r d e k a a n – n a s i o n a l i t u k a u m Ma r h a e n l a h j a n g m e m e g a n g k e k u a s a a n, – bukan kaum borjuis Indonesia, bukan kaum ningrat Indonesia, bukan musuh kaumMarhaen. [...]. Adakah dus saya kini mengutamakan klassenstrijd [pertentangan kelas]? Saya belum mengutamakan klassenstrijd antara bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia, walau pun tiap-tiap nafsu kemodalan di kalangan bangsa sendiri kini sudah saya musuhi. Saya seorang nasionalis ... selamanya menganjurkan supaya semua tenaga nasional yang bisa dipakai menghantam musuh untuk mendatangkan kemerdekaan-nasional itu, haruslah dihantamkan pula.” “‘De sociale tegenstellingen worden in onvrije landen in nationale vormen uitgevochten’, ‘pertentangan sosial di negerinegeri yang ta’ merdeka diperjoangkan secara nasional’, begitulah juga Henriette Roland Holst berkata. Tetapi kemerdekaan-nasional hanyalah suatu jembatan, suatu syarat, 98 lampiran-lampiran suatu strijdmoment. Di belakang Indonesia Merdeka itu kita kaum Marhaen masih harus mendirikan kita punya Gedung Keselamatan, bebas dari tiap-tiap macam kapitalisme.” Jadi, syarat ketiga adalah: kesadaran bahwa kemerdekaan nasisonal hanyalah jembatan emas. 7. Sana Mau ke Sana, Sini Mau ke Sini “Tapi sekarang timbul pertanyaan: bagaimana kita [memenuhi] ... tiga [syarat] itu?” “[K]ita lebih dulu harus mengetahui hakekatnya kedudukan antara imperialisme dan kita, hakekat kedudukan antara s a n a dan s i n i.” Inilah yang menentukan “azas-azas perjoangan kita, ... strategi kita, ... taktik kita ... ‘houding’ [sikap] kita terhadap ... kaum sana itu ...” Hakekat “kedudukan” itu “boleh kita gambarkan dengan satu perkataan sahaja: p e r t e n t a n g a n. Pertentangan di dalam segala hal. [...] Tidak ada persesuaian antara sana dan sini. Antara sana dan sini ada pertentangan sebagai api dan air, sebagai serigala dan rusa, sebagai kejahatan dan kebenaran.” Inilah “yang oleh kaum Marxis disebutkan d i a l e k t i k-nya sesuatu keadaan ...” Pertentang sana dan sini berada dalam dialektik itu, yang disebut “ber-antitese”. Dialektik ini “menyuruh kita selamanya ... t i d a k b e k e r j a [s a m a] terhadap ... kaum sana itu, – s a m p a i kepada saat keunggulan dan kemenangan. [...] kemenangan hanyalah bisa 99 panggilan tanah air kita capai dengan kebiasaan s e n d i r i, tenaga s e n d i r i, usaha s e n d i r i. [...]. Inilah yang biasanya kita sebutkan politik ‘p e r c a y a p a d a k e k u a t a n s e n d i r i’, politik ‘s e l f – h e l p dan n o n – c o o p e r a t i o n’.” 8. Machtsvorming, Radikalisme, Massa-Aksi Selain membawa kita ke “politik selfhelp dan non-cooperation”, dialektika tadi juga membawa kita “ke dalam kawah candradimukanya politik machtsvorming, radikalisme dan massaaksi.” Machtsvorming “adalah ... pembikinan kuasa ... jalan satusatunya untuk memaksa kaum sana tunduk kepada kita.” Jalan satu-satunya, karena “’nooit heeft een klasse vrijwillig van haar bevoorrechte positie afstand gedaan”, begitulah Karl Marx berkata ... ‘Ta’ pernahlah sesuatu kelas suka melepaskan hakhaknya dengan ridlanya kemauan sendiri’.” “Radikalisme” berarti menggunakan “machtsvorming” kita, bukan “kepandaian putar lidah, bukan kepandaian menggerutu dengan hati dendam terhadap kaum sana.” Dengan kata lain, “[t]iap-tiap kemenangan kita, dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil, adalah hatsilnya d e s a k a n dengan kita punya tenaga. Oleh karena itu ‘teori’ dan ‘prinsip’ sahaja buat saya belum cukup. Tia-tiap orang bisa menutup dirinya di dalam kamar, dan menggerutu ‘ini tidak menurut teori’, ‘itu tidak menurut prinsip’. Saya tidak banyak menghargakan orang yang demikian itu. Tetapi yang paling sukar ialah, di muka musuh yang kuat dan membutatuli ini, menyusun suatu m a c h t yang terpikul oleh suatu prinsip. Keprinsipiilan dan keradikalan zonder machtsvorming yang bisa 100 lampiran-lampiran menundukkan musuh di dalam perjoangan yang haibat, bolehlah kita buang ke dalam sungai Gangga. Keprinsipiilan dan keradikalan yang menjelmakan kekuasaan, itulah kemauan Ibu!” 9. Di Seberangnya Jembatan Emas “Adakah Indonesia-Merdeka bagi Marhaen menentukan hidupkemanusiaan yang [leluasa dan sempurna, ... yang secara manusia dan selayak manusia]? Indonesia-Merdeka sebagai saya katakan di atas, adalah menjanjikan tetapi belum pasti menentukan bagi Marhaen hidup kemanusiaan yang demikian itu.” Yang menjanjikan itu “barulah menjadi ketentuan, kalau Marhaen sedari sekarang sudah insyaf seinsyaf-insyafnya bahwa Indonesia-Merdeka hanyalah suatu jembatan, – sekali pun suatu jembatan emas!– yang harus dilalui dengan segala keawasan dan keprajinaan, jangan sampai di atas jembatan itu KeretaKemenangan dikusiri oleh lain orang selainnya Marhaen.” Satu calon kusir ialah “kaum ningrat” dengan “nasionalismekeningratan” mereka. “Mereka masih hidup dalam keadaan feodalisme [...] yang biasanya setia sekali pada kaum yang di atas ... Tetapi menurut cita-citanya di dalam Indonesia-Merdeka itu merekalah yang harus menjadi ‘kepala’ ... yang sejak zaman purbakala, sejak feodalisme Hindu dan sejak feodalisme ke-Islam-an toch sudah menjadi ‘pohon beringin’ yang melindungi kaum ‘kawulo’”. Calon kusir lain ialah “nasionalisme-keborjuisan” milik kaum modal, industri, kaum berpunya. Dua-duanya memuja individualisme, yang menjerumuskan Marhaen ke lembah demokrasi politik belaka. 101 panggilan tanah air Terhadap mereka ini Marhaen mengajukan demokrasi berdasarkan “gotong royong”, dalam bentuk “sosio-demokrasi” dan “sosio-nasionalisme”. “Dengungkanlah sampai melintasi tanah-datar dan gunung dan samodra, bahwa Marhaen di seberangnya jembatan-emas akan mendirikan suatu masyarakat yang tiada keningratan dan tiada keborjuisan, tiada kelas-kelasan dan tiada kapitalisme.” “Bahagialah partai-pelopor yang demikian itu! “Bahagialah massa yang dipelopori partai yang demikian itu! “Hiduplah sosionasionalisme dan soio-demokrasi!” 10. Mencapai Indonesia-Merdeka! “Sekarang, kampiun-kampiun kemerdekaan, majulah ke muka, susunlah pergerakanmu menurut garis-garis yang saya guratkan di dalam risalah ini. Haibatkanlah partainya Marhaen, agar supaya menjadi partai pelopornya massa. Haibatkanlah semua semangat yang ada di dalam dadamu, haibatkanlah semua kecakapanmengrorganisasi yang ada di dalam tubuhmu, haibatkanlah semua keberanian banteng yang ada di dalam nyawamu [...].” “Hidupkanlah massa-aksi, untuk mencapai IndonesiaMerdeka!” % (Parakitri T. Simbolon. Rebo, 1 Juli 2009). Sumber: http://zamrudkatulistiwa.com/2009/07/01/mancapai_indonesia_ merdeka/ (unduh terakhir pada 5 Mei 2015) 102 Lampiran 2 Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 103 panggilan tanah air Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 104 Lampiran 3 Pidato Soekarno Memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Saudara-saudara sekalian! Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha-penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang, untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu, ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di Jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional juga tidak berhenti-berhenti. Di dalam Jaman Jepang ini, tampaknya-saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dengan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu se-iya sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. 105 panggilan tanah air Saudara-saudara! dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami : Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya. Jakarta, 17-08-1945 Demikianlah, saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, – merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu! 106 Lampiran 4 Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia; Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahoen 1928 di negeri Djakarta; Sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini; Kerapatan laloe mengambil kepoetoesan: Pertama : Kedoea : Ketiga : KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATU, TANAH INDONESIA. KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA. KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENDJOEN-DJOENG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA 107 panggilan tanah air Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkoempoelan kebangsaan Indonesia. Mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannya: KEMAOEAN SEDJARAH BAHASA HOEKOEM ADAT PENDIDIKAN DAN KEPANDOEAN dan mengeloearkan pengharapan soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan di moeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan. 108 lampiran-lampiran 109 Lampiran 5a Lirik Lagu “Indonesia Raya” versi asli (1928)1 I Indonesia, tanah airkoe, Tanah toempah darahkoe, Disanalah akoe berdiri, Mendjaga Pandoe Iboekoe. Indonesia kebangsaankoe, Kebangsaan tanah airkoe, Marilah kita berseroe: “Indonesia Bersatoe”. Hidoeplah tanahkoe, Hidoeplah neg’rikoe, Bangsakoe, djiwakoe, semoea, Bangoenlah rajatnja, Bangoenlah badannja, Oentoek Indonesia Raja. Refrain : Indones’, Indones’, Moelia, Moelia, Tanahkoe, neg’rikoe, jang koetjinta. Indones’, Indones’, Moelia, Moelia, Hidoeplah Indonesia Raja. II Indonesia, tanah jang moelia, Tanah kita jang kaja, Disanalah akoe hidoep, Oentoek s’lama-lamanja. Indonesia, tanah poesaka, Poesaka kita semoeanja, Marilah kita berseroe: “Indonesia Bersatoe”. 110 lampiran-lampiran Soeboerlah tanahnja, Soeboerlah djiwanja, Bangsanja, rajatnja, semoea, Sedarlah hatinja, Sedarlah boedinja, Oentoek Indonesia Raja. Refrain : Indones’, Indones’, Moelia, Moelia, Tanahkoe, neg’rikoe jang koetjinta. Indones’, Indones’, Moelia, Moelia, Hidoeplah Indonesia Raja. III Indonesia,tanah jang soetji, Bagi kita disini, Disanalah kita berdiri, Mendjaga Iboe sedjati. Indonesia, tanah berseri, Tanah jang terkoetjintai, Marilah kita berdjandji:”Indonesia Bersatoe” S’lamatlah rajatnja, S’lamatlah poet’ranja, Poelaoenja, laoetnja, semoea, Madjoelah neg’rinja, Madjoelah Pandoenja, Oentoek Indonesia Raja. Refrain : Indones’, Indones’, Moelia, Moelia, Tanahkoe, neg’rikoe jang koetjinta. Indones’, Indones’, Moelia, Moelia, Hidoeplah Indonesia Raja. (2x) 111 Lampiran 5b Lirik Lagu Kebangsaan Indonesia Raya versi Resmi (1958, 2009)2 I Indonesia Tanah Airkoe, Tanah Toempah Darahkoe Di sanalah Akoe Berdiri, Djadi Pandoe Iboekoe Indonesia Kebangsaankoe, Bangsa Dan Tanah Airkoe Marilah Kita Berseroe Indonesia Bersatoe Hidoeplah Tanahkoe, Hidoeplah Negrikoe Bangsakoe Ra’jatkoe, Sem’wanja Bangoenlah Djiwanja Bangoenlah Badannja Oentoek Indonesia Raja (Reff: Diulang 2 kali, red) Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja II Indonesia Tanah Jang Moelia Tanah Kita Jang Kaja Di sanalah Akoe Berdiri, Oentoek Slama-Lamanja Indonesia Tanah Poesaka, P’saka Kita Semoeanja, Marilah Kita Mendo’a Indonesia Bahagia 112 lampiran-lampiran Soeboerlah Tanahnja, Soeboerlah Djiwanja, Bangsanja, Ra’jatnja, Sem’wanja, Sadarlah Hatinja, Sadarlah Boedinja, Oentoek Indonesia Raja (Reff: Diulang 2 kali, red) Indonesia Raja, Merdeka, Merdeka Tanahkoe, Negrikoe, Jang Koetjinta Indonesia Raja, Merdeka, Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja III Indonesia Tanah Jang Seotji, Tanah Kita Jang Sakti Di sanalah Akoe Berdiri, ‘Njaga Iboe Sedjati Indonesia Tanah Berseri, Tanah Jang Akoe Sajangi Marilah Kita Berdjandji, Indonesia Abadi S’lamatlah Ra’jatnja, S’lamatlah Poetranja Poelaoenja, Laoetnja, Sem’wanja Madjoelah Negrinja, Madjoelah Pandoenja Oentoek Indonesia Raja (Reff: Diulang 2 kali, red) Indonesia Raja, Merdeka, Merdeka Tanahkoe Negrikoe, Jang Koetjinta Indonesia Raja, Merdeka, Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja 113 Lampiran 5c Lirik Lagu Kebangsaan Indonesia Raya versi Resmi (dengan Ejaan Yang Disempurnakan) I Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, Bangsaku, Rakyatku, semuanya, Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya. Refrain : Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Tanahku, neg’riku yang kucinta! Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya! II Indonesia, tanah yang mulia, Tanah kita yang kaya, Di sanalah aku berdiri, Untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, Pusaka kita semuanya, Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. 114 lampiran-lampiran Suburlah tanahnya, Suburlah jiwanya, Bangsanya, Rakyatnya, semuanya, Sadarlah hatinya, Sadarlah budinya, Untuk Indonesia Raya. Refrain : Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Tanahku, neg’riku yang kucinta! Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya! III Indonesia, tanah yang suci, Tanah kita yang sakti, Di sanalah aku berdiri, N’jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, Tanah yang aku sayangi, Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, Selamatlah putranya, Pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah Negerinya, Majulah pandunya, Untuk Indonesia Raya. Refrain(2x) Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Tanahku, neg’riku yang kucinta! Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya! 115 panggilan tanah air Catatan Akhir 1 Lihat Panitia Penyusun Naskah Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (1972), Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan. Versi ini menggunakan sistem ejaan Van Ophuijsen yang secara resmi dipakai di Hindia Belanda sejak 1901 hingga 1947. Soewandi, Menteri Pendidikan Republik Indonesia, memutuskan mengganti sistem ejaan Van Ophuijsen ini menjadi Ejaan Republik (atau juga disebut Ejaan Soewandi) semenjak 17 Maret 1947. Kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mansuri Saleh mengganti Ejaan Republik ini menjadi Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) pada 23 Mei 1972. 2 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958, stanza pertama dari “Indonesia Raja” ini digunakan sebagai lirik resmi lagu kebangsaan Indonesia, yang juga dikukuhkan dengan Undang-undang No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Di dalam Lampiran UU 24/2009 ini dimuat pula yang disebut “Lagu Kebangsaan Indonesia Raya versi Asli dengan T iga Stanza”. Naskah yang dimuat disini berasal dari Lampiran UU 22/2009 ini. 116 Daftar Pustaka Braudel, Fernand. 1979. Civilization and Capitalism 15th–18th Century. Vol. 2. The Wheels of Commerce. New York: Harper & Row. Breman, Jan. 1996. Footloose Labour, Work and Life in the Informal Sector Economy of West India. Cambridge: Cambridge University Press. Davis, Mike. 2006. Planet of Slums. New York: Verso. De Angelis, Massimo. 2007. The Beginning of History. Value Struggles and Global Capital. London: Pluto Press. ERIA. 2009. Comprehensive Asia Development Plan. ERIA: Jakarta (ERIA. ____. 2010. “Comprehensive Asia Development Plan and Beyond-Growth Strategies to More Prosperous East Asia”. ERIAPolicy Brief no. 2010-02, October 2010. Fauzi, Noer, 1997, “Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Paska Kolonial”, dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia p.67-122, Jakarta: LP-FEUI dan KPA. _____. 1999, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerja sama dengan Insist Press dan Pustaka Pelajar. 117 panggilan tanah air _____. 2001. Bersaksi untuk Pembaruan Agraria. Yogyakarta: Karsa bekerja sama dengan Insist Press. Noer Fauzi dan Boy Fidro (Eds), 1998, Pembangunan Berbuah Sengketa, Kumpulan Kasus-kasus Sengketa Pertanahan Sepanjang Orde Baru. Kisaran: Yayasan Sintesa dan Serikat Petani Sumatera Utara. Farid, Hilmar. 2005. “Indonesia’s Original Sin: Mass Killings and Capitalist Expansion, 1965–66". Inter-Asia Cultural Studies 6(1):3-16 _____. 2014. Arus Balik Kebudayaan. Sejarah Sebagai Kritik. Pidato Kebudayaan, Dewan Kesenian Jakarta, 10 November 2014. Geller, Paul K. 2010. “Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Development”, Rural Sociology 75(1): 28–57. Harman, Benny K., Paskah Irianto, Noer Fauzi dan Sigit Pranawa (Eds). 1995. Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Harvey, David 1990. The Condition of Postmodernity: An Inqiury into the Origins of Cultural Change. Oxford, Oxford University Press. _____. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press. _____. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press. _____. 2006. “Neo-liberalism as Creative Destruction. Geogr. Ann., 88 B (2): 145–158 Hadiz, Vedi dan Richard Robison. 2004. Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in the Age of Markets. 118 daftar pustaka London: Routledge Curzon. _____. 2014. “Ekonomi Politik Oligarki dan pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia”.Prisma 33(1): 35-56. Hobsbawm, Eric. 1994. Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. London: Penguin. Juliantara, Dadang. 1997. “Agraria adalah Akibat, Kapitalisme adalah Sebab!”, Jurnal Suara Pembaruan Agraria No. 3/ 1997. Khudori. 2014. “Darurat Lahan Pertanian,” Kompas, 30 Januari 2013. Konsorsium Pembaruan Agraria 2014. Laporan Akhir Tahun 2014 Konsorsium Pembaruan Agraria. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria. Kurosawa, Aiko. 1993. Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942 – 1945. Terjemahan Hermawan Sulistyo. Jakarta: Grasindo. 1993. Lefebvre, Henri. (1970/2003). The Urban Revolution. Foreword by Neil Smith. Translated by Robert Bononno. University of Minnesota Press. _____. 1974/1992. The Production of Space. Donald NicholsonSmith (Translator). London: Wiley-Blackwell. _____. 1976. The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relations of Production. New York: St Martin’s Press. Marx, Karl. 1852/1994. The Eighteenth Brumaire of Louise Bonaparte. Moscow: International Publisher _____. 1976/1898. Capital, Vol. 1, trans. Ben Fowkes. Harmondsworth, Penguin Books. Panitia Penyusun Naskah Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (1972), Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 119 panggilan tanah air Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Peluso, Nancy Lee. 1992. Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Berkeley: University of California Press, 1992. Pemerintah Indonesia. 2011. Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. _____. 2006 Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya di Jawa. Jakarta: Konphalindo Perelman, Michael. 2000. The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation. Durham: Duke University Press. Polanyi, Karl. 1967 (1944).The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press. _____. 2001 (1944) The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press. Rachman, Noer Fauzi. 2013. “Mengapa Konflik-Konflik Agraria Terus-Menerus Meletus di Sana Sini?” Sajogyo Institute‘s Working Paper No. 1/2013. Bogor: Sajogyo Institute. http:/ /www.sajogyo-institute.or.id/article/mengapa-konflikkonflik-agraria-terus-menerus-meletus-di-sana-sini (diunduh 29 Juni 2013). Schumpeter, Joseph A. 1944. Capitalism, Socialism and Democracy. Allen & Unwin. Saasen, Saskia. 2001. The Global City: New York, London Tokyo. Updated 2 ed. Princeton: Princeton Univesity Press. Sangkoyo, Hendro. 1998. Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat-syarat Sosial dan Ekologis Pengurusan Daerah. 120 daftar pustaka Kertas Kerja No. 9. Konsorsium Pembaruan Agraria. Simbolon, Parakitri T. 1999. Menjadi Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Toer, Pramoedya Ananta. 1984. Arus Balik. Jakarta: Hasta Mitra. Tauchid, Mochammad. 1952/3. Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakjat Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Penerbit Tjakrawala. _____. 1952/2009. Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakjat Indonesia, Yogyakarta : STPN Press, 2009 White, Ben. 2011. “Who Will Own The Countryside? Disposession, Rural Youth and The Future of Farming”. Valedictory Address delivered on 13 October 2011 on the occasion of the 59th Dies Natalis of the International Institute of Social Studies, the Hague. ______. 2012. “Agriculture and the Generation Problem: Rural Youth, Employment and Farming”. IDS Bulletin 43: 9-19. 6 November 2012. Winters, Jeffrey A. 2014. ”Oligarki dan Demokrasi di Indonesia”. Prisma 33(1): 11-34. Wibowo. I. dan Francis Wahono (Eds.), 2003, Neoliberalisme, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Wiradi, Gunawan. 2004. “Lagu Kebangsaan dan Nasionalisme”. https://sajogyoinstitute.wordpress.com/2013/09/20/lagukebangsaan-dan-nasionalisme/ (unduh pada 4 April 2015) Wood, Ellen Meiksins. 2002. The Origin of Capitalism. A Longer View. London, Verso. _____. 1994. “From Opportunity to Imperative: The History of the Market”. Monthly Review 46 (3). 121 panggilan tanah air Zakaria, R. Yando. 2000. Abih Tandeh. Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. _____. 2005. Merebut Negara: Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian, dan Pemulihan Otonomi Desa. Yogyakarta: Karsa. 122 Tentang Penulis Noer Fauzi Rachman, Ph.D. adalah pelajar politik dan perubahan agraria, gerakan sosial pedesaan, dan pendidikan rakyat, yang telah bekerja dalam bidang-bidang itu selama sekitar 30 tahun. Sekarang ia bekerja sebagai Ketua Dewan Pengarah Prakarsa Desa (BP2DK), peneliti utama di Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan Studi Agraria Indonesia, anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan pengajar mata kuliah “Politik dan Gerakan Agraria”, Program S2 Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor. Ia memperoleh gelar PhD di University of California, Berkeley tahun 2011 dalam bidang Environmental Science, Policy and Management (ESPM), dengan disertasi “The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia”. Disertasi ini akan diterbitkan menjadi buku oleh Insist Press pada tahun 2015 ini. Ia menulis banyak buku, artikel dan panduan latihan, termasuk Petani dan Penguasa, Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Insist Press dan Konsorsium Pembaruan Agraria, 1999; serta Land Reform dari Masa Ke Masa. Perjalanan Kebijakan Pertanahan Indonesia 19452012. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2013. .