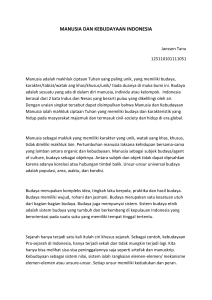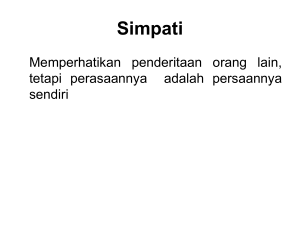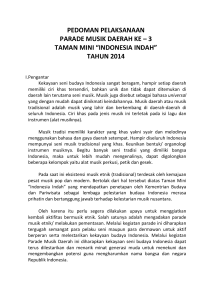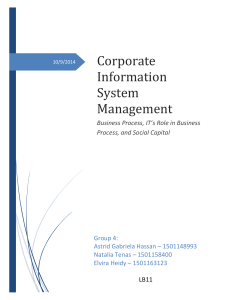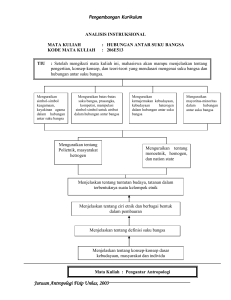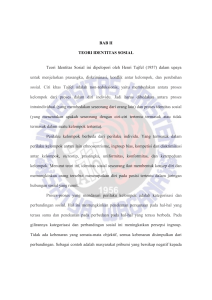Pendidikan Seni untuk Toleransi
advertisement

International Seminar “Today’s Art, Future’s Culture” November 23, 2016 Pendidikan Seni untuk Toleransi G. R. Lono Lastoro Simatupang Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada [email protected] “By learning how the people in another culture express themselves musically, students are not only given insights into others but also learn about themselves.” “Studying the music of other cultures can broaden students’ sound base, enabling them to be more open and tolerant of new musical sounds.” Therese M. Volk (1998) Pengantar Empat belas tahun silam harian Kompas memberitakan uji coba Pendidikan Apresiasi Seni (PAS) yang dilakukan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), bersama STSI Surakarta (sekarang ISI Surakarta) dan Universitas Pendidikan Bandung. Proyek dukungan Ford Foundation Jakarta, Persyarikatan Muhammadiyah, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan membantu perumusan model PAS yang bisa diterapkan di lingkup nasional. PAS bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan apresiasi siswa terhadap berbagai bentuk ekspresi budaya, serta untuk menanamkan kesadaran pluralitas. Uji coba dilakukan lewat pengenalan kesenian Topeng Cirebon dari desa Lelea, Indramayu kepada siswa SD Muhammadiyah Karanganyar, Jawa Tengah. Melukiskan jalannya proyek, Kompas menyajikan penggalan percakapan dalam kelas sebagai berikut: “Dan, masih dalam kaitan dengan budaya Sunda, kemudian menyinggung upacara tradisi setempat yang disebut Ngarot di desa Lelea, Indramayu (Jabar). Setelah itu, ia menanyakan kepada siswa, kegiatan tersebut berkaitan dengan kepercayaan apa? Siswa pun menjawab, ‘Animisme.’ “Bagaimana sikap Muslim memandang kegiatan tersebut? Apakah kita melecehkan atau melarangnya? Para siswa SD Muhammadiyah itu menjawab spontan, ‘Tidak, karena itu memang berkaitan dengan adat setempat.’”1 Walaupun potongan kutipan itu mungkin tidak menggambarkan setepat-tepatnya interaksi guru-murid yang senyatanya terjadi di ruang kelas, pengaitan antara kesenian, upacara adat dan praktek ritual semacam itu sungguh merisaukan, apalagi mengingat bahwa hal itu terjadi dalam upaya penanaman kesadaran akan pluralitas. Muncul pertanyaan: apakah melabeli Ngarot, atau Topeng Cirebon dengan ‘animisme’ merupakan langkah penumbuhan apresiasi pluralitas budaya yang bijak? Apakah orang desa Lelea, Indramayu, atau pelaku Ngarot dan Topeng Cirebon, menganggap diri animis? Refleksi di atas menunjukkan betapa upaya penanaman kesadaran pluralitas budaya melalui seni, yang telah dilakukan sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, memerlukan kematangan pemikiran dan persiapan tidak sederhana, serta menuntut kebijaksanaan pelaksanaan. Sayangnya wacana akademis tentang pendidikan seni dalam konteks 1 Kompas, 31 Agustus 2002. Garisbawah penulis. PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 1 International Seminar “Today’s Art, Future’s Culture” November 23, 2016 pluralitas budaya masih terbatas di Indonesia. Melalui tulisan ini penulis bermaksud berbagi gagasan tentang pendidikan seni untuk toleransi yang disusun berdasarkan pengalaman penyelenggaraan matakuliah Apresiasi Musik Etnik bagi mahasiswa program studi S1 Antropologi di UGM. Mengenalkan Perbedaan, Menemukan Kesamaan Matakuliah Apresiasi Musik Etnik, dan tiga matakuliah apresiatif lainnya,2 diberikan sebagai bagian integral pengenalan mahasiswa tahun pertama tentang konsep, perspektif dan cara kerja antropologi – sebuah disiplin ilmu yang secara spesifik berfokus pada pemahaman mengenai keanekaragaman budaya umat manusia. Penyelenggaraan matakuliah tersebut bersandar pada ‘filosofi’ sederhana “tak kenal maka tak sayang.” Dalam konteks pendidikan antropologi, ‘filosofi’ itu menganjurkan perlunya mahasiswa mengenal budaya-budaya selain budaya diri sendiri. Meskipun tampaknya kuliah apresiatif tersebut sepele, namun pelaksanaannya memerlukan pengumpulan dan penyusunan materi yang cukup kompleks. Proses perkuliahan Apresiasi Musik Etnik disusun berdasarkan sebuah nalar andragogi (pendidikan untuk orang dewasa) yang dijuluki ‘Johari’s window’ berserta semboyannya ‘masuk dari jendela mereka, keluar dari pintu kita.’ Mengikuti semboyan tersebut, proses pembelajaran dimulai dengan memasuki dunia musik melalui ‘jendela’ musik yang diakrabi mahasiswa, namun proses selanjutnya mengarah pada ‘pintu’ luaran berupa kesadaran akan pluralitas jagad musik. THE ANTHROPOLOGY OF MUSIC Sesi-sesi awal pertemuan berupa pengarahan mahasiswa pada pengertian musik dan budaya sebagaimana dikemukakan Alan P. Merriam dalam The Anthropology of Music. Secara ringkas mahasiswa diperkenalkan pada tiga dimensi musik: konsep musikal, 2 Tiga mata kuliah apresiatif yang lain adalah Apresiasi Film Etnografi, Apresiasi Kuliner Etnik, dan Apresiasi Kriya Etnik. PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 2 International Seminar “Today’s Art, Future’s Culture” November 23, 2016 perilaku musikal, dan materi musik, serta interrelasi ketiganya.3 Penjelasan tentang ketiga dimensi musik tersebut dilakukan dengan merujuk pada pengetahuan dan pengalaman musikal mahasiswa (‘jendela’ mereka). Diasumsikan bahwa pengetahuan musikal mayoritas mahasiswa terutama merujuk pada musik ‘barat.’ Asumsi ini dibangun berdasarkan kenyataan sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas mereka lebih sering diperkenalkan pada khasanah musik ‘barat.’ Begitu pula, dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering mendengar dan berkegiatan musik ‘barat.’ Konsep-konsep tentang ‘musik,’ ‘nada,’ ‘melodi,’ ‘irama,’ ‘harmoni,’ kategorisasi ‘instrumen musik,’ yang telah mereka ketahui digunakan sebagai titik-berangkat penjelajahan keanekaragaman jagat musik. Secara garis besar, penjelajahan pluralitas musik dilakukan dengan cara mendekonstruksi konsep musik (‘barat’ dan pop) yang selama ini ‘ditelan’ begitu saja. Dekonstruksi ini berupa pembenturan konsep musikal ‘barat’ dengan kenyataan pluralitas fenomena maupun praktik musikal. Contohnya, kepada mahasiswa diminta membandingkan cara bernyanyi dalam lagu pop dengan salah satu cara bernyanyi orang Maasai di sepanjang sungai Nil, Kenya bagian Selatan dan Tanzania bagian Utara. Dapat pula dilanjutkan dengan mendengarkan vokalisasi pemain teater Noh Jepang. Contoh-contoh tersebut disajikan untuk mempertanyakan kembali pengertian dan batasan, misalnya, apa itu menyanyi? Apa bedanya dengan berbicara, mengeluh, menggeram, dan seterusnya. Diskusi tentang perbedaan demi perbedaan tersebut diarahkan pada pelonggaran batasan menyanyi yang selama ini dipahami, menuju pada pengertian ‘menyanyi’ atau ‘musik’ yang lebih inklusif sebagai gejala pengaturan bunyi – tanpa harus membatasi pada teknik maupun jenis atau kualitas bunyi (manusia maupun benda) tertentu. Strategi serupa juga diterapkan untuk mendekonstruksi pengertian nada. Dalam sesi ini diperkenalkan prinsip pokok pengaturan bunyi berdasarkan tinggi rendahnya. Pembedaan tinggi-rendah bunyi yang paling sederhana berupa dua buah bunyi: rendah dan tinggi tanpa menentukan interval kedua bunyi tersebut. Pembedaan tinggi-rendah bunyi tanpa penetapan interval, baik pembedaan dalam dua, tiga, atau lebih banyak kategori, sejatinya merupakan prinsip dasar yang diterapkan pada alat-alat musik perkusi bermembran seperti tabla. Teknik Pukulan Tabla (Sumber: Youtube) 3 Tiga dimensi musikal Merriam dapat dengan mudah disejajarkan dengan pendapat Koentjaraningrat tentang tiga wujud kebudayaan: gagasan/nilai, perilaku, dan materi. PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 3 International Seminar “Today’s Art, Future’s Culture” November 23, 2016 Permainan tabla di India mengenal pembedaan 6 jenis bunyi gendang yang disimbolkan dalam suku kata: na, ti, ting untuk bunyi gendang kecil, dan tha, thi, thing bila masingmasing bunyi gendang kecil tersebut dibunyikan bersama dengan pemukulan gendang besar. Sementara itu, angklung dan kenong pengiring reyog Ponorogo juga hanya dibedakan berdasarkan tinggi dan rendah bunyi, yang disebut ‘krik’ dan ‘krok’ untuk angklung serta ‘ning’ dan ‘nong’ untuk kenong. Melalui contoh-contoh serupa ini, mahasiswa diajak untuk melonggarkan pengertian nada yang sejatinya sangat berorientasi musik ‘barat’ untuk mencapai pengertian yang lebih universal dan inklusif tentang tinggi-rendah bunyi. Peninjauan ulang kemudian berlanjut pada pengertian sistem tangganada (scale system). Untuk membahas topik ini disajikan contoh sistem tangganada gamelan (Jawa, Bali, Sunda) dan dapat juga diperkenalkan dengan variasi 7 Maqom Tilawah Seni Baca al-Quran. Pembahasan sistem tangganada slendro dan pelog dalam gamelan juga membuka peluang untuk memperkenalkan konsep pathet yang kurang lebih setara dengan modus dalam tradisi musik ‘barat.’ Saron Slendro Gamelan Jawa (Sumber: Youtube) Salah satu materi bahasan yang menarik adalah perihal warna suara (tone color, tembre). Topik ini jarang dibicarakan dalam jenjang pendidikan sebelumnya. Padahal, warna suara merupakan salah satu unsur musik yang mendasar: musik bukan melulu pengaturan tinggi-rendah dan panjang-pendek bunyi, melainkan juga pengaturan warna suara – baik yang dihasilkan oleh tubuh manusia maupun oleh alat bunyi lainnya. Di sini mahasiswa diajak untuk mengenali kekayaan warna suara dan bagaimana masyarakat yang berlainan mengolah variasi warna suara yang mereka kenal (tentu saja bersama dengan tinggi-rendah dan panjang-pendek bunyi) untuk memproduksi musik. Materi contoh warna suara yang paling saya sukai adalah throat singing orang-orang Tuva yang hidup di perbatasan RRC dan Rusia. Throat singing sangat mengejutkan kebanyakan peserta kelas karena tidak terbiasa mendengar teknik vokal yang memproduksi lebih dari satu bunyi – suara rendah menggeram yang panjang disertai suara suara tinggi yang meliuk-liuk seperti bunyi seruling. PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 4 International Seminar “Today’s Art, Future’s Culture” November 23, 2016 Tuvan Throat Singing (Sumber: Youtube) Untuk menjembatani antara pengalaman mendengar warna suara vokal orang Tuva dengan pengalaman yang pernah atau dapat didengar mahasiswa dalam khasanah musik pop, teknik throat singing tersebut dapat disandingkan dengan teknik vokal penyanyi dari kelompok Linkin Park; atau dengan teknik vokal pemeran drama tradisional Gambuh di Bali. Hanya saja, teknik-teknik vokal yang disebut belakangan tidak menghasilkan ganda-suara. Video-clip berjudul Foli suntingan Thomas Reubers dan Floris Leuwenberg menyajikan contoh sangat baik tentang pengaturan variasi warna suara bebunyian secara ritmis menjadi sebuah komposisi musik yang menawan. Foli (Sumber: Youtube) Topik warna-suara merupakan pengantar bagi pembahasan tentang teknik produksi bunyi. Di sini pendapat Alfred Gell bahwa seni merupakan teknologi pesona (technology of enchantment) memperoleh ruang pembahasan yang tepat. Ringkasnya, Gell menyatakan bahwa daya pesona seni (termasuk musik) terletak pada teknik produksi karya seni.4 Contoh sederhana tentang pesona teknik tersebut dijumpai pada 4 Alfred Gell. 2005. ‘The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology,’ dalam Anthropology, Art and Aesthetics, Jeremy Coote dan Anthony Shelton (Eds.), Oxford: Oxford University Press PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 5 International Seminar “Today’s Art, Future’s Culture” November 23, 2016 komentar pemirsa/apresiator seni yang sering dijumpai: “Kok bisa ya.” Komentar semacam itu jelas diberikan pada aspek ketrampilan teknis pencipta/penyaji karya seni. Materi pembelajaran yang tepat digunakan untuk membangkitkan apresiasi pada ketrampuilan teknis adalah teknik pernapasan berputar (circular breathing) yang dimi8liki para pemain alat tiup etnik, seperti didgeridoo (Aborigin Australia), saluang (Minangkabau), slompret (reog Ponorogo), dan lain sebagainya. Teknik pernapasan yang memungkinkan pemain alat tiup mengalirkan udara tanpa henti seperti ini bukanlah hal yang mudah dikuasai. Melalui contoh-contoh tersebut dibangun apresiasi (penghargaan) terhadap aspek teknik musik etnik. Circular Breathing peniup Slompret Ponorogo (Sumber: Youtube) Pembahasan teknik produksi bunyi di atas dapat dilanjutkan dengan penyandingan dengan kemudahan teknis yang disediakan oleh teknologi alat musik elektronik, terutama sesudah ditemukannya Musical Instrument Digital Interface (MIDI). Pada topik bahasan ini mahasiswa diajak mengenali dilema perkembangan dan pertumbuhan teknologi rekam dan rekayasa bunyi (mulai dari amplifier, radio, hingga editing) melalui tulisan Steve Feld, seorang etnomosikolog.5 Feld menggunakan istilah schizophonia yang diperkenalkan oleh Murray Schafer untuk menyebut keterpisahan (schizm) bunyi dari sumber bunyi asali, serta menyebut pelipatgandaan lahirnya produk-produk musikal akibat pemisahan tersebut dengan istilah schizmogenesis. Contoh paling menyolok dari schizophonia dan schizmogenesis adalah kehadiran “organ tunggal” dengan keyboard canggihnya. Keyboard canggih semacam itu merupakan buah perkawinan antara teknologi dan industri-kapitalistik yang berslogan “user friendly” (ramah pengguna), memudahkan pengguna. Pada sisi kemudahan pengguna kehadiran keyboard pantas disyukuri, namun di sisi lain kehadirannya menekan peran penting relasi sosial dalam proses penguasaan teknik permainan serta menyempitkan ruang kolektivitas permainan musik. Dengan demikian, diskusi dapat diarahkan pada pemahaman tentang apresiasi musik yang berfokus pada proses dengan yang merujuk pada hasil; individual versus kolektif. 5 Steve Feld. 1995. ‘From Schizophonia to Schizmogenesis. The Discourse and Practice of World Music and World Dance,’ dalam The Traffic in Culture. Refiguring Art and Anthropology. George E. Marcus dan Fred R Myers (eds). Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 6 International Seminar “Today’s Art, Future’s Culture” November 23, 2016 Kolektivitas Kuntulan Banyuwangi (Sumber: Youtube) Menghidupi Tradisi: Dari Dekonstruksi Menuju Rekonstruksi Salah satu ciri khas pembelajaran untuk orang dewasa adalah perlunya partisipan belajar memperoleh gambaran kegunaan pengetahuan yang dipelajari. Bagi orang dewasa, materi pembelajaran akan lebih kuat diterima dan terhayati bila pengetahuan tersebut memiliki kegunaan praktikal. Matakuliah Apresiasi Musik Etnik menjawab tantangan tersebut dengan membahas dan memberi contoh pemanfaatan elemen-elemen bunyi etnik bagi musik masa kini. Pengenalan bagaimana elemen-elemen bunyi etnik digunakan dalam kehidupan musik masa kini diharapkan mampu meningkatkan penghargaan terhadap musik etnik. Contoh pemanfaatan musik etnik dalam musik populer yang paling sederhana dijumpai pada penggunaan alat bunyi etnik oleh kelompok musik populer. Jenis alat bunyi etnik yang paling sering digunakan dalam format musik populer adalah perkusi bermembran, seperti tabla, jembe, kendang, dan alat bunyi ritmis lainnya. Alat bunyi tradisional bernada, misalnya alat bunyi tiup, petik, dan pukul (logam maupun kayu) lebih jarang dan sulit dicampurkan dengan alat musik ‘Barat’ modern karena adanya perbedaan sistem tangga nada (tone system). Meskipun demikian, ada pula alat bunyi etnik berdawai (yang digesek maupun dipetik) yang ketegangan dawainya diatur menyesuaikan tangga nada musik ‘barat’ modern. Begitu pula, pengubahan tinggi rendah bunyi dan interval dapat dilakukan pada alat bunyi tradisional logam maupun kayu yang dimainkan dengan cara dipukul (angklung, gamelan, marimba, dan lainnya). Kehadiran berbagai warna suara alat bunyi tradisional di antara bebunyian alat elektronik menghadirkan nuansa bunyi yang alami dan variatif. Kelompok 12 Girls Band dari Cina merupakan salah satu contoh penggunaan alat musik etnik tradisional dalam format musik populer. Komposisi musik karya selusin perempuan ini menyajikan bunyi-bunyian khas alat musik etnik tradisional Cina, namun sekaligus cukup akrab di telinga karena dikemas dalam citarasa musik pop modern. Di tanah air gejala serupa antara lain dapat dijumpai pada Saung Angklung Mang Ujo, Bandung, Jawa Barat. Mereka menggunakan ensambel angklung yang telah ditala secara kromatis musik ‘barat’ untuk memainkan lagu-lagu populer, misalnya We Are the Champion yang dipopulerkan oleh grup rock Inggris The Queen. PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 7 International Seminar “Today’s Art, Future’s Culture” 12 Girls Band (Sumber: Youtube) November 23, 2016 Angklung Mang Ujo (Sumber:Youtube) Pemanfaatan ke dalam musik populer juga dilakukan berupa pencangkokan idiom musikal etnik ke dalam karya musik populer. Salah satu contoh yang baik untuk praktik ini adalah kelompok Ladysmith Black Mambazo dari Zulu, Afrika. Kelompok accapela laki-laki ini menyajikan lagu-lagu dengan teknik dan gaya bernyanyi etnik mereka yang khas. Keunikan nyanyian mereka telah menarik perhatian Paul Simon untuk berkolaborasi dalam album Graceland, dan suara mereka juga dapat dinikmati dalam lagu tema film The Lion King. Ladysmith Black Mambazo (Sumber: Youtube) Masih dalam topik bahasan persenyawaan alat bunyi dan idiom musik etnik dengan musik populer, mahasiswa juga diajak untuk mengapresiasi musik dangdut dan keroncong. Ditunjukkan bagaimana dangdut menyerap berbagai unsur musikal etnik, mulai dari alat bunyi, melodi hingga teknik vokal penyanyinya. Sementara itu, permainan cello pada musik keroncong dapat digunakan sebagai contoh bagaimana alat musik ‘Barat’ dimainkan dengan teknik dan pola permainan yang mengacu pola permainan kendang ciblonan dalam tradisi gamelan Jawa. Keroncong dan dangdut, dua PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 8 International Seminar “Today’s Art, Future’s Culture” November 23, 2016 jenis musik hibrida produk kreativitas anak bangsa tersebut, saat ini diakui dunia sebagai dua jenis musik populer Indonesia. Penutup Paparan di atas telah menggambarkan bagaimana matakuliah Apresiasi Musik Etnik telah diarahkan pada penumbuhan kesadaran akan perbedaan dan kemajemukan (pluralitas) jagat musik. Darinya dapat dirangkum butir-butir gagasan umum sebagai berikut: 1. Mengalami materi dan perilaku seni yang berbeda dari yang biasanya dialami merupakan syarat utama bagi apresiasi pluralitas seni. Pengenalan materi dan perilaku seni yang berbeda-beda diarahkan pada ditemukannya kesamaan atau padanan di ranah konseptual. 2. Penilaian estetik (misalnya indah/buruk, merdu/sumbang) diakui keniscayaannya bukan sebagai norma untuk diikuti begitu saja, namun untuk dikritisi kemampuan norma tersebut bagi pemahaman gejala seni yang lebih luas dan inklusif. 3. Salah satu alternatif menuju pemahaman seni yang lebih inklusif adalah dengan memandang seni secara akademis sebagai teknik pengaturan gejala inderawi untuk menghasilkan pesona. 4. Pendekatan teknis terhadap seni membuka peluang bagi pemanfaatan dan pengkombinasian berbagai unsur material dan perilaku seni untuk kerja kreatif seni atau untuk mengapresiasi karya-karya serupa. Sementara itu, paparan di atas juga menunjukkan bahwa: 1. Pendidik seni untuk toleransi terutama perlu memiliki pengetahuan, pengalaman dan menguasai perbendaharaan seni yang kaya serta beranekaragam. 2. Keterbatasan penguasaan teknis pendidik seni dapat dilengkapi lewat penggunaan sumber-sumber informasi internet untuk menghadirkan contoh-contoh materi pembelajaran. Akhirnya, mengutip ulang kolofon di awal tulisan, penulis percaya bahwa “By learning how the people in another culture express themselves musically, students are not only given insights into others but also learn about themselves.” ****** Daftar Pustaka Feld, Steve. 1995. ‘From Schizophonia to Schizmogenesis. The Discourse and Practice of World Music and World Dance,’ dalam The Traffic in Culture. Refiguring Art and Anthropology. George E. Marcus dan Fred R Myers (eds). Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Gell, Alfred. 2005. ‘The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology,’ dalam Anthropology, Art and Aesthetics, Jeremy Coote dan Anthony Shelton (Eds.), Oxford: Oxford University Press. Volk, Terese M.. 1998. Music Education and Multiculturalism. Foundations and Principles. New York & Oxford: Oxford University Press. PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 9 International Seminar “Today’s Art, Future’s Culture” November 23, 2016 BIODATA SINGKAT Nama lengkap : Gabriel Roosmargo Lono Lastoro Simatupang Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 22 Maret 1960 Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan Terakhir : Doktor Antropologi, University of Sydney (2004), disertasi “Play and Display. An Ethnographic Study of Reyog Ponorogo in East Java, Indonesia.” Instansi Kerja : Departemen Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, UGM Pekerjaan : Dosen di Departemen Antropologi Budaya, FIB, UGM; di Program Studi S2/S3 Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Sekolah Pasca Sarjana, UGM, dan di Program Studi S2/S3 Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pasca Sarjana, UGM. Jabatan : Ketua Program Studi S2/S3 Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Sekolah Pasca Sarjana, UGM (2012 – sekarang) Publikasi : Pergelaran. Mozaik Kajian Seni dan Budaya. Yogyakarta: Jalasutra (2013) PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 10