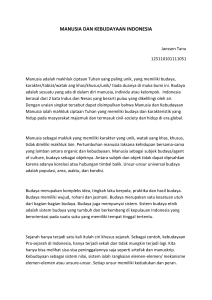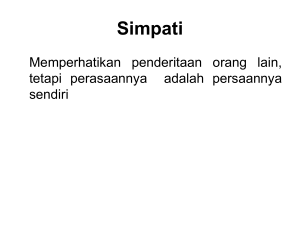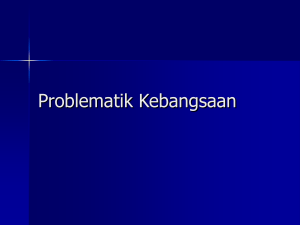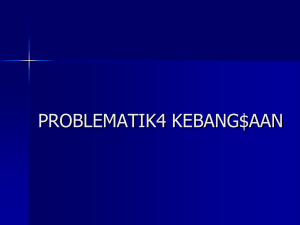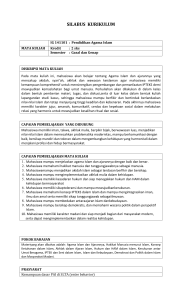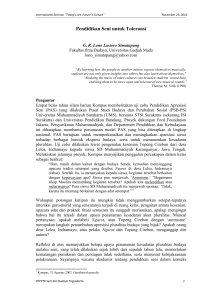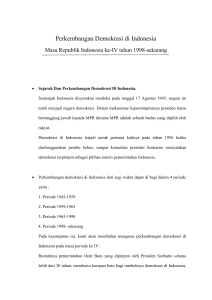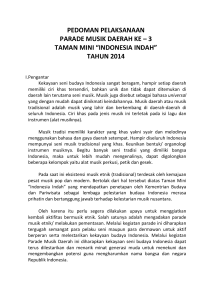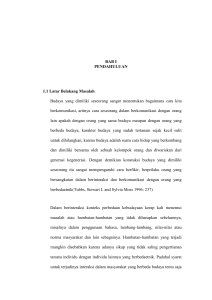MANAJEMEN BENCANA SOSIAL DAN AKAR KONFLIK SOSIAL
advertisement
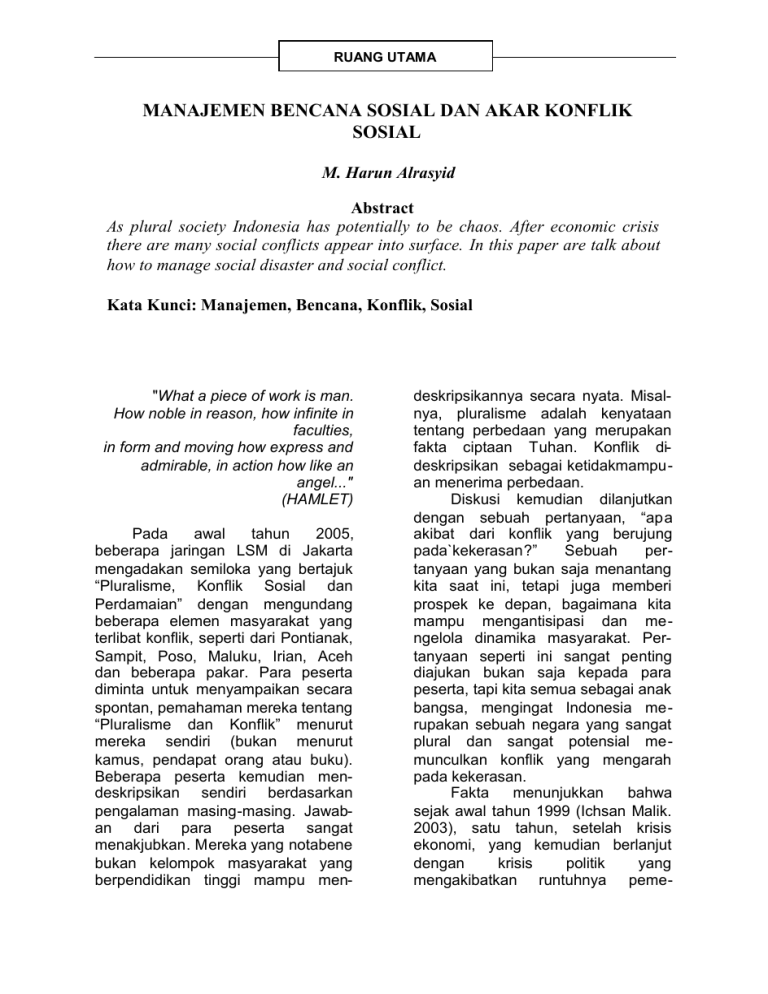
RUANG UTAMA MANAJEMEN BENCANA SOSIAL DAN AKAR KONFLIK SOSIAL M. Harun Alrasyid Abstract As plural society Indonesia has potentially to be chaos. After economic crisis there are many social conflicts appear into surface. In this paper are talk about how to manage social disaster and social conflict. Kata Kunci: Manajemen, Bencana, Konflik, Sosial "What a piece of work is man. How noble in reason, how infinite in faculties, in form and moving how express and admirable, in action how like an angel..." (HAMLET) Pada awal tahun 2005, beberapa jaringan LSM di Jakarta mengadakan semiloka yang bertajuk “Pluralisme, Konflik Sosial dan Perdamaian” dengan mengundang beberapa elemen masyarakat yang terlibat konflik, seperti dari Pontianak, Sampit, Poso, Maluku, Irian, Aceh dan beberapa pakar. Para peserta diminta untuk menyampaikan secara spontan, pemahaman mereka tentang “Pluralisme dan Konflik” menurut mereka sendiri (bukan menurut kamus, pendapat orang atau buku). Beberapa peserta kemudian mendeskripsikan sendiri berdasarkan pengalaman masing-masing. Jawaban dari para peserta sangat menakjubkan. Mereka yang notabene bukan kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi mampu men- deskripsikannya secara nyata. Misalnya, pluralisme adalah kenyataan tentang perbedaan yang merupakan fakta ciptaan Tuhan. Konflik dideskripsikan sebagai ketidakmampuan menerima perbedaan. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan, “apa akibat dari konflik yang berujung pada`kekerasan?” Sebuah pertanyaan yang bukan saja menantang kita saat ini, tetapi juga memberi prospek ke depan, bagaimana kita mampu mengantisipasi dan mengelola dinamika masyarakat. Pertanyaan seperti ini sangat penting diajukan bukan saja kepada para peserta, tapi kita semua sebagai anak bangsa, mengingat Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat plural dan sangat potensial memunculkan konflik yang mengarah pada kekerasan. Fakta menunjukkan bahwa sejak awal tahun 1999 (Ichsan Malik. 2003), satu tahun, setelah krisis ekonomi, yang kemudian berlanjut dengan krisis politik yang mengakibatkan runtuhnya peme- rintahan Orde Baru, meledaklah konflik sosial atau konflik antar kelompok masyarakat dengan menggunakan identitas agama dan etnis di berbagai propinsi di Indonesia seperti Maluku, Poso dan Sampit. Yang paling ekstrim konfliknya adalah di Maluku, dengan korban nyawa ribuan jiwa, 300 ribu orang menjadi pengungsi di negerinya sendiri, masyarakat terbelah menjadi dua berdasarkan identitas agama, kedua kelompok dilanda rasa putus asa, rasa dendam yang masih terus membara, serta ”luka psikologis” yang masih menganga pada sebahagian korban hingga saat ini. Rentetan konflik yang telah memakan korban tak terhingga sepatutnya menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa konflik kekerasan hanyalah meninggalkan luka yang tak berkesudahan. Konflik yang semakin meluas ini seyogyanya menjadi bahan pelajaran tentang perlunya rekonstruksi wacana dan praktik kebangsaan yang baru, di mana selama tiga dasawarsa terakhir mengalami disorientasi lewat konstruksi yang dipaksakan dan hanya memenuhi absolutisme negara. Sistem poitik Orde Baru adalah contoh bagaimana wawasan kebangsaan digunakan sebagai instrumen untuk memaksa warganya tunduk dan patuh atas nama nasionalisme dan kepentingan nasional. sempit lainnya semakin mengkristal dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan ini mendorong mencuatnya kembali pembahasan mengenai pentingnya reaktualisasi wawasan kebangsaan. Nilai-nilai moral banyak dilanggar, kerukunan dirusak, dan kedamaian dicabikcabik. Perkelahian antar etnis makin besar, pertarungan antar golongan makin keras, permusuhan antar agama makin meletup, pertikaian antar elite makin mengembang. Bahkan tawuran antar siswa makin menjadi-jadi. Itu semua melambangkan makin lemahnya manusia Indonesia sekarang dalam mengaplikasi nilai-nilai kebangsaan. Samuel Huntington pernah berkomentar pada akhir abad ke-20, bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi paling besar untuk hancur, setelah Yugoslavia dan Uni Soviet akhir abad ke-20 ini. Demikian juga Clifford Geertz, antropolog yang Indonesianis ini pernah mengatakan; kalau bangsa Indonesia tidak pandai-pandai memanajemen keanekaragaman etnik, budaya, dan solidaritas etnik, maka Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil. Masalah wawasan kebangsaan dalam negara kesatuan yang multietnik dan struktur masyarakatnya majemuk, seperti “srigala berbulu domba” atau penuh ambivalensi (ambigu). Perfomancenya menam pakan sebuah keseimbangan (equillibrium) diantara struktur sosial, politik, dan kebudayaan, tetapi isinya penuh dengan intrik, ketidakpuasan, paradoks, etnosentrisme, stereotipisme, dan konflik sosial yang tidak kunjung selesai. Wawasan Kebangsaan: Mitos yang mulai pudar Banyak kalangan mulai mempersoalkan mengapa sekarang ini paham kelompok atau golongan, sikap individualistik dan wawasan 2 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005 Wawasan kebangsaan atau nasionalisme adalah ideologi yang memandang seluruh rakyat yang menginginkan membangun masa depannya secara bersama sebagai suatu nation atau bangsa. Ir Soekarno sebagai tokoh pergerakan nasional Indonesia amat gemar mengutip penjelasan Ernest Renan dan Otto Bauer. (Heriyadi, 2004). Ernest Renan menerangkan, nation adalah mereka yang mempunyai hasrat kuat untuk hidup bersama. bangsa menjaga kemampuan survivalnya. Otto Bauer menambahkan suatu faktor lagi untuk terbentuknya bangsa, yaitu persamaan watak yang terbentuk dari persamaan nasib. Ciri khas suatu nation adalah adanya persamaan status dari seluruh rakyat walaupun beraneka ragam latar belakang agama, ras, etnik atau golongannya. Dalam lingkup Indonesia, berkembang pula berbagai pemikiran yang membatasi pengertian wawasan kebangsaan. Salah satunya adalah pandangan Siswono Yudohusodo (1996) yang mengatakan, substansi dari rasa kebangsaan adalah kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa akibat kesamaan sejarah dan kepentingan masa depannya dan merupakan perekat yang mempersatukan sekaligus memberi dasar kepada jati diri bangsa. Operasionalisasi dari rasa kebangsaan itu kemudian disebut sebagai wawasan kebangsaan. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memaknai pemahaman itu. (1) Adanya keputusan rakyat untuk bersatu sebagai bangsa. (2) Perasaan senasib dan sepenanggungan. (3) Adanya kepentingan bersama dan kepentingan dari unsur-unsur pembentuk bangsa. (4) Kesadaran mendahulukan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan pribadi atau golongan. (5) Semangat untuk mempertahankan rasa dan semangat kebangsaan itu. (6) Adanya kemampuan bangsa untuk secara terusmenerus memenuhi kepentingan unsur-unsur pembentuknya. (Heriyadi, 2004) "Bangsa ialah jiwa, suatu asas rohani. Dua hal yang sesungguhnya hanya berwujud satu yang membentuk jiwa atau asas rohani itu. Yang satu terdapat dalam waktu yang silam, yang lain dalam waktu sekarang. Yang satu yakni me-miliki bersama kenang-kenang-an yang kaya raya, yang lain mempergunakan warisan yang diterima secara tidak terbagi. Bangsa tidak timbul se-konyong-konyong, melainkan hasil masa silam yang penuh dengan usaha, pengorbanan dan pengabdian." (Dalam S Bahar: 2000). Hal yang menjadi penekanan Renan, asumsi hidup sebagai suatu bangsa adalah suatu plebisit atau keputusan rakyat dan keputusan tersebut didasari oleh adanya keinginan dari segenap komponennya. Keinginan sendiri itulah yang akhirnya menjadi satu-satunya kriterium atau tanda pengenal dan pegangan yang sah dan harus selalu diperhatikan. Ketidakmampuan bangsa memelihara dan memenuhi keinginan komponen bangsa itu, akan menjadi pemicu awal gagalnya suatu 3 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005 Dalam wawasan kebangsaan kita dewasa ini, unsur tadi dirasakan semakin mengalami kemunduran yang drastis. Bahkan ada yang mengatakan telah kehilangan "greget". Misalnya, mencuatnya paham kelompok/golongan, miskin nasionalisme, warga bangsa seperti kehilangan daya rekat, konflik horizontal, konflik vertikal. (Ryacudu, 2004) Karena itu, dalam upaya merekonstruksi konsepsi kebangsaan kita di era reformasi ini, setidaknya ada tiga tantangan yang terlebih dahulu harus mendapat perhatian serius. Pertama, jika kita mengartikan Indonesia sebagai nation state sebagaimana pembentukan nation state di Eropa, maka konsepsi kebangsaan kita memang telah “membingungkan” sejak awal (complecatted). Jika rasionalitas pembentukan nation state di Eropa adalah pengelompokkan sosiokultural yang dibangun bersama dalam dan melalui state, maka pembentukan nation state di Indonesia lebih karena “beban” politik yang mesti ditanggung sepeninggal hengkangnya pemerintah kolonial. Kedua, nation dan state adalah dua domain yang berbeda namun berimpit posisinya dalam konteks pembentukan negara modern. Namun yang terjadi selama dekade rezim Orde Baru lebih sebagai perebutan dan penaklukan domain nation oleh state. Pluralitas diakui namun lebih bersifat artifisial dan berikutnya beranjak menjadi haram dalam pengelolaan wacana kebangsaan dan kenegaraan. Kebutuhan strategis yang hendak dielaborasi adalah bagaimana ada perimbangan baru antara wilayah nation dan state ini dalam lingkup Indonesia yang multikultural. Yang diharapkan kemudian adalah munculnya kebijakankebijakan politik yang lebih adil dan sensitif terhadap pluralitas keindonesiaan. Jika selama ini negara tampil sebagai aktor yang dominan di atas masyarakat, maka kerangka pengelolaan ke depan membutuhkan pelibatan yang lebih besar dari masyarakat. Ketiga, kegagalan untuk menemukan satu faktor yang secara kuat dapat menumbuhkan kebanggaan kolektif atau membuat berbagai komponen masyarakat merasa satu. Identitas kolektif seperti Pancasila, yang sebelumnya dipercaya sebagai sumber perekat bangsa, seperti kehilangan makna, tenggelam oleh bangkitnya sentimen primordial yang cenderung eksklusif. Karena itu, pencarian kebanggaan kolektif merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai upaya untuk merevitalisasi wawasan kebangsaan yang mulai menurun. Namun, terlepas dari tiga tantangan tersebut, hal pokok yang harus dipetik dan disepakati bahwa persatuan bangsa yang kita bangun tidak tersaji atas landasan dan kepentingan etnik, maupun primordialisme. Tidak juga bersifat temporer dan untuk waktu sementara. Persatuan nasional itu dibangun dan ditegakkan justru lebih didasari oleh landasan etik dan kesadaran bersama sebagai satu bangsa sehingga nilai-nilai etika kebangsaan yang menyangkut persatuan dan kesatuan terbangun cukup kuat untuk mengakomodasikan berbagai perbedaan dan bahkan konflik kepentingan. 4 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005 Konflik Sosial: Bangsa Multietnik Keniscayaan Hal ini sesuai dengan konsep konflik yang definisikan oleh Lewis Coser, bahwa konflik sesungguhnya adalah usaha untuk memperebutkan status, kekuasaan, dan sumbersumber ekonomi yang sifatnya terbatas, di mana pihak-pihak yang berkonflik bukan hanya berniat untuk memperoleh barang yang dimaksud tetapi juga berniat untuk menghancurkan lawannya. Dalam kondisi konflik, maka sadar ataupun tidak sadar setiap yang berselisih akan berusaha untuk meningkatkan dan mengabdikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas di antara sesama anggotanya. Misalnya, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama; mendirikan sekolah untuk memperkuat identitas kultural, meningkatkan sentimenitas etnosentrisme, stereotipisme, keagamaan dan usaha-usaha lain yang meningkatkan primordialisme. Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, sangat rasional sekali bila Indonesia selalu menghadapi permasalahan konflik antar etnik, kesenjangan sosial, dan sukar sekali terjadinya integrasi secara permanen. Hambatan demikian semakin nampak dengan jelas, jika diferensiasi sosial berdasarkan parameter suku bangsa jatuh berhimpitan (Coincided) dengan parameter lain (agama, kelas, ekonomi, dan bahasa), sehingga sentimen-sentimen yang bersumber dari parameter sosial yang satu cenderung berkembang saling mengukuhkan dengan sentimen-sentimen yang bersumber dari diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain. Konsolidasi parameter struktur sosial Kata konflik menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti percekcokan, perselisihan, pertikaian, pertentangan, benturan, atau clash antar manusia. Konflik seperti itu bisa timbul bila ada perbedaan pendapat, pandangan, nilai, cita- cita, keinginan, kebutuhan, perasaan, kepentingan, kelakuan, atau kebiasaan. Sedangkan dalam pengertian yang umum (longgar), didefinisikan sebagai perbedaan sosio-kultural, ekonomi, politik, dan ideologis di antara berbagai kelompok masyarakat, pada dasarnya tak bisa dipisahkan dari hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan kolektif. Apalagi bangsa kita dianugerahi keanekaragaman sosio-kultural yang bahkan sering saling tumpang tindih. Karena itu wajar jika bangsa yang heterogen ini menyimpan potensi konflik tinggi. Sementara itu segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuankesatuan sosial yang terikat ke dalam ikatan-ikatan primordial dengan subkebudayaan yang berbeda sangat mudah sekali melahirkan konflikkonflik sosial. Dalam kondisi seperti ini, konflik akan terjadi dalam dua dimensi; dimensi pertama adalah konflik di tingkatan ideologis, konflik ini terwujud di dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh etnik pendukungnya serta menjadi ideologi dari kesatuan sosial. Dimensi kedua adalah konflik yang terjadi dalam tingkatan politis, pada konflik ini terjadi dalam bentuk pertentangan dalam pembagian status kekuasaan dan sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat. (Nasikun, 1989). 5 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005 (Concolidated Social Structure) yang demikian menurut Peter Blau merupakan kendala yang paling besar bagi terciptanya integrasi sosial. Sementara itu ,secara antropologis diferensiasi sosial yang melingkupi struktur sosial kemajemukan masyarakat Indonesia adalah; pertama, diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat (custome diferentiation). Hal ini karena perbedaan etnik, budaya, agama, dan bahasa. Kedua adalah diferensiasi yang disebabkan oleh struktural (strucural diferentiation). Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengakses ekonomi dan politik secara adil, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di antara etnik yang berbeda. Pada zaman Hindia-Belanda masyarakat Indonesia digolongkan menjadi tiga golongan oleh antropolog Belanda Furnivall; yaitu golongan penjajah Belanda yang menempati tingkat pertama, kedua adalah golongan minoritas Cina, sedangkan golongan pribumi menempati tingkat yang ketiga. Terlepas dari pendekatan konsep mana yang akan digunakan, tapi secara substansi semua konsep yang menjelaskan tentang heteregonitas (kemajemukan) ataupun masyarakat yang plural, pada hakekatnya tidak jauh berbeda (congruent). Pada satu sisi kemajemukan menyimpan kekayaan budaya dan khasanah tentang kehidupan bersama yang harmonis, jika integrasi berjalan dengan baik (menurut aksioma; structural functionalism approach). Tetapi pada sisi lain, kemajemukan selalu menyimpan dan menyebabkan ter- jadinya konflik antar etnik, baik yang bersifat latency maupun yang manifest (dalam aksioma, conflict approach) yang disebabkan oleh etnosentrisme, primordialisme dan kesenjangan sosial. Wawasan Kebangsaan Dinamika Konflik Perbedaan antar golongan dalam sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia merupakan sesuatu yang wajar dan lazim adanya, tetapi menjadi tidak wajar apabila perbedaan dijadikan alasan untuk saling menyerang atau mengucilkan satu golongan sehingga kemudian konflik terus dipelihara dan dibiarkan terus berkembang menjadi sebuah tindak kekerasan. Eskalasi konflik sosial di Indonesia terjadi setelah adanya perubahan rezim dari era Orde Baru ke Orde Reformasi. Perubahan ini ditandai dengan melemahnya Pemerintah Pusat dan berbagai institusi pemerintahan, seperti kepolisian dan militer. Selama kurun waktu 1998 – 1999 saja berbagai konflik terjadi di berbagai tingkatan, yang dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu: Pertama, konflik sosial antar ras berupa penjarahan pertokoan, pembunuhan dan pemerkosaan non pribumi bulan Mei 1998 di Jakarta. Kedua, konflik sosial antar kelompok beragama berupa pembakaran dan pemboman gereja (peristiwa Ketapang, Jakarta), pembakaran mesjid (Kupang, NTT) dan kemudian menyebar ke Ambon, Januari 1999 dan Ujung Pandang, April 1999. Ketiga, konflik sosial antar suku berupa perkelahian dengan 6 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005 Dan pembunuhan antar suku di Sambas Kalimantan Barat. Keempat, konflik antar pusat dan daerah seperti Aceh, Irian dan Riau berhadapan dengan Pemerintah Pusat, termasuk TNI. Kelima, konflik sosial antar kelompok politik seperti terdapat dalam kasus santet di Jawa Timur, 1998, perbenturan antar partai di Purbalingga Jawa Tengah, 1999, bentrok bersenjata antar kelompok pro-integrasi dengan pro-kemerdekaan di Timor Timur (Abas, 2002). Adapun dampak sosial yang ditimbulkan oleh konflik kekerasan tersebut, baik itu bernuansa etnik maupun politik, dampaknya tidak dapat terkirakan. Pertama, hancurnya sumber-sumber kehidupan dan mata pencaharian penduduk, hilangnya kepercayaan investor yang pada akhirnya mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat menurun drastis. Kedua, kebebasan berdemokrasi menjadi tertekan akibat adanya dominasi etnik tertentu dalam politik dan kekuasaan, sistem pelayanan dalam birokrasi menjadi terganggu, rusaknya struktur pemerintahan dan tatanan birokrasi pada tingkat lokal dan adanya gangguan stabilitas keamanan. Ketiga, hancur dan retaknya nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang mengakibatkan nilai-nilai kearifan lokal pun semakin memudar. Konflik menyebabkan masyarakat yang bertikai menjadi terbatas dalam berinteraksi. Keempat, timbulnya rasa takut, bahkan mungkin saja menjadi paranoid yang berkepanjangan karena menyaksikan secara langsung pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing etnik yang bertikai. Era reformasi yang diharapkan menjadi gerbang ke arah terbentuknya negara modern, menghadapi tantangan besar dalam upaya tetap dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kedewasaan dan kearifan kita tampaknya belum cukup matang untuk menyikapi berbagai konflik dan benturan kepentingan. Demikian halnya jika agenda reformasi politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam tidak lagi diletakkan dalam kerangka kebangsaan, maka mimpi buruk akan terjadinya disintegrasi bisa jadi akan menjadi kenyataan. Dalam tatanan masyarakat maju dan mandiri, di mana lintas batas tidak lagi jelas, justru wawasan kebangsaan amat memegang peranan sentral. Wawasan kebangsaan bukan hanya menjadi push power untuk berpacu dan mampu bersaing dengan negara lain, tetapi secara simultan paham kebangsaan sekaligus juga menjadi daya tangkal terhadap berbagai upaya yang dapat mengancam eksistensi bangsa. Di tengah makin terbukanya koridor dan bahkan otoritas suatu bangsa atas wilayahnya, wawasan kebangsaan atau nasionalisme menjadi perekat utama yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai masalah internal kebangsaan. Paling tidak ada penyikapan yang sama dalam merespon tantangan global yang makin signifikan jika seluruh komponen bangsa mendasarkan diri pada dasar kebangsaan (nasionalisme). Dalam konteks inilah siapa pun dan apapun peran kebangsaannya, harus secara konsisten dapat mengembangkan sikap nasionalismenya. 7 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005 Hal pokok yang harus dipetik dan disepakati bahwa persatuan bangsa yang kita bangun tidak tersaji atas landasan dan kepentingan etnik, maupun primordialisme. Tidak juga bersifat temporer dan untuk waktu sementara. Persatuan nasional itu dibangun dan ditegakkan justru lebih didasari oleh landasan etik, dan kesadaran bersama sebagai satu bangsa sehingga nilai-nilai etika kebangsaan yang menyangkut persatuan dan kesatuan terbangun cukup kuat untuk mengakomodasikan berbagai perbedaan dan bahkan konflik kepentingan. Manajemen Keharusan Konflik: perbedaan, dan pluralitas yang ada di dalam dirinya sendiri. Itu sebabnya mengapa ketika konflik antar etnis, suku, golongan, kelompok politik dan agama itu muncul dan merebak ke mana-mana, lantas kita kebingungan sendiri, tidak tahu dan tidak mampu mengatasinya. Lemahnya kita menguasai manajemen konflik, disebabkan kurangnya pengalaman kita mengelola perbedaan dan pluralitas secara demokratik, dan aparat keamanan hanya mengenal cara-cara kekerasan saja, dan elite politik miskin wawasan pluralitasnya, kurang pengalaman dalam praktik demokrasi politik, sehingga kurang mampu mengendalikan kepentingan politik dan egoisme pribadinya yang berbenturan dengan kepentingan berbangsa dan bernegara. (Asyhari, 2005). Oleh karena itu, ada dua hal yang harus mendapatkan perhatian serius, yaitu, pertama, terus menerus menumbuhkan “solidaritas emosional” dalam bingkai kebangsaan, sehingga interaksi antar etnis dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Pengelolaan negara pun harus diarahkan sedemikian rupa sehingga berbagai kebijakan yang dijalankan tidak menimbulkan perasaan termarginalisasi bagi suatu kelompok etnis tertentu. Kedua, nation building harus terus menerus ditumbuhkembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mewujudkan “solidaritas fungsional”, yaitu solidaritas yang didasarkan pada ikatan saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. (KOMPAS, 20 Desember 2002). Jadi, kata kuncinya adalah membangun kerja sama dan Sebuah Konflik dalam kehidupan masyarakat, didorong oleh perubahan, perbedaan dan pluralitas yang bergerak dialektik. Manajemen konflik diperlukan agar proses dialektika perubahan, perbedaan, dan pluralitas berjalan wajar, terbuka, cerdas dan mencerahkan guna menemukan sintesa baru yang adil dan dapat diterima sebagai keniscayaan sementara, dan bentukbentuk sintesa baru selalu lahir dan memperkaya kehidupan masyarakat. Dalam manajemen konflik tidak ada penolakan terhadap perubahan, perbedaan dan pluralitas kehidupan masyarakat, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya maupun keagamaan, tetapi menjaga, mengelola dan mengarahkannya membentuk sintesa-sintesa baru. Karena itu masyarakat harus punya waktu dan kesempatan mendidik dirinya menjadi makin dewasa dalam menghadapi dinamika perubahan, 8 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005 kemitraan antar pihak berkepentingan tanpa harus membeda-bedakan. Untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik di masa mendatang, kiranya langkah berikut perlu untuk dipertimbangkan: 1. Memantapkan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan, terutama melalui jalur pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan bisa memainkan tiga fungsi sekaligus. Dalam jangka pendek memainkan fungsi instruksionalisasi, jangka menengah memainkan fungsi ekonomasi, dan jangka panjang memainkan fungsi kulturalisasi. 2. Segenap pihak perlu membangun kesepakatan atau konsensus lokal dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik dan gejolak, terutama bagi daerah yang potensial konflik. Konsensus lokal itu tidak hanya melibatkan elemen pemerintahan, tetapi juga tokohtokoh LSM, ormas, pers dan akademisi setempat. Melalui kesepakatan lokal itu diharapkan dapat dihasilkan, misalnya kode etik kehidupan bermasyarakat, kode etik kampanye, komitmen rule of law dan seterusnya. 3. Mengevaluasi kembali berbagai kebijakan yang cenderung mempertajam konflik dalam masyarakat. Konflik tidak saja disebabkan semata-mata faktor masyarakat yang multi etnis, namun juga berbagai kebijakan nasional justru telah mendorong munculnya konflik, seperti kebijakan pemanfaatan sumber daya air, eksplorasi hutan lindung dan tentang pemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan Pilkada Langsung sangat berpeluang munculnya konflik dalam kehidupan masyarakat. 4. Perlu kembali digalakkan komunitas atau forum-forum warga dengan perspektif baru melalui pendekatan partisipasi dan kebutuhan lokalitas, di mana sejak reformasi dan era otonomi daerah forum -forum warga semakin menghilang, seperti kelompencapir, posyandu, UDKP, dan sebagainya. Forum ini sebaiknya didesain bukan hanya sekedar diskusi me lainkan juga menjadi wadah untuk mencairkan perbedaan dalam masyarakat, sebagai early warning bila ada kejadian yang extra-ordinary. Kepustakaan Adisubrata, W.S. 1999. Otonomi Daerah di Era Reformasi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN. Burton, J. 1990 . Conflict: Resolution and Prevention. New York: St. Martin’s Press. Hidayat, S.N. 2000. Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan. PT Pustaka Quantum Indonesia. Malik, Ichsan. 2003. BAKUBAE, Gerakan Dari Akar Rumput Untuk Penghentikan Kekerasan di Maluku , Jakarta: LSPP Malik, Ichsan. Pidato Ilmiah. Kontribusi Psikososial Dalam Penanganan Konflik. 2004. 9 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005 Markum, Enoch. 2004. Paper, Konflik Antar kelompok Dalam Perspektif Psikologi, Jakarta. Nasikun. 1989. Indonesia. Sistem University of New South Wales Taylor, P.M. (peny.) 1994. The Nusantara Concept of Culture: Local Traditions and National Identity as Expressed in Indonesia’s Museums’, in P.M. Taylor (peny.) Fragile Tradition: Indonesian Art in Jeopardy. Honolulu: The University of Hawaii Press. Sosial Sakai, Minako. (peny.) In-Press Beyond Jakarta: Regional Autonomy and Local Societies in Indonesia. Adelaide: Crawford House Publishing. Usman, Dahrun. Etnopolitic Conflict, Sparatisme, Dan Masalah Integrasi Nasional. Jurnal Antropologi Indonesia, 2004 Sakai, Minako. Konflik sekitar Devolusi Kekuasaan Ekonomi dan Politik: Suatu Pengantar, The 10 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005