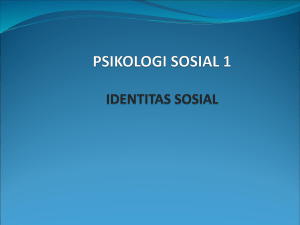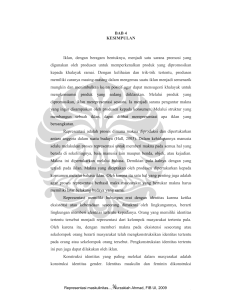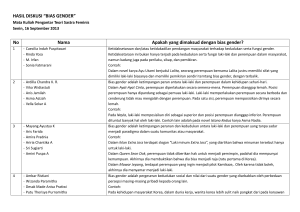BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada abad pertengahan
advertisement

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada abad pertengahan, tepatnya abad ke-14 dan ke-15, Eropa dihebohkan oleh isu witch-hunt atau perburuan penyihir. Di Eropa tengah, isu witch-hunt mengakibatkan banyak orang diadili, disiksa, dieksekusi, bahkan digantung atau dibakar hidup-hidup di depan umum karena dianggap penyihir. Larner (2000:3) menyebutkan tiga-perempat dari para korban tersebut adalah perempuan. Pada masa itu, perempuan hampir menjadi jaminan melakukan praktek sihir. Para perempuan Eropa, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa, secara selektif telah ditargetkan untuk menjadi korban kekejaman tersebut. Secara keseluruhan sekitar 7580 persen dari mereka yang dituduh dan dihukum karena sihir di masa awal era Eropa Modern adalah perempuan. Sekitar 9 juta perempuan dibakar hidup-hidup. Melihat jumlah ini, dapat dikatakan bahwa perburuan penyihir ini merupakan kasus pembunuhan massal terbesar berbasis gender. Di abad pertengahan, konsep orang Eropa dalam memahami perempuan berangkat dari tradisi teologi tentang Eve dan Lilith. Perempuan dianggap sebagai perwujudan negatif yang tidak ada habisnya. Secara ontologi, perempuan adalah sepupu pertama yang muncul dari “kiri” atau sisi buruk manusia (Katz, 1994: 435). Sebuah buku berjudul Malleus Maleficarum (The Hammer of Witches) yang diterbitkan oleh Otoritas Inkuisisi Katolik mencatat hal tersebut. Buku ini telah 1 menimbulkan aib pada ribuan perempuan, yang sekaligus menjadi penyulut misogini gila. “sebagian dari kejahatan adalah kejahatan perempuan… perempuan adalah musuh dari persahabatan, hukuman yang tak dapat terhindari, hasrat akan bencana, bahaya yang sifatnya domestik, kelezatan yang merugikan, sebuah sifat jahat, yang terbungkus dalam balutan kecantikan…. Pada dasarnya perempuan adalah instrument dari setan—mereka pada dasarnya adalah cacat struktural yang berakar pada penciptaannya (Katz, 1994: 438– 439). Menurut Katz (1994: 350) ada beberapa aspek yang membuat perempuan dituduh sebagai penyihir. Perempuan yang tampaknya paling independen terhadap norma-norma patriarkal sering dianggap sebagai peyihir. Selain itu, perempuan tua yang hidup sendiri tanpa anak dan suami, serta banyak meminta dari tetangganya untuk bertahan hidup, tetapi tidak banyak yang bisa ia tawarkan sebagai imbalannya adalah golongan yang paling rentan terhadap tuduhan praktik sihir. Perempuan seperti ini dianggap sebagai beban ekonomi oleh lingkungannya, sehingga dirasa merupakan lokus dari sifat dengki yang berbahaya dan kekerasan verbal. Keyakinan bahwa witch adalah perempuan yang memiliki kemampuan magis dan menggunakannya untuk kejahatan, kemudian diadopsi ke dalam cerita anak-anak Barat. Cerita anak yang mengangkat penyihir perempuan (witch) sebagai tokoh antagonis misalnya Sleeping Beauty, Snow White, Rapunsel, Donal Duck, Alice in Wonderland, dan The Chronicle of Narnia. Dalam dongeng-dongeng anak, seperti Sleeping Beauty, Snow White, dan Rapunsel, Witch digambarkan bahwa perempuan 2 adalah makhluk yang mengerikan, hidup sendirian di tempat-tempat menyeramkan dan berusaha merusak kebahagiaan orang lain karena rasa iri dan dengki. Sementara di cerita Alice in Wonderland dan The Chronicle of Narnia, Witch adalah perempuan keji yang berusaha menguasai dunia dengan kejahatannya. Deskripsi ini sama persis dengan apa yang diyakini masyarakat di masa awal Eropa Modern tentang perempuan. Cerita-cerita ini terus bertahan dari masa ke masa, dibaca oleh generasi ke generasi, yang tidak diragukan lagi telah membentuk stereotip Witch di masyarakat. Di tahun 1997, seorang penulis perempuan asal Inggris memunculkan novel bertema sihir dengan judul Harry Potter. Dia adalah J.K Rowling. Dia adalah seorang orang tua tunggal dan sebelum menjadi penulis, dia bekerja di lembaga penelitian yang berfokus pada hak asasi manusia. Rowling sudah senang menulis cerita-cerita fantasi sejak kanak-kanak dan mengaku bahwa dia sangat dipengaruhi oleh cerita The Lion, The Witch, and Wardrobe karya C.S. Lewis. Merujuk pada latar belakangnya tersebut, adalah hal yang wajar jika kemudian Rowling menulis cerita bertema sihir yang sarat akan isu persamaan hak. Setelah berabad-abad lamanya, keyakinan tentang penyihir (witch) itu tumbuh di masyarakat khususnya di Eropa, J.K Rowling hadir dengan perspektif berbeda mengenai witch dan witchcraft. Melalui Novel anak fantasi yang ditulisnya, Rowling merekonstruksi definisi penyihir yang diyakini masyarakat selama ini. Dalam novel Harry Potter, tidak ada penyihir nenek-nenek berwajah mengerikan yang tinggal di tempat-tempat menyeramkan dan suka menculik anak-anak. Sebaliknya novel ini 3 diisi dengan tokoh-tokoh yang peduli pada anak-anak, misalnya Profesor Albus Dumbledore Kepala sekolah Hogwarts yang pembawaannya tenang, kalem, ramah, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rowling menceritakan kehidupan menyenangkan yang penuh hal-hal fantastik yang dialami anak-anak penyihir di dunia sihir. Di sekolah sihir “Hogwarts”, ada banyak permainan-permainan luar biasa, seperti : telinga terjulur yang membuat kita bisa menguping dari kejauhan, makanan-makanan yang sangat ajaib seperti cokelat kodok yang bisa melompat seperti kodok sungguhan dan lain sebagainya. Kekuatan sihir yang dimiliki anak-anak dalam novel ini membuat kehidupan di dunia sihir sangat menyenangkan. Novel Harry Potter karya J.K. Rowling ini, ingin mengubah persepsi orang tentang penyihir yang jahat dan menyeramkan. Dia menempatkan Harry Potter yang berpenampilan layaknya orang biasa sebagai pemeran utama, serta menceritakan dunia sihir yang penuh dengan suka ria sebagai fantasi cerita. Bersamaan dengan itu, novel ini juga merombak konstruksi maskulinitas dan femininitas berhubungan dengan isu witch yang telah menjadi momok bangsa Eropa selama berabad-abad. Rowling menggambakan witch tidak selamanya perempuan jahat yang diidentikkan dengan setan. Bangsa Eropa khususnya pada abad pertengahan percaya bahwa witchcraft adalah simbol dari kelemahan perempuan. Oleh karena mereka lemah, tetapi ingin memiliki kuasa, maka mereka keluar dari sistem patriarkal dan bersekutu dengan setan untuk mendapatkan kekuatan. Kondisi ini membuat bangsa Eropa pada 4 umumnya menganggap menjadi witch merupakan perbuatan terhina dan perlu dimusnahkan. Posisi perempuan yang dianggap witch diputarbalikkan dan maskulinitas konvensional dibongkar. Novel Harry Potter tetap menggunakan sebutan witch untuk penyihir perempuan dan wizard untuk penyihir laki-laki. Namun, tidak seperti yang lazim terjadi dimana witch diartikan sebagai penyihir perempuan yang jahat dan wizard penyihir laki-laki yang baik dan bijaksana. Di dunia sihir yang diciptakan J.K. Rowling, semua penyihir belajar bersama-sama di sekolah sihir Hogwarts. Apapun yang dilakukan oleh laki-laki juga bisa dilakukan oleh perempuan, misalnya olahraga, menjadi auror—semacam polisi yang bertugas menangkap penyalahgunaan sihir hitam, bahkan bertarung. Setiap anak punya kesempatan untuk belajar di Hogwarts, selama mereka memiliki bakat sihir, baik itu laki-laki, perempuan, darah murni, darah campuran, bahkan mugle (orang biasa yang bukan keturunan penyihir). Tokoh perempuan yang sangat menonjol dan berdampingan dengan Harry Potter dalam novel ini adalah Hermione Granger. Dia adalah sahabat Harry Potter yang selalu ada bersama Harry dan memiliki andil yang besar dalam setiap petualangannya. Namun Rowling tidak mengambil Hermione sebagai tokoh utamanya. Ia justru menggunakan seorang anak laki-laki yaitu Harry Potter. Namun begitu, perlu diingat bahwa sosok Harry dalam novel ini bukanlah seperti sosok maskulin yang umumnya dimunculkan dalam cerita-cerita barat misalnya bertubuh kekar, jago berkelahi, ganteng, atau kaya. Sebaliknya, Harry adalah gambaran anak laki-laki yang dalam hirarki maskulinitas barat merupakan laki-laki yang masuk 5 dalam kategori tidak maskulin (wimpy boy). Dia adalah anak laki-laki yatim piatu dengan penampilan yang selalu berantakan, memakai kacamata bulat yang gagangnya diselotape, dan tubuh kecilnya tenggelam dalam pakaian lusuh yang kebesaran, serta sangat sentimental dan emosional. Kemenangannya melawan Voldemort yang jahat pun kebanyakan adalah keberuntungan sihir yang melindunginya. Sihir menjadi satusatunya harapan Harry untuk bertahan. Sihir ini menjadikan penampilan yang ditunjukkan Harry tak lagi penting dalam menentukan apakah dia maskulin atau tidak. Ini mengindikasikan bahwa Rowling ingin melakukan perubahan baik itu pada konsep maskulinitas maupun witchcraft. Di satu sisi, witch dan wizard mencoba untuk disatukan untuk memberikan persepsi bahwa sihir merupakan sesuatu yang dapat diterima. Namun di sisi lain, tetap saja simbol-simbol yang digunakannya adalah laki-laki. Namun laki-laki yang digunakan Rowling bukanlah laki-laki seperti yang lazim didefinisikan sebagai maskulinitas hegemonik konvensional. Untuk itu, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam makna sihir dalam novel Harry Potter dan bagaimana sihir mengonstruksi maskulinitas dan femininitas, serta citra perempuan tukang sihir (witch) dalam novel tersebut. 1.2 Rumusan Masalah Mengingat dalam sejarah, witch mendapat perlakuan yang sangat keji di masa lalu, serta persepsi buruk itu terus melekat hingga sekarang, pengarang melalui novelnya Harry Potter jelas ingin mengubah persepsi buruk tersebut. Witch dan 6 wizard disatukan untuk menunjukkan bahwa witch tidak selalu buruk. Witchcraft yang pada kenyataannya dianggap sebagai simbol lemahnya perempuan, dalam novel ini dibalik posisinya menjadi simbol kekuatan, tetapi tetap saja simbol-simbol yang digunakan adalah laki-laki. Namun, laki-laki yang dipakai disini bukanlah laki-laki yang kekar, kuat, jago berkelahi, seperti kriteria maskulin yang lazim kita temui melainkan anak laki-laki yang umumnya masuk dalam kelompok wimpy boy yang sering diejek karena penampilan mereka yang tidak maco, misalnya Harry yang berkacamata tebal, berantakan, sentimental, dan emosional. Selain untuk mengangkat posisi sihir, novel ini juga membongkar wacana maskulinitas hegemonik. Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tiga pertanyaan yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana sihir (witchcraft), witch dan wizard diposisikan dalam novel Harry Potter; 2) Bagaimana konstruksi maskulinitas dan femininitas terkait isu witch dan wizard dalam novel Harry Potter; dan 3) Bagaimana pemosisian sentral dan periferi terkait femininitas dan maskulinitas tersebut. 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk memperlihatkan makna dari sihir itu diputarbalikkan untuk mengubah persepsi tentang witchcraft yang diyakini merupakan simbol bahwa perempuan adalah mahluk yang lemah. Maka, mereka bersekutu dengan setan. Penelitian ini juga melihat bagaimana melalui sihir tersebut, konstruksi maskulinitas dibongkar, serta melakukan pencitraan ulang terhadap perempuan tukang sihir (witch) dalam novel Harry Potter. 7 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian terhadap novel Harry Potter ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam dunia sastra, akademik, dan masyarakat secara luas. Diharapkan nantnya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap dunia akademik yang melihat karya sastra sebagai produk budaya yang menjadi cerminan serta refleksi masyarakat serta dapat dijadikan sebagai acuan serta referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu bukan saja kalangan pendidik, mahasiswa, tetapi secara keseluruhan pada masyarakat agar dapat lebih kreatif dalam menciptakan karya sastra sebagai cerminan dan wujud dari kelompok masyarakat. 1.5 Tinjauan Pustaka Selama beberapa tahun terakhir, sudah sangat banyak penelitian-penelitian yang membahas novel Harry Potter kaitannya dengan gender, feminisme, ataupun unsur-unsur sihir dan magis yang ada di dalamnya. Namun, sampai saat ini penulis belum menemukan ada penelitian yang mengaitkan antara isu gender dan sihir yang ada dalam novel ini. Dalam tesisnya yang mengangkat isu peran gender dalam novel Harry Potter, Tsatsa (2013) menganalisis bagaimana gender ditampilkan oleh tiga pemeran utama dalam novel ini yaitu Harry, Ron dan Hermione. Tsatsa mengfokuskan penelitiannya 8 untuk melihat apakah ketiga tokoh tersebut melawan stereotip gender, ataukah mereka membangun sebuah klise, norma, dan sereotype terkait dengan gender. Dengan mengacu pada teori gender yang dikemukakan oleh Judith Butler mengenai gender sebagai sesuatu yang performatif, Tsatsa menemukan bahwa sifat maskulin dan feminin tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Ketiga tokoh tersebut merupakan perwakilan performa gender yang berbeda-beda. Harry diperlihatkan sebagai tokoh yang memiliki karakteristik maskulinitas tradisional, Ron sebagai laki-laki yang memiliki sisi-sisi feminin dan Hermione adalah perempuan yang memiliki sisi-sisi maskulin dalam dirinya, tetapi juga tetap sebagai perempuan yang feminin. Oskarsdottir (2012) membandingkan antara representasi gender yang dimunculkan dalam novel dan film Harry Potter dan efeknya sebagai agen sosialisasi gender. Oskarsdottir menemukan bahwa walaupun karakter-karakter perempuan dalam novel ini tidak sepasif karakter dalam cerita-cerita dongeng barat, tapi laki-laki tetap memegang posisi yang lebih tinggi dan menguasai. J.K. Rowling gagal menempatkan tokoh-tokoh perempuan dalam novelnya sejajar dengan laki-laki. Dalam filmnya, persamaan posisi perempuan dengan laki-laki digambarkan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan novelnya, khususnya dalam penggambaran tokoh Hermione. Menganalisis karakter keluarga Weasley, Dursley, Harry, Hermione, Nevil, dan Ginny, Oskarsdottir berpendapat bahwa novel Harry Potter memuat opini umum tentang stereotip gender bahwa jenis kelamin secara alamiah berbeda. Menurutnya, buku ini akan berperan sebagai agen untuk meneruskan keyakinan tentang perbedaan 9 gender antara feminin dan maskulin, sekaligus mengajarkan anak-anak bagaimana berperilaku sesuai gendernya. Turbiville (2005) melakukan sebuah penelitian untuk melihat apakah ada korelasi antara pencekalan film Bewitch pada era 1960-an dan novel Harry Potter pada awal kemunculannya di tahun 1999. Hasilnya, terdapat korelasi antara alasan dicekalnya Bewitch dan Harry Potter, yaitu karena ada unsur witch dan witchcraft dalam film dan novel tersebut. Buku Harry Potter dianggap membahayakan karena unsur witch dan witchcraft yang ada di dalamnya. Milwee (2009) menganalisis apakah Harry Potter adalah novel bertema keluarga atau rahasia sihir hitam. Ia menemukan bahwa Harry Potter adalah bacaan yang menarik, tidak seperti yang dikecam para penganut Kristen fanatik. J.K Rowling berhasil menghadirkan sihir sebagai dunia yang menarik, penuh dengan imajinasi dan humor. Para penyihir yang mengalami berbagai komplikasi yang hampir sama dengan manusia pada umumnya memunculkan persepsi tidak ada perbedaan antara penyihir dan bukan penyihir selain mereka memiliki kemampuan magis namun sama dengan dunia kita, dunia sihir juga bukan dunia yang sempurna. Di tahun 2011, Debbie June Rodrigues menulis sebuah tesis yang menganalisis sihir dan gender dalam novel Harry Potter. Namun, sihir dan gender dibahas secara terpisah dalam dua kerangka yang berbeda. Hal-hal magis yang terjadi dalam novel Harry Potter dianalisis dengan teori semiotik, karena dianggap sebagai simbol dan metafora. Simbol dan metafora ini mewakili fenomena yang terjadi di masyarakat kita, agar pembaca dapat menyadari fenomena yang ada di sekitar mereka 10 dengan cara yang lebih segar. Sementara fenomena gender dilihat dari sifat para tokoh dan perubahan yang terjadi pada diri tokoh-tokoh tersebut dari novel seri pertama sampai ke tujuh. Menurut Rodrigues (2011), J.K. Rowling menunjukkan bahwa gender adalah proses sosial. Gender bersifat cair dan asumsi gender yang sudah ada berpotensi untuk ditolak atau diganti dengan perspektif yang baru. Sebagaimana yang ditunjukkan Wannamaker, kemungkinan mendefinisikan ulang asumsi gender menjadi lebih inklusif dan kurang memiliki batasan, karena buku-buku menggambarkan harapan masyarakat melalui tokoh-tokoh yang tidak selalu sesuai atau dengan jelas masuk ke dalam salah satu kategori-kategori gender tertentu. Sama hanya seperti Rowling yang menunjukkan bahwa maskulinitas dan femininitas didefinisikan sebagai konsep yang dapat tumpang tindih dalam diri individu. Krunoslav (2009) menganalisis relasi gender yang terdapat dalam novel Harry Potter karya J.K. Rowling dan menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam posisi yang setara tanpa menghilangkan perbedaan-perbedaan yang fundamental dari keduanya. Niat Rowling tidak menghapus perbedaan, sebaliknya dia menempatkan mereka di ujung-ujung lingkaran bayangan, pada lintasan berjarak sama, sehingga mereka tidak pernah menghapuskan satu sama lain. Dalam sistem ini, baik androgenisasi karakter perempuan, maupun feminisasi karakter laki-laki tampaknya diperlukan untuk mencapai saling menghormati dan kesetaraan dalam tekstur sosial dunia modern. Ruthann (2003) mengkritik cara J.K. Rowling dalam mengkonstrusi gender, serta agensi karakter perempuan dengan cara mendekonstruksi representasi dari 11 agensi perempuan dalam teks. Ruthann melihat agensi perempuan dalam novel Harry Potter dengan menggunakan analisis wacana kritis. Interpretasi agensi perempuan dalam disertasinya ditekankan pada 5 tema: taat/pelanggar aturan, kecerdasan, pengesahan/kemungkinan, perempuan tipe pengasuh dan perlawanan yang “tertahan”. kelima tema ini mengandung unsur oposisi biner, ikatan gender, dan perempuan sebagai “yang lain/ other”. Dalam disertasinya Ruthann menemukan adanya konstruksi gender tradisional dalam novel Harry Potter. Menurut Ruthann (2003), J.K Rowming mengkonstruksi perempuan dan lakilaki dalam sebuah oposisi yang sangat jelas satu sama lain. Petualangan dalam novel ini menonjolkan karakter laki-laki yang aktif, sementara karakter perempuan yang pasif hanya sekedar sebagai tubuh di belakang laki-laki yang mendukun aksi lakilaki. Adapun yang membuat novel ini menjengkelkan dan menarik di saat yang bersamaan adalah perlawanan tokoh perempuan. Kebanyakan tokoh perempuan dalam teks melakukan perlawanan, tetapi ketika mereka melawan hanya sampai pada titik tertentu dan kemudian mundur kembali. Dengan mengkonstruksi karakter perempuan seperti ini, Rowling memberikan pesan kepada pembaca bahwa perempuan harus menunjukkan diri, tetapi hanya sampai pada titik tertentu dan tidak mengambil posisi laki-laki. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketujuh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menganalisis unsur gender dalam novel Harry Potter hanya pada tataran yang sangat umum. Ketujuh penelitian tersebut juga hanya sampai pada menjelaskan bagaimana karakteristik dan pemosisian laki-laki dan perempuan dalam 12 novel ini. Untuk itu, penelitian yang penulis lakukan ini mengaitkan unsur sihir yang menjadi tema novel ini—sekaligus menjadikan novel ini populer—dengan konstruksi maskulin – feminin dan posisi laki-laki – perempuan, serta melihat dampaknya terhadap citra perempuan yang dalam novel ini merupakan perempuan tukang sihir (witch). 1.6 Landasan Teori 1.6.1 Gender dan Konstruksi Maskulinitas dan Femininitas Dalam ruang kajian gender, laki-laki dan perempuan dibagi ke dalam dikotomi maskulin dan feminin yang kemudian melahirkan oposisi biner dalam hubungan keduanya. Oleh karena gender merupakan sebuah pencapaian status (Connell, 1995:71) baik laki-laki maupun perempuan memerankan gendernya masing-masing. Relasi gender ini pada dasarnya merupakan relasi power (Cornwall, 1997:8). Bagi laki-laki, gender tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga menyangkut sikap, persepsi, dan kecerdasan. Secara historis, kecerdasan itu sendiri adalah sifat yang hanya ada pada diri laki-laki, khususnya dalam bidang seperti psikoanalisis, filosofi, dan ilmu kedokteran. Secara tradisional, maskulinitas identik dengan seorang laki-laki yang kuat, rasional, penentu, kompetitif, kuat secara fisik, mengesampingkan aspek emosional, dan non-feminin (Connell via Barker 2011: 53) dan perempuan adalah seseorang yang menarik secara fisik, pengasuh/pemelihara, emosional, dan peduli. 13 Dalam sebuah proses pengulangan praktik sosial yang terjadi secara terus menerus, kualitas konten maskulinitas dan femininitas menjadi bukan hanya sekedar identitas gender atau menunjukkan jenis individu, tetapi juga yang lebih penting, pengulangan kolektif dalam bentuk budaya, struktur sosial, dan organisasi sosial. Ciri-ciri ideal maskulinitas dan femininitas sebagai dua kubu yang saling melengkapi dan hirarkis memberikan alasan adanya relasi-relasi sosial antara laki-laki dan perempuan pada semua level organisasi sosial mulai dari diri, interaksi, struktur institusional, sampai pada hubungan global dominasi. Individu, kelompok, dan masyarakat menggunakan maskulinitas dan femininitas sebagai alasan atas apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan secara kolektif melakukannya secara berulang pada berbagai keadaan institusional. Tidak hanya perbedaan gender, tetapi juga hubungan implisit antara gender yang menjadi ciri-ciri taken-for-granted dari relasi interpersonal, budaya, dan struktur sosial. Artinya, perbedaan gender kini dilembagakan, begitu pula rasionalitas gender (Schippers, 2007: 91). Dalam suatu masyarakat, selalu terdapat lebih dari satu jenis maskulinitas dan femininitas. Jenis-jenis maskulinitas dan femininitas ini tidak begitu saja saling berdampingan satu sama lain. Ada sebuah relasi dimana jenis maskulinitas tertentu lebih dihargai dan lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan jenis maskulinitas yang lain, begitu pula yang terjadi dalam relasi antar femininitas. Maskulinitas dan femininitas ini mendominasi pada waktu dan tempat tertentu, tetapi bukan berarti mematikan jenis maskulinitas dan femininitas yang lain. Jenis- jenis maskulinitas dan femininitas yang lain masih tetap bertahan, tetapi menjadi yang subordinat. 14 Maskulintas dan femininitas hegemonik merupakan ideologi tentang bagaimana menjadi laki-laki atau perempuan yang dapat diterima (Connell, 2000:4). Maskullinitas dan femininitas yang lebih tinggi posisinya disebut sebagai maskulinitas dan femininitas hegemonik. Hegemonik berarti berkaitan dengan dominasi budaya dalam masyarakat secara keseluruhan (Connell, 1995:78). Jadi, wacana maskulinitas dan/atau femininitas ini menggunakan aspek budaya, institusi, dan cara-cara persuasif untuk meyakinkan masyarakat sampai masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi untuk ikut pada satu ideologi. Oleh karena itu, Connell menyebutnya sebagai maskulinitas dan/atau femininitas yang mendominasi secara kultural. Femininitas hegemonik yang konvensional mengatur penampilan dan perilaku perempuan, bahwa perempuan dinilai dari proporsi tubuh, penampilan dan kecantikan mereka. Salah satu contohnya adalah keyakinan bahwa perempuan yang ideal harus bertubuh langsing. Penelitian menunjukkan adanya tekanan sosial budaya yang signifikan pada perempuan untuk menjadikan tubuhnya kurus. Dalam masyarakat Amerika mas kini, gemuk disamakan dengan "devaluasi feminin" (Dworkin & Wachs, 2004: 611). Dworkin dan Wachs menemukan bahwa tekanan untuk menjadi kurus dan bugar telah meningkat dengan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tubuh perempuan sebelum, selama, dan setelah kehamilan dinilai berdasarkan penampilan bugar, yang berhubungan dengan femininitas. Pentingnya tipe tubuh tertentu untuk mencapai femininitas memupuk sikap usaha untuk mendorong penampilan. 15 Selain tubuh langsing sebagai tolak ukur ideal perempuan, kosmetik dan rambut adalah penanda lain dari femininitas. Rambut yang panjang dan sehat sebagai tipe yang ideal. Koppelman (1996:87) menyebutkan bahwa perempuan dengan kepala botak atau rambut berwarna abu-abu atau putih dianggap menentang konstruksi sosial kecantikan perempuan. Kata feminin pada dasarnya merupakan naskah yang diikuti oleh perempuan untuk bisa menjadi menarik dan diinginkan oleh laki-laki heteroseksual, serta untuk membuat perempuan lain iri (Leavy, 2009: 272). Artinya, terjadi sebuah kompetisi di antara perempuan untuk menunjukkan dirinya sebagai yang paling tinggi posisinya dalam hirarki femininitas, berdasarkan kriteria femininitas hegemonik. Meskipun keduanya hegemonik, femininitas dan maskulinitas hegemonik adalah struktur yang tidak setara. Maskulinitas hegemonik adalah suprastruktur dominasi sementara femininitas hegemonik terbatas pada hubungan kekuasaan kalangan perempuan. Namun begitu, kedua struktur ini saling terkait dimana femininitas hegemonik dibangun untuk melayani maskulinitas hegemonik, sebagaimana legitimasi yang diberikan terhadap femininitas (Schippers, 2007: 88). Femininitas hegemonik tidak pernah bisa berada sejajar dengan maskulinitas hegemonik. Connell (1987: 187) menyebutkan bahwa semua bentuk femininitas di masyarakat dikonstruksi dalam konteks subordinsi penuh perempuan pada laki-laki. Untuk alasan ini, tidak ada femininitas yang memegang kekuasaan di antara perempuan yang mampu memperoleh posisi dalam maskulinitas hegemonik laki-laki. 16 Femininitas hegemonik sekalipun akan selalu berada di bawah maskulinitas. Ia kemudian membuat istilah emphasized femininity : Salah satu bentuk [femininitas] didefinisikan semacam kepatuhan terhadap subordinasi ini dan diorientasikan untuk mengakomodasi kepentingan dan keinginan laki-laki. Saya akan menyebutnya “emphasized feminity”. Bentuk yang lain ada yang diartikan secara sentral dengan strategi-strategi resistensi atau bentuk-bentuk ketidakpatuhan. Yang lainnya lagi diartikan dengan kombinasi strategi kompleks kepatuhan, resistensi, dan kerjasama (Connell, 1987: 184 –185) Disini Connell mengungkapkan bahwa ada banyak bentuk femininitas, tetapi fokus dari kesemuanya itu lebih pada relasi dengan maskulinitas. Connell (1987:188) menulis bahwa femininitas diatur sebagai bentuk adaptasi kekuasaan laki-laki, dan menekankan kerelaan, pengasuhan, dan empati sebagai sifat kebajikan feminin untuk membentuk hegemoni atas semua bentuk femininitas. Berbeda halnya dengan femininitas hegemonik yang hanya membawahi femininitas-femininitas lain yang subordinat, maskulinitas hegemonik tidak hanya hegemonik dalam konteks hubungannya dengan bentuk maskulinitas yang lain, melainkan dalam relasinya dengan susunan gender secara umum. Maskulinitas hegemonik merupakan wujud hak istimewa laki-laki secara kolektif terhadap perempuan. Identitas maskulinitas hegemonik dibentuk menentang “yang lain (otherness)” baik itu perempuan pada umumnya dan homosexual khususnya, kebencian terhadap perempuan dan homophobia. Di bawah hirarki maskulinitas hegemonik ini, hadir maskulinitas subordinat, femininitas hegemonik, dan 17 femininitas subordinat, yang artinya mereka tunduk di bawah dominasi maskulinitas hegemonik dan mengikuti segala aturan yang diberlakukan oleh maskulinitas ideal dalam patriarki. Maskulinitas hegemonik sebagai kualitas kelaki-lakian yang membentuk dan melegitimasi relasi hirarkis dan saling melengkapi dengan femininitas (Connell, 1995: 78–80). Berangkat dari definisi ini, Schippers, 2007: 94) mendefinisikan femininitas hegemonik terdiri dari ciri-ciri yang mendefinisikan keperempuanan yang membentuk dan meligitimasi relasi hirarkis, sehingga saling melengkapi dengan maskulinitas hegemonik. Dengan demikian, konsep itu menjamin posisi dominan laki-laki dan subordinasi perempuan. Hegemoni gender beroperasi tidak hanya melalui subordinasi femininitas pada maskulinitas hegemonik, tetapi juga melalui subordinasi dan marginalisasi maskulinitas lainnya. Jadi, meskipun penekanannya lebih pada femininitas sebagai pusat dominasi maskulin, hal itu bukan satu-satunya mekanisme untuk memastikan dominasi laki-laki. Dalam hegemoni gender, pengaruh maskulinitas hegemonik atas kelompok maskulinitas terpinggirkan lainnya sama pentingnya dengan kekuasaan maskulin terhadap kelompok tersubordinasi (perempuan). Maskulinitas hegemonik memastikan dominasi laki-laki, sehingga semua laki-laki bisa mendapatkan keuntungan pada tingkat-tingkat tertentu meskipun kebanyakan laki-laki tidak harus "di garis depan" atau mewujudkan maskulinitas hegemonik dalam dirinya. Connell (1995:77) mendefinisikan maskulinitas hegemonik sebagai konfigurasi praktek gender yang memberikan jawaban yang dapat diterima menyangkut masalah legitimasi partiarki, yang menjamin (atau memberikan jaminan) posisi dominan laki18 laki dan subordinasi perempuan. Maskulinitas hegemonik, ketika diwujudkan oleh sekurangnya beberapa laki-laki dari waktu ke waktu, akan melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan sebagai kelompok. Stereotip maskulinitas hegemonik itu, menurut Barker (2011: 241) umumnya adalah maskulinitas tradisional—yang merupakan suatu generalisasi—yang menjelaskan nilai-nilai kekuatan, kekuasaan, ketabahan, aksi, kontrol, independensi, keswadayaan, perkawanan/ jalinan persahabatan laki-laki, kerja dan lain-lain. Adapun yang dipandang rendah adalah dependensi, kemampuan verbal, kehidupan domestik, kelembutan, komunikasi, perempuan, dan anak-anak. Sejalan dengan itu, Connel (1995:68) menyebutkan konsep mendasar dari maskulinitas hegemonik adalah kekuatan fisik, heteroseksualitas eksklusif, daya saing, homofobia, ketangguhan emosional, kemampuan untuk menggunakan kekerasan interpersonal, kemampuan dalam menghadapi konflik, dan pemilik otoritas. Karakteristik ini menjamin dominasi yang sah laki-laki atas perempuan, hanya ketika mereka secara simbolis dipasangkan dengan sifat-sifat inferior yang melekat pada femininitas. Sifat-sifat itu meliputi kerentanan, ketidakmampuan untuk menggunakan kekerasan secara efektif, dan kepatuhan. Laki-laki heteroseksual pada umumnya mendapatkan apa yang diistilahkan sebagai keuntungan patriarkal, misalnya gaji yang lebih tinggi, kesempatan yang lebih luas dalam hal pekerjaan dan partisipasi politik dibandingkan perempuan. Namun, ada grup-grup laki-laki tertentu yang tidak mendapatkan hal tersebut. Kelompok-kelompok ini biasa disebut kelompok maskulinitas yang termarginalkan, 19 yaitu mereka yang dianggap tidak dapat memenuhi kriteria maskulinitas hegemonik. Laki-laki yang masuk dalam golongan ini misalnya mereka yang memiliki sifat menyerupai perempuan, lemah, atau karena kelas sosial dan ras mereka otomatis menjadi laki-laki yang terpinggirkan (Connell, 1997:64). Maskulinitas marginal bisa juga mereka yang berasal dari kelas atau ras subordinat/ kelompok etnis tertentu. Sementara hegemoni, subordinasi, dan komplisitas adalah aspek-aspek dari aturan gender. Oleh karena alasan tersebut, laki-laki menggunakan tingkat maskulinitas untuk berkompetisi satu sama lain. Mereka mereka saling membandingkan satu sama lain berdasarkan segala jenis sumberdaya yang mereka miliki, yang dianggap dapat menunjukkan maskulinitasnya. Semakin besar ciri-ciri maskulinnya dan paling mendekati kriteria maskulinitas hegemonik yang diperesyaratkan oleh lingkungan tempat mereka hidup, maka semakin tinggi pula posisinya (top level masculinity). Sebaliknya, jika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi dan jauh dari stereotip maskulinitas hegemonik, maka dia dianggap bukan bagian dari mereka (low level masculinity). Dalam konteks lingkungan sekolah misalnya, laki-laki yang masuk dalam kelompok high level masculinity adalah kelompok remaja laki-laki yang dianggap memiliki pengaruh besar di lingkungannya dan diidolakan oleh anak-anak lain yang tidak mampu meniru penampilan mereka, sementara low level masculinity ini biasanya yang berkacamata, berkawat gigi, berpenampilan culun, kutu buku, dan/atau berasal dari kelas sosial yang dianggap lebih rendah. Maskulinitas dapat dipaparkan sebagai nilai-nilai yang membangun identitas kelaki-lakian dalam 20 masyarakat sebagai pembatas tentang nilai-nilai, bukan feminin atau dengan kata lain merupakan perwujudan ideal laki-laki. Oleh karena legitimasi bahwa ciri-ciri maskulin adalah milik laki-laki, serta melekat pada tubuh laki-laki, maka perempuan yang menunjukkan ciri maskulin dianggap keluar dari jalurnya. Mereka dicela karena dianggap sebagai perempuan yang rendah kualitas femininitasnya, karena femininitas mereka dicemari oleh sifatsifat maskulin. Schippers (2007: 95) mengistilahkan perempuan seperti ini sebagai pariah femininity. Pariah artinya “kasta yang terendah” bahkan arti kasarnya “sampah masyarakat”. Perempuan yang masuk dalam kategori ini misalnya mereka yang tangguh dan agresif dicela sebagai “badass girl”, yang membebaskan dari kekuasaan patiarki disebut “bitch”, atau yang mandiri dan tidak mudah mengalah (“cock-teaser” and slut). Perempuan yang seperti ini secara sosial tidak diinginkan dan dianggap mencemari masyarakat. sebaliknya jika sifat seperti ini melekat pada laki-laki, posisinya akan sangat positif. Schippers (2007: 97) meyakini bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga tatanan gender, serta hubungan subordinasi dan dominasi antara lakilaki dan perempuan. Sama halnya dengan perempuan, laki-laki yang menunjukkan ciri-ciri feminin misalnya tertarik pada laki-laki, lemah, selalu tunduk dan mengalah juga dianggap sebagai pencemaran dan meresahkan masyarakat. Laki-laki seperti ini menjadi sasaran stigma dan sanksi sosial. Laki-laki seperti ini biasa diejek sebagai “fag,” “pussy”, dan “the wimp”. Apa yang oleh Connell disebut sebagai maskulinitas subordinat. 21 Maskulinitas dan femininitas bisa menjadi "proyek gender" dalam kehidupan individu, tetapi tidak mengacu pada fitur atau jenis orang tertentu. Alih-alih menguasai atau memiliki maskulinitas, individu juga akan bergerak dan menghasilkan maskulinitas dengan terlibat dalam praktik maskulin. Dengan begitu, maskulinitas adalah praktek teridentifikasi yang muncul di seluruh ruang, dari waktu ke waktu, akan diakui dan disahkan secara kolektif oleh kelompok, komunitas, dan masyarakat. Dengan pengesahan yang berulang dari waktu ke waktu, praktek-praktek ini membentuk sebuah produksi dan distribusi sumber daya, distribusi kekuasaan dalam bentuk otoritas, cathexis, dimana Connell mengartikannya sebagai arena sosial keinginan dan seksualitas, dan simbolisme atau produksi makna dan nilai-nilai. Oleh karena itu, secara ringkas dapat dikatakan bahwa maskulinitas adalah posisi sosial, seperangkat praktek, dan efek dari perwujudan kolektif praktek-praktek pada individu, hubungan, struktur institusional, dan hubungan global dari dominasi. Konsep maskulinitas dan femininitas dihasilkan, diperebutkan, dan diubah melalui proses diskursif, dan karena itu dapat tertanam dengan baik, serta sarat dengan hubungan kekuasaan. Dalam model ini, maka, dinamika kekuasaan adalah pusat, tidak hanya dalam fokus konseptual pada hubungan hirarkis antara maskulinitas dan femininitas daripada karakteristik tertentu ideal, tetapi juga dalam hal dinamika produksi, proliferasi, dan kontestasi wacana yang mengartikulasikan apa laki-laki dan perempuan dan hubungan mereka satu sama lain. Femininitas dan maskulinitas sebenarnya merupakan suatu konsep yang sangat kompleks dan dapat selalu berubah (shifting). Penelitian di bidang sosiologi menemukan bahwa 22 masyarakat dengan budaya dan periode sejarah yang berbeda mengkonstruksi karakter maskulinitas yang berbeda (Connell, 2000:3). Dalam setiap lingkungan kerja, bertetangga atau kelompok teman sebaya misalnya, masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda mengenai karakter laki-laki maskulin. Apa yang disebut sebagai “isu-isu perempuan” menyangkut opresi dan patriarki juga adalah “isu-isu laki-laki”, karena sama seperti halnya perempuan, lakilaki juga tergenderkan (Connel, 1997: 63). Adanya stereotip maskulin dan feminin membuat perempuan tersubordinasi karena dianggap lemah. Sementara bagi laki-laki hirarki maskulinitas dalam dunia mereka membuat mereka yang tidak dapat menunjukkan ciri-ciri maskulinitas hegemonik menjadi laki-laki yang terpinggirkan. Pendikotomian gender menjadi maskulin dan feminin telah memunculkan dualisme dalam diri perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian terbaru meyakini bahwa gender tidak boleh dilekatkan pada tubuh seperti yang selama ini diartikan bahwa maskulinitas melekat pada tubuh laki-laki dan femininitas pada tubuh perempuan, melainkan lebih sebagai seperangkat perilaku yang dominan dan diekspresikan melalui wacana seksual. Connell (1987:67) menyatakan bahwa dalam diri setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki sisi maskulin dan feminin. Sementara itu gender memaksa mereka untuk memilih masuk ke kategori maskulin atau feminin. Ketika dikotomi gender ini dihilangkan, maka sifat-sifat feminin dan maskulin dalam diri individu dapat dinegosiasikan, sehingga terjadi keselarasan antar keduanya. 23 Penelitian yang dilakukan oleh Barker di tahun 2011 pada sebuah sekolah gulat menunjukkan bahwa bahkan di lingkungan sekolah gulat yang sangat menekankan kekuatan fisik, homofobia, daya saing, dan mengesampingakan perasaan (emosi), tetap ditemukan perilaku-perilaku inklusif yang mengarah ke feminin. Sejalan dengan pernyataan Connel dan hasil penelitian Barker, Cornwall (1997: 11) menerangkan bahwa walaupun maskulinitas hegemonik berhubungan dengan dominasi dan kekuasaan (power), tetapi atribut yang menandakan maskulinitas tidak selalu berasosiasi dengan laki-laki. Perempuan juga dapat memiliki beberapa atribut ini. Dengan begitu, tidak semua laki-laki memiliki power, dan tidak semua yang memiliki power adalah laki-laki. Dalam konseptualisasi yang ditawarkan di sini, maskulinitas bukanlah sebuah tempat, praktik, atau struktur yang dihasilkan. Bagi Connell (1997: 66), "tempat" merujuk pada posisi sosial "perempuan" dan "laki-laki", sementara perwujudan karakter maskulinitas atau femininitas oleh individu adalah perwujudan gender atau display. Mewujudkan dan memproduksi relasi antara maskulinitas dan femininitas dalam interaksi sosial adalah "doing gender". Sejauh mana relasi hirarkis dan saling melengkapi antara maskulinitas dan femininitas yang dilembagakan merupakan struktur gender (Schippers, 2007: 93). Hal ini menawarkan jalur konseptual dan empirik keluar dari peleburan antara praktik laki-laki dan perempuan, dengan maskulinitas dan femininitas yang memungkinkan mereka menduduki posisi sebagai "perempuan" untuk terlibat dalam praktik atau mewujudkan ciri-ciri yang dianggap maskulin, serta bagi "laki-laki" untuk mewujudkan ciri-ciri femininitas. Maskulinitas 24 dan femininitas beserta konstruksi relasi mereka satu sama lain merupakan sebuah alasan yang terbuka untuk praktik, sekaligus sebagai rujukan yang dapat digunakan untuk menafsirkan dan menilai, tidak hanya sekedar display gender dan praktik individu, tetapi semua relasi sosial, kebijakan, aturan, dan praktik institusional dan struktur (Schippers, 2007: 93). Connell (1997:67) tidak setuju dengan dimensi tubuh gender yang sering dianggap batas absolut perubahan. Menurutnya, jika kita memahami gender sebagai cara tubuh ditarik ke dalam proses historis, maka kita bisa mengenali kontradiksi dalam perwujudan yang ada, serta dapat melihat besar kemungkinan untuk perwujudan kembali tubuh laki-laki. Menurut Connell (1997:66), ada banyak cara berbeda untuk menggunakan, merasakan, dan menunjukkan tubuh laki-laki. Hubungan gender bersifat historis, sehingga hierarki gender dapat berubah. Oleh karena itu, maskulinitas hegemonik muncul dalam situasi tertentu dan terbuka untuk perubahan yang sifatnya historis. Penggunaan kostum berwarna pink oleh tim tasional sepak bola Amerika yang tidak menimbulkan komentar negatif, adalah bukti bahwa gender bisa dinegosiasikan, sehingga perubahan selalu terbuka (Barker, 2011: 61). Di tahun 1970, sebuah gerakan yang disebut “men’s Liberation” menyimpulkan bahwa feminisme baik untuk laki-laki, karena laki-laki juga menderita akibat dikotomi jenis kelamin ini. Tujuan yang diusung oleh kelompok ini adalah penghapusan maskulinitas (dan femininitas) melalui sebuah gerakan menuju androgini, pencampuran dua sex roles yang berarti bahwa kita harus mengubah kehidupan pribadi. Namun, menurut Connell hal ini meremehkan kompleksitas 25 maskulinitas dan femininitas, sehingga pembahasan terlalu banyak menekankan sikap pada kesenjangan material dan isu-isu kekuasaan. Untuk itu, Connell (1997: 66) lebih menyarankan “mengubah komposisi” elemen gender; membuat berbagai macam simbolisme gender dan kegiatan yang didesain terbuka untuk semua orang. Contohnya di sekolah siswa perempuan diberi peluang untuk mempelajari sains dan teknologi, sehingga mendukung siswa laki-laki untuk belajar memasak dan menjahit. Connell (1995: 71) mendefinisikan gender sebagai sebuah cara dimana “arena reproduksi”, yang mencakup "struktur tubuh dan proses reproduksi manusia", mengatur praktik di semua tingkat organisasi sosial mulai dari identitas, ritual simbolik, sampai ke lembaga-lembaga dalam skala besar. Sebagai fitur utama dari relasi gender, ia mendefinisikan maskulinitas sebagai sebuah posisi dalam relasi gender yang secara bersamaan merupakan praktek, dimana laki-laki dan perempuan terlibat pada posisi tersebut dalam gender, dan efek dari praktek tersebut terhadap pengalaman tubuh, kepribadian dan budaya. Menurut Schippers (2007: 86), maskulinitas memiliki tiga komponen; pertama, maskulinitas merupakan lokasi sosial perorangan, terlepas dari jenis kelamin, dapat berpindah melalui praktek; kedua, merupakan serangkaian praktek dan karakteristik yang dipahami sebagai "maskulin"; ketiga, ketika praktik-praktik ini diwujudkan terutama oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan, maka akan memberikan efek budaya dan sosial yang luas. Dari berbagai penelitian empirik mengenai relasi maskulinitas dan femininitas, Schippers (2007: 97) menyimpulkan bahwa karakteristik dan praktik ideal maskulinitas dan femininitas merupakan hal yang bervariasi tergantung pada 26 konteks, kelompok, dan masyarakatnya. Variasi budaya, ekonomi, dan politik di semua kelompok dan masyarakat, serta ciri-ciri khusus dari maskulinitas dan femininitas yang memastikan dominasi laki-laki terhadap perempuan akan berbedabeda sesuai dengan konteks. Di tahun 2002, Schippers melakukan sebuah penelitian empiris dan menyimpulkan bahwa terdapat peluang untuk secara sengaja mengganti maskulinitas hegemonik, femininitas hegemonik, pariah feminity, male femininities dengan maskulinitas dan/atau femininitas alternatif. Dalam penelitiannya, Schippers mengidentifikasi bagaimana anggota subkultur musik rock tertentu menolak maskulinitas dan femininitas hegemonik yang telah menjadi wacana mainstream dalam komunitas rock. Wacana baru yang mereka bentuk untuk menolak wacana yang lama merupakan maskulinitas dan femininitas alternative (Schippers, 2007: 97) Cornwall (1997:12) menyatakan bahwa hanya karena beberapa laki-laki menempati posisi subyek pada beberapa keadaan yang memberikan mereka kekuasaan atas orang lain, tidak berarti bahwa posisi ini kongruen dengan semua aspek kehidupan mereka. Dia kemudian menyimpulkan bahwa gender adalah masalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kita perlu menemukan cara konstruktif yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan dikotomi laki-laki perempuan ini. Ia menyarankan merekonstruksi asumsi kultural tentang “menjadi laki-laki”. Menurutnya, dengan begitu akan dicapai sebuah kesadaran bahwa gender menempatkan banyak orang pada posisi yang tidak menguntungkan dan membangun kepercayaan diri untuk bersikap berbeda. 27 Menurutnya sudah waktunya keluar dari ide-ide lama tentang peran gender dan dominasi laki-laki yang universal. Ini adalah waktunya untuk menemukan cara berpikir dan analisis gender yang lebih masuk akal, serta cocok dengan kompleksitas realitas hidup masyarakat. 1.6.2 Gender dan Posisi Sentral – Periferi Periferi adalah sebuah kondisi. Kondisi dimana seseorang menjadi periferi atau sentral sangat tergantung dengan konteks keberadaan, sehingga periferi dan sentral adalah posisi yang selalu berubah (shifting). Cornwall (1997: 10) menjelaskan bahwa setiap hari dalam hidup, identitas kita sebagai perempuan atau laki-laki tidak pernah tetap atau absolut, melainkan beragam dan berubah-ubah. Menurut Cornwall (1997: 10), relasi gender tergantung pada konteks di mana kita berada. Hollway menyebutnya “subject-position”. Saat perempuan menganalisis kehidupannya, tidak satu pun dari perempuan yang selalu berada dalam posisi subordinasi orang lain. Hubungan perempuan dengan orang-orang di sekitarnya mungkin merupakan “hubungan gender”, dalam artian hubungan jenis kelamin yang membuat perbedaan, tetapi tidak dalam arti hanya satu dimensi hubungan kekuasaan. Sebagai perempuan, mungkin memiliki anak laki-laki, ayah, saudara, teman-teman laki-laki atau karyawan laki-laki. Dengan orang-orang yang posisinya berbeda-beda ini, tentunya perempuan juga memiliki pola hubungan yang berbeda dibandingkan dengan hubungan dibandingkan dengan kekasih, suami atau atasan. Oleh karena itu, dalam konteks 28 yang menempati posisi sentral atau periferi, bisa saja laki laki dan perempuan saling tumpang tindih. Dikotomi laki-laki – perempuan, maskulin-feminin telah menghasilkan sebuah oposisi biner yang membuat dua kubu ini bertentangan satu sama lain. Laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi (sentral) dan perempuan pada posisi marginal (periferi). Bartky (1988: 30) menuliskan hal tersebut. Ruang perempuan bukan bidang di mana intensionalitas tubuhnya dapat secara bebas direalisasikan, tetapi sebuah kandang di mana dia merasa dirinya diposisikan, serta di mana dia di kurung. Konsepsi ruang perempuan menggambarkan ide umum dari ruang tertutup, daya / ketidakberdayaan, dan tubuh sebagai situs gender performativity (Butler via Leavy, 2009: 261). Hubungan antara feminin dan maskulin ini telah membentuk sebuah hirarki gender dimana perempuan sebagai yang feminin berada pada posisi di bawah, diyakini menjadi pihak yang terdomestifikasi, teropresi, dan korban kekerasan berbasis gender. Sementara itu, laki-laki sebagai yang maskulin berada di posisi atas hirarki, sebab dianggap memiliki power untuk menguasai. Kalkulasi, kompetensi, dan logika yang dianggap merupakan kemampuan laki-laki memungkinkan laki-laki untuk memiliki kontrol atas konstruksi kultural femininitas, serta telah memposisikan tubuh perempuan sebagai situs objektifikasi (Leavi, 2009: 262). Baik secara pikiran maupun fisik laki-laki, selalu diletakkan dalam posisi menguasai perempuan atau sebagai perbandingan dengan tubuh perempuan, untuk membuat pemisahan antara yang kuat dan kurang kuat (Leavy, 2009: 262). Melalui seksualisasi tubuh 29 perempuan, tubuh fisik itu sendiri menjadi situs seksualitas, di mana kepribadian dan emosi dihapus atau diabaikan. Dalam konteks dunia barat, hubungan sentral dan periferi umumnya ditentukan oleh ras dan kelas. Konsep ini didasarkan pada etnosentrisme yang dianut oleh ras kulit putih. Imperialisme Barat yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih memungkinkan kolonisasi oleh bangsa kulit putih terhadap ras dan kelompok lain, utamanya ras kulit hitam dan negara dunia ketiga. Dengan demikian, ras kulit putih mampu menempati posisi sentral dan ras kulit hitam, serta negara dunia ketiga sebagai the other (periferi). Berbagai penelitian dalam bidang kajian gender membuktikan bahwa ketidaksetaraan gender bisa sangat beragam diakibatkan oleh ras/etnisitas dan kelas. Gender, ras dan kelas saling mempengaruhi sistem dominasi yang berefek pada akses terhadap kekuasaan dan hak-hak istimewa, mempengaruhi relasi sosial, mengkonstruksi makna, dan membentuk pengalaman sehari-hari masyarakat (Cotter dkk, 1999: 433). Dalam relasi laki-laki kulit putih dan kulit hitam, laki-laki kulit putih merupakan sentral, sementara laki-laki kulit hitam menempati posisi periferi. Namun, antara laki-laki kulit hitam dan perempuan kulit hitam, lakilaki kulit hitam menempati posisi sentral dan perempuan kulit hitam merupakan periferi. Dalam hirarki ini, perempuan kulit hitam selalu menempati posisi periferi baik dalam relasinya dengan laki-laki kulit hitam, laki-laki kulit putih, maupun dengan perempuan kulit putih. Hirarki ini terjadi karena posisi sentral dan periferi merupakan posisi yang dinamis, tergantung dengan siapa seseorang direlasikan. 30 Dalam teori Connell (1997:64), ada yang dia sebut sebagai maskulinitas yang termarginalisasi. Connell memberikan istilah marginalisasi untuk mengkarakterisasi hubungan antara laki-laki yang merupakan hasil dari persinggungan antara kelas, ras dan gender. Maskulinitas yang terpinggirkan (marginalized masculinity) adalah mereka yang berasal dari kelas-kelas atau kelompok ras/etnis subordinat. Hubungan ini merupakan salah satu otorisasi dan marjinalisasi, karena maskulinitas hegemonik digabungkan dengan kulit putih dan status kelas menengah, dimana laki-laki kulit putih diberikan kewenangan, sementara ras dan kelas lain yang dianggap marginal tidak (Schippers, 2007: 88). Schippers (2007:88) menyebutkan bahwa di tahun 2003, Peaky dan Johnson mengaplikasikan teori Connell dalam penelitian terhadap perempuan generasi ke-2 di Korea dan Vietnam. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat relasi subordinasi dan dominasi antara perempuan kulit putih dan perempuan Asia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perempuan kulit putih menduduki posisi hegemonic, sedangkan perempuan Asia pada posisi subordinasi. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana kinerja gender rasial yang terlibat dalam ketidaksetaraan antara perempuan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ada femininitas yang lebih berkuasa dari femininitas yang lain, karena aspek ras. Tentunya, hubungan antara perempuan kulit putih dan perempuan Asia adalah hasil dari persimpangan gender dan ras. Penelitian lain dilakukan oleh Bettie pada tahun 2003 di sebuah sekolah di Inggris mengenali pola hirarki femininitas, yaitu hubungannya dengan ras dan kelas. 31 Ia menemukan bahwa perempuan kulit putih kelas menengah yang menunjukkan heterosexualitas, dianggap sebagai perwujudan “gadis baik” dan “siswa yang baik”. Sementara Las Chilas, siswa keturunan Mexico-Amerika yang berasal dari golongan kelas pekerja (working class) dianggap sebagai hiper-seksual dan lebih fokus pada hetero-romance daripada sekolah karena alasan race-class femininity (Schippers, 2007:99). Apa yang dialami oleh Chilas, bukan lagi hanya masalah gendernya, melainkan ras dan kelasnya. Meskipun dia tidak benar-benar mengacuhkan sekolah, orang-orang tetap berpendapat demikian, karena melihat latar belakang ras dan kelasnya. Butler via Schippers (2007:99) mengungkapkan bahwa tidak memasukkan ras dan kelas subordinat dalam kategori laki-laki dan perempuan "sejati", berarti memberikan legitimasi yang sangat jelas akan subordinasi sosial, politik, dan ekonomi mereka. Selain itu hal ini, berarti melegitimasi supremasi dan hak istimewa bangsa kulit putih, dan bahwa kualitas ideal konten maskulinitas dan femininitas ditekankan pada posisi seseorang secara social, apakah dia berada pada kelompok dominan atau subordinat (Schippers, 2007:100). Schippers (2007: 99) menambahkan bahwa kelompok ras/etnis minoritas, serta kelas pekerja dan ekonomi kelas bawah dikonstruksi sebagai the other yang tidak memiliki kelayakan atau sebagai kelompok bermasalah, karena praktik gender mereka. Kondisi ini ditunjukkan oleh Pyke dan Johnson bahwa stereotip praktik gender yang sesungguhnya dari kelompok ras dan kelas subordinat seringkali mendukung hegemoni gender, tetapi terhalangi oleh hegemoni ras dan kelas. 32 Dalam pemikiran biner, the Other dilihat sebagai objek yang dikontrol dan dimanipulasi. Collins (2000:70) mengungkapkan bahwa gagasan Barat mengharuskan objeksifikasi, sebuah proses “pemisahan knowing self dari knowing object dalam konsep tersebut. Dominasi selalu melibatkan usaha untuk mengobjeksi kelompok subordinat. Subyek memiliki hak untuk mendefinisikan realitas mereka sendiri, membentuk identitas mereka sendiri, menamai sejarah mereka. Sementara itu realitas, identitas, dan kesejarahan mereka didefinisikan dan dibentuk oleh kelompok lain yang disebut obyek (Collins, 2000:71). Untuk masyarakat kulit putih, kelompok masyarakat “kulit berwarna” selalu dianggap stranger. Tidak hanya itu, mereka dianggap stranger yang tuli, sehingga tak ada yang bisa disampaikan pada mereka. Sebagai “Others” yang tidak akan pernah bisa masuk dalam masyarakat, strangers mengancam tatanan moral dan sosial (Collins, 2000:70). Yang paling mencolok di Barat adalah ketidaksetaraan ekonomi yang diakibatkan oleh gender, kelas, dan ras karena kesenjangan upah dan pengkotakkotakan jenis pekerjaan berdasarkan ketiga aspek yang saling berhubungan tersebut. Dalam sebuah studi empitik mengenai perbedaan penghasilan hubungannya dengan gender, ras, dan kelas, Cotter dkk (1999) menemukan bahwa perempuan kulit putih secara ekonomi dirugikan dalam hubungannya dengan laki-laki kulit putih, karena mereka adalah perempuan. Namun, ketidaksetaraan penghasilan yang dialami oleh perempuan kulit putih tidak separah yang dialami oleh perempuan African American dan Amerika Latin. Hal ini disebabkan keuntungan yang didapatkan perempuan kulit putih karena masuk dalam kelompok ras/etnik yang dominan. Perempuan African 33 American dan Amerika Latin di lain sisi menjadi pihak yang terhukum karena mereka perempuan dan bukan ras kulit putih. Perempuan Asia, walaupun tidak separah African Afro Amerika dan Amerika Latin, tetap mendapatkan kerugian karena nonkulit putih. Ras dan kelas sering dianggap sebagai faktor sekunder dalam organisasi sosial. Teori feminis menulis dari pengalaman di mana ras dan kelas dirasa bukan merupakan elemen yang menindas dalam kehidupan mereka. Ini adalah teori dari kulit putih, pengalaman kelas menengah yang memberikan kontribusi untuk etnosentrisme yang sering terdapat dalam tulisan-tulisan feminis putih (Palmer, 1983: 154). Faktanya, opresi ras, gender, dan kelas menjadi penyebab utama dari kemelaratan perempuan kulit hitam (Collins, 2000:1). Telah banyak yang dibuktikan bahwa masalah ras dan kelas ini, dengan sendirinya ikut mempengaruhi relasi gender dan studi feminis. Patricia L. Collins contohnya merupakan salah satu tokoh yang paling santer berbicara masalah ras dan kelas hubungannya dengan relasi gender dan wacana feminis. Collins mengfokuskan kritiknya terhadap pemosisian perempuan kulit hitam oleh bangsa kulit putih. Perspektif feminis kulit putih telah menghasilkan teori dan tindakan yang berfokus pada masalah perilaku seks dan prasangka terhadap laki-laki, dimana semua laki-laki dilihat sebagai penindas dengan level yang sama. Hal ini membuat perempuan kulit hitam dicela karena keengganan mereka untuk berbicara tentang seks dalam masyarakat hitam. Suatu realitas yang perlu dibahas, tetapi tidak dalam cara yang sama seperti yang dialami perempuan kulit putih. Perempuan kulit 34 hitam berargumen bahwa sulit untuk memperhatikan seksisme kulit laki-laki hitam, ketika teori dan praktek feminis kulit putih tidak memberi pertimbangan lebih pada aspek historis masyarakat Amerika, yaitu bahwa laki-laki kulit putih, sebagai pihak yang utama dengan hak istimewa berdasarkan kelas sosial mereka merupakan penerima manfaat utama dalam hal seksisme dan rasisme (Palmer, 1983: 154-155). Ras, kelas, gender, seksualitas, kebangsaan, usia, dan etnisitas merupakan bentuk operasi utama yang terjadi di USA. Konvergensi karakteristik penindasan ras, kelas, dan gender terhadap budak di USA membentuk hubungan konsekuensional perempuan keturunan Afrika dalam keluara Afrika Amerika dan komunitas, dengan majikan, dan antara sesame mereka. Hal ini juga menciptakan sebuah konteks politik untuk karya intelektual perempuan kulit hitam (Collin, 2000: 4). Dalam budaya Amerika, ideologi budaya, ras, dan seks meresap ke dalam struktur sosial sebagai semacam “tingkatan” yang menjadi hegemonik, dilihat sebagai hal yang natural, normal, dan tidak terelakkan. Stereotip negatif dilekatkan pada perempuan kulit hitam dan telah menjadi hal yang mendasari opresi yang mereka alami. Sistem penindasan ini bekerja untuk menekan ide-ide intelektual perempuan kulit hitam, untuk melindungi kepentingan para elit laki-laki kulit putih elit, serta pandangan dunia. Studi perempuan di Amerika dan Eropa telah menentang pemikiran hegemonik elit laki-laki kulit putih. Ironisnya, feminis barat juga menekan pemikiranpemikiran perempuan kulit hitam. Ketidakhadiran pemikiran feminis kulit hitam dalam studi feminis di barat menempatkan perempuan kulit hitam ke dalam posisi 35 yang lebih lemah lagi dari hegemoni ideologi mainstream yang ada pada separuh dari para kaum perempuan. Di Barat, perempuan kulit hitam mengalami dualisme. Di satu sisi, untuk menunjukkan bahwa perempuan juga bisa seperti laki-laki, sehingga mereka menuntut kesetaraan gender, mereka menggunakan perempuan kulit hitam sebagai ikon. Namun, di sisi lain perempuan kulit hitam tidak mendapat pengakuan atas identitas diri mereka. Mereka selalu dianggap powerless, baik itu oleh laki-laki maupun oleh perempuan kulit putih. Perempuan kulit hitam, menurut Collin dan Palmer memiliki semua ciri-ciri keperempuanan, seperti yang melekat pada perempuan kulit putih. Sama seperti perempuan kulit putih, mereka juga adalah ibu. Mereka memiliki semangat laki-laki : tegas, gagah giat, memiliki jiwa mandiri, dan tidak mengenal rasa takut—sifat-sifat yang menurut feminis Barat juga dapat dimiliki oleh perempuan, sehingga mereka seharusnya punya hak yang sama dengan laki-laki. Namun begitu, karena label mereka adalah “kulit hitam”, mereka tak mendapatkan pengakuan yang seharusnya menjadi milik mereka. Bangsa Barat khususnya di Amerika menyebut “the daughter of Africa tidak memiliki ambisi dan kekuatan” (Collins, 2000: 2). Perempuan kulit hitam telah lama menjadi kelompok yang paling tertindas di Amerika. Mereka merupakan kelompok dengan pendapatan terendah, presentasi penyelesaian studi di perguruan tinggi rendah, dan proporsi tertinggi untuk kehamilan remaja. Bagi banyak perempuan kulit putih, perempuan kulit hitam adalah korban 36 klasik dalam hal penindasan seks (Palmer, 1983: 153). Collins (2000: 54) menulis pengakuan seorang perempuan kulit hitam. Saya kehilangan posisi saya, karena saya menolak mengizinkan suami Nyonya saya mencium saya. Ketika suami saya datang kepada laki-laki yang telah melecehkan saya, dia mengumpat suami saya, dan menamparnya, lalu suami saya ditangkap dan diadili. Meskipun, perempuan ini telah memberikan kesaksian di pengadilan, suaminya tetap membayar denda $25 dan ketua majelis hakim berkata “Pengadilan ini tidak akan pernah memihak kesaksian seorang nigger yang melawan perintah laki-laki kulit putih”. Pengalaman historis kolektif perempuan kulit hitam terkait opresi menstimulasi pendirian definisi diri perempuan kulit hitam ini, dapat membantu aktivisme perempuan kulit hitam (Collins, 2000: 30). Bagi perempuan Afro Amerika, pengalaman yang diperoleh dari opresi ras, kelas, dan gender, telah memeberikan stimulus pada mereka untuk mengangkat pengetahuan tentang teori sosial kritis perempuan kulit hitam yang tidak pernah diindahkan (Collins, 2000 : 9). Sebagai kelompok yang selalu teropresi, perempuan kulit hitam di Amerika telah menciptakan gagasan sosial yang didesain untuk melawan opresi. Tujuan dari gagasan kolektif perempuan kulit hitam sangat jelas berbeda dengan teori sosial yang sudah ada. Teori sosial yang dimunculkan oleh separuh perempuan kulit hitam di Amerika dan kelompok lain, selalu bertujuan untuk mendapatkan jalan bertahan dan keluar dan/atau melawan ketidak adilan social, serta ekonomi yang mereka alami. Teori sosial “kritis” ini berpegang pada komitmen akan keadilan baik untuk perempuan kulit hitam di Amerika, maupun kelompok-kelompok lain yang sama teropresi seperti mereka (Collins, 2000: 8-9). 37 Melihat kehidupan yang dialami oleh perempuan kulit putih, perempuan kulit hitam kemudian mempertanyakan kontradiksi-kontradiksi antara ideologi dominan perempuan kulit putih dan status devaluasi perempuan kulit hitam. Jika perempuan diasumsikan pasif dan rapuh, lalu kenapa perempuan kulit hitam disebut “bagal/mules” dan disuruh mengerjakan pekerjaan rumah yang berat? Jika ibu yang baik adalah yang tinggal di rumah bersama anak-anak mereka, lalu kenapa perempuan kulit hitam dipaksa untuk mencari pekerjaan dan meningalkan anak mereka di penitipan anak? Jika prioritas tertinggi perempuan adalah menjadi ibu, lalu kenapa perempuan kulit hitam yang menjadi ibu di usia muda ditekan untuk menggunakan Norplant dan Depo Provera? (Collins, 2000 : 12) Baik dalam kelompok ras kulit putih maupun kulit hitam, ada pengkotakkotakan lagi menurut kelas mereka, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas pekerja pada hirarki terbawah. Antara perempuan kulit hitam middle class dan working class mengalami jenis opresi yang berbeda karena mereka memiliki kelas yang berbeda. Namun tetap saja, pekerja yang berasal dari ras kulit putih mendapatkan keuntungan lebih dibanding kulit hitam. Dalam masing-masing kelas ini, perempuan memiliki posisi di bawah laki-laki. Sementara, segregasi rasial memisahkan Afro Amerika dari Amerika kulit putih, relasi gender dalam masyarakat kulit hitam memisahkan laki-laki dan perempuan. Ruang laki-laki adalah jalanan, rumah cukur, rumah biliar, sedangkan ruang perempuan adalah rumah dan gereja. Selain itu, sebenarnya ada perbedaan kelas di kalangan masyarakat kulit hitam, tetapi tertutupi oleh segregasi yang lebih 38 besar, yaitu segregasi rasial. Laki-laki kulit hitam bisa mendapatkan gaji yang tinggi, tetapi pekerjaannya beresiko, sementara perempuan kulit hitam mendapatkan upah yang lebih rendah, pekerjaan yang lebih banyak. Namun, karena laki-laki kulit hitam berkompetisi langsung dengan laki-laki kulit putih, maka mereka lebih rentan di PHK (Collins, 2000:55). Meskipun kebanyakan perempuan kulit hitam menolak untuk diobjeksi sebagai the Other, pengendalian image ini masih kuat pengaruhnya dalam relasi perempuan kulit hitam dengan ras kulit putih, laki-laki kulit hitam, grup rasial/etnis yang lain, dan sesama perempuan kulit hitam. Standar kecantikan yang berlaku (terutama warna kulit, bentuk wajah, tekstur rambut) merupakan salah satu contoh spesifik bagaimana kontrol image menghina diri perempuan kulit hitam. Perempuan Afro Amerika mengalami penderitaan, karena tidak pernah mampu mencapai standar kecantikan yang berlaku; standar yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan kulit putih, laki-laki kulit hitam, dan yang paling menyedihkan sesama perempuan kulit hitam juga demikian. Hal ini karena pengendakian image kontrol ini sifatnya hegemonik dan taken for granted, sehingga pada hakekatnya tidak mungkin untuk keluar darinya (Collins, 2000: 89-90). 1.7 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, kemudian diaplikasikan secara sistematis. Tahap pertama adalah proses pengumpulan 39 data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian melangkah ke tahap ke dua yaitu analisis data. Adapun objek dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu objek material dan objek formal. Objek material penelitian ini adalah novel Harry Potter, sedangkan objek formalnya adalah konstruksi femininitas dan maskulinitas. 1. Metode Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Novel Harry Potter yang sekaligus merupakan objek material dari penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku – buku, artikel, jurnal, serta hasil penelitian relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diambil, baik data primer maupun sekunder adalah yang berhubungan dengan citra sihir serta witch dan wizard di masyarakat khususnya di Eropa, wacana maskulinitas hegemonik, posisi laki-laki dan perempuan, hubungan keduanya dalam relasi gender, serta pemosisian sentral dan periferi akibat persinggungan gender/ras/kelas. Dalam proses pengumpulan data ini, yang pertama kali dilakukan adalah membaca novel Harry Potter secara keseluruhan, kemudian menentukan aspek apa yang akan menjadi fokus kajian penelitian, dimana yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah hubungan antara sihir dan konstruksi masskulinitas femininitas. Setelah itu, menentukan konsep teoretis apa yang akan digunakan untuk mendukung analisis. Konsep teoretis dalam penelitian ini adalah konsep maskulinitas dan hirarki 40 gender R.W. Connell. Kemudian dilakukan pengelompokan narasi dan dialog-dialog dalam teks Harry Potter yang didasarkan beberapa implikatur sebagai berikut: a. Sihir sebagai penentu kekuasaan Contohnya: “…Dumbledore is particularly famous… for the discovery of twelve uses of dragon’s blood, and his work on alchemy with his partner, Nicolas Flamel” (HP Vol.1, 67). (Dumbledore khususnya terkenal… karena penemuannya untuk dua belas kegunaan darah naga, dan karyanya di bidang alkimia yang dikerjakan bersama temannya, Nicolas Flamel). b. Kesetaraan posisi dalam memaknai witch dan wizard Contohnya: The name of Grindelwald is justly famous: In a list of Most Dangerous Dark Wizards of All Time, he would miss out on the top spot only because You-KnowWho arrived, a generation later, to steal his crown… (HP Vol. 7, 355) (Nama Grindelwald pantas terkenal dalam daftar Penyihir Hitam paling berbahaya sepanjang masa, dia terusir dari tempat pertamanya hanya karena kemunculan Voldemort, satu generasi kemudian untuk mencuri mahkotanya…). c. Karakteristik maskulinitas hegemonik Contohnya: “That Harry Potter’s got more backbone than the whole Ministry of Magic put together!” (HP Vol. 6, 139). (“Si Harry Potter itu punya keberanian lebih besar daripada seluruh Kementerian Sihir bersama-sama!”). d. Perempuan sebagai individu yang cerdas, kuat dan mandiri 41 Contohnya: Harry now saw red hair flying like flames in front of him: Ginny was locked in combat with the lumpy Death Eater,… (HP Vol. 5, 598). (Harry sekarang melihat rambut merah berkibar seperti lidah api di depannya. Ginny sedang bertempur melawan si Pelahap Maut gendut,…). e. Relasi laki-laki dan perempuan dalam hirarki gender Contohnya: Hermione let out a great sigh "Brilliant," said Hermione. "This isn't magic—it’s logic—a puzzle. A lot of the greatest wizards haven't got an ounce of logic, they'd be stuck in here forever." "But so will we, won't we?" "Of course not," said Hermione. "Give me a minute." Hermione read the paper several times. Then she walked up and down the line of bottles, muttering to herself and pointing at them. (HP Vol. 1, 231) (Hermione mengembuskan napas lega “Brilian! Ini bukan sihir,” puji Hermione. “Ini bukan sihir—ini logika—teka-teki. Banyak penyihir besar yang tidak punya logika sama sekali, akan terkurung di sini selamanya.” “Kita juga begitu, kan?” “Tentu saja tidak,” kata Hermione. “Beri aku waktu sebentar.” Hermione membaca kertas itu beberapa kali. Kemudian dia berjalan mondar mandir di depan deretan botol, bergumam sendiri dan menunjuk-nunjuk botol itu). f. Pemosisian sentral dan periferi yang dipengaruhi oleh persinggungan antara gender dengan ras dan kelas. Contohnya: “…choked the elf. “Dobby has neverbeen asked to sit down by a wizard — like an equal—” (HP Vol. 2, 13) (Si peri tersedak. “Belum pernah Dobby dipersilahkan duduk oleh seorang penyihir—seakan kita sederajat…”). 42 2. Klasifikasi Data Pada tahap ini penulis mendaftar semua penggalan isi cerita dan dialog yang menjadi korpus data, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan poin-poin yang menjadi pembahasan. Data yang diperoleh dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah pencitraan ulang sihir, wirch, dan wizard. Yang kedua relasi antara konstruksi wacana maskulinitas dan femininitas. Dari dua kelompok besar ini kemudian dikelompokkan lagi menjadi enam kelompok yang lebih kecil agar pembahasan dapat menjadi lebih spesifik. Keenam kelompok tersebut meliputi: a. Pemosisian sihir sebagai penentu kekuasaan b. Pemaknaan witch dan wizard sebagai dua hal yang setara c. Rekonstruksi wacana maskulinitas hegemonik d. Perempuan sebagai individu yang cerdas, kuat, dan mandiri e. Relasi saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan f. Pemosisian sentral dan periferi 3. Metode Analisis Data Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan adalah menganalisis sifat dan karakter para tokoh, interaksi antar tokoh, dan dinamika lingkungan sosial yang dibangun pengarang dalam novel tersebut melalui dialogdialog, serta narasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian, hasil analisis itu digunakan untuk menjabarkan hubungan antara sihir dan konstruksi maskulinitas 43 femininitas dalam novel dengan konsep-konsep dalam teori Connell sebagai acuannya. 1.8 Sistematika Penyajian Studi tentang wajah baru maskulinitas hegemonik dan witch (perempuan tukang sihir) dalam novel Harry Potter ini disajikan dalam empat bab. Secara garis besar penyajiannya terdiri dari bagian pendahuluan, pembahasan permasalahan penelitian, dan kesimpulan. Secara lebih spesifik, akan dijelaskan sebagai berikut. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari poin-poin sebagai berikut : 1). Latar Belakang, berisikan alasan yang mendasari penulis untuk mengambil kajian tentang pembongkaran wacana maskulinitas hegemonik dan citra witch dalam novel Harry Potter; 2). Rumusan Masalah, yaitu tentang permasalahanpermasalahan yang akan dikaji dalam studi ini; 3). Tujuan Penelitian; 4). Manfaat Penelitian; 5). Tinjauan Pustaka; 6). Landasan Teori; 7). Metode Penelitian. Bab II merupakan pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian pertama yang ada di rumusan masalah. Bab II dibagi menjadi dua sub poin yaitu; 1). Tentang sihir yang ditempatkan sebagai penentu kekuasaan dalam novel Harry Potter. Narasi ini menjelaskan tentang bagaimana Rowling mengubah makna dan posisi sihir. Sihir yang tadinya merupakan simbol kelemahan dan keburukan yang melekat pada perempuan diubah menjadi sesuatu yang bernada positif dan lekat dengan kekuasaan; 2). Witch dan Wizard yang dimaknai sebagai dua hal yang setara. Sub poin ini 44 menjelaskan bagaimana Rowling mengubah makna witch. Menunjukkan bahwa Witch tidak selalu berarti perempuan yang menggunakan sihir untuk kejahatan. Bab III merupakan pembahasan yang menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga. Bab ini dibagi menjadi empat sub poin; 1). Wajah baru maskulinitas hegemonik. Bagian ini membahas karakteristik maskulinitas hegemonik dalam Novel Harry Potter yang menentang ciri-ciri maskulinitas hegemonik yang kerap dijumpai di masyarkat. Disini digambarkan sebagai seorang laki-laki, merupakan hal yang wajar kalau seseorang menunjukkan sisi feminine; 2). Karakteristik perempuan yang merupakan individu yang cerdas, kuat, mandiri, tetapi tetap tidak menghapus femininitasnya; 3). Mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, sehubungan dengan karakteristik yang sudah dibahas pada sub poin 1 dan 2; 4). Membahas hubungan sentral-periferi yang lebih kompleks dalam hirarki gender, sebagai akibat persinggungan antara gender, ras, dan kelas. Bab IV merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari kajian yang sudah dilakukan. 45