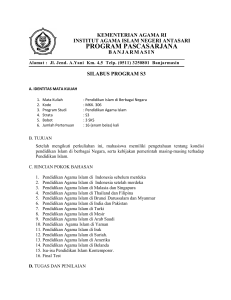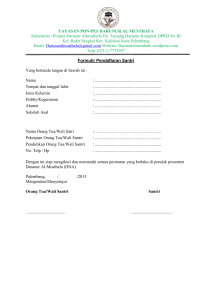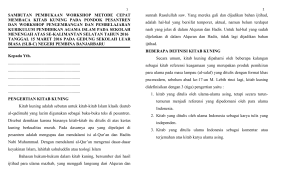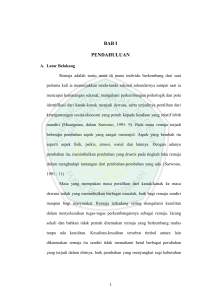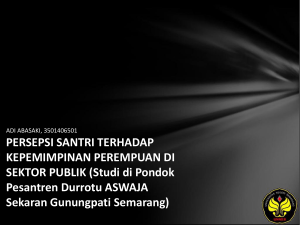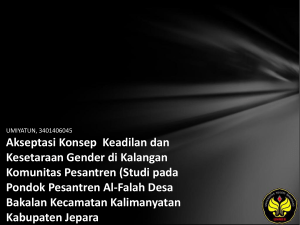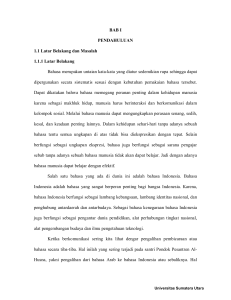BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan tentang Pendidikan Politik 1
advertisement

BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan tentang Pendidikan Politik 1. Pengertian Pendidikan Politik Pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdasarkan falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Selain itu, fungsi pendidikan di Indonesia adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sesuai rumusan pasal 7 Bab V Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, upaya pendidikan politik merupakan sarana vital dalam pembentukan warga negara atau individu-individu untuk mendapatkan informasi, wawasan, serta memahami sistem politik yang berimplikasi pada persepsi mengenai politik dan peka terhadap gejala-gejala politik yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya, warga negara diharapkan memiliki keterampilan politik sehingga memiliki sikap yang kritis dan mampu mengambil alternatif pemecahan masalah dari masalah-masalah politik yang ada. Pendidikan politik di Indonesia secara edukatif merupakan upaya yang sistematis untuk memantapkan kesadaran politik dan bernegara untuk menjaga kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Jadi, pendidikan politik disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta yang menjadi landasan moral bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasai Muda sebagai berikut: Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya bangsa. Perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai-nilai tertentu yang secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu. Dalam hal ini Affandi (1993:3) menyatakan pendapatnya, “Pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, yakni sebagai proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dari konsep dirinya”. Proses internalisasi nilai-nilai ini menjadi kekuatan pendidikan politik yang memberi makna bahwa pendidikan dan politik itu saling bertautan. Pendidikan politik mencoba mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan diterapkan pada warga negara sebagai landasan pola pikir dalam membangun partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik warga negara dapat diwujudkan dalam bentuk pengambilan keputusan politik yang didasarkan pada kebebasan memilih dan menentukan keputusan yang dibuat. Hal ini senada dengan Haines (Brownhill, 1989:4) bahwa upaya pendidikan politik bertujuan untuk “Free men have to decide, to chose, to elect refresentatives, support or under mine policies, advocate, persuade, guide, teach, as well as manage, their own affairs as well as they are able”. Dengan demikian pendidikan politik menghargai hak setiap individu untuk memilih dan mengambil keputusan politik tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta berpartisipasi dalam sistem politik yang ada. Pendidikan politik pun memiliki tujuan untuk menarik individu memahami politik sehingga menjadi warga negara yang bertanggungjawab dengan mencoba bagaimana menganalisa dan memberikan penilaian terhadap situasi politik yang sedang berlangsung secara mandiri. Pendapat ini senada dengan pernyataan Haines (Idrus Affandi, 1993:5) bahwa: Pendidikan politik adalah bagaimana mengembangkan keinginan professional dalam politik dan mengutamakan yang mengarah kepada tanggungjawab politik, yang dalam waktu yang sama berusaha memberikan kepada mereka pengetahuan yang penting dan keterampilan untuk melaksanakan tanggungjawab. Definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan politik merupakan upaya pembinaan kepada setiap individu untuk berpartisipasi terhadap kehidupannya dengan penuh rasa tanggungjawab. Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang bahwa “pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara nasional dalam sistem politiknya”. Dengan demikian pendidikan politik sebagai cara untuk mengenalkan serta memahami politik kepada warga negara untuk secara aktif berpartisipasi dalam sistem politik yang sedang berjalan. Sedangkan Alfian (1992:235) mengemukakan pendapat tentang pendidikan politik sebagai berikut: Pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Dengan demikian, pendidikan politik menurut Alfian sama dengan sosialisasi politik, yaitu proses menyampaikan atau menyebarkan program-program pemerintah (penguasa) kepada masyarakat dalam suatu sistem politik. Senada dengan Alfian, Wahab (Komarudin, 2005:19) mengemukakan, bahwa “pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilainilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Kedua pendapat tersebut berkaitan erat dengan sosialisasi politik. Dalam hal ini pendidikan politik merupakan upaya mengenalkan suatu sistem politik pada individu dan menentukan reaksi terhadap gejala-gejala politik dalam sistem tersebut. Konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (2001:22), bahwa sosialisasi politik diartikan sebagai “suatu proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat-sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik”. Inti dari pengertian sosialisasi yang diungkapkan Michael Rush dan Philip Althoff tersebut, yaitu pengenalan terhadap sistem politik. Apabila seorang individu telah mengenali lingkungan sistem politiknya maka individu tersebut akan memiliki persepsi terhadap lingkungan sistem politiknya. Perlu diketahui bahwa persepsi setiap individu terhadap lingkungan sistem politiknya akan berbeda-beda tergantung intensitas sosialisasi, pesan yang ada dalam sosialisasi, penyampaian atau media sosialisasi tersebut. Selain itu aspek-aspek yang ada dalam individu juga akan mempengaruhi tingkat persepsi orang mengenai sistem politiknya seperti intelegensi, tingkat pendidikan, emosi, nilai-nilai, dan sebagainya. Karena persepsi setiap individu berbeda maka tidak aneh reaksi-reaksi terhadap sistem politiknya pun akan berbeda-beda pula. Proses ini dipengaruhi oleh lingkungan individu berada baik secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan politik yang diperoleh setiap individu menimbulkan pengalaman-pengalaman politik yang baru sehingga menimbulkan perilaku politik. Perilaku politik sebagai hasil pendidikan politik diungkapkan oleh Kenzie dan Silver (Rush dan Althoff, 200:180) bahwa: Perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar, dan oleh situasi khusus yang dihadapainya. Asosiasi antara berbagai karakteristik pribadi dan sosial dan tingkah laku politik mungkin adalah hasil dari motivasi sadar atau tidak sadar, atau yang lebih mungkin lagi kombinasi keduanya. Dengan demikian perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai-nilai tertentu yang secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu. Dalam hal ini Affandi (1996:3) menyatakan pendapatnya “pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, yakni sebagai proses dengan mana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dari konsep dirinya”. Dalam hal ini politik dilihat sebagai inti dari proses pendidikan politik yakni membenarkan nilai-nilai dan menerapkannya di masyarakat, sedangkan pendidikan adalah media untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut. Sehingga inti dari proses pendidikan politik yakni internalisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk mengembangkan pemahaman sistem politik menuju pembentukan warga negara yang melek politik. Hal ini sesuai dengan Made Suara (2006) bahwa “Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar mendapat informasi, wawasan, dan keterampilan politik hingga sanggup bersikap kritis dan lebih internasional serta lebih terarah hidupnya”. Dengan demikian, pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk menciptakan warga negara yang benar-benar melek politiknya. Selain itu, pendidikan politik sebagai usaha dalam mencapai hak politik yang dimiliki setiap warga negara dalam membangun dan menjalankan suatu sistem politik yang ada. Di samping itu warga negara diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang menuntut kedewasaan berpolitik untuk menciptakan kedamaian bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Tujuan Pendidikan Politik Pada dasarnya tujuan pendidikan politik di setiap negara berbeda-beda. Hal ini terjadi karena landasan serta tujuan pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan dengan dasar dan falsafah bangsa. Indonesia sebagai negara yang demokratis menjalankan proses pendidikan politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan warga negara. Sehingga tujuan pendidikan politik harus sejalan dengan penjabaran tujuan pendidikan nasional. Dalam rumusan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Upaya untuk mengembangkan pendidikan yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta menjadi warga negara adalah bagian penting dari tujuan pendidikan politik. Menurut Wahab (Komarudin, 2005:24), “… pendidikan politik bertujuan membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara”. Dengan demikian, terwujudnya warga yang baik (good citizen) yaitu warga negara yang melek politik, memiliki kesadaran politik, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan tujuan utama dari pendidikan politik. Proses pendidikan politik merupakan suatu proses untuk membina dan mengembangkan warga negara untuk mengenali sistem politik dan reaksi terhadap gejalagejala politik. Pada dasarnya tujuan pendidikan politik adalah membentuk manusia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam rangka memahami situasi sistem politik menuju kesejahteraan hidup bangsa. Selain itu, pendidikan politik diharapkan mampu menciptakan warga negara yang memiliki jiwa nasionalis dan egaliter serta kualitas pribadi yang kuat sebagai warga negara. Terdapat beberapa tujuan dari pendidikan politik sebagaimana dikemukakan oleh Amril (2004:104) sebagai berikut: a. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga negara yang baik; khususnya dalam fungsi sosial dan fungsi politik, seperti bisa mengembangkan sikap gotong royong/kooperatif, mau bermusyawarah dan kerjasama; bersikap toleran, solider, loyal terhadap bangsa dan negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama. b. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggungjawab politik, agar orang menjadi insan politik yang terpuji (bukan memupuk egoisme dan menjadi bintang politik). c. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada di tengah masyarakat itu tidak permanen, tidak massif atau immanen sifatnya, tetapi selalu saja bisa berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik. d. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik politik yang aktual, lalu berusaha ikut memecahkan; jadi terdapat partisipasi politik. Sebab, urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau dampak keburukan kepada rakyat banyak. Karena itu rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan politik yang menyangkut mati hidupnya diri sendiri dan keselamatan rakyat pada umumnya. e. Selanjutnya berpartisipasi politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan proses-proses politik dari warga negara dan pertanggungjawabannya untuk mengatur masyarakat dan negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera. f. Partisipasi aktif itu memiliki pengaruh dan kekuatan sebab biasanya ikut pula dalam pengawasan aktivitas mengatur masyarakat dan negara. Maka menjalani proses pendidikan politik tanpa bisa berbuat politik itu sama saja dengan berenang di atas kasur. Sebaliknya melakukan perbuatan politik tanpa refleksi atau kearifan dan pendidikan politik bisa disebut aktivisme, yaitu berbuat awurawuran atau anarki dan perbuatan makar. Jika melihat maksud pendidikan politik di atas tidaklah salah apabila pendidikan politik diberikan kepada generasi muda sebagai bagian dari pembinaan generasi muda Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang demokratis di masa yang akan datang. Selain itu diharapkan para generasi muda mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara tangguh dan penuh tanggungjawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan tujuan pendidikan politik sebagai berikut: Untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat sebagai berikut: a. Sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggungjawab sebagai warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara. b. Sadar dan taat pada hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku. c. Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan objektif bangsa saat ini. d. Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional. e. Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. f. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan bangsa dan bernegara khususnya dalam usaha pembangunan nasional. g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa. h. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi, dan seimbang. i. Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan, nilai serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain di luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir dan penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini pendidikan politik di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Peningkatan pemahaman akan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu meningkatkan partisipasi secara aktif untuk membangun bangsa sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa. Pandangan di atas sejalan dengan Sumantri dan Affandi (1986:126) yang menyatakan bahwa: Maksud diselenggarakannya pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Generasi muda sebagai pewaris cita-cita bangsa dituntut untuk berpartisipasi secara aktif membangun bangsa. Oleh sebab itu, generasi muda harus memiliki pengetahuan serta keterampilan politi sehingga para generasi muda menggunakan pengetahuannya untuk berpolitik secara bertanggungjawab. Pendapat ini sejalan dengan Brownhill dan Patricia Smart (1989:4) bahwa: The aim of political education should therefore be to develop the professionals interest and to poin them toward their political responsibilities, while at the same time endeavouring togive them the necessary knowledge and skills to carry out those responsibilities. Dengan demikian, pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan untuk bertanggungjawab sebagai warga. Selain itu memberikan pemahaman mengenai pengetahuan politik sehingga warga negara berpartisipasi dalam sistem politik yang sedang berjalan. Pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan secara sistematis untuk menumbuhkan iklim demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ragnar Muller (2006) mengungkapkan bahwa “One of the fundamental objectives of political education is to develop an understanding of politics among pupils and to give them an insight into how politics works and how it is connected”. Jadi, salah satu tujuan pendidikan politik adalah mengembangkan sebuah pemahaman diantara siswa dan memberikan kepada siswa wawasan tentang bagaimana politik berjalan dan mencari hubungan konsep dasar politik. Konsep dasar politik atau basic knowledge yang dapat diberikan kepada setiap individu adalah konsep demokrasi, pemilihan umum, partai politik, dan lain-lain. Konsep ini diberikan kepada individu sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap politik. Setelah memahami politik diharapkan individu mampu memberikan opini politik secara independent berdasarkan konsep dasar politik yang diketahuinya. Setelah itu, individu diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam politik sebagai perwujudan bertanggungjawab. Berikut ilustrasi dari uraian di atas: dari warga negara yang Gambar 2.1 Tujuan dan Tugas Pendidikan Politik WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB PARTISIPASI POLITIK OPINI POLITIK INDEPENDENT [ PEMAHAMAN POLITIK KONSEP DASAR POLITIK TUJUAN DAN TUGAS PENDIDIKAN POLITIK (Sumber: Devi Andriana, 2007:34) Dalam hal ini pendidikan politik diarahkan pada pembentukan warga negara yang memiliki sikap dan analisis kritis terhadap berbagai masalah sosial politik di lingkungannya. Sehingga diharapkan warga negara ikut serta dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan memiliki kesadaran politik yang berimbas pada partisipasi politik aktif. Pendidikan politik menjadi sebuah pemahaman dalam setiap warga negara untuk dihayati sehingga membentuk perilaku politik atau melek politik. Kedudukan dan pelaksanaan pendidikan politik dikemukakan oleh Affandi (1996:6) sebagai berikut: Pendidikan politik tidak saja akan menentukan efektivitas sebuah sistem politik karena mampu melibatkan warganya, tetapi juga memberikan corak pada kehidupan bangsa di waktu yang akan datang melalui upaya penerusan nilai-nilai politik yang dianggap relevan denga pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Sedangkan A. Kosasih Djahiri (Iyep Candra Hermawan, 2004:33) mengemukakan bahwa pendidikan politik di Indonesia memiliki target ysng jelas, yaitu membina siswa melek politik yakni manusia Indonesia yang: 1. Melek konstitusi dan hukum; yang memahami pokok pikiran UUD 1945 dan hukum yang ada dalam negara RI serta mengerti esensi penegakkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Melek pembangunan; yakni manusia yang memahami laju gerak kemajuan bangsa yang sudah, sedang, dan akan ditempuh serta mau dan mampu berpartisipasi secara aktif dan fungsional. 3. Melek masalah; yakni tahu persoalan, kendala, dan kesulitan yang dihadapi masyarakat, bangsa, negara, dan dirinya dalam membina hal-hal di atas. Dari penjelasan di atas, pendidikan politik memegang peranan yang sangat vital untuk mencapai kehidupan bangsa yang lebih demokratis. Dengan pendidikan politik dibentuk dan dikembangkan warga negara yang memiliki kesadaran politik dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik ditinjau dari sudut proses merupakan upaya pewarisan nilai-nilai budaya bangsa, proses peningkatan dan pengembangan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Sehingga partisipasi aktif warga negara memberikan konstribusi bagi pembangunan demokrasi Indonesia serta sesuai dengan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bentuk-bentuk Pendidikan Politik Pendidikan politik ditinjau dari sudut proses merupakan upaya pewarisan nilai-nilai budaya bangsa, proses peningkatan dan pengembangan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Sehingga partisipasi aktif warga negara memberikan kontribusi bagi pembangunan demokrasi Indonesia yang sesuai dengan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian ini berkaitan dengan bentuk-bentuk pendidikan politik yang akan dilaksanakan dan ditinjau dari sudut proses maupun tujuan yang hendak dicapai. Bentuk-bentuk pendidikan politik diharapkan mampu menciptakan warga negara yang melek politik. Menurut Stradling (Brownhill dan Patricia Smart, 1989:105) mengemukakan bahwa: Pengertian melek politik di sini sebaiknya menyangkut keterampilan tindakan yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk berpartisipasi dalam membentuk keputusan kelompok dan kemampuan secara selektif untuk mempengaruhi dan atau merubah institusi politik. Pendidikan politik untuk menciptakan warga negara yang melek politik merupakan upaya pembangunan politik masyarakat untuk mengenal, mengetahui, dan memahami sistem politik yang berjalan serta nilai-nilai politik tertentu yang akan mempengaruhi perilaku warga negara. Menurut Idrus Affandi (Komarudin S, 2005:22) bahwa: “Pembangunan politik merupakan proses penataan kehidupan pemerintah yang terus-menerus sesuai dengan pertumbuhan sosial politik masyarakata dan tidak dapat dibendung oleh suatu rezim tertentu yang menghendaki kekuasaan absolut”. Dari definisi tersebut terungkap bahwa perubahan yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia harus disikapi serta direspon melalui pembangunan politik atau pendidikan politik agar manusia sebagai warga negara dapat menyikapi perubahan yang terjadi secara sadar dan bertanggungjawab. Perubahan yang selalu terjadi menjadi wahana bagi pembinaan perilaku politik yang cerdas, kritis, dan bertanggungjawab. Pembinaan perilaku politik dapat melalui penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan dengan pengajaran-pengajaran yang mengacu pada substansi dari pendidikan politik tersebut. Dalam hal ini, substansi kurikulum pendidikan politik menurut Stradling (Brownhill dan Patricia Smart, 1989:104) membaginya ke dalam tiga bagian, yaitu: Pertama, pengetahuan; yang terdiri dari pengetahuan professional, dan pengetahuan praktikal, pemahaman. Kedua, keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi. Ketiga, sikap dan nilai-nilai prosedural. Dari pendapat di atas, secara garis besar kurikulum pendidikan politik menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam aspek kognitif pendidikan politik memberikan pengetahuan dan pemahaman politik terhadap setiap individu. Sedangkan dalam aspek psikomotor kurikulum pendidikan politik hendaknya memberikan kemampuan keterampilan kepada individu untuk memiliki keterampilan intelektual, tindakan, dan komunikasi politik secara efektif. Kurikulum pendidikan politik secara efektif harus membuat individu menimbulkan sikap politik sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal senada diungkapkan oleh Brownhill dan Patricia Smart (1989:110) yang mengungkapkan bahwa kurikulum pendidikan politik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Nilai-nilai, tujuan, etika dasar serta sasaran yang dicapai, antara lain: isi kurikulum harus didasarkan kepada suatu etika yang dapat diterima oleh semua jenis dan kalangan masyarakat. b. Nilai-nilai tersebut nantinya dipakai sebagai bahan untuk menyusun informasi, pengetahuan teoritis serta hal-hal yang bersifat informative dan kognitif. c. Selain pengetahuan yang bersifat teoritis, kurikulum pendidikan politik harus mengandung seperangkat pengetahuan praktis. Lebih lanjut, Brownhill dan Patricia Smart (1989:110) mengemukakan pengetahuan praktis dalam kurikulum pendidikan politik terdiri dari: a. Hakekat argumen rasional, argument deduktif. Argument induktif, serta bentuk-bentuk argumen dialektika dari argument politik. b. Argument persuasive, yakni bagaimana memberikan argumentasi dengan caracara yang dapat meyakinkan orang dan mampu memprestasikan secara logis maupun retorik. c. Penggunaan tekanan dalam perjanjian, bargaining, dan diplomasi dinamika kelompok diskusi. d. Keterampilan berkomunikasi dan menanamkan pengaruh di kalangan pengikut, keterampilan mengembangkan argument secara rasional maupun tertulis serta teknik-teknik persuasi. Dengan demikian isi dari kurikulum pendidikan politik tidak hanya menanamkan pengetahuan dan keterampilan semata, akan tetapi mengandung bagaimana bersikap secara politik yang disertai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pewarisan dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat ke setiap individu. Pendidikan politik sesungguhnya telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia sebab di mana ada manusia maka terdapat pula masyarakat atau dengan kata lain manusia adalah zoon politicon. Sehingga ketika terdapat unsur politik dalam kehidupan manusia maka akan terjadi sosialisasi politik dalam arti longgar dari pendidikan politik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah digariskan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 bahwa jalur-jalur terlaksananya pendidikan politik meliputi: a) jalur informal, b) jalur formal, dan c) jalur non formal. Hal senada diungkapkan oleh Kuntowijoyo (Dian Sudiono, 2004:78) yang menyebutkan bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan politik sebagai berikut: Pendidikan politik formal, yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi. Berikutnya adalah pendidikan politik yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan formal, seperti pertukaran pemikiran melalui mimbar bebas, sedangkan pendidikan politik yang baik adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbolsimbol nasional, seperti sejarah, seni, sastra, dan bahasa. Dalam definisi di atas metode indoktrinasi merupakan metode pendidikan politik secara formal yakni di tingkat persekolahan. Namun pendidikan politik yang baik adalah pendidikan politik yang menampilkan simbol-simbol nasional untuk memperkuat jati diri bangsa. Warga negara yang melek politik harus memiliki karakter atau jati diri bangsa yang tangguh. Ruslan (Abu Ridha, 2002:58) mengemukakan, bahwa institusi untuk menyampaikan pendidikan politik meliputi “Keluarga, sekolah, partai politik, dan kelompok penekan, berbagai media informasi dan komunikasi massa”. Dari dua pendapat di atas menunjukkan, bahwa media massa memegang peranan yang sangat besar untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu sebagai imbas dari era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Selain media massa pendidikan politik secara formal dilakukan pada persekolahan dan hal ini menjadi tahap awal yang penting bagi proses pendidikan politik sehingga peranan sekolah sangat penting dalam pendidikan politik. Pendidikan politik di persekolahan akan menentukan sikap politik setiap individu yang dipengaruhi pula oleh faktor lingkungan serta keakuratan informasi yang diterima dari media cetak atau elektronik. Proses pendidikan politik yang dilakukan secara formal di persekolahan menjadi tahap awal untuk indoktrinasi politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Brownhill (1989:143) bahwa “Most opposition to the inclusion of political education in the curriculum comes from those who maintain that the teaching of politics in schools would be the first stepping stone to political indoctrination”. Kajian terhadap proses indoktrinasi dalam proses pendidikan masih menjadi perdebatan yang menimbulkan pro dan kontra. Walaupun sesungguhnya dalam proses pendidikan selalu menggunakan indoktrinasi karena indoktrinasi merupakan langkah awal untuk menanamkan ideologi. Pendidikan politik dalam lembaga formal harus menghilangkan kekhawatiran terhadap proses indoktrinasi sebagai hambatan dalam pengajaran politik. Hal ini didasarkan pada pendidikan politik merupakan salah satu pelajaran yang ditempatkan pada semua jenjang persekolahan. Alasan lainnya menurut Dunn (Brownhill, 1989:8) yakni “pendidikan politik di sekolah-sekolah telah memiliki tempat yang sah dalam kurikulum persekolahan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan politik sebagai syarat mutlak menjadi warga negara yang lebih dewasa”. Di Indonesia pendidikan politik yang diberikan di persekolahan dilakukan melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal ini tercantum dalam misi Pendidikan Kewarganegaraan yang baru yakni sebagai pendidikan politik. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki program pendidikan untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (political literacy) dan kesadaran politik (political awareness), serta kemampuan berpartisipasi politik (political participation) yang tinggi. Dalam bentuk pendidikan nonformal, pendidikan politik dapat dilakukan oleh partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan partai politik merupakan sebuah kewajiban karena salah satu ciri berjalannya fungsi partai politik sebagai media pendidikan politik. Berfungsinya partai politik sebagai media pendidikan politik merupakan tahap lanjutan bahkan tingkat akhir dari proses pendidikan politik di persekolahan. Partai politik dapat dijadikan tempat setiap warga negara untuk mengaplikasikan ilmu politik yang diperoleh sebagai perwujudan partisipasi politik. Sedangkan secara informal pendidikan politik dapat dilakukan dalam keluarga dan lingkungan, diantaranya memberikan contoh keteladanan. Secara nonformal dapat dilakukan oleh partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Dengan demikian bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan politik dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah melalui partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Penyelenggaraan pendidikan politik yang terbagi ke dalam tiga jalur tidak menghilangkan esensi dari tujuan pendidikan politik itu sendiri yakni meningkatkan kemelekan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik yang tinggi. Sesungguhnya komponen pokok dari proses pendidikan politik bukan terletak pada bentuknya, akan tetapi yang lebih pokok adalah substansi dari proses pendidikan politik tersebut yang meliputi materi dan kurikulum pendidikan politik. B. Tradisi Politik Pesantren 1. Landasan Etik Politik Islam Islam sebagai agama samawi yang komponen dasarnya aqidah, syariah, dan akhlak mempunyai korelasi yang erat dengan politik dalam arti yang luas. Sebagai sumber motivasi masyarakat, Islam berperan penting menumbuhkan sikap dan perilaku sosial politik. Implementasinya kemudian diatur dalam rumusan syari’ah sebagai katalog lengkap dari perintah dan larangan Alloh SWT, pembimbing manusia dan pengatur lalu lintas aspek-aspek kehidupan manusia. Islam dan politik mempunyai titik singgung yang kuat bila keduanya dipahami sebagai sarana untuk menata hidup manusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan sebagai ‘kedok” dan “alat legitimasi’ terhadap kekuasaan dan dipahami sebagai sarana perjuangan untuk menduduki struktur kekuasaan. Politik yang hanya dipahami demikian pada akhirnya akan mengaburkan makna dan menutup kontribusi Islam terhadap dunia politik. Dengan demikian Islam perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi cultural dan kerangka paradigmatic dalam pemikiran politik. Namun dalam perjalanan sejarahnya, Islam belum mampu meletakkan sistem religiopolitiknya sebagai kekuatan pembebas atau pengatur pranata sosial yang mapan. Islam cenderung berperan sebagai sumber ideologis untuk menjustifikasi kemapanan sebuah kekuasaan (status quo). Pemikiran politik Islam sebagai hasil sistematisasi ajaran-ajaran Islam dan tradisitradisi kaum muslimin di bidang politik muncul sejalan dengan kepesatan Islam keluar jazirah Arab. Ekspansi ini menimbulkan masalah-masalah baru tentang cara pengaturan negara, di samping konsekuensi logis munculnya kelompok-kelompok kepentingan (political interest groups). Kelompok-kelompok ini baik yang berbasis sosial budaya atau sosial keagamaan tertentu (mazhab) merasa ikut memberi kontribusi dalam proses jihad fisabilillah. Data historis menyebutkan fenomena persaingan-persaingan kelompok pemikiran keagamaan baik mazhab pemikiran kalam maupun dalam merebut pengaruh dan patronase dengan penguasa. Polarisasi pemikiran politik dalam Islam tampaknya lebih disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan teks-teks normative agama, disamping perbedaan-perbedaan basis sosial budaya yang melingkupinya. Perbedaan itu sangat wajar karena Islam tidak secara eksplisit memberikan suatu formulisasi bagi sistem kenegaraan yang baku dan harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Perhatian utama Al-Qur’an adalah memberikan landasan etik bagi terbangunnya sistem politik yang didasarkan pada prinsip tegaknya masyarakat yang berkeadilan dan bermoral. Oleh karena itu modal dan struktur ketatanegaraan Islam bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah karena ia senantiasa terikat dengan perubahan dimensi ruang dan waktu. Salah satu isu yang kontroversial dalam sejarah pemikiran politik Islam mengenai teori khilafah atau imamah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, masyarakat Islam yang masih baru mengalami kekosongan pemerintahan dihadapkan pada suatu krisis konstitusional, yaitu mengenai bagaimana mekanisme pemilihan kepala negara untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin komunitas Islam. Dalam konteks yang demikian ini, Al-Qur’an dan Al-Sunah tidak memberikan ketentuan yang jelas tentang mekanisme suksesi, bentuk pemerintahan dan lembaga politik lainnya. Informasi yang ada hanya bersifat global tentang garis-garis besar bagaimana suatu masyarakat harus dibentuk. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa Al-Qur’an ataupun AlSunah tidak memberikan suatu teori atau sistem politik yang baku sebagai pedoman masyarakat muslim? Paling tidak ada dua alasan pokok yang mendasarinya. Pertama, AlQur’an bukanlah sebuah kitab politik. Kedua, sudah merupakan kenyataan sejarah (sunnatullah) bahwa institusi-institusi sosial politik dan organisasi yang dibentuk manusia akan mengalami perubahan. Dari sini dapat dimengerti bahwa diamnya Al-Qur’an dalam masalah ini memberikan suatu jaminan dan sengaja member peluang bagi umat Islam untuk melakukan kajian-kajian dalam memformulasikan sistem politiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Landasan etik dari bangunan politik Islam adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Dari perspektif ini, suatu negara bisa dikatakan bercorak Islam manakala mampu menerjemahkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam tatanan politik praktis tanpa harus mempertanyakan bentuk dan sistem politik apa yang harus dibangun. Oleh karena itu mengkaji pemikiran politik dan sistem ketatanegaraannya dalam Islam harus diorientasikan pada upaya menerjemahkan cita-cita politik Islam dengan cara membuat format dan sistem politik yang sesuai dengan etika Al-Qur’an. Pada level perumusan formulasi sistem politik inilah sesungguhnya yang menjadi fokus perdebatan di kalangan pemikir muslim dari zaman klasik sampai pemikir muslim kontemporer. 2. Islam dan Wawasan Politik Salah satu karakteristik syariah Islam adalah cakupannya. Tidak ada satu pun dalam kehidupan yang tidak ada hukumnya dalam syariah. Oleh karena itu, dalam teks-teks AlQur’an kita dapat menemukan hukum-hukum ibadah, aqidah (teologi), akhlak dan muamalah dalam maknanya yang luas yang mengatur hubungan timbal balik manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Islam bukanlah agama yang hanya mementingkan persoalan keagamaan yang bersifat ritual saja. Lebih dari itu, Islam merupakan sistem ajaran yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Dari kajian tentang Al-Qur’an dan karir Nabi Muhammad selama ke-Rasul-annya, disimpulkan bahwa Islam dan wawasan kekuasaan (politik) harus disinari oleh wawasan moral sebagai salah satu indicator iman dalam konteks sosial dan realitas sejarah. Al-Qur’an telah menegaskan bahwa, “Katakanlah sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah pemelihara alam semesta”. Menurut ayat ini, shalat di masjid, berjualan di pasar, atau berbicara tentang masalah pembatasan masa jabatan presiden di parlemen tidaklah ditempatkan pada kategori dikhotomis antara ibadah dan kerja sekuler. Oleh karena itu agama tidak bisa dipisahkan dari politik dan politik harus disinari oleh nilai moral. Hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah diberi tauladannya oleh Rasulullah setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah (Al-Madinah, kota parexcellence). Dari nama yang dipilih oleh Nabi sebagai kota hijrahnya, menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi suci dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat yang berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan suatu entetitas sosial politik sebuah negara. Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Risalah Al-Qur’an adalah untuk member petunjuk kepada manusia termasuk dalam kapasitasnya sebagai makhluk politik. Maka agar kita mendapat gambaran yang memadai tentang petunjuk Al-Qur’an yang telah beroperasi dalam kenyataan sejarah, kita perlu mempelajari secara ringkas karir sejarah Nabi Muhammad, baik periode Mekkah maupun Madinah. Pada periode Mekkah, Nabi tidak mempunyai kekuasaan politik untuk menyokong misi kenabiannya, sementara di Madinah Nabi berperan sebagai kepala politik. Kerangka dasar pemikiran politik dalam Islam banyak diintrodusir oleh nash, baik AlQur’an maupun Al-Hadist terutama nash-nash yang berkaitan dengan konsep musyawarah (syura), keadilan (‘adalah), dan perjuangan melawan agresi. Pada umumnya konsep-konsep ini jarang tersentuh pada pembahasan kitab fiqih karena aksetuansi kitab fiqih lebih banyak pada aspek ibadah, mu’amalah dan jinayat. Oleh karena itu, maka kajian pada wilayah politik ini membuka kita untuk melakukan entellectual exercise (ijtihad) yang didasarkan pada penalaran manusia dan menjadi wilayah ijtihadiyyah. Prinsip syura dalam Islam sesungguhnya mengidealkan suatu sistem sosial politik sebagai manifestasi dari egaliter dan penegakkan nilai demokrasi. Dalam Islam mendirikan institusi politik (imamah) adalah bagian tugas keagamaan, rangka membumikan ajaran Islam dalam kerangka kehidupan sosial. Persoalannya kemudian adalah bagaimana sistem politik dijalankan. Diantara refleksi tauhid dalam kehidupan bermasyarakat adalah tumbuhnya sikap egaliter. Sikap ini akan dapat tercermin dan menjadi sistem nilai manakala teori-teori tentang keunggulan ras, suku bangsa, dan keturunan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam negara dipandang sebagai instrument bagi tegaknya syariah dan ia bukan eksistensi dari agama. Persoalannya kemudian, kenapa Islam tidak memberikan suatu sistem politik yang baku dan sistematis sehingga dapat dijadikan srandar dan berlaku universal bagi dunia Islam. Dalam hal ini ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, Al-Qur’an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia, ia bukanlah kita ilmu hukum atau politik. Kedua, sudah menjadi kenyataan sejarah manusia bahwa institusi politik dan organisasi manusia akan selalu berubah seiring dengan dinamika perubahan masyarakat. Oleh karena itu, diamnya Al-Qur’an dalam konteks ini justru memberikan ruang gerak bagi munculnya pemikiran-pemikiran baru dengan didasarkan pada kerangka etik Al-Qur’an. Dengan kata lain, Al-Qur’an tidak tertarik pada teori tertentu tentang bentuk dan sistem politik tertentu. Perhatian utama Al-Qur’an adalah agar masyarakat ditegaskan atas nilai-nilai keadilan dan moralitas. Konsekuensinya adalah model dari ketatanegaraan Islam bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah tetapi ia senantiasa terikat dengan perubahan, modifikasi, dan perbaikan menurut kebutuhan waktu dan tempat. Untuk membumikan nilainilai etika Al-Qur’an dalam kerangka kehidupan dan menjadi sistem sosial maka negara menjadi alat untuk mengorganisasikan dan menggerakkannya. Tanpa dukungan otoritas politik, syariah tidak akan tegak maksimal. C. Kultur Pesantren Anwar dan Matahari (2000:3) berpendapat, bahwa: “Secara kultural lembaga pondok pesantren telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan telah ikut serta membentuk dan memberikan corak serta nilai kehidupan kepada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Figur kyai, santri, dan perangkat fisiknya biasanya menunjukkan iklim yang senantiasa dikelilingi oleh kultur yang bersifat religious keislaman. Proses keterpaduan dalam pesantren antara belajar, beribadah, dan bekerja merupakan proses keterpaduan dalam melaksanakan hakekat hidup manusia yang sudah diamalkan oleh santri”. Perlu dibedakan antara kultur pesantren dengan pesantren kultural. Kultur pesantren adalah kultur atau budaya yang eksis sebagaimana adanya dan terjadi di suatu pesantren tertentu berdasarkan khas nilai-nilai keislaman, yaitu yang berlandaskan ajaran Islam. Sedangkan pesantren kultural adalah kehidupan pesantren yang lebih menitikberatkan atau mengedepankan kultur atau budaya sehingga pesantren itu eksis dalam menjalankan fungsi dan perannya. Apabila meninjau pendapat di atas maka secara eksplisit pesantren itu merupa kan lembaga yang berperan serta dalam aspek kebudayaan di masyarakat, yaitu dalam membentuk dan memberikan corak serta nilai kehidupan kepada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kultur pesantren menurut pendapat di atas lebih menekankan kepada iklim yang senantiasa bersifat religious keislaman. Pendapat tersebut memang benar karena dalam pesantren terdapat budaya yang melekat (inhern). Biasanya budaya yang dikembangkannya berbeda-beda sesuai dengan latar belakang historisnya, kondisi masyarakat setempat, dan dengan faktor kedekatannya dengan budaya masyarakat, misalnya antara pesantren di daerah Sunda memiliki kultur dan tradisi yang berbeda dengan pesantren di daerah Jawa. Walaupun demikian setiap pesantren memiliki kesamaan khas kultural, yaitu terdapat pewarisan nilai-nilai lama yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. D. Tinjauan tentang Kiai 1. Pengertian Kiai Menurut Dhofier Z (2000:55) asal-usul perkataan Kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: a. b. c. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; umpamanya, “Kiai garuda kencana” dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di keratin. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahun Islamnya). Adapun penggolongan pengertian kiai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Perlu ditekankan di sini bahwa ahli-ahli pengetahuan Islam di kalangan umat Islam disebut ulama. Di Jawa Barat mereka disebut ajengan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ulama yang memimpin pesantren disebut Kiai. Namun di zaman sekarang banyak ulama yang cukup berpengaruh di masyarakat mendapat gelar Kiai juga walaupun mereka tidak memimpin pesantren. Gelar kiai biasanya dipakai untuk menunjuk para ulama dari kelompok Islam tradisional. Pendapat lain tentang definisi kiai dikemukakan oleh Turmudi, bahwa Kiai adalah orang yang diyakini penduduk desa mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Hal ini karena kiai adalah orang suci yang dianugerahi berkah. 2. Kategori Kiai Kiai dalam menjalankan perannya sebagai pengembang agama Islam dapat dikategorikan menjadi beberapa macam diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Turmudi E (2004:32) ada beberapa kategori kiai, yaitu Kiai pesantren, Kiai tarekat, Kiai politik, dan Kiai panggung sesuai dengan kegiatan-kegiatan khusus mereka dalam pengembangan Islam. Kemudian Turmudi E (2004:32) mengungkapkan lebih lanjut tentang kategori kiai, bahwa dari empat kategori tersebut kekiaian dapat dibagi menjadi dua kategori yang lebih besar dalam kaitannya dengan para pengikutnya. Kategori pertama adalah kiai yang mempunyai pengikut yang lebih banyak dan pengaruh yang lebih luas daripada kiai yang masuk kategori kedua. Pengaruh kiai yang masuk kategori pertama menyebar ke seluruh daerah. Kategori yang pertama ini terdiri dari kiai pesantren dan kiai tarekat. Kiai pesantren memusatkan perhatiannya pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pendidikan. Hubungan antara santri dengan kiai menyebabkan keluarga santri secara tidak langsung menjadi pengikut sang kiai. Ketika orangtua mengirimkan anak-anaknya kepada seorang kiai maka secara tidak langsung mereka juga mengakui bahwa kiai itu adalah orang yang patut untuk diikuti dan seorang pelajar yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan Islam. Santri adalah sumber pendukung lain bagi kiai pesantren. Santri tidak saja penting bagi eksistensi pesantren tetapi juga menjadi sumber yang menjamin eksistensinya di masa mendatang. Selain itu santri adalah sumber jaringan yang menghubungkan satu pesantren dengan pesantren lainnya. Mereka yang menyelesaikan pendidikan di suatu pesantren dan kemudian menjadi kiai maka mereka juga membangun jaringan yang menghubungkan antara mereka dengan kiai pesantren di mana mereka nyantri atau dengan penggantinya yang melanjutkan kepemimpinan di pesantren. Kiai tarekat memusatkan kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam. Tarekat adalah sebuah lembaga formal dan para pengikut kiai tarekat merupakan anggota formal gerakan tarekat. Jumlah pengikut ini bisa lebih banyak daripada pengikut kiai pesantren karena melalui cabang-cabang di berbagai kota di Indonesia para anggota tarekat secara otomatis menjadi pengikut kiai tarekat. Kategori kedua terdiri dari kiai panggung dan kiai politik. Kiai panggung adalah para dai. Mereka menyebarkan dan mengembangkan Islam melalui kegiatan dakwah. Seorang kiai panggung mempunyai pengikut dari berbagai daerah namun demikian hal itu jarang terjadi karena hanya kiai panggung yang popular saja yang biasa diundang memberikan ceramah di daerah lain. Kebanyakan kiai panggung bersifat local dalam arti hanya dikenal oleh umat Islam di daerahnya saja. Sementara itu kiai politik lebih merupakan kategori campuran. Ia merujuk pada kiai yang mempunyai concern untuk mengembangkan aliran Islam secara politis. 3. Peran Kiai Ciri budaya pesantren yang bersifat komunal menempatkan figur kiai sebagai pencetus gagasan dan penjaga tradisi keagamaan. Karena itu, Gertz menyebut kiai sebagai cultural broker yang berfungsi menyampaikan informasi-informasi baru dari lingkungan yang dianggap baik dan membuang informasi-informasi yang dianggap kurang baik atau menyesatkan komunitas pesantren. Sukamto (1996:6) memaparkan tentang peran kiai, bahwa berdasarkan penelitian Horikhosi, kiai adalah figur yang berperan sebagai penyaring informasi dalam memacu perubahan di dalam pondok pesantren dan sekitarnya. Peran dalam kedudukan kiai di atas adalah pemegang pesantren yang menawarkan agenda perubahan sosial keagamaan, baik yang menyangkut masalah interpretasi agama dalam kehidupan sosial maupun perilaku keagamaan santri yang kemudian menjadi rujukan masyarakat. Selain peran kiai yang telah disebutkan di atas, Sukamto (1999:7) juga memaparkan peran kiai yang lain, yaitu “Kiai berperan dalam melakukan sosialisasi budaya baru melalui berbagai kegiatan dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada. Karena itu penerimaan budaya baru sangat bergantung atas keberhasilan kiai dalam melakukan akulturasi budaya”. Penelitian Jackson berkaitan dengan fungsi tokoh masyarakat atau kewibawaan tradisional seorang tokoh dalam mendominasi aktivitas politik masyarakat, di mana keikutsertaan masyarakat dalam politik disebabkan oleh pengaruh posisi tokoh tradisional yang senantiasa dipatuhi orang-orang Sunda. Peranan tokoh tradisional sangat besar dalam mempengaruhi komunitas Sunda untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap penjajah. Kekuatan hubungan kewibawaan tradisional dalam kehidupan masyarakat dibuktikan oleh adanya kepatuhan dan keikutsertaan masyarakat di bidang politik sesuai dengan pilihan politik yang ditentukan oleh kalangan orangtua atau tokoh masyarakat. Jackson mengklasifikasikan bentuk hubungan masyarakat, di satu sisi sebagian kelompok masyarakat menduduki status sosial yang tinggi atau superior, terdiri atas tokoh masyarakat informal maupun formal, para orangtua, dan sesepuh desa. Kelompok ini menjadi panutan masyarakat dan menentukan corak kehidupan masyarakat desa. Di sisi lain, kelompok yang jumlahnya lebih besar terdiri atas anggota masyarakat secara keseluruhan dan kalangan muda yang menduduki posisi status sosial lebih rendah atau subordinat. Afiliasi pilihan politik kelas subordinat ditentukan dan mengikuti kelas superior. Ikatan-ikatan sosial yang terjalin dalam komunitas membentuk suatu pengaruh kewibawaan tradisional dengan kehidupan sosial politik masyarakat. Para kiai membentuk jaringan kerja sampai tingkat desa dalam melakukan transformasi keagamaan. Karena itu para pemimpin formal yang terdiri dari kepala desa dam pamong desa hampir semua merupakan kepanjangan dari peranan kiai atau ulama dan pengaruh kepala desa tidak terlepas dari pengaruh kiai. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukamto (1999:9) tentang fungsi kiai, yaitu “Fungsi kiai tidak hanya sebagai ahli ilmu keagamaan yang sikap dan tindakannya dijadikan rujukan masyarakat melainkan juga menjadi pimpinan masyarakat yang sering kali dimintai pertimbangan dalam menjaga stabilitas keamanan desa”. Kiai khususnya yang memimpin pesantren mempunyai posisi yang lebih terhormat. Hal ini telah menjadikannya sebagai pemimpin dalam masyarakat dan kepemimpinannya juga tidak terbatas pada wilayah agama tetapi meluas pada wilayah politik. Keberhasilannya dalam peran-peran kepemimpinan ini menjadikannya semakin kelihatan sebagai orang berpengaruh yang dengan mudah dapat menggerakkan aksi sosial. Oleh karena itu kiai telah lama menjadi elit yang sangat kuat. Hukum agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan tetapi juga hampir semua hubungan sosial dan personal sehingga dengan demikian memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada para kiai dalam masyarakat. Masyarakat mempercayakan kepada kiai bimbingan dan keputusan-keputusan tentang hak milik, perkawinan, perceraian, warisan dan sebagainya, itulah sebabnya pengaruh mereka sangat kuat. Dibarengi dengan sikap enggan mereka terhadap urusan-urusan kenegaraan maka pengaruh mereka yang sangat besar itu memberikan pula kekuasaan moral yang luar biasa dan mempersembahkan kepada mereka kedudukan sebagai suatu kelompok intelektual yang menonjol. Para kiai yang memimpin pesantren besar telah berhasil memperluas pengaruh mereka di seluruh wilayah negara dan sebagai hasilnya mereka diterima sebagai bagian dari elite nasional. Sejak Indonesia merdeka banyak diantara mereka yang diangkat menjadi menteri, anggota parlemen, duta besar, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan. 4. Tipe Kepemimpinan Kiai Kepemimpinan kiai sering diidentikan dengan sebutan kepemimpinan kharismatik sekalipun telah lahir pemetaan kedudukan dan fungsi dalam struktur organisasi pondok pesantren. Berkaitan dengan figure kharismatik ini, Sartono Kartodirjo (1999:21) yang dikutip oleh Sukamto mengatakan bahwa “Kiai-kiai pondok pesantren dulu dan sekarang merupakan sosok penting yang dapat membentuk kehidupan sosial cultural dan keagamaan warga muslim Indonesia”. Pengaruh kiai sendiri terhadap kehidupan santri tidak terbatas pada saat santri masih di pondok pesantren saja melainkan juga pengaruh itu tetap berlaku dalam kurun waktu yang panjang bahkan seumur hidup. Mendefinisikan kepemimpinan sebagai usaha untuk mengarahkan perilaku orang lain guna mencapai tujuan mempunyai makna bahwa kepemimpinan memerankan fungsi penting sebagai pelopor dalam menetapkan struktur kelompok, keadaan kelompok, ideologi kelompok, pola dan kegiatan kelompoknya. Sukamto (1999:22-24) membagi kepemimpinan menjadi tiga cara pandang yang berbeda, yaitu: “Pertama, kepemimpinan dapat dipandang sebagai kemampuan yang melekat dalam diri individu atas orang-perorangan. Kedua, bentuk kepemimpinan terletak bukan pada diri kekuasaan individu melainkan dalam jabatan atau status yang dipegang individu. Ketiga, kepemimpinan bersumber pada kepercayaan yang telah mapan terhadap kesakralan tradisi kuno”. Untuk lebih jelasnya tentang kepemimpinan di atas dipaparkan di bawah ini: Pertama, kepemimpinan dapat dipandang sebagai kemampuan yang melekat dalam diri individu atas orang-perorangan. Hal ini berarti aspek tertentu dari seseorang telah memberikan suatu “penampilan berkuasa” dan menyebabkan orang lain menerima perintahnya sebagai sesuatu yang harus diikuti (sang individu dianggap mendapat anugerah kekuasaan luar biasa). Individu yang memiliki kekuasaan tersebut diyakini mendapat bimbingan wahyu, memiliki kualitas yang sacral dan menghimpun massa dari masyarakat kebanyakan. Menurut Max Weber, kepemimpinan yang bersumber dari kekuasaan luar biasa disebut kepemimpinan charisma atau charismatic authority. Kepemimpinan jenis ini didasarkan pada identifikasi psikologis seseorang dengan orang lain. Makna identifikasi adalah keterlibatan emosional seorang individu dengan individu lain yang akhirnya nasib orang itu berkaitan dengan nasib orang lain. Bagi para pengikut, pimpinan adalah harapan untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Dia adalah penyelamat dan pelindung. Kedua, bentuk kepemimpinan terletak bukan pada diri kekuasaan individu melainkan dalam jabatan atau status yang dipegang individu. Menurut Max Weber kekuasaan yang bersandar pada tata urutan disebut legal authority. Otoritas legal diwujudkan dalam organisasi birokratis, tanggungjawab pemimpin dalam mengendalikan organisasi tidak ditentukan oleh penampilan kepribadian dari individu melainkan dari prosedur aturan yang telah disepakati. Unsur-unsur emosional dikesampingkan dan diganti unsur rasional. Ketiga, kepemimpinan bersumber pada kepercayaan yang telah mapan terhadap kesakralan tradisi kuno. Kedudukan pemimpin ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang lama dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam menjalankan berbagai tradisi. Kepemimpinan kharismatik didasarkan pada kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seseorang sebagai pribadi. Pengertian ini sangat ideologis karena untuk mengidentifikasi daya tarik pribadi yang melekat pada diri seseorang harus dengan menggunakan asumsi bahwa kemantapan dan kualitas kepribadian yang dimiliki adalah merupakan anugerah Tuhan. 5. Tradisi Hubungan Kiai-Santri Kharisma yang dimiliki oleh para kiai menyebabkan mereka menduduki posisi kepemimpinan dalam lingkungannya. Selain sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat desa, kiai juga memimpin sebuah pondok pesantren tempat di mana ia tinggal. Di lingkungan pondok pesantren inilah kiai tidak saja diakui sebagai guru pengajar pengetahuan agama tetapi juga dianggap oleh santri sebagai seorang bapak atau orangtuanya sendiri. Sebagai seorang bapak yang luas jangkauan pengaruhnya kepada semua santri menempatkan kiai sebagai seorang yang disegani, dihormati, dipatuhi, dan menjadi sumber petunjuk ilmu pengetahuan bagi santri. Kedudukan kiai seperti itu sesungguhnya merupakan patron, tempat bergantung para santri. Hubungan santri dan kiai apalagi dilandasi dengan pembenaran ajaran agama, seperti hubungan murid-guru di lingkungan tarekat. Karena kewibawaan kiai, seorang murid tidak pernah (enggan) membantah apa yang dilakukan kiai. Kedudukan santri sebagai client bagi dirinya. Lajimnya kiai sebagai patron tidak saja terbatas pada kehidupan santri tetapi juga warga masyarakat sekitarnya dan para orangtua santri. Keampuhan kiai selain ilmu agama juga mahir dalam pengobatan, mempunyai kesaktian atau hal-hal lain yang dianggap luar biasa sering memperkuat kedudukannya sebagai patron dalam masyarakatnya. Hubungan pemimpin dan yang dipimpin dalam orientasi budaya seperti itu setidaknya melahirkan hubungan kepemimpinan model patron-client relationship. Secara definitive, James C. Scoot yang dikutip Sukamto (1999:78) menjelaskan hubungan patron-client sebagai berikut: “Hubungan timbal balik diantara dua orang dapat diartikan sebagai sebuah kasus khusus yang melibatkan perkawanan secara luas, di mana individu yang satu memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan-keuntungan kepada individu lain yang memiliki status lebih rendah (klien). Dalam hal ini klien mempunyai kewajiban membalas dengan memberikan dukungan dan bantuan secara umum termasuk pelayanan-pelayanan pribadi kepada patron. Merujuk pada penjelasan Scoot di atas, peran patron dalam kehidupan kepemimpinan di pondok pesantren dijalankan oleh kiai atau keluarga kiai. Seperti diungkapkan Dhofier, bahwa kiai merupakan patron karena memiliki otoritas dan kekuasaan mutlak dalam mewarnai lembaga pondok pesantren. Tak satu pun melawan kiai apalagi santri di lingkungan pesantren, kecuali kiai yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar. Dengan sumber-sumber kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki berarti kiai secara normative ditempatkan dalam status paling tinggi dari unsur-unsur lain yang ada di lingkungan pondok pesantren. Dari penjelasan ini tampak bahwa hubungan kiai sebagai patron dengan santri sebagai klien diperkuat oleh sistem nilai yang melembaga, yaitu tradisi sami’na wa’atho’na (mendengar dan menaati). 6. Unsur-unsur Patron Klien a. Kiai Kiai adalah orang yang memiliki lembaga pondok pesantren dan menguasai pengetahuan agama serta secara konsisten menjalankan ajaran-ajaran agama. b. Santri Istilah santri ditujukan kepada orang yang sedang menuntun pengetahuan agama di pondok pesantren. Para santri menuntut pengetahuan agama kepada para kiai dan mereka bertempat tinggal di pondok pesantren. Karena posisi santri seperti ini maka kedudukan dalam komunitas pesantren menempati status sosial subordinat sedangkan kiai menempati posisi superdinat. Menurut Zamakshari D yang dikutip oleh Sukamto (1999:102), istilah santri terbagi menjadi dua pengertian yang berbeda, yaitu santri mukim dan santri kalong. Pengertian secara lughowi, mukim adalah orang yang bertempat tinggal di suatu tempat. Istilah ini kemudian berkembang menjadi istilah santri mukim, yaitu santri yang menetap di pondok pesantren dalam kurun waktu yang relative lama dan berasal dari daerah jauh. Sedangkan istilah santri kalong mempunyai arti bahwa santri yang bersangkutan tidak menetap di pondok pesantren. Mereka pergi ke pondok pesantren dan pulang ke rumah dalam sehari dan begitu pula pada hari-hari berikutnya mereka tidak menginap di pondok. Disebut kalong karena mereka diibaratkan seperti binatang kelelawar yang pada waktu siang hari tinggal di sarang dan pada malam hari mereka mencari makan. c. Khadam Istilah khadam mempunyai arti sikap rendah diri seorang ulama akan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Hubungan khadam dan kiai bersifat vertical. Kedudukan kiai berada di posisi atas dan khadam berada di posisi bawah. Hubungan keduanya dapat diibaratkan sebagai majikan dengan buruh meskipun berbeda karakter. d. Guru/Ustadz Istilah ustadz lebih khusus lagi berlaku di pesantren dengan sebutan sebagai ahli ilmu agama yang dipercaya kiai. Mereka membantu para santri dalam memahami kitab dan membaca Al-Qur’an secara benar. Ustadz adalah wakil kiai dalam mengajarkan pebgetahuan agama di pondok pesantren bila kiai tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya. Berikut ilustrasi tentang hubungan antar unsur-unsur pendukung kekuasaan kiai dalam mengembangkan ikatan-ikatan sosial budaya. Gambar 2.2 : Ilustrasi tentang hubungan antar unsur-unsur pendukung kekuasaan kiai dalam mengembangkan ikatan-ikatan sosial budaya KIAI SANTRI KHADAM GURU / USTADZ Kesimpulan yang dapat ditarik dari sketsa ini adalah bahwa kiai memiliki tiga unsur pendukung kekuasaan yang selalu dipertahankan di pondok pesantren, yaitu santri, khadam, dan ustadz. Santri merupakan unsur dalam komunitas pesantren karena selain jumlahnya besar juga sebutan santri dirujuk dari istilah pesantren. Kiai dapat menyampaikan perintahperintah secara langsung berupa fatwa, pengajian, wejangan, dan pengumuman tertulis kepada ketiga unsure tanpa ada hambatan. Di pondok pesantren hanya kiai yang memiliki posisi yang tertinggi. Kiai adalah sumber pengetahuan agama, santri memperoleh pengetahuan dari kegiatan mengaji atau melihat perilaku keagamaan sehari-hari dalam kehidupan pondok pesantren. Dalam melestarikan tradisi-tradisi kepercayaan, kiai mempercayakan ustadz menjadi wakilnya untuk melakukan transformasi pengetahuan. Seorang ustadz pada awalnya mentransfer ilmu-ilmu keagamaan dari kiai dan kemudian menyampaikannya kepada santri. Proses transformasi pengetahuan dan perilaku keagamaan ini memakan waktu yang cukup lama sehingga akhirnya membentuk tradisi keilmuan pondok pesantren. 7. Hubungan Kiai-Masyarakat Hubungan kiai dengan masyarakatnya diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Kharisma yang menyertai aksi-aksi kiai juga menjadikan hubungan penuh emosi. Alasan tersebut didukung oleh pendapat cf Horiskoshi yang dikutip oleh Turmudi E (2004:97) yang menyatakan bahwa: “Karena kiai telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah-masalah mereka yang tidak hanya terbatas pada masalah spiritual tetapi juga mencakup aspek kehidupan yang lebih luas, maka para penduduk juga menganggap kiai sebagai pemimpin dan wakil mereka dalam sistem nasional”. Keberhasilannya dalam menunjukkan peran penting tersebut diungkapkan oleh Geertz (1962:238) yang menyatakan sebagai berikut: “….mengarah secara hampir tak terelakan pada penempatannya tidak hanya sebagai seorang mediator hukum dan doktrin Islam, tetapi juga sebagai kekuatan suci itu sendiri”. Di bawah kondisi-kondisi seperti ini, kiai di Jawa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat dan memainkan peran krusial dalam menggerakkan aksi-aksi sosial dan bahkan politik. Posisi dan peran pentingnya juga tidak hanya terbatas pada masyarakat di bawah saja, seperti dapat dilihat dalam NU khususnya ketika ia merupakan organisasi politik yang mempunyai berbagai macam anggota termasuk para intelektual dan politisi professional. Hal ini senada dengan pendapat Samson (1978:201) yang menyatakan, bahwa “Persetujuan kiai dapat menjamin dukungan masyarakat pada sebuah partai politik karena kiai pada umumnya diyakini sejak lama menggunakan kekuasaan secara sah karena mereka melakukannya demi Tuhan”. Hubungan antara kiai dengan masyarakat mirip dengan hubungan antara ulama atau orang suci dalam masyarakat dunia Islam lain. Kemiripan ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa umat Islam sama-sama menerima konsep dan pengalaman keagamaan yang menciptakan gaya kepemimpinan yang sama. Gagasan yang mempengaruhi terbentuknya pola-pola ini ditemukan dalam ajaran Islam. Posisi terhormat kiai pada dasarnya berasal dari fatwa bahwa Islam menekankan pentingnya pengetahuan yang harus dikejar oleh semua umat Islam. Dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits selalu ditekankan bahwa mencari ilmu adalah bagian penting dari kehidupan umat Islam dan bahwa seorang muslim yang berpengetahuan mempunyai status yang lebih tinggi di hadapan Alloh SWT. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa konsep ini mendorong umat Islam untuk mencari pengetahuan. Oleh karenanya memiliki keingintahuan akademik menjadi bagian dari kewajiban seorang muslim dan mereka yang berhasil memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan itu akan dihargai oleh masyarakat. Pandangan ini melahirkan sebuah budaya yang menghargai ulama karena ia adalah orang yang memperoleh pengetahuan seperti itu. 8. Hubungan Kiai-Penguasa Baik kiai maupun pemerintah mempunyai kekuasaan dalam hubungannya dengan masyarakat. Mereka menggunakan kekuasaannya ini untuk saling menawar dan mendapat keuntungan. Dari perspektif pemerintah, kekuasaan kiai cukup kuat untuk mempengaruhi tindakan sosial politik masyarakat. Hal ini karena mereka menduduki posisi sebagai legitimator keagamaan dan umat Islam seperti di Indonesia membutuhkan legitimasi kiai untuk melakukan hal-hal duniawi mereka. Pandangan kiai dan pemerintah yang berbeda sering kali menyulut situasi dimana hubungan mereka ditandai oleh disharmonisasi dan bahkan ketegangan. Di Indonesia ketegangan ini biasanya terjadi karena pemerintah membutuhkan kiai untuk memperoleh dukungan politik dari umat Islam. Selain itu pemerintah juga memerlukan legitimasi kiai atas kebijakan-kebijakannya yang bersentuhan dengan persoalan agama. Para kiai telah memegang posisi penting sejak kedatangan Islam di Indonesia. Sejak pembentukan kerajaan Islam pada masa-masa awal Indonesia, beberapa kiai terkenal sudah terlibat dalam masalah-masalah pemerintahan. Namun demikian hubungan antara kiai dan pemerintah Indonesia mengalami fluktualisasi. Pandangan-pandangan yang mendasari hubungan ini kebanyakan berasal dari ulama salaf. Bagi kebanyakan dari mereka bergabung dengan pemerintah selalu dipandang secara negative. Pada saat itu ada pandangan umum bahwa menjadi bagian dari pemerintah adalah tidak baik karena jika ini terjadi orang akan masuk pada hal-hal secara agama kurang bisa diterima. Meski demikian, garis antara ‘dapat diterima’ dan ‘tidak dapat diterima’ tidak ditetapkan secara jelas. Akibatnya kiai manapun yang benar-benar mendekati pemerintah akan menjadi sasaran gosip dan cemooh sebagai kiai keceng. Oleh karena hubungan antara kiai dan masyarakat telah lama terlembagakan melalui norma-norma patron klien, pemerintah menyadari posisi kiai yang begitu menentukan dalam mempengaruhi tidakan sosial politik masyarakat serta dalam membimbing mereka untuk menerima langkah-langkah tertentu. Pemerintah lantas coba memasukkan kiai dalam mesinnya dengan mendirikan sebuah lembaga formal yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari tingkat Kecamatan hingga tingkat nasional. Tujuan awal lembaga ini adalah untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah di satu sisi dengan umat Islam di sisi lain. Akan tetapi secara praktis lembaga ini sering dikritik karena menjadi alat pemerintah untuk melegitimasi program-programnya. Namun demikian hanya sejumlah kecil saja kiai yang mau direkrut ke dalam badan milik pemerintah ini, mayoritas mereka bersikap independen. E. Pesantren dan Pendidikan Politik Pendidikan politik di Indonesia secara edukatif merupakan upaya yang sistematis untuk memantapkan kesadaran politik dan bernegara untuk menjaga kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Jadi, pendidikan politik disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta yang menjadi landasan moral bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasai Muda sebagai berikut: Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya bangsa. Perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai-nilai tertentu yang secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu. Dalam hal ini Affandi (1993:3) menyatakan pendapatnya “Pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, yakni sebagai proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dari konsep dirinya”. Proses internalisasi nilai-nilai ini menjadi kekuatan pendidikan politik yang memberi makna bahwa pendidikan dan politik itu saling bertautan. Salah satu tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia adalah budaya politik Islam. Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada suatu keyakinan dan nilai agama tertentu, dalam hal ini tentu saja agama Islam. Agama Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas dan Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Islam menjadi salah satu budaya politik yang cukup mewarnai kebudayaan politik di Indonesia. Orientasi politik yang mendasarkan pada nilai agama Islam mulai tampak sejak para pendiri bangsa membangun negeri ini. Politik budaya Islam biasanya dipelopori oleh salah satu kelompok masyarakat yang biasa disebut sebagai kelompok santri. Kelompok santri adalah kelompok kelompok masyarakat yang identik dengan pendidikan pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Kelompok masyarakat ini, dapat kita klasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Kelompok tradisional biasanya diwakili oleh masyarakat santri yang berasal dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Sementara yang modern biasanya diwakili oleh masyarakat santri yang berasal dari organisasi Muhammadiyah. Perbedaan karakter Islam ini juga turut melahirkan perbedaan pilihan politik. Ini membuat budaya politik Islam menjadi tidak satu warna. Pada masa lalu, kelompok santri biasanya berafiliansi pada partai seperti Masyumi dan partai NU. Kedua partai ini memiliki basis pada kelompok masyarakat Islam. Pendidikan politik harus diajarkan secara komprehensif di lingkungan pesantren. Pendidikan kewarganegaraan yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban warga negara harus kembali diajarkan sehingga proses demokrasi yang dilangsungkan benar-benar menjadi ajang pembelajaran, bukan pembodohan terhadap rakyat. Kalangan pesantren, selain mengajarkan ilmu politik melalui Adab al-Dunya wa al-Din dan Ahkam al-Sulthaniyya, juga perlu memahami secara baik ilmu politik Barat yang dianut Indonesia. Pesantren sangat perlu melakukan kajian kritis atas pasang surutnya politik pada era daulat-daulat Islam, terutama Muawiyah dan Abbasiyah. Santri dapat mengkaji bagaimana ilmu pengetahuan bisa mencapai puncaknya berkat suksesnya kepemimpinan politik dua dinasti itu. Sebaliknya, santri akan mengerti pula bagaimana puncak-puncak peradaban itu hancur oleh ambisi-ambisi kekuasaan. Dari kajian ilmu politik ini akan diketahui bahwa batas antara agama dan politik sangatlah tipis. Dengan begitu, santri akan mampu mengkritisi klaim-klaim keagamaan (keislaman) yang dijual para politisi mutakhir. Dengan pendidikan politik yang terstruktur itu, pesantren sejak awal bisa membagibagi peran. Kepada santri yang berniat menjadi politisi, pesantren membekalinya dengan etika berpolitik. Sementara santri yang memilih jalur keilmuan bisa memahami permainan dunia politik sehingga tidak mudah diperdaya oleh broker politik. Kepada santri yang ingin berdagang, pesantren bisa mengajarkan kiat-kiat bisnis serta aturan, hukum, dan perundangan di dunia bisnis saat ini. Dari praktik dagang Nabi Muhammad SAW, kejujurannya itulah yang patut diteladani. Adapun untuk terjun di dunia bisnis mutakhir, santri harus berbekal ilmu ekonomi mutakhir pula. Mengubah kurikulum, menambah atau mengurangi bukan perkara mudah. Di sekolah formal, hal itu berkaitan dengan proses birokrasi yang berbelit. Sementara di pesantren, problemnya adalah tantangan untuk merombak konvensi, wasiat, dan tradisi yang sudah terlanjur disakralkan. Dibandingkan dengan sekolah formal, pesantren mempunyai peluang yang lebih terbuka. Untuk memasukkan mata pelajaran ilmu politik, pesantren hanya memerlukan izin ajengan atau dewan ustadz. Pilihan pada ilmu politik ini karena real life saat ini menuntut kalangan pesantren untuk segera melek politik agar tidak selalu menjadi bulanbulanan permainan para politisi. Untuk mewujudkan pendidikan ilmu politik itu, ada beberapa tahap yang dapat dilalui kalangan pesantren. Pertama, sharing (membagi) gagasan antarpengasuh pesantren yang sudah terorganisasi dalam asosiasi pesantren. Pesantren saat ini terkotak dalam berbagai organisasi sesuai dengan afiliasi organisasi massa, partai politik, atau aliran Islam yang dianutnya. Dari sharing awal ini akan dihasilkan beberapa rancangan, yaitu materi (kurikulum), pengajar, dana belajar-mengajar, jenjang usia santri, termasuk dampak yang akan timbul akibat penerapan pelajaran baru ini. Kedua, para pengasuh yang sudah sepakat itu mengadakan pertemuan. Mereka membawakan bahan (kertas kerja) yang dipresentasikan dalam forum sesuai dengan sudut pandang yang disepakati sebelumnya. Sebagai pembanding, bisa dihadirkan pakar ilmu politik dan politisi yang dianggap kapabel serta kredibel. Dalam forum ini, rancangan dalam sharing gagasan dimatangkan sampai siap untuk diaplikasikan. Ketiga, memilih satu-dua pesantren sebagai proyek rintisan. Menilik kemampuan sarana dan prasarana yang dimiliki, tidak mungkin menerapkan kurikulum itu secara langsung di semua pesantren yang mengikuti pertemuan. Ke pesantren terpilih inilah secara periodik pesantren lainnya mengirimkan santri untuk belajar ilmu politik. Maka dengan adanya pembelajaran ilmu politik ini pesantren secara sadar memandang perlunya santri mengerti dunia politik. Dengan pilihan itu, pesantren membuktikan diri tidak setengah-setengah dalam membimbing santri. Santri diberi wawasan seluas-luasnya dalam berbagai bidang kajian. Trauma masa lalu biarlah berlalu seiring dengan perjalanan waktu. Sebab, jika membiarkan santri sekadar menjadi bobotoh partai politik atau politisi tertentu, hal itu akan menghasilkan sejarah yang lebih pahit lagi. Dengan inovasi ini, tidak berlebihan jika pesantren di masa depan diprediksikan akan sangat menentukan kehidupan di tengah masyarakat. F. Pengembangan Budaya Politik Pesantren Pada dasarnya kondisi kehidupan yang dibentuk atau terjadi dalam suatu komunitas masyarakat tentunya diwarnai budaya-budaya yang sudah ada. Budaya melalui kompleksitas nilai-nilainya akan bersentuhan, baik dengan individu maupun dengan kelompok. Begitu juga sebaliknya kondisi dan situasi baru dalam masyarakat bisa juga memberikan corak dan warna bagi kebudayaan yang sudah ada sehingga muncul budaya baru. Kondisi demikian merupakan dinamika cultural dalam masyarakat sebagai konsekuensi tarik ulurnya faktor manusia sebagai pelaku budaya dengan aspek-aspek kehidupannya, termasuk di dalamnya aspek religi, ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Pembahasan tentang pengembangan budaya politik pesantren tentunya harus ditinjau dari perkembangan masyarakat pesantren itu sendiri. Antara politik-lembaga politik dengan masyarakat. Perkembangan masyarakat erat kaitannya dengan bagaimana konsepsi pemikiran dan perilakunya yang ditunjukkan dalam politik. Dilihat dari tingkah laku atau perilaku politik masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh David E. Apter (1996:210), bahwa: “Perhatian utama paham tingkah laku terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa-peristiwa politik. Kategori-kategori pemikiran seperti itu biasanya dianggap sebagai ideologi atau sistem kepercayaan yang menciptakan pola-pola tingkah laku yang penuh makna”…. Pendekatan behavioral memperhitungkan factor-faktor sosialisasi, cara kita menginternalisir nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berlaku, cara perubahan-perubahan pandangan yang terjadi”. Berdasarkan pendapat tersebut, penekanan utama adanya perkembangan budaya politik masyarakat pesantren tentunya harus ditinjau dari sistem kepercayaan atau keyakinan (ideologi) masyarakat itu sendiri dan kaitannya dengan perilaku politiknya. Sistem keyakinan politik tentunya memiliki kaitan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Karena itu dalam penguatan politik termasuk lembaga politik di dalamnya harus dipertimbangkan pula kekuatan sosial yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Samuel P. Huntington (2003:12), bahwa: “Dalam praktek perbedaan antara suatu lembaga politik dengan kekuatan sosial bukan merupakan perbedaan yang tegas. Banyak kelompok dapat menggabungkan beberapa ciri khas kedua bentuk tersebut. Namun bagaimana pun secara teoritis perbedaan antara kedua kelompok itu cukup jelas. Semua orang yang melibatkan diri di dalam suatu tindakan politik dapat diasumsikan bahwa mereka adalah juga anggota berbagai kelompok sosial. Tingkat pembangunan politik yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat sebagian besar tergantung dari sejauh mana orang-orang yang aktif berkecimpung di bidang politik itu termasuk juga di dalam mengidentifikasikan dirinya dengan berbagai lembaga politik”. Ditinjau dari arah pengembangan budaya politik pesantren, memang pesantren bukan merupakan lembaga politik sebagaimana dijumpai dalam struktur politik. Tetapi bagaimanapun dalam kaitannya dengan politik kenegaraan, tentunya pesantren itu tidak mungkin dapat menarik diri dari dinamika politik yang terjadi. Dengan demikian adanya preseden bahwa pesantren sebagai lembaga non-politik atau memiliki kiprah secara aktif di bidang politik pun termasuk satu bukti bahwa pesantren dengan independensinya yang otonom harus mampu mengimbangi dinamika masyarakat, terutama dalam bidang politik yang sedang dan akan terjadi. Secara historis pesantren telah memberikan peranan sangat berarti bagi proses pendewasaan berpikir masyarakat, bahkan menjadi garda terdepan dalam menentang sistem kolonialisme di Indonesia. Ketika penjajahan terjadi, solidaritas kalangan penduduk termasuk kalangan Islam-pesantren di dalamnya telah mampu mengusir dan menghantam penjajah dan kebodohan sehingga mencapai puncak kemerdekaan. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan Manfred Ziemek (1986:188), sebagai berikut: “Berbeda dengan abad ke-18 dan 19, ketika pesantren menjadi basis revolusi politik, dimana dikorbankan semangat terhadap tekanan sosial tumbuh di kalangan penduduk pedesaan, yang menjadi bebas dalam luapan kekerasan, sudah dalam bagian pertama abad ini jawaban dari Islam politik atas penindasan colonial amat lebih rasional dan efektif. Dikonsentrasikan dalam gerakan-gerakan sosial dan politik, potensi-potensi Islam itu tidak hanya sanggup membangun dalam sistem sekolah pribumi terhadap sistem sekolah colonial, melainkan juga dalam perjuangan militer dan politik merupakan sumbangan yang menentukan untuk mencapai kemerdekaan”. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis sependapat bahwa pada dasarnya adanya gerakan-gerakan sosial dan politik Islam (pesantren) apabila dilihat dari potensi-potensi yang dimilikinya akan sangat menentukan dinamika politik yang terjadi. Interpretasi kemerdekaan di atas tidak hanya diartikan sebagai secara sempit, yaitu hanya terbebas dari kemelut penjajahan kolonialisme tetapi kemerdekaan sebenarnya, termasuk dalam mengisi kemerdekaan dewasa ini. Alasannya didasarkan pada kenyataan bahwa pesantren merupakan lembaga yang menunjukkan eksistensinya, baik sebelum kemerdekaan negara dicapai maupun setelah merdeka. Pesantren dalam kaitannya dengan kondisi kehidupan masyarakat yang terjadi, lebih lanjut menurut Manfred Ziemek (1986:188): “Bilamana pesantren ingin memelihara komponen-komponen terpenting dari identitasnya (pendidikan pemimpin masyarakat Muslim, pemeliharaan sistem nilai dan dengan demikian perkembangan selanjutnya dari tradisi Islam), haruslah diberikan jawaban baru atas pengaruh-pengaruh luar yang kuat, yang merubah kehidupan masyarakat”. Apabila penulis tinjau dari pendapat Ziemek di atas, beliau melihat kehidupan pesantren (budaya pesantren) sebagai sesuatu yang dinamis. Pendapat tersebut menempatkan “memberikan jawaban baru terhadap pengaruh luar” menunjukkan identitas pesantren dengan segala kelengkapannya komponen-komponennya itu harus mampu relevan dengan kondisi masyarakat. Walaupun demikian tentunya jangan sampai identitas pesantren ini menjadi semu atau hilang karena elasitiasnya dalam beradaptasi dengan masyarakat, tetapi tingkat elasitas itu justru menjadi fondasi dalam menciptakan budaya yang benar-benar menjadi sentral tauladan untuk masyarakat. Pesantren ditinjau dari peranan politik kemasyarakatannya, menurut Manfred Ziemek (1986:191), sebagai berikut: “Pesantren sehubungan dengan peranan politik kemasyarakatannya berada dalam tatanan hubungan yang mempunyai tiga komponen, yaitu: pesantren dan atau kyai, masyarakat dan kelembagaan negara (pemerintah daerah/lingkungan instansi negara)….dalam ikatan segitiga ini untuk membedakan tiga macam proses: proses keputusan politik, komunikasi dan pelaksanaan program. Dengan demikian dapat lebih dibedakan bidang tegangan politik di lingkungan yang untuk pengamanan selanjutnya dianggap relevan…” Kedekatan hubungan pesantren dengan masyarakat dalam peranannya di kehidupan masyarakat, lembaga pesantren ini merupakan lembaga yang sangat diperhitungkan. Dalam pola hubungannya tentunya pesantren memiliki andil besar termasuk dalam proses keputusan politik. Dilihat dari statusnya, pesantren bukan merupakan lembaga dalam infrastruktur politik, tetapi hanya sebagai suprastruktur politik yang berada di luar kelompok kepentingan atau juga kelompok penekan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pesantren itu lebih otonom dalam membangun komunikasi baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat dan lembaga lainnya. Akan tetapi permasalahannya yang berkembang di masyarakat timbulnya preseden negatif, bahwa pesantren termasuk santri di dalamnya itu seringkali dijadikan onderbouw kendaraan politik tertentu dan mudah tergiur untuk membackup kiai sebagai orang yang berpengaruh. Terlebih budaya politik yang berkembang di pesantren dianggap budaya paternalistic, yaitu sebagai politik manut atau taklid buta. Asumsi atau preseden buruk tersebut sangat kontradiktif dengan pendapat Ziemek (1986:193) yang mengemukakan, bahwa: “Berdasarkan pandangan para kyai maka pesantren membentuk dasar dan alat dari politik kemasyarakatannya. Akan tetapi para kyai tidak dapat secara mutlak atau otonom melaksanakan pengaruhnya. Mereka harus mempertimbangkan pandangan dari tokoh-tokoh pimpinan lainnya dalam pesantren dan seraya berada dalam ikatan tradisi, turut menentukan aliran politik dan pandangan duniawi. Terlebih jelas adalah perluasan proses pengambilan keputusan dalam pesantren yang didukung oleh sebuah Yayasan…. Ikatan tradisional sebagai dasar pandangan duniawi bersama dalam hal itu ditunjukkan sebagai contoh dengan mematuhi fatwa-fatwa yang diucapkan oleh para ulama yang terhormat, atau warisan rohaniah dari para kyai pendiri, yang lama setelah ia meninggal tetap menjadi inspirasi sehingga tetap langgeng dan dihormati”. Berdasarkan pendapat tersebut maka secara eksplisit disebutkan bahwa atas kyai tidak dijalankan mutlak, tetapi didasarkan pada pertimbangan para pemimpin pesantren lainnya. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Ziemek, bahwa dengan adanya tradisi yang digunakan di pesantren itu merupakan salah satu pengukur normatif yang dapat ditempuh dalam menentukan aliran politik dan pandangan terhadap kondisi duniawi. Dengan demikian keputusan santri terhadap consensus ulama atau para pemimpin pesantren bukan merupakan harga mati pandangan berikutnya tetapi hanya sebuah pelanggengan tradisi. Keadaan tersebut sama dengan yang dikemukakan Ziemek (1986:193-194), sebagai berikut: “Selanjutnya dalam hal keputusan-keputusan tentang rencana kemasyarakatan harus memperhatikan pendapat rakyat desa, demikian juga pendapat pemimpin formal dan informal. Karena kemufakatan tradisional dan sebagai hasil partisipasi sukarela dari penduduk pada pelaksanaan program hanya dapat dicapai bilamana keputusankeputusan dibuat, yang semua peserta dapat mengidentifikasikan diri dengannya”….dengan demikian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pesantren berada dalam suatu bidang tegangan antara kepentingan sendiri, tugas pendidikan keagamaan dan kecakapan untuk memobilisasi loyalitas dari penduduk pedesaan”. Berdasarkan pendapat di atas, peletak dasar adanya kesolidan yang mungkin menunjukkan warna yang sama memiliki alasan yang sangan kuat. Dalam terminology budaya politik, kondisi demikian tidak menjadi permasalahan selama masih berada dalam suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi, tugas pendidikan keagamaan, dan kecakapan untuk memobilisasi loyalitas dari penduduk pedesaan. Selain dari kajian terhadap tradisi kepatuhan santri dan masyarakat pesantren terhadap kiai yang menjadi dasar pertimbangan kita menurut penulis adalah seberapa kuat dasar rasionalitas dan emosi yang dimiliki masyarakat pesantren itu dalam menentukan sikap, cara berpikir, dan tindakan politik tersebut. Tentang kedekatan emosi atau ikatan moral yang terjadi di pesantren kaitannya dengan tindakan politik dikemukakan Jackson dan Moeliono yang dikutif Manfred Ziemek (1986:194): “Dalam penyelidikan mereka mengenai mekanisme pengaruh otoritas tradisional dalam situasi-situasi ketegangan politik di Jawa Barat, ikatan-ikatan moral dan pribadi antara pemimpin dan pengikut tradisional menentukan tingkat sosial kemasyarakatan. Ikatan sosial dan pribadi ini mengandung kewajiban moril atau hutang budi seorang anak buah yang diwajibkan terhadap bapak. Sekali terbentuk hubungan antara bapak dan anak buah mengandung arti emosional dan praktis bagi kedua belah pihak. Kewajiban moril yang diikuti oleh hutang budi dapat dimobilisasi untuk aksi politik dan malaham untuk tindak kekerasan politik walaupun hampir tanpa ada petunjuk terhadap isi ideologi dari pertentangan itu”. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis melihat bahwa interpretasi Jackson dan Moeliono di atas berkenaan dengan factor pola hubungan yang dibentuk antara kiai dengan santri. Permasalahan yang menjadi focus kajian dalam hal itu bukan tentang kekentalan atau kedekatan emosi antara kiai dengan santrinya yang diinterpretasikan Jackson dan Moeliono sebagai “hutang budi seorang anak buah yang diwajibkan terhadap bapaknya”, tetapi tentang bagaimana pola hubungan , termasuk komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apabila pola hubungan yang dilakukan cenderung searah, yaitu secara sepihak memposisikan santri sebagai yang dirugikan tentunya keseimbangan dalam sistem budaya pesantren itu belum tercapai. Artinya kepatuhan tersebut hanya didasarkan atas tradisi yang keliru dan dapat dikatakan sebagai non-ideologis, tetapi hanya merupakan cikal entropi cultural pesantren karena tidak menempatkan pesantren sebagai lembaga yang independen atau mandiri dalam eksistensi budayanya. Pendapat Ziemek juga tidak membatasi pesantren sebagai lembaga stagnan dalam kaitannya dengan kondisi sosial-kemasyarakatan. Beliau melihat pesantren itu sebagai lembaga yang dinamis. Menurut Ziemek (1986:197): “Kebanyakan pesantren termasuk tradisional yang khusu mengajarkan agama dan terutama mengarah pada para santri yang berdiam dalam pondok. Namun di sini masih terdapat proses reformasi yang luas, yang menuju pada ilmu pendidikan kemasyarakatan yang lebih kuat. Ini adalah hasil kesadaran baru yang diperluas: • Bagi peranan politik kemasyarakatan pesantren dalam masyarakat di lingkungannya; • Bagi keharusan perkembangan selanjutnya dari sistem nilai Islam dan sehubungan dengan itu pemahaman ilmu pendidikan keagamaan sebagai konsekuensi perubahan sosial budaya yang cepat; • Bagi peranan ilmu pendidikan yang berkonsentrasi kemasyarakatan, dipahami sebagai proses interaksi antara tempat pendidikan desa dengan masyarakat sekelilingnya”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa peran pesantren erat sekali dengan pendidikan yang terjadi. Dalam hal ini penulis sependapat bahwa kondisi yang tidak rigid pesantren sebagai institusi dapat dicapai apabila pola pendidikan yang dikemas menempatkan faktor kesadaran masyarakat sebagai hal yang sangat penting sehingga santri diorientasikan dan memiliki orientasi baik ke dalam pesantren itu sendiri maupun ke dalam kehidupan masyarakat di luar pesantren. Manfred Ziemek (1986:239) berpendapat, bahwa sikap dasar konservatif dan individualistis para kiai dengan interpretasi mereka yang khas mengenai masalah agama, sosial, dan politik pada mulanya menghambat kerjasama yang lebih erat dan diterimanya pembaharuan. Di lain pihak, sifat-sifat baik yang seringkali terdapat pada mereka, seperti toleransi, keterbukaan, kesediaan dalam diskusi mempertimbangkan pikiran baru, dapat menyebabkan adanya fleksibilitas. Karena itu kiai berorientasi pada nasehat tokoh-tokoh yang mereka terima sebagai yang berwenang dalam hal agama, maka pikiran baru akan relative cepat diterima jika ada seorang pemimpin terkemuka dengan memiliki charisma di bidang ini, dapat diyakinkan akan kebenaran suatu perencanaan. Loyalitas terhadap seorang kiai yang diakui sebagai senior adalah demikian besar sehingga seorang ulama yang begitu muda menuruti nasehatnya bagi suatu perintah. Dari sanalah demi kelanjutan perkembangan dan terbukanya kesempatan kegiatan pesantren, dapat terjadi efek-efek bola salju”….loyalitas agama dan politik seringkali mempercepat dalam suatu “ikatan-kiai” pembaharuan, akan tetapi di lain pihak menghambat pula komunikasi dengan warga-warga pesantren yang tidak termasuk ikatan tersebut. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Devi Andriana dalam skripsi sarjana SI-nya (2007:93-94) mengutif pendapat Abdurrahman Wahid sebagaimana dikutif Manfred Ziemek (1986:253), mengemukakan tentang masalah-masalah penting yang harus dipecahkan apabila ingin mempertahankan dan membangun peranan pesantren dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia, sebagai berikut: 1. Bagaimana pesantren menyesuaikan dirinya dengan kenyataan bahwa sistem sekolah modern tak terhindarkan dalam jangka panjang, dengan implikasiimplikasi besar bagi pesantren sendiri (hubungan antara kyai dengan santri pengembangan suatu sistem nilai yang baru dalam lingkungannya sendiri dan sebagainya). 2. Bagaimana pesantren merencanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatannya sendiri, dalam bidang pendidikan maupun pelayanan sosial, sedangkan dalam jangka jauh, memusatkan perhatian kepada pola pembiayaan sendiri di masa mendatang. 3. Bagaimana pesantren menemukan cara pemecahan dilemma dasarnya kepada kehidupannya walaupun kyai tidak tergantung kepada bantuan pemerintah, pesantren masih lebih melayani golongan berpunya daripada yang tidak berpunya, akibat ketergantungannya kepada bantuan-bantuan keuangan dari lapisan atas masyarakat pedesaan (suatu dilemma yang dikenal sebagai hal umum di lembaga-lembaga tradisional di dunia ketiga). 4. Bagaimana pesantren memahami implikasi stuktural dari peran serta rakyat dalam pengembangan masyarakat dan bagaimana pesantren menanggapi peranannya dalam proses tersebut. 5. Bagaimana pesantren merencanakan untuk membina sifat-sifat khas budaya maupun kedudukan sosio-kulturalnya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka tanggapannya tentang peranannya sendiri dalam pengembangan masyarakat. Berdasarkan pendapat Wahid di atas, Devi Andriana mengemukakan pendapatnya (2007:94-95), bahwa ia sepakat dengan argumen yang diajukan karena bagaimanapun pesantren harus mampu menunjukkan kiprahnya, baik dalam skala kehidupan pesantren itu sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat luas. Dengan demikian pesantren akan lebih menunjukkan eksistensinya sebagai tempat pendalaman ilmu-ilmu agama dan mampu berkiprah sesuai dengan keaslian karakteristiknya dalam kehidupan masyarakat. Apabila dihubungkan dengan masalah budaya berkaitan dengan pengembangan budaya pesantren, penulis sependapat dengan Andriana (2007:95), bahwa kajian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dapat difokuskan menjadi tiga prioritas. Pertama mengenai kemandirian pesantren dalam berbudaya termasuk di dalamnya memberi arah penyesuaian serta peka dengan perkembangan masyarakat dan mampu memfilterisasi terhadap budaya negatif yang masuk. Permasalahan kedua tentang kemampuan kemandirian dalam hal financial dan manajerialnya, tentunya pertimbangannya agar secara ekonomi pesantren itu memiliki potensi untuk mensejahterakan masyarakatnya atau minimal orangorang di dalam pesantren, sehingga tidak selamanya tergantung kepada bantuan pihak lain termasuk bantuan dari pemerintah. Kemudian permasalahan yang terakhir, pesantren merencanakan untuk membina sifat-sifat khas keaslian budaya Indonesia maupun dalam kedudukan sosio-kulturalnya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka tanggapannya tentang peranannya sendiri dalam pengembangan masyarakat. Berbeda dengan pendapat Wahid yang lebih melihat pesantren sebagai lembaga yang sangat potensial dalam terminology budaya atau sosio-kultural. Hasil penelitian Horikoshi lebih menyoroti tentang aspek politiknya (budaya politik) berkenaan dengan masalah kepemimpinan di pesantren. Sebagaimana dikutif oleh Manfred Ziemek (1986:194), bahwa posisi yang menentukan dari pemimpin keagamaan tradisional juga berdasarkan berbagai faktor sebagai berikut: Kekayaan di atas rata-rata dalam bentuk pemilikan tanah dan pemanfaatan tanah secara efisien yang mengikutsertakan penduduk pedesaan melalui pengupahan dan penyewaan lahan. Keunggulan intelektual, baik dalam pemanfaatan pengetahuan secular maupun keagamaan. Daya memimpin kharismatik dengan menerapkan kepintaran berpidato mereka, demikian pula memanfaatkan loyalitas moral dan keagamaan. Ikatan kekeluargaan atau hubungan keagamaan yang erat dengan keluargakeluarga pemimpin lainnya di lingkungan dan juga di tingkat wilayah. Koneksi dengan instansi pemerintah di tingkat wilayah. Mekanisme komunikasi keagamaan dan politik sendiri di tingkat wilayah. Partisipasi pada pembentukan kehendak politik sentral dengan memasuki partai Islam, pers, dan parlemen. Berdasarkan pendapat tersebut, mengenai kemampuan pemimpin tradisional tersebut selain memiliki keunggulan potensi sebagai individu dalam bidang finansial, intelektual serta spiritual tentunya sangat cerdas dalam memainkan simbol-simbol politik sesuai dengan perkembangan budaya masyarakatnya. Mengenai keunggulan yang dikemukakan di atas tidak terdapat arah atau potensi kekuasaan yang didasarkan atas kekuatan fisik atau melalui caracara pemaksaan kehendak untuk menjadi pemimpin. Karakteristik yang khas adalah tentang potensi kharismatis dan kedekatan emosi atau hubungan keagamaan dengan keluargakeluarga pemimpin lainnya. Setiap masyarakat tentunya memiliki dinamika budaya dan politiknya. Berkaitan dengan politik Islam, termasuk yang dikembangkan oleh pesantren tentunya konsepsi tentang pengembangannya tidak lepas dari bagaimana langkah setting sosiokultural yang dilakukan akan dihadapkan dengan kondisi riil sosiokultural itu sendiri. Pembangunan budaya politik pesantren erat kaitannya dengan usaha bagaimana menumbuhkan tingkat kemelekkan politik santri. Mengenai pentingnya kemelekkan politik itu sebagaimana dikemukakan oleh Idrus Affandi (1996:27). Aspek pengetahuan seseorang dapat diketahui dapat dikatakan melek politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang: Informasi dasar tentang siapa pemegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja. Bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan. Kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana memutuskan sebuah isu. Kemampuan mengenali tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika isu (masalah) terpecahkan. Kemampuan memahami pandangan orang lain dan pembenaran mereka tentang tindakannya sendiri. Untuk mengukur tinggi rendahnya kesadaran politik sangatlah sulit untuk diukur secara kuantitaf, maka salah satu jalan yang ditempuh untuk mengukur tingkat kesadaran politik tersebut yaitu dengan mengemukakan dan menggali indikator-indikator yang dapat menunjukkan kecenderungan kesadaran politik warga negara. Tentunya dalam hal ini peranan ulama dan santrinya sangat diperhitungkan dalam keterlibatannya berkaitan dengan orientasi-orientasi dan perilaku politiknya. Peran ulama dalam kehidupan dewasa ini sebagaimana dikemukakan Nanang Takik (2004:189) yang dikutif oleh Andriana (2007:101), sebagai berikut: “Dalam bahasa lain peran ini (ulama) disebut juga amar ma’ruf nahy munkar, yang rinciannya meliputi tugas untuk: (1) menyebarkan dan mempertahankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama, (2) melakukan control dalam masyarakat (social control), (3) memecahkan problem yang terjadi dalam masyarakat, dan (4) menjadi agen perubahan sosial (agent of social change)…peran tersebut teraktualisasi sepanjang sejarah Islam, meskipun bentuk dan kapasitasnya tidak selalu sama antara satu waktu dengan lainnya dan antara satu tempat dengan lainnya. Hal ini tergantung pada struktur sosial dan politik serta problem dihadapi oleh masyarakat Islam dimana ulama itu berada….” Peran ulama sebagaimana dikemukakan Nanang di atas berkaitan dengan posisinya sebagai leader baik di pesantren maupun di masyarakat sekitar pesantren itu. Peran tersebut memang harus mampu mengimbangi kondisi-kondisi yang terjadi termasuk memiliki relevansi dengan kondisi sosial dan politik serta permasalahan yang terjadi. Tentang keterlibatan ulama dalam politik, khususnya partai politik lebih lanjut dikemukakan oleh Nanang Takik (2004:199) yang dikutif oleh Andriana (2007:102), sebagai berikut: “Keterlibatan ulama dalam partai-partai politik itu dengan sendirinya menjadikan mereka ikut berkiprah dalam memenangkan partai tertentu. Memang hal ini bisa membawa dampak positif karena mereka akan dapat ikut serta memberikan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan umum. Namun hal ini juga bisa membawa dampak negatif karena mereka kemudian berupaya mempengaruhi umatnya untuk memilih partainya dengan cara bijaksana dalam sistem dan budaya demokrasi di Indonesia yang belum mapan ini, kini memang masih tampak perilaku politik yang belum dewasa, baik dilakukan oleh para tokoh maupun oleh publik”. Berdasarkan pendapat di atas, telah jelas bahwa segala sesuatunya memiliki dua sisi seperti uang koin, sisi positif dan negatif begitu pula dalam hal berpolitik. Konsepsi politik dalam Islam tidak dimaknai sebagai alat atau kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan semata apalagi diorientasikan untuk dijalankan dengan penuh kesewenang-wenangan (corrupt). Perlu diperhatikan bagaimana sistem politik itu mampu berjalan secara efektif termasuk berkaitan dalam hal budaya masyarakatnya. Kedewasaan dalam berpolitik baik dalam menentukan atau mengakomodir orientasi politik individu maupun orientasi kelompok harus mampu menjadikan lahirnya genuine will (kemauan asli) ke dalam political will atau kehendak politik bersama yang didasarkan untuk kemaslahatan umat. Kondisi demikian dapat tercapai apabila budaya yang dikembangkan di pesantren itu menciptakan kemelekan politik (political democracy) sehingga tertanam adanya penalaran, pengetahuan, pemahaman, serta internalisasi nilai moral politik demokrasi. Urgensi pendidikan politik dalam kaitannya dengan perilaku politik sebagaiman dikemukakan Kartini Kartono (1989:4) yang dikutif oleh Devi Andriana (2007:103), bahwa “pendidikan politik pada hakikatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa”. Karena itu para ulama termasuk santri diusahakan agar mempunyai kecakapan politik sehingga dapat memainkan peranan penting dalam kehidupan politik demokrasi dalam membentuk tatanan sistem politik (political system). Langkah yang ditempuh dalam hal ini adalah peningkatan pemahaman tentang budaya pesantren dan kaitannya dengan politik agar mereka menjadi insan politik yang melek atau cakap politik. Peningkatan pemahaman tersebut dapat ditempuh misalnya melalui pendidikan politik yang bertujuan agar mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemelekan politik sehingga mereka menjadi cakap dalam tindakan politiknya. Dengan adanya perkembangan politik Islam sekarang ini sesuai dengan dinamika yang terjadi tidak menjadikan politik Islam yang dijalankan oleh para aktor politik, baik ulama maupun kalangan santri yang terjun dalam politik itu menyimpang dari nilai-nilai Islam, termasuk nilai budaya pesantren. Percaturan politik Islam oleh kalangan ulama maupun santri tidak diorientasikan sebagai langkah politik yang melahirkan polarisasi diantara umat Islam itu sendiri karena bagaimanapun adanya konsepsi, orientasi, dan tindakan politik Islam harus sanggup mengarungi dinamika politik dan dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas. Dalam kaitannya dengan keterlibatan ulama dalam berpolitik, Nanang Takik (2004:200), berpendapat bahwa: “Sementara itu para ulama yang tidak terlibat dalam politik praktis tetap memiliki peran politis dalam bentuk pendidikan politik rakyat, sebagai perwujudan dari peran pencerahan mereka terhadap umat. Peran ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para ulama, tetapi belum optimal. Mereka juga bisa melakukan tindakan politik meski dengan jalan non-politik (political action in the non-political way), yang dilakukan dalam kerangka melakukan amr ma’ruf nahy munkar (mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan komitmen kepada penegakkan etika-moral, mereka bisa jadi pihak independen dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah serta proses dan aktivitas politik yang berlangsung”. Pendidikan politik bagi rakyat sangatlah penting karena secara prinsipil setiap warga negara harus cakap berpolitik. Diperlukan pola pengembangan budaya yang mampu menjembatani nilai-nilai budaya yang menunjukkan eksistensi realitas dalam dinamika serta kondisi politik yang diharapkan. Lebih lanjut tentang urgensi pendidikan politik dikemukakan Idrus Affandi (1996:132) yang dikutif oleh Andriana (2007:104), bahwa: “…pendidikan dengan indoktrinasi dipandang sudah kurang tepat karena dalam banyak hal terbukti kurang memberi hasil sebagaimana diinginkan. Sementara itu penyadaran politik lebih berorientasi pada tindakan-tindakan, yakni mempraktekkan apa yang telah diketahui dan dipahami masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan politik yang efektif tidak sekedar menambah pengetahuan, tetapi sampai pada tingkat pengambilan keputusan dan tindakan…” Urgensi pendidikan politik dalam meningkatkan pemahaman dan penyadaran akan menggeser budaya politik parochial-kaula ke partisipan. Tentunya membutuhkan eksistensi nilai-nilai budaya sehingga mencerminkan adanya moral politik-demokrasi. Dengan demikian kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang melandasi pengetahuan, orientasi, dan tindakan politik sangat dibutuhkan bagi setiap insan politik sehingga pomeo “Islam yes dan Islam politik atau politik Islam no” atau berpolitik itu kotor ditepis dan dikikis dalam kultur sebagian masyarakat terlebih dalam masyarakat pesantren. Memang nilai budaya memiliki urgensi dan relevansinya dengan realita kehidupan masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan Berliana Kartakusumah (2006:35) yang dikutif oleh Andriana (2007:105), bahwa: “…dalam kehidupan manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar nilai-nilai, yaitu (1) nilai-nilai dasar atau pokok (fundamental values), dan (2) nilai-nilai tambahan (instrumental values). Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai yang memiliki sifat mutlak, abadi, dan universal semisal nilai agama yang tertulis dalam kitab suci maupun di dalam hukum alam semesta. Sedangkan nilai-nilai tambahan adalah nilainilai yang memiliki sifat berubah, terbatas, dan kontekstual. Kedua nilai tersebut di dalam kehidupan manusia amat berpengaruh dan menentukan”. Apabila pendapat di atas dihubungkan dengan nilai budaya tentu saja nilai budaya politik terkait dengan fundamental values. Adanya nilai tambahan bukan berarti kontradiktif dengan nilai universal tetapi sebagai tambahan dalam penjabaran untuk memperkuat eksistensi nilai fundamental. Kondisi demikian apabila ditafsirkan dan diterapkan dalam perilaku sosial akan menciptakan masyarakat yang tidak determinan (free will) tetapi merupakan kesatuan yang terikat dalam tatanan nilai. Namun tantangannya adalah tentang pola pendidikan dan penyadaran berpolitik yang diterapkan di masyarakat pesantren itu berperan optimal, yaitu menempatkan santri sebagai agen perubahan, pembaharu, dan calon pemimpin masa depan sebagai subjek politik yang aktif.