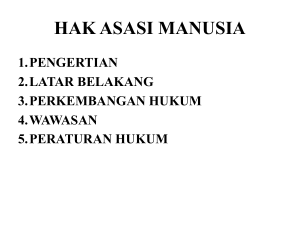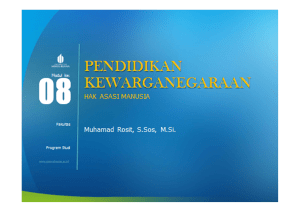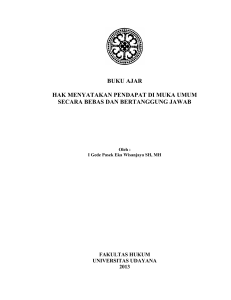sejarah, teori, prinsip dan kontroversi ham
advertisement
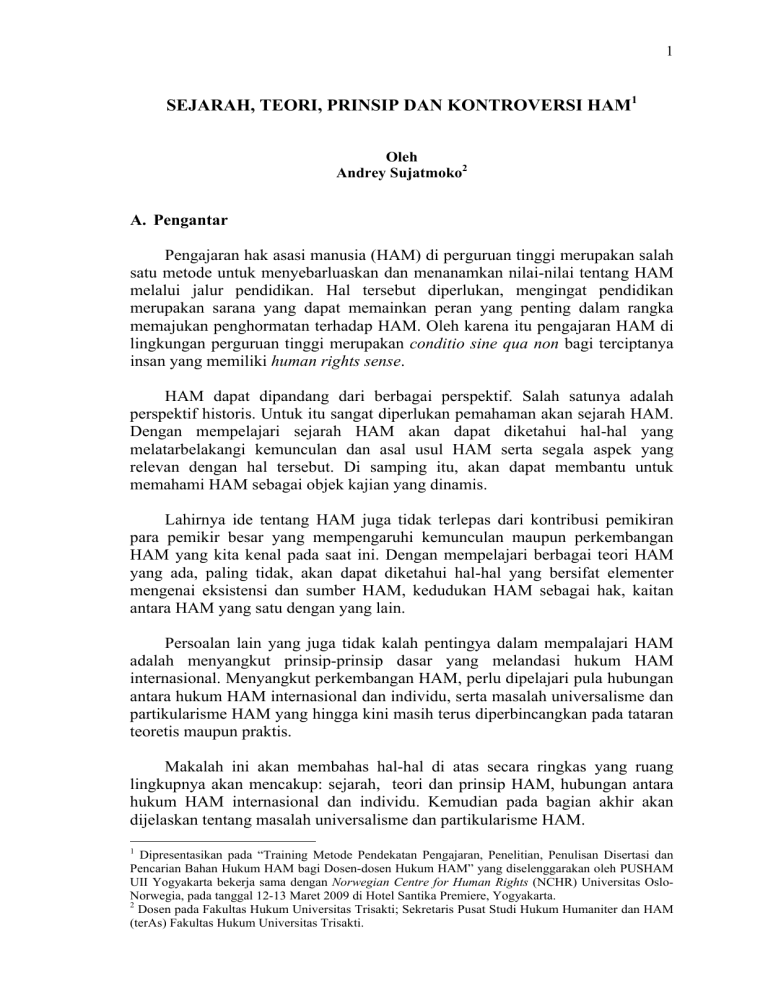
1 SEJARAH, TEORI, PRINSIP DAN KONTROVERSI HAM1 Oleh Andrey Sujatmoko2 A. Pengantar Pengajaran hak asasi manusia (HAM) di perguruan tinggi merupakan salah satu metode untuk menyebarluaskan dan menanamkan nilai-nilai tentang HAM melalui jalur pendidikan. Hal tersebut diperlukan, mengingat pendidikan merupakan sarana yang dapat memainkan peran yang penting dalam rangka memajukan penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu pengajaran HAM di lingkungan perguruan tinggi merupakan conditio sine qua non bagi terciptanya insan yang memiliki human rights sense. HAM dapat dipandang dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah perspektif historis. Untuk itu sangat diperlukan pemahaman akan sejarah HAM. Dengan mempelajari sejarah HAM akan dapat diketahui hal-hal yang melatarbelakangi kemunculan dan asal usul HAM serta segala aspek yang relevan dengan hal tersebut. Di samping itu, akan dapat membantu untuk memahami HAM sebagai objek kajian yang dinamis. Lahirnya ide tentang HAM juga tidak terlepas dari kontribusi pemikiran para pemikir besar yang mempengaruhi kemunculan maupun perkembangan HAM yang kita kenal pada saat ini. Dengan mempelajari berbagai teori HAM yang ada, paling tidak, akan dapat diketahui hal-hal yang bersifat elementer mengenai eksistensi dan sumber HAM, kedudukan HAM sebagai hak, kaitan antara HAM yang satu dengan yang lain. Persoalan lain yang juga tidak kalah pentingya dalam mempalajari HAM adalah menyangkut prinsip-prinsip dasar yang melandasi hukum HAM internasional. Menyangkut perkembangan HAM, perlu dipelajari pula hubungan antara hukum HAM internasional dan individu, serta masalah universalisme dan partikularisme HAM yang hingga kini masih terus diperbincangkan pada tataran teoretis maupun praktis. Makalah ini akan membahas hal-hal di atas secara ringkas yang ruang lingkupnya akan mencakup: sejarah, teori dan prinsip HAM, hubungan antara hukum HAM internasional dan individu. Kemudian pada bagian akhir akan dijelaskan tentang masalah universalisme dan partikularisme HAM. 1 Dipresentasikan pada “Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM” yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas OsloNorwegia, pada tanggal 12-13 Maret 2009 di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta. 2 Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti; Sekretaris Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2 B. Latar Belakang dan Sejarah HAM Sejarah tentang HAM sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Mengapa dikatakan demikian, karena HAM memiliki sifat yang selalu melekat (inherent) pada diri setiap manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan umat manusia. Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata –sejak dahulu hingga saat sekarang ini– tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tiran. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan sematamata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.3 Dengan demikian, faktorfaktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia. Meskipun beberapa pakar menyatakan dapat merunut konsep HAM yang sederhana sampai kepada filsafat Stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan ius naturale dari Undang-undang Romawi, tampak jelas bahwa asal usul konsep HAM yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.4 Hugo de Groot –seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”– atau yang dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.5 3 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003, hlm. 7-21 dan Maurice Cranston, What are Human Rights? New York: Taplinger, 1973 dalam Rhona K. M. Smith, et. al., Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008, hlm. 11. 4 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, Jakarta: Grafiti, 1994, hlm. 2. 5 Rhona K. M. Smith, et. al., op. cit., hlm. 12. 3 Paham HAM lahir di Inggris pada abad ke-17. Inggris memiliki tradisi perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak.6 Sementara Magna Charta (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris –piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini– sebenarnya baru dalam Bill of Rights (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.7 Kemudian, tahun 1679 menghasilkan pernyataan Habeas Corpus, suatu dokumen keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.8 Bill of Rights (1689), sebagaimana diperikan dengan judulnya yang panjang “An act Declaring the Rights and the Liberties and the Subject and Setting the Succession of the Crown” (Akta Deklarsi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja), merupakan hasil perjuangan Parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17. Disahkan setelah raja James II dipaksa turun takhta dan William II serta Mary II naik ke singgasana menyusul “Revolusi Gemilang” (Glorious Revolution) pada tahun 1688, Bill of Rights, yang menyatakan dirinya sebagai deklarasi undang-undang yang ada dan bukan merupakan undang-undang yang baru, menundukkan monarki di bawah kekuasaan Parlemen, dengan menyatakan bahwa kekuasaan Raja untuk membekukan dan memberlakukan seperti yang diklaim raja adalah ilegal.9 Perlu dicatat pula bahwa dengan adanya Bill of Rights timbul kebebasan untuk berbicara (speech) dan berdebat (debate), sekalipun hanya untuk anggota Parlemen dan untuk digunakan di dalam gedung parlemen. Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad ke-18 tidak melupakan pengalaman Revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoretis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni itu dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tiadanya wakil dalam Parlemen Inggris, para pendiri Amerika Serikat ini mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson, gagasangagasan ini diungkapkan dengan kata-kata yang sangat jelas dan tepat.10 Deklarasi tersebut secara eksplisit mengakui kesetaraan manusia dan adanya 6 Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, 1994, hlm. 123. 7 Scott Davidson, op. cit., hlm. 2. 8 Franz Magnis Suseno, op. cit., hlm. 123. 9 Scott Davidson, op. cit., hlm. 3. 10 Ibid., hlm. 4. 4 hak-hak pada diri manusia yang tidak dapat dicabut (inalienable), yaitu hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan. Pada tahun 1791 barulah Amerika Serikat mengadopsi Bill of Rights yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. Di antara amandemen-amandemen yang tekenal adalah Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat; Amandemen Kelima yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.11 Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat kemudian dijadikan model yang mempengaruhi revolusi di Prancis dalam menentang rezim yang tiran. Revolusi ini menghasilkan Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) (1789). Deklarasi ini membedakan antara hak-hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrati yang dibawa ke dalam masyarakat dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga negara. Beberapa hak yang disebutkan dalam Deklarasi, antara lain, yaitu: hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, hak untuk melawan penindasan. Apapun debat teoretis atau doktriner mengenai dasar-dasar revolusi Inggris, Amerika dan Prancis yang jelas masing-masing revolusi itu, dengan caranya sendiri-sendiri, telah membantu perkembangan bentuk-bentuk demokrasi liberal di mana hak-hak tertentu dianggap sebagai hal terpenting dalam melindungi individu terhadap kecenderungan ke arah otoriterisme yang melekat pada negara. Hal penting mengenai hak-hak yang diproteksi itu adalah bahwa hak-hak ini bersifat individualistis dan membebaskan (libertarian): hakhak ini didominasi dengan kata-kata “bebas dari” dan bukan “berhak atas”. Dalam bahasa modern, hak-hak ini akan disebut hak sipil dan politik, karena hak-hak ini terutama mengenai hubungan individu dengan organ-organ negara. Begitu besar kekuatan ide-ide revolusioner ini sehingga hanya sedikit konstitusi modern yang tidak menyatakan akan melindungi hak-hak individu ini.12 Dalam perkembangannya, hak-hak yang dicirikan dengan kata-kata “berhak atas” kemudian dikenal sebagai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya, dikenal pula apa yang disebut dengan hak-hak solidaritas (solidarity rights) yang muncul sebagai perkembangan terakhir menyangkut HAM. Babak baru perkembangan HAM secara internasional terjadi setelah dunia mengalami kehancuran luar biasa akibat dari PD II. Terbentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional pada tahun 1945 tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan HAM di kemudian hari. Hal itu, antara lain, ditandai dengan adanya pengakuan 11 12 Ibid., hlm. 5. Ibid., hlm. 7-8. 5 di dalam Piagam PBB (United Nations Charter) akan eksistensi HAM dan tujuan didirikannya PBB sendiri yaitu dalam rangka untuk mendorong penghormatan terhadap HAM secara internasional. Walaupun di dalam Piagam belum dirumuskan secara jelas apa yang dimaksud dengan HAM. Tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional baru dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang di dalamnya berisikan “katalog” HAM yang dibuat berdasarkan suatu kesepakatan internasional. Deklarasi tersebut tidak hanya memuat hak-hak asasi yang diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialisme, melainkan juga mencerminkan pengalaman penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasionalis-nasionalis tahun dua puluh sampai empat puluhan. Sementara itu elit nasional bangsa-bangsa yang dijajah mempergunakan paham hak asasi, terutama “hak untuk menentukan dirinya sendiri”, sebagai senjata ampuh dalam usaha untuk meligitimasikan perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan.13 Kemudian, pada tahun 1966 dihasilkan perjanjian internasional (treaty) yang di dalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Poitik (International Covenant on Civil and Political Rights) serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Ketiganya dikenal dengan istilah “the International Bill of Human Rights”. Secara historis dapat dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya mekanisme tersebut adalah akibat dari kekejaman-kekejaman di luar batas-batas peri kemanusiaan yang terjadi selama PD II yang menimbulkan korban terhadap manusia dalam jumlah besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme internasional yang dapat melindungi HAM secara lebih efektif. Dengan tersedianya mekanisme tersebut diharapkan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM paling tidak dapat dicegah atau dikurangi. Berdasarkan pemaparan sejarah HAM secara singkat seperti telah diuraikan di atas, terlihat bahwa pengertian HAM mengalami perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Pengertian HAM yang pada awalnya hanya dimaksudkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara – yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak sipil dan politik–, kemudian beralih untuk mendorong kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi individu–yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Berdasarkan hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa HAM senantiasa berkembang dan bersifat dinamis. 13 Franz Magnis Suseno, op. cit., hlm. 125. 6 C. Teori-teori HAM Banyak pertanyaan yang muncul menyangkut eksistensi dan hakikat HAM. Hal tersebut misalnya: apakah yang dimaksud dengan HAM?; dari mana HAM berasal?; apakah HAM dapat dihapuskan?; apakah ketiga generasi HAM benarbenar merupakan HAM?; apakah semua HAM sederajat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dibutuhkan pemahaman tentang HAM berdasarkan suatu kerangka teori. Teori dapat berfungsi untuk menyediakan suatu alat analisis yang memungkinkan pertanyaan penting seperti di atas dapat diajukan dan jawaban tentatif dapat diberikan. Teori memungkinkan dibangunnya paradigma yang memberikan koherensi dan konsistensi bagi segala perdebatan mengenai hak dan menyumbangkan suatu model yang dapat dipakai untuk mengkur hak-hak yang diandaikan itu. Teori juga menyediakan mekanisme yang dapat dipakai untuk menetapkan dengan tepat batas hak-hak yang eksistensinya telah disepakati.14 Menurut Jerome J. Shestack, istilah ‘HAM’ tidak ditemukan dalam agamaagama tradisional. Namun demikian, ilmu tentang ketuhanan (theology) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi dari pada negara dan yang sumbernya adalah Tuhan (Supreme Being). Tentunya, teori ini mengadaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM.15 Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM, antara lain, yaitu: teori hak-hak kodrati (natural rights theory), teori positivisme (positivist theory) dan teori relativisme budaya (cultural relativist theory). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.16 Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai “Bill of Rights”, seperti yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi 14 Scott Davidson, op. cit., hlm. 34. Lihat Jerome J. Shestack, Jurisprudence of Human Rights, dalam Theodor Meron, edit., Human Rights in International Law Legal and Policy Issues, New York: Oxford University Press, 1992, hlm. 76. Hal itu dinyatakan sebagai berikut: “The term ‘human rights’ as such is not found in traditional religions. Nonetheless, theology presents the basis for a human rights theory stemming from a law higher than the state and whose source is the Supreme Being. Of course, this theory presupposes an acceptance of revealed doctrine as the source of such rights”. 16 Todung Mulya Lubis, In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 15-16. 15 7 Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad kemudian, di penghujung PD II, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di benua Amerika dan Eropa.17 Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM internasional. Namun demikian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan oleh John Locke). Kandungan hak dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hakhak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru” yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM dipahami dewasa ini.18 Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori positivis termasuk salah satunya. Penganut teori ini berpendapat, bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Hal tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai berikut: “Bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum ‘kodrati’, lahir hak imajiner...Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi.”19 Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang a priori, kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.20 Berkenaan dengan perdebatan antara kedua teori tersebut, menurut pengamatan Mieczyslaw Maneli –seorang pakar politik dan sarjana hukum–, 17 Ibid., hlm. 16-17. Rhona K. M. Smith, et. al., op. cit., hlm. 14. 19 Todung Mulya Lubis, op. cit., hlm. 18. 20 Scott Davison, op. cit., hlm. 40. 18 8 perdebatan secara tradisional yang membagi hukum kodrat dan teori positivis saat ini sudah kehilangan validitas dan ketajaman yang sebelumnya berlaku. Benarkah demikian, setelah kita menyaksikan tidak hanya terjadinya suatu proses penyatuan (rapprochment), tetapi juga suatu proses positivisasi (positivization) ide-ide HAM? Menurut Todung Mulya Lubis, Maneli mungkin benar, khususnya jika kita membaca instrumen-instrumen hukum HAM internasional dan konstitusi-konstitusi dari berbagai negara. Sebagai contoh, konstitusi Indonesia, Malaysia dan Filipina telah memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan hak-hak kodrati.21 Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (cultural relativist theory) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperalisme budaya (cultural imperalism). 22 Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (desocialized) dan budaya (deculturized).23 Apa yang ditawarkan oleh para penganut teori ini adalah kontekstualisasi HAM dalam suatu cara seperti yang dinyatakan oleh Asosiasi Anthropolog Amerika (American Anthropologial Association) di hadapan Komisi HAM PBB ketika Komisi ini sedang mempersiapkan rancangan Deklarasi Universal HAM. Pernyataan itu pada intinya menginginkan perlunya dipikirkan, dalam rangka menyusun Deklarasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti: bagaimana Deklarasi nantinya dapat berlaku bagi seluruh manusia dan tidak merupakan suatu pernyataan mengenai hak-hak (statement of rights) yang hanya menggambarkan nilai-nilai yang lazim terdapat di negara-negara Eropa Barat dan Amerika.24 21 Todung Mulya Lubis, op. cit., hlm. 18-19. Ibid., hlm. 19. 23 Ibid. Yaitu dinyatakan sebagai berikut: “According to cultural relativists, there is no such thing as universal rights. They feel that natural rights theory ignores the social basis of an individual’s identity as a human being. A human being is always the product of some social and cultural milieu and different traditions of culture and civilization contain different ways of being human. It follows, therefore, that rights belonging to all human beings at all times and in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings”. 24 Ibid., hlm. 19-20. 22 9 D. Prinsip-prinsip HAM Berbicara mengenai prinsip-prinsip HAM dalam konteks hukum HAM internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional (general principles of law) yang juga merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama (primer), di samping perjanjian internasional (treaty), hukum kebiasaan internasional (customary international law), yurisprudensi dan doktrin. Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional diperlukan dua hal, yaitu adanya penerimaan (acceptance) dan pengakuan (recognition) dari masyarakat internasional. Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM yang telah memenuhi kedua syarat tersebut memiliki kategori sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Pada kenyataannya, hal itu kemudian dielaborasi ke dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, misalnya perjanjian internasional. Beberapa prinsip telah menjiwai HAM. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.25 Gagasan mengenai HAM dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam HAM. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia. Hal tersebut misalnya tercermin dari prinsip equal pay for equal work yang dalam UDHR dianggap sebagai hak yang sama atas pekerjaan yang sama. Prinsip tersebut sekaligus juga merupakan HAM. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.26 Pelarangan terhadap diskriminasi non-diskriminasi merupakan salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).27 Prinsip ini dikenal pula dengan nama prinsip nondiskriminasi. Dalam “International Bill of Human Rights”, yaitu UDHR, ICCPR maupun ICESCR, prinsip ini telah dimuat secara tegas. Bahkan 25 Rhona K. M. Smith, et. al., hlm. 39. Ibid. 27 Ibid., hlm 40. 26 10 sebelumnya, hal yang sama juga telah lebih dahulu ditegaskan dalam Piagam PBB (United Nations Charter). Hukum HAM internasional memperluas alasan diskriminasi. UDHR menyebutkan beberapa alasan diskriminasi, antara lain: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (property), kelahiran atau status lainnya. Semua itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.28 Prinsip kewajiban positif negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum HAM internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (right bearer) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk: melindungi (protect), menjamin (ensure) dan memenuhi (fulfill) HAM setiap individu. Malahan, menurut hukum internasional, kewajiban di atas merupakan kewajiban yang bersifat erga omnes atau kewajiban bagi seluruh negara jika menyangkut norma-norma HAM yang berkategori sebagai jus cogens (peremptory norms). Misalnya, larangan melakukan: perbudakan, genocide dan penyiksaan. E. Hukum HAM Internasional dan Individu HAM yang kini telah menjadi objek kajian dari disiplin ilmu tersendiri merupakan suatu hal yang timbul akibat dari perkembangan yang terjadi dalam hukum internasional. Perkembangan tersebut terutama terjadi setelah PD II, yaitu terkait dengan status atau kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional. Menurut Slomanson, secara historis pada awalnya hukum internasional hanya mengakui negara sebagai subjek hukum. Negara-negara kemudian membuat aturan yang dimaksudkan untuk mengikat mereka dalam hubungannya satu sama lain. Adapun individu secara historis dianggap sebagai subjek dari hukum nasional dari satu negara atau lebih ketika tindakannya muncul dalam konteks internasional.29 Secara tradisional hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan-hubungan antarnegara secara eksklusif, sehingga hanya negara yang dianggap sebagai subjek hukum dan memiliki hak-hak hukum 28 Ibid. Wiliam R. Slomanson, Fundamental Perspectives on International Law, 3rd Edition, Belmont: Wadsworth, 2000, hlm. 172. 29 11 menurut hukum internasional.30 Hal yang sama juga dinyatakan oleh Rhona K. M. Smith sebagai berikut: “Originally, international law was, literally, the law of nations. It was exclusively concerned with interaction of State–diplomatic relations and the laws of war. Individuals were considered the property of the State in which they lived.”31 Para individu dianggap tidak memiliki hak-hak hukum internasional (international legal rights), mereka lebih dianggap sebagai objek daripada subjek hukum internasional. Sepanjang negara-negara mempunyai suatu kewajiban hukum internasional (international legal obligations) terhadap individu, mereka dianggap mempunyai kewajiban terhadap negara yang menjadi nasionalitas dari individu tersebut.32 Kenyataan di atas erat kaitannya dengan aliran pemikiran yang berkuasa pada saat itu. Ajaran hukum alam (natural law) sesungguhnya mengakui individu sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional hingga pertengahan abad ke-19. Namun, setelah itu ajaran kedaulatan negara (state sovereignty) menggantikan ajaran hukum alam. Ajaran kedaulatan negara berpandangan bahwa hanya negaralah yang merupakan subjek hukum internasional. Menyangkut kepentingan individu, hukum internasional tidak menciptakan hak dan kewajiban terhadap individu, tetapi mewajibkan negara-negara untuk memperlakukan individu-individu dalam suatu cara tertentu.33 Berdasarkan hal di atas, menyangkut individu, suatu negara akan memiliki kewajiban secara hukum hanya dalam hubungannya dengan negara yang menjadi nasionalitas dari individu tersebut. Pada saat itu perlakuan suatu negara terhadap warga negaranya belum diatur oleh hukum internasional. Oleh karena itu hukum internasional tidak berlaku terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu negara terhadap warga negaranya, mengingat seluruh persoalan tersebut diangggap termasuk dalam yurisdiksi domestik masingmasing negara. 34 Hal di atas sejalan dengan pandangan pada abad ke-19 bahwa hak dan kewajiban menurut hukum internasional hanya berlaku secara eksklusif bagi negara. Adapun para individu memiliki kewajiban berdasarkan hukum nasional. Oleh karena itu mereka hanya dapat melanggar hukum nasional.35 30 Thomas Buergenthal, International Human Rights, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1995, hlm. 2. 31 Rhona K. M. Smith, Textbook on International Human Rights, 3rd Edition, New York: Oxford University Press, 2007, hlm. 6. 32 Thomas Buergenthal, op. cit., hlm. 2. 33 Karl Josef Partsch, Individuals in International Law, dalam Rudolf L. Bindshdler, et.al., Encyclopedia of Public International Law, Jilid ke-8, Amsterdam: Elsevier Science Publisher B.V., 1987, hlm. 316. 34 Ibid., hlm. 2-3. 35 Wiliam R. Slomanson, op. cit., hlm. 173. 12 Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya kritik terhadap doktrin klasik tersebut datang dari berbagai sumber dan aliran-aliran pemikiran di abad ke-20. Salah satunya yaitu aliran sosiologis dari Prancis (misalnya: Duguit, Scelle, Politis) yang berpandangan bahwa individu pada awalnya tidak hanya dipandang sebagai objek dari keseluruhan tatanan hukum, termasuk hukum internasional, tetapi bahkan dianggap sebagai subjek yang eksklusif (exclusive subject). Negara hanya berfungsi untuk menyediakan suatu “mesin hukum” (“legal machinery”) untuk mengatur hak-hak dan kewajiban dari kelompok para individu.36 Doktrin bahwa hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional juga mendapat tantangan dari para ahli hukum internasional, maupun para sarjana dari Inggris dan Amerika. Mereka berpandangan bahwa individu adalah subjek hukum internasional. Mereka menegaskan bahwa individu menikmati hak-hak internasional –khususnya HAM– dan hak-hak tersebut harus dipertahankan tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh organ-organ internasional yang memiliki kewenangan hukum untuk turut campur dalam masalah-masalah internal dari negara tertentu.37 Perkembangan HAM dalam hukum internasional hingga seperti sekarang ini, tidak terlepas dari adanya perubahan status atau kedudukan individu dalam hukum internasional. Perubahan mendasar yang terjadi yaitu diakuinya individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu menurut hukum internasional. Menurut Ved Nanda, hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan secara dramatis kedudukan (status) individu yang beralih dari semata-mata sebagai objek menjadi subjek hukum internasional. Individu memiliki hak untuk mencari pelunasan (redress) di forum internasional. Perlindungan HAM yang diakui secara internasional merupakan suatu perubahan yang bersifat revolusioner.38 Dengan status individu sebagai subjek hukum internasional, maka secara teori individu dapat melanggar hukum internasional (di samping hukum nasional). Hal tersebut muncul sebagai akibat dari tindakan-tindakan mengerikan yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman. Teori tersebut dihidupkan kembali oleh para sarjana dan ahli hukum dari negara-negara Barat yang menyatakan bahwa individu dapat melanggar hukum internasional. Teori tersebut dikenang dalam putusan Pengadilan Nuremberg dan Tokyo. Praktek negara kemudian setuju untuk mengadili para individu atas tindakannya melanggar hukum internasional.39 36 Karl Josef Partsch, dalam Bindshdler, et.al., op. cit., hlm. 316. Wiliam R. Slomanson, op. cit., hlm. 173. 38 V. Nanda, International Law in the Twenty-First Century, ch. 5 in N. Jasentuliyana (ed.), Perspectives on International Law, at 83 (London: Kluwer, 1995) dalam Ibid., hlm. 175. 39 Wiliam R. Slomanson, op. cit., hlm. 173-174. 37 13 Berkenaan dengan diadilinya para penjahat perang secara individual di hadapan Pengadilan Nuremberg dan Tokyo, Ian Brownlie menyatakan bahwa sejak pertengahan abad ke-19 secara umum telah diakui bahwa ada beberapa tindakan (acts) atau kelalaian (omissions) yang menyebabkan berlakunya tanggung jawab pidana pada para individu dan atas hal itu penghukuman bisa diberlakukan, baik oleh pengadilan internasional atau nasional dan pengadilan militer.40 Dalam putusan yang dibuat oleh Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dinyatakan, telah lama diakui bahwa hukum internasional mengenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap para individu. Mereka memiliki kewajiban internasional melebihi kepatuhan terhadap kewajiban yang dibebankan oleh negaranya. Orang-orang yang melanggar hukum perang tidak dapat memperoleh kekebalan ketika bertindak atas kewenangan dari negara, jika negara dalam mensahkan tindakan tersebut bertindak di luar kewenangannya menurut hukum internasional.41 Tanggung jawab yang bersifat individual selanjutnya juga diterapkan oleh Mahkamah Pidana Internasional ad hoc terhadap kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Bekas Yugoslavia (1993) dan di Rwanda (1994). Hal tersebut juga diatur di dalam Piagam Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2002. Dalam hukum perjanjian internasional juga telah diatur bahwa individu merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, individu harus bertanggung jawab secara individual apabila melakukan kejahatan genocide yang merupakan suatu kejahatan menurut hukum internasional, terlepas dari jabatan yang dimilikinya. Hal tersebut diatur dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide tahun 1948, yaitu sebagai berikut: “Persons committing genocide or any of the other act enumerated in article II shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.”42 Isu HAM dalam konteks internasional, secara luas mulai lebih disuarakan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Besarnya korban jiwa yang jatuh semasa perang tersebut telah menyadarkan negara-negara di dunia untuk lebih memperhatikan aspek kemanusiaan. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan adanya keinginan yang kuat dari sejumlah besar negara untuk menempatkan HAM dalam posisi yang penting. 40 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 5th edition, New York: Oxford University Press, 1998, hlm. 565. Ia mengatakan bahwa: “Since the latter half of the nineteenth century it has been generally recognized that there are acts or omissions for which international law imposes criminal responsibility on individuals and for which punishment may be imposed, either by properly empowered international tribunals or by national courts and military tribunals.” 41 Ibid., hlm. 565-566. 42 Pasal IV Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948. 14 Berdirinya PBB pada tahun 1945 merupakan saat yang sangat penting terhadap eksistensi HAM. Dibentuknya PBB juga merefleksikan komitmen dari sejumlah besar negara menyangkut HAM. Hal tersebut terlihat dari ketentuanketentuan mengenai HAM yang terkandung di dalam Piagam PBB. Menurut Ian Brownlie, klausul-klausul mengenai HAM di dalam Piagam PBB meletakkan suatu dasar dan dorongan bagi perkembangan selanjutnya dalam perlindungan HAM. Hal itu terlihat dalam bagian mukadimah Piagam yang menyatakan bahwa negara-negara anggota PBB menegaskan kembali keyakinannya terhadap HAM yang fundamental. Kemudian dalam Pasal 1 dinyatakan pula bahwa PBB memiliki tujuan dalam mendorong kerja sama internasional dalam rangka mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.43 Piagam PBB tersebut tidak dipungkiri lagi memiliki sejumlah konsekuensi penting bagi perkembangan HAM dewasa ini. Pertama, Piagam PBB “menginternasionalisasi” HAM. Dengan terikat pada Piagam, sebagai perjanjian multilateral, Negara-negara Pihak mengakui bahwa “HAM” yang mengacu kepada Piagam adalah subjek yang menjadi perhatian internasional dan HAM tidak lagi secara eksklusif menjadi masalah yurisdiksi domestik. Kedua, kewajiban dari negara-negara anggota PBB untuk bekerja sama dengan PBB dalam mempromosikan HAM dan kebebasan mendasar telah melengkapi PBB dengan kewenangan hukum yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah secara massif untuk menentukan dan mengkodifikasikan HAM. Upaya tersebut direfleksikan dengan diadopsikannya “International Bill of Human Rights” dan sejumlah instrumen HAM lain yang ada saat ini. Ketiga, PBB telah berhasil menjelaskan ruang lingkup kewajiban anggota PBB untuk mempromosikan HAM, memperluas dan menciptakan institusi-institusi berdasarkan Piagam PBB (Charter-based) yang dirancang untuk menjamin pelaksanaan oleh pemerintah.44 Sejalan dengan terbentuknya PBB, HAM semakin mendapatkan perhatian yang besar. Hal ini dibuktikan dari adanya mandat yang diberikan oleh ECOSOC kepada Komisi HAM PBB agar menyusun semacam dokumen HAM. Dokumen tersebut berisi daftar hak-hak yang termasuk kategori HAM. Dokumen tersebut dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan HAM di dunia. Pertama-tama dapat dicatat bahwa UDHR merupakan pernyataan internasional dasar yang mengatur/menentukan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dicabut/dilanggar dari semua keluarga kemanusiaan. 43 44 Ian Brownlie, op. cit., hlm. 573-574. Thomas Buergenthal, op. cit., hlm. 25-27. 15 Deklarasi tadi dimaksudkan sebagai suatu standar pencapaian bersama bagi semua orang dan semua bangsa (the common standard of achievement for all peoples and all nations).45 Dengan adanya UDHR, dapat dikatakan bahwa HAM memasuki fase baru. Hal itu disebabkan, dimuatnya HAM di dalam dokumen yang bersifat internasional merupakan suatu pengakuan terhadap eksistensi HAM, khususnya ditinjau dari sudut pandang hukum internasional. Walaupun UDHR tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, karena lahir berdasarkan suatu Resolusi Majelis Umum PBB, namun demikian UDHR tidak dipungkiri lagi sangat mempengaruhi perkembangan HAM di berbagai negara. Pengaruh yang terjadi antara lain, banyak negara yang mencantumkan sejumlah hak yang terdapat di dalam UDHR ke dalam konstitusi negaranya. Kesadaran dari negara-negara untuk mengatur HAM lebih lanjut ke dalam sistem hukumnya dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan sekaligus penghormatan terhadap HAM. Deklarasi Universal HAM, sesuai dengan namanya, berbentuk “deklarasi” Majelis Umum PBB. Ini berarti bahwa secara hukum Deklarasi tersebut tidak mengikat para anggota PBB. Namun demikian, beberapa pakar dengan mengajukan berbagai teori ingin membuktikan bahwa Deklarasi toh memiliki daya mengikat. Von Glahn, berpendapat bahwa Deklarasi tersebut merupakan suatu penafsiran resmi atau expository interpretation dari beberapa ketentuan tentang HAM yang bersifat sangat umum, yang terdapat dalam Piagam PBB dan ketentuan dalam Piagam mengikat semua angggota PBB.46 Adapun Lung Chu Chen berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur HAM, terutama yang terdapat dalam Deklarasi sudah dapat digolongkan sebagai jus cogens yang berarti bahwa ketentuan itu hanya dapat diubah atau ditiadakan oleh ketentuan yang berstatus jus cogens juga.47 David Ott, seorang pakar lain, berpendapat bahwa UDHR dapat dianggap telah menjadi dasar bagi tersusunnya customary internatinal human rights. Gagasan ini berdasarkan kenyataan bahwa UDHR: telah berulang kali dijadikan referensi dari sejumlah resolusi PBB; demikian pula telah dijadikan referensi dalam persidangan badan internasional, antara lain, dalam Final Act dari Konferensi Helsinki tahun 1975; telah dicantumkan dalam beberapa statement dan agreement antarnegara yang dibuat di luar lingkungan PBB.48 45 GPH. Haryomataram, Hukum Humaniter: Hubungan dan Keterkaitannya dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Perlucutan Senjata, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, tgl. 2 Oktober 1997, hlm. 10. 46 Ibid., hlm. 13. 47 Loc. cit. 48 Ibid. 16 Berkaitan dengan berbagai pandangan (teori) yang dikemukakan di atas, Thomas Buergenthal berkesimpulan bahwa apapun teorinya, sekarang ini telah jelas bahwa komunitas internasional memberikan suatu atribut moral yang khusus (very special moral) dan status hukum (normative status) kepada Deklarasi Universal HAM bahwa tidak ada instrumen lain semacam itu yang memiliki kedua hal tersebut.49 F. Universalitas dan Partikularitas HAM HAM sebagai suatu konsep sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang membentuknya, seperti ideologi, politik maupun budaya yang melingkupinya. Walaupun HAM secara historis sudah ada jauh ke belakang, tetapi perdebatan menyangkut unversalitas serta partikularitas HAM masih diperbincangkan di berbagai kesempatan oleh berbagai kalangan hingga saat ini. Salah satu wacana yang paling hangat dalam masa dua dekade terakhir adalah konflik antara dua “ideologi” yang berbeda dalam penerapan HAM pada skala nasional, yaitu universalisme (universalism) dan relativisme budaya (cultural relativism). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitif” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Relativisme budaya, di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah.50 Menyinggung perdebatan tersebut, dapat diutarakan bahwa sejak awal masalah universalitas dan relativisme HAM merupakan sumber perdebatan dan pertengkaran. Hal itu dinyatakan sebagai berikut: “The question of the ‘universal’ or ‘relative’ character of the rights declared in the major instruments of the human rights movement has been a source of debate and contention from the movement’s start.”51 Perdebatan tersebut terutama akan terkait dengan dua teori yang memiliki pandangan yang saling bertolak belakang menyangkut gagasan dan penerapan HAM, yaitu teori universalis (universalist theory) dan teori relativisme budaya (cultural relativist theory). Doktrin kontemporer HAM merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis. Asal muasal dan perkembangan HAM tidak dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Prasyarat yang penting bagi pembelaan HAM di antaranya konsep individu sebagai pemikul hak “alamiah” tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan 49 Thomas Buergenthal, op. cit, hlm. 37-38. Ia menyatakan bahwa: “Whatever the theory, it is today clear that the international community attributes a very special moral and normative status to the Universal Declaration that no other instrument of its kind has acquired.” 50 Rhona K. M. Smith., et. al., op. cit., hlm. 18. 51 Henry J. Steiner dan Philip Alston, International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral, New York: Oxford University Press, 2000, hlm. 366. 17 adil bagi setiap individu secara rasional. Menurut teori universalis, HAM berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasikan secara rasional.52 Secara singkat, teori universalis berpandangan bahwa HAM bersifat universal, sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau pun yang ada pada suatu negara. Oleh karena itu HAM tidak memerlukan pengakuan dari otoritas manapun, seperti negara atau penguasa tertentu. Isu relativisme budaya (cultural relativism) baru muncul menjelang akhir Perang Dingin sebagai respons terhadap klaim universal dari gagasan HAM internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu HAM dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masingmasing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi HAM, apalagi bila ia didominasi oleh suatu budaya tertentu.53 Teori relativisme budaya pada intinya berpandangan bahwa HAM harus diletakkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal. Dengan perkataan lain HAM harus dilihat dari perspektif budaya suatu masyarakat atau negara. Perdebatan di atas dapat dicarikan titik temu dengan cara mengkaji HAM dilihat dari esensinya dan aktualisasinya. Hal ini secara sederhana dapat dimulai dengan menjelaskan pengertian HAM. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pengertian HAM yang sekarang dipahami berasal dari pandangan universalis. Sebenarnya hingga saat ini belum ada suatu definisi HAM yang baku dan bersifat otoritatif (mengikat). Berkaitan dengan hal itu, H. Victor Condé mengatakan bahwa belum ada definisi HAM yang diterima secara universal dan otoritatif. Banyak yang mendefinisikannya sebagai suatu klaim yang dapat dipaksakan secara hukum atau hak yang dimiliki oleh manusia vis-á-vis pemerintahan negara sebagai perlindungan terhadap martabat manusia yang bersifat melekat dari manusia.54 Definisi HAM lainnya yang telah dikenal yaitu, 52 Ibid., hlm. 19. Ibid., hlm. 20. 54 H. Victor Condé, A Handbook of International Human Rights Terminology, Lincoln N.E.: University of Nebraska Press, 1999, hlm. 15. Hal itu dinyatakan sebagai berikut: “There is no universally accepted and authoritative definition of human rights. Many define it as a legally enforceable claim or entitlement that is held by an individual human being vis-á-vis the state government for the protection of the inherent human dignity of the human being”. 53 18 HAM secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia.55 Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi HAM merupakan suatu hal yang bersifat universal, mengingat sifatnya yang melekat (inherent). Konsekuensi dari hal tersebut yaitu, karena HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan merupakan pemberian dari orang atau penguasa, maka orang atau penguasa tersebut tidak berhak untuk merampas atau mencabut HAM seseorang. Di samping itu, HAM mengatasi batas-batas geografis maupun adanya perbedaan-perbedaan ras, jenis kelamin, agama, bahasa atau budaya yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan mengenai aktualisasi HAM-nya adalah bersifat partikular, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang bersifat lokal. Sifat partikular HAM merupakan kompleksitas HAM yang multidimensi, artinya HAM mengandung banyak elemen di dalamnya, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu pelaksanaanya pun disesuaikan dengan elemen-elemen tersebut yang bersifat lokal. Dengan demikian masalah universalitas HAM adalah menyangkut esensi dari HAM, sedangkan partikularitas HAM adalah masalah aktualisasi dari HAM. Kedua hal itu harus dipahami dengan baik, karena pemaknaan yang keliru terhadap dua masalah tersebut akan menimbulkan pandangan yang salah. Berkaitan dengan hal di atas, Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa: “Antara kontekstualitas dan universalitas HAM tidak ada pertentangan. Universalitas menyangkut isi HAM, sedangkan kontekstualitas menyangkut relevansinya. HAM memang berlaku universal, jadi segenap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak itu...”. Oleh karena esensi HAM bersifat universal, maka pandangan yang menyatakan bahwa HAM berasal dari budaya “Barat” sehingga bertentangan dengan budaya “Timur” adalah keliru. Sesunguhnya, persoalan HAM bukanlah masalah budaya “Barat” berhadapan dengan budaya “Timur”, sehingga tesis yang menghadapkan kedua hal tersebut dan kemudian mempertentangkannya adalah tidak sesuai dengan sifat melekat dan universal dari HAM. Dapat dicatat di sini, bahwa revolusi yang tejadi di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18 dapat dianggap sebagai asal-usul konsep HAM yang modern. Namun demikian hal tersebut tidak berarti bahwa HAM berasal dari (bangsa) Barat atau Eropa. Berdasarkan fakta sejarah, HAM muncul karena adanya penindasan terhadap manusia oleh penguasa yang tiran, sehingga menimbulkan kesadaran menyangkut harkat dan martabat manusia. 55 The United Nations, Human Rights Questions and Answers, New York; the United Nations Department of Public Information, 1988, hlm. 4. Yaitu dinyatakan: “Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being”. 19 Meskipun pengertian HAM baru dirumuskan secara eksplisit pada abad ke-18, asal mula pendapat dari segi hukum dan prinsip dasarnya sudah lebih dahulu eksis jauh ke belakang dalam sejarah. *** 20 DAFTAR PUSTAKA Bindshdler, Rudolf L. et.al., Encyclopedia of Public International Law, Jilid ke8, Amsterdam: Elsevier Science Publisher B.V., 1987. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 5th edition, New York: Oxford University Press, 1998. Buergenthal, Thomas, International Human Rights, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1995. Condé, H. Victor, A Handbook of International Human Rights Terminology, Lincoln N.E.: University of Nebraska Press, 1999. Davidson, Scott, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, Jakarta: Grafiti, 1994. Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, 1994. Meron, Theodor, edit., Human Rights in International Law Legal and Policy Issues, New York: Oxford University Press, 1992. Slomanson, Wiliam R., Fundamental Perspectives on International Law, 3rd Edition, Belmont: Wadsworth, 2000. Steiner, Henry J. dan Alston, Philip, International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral, New York: Oxford University Press, 2000. Smith, Rhona K. M., Textbook on International Human Rights, 3rd Edition, New York: Oxford University Press, 2007. Smith, Rhona K. M., et. al., Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008. The United Nations, Human Rights Questions and Answers, New York; the United Nations Department of Public Information, 1988. Todung Mulya Lubis, In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990, Jakarta: Gramedia, 1993. ***