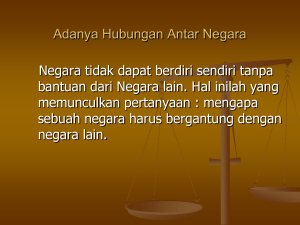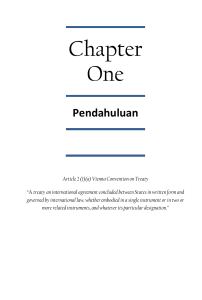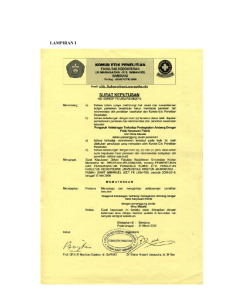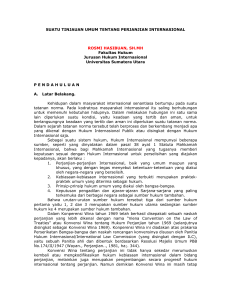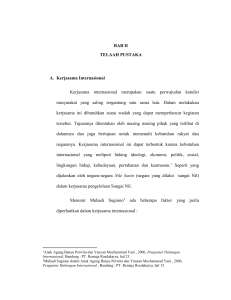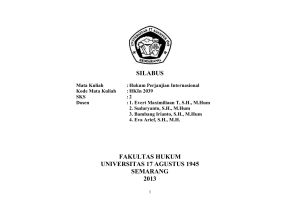Chapter Five - Repository UNIMAL
advertisement

Chapter Five Pelaksanaan Perjanjian Internasional Article 26 Vienna Convention on Treaty “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.” Chapter Five – Pelaksanaan Perjanjian Internasional 53 A. Prinsip Perjanjian Internasional Konvensi Wina yang terdiri dari 85 pasal, delapan bagian, dan sebuah ketentuan tambahan termasuk lima asas atau prinsip dasar perjanjian internasional. Adapun prinsip-prinsip perjanjian internasional yang akan dibahas di sini termasuk free consent, good faith, pacta sunt servanda, dan rebus sic stantibus. Free consent dan good faith adalah prinsip utama dalam perjanjian yang selalu ditaati oleh engara-negara dalam berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan prinsip yang lainnya berasal dari kebiasaan hukum Romawi, khususnya pacta sunt servanda. Prinsip-prinsip ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. 1. Free Consent (Kebebasan Berkontrak) Prinsip ini terkandung dalam Mukaddimah Konvensi Wina Paragraf ketiga yang berbunyi, noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized. Menurut prinsip ini, perjanjian internasional mengikat bagi para pihak dan hanya bagi mereka saja. Para pihak ini tidak bisa membentuk hak ataupun kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut. Aturan ini biasanya disebut asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt dan ditegaskan dalam Pasal 34 Konvensi Wina yang menyebutkan, “A treaty dosen not create either obligations or rights for a third State without its consent.” Lebih lanjut Pasal Pasal 35 menjelaskan jika perjanjian internasional dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi Negara ketiga, dengan syarat memang dimaksudkan untuk itu dan diterima oleh negara ketiga tersebut dengan pernyataan tertulis. Pasal 35 menyebutkan: “An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing.” 54 Chapter Five – Pelaksanaan Perjanjian Internasional Konvensi Wina memberikan beberapa kemungkinan untuk menunjukkan persetujuannya, seprti tanda tangan, pertukaran piagam perjanjian atau naskah perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, aksesi, dan beberapa metode lain yang telah disepakati sebelumnya.33 Sebagai perbandingan, ada juga konstitusi negara yang tidak mengijinkan semua metode atau cara persetujuan yang disebutkan dalam Pasal 11 Konvensi Wina, dalam hal ini Portugal. Konstitusi Portugal hanya memungkinkan persetujuan perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi. Satu-satunya pengecualian terhadap prinsip free consent yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 22 (1) Konvensi Wina yang merupakan perwujudan dari prinsip favor contractus dan terkait dengan penarikan reservasi. Pasal 22 menyebutkan: (1) Unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn at any time and the consent of a State which has accepted the reservation is not required for its withdrawal. Asas lain yang dapat dikurangi dari prinsip free consent adalah asas yang dikenal dalam Bahasa Latin lex posterior derogat legi priori. Berdasarkan asas ini, perjanjian yang lebih baru dapat mengalahkan perjanjian yang terdahulu, bilamana kedua perjanjian tersebut mengatur materi yang sama. Asas ini terkandung dalam Pasal 30 (3) Konvensi Wina, yang menyatakan: … (3) When all the parties to the earlier treaty are parties also to the later treaty but the earlier treaty is not terminated or suspended in operation under Article 59, the earlier treaty applies only to the extent that its provisions are compatible with those of the later treaty.” Asas ini banyak digunakan terhadap perjanjian amademen yang dibuat belakangan. 33 Pasal 11 Konvensi Wina 1969 Chapter Five – Pelaksanaan Perjanjian Internasional 55 Harus dipahami juga bahwa dengan memberikan persetujuan (consent), sebuah negara akan mengikatkan dirinya secara keseluruhan wilayah dan tidak berlaku surut, kecuali maksud dan tujuan perjanjian menyebutkan lain. Pasal 29 menyatakan: “Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory.” Asas ini sering diingatkan dalam ketentuan khusus sebuah perjanjian internasional. Contohnya perjanjian terdahulu sering mengandung ketentuan terkait daerah jajahan, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku pada wilayah nonjajahan, tapi dimungkinkan bagi para pihak untuk memperluas penerapan perjanjian ke wilayah jajahannya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa meskipun prinsip free consent merupakan prinsip utama dalam perjanjian internasional, namun masih ada pembatasanpembatasan terhadap prinsip tersebut. 2. Good Faith (Itikad Baik) Sebagaimana prinsip free consent, prinsip good faith merupakan asas dasar dalam melaksanakan hubungan internasional secara umum dan diakui sebagai prinsip hukum internasional yang fundamental.34 Jika negara-negara tidak memiliki good faith (itikad baik), keamanan dan perdamaian internasional yang merupakan tujuan utama Piagam PBB dapat terancam keberlangsungannya. Dalam sebuah resolusi pada Bulan Juli 2001, Dewan Perlindungan Ikan Paus Internasional yang beranggotakan lebih dari 40 negara menyatakan bahwa itikad baik mensyaratkan adanya keadilan, alasan yang logis, ketulusan, dan kejujuran dalam tingkah laku internasional. Penyalahgunaan hak sangat 34 Lihat Paragraf Ketiga Mukaddimah Konvensi Wina 1969. 56 Chapter Five – Pelaksanaan Perjanjian Internasional berlawanan dengan prinsip itikad baik. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 secara khusus mengatur tentang itikad baik dan penyalahgunaan hak dalam Pasal 300, yang berbunyi: “Negara-negara Peserta harus memenuhi dengan itikad baik (in good faith) kewajiban-kewajiban yang dipikulkan berdasarkan Konvensi ini dan harus melaksanakan hak-hak, yurisdiksi dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Konvensi ini dengan cara yang bukan merupakan suatu penyalahgunaan hak.” Sebagai unsur yang sangat subjektif, keberadaan itikad baik akan sangat sulit untuk dibuktikan. Dalam berbagai analisis untuk menentukan sebuah itikad tersebut baik ataupun jahat, hanya dapat ditemukan dari pikiran seseorang, yang secara khusus memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan politik luar negeri dan orang tersebut ditugaskan untuk menegosiasikan dan menerapkan perjanjian internasional. Berdasarkan Pasal 26 Konvensi Wina, setiap perjanjian yang telah mengikat harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 31(1), menuntut itikad baik dalam penafsiran perjanjian internasional. 3. Pacta Sunt Servanda Dalam menjalankan perjanjian internasional dikenal sebuah prinsip yang sangat penting yaitu pacta sunt servanda, yang maksudnya setiap perjanjian harus ditepati. Prinsip ini sangat mendasar dalam hukum internasional dan menjadi norma imperatif dalam praktik perjanjian internasional. Prinsip ini memastikan bahwa sebuah perjanjian akan ditaati setelah berlakunya. Dalam Pasal 26 Konvensi Wina disebutkan bahwa: “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.” Menurut Paul Reuter, prinsip ini dapat ditafsirkan bahwa: “treaties are what the authors wanted them to be and Chapter Five – Pelaksanaan Perjanjian Internasional 57 only what they wanted them to be and because they wanted them to be the way they are.” Para pihak tidak diijinkan untuk mendasarkan pada ketentuan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk kegagalannya dalam melaksanakan perjanjian. Pasal 27 Konvensi menyebutkan bahwa: “a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.” Satu-satunya pembatasan terhadap prinsip pacta sunt servanda ini adalah ketentuan peremptory norm of general international law atau jus cogens. Pasal 64 Konvensi Wina menyatakan bahwa: “if a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates.” Jelas disini ditentukan bahwa perjanjian akan batal dan dihentikan apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan norma umum hukum internasional yang berlaku. Namun perjanjian tersebut tidak akan batal secara retroaktif atau berlaku surut. Pada perkembangan terakhir, negara-negara mulai menyadari bahwa terdapat perjanjian-perjanjian yang dibuat terkait bidang-bidang tertentu, khususnya dalam bidang pelestarian lingkungan, tidak akan dapat dijalankan dengan sepatutnya oleh negara-negara anggota, walaupun sudah terdapat asas pacta sunt servanda. Hal ini kemudian yang menjadi dasar dimasukkannya kewajiban untuk bekerjasama dalam perjanjian internasional untuk menfasilitasi pelaksanaan perjanjian secara bersama-sama. 4. Rebus Sic Stantibus Menurut prinsip rebus sic stantibus, keadaan yang luar biasa dapat menyebabkan penghentian perjanjian internasional. Beberapa abad terdahulu, ahli berusaha menjelaskan asas ini dengan mengatakan bahwa setiap perjanjian memuat ketentuan secara tersirat bahwa perjanjian akan terus berlanjut sepanjang 58 Chapter Five – Pelaksanaan Perjanjian Internasional keadaannya sama (rebus sic stantibus) dengan kondisi pada saat perjanjian tersebut disetujui. Hal ini tentu saja sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Para pihak tidak terikat lagi dengan perjanjian hanya jika memang telah terjadi sebuah kondisi yang sangat fundamental ketika proses pelaksanaannya. Kondisi ini bisa saja terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu negara pihak terhadap perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 Konvensi Wina.35 Perjanjian juga dapat dihentikan apabila objek yang diperjanjian musnah secara permanen36, ataupun terjadi perubahan kondisi yang sangat fundamental sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dituntaskan.37 Perubahan keadaan yang fundamental juga dapat terjadi karena terjadinya suksesi negara baru, atau timbulnya kewajiban internasional dari negara anggota, atau timbulnya permusuhan di antara sesama negara anggota perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 Konvensi Wina, yaitu: “the provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to atreaty from a succession of States or from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.” Beberapa pakar berpendapat, perubahan kondisi fundamental akan otomatis menghentikan perjanjian. Sedangkan sebagian pakar lagi menganggap bahwa perubahan kondisi hanya akan memberikan pilihan bagi negara untuk meneruskan atau menghentikan perjanjian tersebut. Konvensi Wina pada dasarnya mengadopsi pendapat yang menyatakan bahwa kondisi tersebut hanya memberikan pilihan saja kepada para pihak, tidak otomatis menghentikan perjanjian. 35 36 37 Pasal 60 (1) menyebutkan: “A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as aground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part.” Lihat Pasal 61 Konvensi Wina Lihat Pasal 62 Konvensi Wina. Chapter Five – Pelaksanaan Perjanjian Internasional 59 Namun demikian, kondisi ini tidak dapat dijadikan dasar utama dalam menghentikan perjanjian apabila di dalam perjanjian tersebut telah diatur mengenai kemungkinan terjadinya sengketa bersenjata, seperti pengalaman pada Kasus Konvensi Jenewa 1949 (Konvensi Palang Merah) atau Konvensi Den Hague 1988 dan 1907. Pada konvensi ini telah dimasukkan ketentuan tentang akibat dari konflik bersenjata terhadap perjanjian internasional.38 Berdasarkan Pasal 62 (2)(a), alasan perubahan kondisi yang fundamental tidak dapat diajukan bila terkait perjanjian batas wilayah negara karena apabila hal ini diperbolehkan akan dapat mengancam keamanan dan perdamaian wilayah, serta mengancam integritas dan kedaulatan wilayah sebuah negara, yang juga merupakan asas fundamental dalam hubungan internasional.39 Begitu juga dengan kasus suksesi negara, dimana Konvensi Wina tentang Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional Tahun 1978 telah menegaskan bahwa suksesi negara tidak akan mempengaruhi perjanjian batas wilayah atau ketentuan wilayah lainnya yang telah dihasilkan oleh perjanjian internasional. B. Penafsiran Perjanjian Sebuah pasal yang sudah memiliki arti yang jelas, maka pasal tersebut tidak perlu diinterpretasikan. Namun apabila pasal tersebut masih belum jelas dan terdapat perbedaan penafsiran tentang itu, maka diberi kemungkinan untuk diinterpretasikan. Pasal 31 (1) menyebutkan: “A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty intheir context and in the light of its object and purpose.” Disini persyaratan untuk melakukan penafsiran harus dilakukan dengan itikad baik, dan harus sesuai 38 39 Walter Gehr, the International Law of Treaty, on the internet: www.public-internationallaw.net. 2009. Hlm. 13. Lihat Pasal 2 (4) Piagam PBB. 60 Chapter Five – Pelaksanaan Perjanjian Internasional dengan maksud dan tujuan perjanjian tersebut. Sedikit rancu ketika ada persyaratan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian, karena bila maksud dan tujuan telah diketahui dengan jelas, tentunya tidak diperlukan lagi penafsiran. Agar maksud dan tujuan perjanjian diketahui dengan jelas, tentunya yang berhak untuk menafsirkan perjanjian hanyalah para pihak pembuat perjanjian. Merekalah yang mengerti sekali dengan landasan filosofis, sosiologis, dan politis dari pembuatan perjanjian tersebut. Namun bila interpretasi diharapkan dari pembuat perjanjian saja, akan muncul permasalahan apabila pembuat perjanjian terdiri dari banyak negara dengan banyak pendapat. Untuk itu, diberikan juga kemungkinan bagi hakim internasional untuk menafsirkan sebuah perjanjian, sebagai bentuk penemuan hukum oleh para hakim. Hal ini didukung oleh Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi: “Mahkamah mempunyai wewenang untuk memeriksa sengketa-sengketa yang berkenaan dengan interpretasi suatu perjanjian.” Berdasarkan badan penyelesaian sengketa tinggi WTO, the appellate body, konteks instrumen hukum yang dapat ditafsirkan juga termasuk perjanjian lain yang dilekatkan atau diikutkan oleh para pihak dalam perjanjian induk (utama). Dalam contoh kasus “Standars for Reformulated and Conventional Gasoline”, the appellate body menjelaskan bahwa Marrakesh Agreement tentang pendirian WTO (WTO Agreement) jangan diartikan secara terpisah atau semata-mata masalah perdagangan. Maksudnya, ketentuan perdagangan dalam WTO Agreement juga harus ditafsirkan dalam lingkup perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan ini juga menjadi kewajiban para pihak untuk melaksanakannya. Selain itu juga terdapat cara penafsiran yang dimuat dalam Pasal 32 Konvensi Wina, yaitu: “… including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion,…” Maksudnya, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dalam melakukan penafsiran, apabila penafsiran Chapter Five – Pelaksanaan Perjanjian Internasional 61 yang dilakukan sesuai dengan Pasal 31 belum mendapatkan hasil yang memuaskan atau belum jelas dan masih ambigu. Hal tersebut diantaranya adalah mempertimbangkan proses persiapan pembuatan perjanjian dan juga kondisi pada saat perjanjian tersebut dibuat. Adapun ketentuan yang dapat dilakukan penafsiran adalah naskah atau batang tubuh perjanjian, pembukaan dan ketentuan tambahan, bahkan dokumen dan perjanjian tambahan lain yang terkait dengan perjanjian tersebut. Terhadap naskah perjanjian yang dibuat dalam dua atau lebih bahasa, maka semuanya harus ditafsirkan dalam maksud dan tujuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka harus kembali ditafsirkan sesuai dengan Pasal 31 dan Pasal 32 Konvensi Wina.40 Dan bila hal tersebut juga tidak mendapatkan kesamaan persepsi, maka harus diambil penafsiran yang paling mendekati maksud dan tujuan perjanjian tersebut. Pengaturan mengenai penafsiran tidak diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme penafsiran pada praktiknya lebih merujuk kepada mekanisme Konvensi Wina, sehingga penafsiran lebih banyak diselesaikan melalui kesepakatan para pihak. C. Akibat Perjanjian Internasional Terhadap Negara Ketiga Pada prinsipnya, sebuah perjanjian internasional tidak akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara ketiga, yaitu negara yang tidak termasuk para pihak perjanjian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Konvensi Wina, “A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.” Namun ada beberapa pengecualian terhadap ketentuan umum ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Konvesi. 40 Pasal 33 (4) Konvensi Wina yang berbunyi: “Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of the authentic texts discloses a different of meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove, the meaning which best reconcile the texts, having regard to the object and purpose of the treaty, shall be adopted.” 62 Chapter Five – Pelaksanaan Perjanjian Internasional Pasal 35 dan Pasal 36 menyebutkan bahwa perjanjian internasional dapat memunculkan hak dan kewajiban bagi negara ketiga, atau kelompok negara-negara, atau kepada semua negara, apabila ketentuan dalam perjanjian tersebut memang dimaksudkan untuk itu dan negara ketiga tersebut menyetujuinya. Sedangkan Pasal 37 menyebutkan bahwa terhadap kewajiban yang timbul bagi negara ketiga hanya dapat diubah atau ditarik berdasarkan persetujuan negara peserta dan negara ketiga, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Sedangkan hak yang timbul bagi negara ketiga tidak dapat ditarik atau diubah oleh negara para pihak tanpa persetujuan negara ketiga. Sebagai contoh dapat kita lihat pada Pasal 2 (6) Piagam PBB, yang sering dikatakan dapat diberlakukan pada pihak ketiga yang bukan merupakan negara anggota PBB, tanpa persetujuan mereka. Selengkapnya bunyi Pasal 2 (6) Piagam PBB adalah sebagai berikut: “The organization shall ensure that States which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles [that is, the principles of the United Nations, set out in Article 2 of the Charter] so far as may be necessary for the maintenance of International peace and security.” Pada kenyataannya, Pasal 2 (6) tidak mengandung maksud untuk mewajibkan negara ketiga (bukan anggota PBB), melainkan hanya mengumumkan kebijakan yang akan dijalankan oleh PBB dalam berhubungan dengan negara bukan anggota PBB.