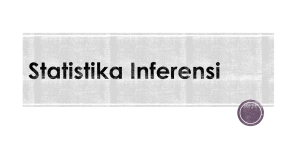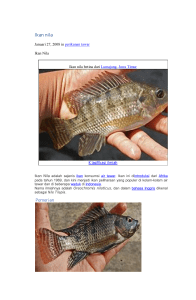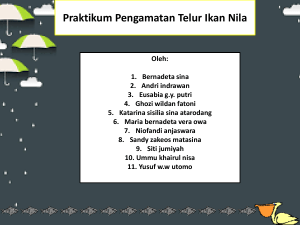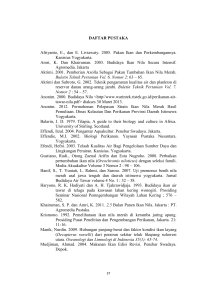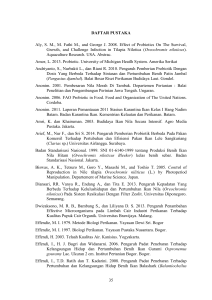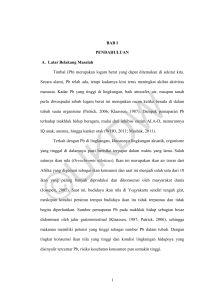Uploaded by
common.user151024
Kajian Teknis dan Analisis Finansial Pembesaran Ikan Nila Kekar Sistem Bioflok
advertisement

KAJIAN TEKNIS DAN ANALISIS FINANSIAL PEMBESARAN IKAN NILA KEKAR (Oreochromis niloticus) SISTEM BIOFLOK DI CV HATCHERY NILA KEKAR RETAIL MALANG , JAWA TIMUR PROPOSAL PRAKTIK LAPANG II Oleh : DEAVCONIA PUTRI EKASARI DEWANTA PRAMAYOGA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA 2024 i KAJIAN TEKNIS DAN ANALISIS FINANSIAL PEMBESARAN IKAN NILA KEKAR (Oreochromis niloticus) SISTEM BIOFLOK DI CV HATCHERY NILA KEKAR RETAIL MALANG, JAWA TIMUR Oleh : DEAVCONIA PUTRI EKASARI DEWANTA PRAMAYOGA NRP 57214213742 Proposal Laporan Praktik Lapang II Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melakukan Praktik Lapang II PROGRAM SARJANA TERAPAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI AKUAKULTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA 2024 ii i KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Praktik Lapang II yang berjudul “Kajian Teknis dan Analisis Finansial Pembesaran Ikan Nila Kekar (Oreochromis niloticus) Sistem Bioflok di CV Hatchery Nila Kekar Retail Malang, Jawa Timur”. Proposal ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk melakukan Praktik Lapang II pada Program Studi Teknologi Akuakultur, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Proposal Praktik Lapang II ini menjadi acuan penulis dalam melakukan Praktik Lapang II. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan proposal ini. Serang, Juli 2024 Penulis i UCAPAN TERIMAKASIH Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Praktik Lapang II ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selama proses penyusunan Proposal Praktik Lapang II ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Erni Marlina, S.Pi., M.Pi dan Bapak Prof. Dr.Sinung Rahardjo, A.Pi., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penyusunan Proposal Praktik Lapang II. Selain itu penulis menyampaikan terima kasih banyak yang sebesarbesarnya khususnya kepada : 1. Dra. Ani Leilani, M.Si. selaku Direktur Politeknik AUP Jakarta; 2. Dr. Heri Triyono, A.Pi., M. Kom. selaku Wakil Direktur I Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta; 3. Dr. Danu Sudrajat, A.Pi., M.AP. selaku Wakil Direktur II Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta; 4. Yenni Nuraini. S.Pi., M.Sc. selaku Wakil Direktur II Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta; 5. Dr. Eng Sinar Pagi Sektiana, S.St.Pi. M.Si. Selaku Ketua Program Studi Teknologi Akuakultur Jakarta; 6. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan yang selalu memberi dukungan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan isi Proposal Praktik Lapang II ini. Semoga Laporan Pratik Lapang II ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang membacanya sebagai ilmu pengetahuan. ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i UCAPAN TERIMAKASIH ............................................................................................... ii DAFTAR ISI ..................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... v DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................... vi 1. PENDAHULUAN .........................................................................................................1 1.1 Latar Belakang ......................................................................................................1 1.2 Tujuan .....................................................................................................................2 1.3 Batasan Masalah ..................................................................................................3 1.4 Manfaat ..................................................................................................................3 2. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................................4 2.1 Biologi Ikan Nila (Oreochromis niloticus) ...........................................................4 2.2 Pra Produksi ..........................................................................................................7 2.3 Proses Produksi ....................................................................................................8 2.4 Pasca Produksi ...................................................................................................12 2.5 Identifikasi Masalah ............................................................................................12 2.6 Analisis Finansial ................................................................................................13 3. METODE PRAKTIK ..................................................................................................15 3.1 Waktu dan Tempat ..............................................................................................15 3.2 Alat dan Bahan ....................................................................................................15 3.3 Metode Pengumpulan Data ...............................................................................16 3.4 Metode Kerja .......................................................................................................18 3.5 Metode Pengolahan Data ..................................................................................21 3.6 Metode Analisis Data ..........................................................................................22 4. RENCANA PRAKTIK ................................................................................................25 4.1 Rencana Kegiatan ..............................................................................................25 4.2 Anggaran Praktik ................................................................................................25 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................26 LAMPIRAN .....................................................................................................................30 iii DAFTAR TABEL 1 Penguikuirain kuiailitais aiir .............................................................................................10 2 AIlait yaing Akan Diguinaikain ........................................................................................15 3 Baihain yaing Akan Diguinaikain ...................................................................................16 4 Daitai Primer .................................................................................................................17 5 Daitai Sekuinder............................................................................................................18 6 Rencainai Kegiaitain .....................................................................................................25 7 AInggarain Praiktik........................................................................................................25 iv DAFTAR GAMBAR 1 Morfologi Ikan Nila (Sumber: Alfira, 2015) ................................................................4 2 Analisis Fishbone (suimber :Irwain Suisainto, 2011) ................................................13 3 Peta Lokasi Praktik ....................................................................................................15 v DAFTAR LAMPIRAN 1 Kesesuaian Lokasi .....................................................................................................30 2 Alat dan Bahan yang Digunakan Untuk Persiapan Wadah ..................................31 3 Kontrol Penyakit .........................................................................................................32 4 Pengecekan Kualitas Air ...........................................................................................33 5 Pengelolaan Pakan ....................................................................................................34 6 Pengukuran Pertambahan Panjang dan Bobot Ikan .............................................35 vi 1 1 1.1 PENDAHULUAN Latar Belakang Negara Indonesia merupakan negara maritim dengan luas perairan kurang lebih 6,4 juta km². Indonesia juga memiliki potensi perikanan, baik laut maupun tawar dan Indonesia memiliki berbagai jenis spesies ikan, salah satu jenis ikan yang banyak digemari untuk dikonsumsi adalah ikan demersal. Ikan demersal yaitu ikan yang hidup dan makan di dasar laut dan danau (zona demersal), dimana secara komersial ikan demersal ini layak untuk diusahakan. Salah satu ikan demersal yang ada di Indonesia adalah ikan nila (Fitri & Rasyid, 2023). Ikan nila sering dijumpai di pasaran dalam bentuk olahan maupun bentuk ikan segar. Perikanan Budidaya di Indonesia merupakan salah satu komponen yang penting disektor perikanan. Hal ini berkaitan dengan perannya dalam menunjang persediaan pangan nasional, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja serta mendatangkan penerimaan negara dari ekspor. Perikanan budi daya juga berperan dalam mengurangi beban sumber daya laut. Disamping itu perikanan budi daya dianggap sebagai sektor penting untuk mendukung perkembangan ekonomi pedesaan. Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu ikan asing asal daratan Cina yang telah lama dibudidayakan di Indonesia, dan banyak diminati oleh masayarakat sebagai ikan konsumsi, sehingga di Indonesia telah dikuasai teknologi pembenihannya (Fradina & Latuconsina, 2022). Ikan nila (Oreochromis niloticus) cukup mudah dibudidayakan dan telah banyak dipelihara oleh masyarakat secara tradisional untuk dikonsumsi keluarga. Keunggulan ikan nila antara lain mudah dikembangbiakan dan kelangsungan hidup tinggi, pertumbuhan relatif cepat dengan ukuran badan relatif besar, serta tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan Sallata, (2015) dalam Sutrisno, (2019). Ikan Nila (Oreochoromis niloticus) juga cukup potensial untuk dibudidayakan karena memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya Mulyani, (2017) dalam (Cahyati et al., 2022). Salah satu varietas unggul dari ikan nila adalah ikan nila kekar. Ikan nila kekar sendiri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan varietas nila lainnya, yang membuatnya menjadi pilihan utama dalam budidaya ikan. Keunggulan utama dari ikan nila kekar adalah pertumbuhannya yang lebih cepat dan lebih efisien dalam konversi pakan dibandingkan dengan varietas nila lainnya. Hal ini berarti bahwa ikan nila kekar dapat mencapai ukuran panen dalam waktu yang lebih singkat, sehingga meningkatkan produktivitas budidaya. Selain itu, ikan nila kekar juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit, yang merupakan faktor penting dalam mengurangi tingkat kematian ikan dan meningkatkan hasil panen. Keunggulan ini didukung oleh struktur tubuh yang lebih kuat dan daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan yang berfluktuasi (Limbong et al., 2018). Usaha pembesaran ikan termasuk dalam pengendalian pertumbuhan. Budi daya ikan bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi atau lebih banyak dan lebih baik daripada bila ikan tersebut dibiarkan hidup secara alami sepenuhnya. Beberapa teknik dalam pembudidayaan ikan pun dikembangkan 2 untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan perikanan yang tersedia. Teknik-teknik pembudidayaan ikan yang dikenal di Indonesia antara lain pembudidayaan ikan di kolam air deras, kolam air tenang, bioflok dan karamba (Rahayu, 2011). Ikan nila merupakan spesies budidaya yang dikenal luas di masyarakat dan telah menjadi andalan komoditas perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan ekspor komoditas perikanan. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang dapat diproduksi secara massal dan mudah. Selain itu produk daging ikan nila dalam bentuk filet sangat diminati pasar dunia, sehingga memiliki pasar ekspor yang luas di tingkat internasional Farman, (2010) dalam (Rahmatillah et al., 2018). Hatchery Nila Kekar di Retail Malang menghadapi berbagai permasalahan dalam pembesaran ikan nila yang berdampak pada produktivitas dan efisiensi operasional. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi fluktuasi kualitas air yang tidak stabil, seperti perubahan suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut, yang dapat mempengaruhi kesehatan ikan (Suryono et al., 2019). Selain itu, kepadatan tebar yang berlebihan menyebabkan persaingan ketat untuk pakan dan oksigen, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit (Primyastanto, 2011). Manajemen pakan yang kurang efisien dan infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi kendala signifikan dalam mendukung pertumbuhan optimal ikan nila (Carman & Sucipto, 2013). Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya peningkatan manajemen dan teknologi untuk memastikan keberhasilan pembesaran ikan nila di Hatchery Nila Kekar. Pemilihan lokasi untuk pembesaran ikan nila di Hatchery Nila Kekar di Retail Malang sangat penting untuk memastikan keberhasilan budidaya. Lokasi ini dipilih karena ketersediaan air bersih yang melimpah serta kondisi tanah yang sesuai untuk konstruksi tambak, yang merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan ikan (Sumanto, 2017). Selain itu, aksesibilitas yang baik ke fasilitas distribusi dan pasokan pakan juga menjadi pertimbangan utama untuk mendukung efisiensi operasional dan pengelolaan yang efektif (Sugiarto, 2016). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Hatchery Nila Kekar dapat memanfaatkan potensi lokasi tersebut untuk mencapai hasil pembesaran yang optimal dan berkelanjutan. Dengan adanya upaya untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam budi daya dan meningkatkan hasil produksi, kegiatan pembesaran ikan nila dapat dioptimalkan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat topik yang berfokus pada analisis teknis dan finansial dalam pembesaran ikan nila. Oleh karena itu, pada kegiatan Praktik Lapang II, penulis memilih judul "Kajian Teknis dan Analisis Finansial Teknik Pembesaran Ikan Nila Kekar (Oreochromis niloticus) Sistem Bioflok di CV Hatchery Nila Kekar Retail Malang, Jawa Timur" untuk mengevaluasi secara mendalam aspek-aspek teknis dan ekonomi dari pembesaran ikan nila di lokasi tersebut. 1.2 1) Tujuan Tujuan pelaksaan Praktik Lapang II ini adalah sebagai berikut : Mengkaji aspek teknis dalam pengembangan ikan nila (Oreochromis niloticus) di CV Hatchery Nila Kekar Retail. 3 2) Menganalisis kinerja budidaya dalam pengembangan ikan nila (Oreochromis niloticus) di CV Hatchery Nila Kekar Retail. 3) Menganalisis aspek finansial dalam usaha pengembangan ikan nila (Oreochromis niloticus) meliputi biaya produksi, analisis laba/rugi, R/C Ratio, Break Event Point (BEP) dan Payback Period (PP) di CV Hatchery Nila Kekar Retail. 4) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam proses pembesaran Ikan Nila dan menyusun usulan inteversi. 1.3 Batasan Masalah Batasan masalah dalam praktik yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut: 1. Aspek teknis dari pengembangan ikan nila (Oreochromis niloticus) yang terdiri dari tahapan pra produksi, produksi, dan pasca produksi. 2. Aspek kinerja yang dianalisis dalam pengembangan ikan nila, termasuk biomassa, tingkat kelangsungan hidup ikan (Survival Rate), rasio konversi pakan (Food Conversion Ratio), berat rata-rata (Average Body Weight), dan pertambahan berat harian rata-rata (Average Daily Growth). 3. Analisis finansial dalam usaha pembesaran ikan nila (Oreochromis niloticus) yang mencakup biaya investasi, biaya produksi, analisis raba/rugi, Rasio Biaya/Pendapatan (R/C Ration), Titik Impas (Break Even Point), dan Periode Pengembalian Modal (Payback Period). 4. Identifikasi masalah dengan metode Fishbone yang dilakukan pada penerapan 4M yaitu Men, Methode, Machine,dan Material. 1.4 Manfaat 1. Dapat memperoleh gambaran secara langsung tentang lingkungan kerja serta meningkatkan pengetahuan dan mempraktikkan secara langsung bagaimana cara pembesaran ikan nila yang berkualitas. 2. Menambah wawasan terhadap masalah-masalah di lapangan dan membandingkan dengan teori yang telah didapat selama perkuliahan dengan praktik produksi dilapangan usaha perikanan pembesaran. 4 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 A. Biologi Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Klasifikasi dan Morfologi Ikan Nila Menurut (Saanin, 1984) ikan nila ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Kingdom : Animalia Filum : Chordata Sub Filum : Vertebrata Kelas : Osteichyes Sub Kelas : Acanthopterygii Ordo : Percomorphi Sub ordo : Percoidae Famili : Cichlidae Genus : Oreochromis Spesies : Oreochromis niloticus Adapun gambar morfologi ikan nila (Oreochromis niloticus) dapat dilihat pada gambar 1. Gambar 1 Morfologi Ikan Nila (Sumber: Alfira, 2015) Secara umum ikan nila mempunyai bentuk tubuh panjang dan ramping, dengan sisik berukuran besar, matanya besar, menonjol dan bagian tepinya berwarna putih, gurat sisi (linea literalis) terputus dibagian tengah badan kemudian sirip dubur lanjut, tetapi letaknya kebawah dari telaknya yang memanjang diatas sirip dada, jumlah sisik dan sirip dubur mempunyai jari-jari lemah tetap keras dan tajam seperti duri. Sirip punggungnya berwarna hitam dan sirip dadanya juga tampak hitam. Bagian pinggir sirip punggung berwarna abu-abu atau hitam (Khairuman & Amri, 2005a). Ikan nila memiliki lima buah sirip, yaitu sirip punggung (dorsal fin), sirip dada (pectoral fin), sirip perut (venteral fin), sirip anus (anal fin), dan sirip ekor (caudal fin). Sirip punggung, sirip perut, dan sirip dubur mempunyai jari-jari lemah tetapi keras dan tajam seperti duri. Sirip punggung memanjang dan bagian atas tutup insang hingga bagian atas sirip ekor, dan berwarna hitam sirip dada ada sepasang dan tampak hitam sirip perut berukuran kecil, sirip anus dan sirip ekor ada satu buah, sirip anus berbentuk agak panjang sedangkan sirip ekor berbentuk bulat bagian pinggir sirip punggung berwarna abu-abu atau hitam (Suryam, 2006). i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 5 Jika dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, ikan nila jantan memiliki ukuran sisik yang lebih besar dari pada ikan nila betina. Alat kelamin ikan nila jantan berupa tonjolan agak runcing yang berfungsi sebagai muara urine dan saluran sperma yang terletak di depan anus. Jika diurut, perut ikan nila jantan akan mengeluarkan cairan bening. Sementara itu, ikan nila betina mempunyai lubang genital terpisah dengan lubang saluran urine yang terletak di depan anus. Bentuk hidung dan rahang belakang ikan nila jantan melebar dan berwarna biru muda. Pada ikan betina, bentuk hidung dan rahang belakangnya agak lancip dan berwarna kuning terang. Sirip punggung dan sirip ekor ikan nila jantan berupa garis putus-putus. Sementara itu, pada ikan nila betina, garisnya berlanjut (tidak terputus) dan melingkar (Khairuman & Amri, 2005a). Ikan nila dapat dipindahkan ke air asin dengan proses adaptasi yang bertahap kadar garam air dinaikkan sedikit demi sedikit Pemindahan ikan nila secara mendadak ke air yang kadar garamnya sangat berbeda dapat mengakibatkan stres dan kematian ikan (Suryani, 2006). B. Habitat Ikan Nila Ikan nila (Oreochromis niloticus) adalah spesies ikan air tawar yang berasal dari wilayah tropis dan subtropis. Habitat alami ikan nila meliputi sungai-sungai, danau-danau, rawa-rawa, dan tambak-tambak. Mereka lebih cenderung hidup di perairan yang tenang dengan sedikit aliran air. Ikan nila memilih habitat yang memiliki perairan hangat dengan suhu berkisar antara 25°C hingga 30°C. Substrat di habitat alami ikan nila dapat berupa lumpur, pasir, atau campuran keduanya, dan seringkali terdapat vegetasi air yang cukup untuk melindungi dan menyediakan makanan bagi mereka. Selain itu, ikan nila juga sering dibudi dayakan di kolam-kolam budi daya dengan kondisi air yang terkontrol. Dalam semua spesies Oreochromis, jantan menggali sarang di dasar kolam (umumnya di perairan dangkal dari 3 kaki) dan kawin dengan beberapa betina. Setelah ritual kawin singkat, betina bertelur di sarang (sekitar dua hingga empat telur per gram induk betina), jantan membuahi telur, dan kemudian memegang dan mengerami telur di mulutnya (rongga bukal) sampai menetas. Benih ikan (benur) tetap berada di mulut betina melalui penyerapan kantung kuning telur dan sering berlindung di mulutnya selama beberapa hari. Kematangan seksual pada ikan nila adalah fungsi dari usia, ukuran dan kondisi lingkungan. Ikan nila mencapai kematangan seksual pada ukuran yang lebih kecil dan usia yang lebih muda daripada tilapia (Dailami et al., 2021). Populasi nila di danau besar menjadi dewasa pada usia yang lebih tua dan ukurannya lebih besar dari spesies yang sama yang dibesarkan di kolam pertanian kecil. Misalnya, ikan nila matang sekitar 10 sampai 12 bulan dan 3/4 sampai 1 pon (350 sampai 500 gram) di beberapa danau Afrika Timur. Dalam kondisi pertumbuhan yang baik spesies yang sama isi akan mencapai kematangan seksual di kolam pertanian pada asia 5 sampai 6 bulan dan 5 sampai 7 ons (150 sampai 200 gram). Ketika pertumbuhan lambat, kematangan seksual pada ikan nila nila tertunda satu atau dua bulan tetapi ikan kerdil dapat bertelur dengan berat kurang dari 1 ons (20 gram). Dalam kondisi pertumbuhan yang baik di kolam, nila Mozambik dapat mencapai kematangan seksual hanya dalam usia 3 bulan, ketika beratnya jarang lebih dari 2 hingga 4 ons (60 hingga 100 gram). Di kolam yang i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 6 tidak dibuahi dengan baik, ikan nila Mozambik yang dewasa secara seksual mungkin berukuran 1/2 ons (15 gram) (Dailami et al., 2021). C Kebiasaan Makan Ikan Nila Ikan nila termasuk dalam kelompok ikan pemakan segala atau omnivora, sehingga memiliki kemampuan untuk mengonsumsi makanan berupa hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, ikan ini mudah untuk dibudidayakan. Pada tahap benih, ikan nila cenderung mengonsumsi zooplankton (plankton hewani), seperti Rotifera sp., Moina sp., dan Daphnia sp. Selain itu, mereka juga memakan alga atau lumut yang melekat pada benda-benda di lingkungan tempat tinggalnya. Ikan nila juga akan mengonsumsi tanaman air yang tumbuh di dalam kolam budidaya. Setelah mencapai ukuran dewasa, ikan nila bisa diberikan berbagai jenis makanan tambahan, seperti Pelet (Anonimo, 2010). Selanjutnya menurut (Sugiarto, 2016), ikan nila (Oreochromis niloticus) dewasa memiliki kemampuan mengumpulkan makanan diperairan dengan bantuan lendir (mucus) dalam mulut, makanan tersebut membentuk gumpalan partikel sehingga tidak mudah keluar. Fungsi utama pakan adalah sebagai penyedia energi bagi aktifitas sel-sel tubuh. Karbohidrat, lemak dan protein merupakan zat gizi yang terdapat dalam pakan yang berfungsi sebagai energi tubuh. Protein bersama dengan mineral dan udara merupakan bahan baku utama dalam pembentukan sel-sel dan jaringan tubuh, sedangkan protein bersama-sama dengan mineral dan vitamin berfungsi dalam pengaturan keseimbangan asam basah, pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh, serta pengaturan proses metabolisme dalam tubuh. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ikan dalam budi daya di kolam maupun wadah lainnya adalah melalui penggunaan pakan buatan, khususnya ketika pakan alami sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan nutrisi ikan yang dipelihara (Wardhani et al., 2011). Pakan yang dimakan ikan berasal dari alam (disebut pakan alami) dan dari buatan manusia (disebut pakan buatan). D Reproduksi Ikan Nila Secara alami, ikan nila memiliki kemampuan untuk memijah sepanjang tahun, terutama di daerah tropis. Namun, frekuensi pemijahan yang paling tinggi terjadi pada musim hujan. Di habitat aslinya, ikan nila dapat melakukan pemijahan sebanyak 6-7 kali dalam setahun, yang berarti rata-rata setiap dua bulan sekali. Proses pemijahan ini umumnya dimulai ketika ikan nila mencapai stadium dewasa pada usia 4-5 bulan dengan berat sekitar 250 gram. Masa pemijahan produktif biasanya terjadi ketika induk berusia 1,5-2 tahun dengan berat di atas 500 gram per ekor. Sebuah ikan nila betina dengan berat sekitar 800 gram dapat menghasilkan sekitar 1.200-1.500 ekor larva pada setiap pemijahan (Khairuman & Amri, 2005a). Sebelum memijah, ikan nila jantan cenderung membuat sarang yang berupa lekukan bulat di dasar perairan. Diameter lekukan tersebut sebanding dengan ukuran tubuh ikan nila jantan, dan fungsi utamanya adalah sebagai daerah teritorial bagi ikan nila jantan. Ketika dalam masa kawin, ikan nila jantan akan menunjukkan perilaku yang agresif dan secara tegar mempertahankan daerah teritorialnya tersebut. Sarang ini kemudian berfungsi sebagai tempat pemijahan dan pembuahan telur (Khairuman & Amri, 2005a). i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 7 Proses pemijahan ikan nila berlangsung dengan sangat cepat, di mana dalam waktu 50-60 detik, ikan nila dapat menghasilkan 20-40 butir telur yang telah dibuahi. Proses pemijahan ini dapat terjadi beberapa kali dengan pasangan yang sama atau berbeda, dan keseluruhan proses pemijahan biasanya memakan waktu 20-60 menit. Telur ikan nila memiliki diameter sekitar 2,8 mm, biasanya berwarna abu-abu atau kadang-kadang kuning, tidak lengket, dan cenderung tenggelam di dasar perairan. Setelah dibuahi, telur-telur ini akan dijemur di dalam mulut induk betina dan menetas setelah 4-5 hari. Telur yang sudah menetas disebut larva, yang pada awalnya memiliki panjang sekitar 4-5 mm. Larva yang baru menetas akan dirawat oleh induk betina hingga mencapai usia 11 hari dan memiliki ukuran sekitar 8 mm. Setelah tidak dirawat lagi oleh induknya, benih akan berkumpul dan berenang bersama di bagian perairan yang dangkal atau di pinggiran kolam (Khairuman & Amri, 2005a) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 2.2 A. Pra Produksi Pemilihan Lokasi Lokasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha pembenihan yang mengandung faktor pendukung dan faktor pembatas. Beberapa faktor pendukung (non teknis) yaitu kemudahan pencapaian, kemudahan mendapatkan sumber energi listrik (PLN), kedekatan dengan lokasi budidaya dan pasar benih, serta kemudahan memperoleh kebutuhan sehari hari. Sementara faktor pembatasnya antara lain ialah ketersediaan air tawar, status lahan dan keamanan (Hastari et al., 2017). B. Persiapan Wadah Persiapan wadah budi daya tambak melibatkan serangkaian langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dan produksi hasil budidaya. Pertama-tama, pemilihan lokasi yang tepat sangatlah penting. Lokasi tambak haruslah memenuhi persyaratan seperti ketersediaan air yang cukup, tanah yang sesuai untuk konstruksi tambak, dan aksesibilitas yang baik (Sumanto, 2017). Selanjutnya, persiapan tanah dan pembangunan infrastruktur tambak menjadi tahap berikutnya. Ini meliputi pembersihan dan persiapan tanah, pembuatan saluran air, dan konstruksi tanggul. Infrastruktur tambak harus dirancang dan dibangun dengan baik untuk memastikan sirkulasi air yang baik, pengendalian air yang efektif, dan keamanan tanggul (Subagja et al., 2020). Setelah infrastruktur tambak selesai dibangun, langkah selanjutnya adalah pengisian air dan persiapan kualitas air yang sesuai. Air tambak harus memiliki kualitas yang baik untuk mendukung pertumbuhan organisme budi daya, seperti suhu yang sesuai, pH yang stabil, dan kadar oksigen yang cukup. Pengukuran dan pemantauan secara teratur terhadap parameter-parameter kualitas air sangatlah penting untuk menjaga kondisi lingkungan yang optimal (Suryono et al., 2019). Terakhir, persiapan wadah budi daya tambak juga melibatkan pemilihan dan penebaran bibit atau benih budidaya yang sesuai. Penebaran benih harus dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan jumlah yang tepat dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Selain itu, pemilihan bibit yang unggul secara genetik juga dapat meningkatkan produktivitas tambak. Tahapan persiapan budi daya ikan nila yaitu pengeringan, pembuangan lumpur, pengapuran, pemupukan dasar (Dharmaji et al., 2017). i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 8 C. Persiapan Media Kegiatan pertama yang perlu dilakukan dalam pembesaran ikan nila adalah persiapan kolam. Salsabila et al., (2018) mengatakan bahwa persiapan kolam pembesaran terdiri dari pengeringan tanah, pembalikan tanah, pengapuran tanah dan pengisian air. Wadah pemeliharaan dapat berupa tanah atau dinding beton dengan dasar tanah atau lumpur. Proses pengeringan bertujuan untuk mengurangi kelembapan tanah dan membunuh organisme berbahaya seperti patogen dan parasit yang dapat mengganggu kesehatan ikan (Andriyanto et al., 2013). Pengeringan dilakukan dengan membiarkan kolam tanpa air selama beberapa hari hingga tanah benarbenar kering. Pengapuran bertujuan untuk menstabilkan pH tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara, dan mengendalikan patogen (Salsabila et al., 2018). Kapur membantu dalam memperbaiki kondisi kimia tanah sehingga lebih mendukung pertumbuhan plankton yang menjadi sumber pakan alami bagi ikan. Tahap berikutnya adalah pemupukan yang bertujuan untuk mempersubur kondisi air dan menghidupkan organisme seperti plankton sebagai pakan alami bagi ikan. Tahap akhir pada persiapan kolam adalah pengisian kolam dengan air. Setelah kolam diisi, biasanya dibiarkan selama beberapa hari agar mikroorganisme dan plankton dapat berkembang, sehingga menyediakan pakan alami bagi ikan yang akan ditebar serta diharapkan kondisi lingkungan menjadi lebih stabil (Salsabila et al., 2018). 2.3.1 Proses Produksi A. Penebaran Benih Penebaran benih dapat dilakukan setelah melalui tahap seleksi benih. Sebelum benih ditebar, perlu memperhatikan padat tebar dengan kapasitas kolam pemeliharaan. Menurut SNI (2009) padat tebar benih ikan nila pada budidaya di kolam adalah 100 ekor/m² dan pada ukuran larva dan 25-50 ekor/m² pada kisaran ukuran 3-5 cm. Padat tebar menjadi faktor penting dalam pemeliharaan ikan yang akan berdampak terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan (segarati, 2014). Menurut (Arzad et al., 2019) padat tebar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam perairan, jika oksigen terlarut berkurang, ikan dapat mengalami stres atau bahkan kematian. Penebaran benih dilakukan pada pagi atau sore hari saat suhu udara rendah. Tujuannya untuk menghindari terjadinya stres pada benih. Sebelum dilakukan penebaran benih, sebaiknya dilakukan seleksi benih guna menjaga keseragaman ukuran benih dan mengetahui kondisi kesehatan benih. Ciri – ciri benih yang sehat adalah tubuhnya berwarna cerah, gerakan lincah dan gesit, serta responsif terhadap makanan. Padat tebar benih tergantung dari ukuran benih yang ditebar atau berdasarkan target panen yang akan dicapai (Salsabila et al., 2018). Benih ikan nila yang akan ditebar di petakan pembesaran di aklimatisasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan suhu di lingkungan baru. Peralatan dan bahan yang digunakan antara lain plastik, air, dan oksigen (Salsabila et al., 2018). B. Manajemen Pakan Salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan mortalitas ikan yang dipelihara adalah faktor ketersediaan pakan yang cukup. Jumlah pakan yang diberikan tergantung pada ukuran ikan yang dipelihara, mengingat ikan i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 9 berkembang setiap hari, maka penambahan perlu dilakukan setiap 15 hari sekali berdasarkan hasil pengamatan pertumbuhan (Iskandar & Elrifadah, 2015). Rochdianto, (2004) menyatakan, agar cepat tumbuh besar selama pemeliharaan, maka ikan harus selalu diberi pakan bergizi tinggi dengan kandungan protein diatas 20%. Untuk memenuhi persyaratan pakan bergizi tinggi ini, kita dapat memanfaatkan pakan bergizi tinggi ini, kita dapat memanfaatkan pakan berupa pellet yang banyak tersedia di pasaran. Setiap hari, ikan yang dipelihara diberi pelet sebanyak 3 kali pagi, siang, sore hari. Bila jumlah pakan yang diberikan setiap hari sejumlah 3%, maka porsi pemberian itu dibagi tiga untuk pemberian pada pagi, siang, dan sore hari. Masing-masing porsinya 1%. Pemberian pakan ini hendaknya sedikit demi sedikit sesuai dengan nafsu makan ikan. Agar tidak hanyut terbuang, maka cara pemberian pakan sebaiknya disebarkan dibagian tengah kantong jaring. Pakan ikan untuk ikan nila dalam bak beton harus bermutu. Menurut Puslitbangkan (1992) dalam (Sunarto & Sabariah, 2009), pakan untuk ikan nila yang dipelihara dalam bak beton haruslah pelet terapung. Pakan yang tenggelam kurang efisien karena banyak yang tidak termakan. pakan yang baik harus mempunyai derajat konversi (FCR) antara 1,2-1,8. Artinya 1,2-1,8 kg pakan dapat menjadi 1 kg ikan. Berat konversi pakan dipengaruhi oleh kesuburan perairan karena ikan nila juga memakan plankton yang ada di perairan tersebut (Suryanto, 2011). Odang Carman, (2013) menyatakan, dosis yang dianjurkan dalam pemberian pakan nila disesuaikan dengan ukuran ikan, suhu air, kepadatan biomas ikan dan kelimpahan pakan alami. Seperti halnya dengan ikan lainnya, dosis pemberian pakan maksimum yang diberikan berbanding terbalik dengan ukuran ikan. Carman & Sucipto, (2013) juga menyatakan, jumlah pakan yang dibutuhkan ikan setiap harinya berhubungan erat dengan berat dan umurnya, rata rata jumlah pakan harian yang dibutuhkan oleh seekor ikan adalah sekitar 3-5 % dari berat total badannya. C. Pengelolaan Kualitas Air Odang Carman, (2013) menyatakan, air merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika akan memilih lokasi usaha pembesaran nila. Terkait dengan air, hal yang perlu diperhatikan adalah sumber air dan kualitas. Dalam budi daya ikan, secara umum kualitas air dapat diartikan sebagai setiap perubah (variabel) yang mempengaruhi pengelolaan, kelangsungan hidup, dan produktivitas ikan yang memenuhi syarat bagi kehidupan dan pertumbuhan ikan yang kita budi dayakan. Kualitas air disini meliputi sifat kimia dan fisika yang dinyatakan dalam kisaran angka (Rochdianto, 2005). Adapun tabel pengukuran kualitas air bisa dilihat di tabel 1. i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 10 Tabel 1 Pengukuran kualitas air i i i i i i i i No Parameter 1 Suhu 2 pH 3 Oksigen terlarut (DO) 4 Amoniak (NH3) 5 Nitrit (NO2) 6 Nitrat (NO3) Sumber : (SNI 7550:2009) i Satuan º mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 i i i i i I i i i Kisaran 25 – 32 6,5 – 8,5 ≥3 < 0,02 ≤ 0,06 ≤3 i i i i Suhu Suhu air adalah parameter fisika yang dipengaruhi oleh kecerahan dan kedalaman. Air yang dangkal dan daya tembus cahaya matahari yang tinggi dapat meningkatkan suhu perairan. Parameter suhu untuk kelangsungan hidup ikan nila yaitu 25 - 32°C. Adanya peningkatan suhu pada air media pemeliharaan diduga disebabkan oleh penempatan wadah pemeliharaan. Berdasarkan (Effendi, 2003), bahwa cahaya matahari yang masuk ke perairan akan mengalami penyerapan dan perubahan energi panas. Sehingga wadah pemeliharaan terpapar langsung pada sinar matahari dan mengakibatkan nilai suhu air media pemeliharaan mengalami perubahan pada pagi hari, siang, dan sore hari. Peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, evaporasi, dan volansiasi. Peningkatan suhu ini disertai dengan penurunan kadar oksigen terlarut sehingga keberadaan yang digunakan untuk melakukan proses metabolisme dan respirasi ikan mengalami kerentangan terhadap penyakit pada suhu yang kurang optimal. Fluktuasi suhu yang terlalu besar akan membuat stres yang akan mengakibatkan kematian pada ikan (Gery Purnomo, 2020) 2) Oksigen Terlarut (DO) Arisya et al., (2013) menyatakan, oksigen terlarut (DO) adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorbsi atmosfer/udara. Penyebab utama berkurangnya oksigen terlarut di dalam air adalah adanya bahan-bahan buangan organik yang banyak mengkonsumsi oksigen sewaktu penguraian berlangsung 0,0– 15,0 mg.l-1. Kandungan oksigen terlarut SNI ≥3 mg.l-1. Konsentrasi oksigen terlarut yang aman bagi kehidupan di perairan sebaiknya harus diatas titik kritis dan tidak terdapat bahan lain yang bersifat racun, konsentrasi oksigen minimum sebesar 2 mg.l-1 cukup memadai untuk menunjang sacara normal komunikasi akuatik di perairan. Kandungan oksigen terlarut untuk menunjang usaha budidaya adalah 5–8 mg.l-1. 3) Potential of Hydrogen (pH) (Khairuman & Amri, 2005b) menyatakan, derajat keasaman atau lebih popular di sebut pH (power of Hydrogen) merupakan ukuran konsentrasi ion hydrogen yang menunjukan suasana asam atau basa maupun perairan. Kisaran pH adalah 6,5–8,5. Keasaman (pH) yang tidak optimal dapat menyebabkan ikan stress, mudah terserang penyakit, produktivitas dan pertumbuhan rendah. Umumnya, pH air tambak pada siang hari lebih tinggi daripada pagi hari. Penyebabnya yaitu adanya kegiatan fotosintesis oleh pakan alami, seperti 1) i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 11 fitoplankton yang menyerap CO2. Perbaikan nilai pH yang kurang optimal dapat dilakukan dengan aplikasi pengapuran pada saat masa pemeliharaan. 4) Nitrit, Nitrat dan Amonia Rostro et al. (2014) dalam (Ombong & Salindeho, 2016) bahwa konsentrasi NO3-N pada bioflok sebaiknya tidak melebihi 10.0 mg.l-1. Batas maksimal yang dianjurkan yaitu 30 mg.l-1 (Oktavia et al., 2012). Namun menurut Taw, (2014) peningkatan kandungan nitrat sampai 40 mg.l-1 tidak membahayakan bagi organisme kultur. Konsentrasi Nitrat dalam medium kultur ikan bersirip berada dibawah 100 mg.l-1 (Forteath, 1993). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Avnimelech (2009) dalam (Al., 2023), pola fluktuasi yang terjadi pada konsentrasi amonia sangat dipengaruhi oleh paramater suhu dan pH di mana hal ini berkaitan dengan perombakan bahanbahan organik yang terjadi di dalam bak pemeliharaan. (Radhiyufa, 2011), menjelaskan amoniak akan membentuk kesetimbangan antara bentuk tosik (NH3) dan partikel amonium non toksik (NH4+) yang masih dapat dimanfaatkan dalam pertumbuhan fitoplankton. Menurut (Effendi, 2003), kadar amonia di perairan alami biasanya kurang dari 0,1 mg.l-1, namun menurut (Hoffman, 2010), Amonia-N bersifat toksik pada ikan kultur jika konsentrasinya sudah berada di atas 1,5 mg.l-1. Sementara itu konsentrasi amonia pada perlakuan bioflok menunjukan nilai yang masih bisa ditoleransi oleh ikan. D. Hama dan Penyakit Dalam budidaya ikan, sesuatu hal yang rawan dan tidak diharapkan kehadiran adalah datangnya hama dan penyakit. Hingga saat ini, memang belum pernah terdengar kabar tentang usaha budidaya ikan dalam kantong jaring terapung terhenti gara gara serangan hama penyakit (Rochdianto, 2005) a) Hama Susanto, (2012) menyatakan, hama adalah organism pengganggu yang dapat memangsa, membunuh dan memengaruhi produktivitas, baik secara langsung ataupun bertahap. Hama ini berasal dari aliran air masuk, baik udara maupun darat. Hama dapat berupa predator (pemangsa), kompetitor (penyaing), dan perusak sarana. Untuk menanggulangi serangan hama, sebaiknya lebih menekankan pada sistem pengendalian hama terpadu, yaitu pemberantasan hama yang berhasil, tetapi tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem. Dengan kata lain, apabila masih ada cara yang dapat dilakukan dan ternyata memberikan hasil baik maka tidak perlu menggunakan obat-obatan apalagi pestisida organik. Berikut ini adalah hama yang biasa menyerang ikan nila adalah kodok, ular, biawak, dan burung. b) Penyakit Susanto, (2012) menyatakan, penyakit merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi dalam usaha budidaya ikan. Penyakit ikan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penyakit ikan nila dapat disebabkan oleh faktor lingkungan dan keadaan yang tidak menyenangkan. Penanggulangan yang paling baik dan efektif adalah dengan cara memberikan kondisi air yang baik pada perairan tersebut. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 12 Pencegahan minimal dapat dilakukan dengan cara : 1) Hindari penebaran ikan secara berlebihan atau melebihi kapasitas. 2) Berikan pakan secukupnya dan perhatikan kualitas dan maupun kuantitasnya. 3) Hindari pakan yang sudah berjamur. 4) Pisahkan ikan yang sudah terlanjur sakit dari ikan yang lain Rochdianto, (2004) menyatakan penyakit terbagi dua yaitu pertama penyakit nonparasit diantaranya adalah : pembalikan lapisan air, kekurangan oksigen, dan keracunan yang kedua adalah penyakit parasit diantaranya adalah kutu ikan, jamur, bintik putih dan bakteri. 2.4.1 Pasca Produksi A. Panen Ikan dipanen setelah 3 bulan masa pemeliharaan atau setelah mencapai ukuran konsumsi. Ikan yang sudah mencapai ukuran konsumsi yang sesuai dengan permintaan pasar panen. Petakan yang akan dipanen airnya dikurangi terlebih dahulu secara perlahan dan bertahap. Setelah air surut, ikan diambil dengan menggunakan seser, yaitu menggunakan jaring yang dipegang oleh minimal 2 orang. Ikan yang sudah terambil dimasukkan ke dalam bak penampung. Tujuan ikan dimasukkan ke dalam bak penampung adalah untuk menjaga ikan tetap segar hingga saat di packing (Salsabila et al., 2018) Pemanenan ikan nila dapat dilakukan menggunakan dua metode yaitu panen total dan panen selektif (sebagian). Panen total dilakukan dengan cara mengeringkan petakan, hingga ketinggian air tinggal 10 cm. Petak pemanenan/petak penangkapan dibuat seluas m2 di depan pintu pengeluaran, sehingga memudahkan dalam penangkapan ikan. Pemanenan dilakukan di pagi hari saat keadaan tidak panas dengan menggunakan waring atau scoopnet yang halus. Lakukan pemanenan secepatnya dan hati-hati untuk menghindari lukanya ikan. Panen selektif dilakukan tanpa pengeringan petakan, ikan yang akan dipanen dipilih dengan ukuran tertentu. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan waring yang diatasnya telah ditaburi umpan (pellet) (Khairuman & Amri, 2005a). B. Pasca Panen Pasca panen merupakan proses akhir dari rangkaian kegiatan budidaya. Pasca panen bertujuan untuk menjamin mutu ikan tetap tinggi. Pasca panen yang dimaksud adalah pengemasan dan pemasaran. Pemasaran secara khusus adalah tahapan terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomi serta produsen melalui pedagang kepada para konsumen. Proses pemasaran memiiki fungsi yang harus ditampung baik oleh para pihak produsen maupun lembaga lembaga atau mata rantai penyaluran produk. Apabila produksinya mendapat harga marginal yang baik, maka harus ada konsistensi agar produk tersebut selalu dalam keadaan imbang di pasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk mencari atau berusaha agar produk yang telah dihasilkan dapat dipasarkan ke konsumen dengan harga sesuai dan mendapat keuntungan (Syakhabyatin, 2019). 2.5 Identifikasi Masalah Metode yang digunakan dalam identifikasi masalah yaitu menggunakan metode Fishbone analisis. Menurut (Murnawan & Mustofa, 2014) selain i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 13 menggunakan metode quality control secara statistik di dalam perusahaan, metode fishbone juga harus digunakan untuk pengendalian kualitas. Fishbone merupakan salah satu cara atau alat untuk meningkatkan kualitas. Diagram ini juga disebut diagram sebab dan akibat. Keuntungan dari grafik ini adalah dapat membantu menemukan akar masalah dengan alat yang ramah pengguna dan mudah digunakan. Penerapan fishbone diagram di perusahaan sangat membantu dalam menemukan sumber utama permasalahan di perusahaan. Dengan menggunakan diagram ini, semuanya akan menjadi lebih jelas dan memungkinkan kita untuk melihat akar penyebab dan dampak dari masalah yang terjadi. Adapun gambar tulang ikan bisa dilihat pada gambar 2. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Gambar 2 Analisis Fishbone (sumber :Irwan Susanto, 2011) i i I i i i i i 2.6 Analisis Finansial Untuk memudahkan dalam menilai, membandingkan dan mengendalikan investasi yang ditanamkan di dalam suatu usaha, maka perlu ditetapkan beberapa kriteria/parameter analisis usaha. Beberapa parameter analisis usaha adalah analisis finansial yaitu BEP/ Break Event Point (analisis peluang pokok), R/C Ratio (Return Cost Ratio) atau dikenal dengan perbandingan antara total penerimaan (R) dan total biaya (C) dan analisis Payback Period (PP). A. Biaya Investasi Biaya investasi adalah modal yang ditanamkan untuk tujuan produksi. Investasi cukup besar pada awal kegiatan usaha, karena untuk memulai operasional harus ada infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Bentuk investasi dapat berupa lahan, bangunan pendukung dan peralatan (Sumardika, 2013). B. Biaya Variabel Komponen biaya variabel yang akan dihitung antara lain: Bahan untuk operasional, biaya tenaga kerja tidak tetap, persiapan lahan, panen dan perbaikan fasilitas lainnya. Biaya lainnya termasuk bonus yang harus diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan dan loyalitas bekerja, selain itu juga ada digunakan dana sosial masyarakat sekitar dan keamanan (Sumardika, 2013). C. Analisa Laba/Rugi Analisis laba/rugi merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat usaha dengan menghitung tingkat keuntungan atau kerugian yang didapat I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 14 dalam usaha budidaya dengan menghitung jumlah pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi baik tetap maupun tidak tetap. D. Return Cost Ratio (R/C Ratio) Analisis R/C Ratio merupakan alat analisis untuk melihat keuntungan relative suatu usaha dalam satu tahun terhadap biaya yang dipakai dalam kegiatan tersebut. Suatu usaha dikatakan layak bila R/C lebih besar dari 1 (R/C > 1). Hal ini menggambarkan semakin tinggi nilai R/C, maka tingkat keuntungan suatu usaha akan semakin tinggi (Primyastanto, 2011). E. Break Event Point (BEP) Titik impas adalah suatu titik dimana perusahaan mengalami tidak untung dan tidak rugi. Merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapatkan biaya pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah 0. Analisa BEP adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Analisa ini disebut juga dengan analisa impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu dimana penjualan dapat menutup biaya, sekaligus menunjukan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampui (Sumardika, 2013) F. Payback Period Payback Period merupakan periode jangka waktu yang diperlukan pengembalian untuk mengembalikan modal atau investasi (Manopo et al., 2013). i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 15 3. 3.1 METODE PRAKTIK Waktu dan Tempat Praktik Lapang II dilaksanakan mulai dari tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 8 November 2024 yang berlokasikan di CV Hatchery Nila Kekar Retail. Jl Tajinan No. 204, Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Adapun gambar peta lokasi praktik dapat dilihat pada gambar 3. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Gambar 3 Peta Lokasi Praktik i i i i i 3.2 Alat dan Bahan Alat dan bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Praktik Lapang II berlangsung yang dapat dilihat pada tabel 2 dan 3. Tabel 2 Alat yang Akan Digunakan I i i i i i i i i i i I i No Alat 1 Bak Fiber i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Spesifikasi Diameter 10 dan diameter 8 i i Aerasi Pompa air tandon 2 inch 4 Blower Hiblow Hp-80 5 Timbangan i i i i Kegunaan Media pembesaran ikan nila Mengalirkan oksigen Mengisi air bak dari tandon yang sudah disediakan Untuk meningkatkan oksigen i i i i i i i Digital kapasitas 5 kg i i i i i i i i i i i i i i 2 3 i i I i i i i i i Untuk menimbang berat ikan I i i i i i 16 Tabel 2 Alat yang akan digunakan lanjutan No Alat Spesifikasi 6 pH Ph meter pen i i i Kegunaan Mengukur kadar keasaman Mengukur kandungan oksigen terlarut i i DO Meter DO9100 Digital Pen Type Ligent Dissolved Oxygen Analyzer Portable Meter Water Quality DO Tester 0.0-40.0 mg.l-1 mg.l-1 i I i 8 Test Kit Ammonia, Nitrit dan Nitrat i i i 7 i i i i i i i i i i i i i i i i i Mengetahui kandungan ammonia, nitrit dan nitrat Untuk mengukur panjang ikan i i i i i i i i 9 Penggaris 30 cm i I i i i i i i Tabel 3 Bahan yang Akan Digunakan i i i No Bahan 1 Benih ikan nila 2 Pakan 3 Air tawar 4 Vitamin i i i i i Kegunaan Biota yang dibudidayakan i i i i i i i i i i i i i Sebagai bahan nutrisi untuk ikan Media hidup ikan nila Meningkatkan pertahanan tubuh, meningkatkan makan ikan, melengkapi kebutuhan vitamin C i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i nafsu i i i i 3.3 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang akan diterapkan dalam pelaksanaan Praktik Lapang II adalah metode observasi, wawancara, studi literatur dengan cara mencatat, mengatur, mengukur, menimbang, mengamati dan berpatisipasi langsung dalam semua kegiatan pembesaran ikan nila untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Di bawah ini merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan dua macam cara sebagai berikut. 3.3.1 Jenis Data a) Data Primer Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dengan mengikuti dan mencatat seluruh rangkaian kegiatan di lokasi praktik, data primer yang akan diambil pada Praktik Lapang II dapat dilihat pada tabel 4. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 17 Tabel 4 Data Primer i No i Jenis Data Pra Produksi i 1 i Kegiatan i Data yang Akan Diambil i i i i I i i i i Keadaan Umum Lokasi Kesesuain lokasi, akses lokasi, sumber listrik, sumber air, unit produksi Persiapan wadah alat dan bahan yang digunakan, fungsi alat dan bahan yang digunakan serta dosis yang diberikan, desain dan tata letak, kelayakan dan kondisi kolam, jenis wadah dimensi dan volume wadah Alat dan bahan yang digunakan beserta kegunaanya, sumber air, dan cara treatment/sterilisasi air Asal benih, jenis benih, umur benih, jumlah benih, kondisi benih, padat tebar, waktu pemeliharaan Jenis dan ukuran pakan, Waktu pemberian, dosis dan frekuensi pemberian pakan pakan, Kandungan nutrisi pakan, formulasi pakan serta metode pemberian pakan Tempat dan jumlah titik sampling waktu dan frekuensi sampling, SR (Survival Rate), FCR (Feed Convertion Rate), ABW (Average Body Weight), ADG(Average Daily Growth) Jenis alat beserta spesifikasi dan kegunaannya, data pengukuran kualitas, parameter kualitas air, pergantian air, waktu pergantian air Pengamatan Kesehatan secara visual dan atau laboratorium, teknik pencegahan hama dan penyakit, jenis hama dan penyakit, dosis dan bahan untuk pencegahan dan penerapan biosecurity Alat dan bahan yang digunakan saat panen, waktu pemanenan, teknik panen, jumlah populasi, usia pemanenan Distribusi ikan hasil panen, cara pemasaran, waktu pembersihan petakan Metode yang digunakan i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i Penebaran benih i i I i i i i i Monitoring pertumbuhan i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Manajemen pakan i i i i i i i i i Produksi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Persiapan media i i i i 2 i I I I i i Pengeolaan kualitas air i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Pengendalian Hama dan Penyakit i i i i i i i i i i i i Panen i I i i i i i i i i Pengelolaan limbah Analisis finansial i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Pasca panen i i i i i i i i i i i i Pasca Produksi i i i i 3 i i i i i i i i i i i i i I i i i Biaya produksi, laba/rugi,kelayakan suatu usaha i i i i i i i i i i i i i i i 18 b) Data Sekunder Data sekunder diperoleh melalui informasi dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun jenis data informasi tentang hasil pemeliharaan yang biasa dikumpulkan serta melakukan pengkajian dengan cara membandingkan kondisi lapangan dengan literatur yang ada. Data sekunder yang akan diambil dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5 Data Sekunder i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i No Jenis Data 1 Profile perusahaan Data yang Akan Diambil Sejarah perusahaan, struktur organisasi 2 Luas wilayah, denah lokasi perusahaan, layout unit produksi Target produksi per siklus dan pertahun i i i i i i i i i i I i i i i i i i i Keadaan lokasi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 3 4 Perencanaan produksi Produksi 5 Data produksi i i i i i i i i i i Standar Operasional Produksi (SOP) perusahaan, waktu dan cara kerja karyawan Hasil pemasukan dan pengeluaran perusahaan yang telah berlangsung, yakni log book hasil produksi siklus sebelumnya i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 3.4 Metode Kerja 3.4.1 Pra Produksi A. 1) Kesesuaian Lokasi Mengidentifikasi jenis tanah yang akan digunakan sebagai petakan budidaya. Mengetahui sumber air yang digunakan. Mengidentifikasi sarana dan prasarana. Mengidentifikasi apakah lokasi sesuai digunakan untuk pembesaran. i i 2) 3) 4) B. 1) 2) 3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Persiapan Petakan Mengidentifikasi jenis dan bentuk petakan yang akan digunakan. Mengukur dan mencatat data dimensi petakan yang digunakan. Mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk persiapan petakan pemeliharaan. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i C. 1) Pengisian Air Petakan Mengidentifikasi sumber air yang akan digunakan untuk pengisian petakan pemeliharaan. 2) Mengidentifikasi bahan dan alat yang akan digunakan. 3) Mengamati dan melakukan kegiatan pengisian air petakan. 3.4.2 Produksi i i A. 1) 2) 3) 4) 5) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Penebaran Benih Mempersiapkan alat, bahan dan sarana prasarana. Melakukan aklimatisasi 15-20 menit. Membuka plastik packing benih. Menebar dengan menuang benih secara perlahan Mencatat data penebaran. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 19 B. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Pengelolaan Pemberian Pakan Mengamati jenis dan ukuran pakan. Melakukan wawancara terkait pembagian ukuran pakan ikan. Melakukan teknis pemberiaan pakan (waktu dan cara). Melakukan wawancara terkait dosis pakan. Mengamati cara penyimpanan pakan. Melakukan pengambilan pakan di gudang pakan. Melakukan penghitungan terkait jumlah pakan yang dihabiskan dalam 1 siklus per petakan. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i C. Monitoring Pertumbuhan Monitoring pertumbuhan ikan diukur setiap seminggu sekali dengan cara sampling 1) Menyiapkan Jala, buku, pulpen, ember, tas waring dan timbangan. 2) Menebar jala, kemudian menariknya secara perlahan. 3) Keluarkan ikan dan masukkan ke dalam ember 4) Ambil sampel sebanyak 10% dari populasi untuk sampling pertumbuhan kemudian ikan ditimbang dan catat berat ikan tersebut. 5) Jumlah berat sampel ikan dibagi jumlah ikan yang ada, kemudian ikan juga diukur panjang tubuhnya. 6) Jika sudah selesai di kembalikkan lagi ke petakan pemeliharaan secara perlahan agar ikan tidak stress. D. Pengelolaan Kualitas Air Kegiatan pengelolaan kualitas air terdiri dari monitoring kualitas air dan pergantian air. Pergantian air dilakukan secara rutin seminggu 2 kali pada pagi hari. Penggantian air dilakukan dengan membuang sekitar 20 – 25% air kolam/bak kemudian ditambahkan air baru. Parameter kualitas air yang akan diukur (suhu, pH, DO, dan ammonia) adalah sebagai berikut : 1) Suhu Pengukuran suhu dilakukan menggunakan thermometer dengan frekuensi 2 kali sehari yaitu pada pukul 05.00 dan 16.00 WIB, cara pengaplikasian alat tersebut yaitu dengan memasukan termometer ke dalam air media pemeliharaan dan tunggu selama ± 30 detik hingga angka stabil kemudian mencatat hasil pengukuran. 2) DO Pengukuran oksigen terlarut menggunakan alat DO meter dengan frekuensi 2 kali sehari yaitu pukul 05.00 dan 16.00 WIB (Marion, 1998). Cara pengaplikasian alat tersebut yaitu dengan cara tekan tombol daya untuk menghidupkan alat, lakukan kalibrasi sesuai dengan petunjuk, pastikan sensor tetap lembab sebelum dan selama kalibrasi, tetapi hindari perendaman penuh saat tidak digunakan. Bilas sensor dengan air deionisasi atau air sampel untuk menghindari kontaminasi dari sisa-sisa larutan sebelumnya. Keringkan sensor dengan lembut menggunakan kain atau tisu bebas serat jika perlu. Lalu celupkan probe ke dalam sampel air yang akan diukur, tunggu beberapa saat hingga pembacaan pada layar DO meter stabil lalu setelah selesai mengukur, bilas probe dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa sampel lalu keringkan probe dan atikan DO meter dan simpan alat beserta probe di tempat yang kering dan bersih. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 20 3) pH Pengukuran pH dilakukan menggunakan alat pH meter dengan frekuensi 2 kali sehari yaitu pada pukul 05.00 dan 16.00 WIB (Marion, 1998). Cara pengaplikasian alat tersebut yaitu dengan membuka penutup alat dan menekan tombol on pada pH meter lalu sebelum melakukan pengukuran, kalibrasi pH meter dengan larutan buffer sesuai dengan petunjuk manual pH meter. Bilas elektroda pH dengan air deionisasi atau air sampel untuk menghindari kontaminasi dari sisasisa larutan buffer atau sampel sebelumnya dan keringkan elektroda dengan lembut menggunakan kain atau tisu bebas serat. Kemudian celupkan bagian ujung sensor pH meter ke dalam air media pemeliharaan dan menunggu sampai angka yang tertera pada pH meter stabil atau sampai ± 30 detik, setelah itu mencatat hasilnya, selanjutnya pH meter dibersihkan kembali dengan cara di cuci dengan air bersih kemudian dikengeringkan ujung sensor pH meter. 4) Nitrit, Nitrat dan Amonia Pengukuran nitrit, nitrat dan amonia dilakukan menggunakan alat amonia tes kit dengan frekuensi 1 kali seminggu. Cara pengaplikasian mengambil air bak yang akan diuji dalam wadah bersih dan steril lalu membuka tes kit yang digunakan. Setiap tes kit memiliki petunjuk penggunaan yang spesifik selanjutnya mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera. Menambahkan reagen kedalam sampel air dalam jumlah yang sudah ditentukan lalu setelah menambahkan reagen, mengamati perubahan warna dan reaksi terjadi. Dan tes kit menggunakan perubahan warna sebagai indikator jumlah nitrat,nitrit dan amoniak. Lalu menyesuaikan warna yang muncul dengan skala warna tes kit untuk menentukan konsentrasi nitrat, nitrit dan amoniak. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i E. 1) 2) 3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Pengendalian Hama dan Penyakit Melalukan tindakan pencegahan sebelum ikan terserang penyakit. Melakukan pengamatan kondisi kesehatan ikan secara visual. Mengidentifikasi jenis penyakit yang menyerang ikan nila di Laboratorium Kesehatan Ikan. Melakukan tindakan penanggulangan apabila ikan terserang penyakit mengetahui dan mencatat jenis dan menghitung dosis obat yang akan dibutuhkan dan mengamati biosecurity yang diterapkan. Mencatat hasil pengamatan diagnosa penyakit ikan. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 5) i i i 4) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 3.4.3 Pasca Produksi A. 1) Panen Ikan dipanen setelah 3 bulan masa pemeliharaan atau setelah mencapai ukuran konsumsi. 2) Mengidentifikasi dan menyiapkan peralatan yang digunakan dalam kegiatan panen. 3) Melakukan dan mencatat teknik pemananenan yang akan dilakukan. 4) Mencatat hasil panen dan menghitung hasil panen. 5) Melakukan dan mencatat teknik pernyotiran yang akan dilakukan. B. Pasca Panen Pengambilan data pasca panen didapatkan dari mencatat kegiatan pemasaran, mencatat pengorganisasian dalam pemasaran, mencatat jumlah yang i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 21 dipasarkan, mencatat dan mendokumentasikan kegiatan pemasaran, mencatat alat dan bahan pengemasan serta mencatat langkah-langkah kegiatan pemasaran. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i C. Analisa Usaha Data yang didapatkan pada analisis usaha adalah dengan melakukan pengamatan kelayakan usaha dan observasi dengan pemilik tempat praktik yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, biaya laba/rugi, biaya Break event point (BEP), biaya Payback Period (PP) dan biaya Return Cost Ratio (R/C ratio) 3.5 Metode Pengolahan Data Metode pengolahan data merupakan kumpulan dari rumus-rumus yang akan digunakan selama melaksanakan kegiatan pembesaran ikan nila. Metode pengolahan data meliputi 3.5.1 Kinerja Budi daya A. Biomassa Tingkat produksi biomassa dihitung menggunakan rumus (Fitria, 2012). Biomassa (kg) = ABW x Populasi akhir (ekor) 1) Feed Convertion Ratio (FCR) Perhitungan FCR menurut (Rijal et al., 2022). Wt − Wo FCR = F Keterangan : FCR : Rasio Konversi pakan F : Jumlah pakan yang diberikan (gram) Wt : Bobot ikan pada saat akhir perlakuan (gram) Wo : bobot ikan saat awal perlakuan (gram) 2) Survival Rate (SR) Survival rate atau kelangsungan hidup yaitu jumlah tingkat perbandingan dari ikan yang ditebar awal hingga akhir. Survival rate dapat dihitung menggunakan rumus (Saridu et al., 2023) Perhitungan tingkat kelangsungan hidup (SR) Nt SR (%) = x 100 No Keterangan: SR = Survival Rate (%) Nt = Jumlah Ikan Akhir Pemeliharaan No = Jumlah Ikan Awal Pemeliharaan i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i I i i i i i i i Average Body Weight (ABW) Perhitungan pertambahan bobot dapat dilihat pada rumus berikut (Ramadhan, 2019) Berat total ikan yang ditimbang (g) ABW (g/ekor) = Jumlah sampel (ekor) i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i 4) i i Average Daily Growth (ADG) Untuk mengetahui pertumbuhan ikan nila, dilakukan dengan mengukur pertambahan panjang dan tubuh ikan (Ombong & Salindeho, 2016) i I i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 22 Perhitungan Average Daily Growth (ADG Berat rata − rata akhir (gr) − Berat rata − rata awal (gr) ADG (g/hari = Waktu (hari) i I i i i I i i i i i i i i i i i i i I i i i 3.5.2 Aspek Finansial 1) Biaya Operasional Perhitungan biaya operasional menurut (Ombong & Salindeho, 2016) dapat menggunakan rumus: Biaya Operasional (Rp) = Biaya Tetap (Rp) + Biaya Tidak Tetap (Rp) i i i i i i i i 2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Laba/Rugi Perhitungan Laba/rugi menurut (Yunianto & Suryandari, 2022), dapat dilihat pada rumus berikut: Keuntungan (Rp) = TR − TC Keterangan : TC = Total Cost (Rp) TR = Total Revenue (Rp) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 3) i Return Cost Ratio (R/C) Perhitungan R/C Ratio menurut (Yulia, 2021) dapat menggunakan rumus: Total Penerimaan (Rp) R/C Ratio = Total Biaya (Rp) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 4) i i Break Even Point (BEP) Perhitungan Break Even Point (BEP) harga menurut (Maruta, 2018), dapat menggunakan rumus: Biaya Tetap BEP Unit = Biaya Variabel (Rp) Harga jual Satuan (kg) − Total Produksi (kg) i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i Perhitungan Break Even Point (BEP) menurut (Maruta, 2018) dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut i i i i i i i i i i i i i i i i Payback Period (PP) Perhitungan payback menggunakan rumus: i i i i i i i i i i i i i 5) i Biaya Tetap (Rp) Biaya Variabel (Rp) 1− Hasil Penjualan (Rp) BEP Harga = i i i i i i i i period i (PP) menurut i (Maruta, i 2018) dapat i i i PP (Tahun) = i i Biaya Investasi (Rp) x 1 tahun Keuntungan (Rp) i i i i i i i i 3.6 Metode Analisis Data Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara membahas secara sistematis, menggambarkan dan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan saat praktik atau menganalisis i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 23 lebih dalam kemudian membandingkan dengan literatur dan ditunjang dengan hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di lapangan. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 3.6.1 Analisa Deskriptif Komperatif Analisis yang digunakan dalam pengelolaan data adalah analisis deskriptif komparatif. Analisis ini berupa penyajian yang menjelaskan hal-hal yang diminati berupa teknis produksi yaing dilakukan selain praktik. Analisis membahas sesuai dengan batasan masalah, kemudian membandingkan hasil pengamatan dengan literatur dan narasumber. Data kinerja pembesaran meliputi, pertumbuhan panjang dan berat ikan, dan kelangsungan hidup. Analisis finansial dalam pembesaran ikan (Oreochromis niloticus) melipuiti biaya investasi, biaya produksi, analisis laba/rugi, B/C Rasio, Break Even Pont (BEP), Payback Period (PP). Data tersebut diperoleh dari hasil pengamatan, pengukuran dan perhitungan. Data diolah dengan cara sortasi dan tabulasi data. Pada analisis finansial dilakukan penilain dengan parameter layak atau tidaknya usaha tersebut. Parameter tersebut dapat disimpulkan dari hasil perhitungan analisis finansial. Berikut parameter analisis finansial : 1) Analisa laba/rugi Parameter penilaian laba/rugi adalah sebagai berikut : a. Pendapatan > Pengeluaran, artinya laba/untung b. Pendapatan = Pengeluaran, artinya impas c. Pendapatan < Pengeluaran, artinya rugi 2) Break Even Point (BEP) Suatu usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, maka terjadi keseimbangan atau nilai impas hasil pendapatan. 3) Payback Period (PP) Kriteria Payback Period (PP) adalah sebagai berikut : a. Semakin besar nilai Paybaick Period (PP), maka semakin lama waktu pengembalian investasi usaha. b. Semakin kecil nilai Payback Period (PP), maka semakin cepat waktu pengembalian investasi usaha. 4) Benefit Cost Rasio (B/C Raisio) Kriteriai nilai R/C Rasio adalah sebagai berikut : a. B/C > 1, artinya usaha layak/menguntungkan b. B/C = 1, artinya usaha impas c. B/C < 1, artinya usaha tidak layak/rugi. 3.6.2 Analisis Batasan Masalah Analisis identifikasi masalah yang dilakukan yaitu dengan analisis Fishbone yang berdasarkan 4M (Manusia, Metode, Material dan Mesin). Untuk mengetahui penyebab suatu masalah tertentu dan kemudian membedakan akar penyebabnya, dapat dilakukan dengan menentukan pencapaian tujuan perusahaan, mencari penyebab yang terjadi, dan kemudian mencari solusi atau jalan keluar. Identifikasi masalah pada kegiatan pembesaran yaitu pertambahan berat ikan, kelangsungan hidup, konservasi pakan, produktifitas tidak sesuai target 24 perusahaan. Adapun langkah kerja yang diambil untuk mengindentifikasi masalah adalah : 1. Memahami dan mengikuti kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di lokasi; 2. Mengikuti seluruh kegiatan pembesaran ikan nila (Oreochromis niloticus) ; 3. Menemukan masalah atau kendala dalam kegiatan pembesaran ikan nila (Oreochromis niloticus) ; Intervensi setiap indikasi permasalahan yang muncul pada masing-masing kegiatan dilkasi dengan menggunakan form identifikasi masalah. 25 4. RENCANA PRAKTIK 4.1 Rencana Kegiatan Rencana Praktik Lapang II dilakukan selama 4 bulan yang dimulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 8 November 2024 yang berlokasi CV Hatchery Nila Kekar Retail, Tlogowaru, Kedungkandang, Malang, Jawa Timur dapat di lihat pada Tabel 6. Tabel 6 Rencana Kegiatan i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Kegiatan i i i i i i i i i i i i i i i Waktu Pelaksanaan Juli Agustus September Oktober November 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 i i i 1 i i i i i i i i i No i i i i i i i i i i i i i i i i Penyusunan Proposal Seminar Proposal Berangkat dan Pengenalan Lokasi Pelaksanaan praktik di lapangan Pengumpulan dan analisa data Penyusunan laporan Seminar Hasil PL i i i i 2 i i 3 i i i i i i 4 i i i i i i 5 i i i i i i 6 i i i i i i 7 i i i i i i 4.2 Praktik Adapun rincian biaya yang dibutuhkan selama kegiatan Praktik Lapang II dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 7. I i i i i i i i i i i i i i i i i i Tabel 7 Anggaran Praktik i 1. I i Biaya Transportasi Jakarta – Malang (PP) : Biaya Akomodasi a.Makan @Rp. 30.000 x 120 hari : b. Penginapan @Rp. 500.000 x 4 bulan : c. Penyusunan Laporan : d. Lain-lain : i i i 2. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Rp. 3.600.000 i i i Rp. 1.000.000 i i i i Total i Rp. 2.000.000 Rp. 450.000 Rp. 500.000 Rp. 7.550.000 i i i 26 DAFTAR PUSTAKA Al., S. F. et. (2023). Fluktuasi parameter kualitas air dan perkembangan flok pada budidaya ikan Nila (Oreochromis niloticus) dengan sistem bioflok di BPBAT Talelu. 11(2), 213–226. https://doi.org/10.14341/cong23-26.05.23-39 Alfira, E. (2015). Pengaruh Lama Perendaman Pada Hormon Tiroksin Terhadap Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Benih Ikan Nila (Oreochromis niloticus). In Skripsi. Andriyanto, F., Efani, A., & Riniwato, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor Produksi Usaha Pembesaran Udang Vanname (Litopenaeus vannamei) Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Jurnal ECSOFiM, 1(1), 82–96. Anonimo. (2010). Pembenihan dan Pembesaran Nila (Jakarta: Penebar Swadaya). Arisya, Y., Anggriawan, D., & Hanifa, H. (2013). Laporan oksigen terlarut. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran. Arzad, M., Ratna, R., & Fahrizal, A. (2019). Pengaruh Padat Tebar Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Dalam Sistem Akuaponik. Median : Jurnal Ilmu Ilmu Eksakta, 11(2), 39–47. https://doi.org/10.33506/md.v11i2.503 Cahyati, A., Yuristia, R., & Sumantri, B. (2022). Analisis Efisiensi Usaha Pembesaran Ikan Nila di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh, 3(2), 32. https://doi.org/10.29103/ag.v7i1.12329 Carman, O., & Sucipto, A. (2013). Pembesaran Nila 2,5 Bulan. Dailami, M., Rahmawati, A., Saleky, D., & Toha, A. H. A. (2021). Ikan Nila. Dharmaji, D., Sofarini, D., & Produktif, T. N. (2017). Budidaya Nila Salin Di Lahan Tambak Udang Non Produktif. 4(September). Effendi, H. (2003). Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan. 168–169. Fitri, H., & Rasyid, R. (2023). Rancang Bangun Sistem Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berdasarkan Temperatur Air Pada Kolam Ikan Nila Menggunakan Sensor Suhu DS18B20. Jurnal Fisika Unand, 12(1), 137–143. https://doi.org/10.25077/jfu.12.1.137-143.2023 Fitria, A. S. (2012). Analisis Kelulushidupan dan Pertumbuhan Benih Ikan Nila Larasati (Oreochromis niloticus) F5 D30-D70 pada Berbagai Salinitas. Journal of Aquaculture Management and Technology, 1(1), 18–34. Forteath. (1993). Types of recirculating system, In : Recirculation sistem : Desaign, Construction and management. Hart P and Sullivan, Departement of Aquaculture. 33-39 p. Fradina, I. T., & Latuconsina, H. (2022). Manajemen Pemberian Pakan Pada Induk dan Benih Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di Instalasi Perikanan Budidaya, Kepanjen - Kabupaten Malang. JUSTE (Journal of Science and Technology), 3(1), 39–45. https://doi.org/10.51135/justevol3issue1page39-45 Gery Purnomo. (2020). Klasifikasi, Morfologi Ikan Nila. https://www.melekperikanan.com/2020/08/morfologi-dan-klasifikasi-ikannila.html 27 Hastari, I. F., Kurnia, R., & Kamal, M. M. (2017). Suitability Analysis of Floating Cage Culture of Grouper Fish Using Gis in Ringgung Waters of Lampung. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis, 9(1), 151–159. https://doi.org/10.29244/jitkt.v9i1.17926 Hoffman, D. W. (2010). Bioflocs technology : an integrated system for the removal of nutrients and simultaneous production of feed in aquaculture. Irwan Susanto. (2011). Analisis Fishbone. http://cioindo.blogspot.com/2011/11/analisis-fishbone-ishikawa-diagram.html Iskandar, R., & Elrifadah. (2015). Pertumbuhan dan Efisiensi Pakan Ikan Nila (Oreochromis niloticus) yang Diberi Pakan Buatan Berbasis Kiambang. Jurnal Ziraa’ah, 40(1), 18–24. https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/93 Khairuman, A. M., & Amri, K. (2005a). Budi Daya Ikan Nila Secara Intensif. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BJYu6JiAd0C&oi=fnd&pg=PA18&dq=budi+daya+ikan&ots=2DP2VWtA5G&sig=bUi lHhbP8HSzWShbA_nKWgcSkzI Limbong, M., Satyantini, W. H., & Suharto, S. (2018). The influence of stocking density on the growth performance and survival rate of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultured in floating net cages. Aquaculture International, 26(2), 531–542. Manopo, S. F. J., & J. Tjakra, R. J. M. Mandagi, M. S. (2013). Analisis Biaya Investasi pada Perumahan Griya Paniki Indah. Jurnal Sipil Statik, 1(5), 377– 381. Marion, J. (1998). Water Quality for Pond Aquaculture. International Center Experimental Station, 37. Maruta, H. (2018). Analisis Break Even Point (BEP) Sebagai Dasar Perencanaan Laba Bagi Manajemen. Jurnal Akuntasi Syariah, 2(1), 9–28. Murnawan, H., & Mustofa. (2014). Perencanaan Produktivitas Kerja Dari Hasil Evaluasi Produktivitas Dengan Metode Fishbone Di Perusahaan Percetakan Kemasan Pt . X Latar Belakang Masalah. Jurnal Teknik Industri Heuristic, 11(1), 27–46. Oktapiandi, O., Sutrisno, J., & Sunarto, S. (2019). Analisis Pertumbuhan Ikan Nila Yang Dibudidaya Pada Air Musta’Mal. Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi, 5(1), 16–20. https://doi.org/10.23917/bioeksperimen.v5i1.7982 Oktavia, D. A., Mangunwidjaja, D., Wibowo, S., & Sunarti, T. C. (2012). Pengolahan Limbah Cair Perikanan Menggunakan Konsorsium Mikroba Indegenous Proteolitik dan Lipolitik. Agrointek, 6(2), 65–71. Ombong, F., & Salindeho, I. R. . (2016). Aplikasi teknologi bioflok (BFT) pada kultur ikan nila, (Orechromis niloticus). E-Journal Budidaya Perairan, 4(2), 16–25. https://doi.org/10.35800/bdp.4.2.2016.13018 Primyastanto, M. (2011). Feasibility Study Usaha Perikanan. Kelayakan Usaha Perikanan, 218(treatment D), 1–124. Radhiyufa, M. (2011). Dinamika Fosfat dan Klorofil Dengan Penebaran Ikan Nila (Oreochromis niloticus) pada Kolam Budidaya Ikan Lele (Clarias gariepinus) Sistem Heterotrofik. (Skripsi) Program Studi Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 9. 28 Rahayu, W. (2011). Analisis Pendapatan Usaha Pembesaran Ikan Nila Merah (Oreochromis sp) Pada Kolam Air Deras di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 7(1), 10–25. http://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/index.php/jiip/article/view/338 Rahmatillah, R., Vermila, C. W., & Haitami, A. (2018). Analisis Usaha Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. JAS (Jurnal Agri Sains), 2(2). https://doi.org/10.36355/jas.v2i2.211 Ramadhan, A. (2019). Program Studi Agribisnis. Peningkatan Penerapan Manajemen Budidaya Pembesaran Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Sistem Bioflok Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu Sulawesi Utara, 246, 113–114. Rijal, M. A., Purbomartono, C., & Jannah, I. F. (2022). Respon Pertumbuhan Ikan Nila (Oreochromis niloticus) yang diberi Pakan Supplementasi Bawang Putih (Allium sativum) pada Sistem Bioflok. Sainteks, 18(2), 117. https://doi.org/10.30595/sainteks.v18i2.12773 Rochdianto, R. (2005). Budidaya Ikan di Jaring Terapung. Jakarta: Penebar Swadaya. Saanin, H. (1984). Taksonomi dan Klasifikasi Ikan Nila. Jurnal Ilmu Perikanan, 7(4), 150–158. Salsabila, Meidiana., dan Suprapto, H. (2018). eknik pembesaran ikan nila (Oreochromis niloticus) di instalasi budidaya air tawar pandaan, Jawa Timur. Journal of Aquaculture and Fish Health, 7 (3), 118–123. Saridu, S. A., Leilani, A., Renitasari, D. P., Syharir, M., & Karmila, K. (2023). Pembesaran Ikan Nila (Oreochromis niloticus) dengan Sistem Bioflok. Jurnal Vokasi Ilmu-Ilmu Perikanan (Jvip), 3(2), 90. https://doi.org/10.35726/jvip.v3i2.6559 segarati. (2014). Pengaruh Padat Tebar Yang Berbeda Terhadap Kelulushidupan Dan Laju Pertumbuhan Ikan Wader Pari (Rasbora argyrotaenia). 0, 1–23. SNI 2009. (2009). Produksi Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Kelas Pembesaran di Kolam Air Tenang (7550:2009). Badan Standarisasi Nasional. ICS 65.120 Badan Standardisasi Nasional. Subagja et al. (2020). Perancangan dan Pembangunan Infrastruktur Tambak untuk Memastikan Sirkulasi Air, Pengendalian Air, dan Keamanan Tanggu. Jurnal Rekayasa Lingkungan, 15(2), 87–94. Sugiarto. (2016). Budidaya Ikan Nila. In Aquaculture Journal. Sumanto, A. (2017). Persiapan Wadah Budidaya Tambak: Langkah-Langkah untuk Menciptakan Lingkungan Optimal. Jurnal Akuakultur Dan Teknologi Perikanan, 10(3), 112–119. Sumardika, P. (2013). Kewirausahaan Perikanan. In Bina Sumberdaya MIPA. Sunarto, & Sabariah. (2009). Pemberian Pakan Buatan Dengan Dosis Berbeda Terhadap Pertumbuhan Dan Konsumsi Pakan Benih Ikan Semah (Tor douronensis) Dalam Upaya Domestikasi Artificial. Jurnal Akuakultur Indonesia, 8(1), 67–76. http://journal.ipb.ac.id/index.php/jai Suryam, A. (2006). Struktur Anatomi dan Fungsi Sirip pada Ikan Nila. Jurnal Biologi Perairan, 6(3, 102–110. 29 Suryani, T. (2006). Adaptasi Ikan Nila pada Lingkungan Air Asin. Jurnal Perikanan Dan Kelautan, 5(2), 78-85. Suryanto, A. M. (2011). Kelimpahan dan Komposisi Fitoplankton di Waduk Selorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Jurnal Kelautan, 4(2), 135–140. Suryono, B., Setiawan, H., & Putri, M. (2019). Pentingnya Pengukuran dan Pemantauan Kualitas Air dalam Budidaya Perikanan. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan, 14(1), 45–52. Suryono et al. (2019). Pentingnya Pengukuran dan Pemantauan Kualitas Air dalam Budidaya Perikanan. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan, 14(1), 45–52. Susanto, A. (2012). Pengendalian Penyakit dalam Budidaya Ikan Nila. Jurnal Akuakultur Indonesia, 3(1), 45-52. Syakhabyatin, I. (2019). Manajemen Pemasaran : Manajemen Pemasaran Modern. In Management Pemasaran (Vol. 9, Issue 2). Taw, N. (2014). Shrimp Farming in Biofloc System : Shrimp Farming in Biofloc System: Review and Recent Developments, June. https://courseware.cutm.ac.in/wp-content/uploads/2020/06/Introduction-tobiofloc.pdf Wardhani, L. K., Safrizal, M., & Chairi, A. (2011). Optimasi komposisi bahan pakan pada ikan air tawar menggunakan metode multi-objective genetic algorithm. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 2011(Snati), 112–117. Yulia, I. A. (2021). Analisis Biaya, Pendapatan dan R/C Ratio Usaha Kayu Trubusan Jati Unggul Nasional di Kebun Percobaan Universitas Nusa Bangsa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(2), 277–282. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.779 Yunianto, A., & Suryandari, E. (2022). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Nila Berbasis Teknologi Bioflok Dan Akuntansinya. Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat, 2097–2105. https://doi.org/10.18196/ppm.45.703 30 LAMPIRAN Lampiran 1 Kesesuaian Lokasi i i No Data yang Diambil i i i Layak i i i Tidak Layak i i 1 Sumber Air i Jarak sumber air i i i i i Kualitas air (pH, Suhu, DO, dan Salinitas). Polutan i i i i i i i i i i 2 Sumber Listrik 3 Biosecurity i Aliran listrik i I i Penerapan Biosecurity i i i i 4 IPAL Tempat pembuangan limbah I i i i i i 5 Transportasi dan Distribusi i i i i Akses jalan dan pemasaran I i i i i i i i Keterangan i i 31 Lampiran 2 Alat dan Bahan yang Digunakan Untuk Persiapan Wadah i No i Alat dan Bahan I i i i i Spesifikasi i Jumlah i i Kegunaan i i i Keterangan i i 32 Lampiran 3 Kontrol Penyakit i i No Hari/Tanggal Bak i i i i Jumlah Ikan yang Sakit i i i i i Pengobatan Dosis Waktu i Jenis i i i Keterangan i i 33 Lampiran 4 Pengecekan Kualitas Air i i Parameter Kualitas Air Hari/Tanggal i i i Suhu (oC) i pH DO (mg.l-1 ) Amonia -1 05.00 16.00 05.00 16.00 05.00 16.000 (mg.l ) i i Nitrit (mg.l-1 ) Nitrat (mg.l-1 ) 34 Lampiran 5 Pengelolaan Pakan i i Frekuensi Pemberian Pakan i Hari/Tanggal i i i i i i No Bak Total i i Pagi (Kg) i Siang (Kg) i Sore (Kg) Jenis Pakan i i 35 Lampiran 6 Pengukuran Pertambahan Panjang dan Bobot Ikan i i i i i i i Sampling Berat Tanggal Sampel ke (g) i i i i i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i i i Rata-rata berat (g) i i i i i i Panjang (cm) i i Rata-rata Panjang (cm) i i i i i i