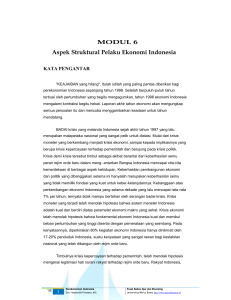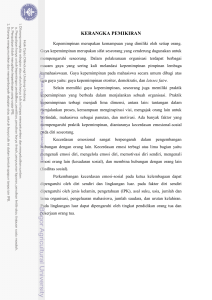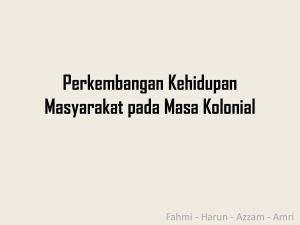Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan?
advertisement

Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan?* Nomor 14, September - 2007 Redaksi: Edi Cahyono, Maxim Napitupulu, Maulana Mahendra, Muhammad Husni Thamrin, Hemasari Dharmabumi Arief Budiman** KEKUASAAN negara, bisa menjadi terlalu besar, dapat menjadi kekuasaan yang totaliter. Pengertian kekuasaan totaliter pada mulanya merujuk kepada rejim fasis di Italia pada tahun 1920-an. Kemudian pengertian ini dikenakan juga pada pemerintah Nazi di Jerman dan pemerintah komunis di Rusia, terutama ketika rejim Stalin. Istilah totaliter kemudian menjadi populer di kalangan ahli ilmu sosial dan wartawan Barat semasa perang dingin. Carl Friedrich kemudian memberikan enam ciri rejim totaliter yang membedakanya dengan rejim otokratis lainnya (dan tentu saja dengan rejim demokratis). Keenam ciri tersebut adalah: adanya sebuah ideologi yang menyeluruh; adanya satu partai yang menganut ideologi ini; adanya polisi rahasia yang canggih; dan adanya tiga monopoli kontrol – yakni terhadap media massa, sarana pelaksana dan semua organisasi yang ada termasuk organisasi ekonomi. Diterbitkan oleh: Yayasan Penebar pEnEbar e-news terbit sebagai media pertukaran dan perdebatan soal-soal perburuhan dan globalisasi. Kami mendukung gerak antiglobalisasi masyarakat Indonesia. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan jebakan negerinegeri imperialis untuk menjadikan negeri-negeri miskin terus menjadi koloni dan dihisap oleh negerinegeri maju. Kami menerima tulisan-tulisan yang sejalan dengan misi kami untuk dimasukkan dan diedarkan melalui e-news ini. Rejim fasis muncul sesudah Perang Dunia I, khususnya di Italia dan Jerman. Rejim-rejim ini menjadi kuat dan mencapai kejayaannya ketika Perang Dunia II sampai mereka * Pernah dimuat dalam Prisma 3, Maret 1987. Arief Budiman lahir tahun 1941 di Jakarta; tamat dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1968 dan memperoleh gelar Ph.D. di bidang sosiologi dari Universitas Harvard, Amerika Serikat pada tahun 1980 dengan disertasi “The Mobilization and the State Strategies in the Democratic Transition to Socialism: The Case of Allende’s Chile.” ** Yayasan Penebar ~ Jl. Makmur, no. 15, Rt. 009/Rw.02, Kelurahan Susukan, Jakarta 13750, Indonesia • Tel./ Facs. ~ (+ 62 21) 841 2546 • email ~ [email protected] • website ~ http://www.geocities.com/ypenebar/ akhirnya dikalahkan. Dalam ensiklopedia, dinyatakan: “Secara negatif, fasisme dapat didefinisikan sebagai sistem yang menolak liberalisme dan parlementarisme. Secara positif fasisme didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang tidak terbatas dalam melaksanakan kegiatan kenegaraannya.” Selanjutnya dikatakan: Bangsa menjelma menjadi semacam corpus mysticum atau badan gaib yang menjelma dari generasi ke generasi dibekali sebuah misi yang harus dibuat menjadi kenyataan. Tugas individu adalah mengangkat dirinya ke taraf kesadaran nasional ini, dan meleburkan identitas dirinya sampai tuntas ke dalamnya. Dia hanya memiliki hak-hak individu sepanjang hak-hak ini tidak bertubrukan dengan kepentingan negara yang berkedaulatan penuh dan mutlak.1 Berbeda dengan pemerintah totaliter komunis yang mendasarkan dirinya pada sistem sosialis, pemerintah totaliter fasis mendasarkan dirinya pada sistem kapitalis, khususnya kapitalisme monopoli. Rejim fasis biasanya didukung oleh kelas menengah. Seperti yang dikatakan oleh Otto Bauer, salah satu proses yang mengakibatkan timbulnya fasisme di Eropa adalah krisis ekonomi sesudah Perang Dunia I yang mengurangi keuntungan kaum pengusaha. Mereka butuh mengeksploitir buruh-buruhnya secara lebih berat. Adanya gerakan kaum sosialis dan komunis yang kuat, tidak memungkinkan hal ini dilaksanakan dalam kerangka sistem yang demokratis. Karena itulah kaum pengusaha kapitalis mendukung sebuah rejim yang totaliter, yang dapat membendung gerakan kaum buruh yang makin agresif ini.2 Rejim totaliter komunis tentu saja berlainan dengan yang fasis. Munculnya juga disebabkan karena terjadinya krisis kapitalisme. Tapi berbeda dengan rejim fasis, dalam krisis ini kaum buruh berhasil muncul sebagai pemimpin dan mendirikan negara komunis. 1 Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 5, 6, 1957, hal. 134. Tom Bottomore (ed.), A Dictionary of Marxist Thought, Cambridge: Harvard University Press, 1983, hal. 162. 2 | 2 | Nomor 14, September - 2007 Negara ini kemudian menjadi totaliter, ekstrimnya terlihat di Rusia ketika pemerintahan dipimpin oleh Stalin.3 Rejim Totaliter di Dunia Ketiga Sementara itu, di Dunia Ketiga muncul pula rejim-rejim totaliter dengan pelbagai variasinya. Rejim-rejim ini mirip dengan rejim fasis di Eropa setelah Perang Dunia I. Pemerintah berkuasa penuh, dan menganut sistem kapitalis. Yang berkuasa biasanya kaum militer, yang juga merebut kekuasaan karena sistem kapitalis liberal yang sebelumnya dianut, mengalami krisis. Karena kelas menengah masih lemah, maka pada mulanya tampak gerakan buruh yang dipimpin oleh partai-partai sosialis atau komunis yang berada di atas angin, sampai pada akhirnya muncul kaum militer yang datang “memenuhi panggilan sejarah untuk menyelamatkan negara.” Contoh misalnya yang terjadi di Chili pada permulaan 1970-an. Pemerintah presiden Eduardo Frei (1964-1970) mengalami krisis karena meskipun kelas menengah mengalami kemajuan dalam kehidupan ekonomi mereka, kelas bawah merasa janji-janji pemerintah Frei ketika kampanye pemilihan umum dulu tidak dipenuhi. Maka terjadi mobilisasi kelas ini oleh gabungan partai sosialis dan komunis serta gerakan-gerakan yang berhaluan Marxis lainnya. Di bawah sebuah federasi politik yang bernama Unidad Popular (Persatuan Rakyat), gabungan partai-partai ini berhasil menang dalam pemilihan umum tahun 1970 dengan Salvador Allende sebagai calon presidennya. 3 Tidak semua negara komunis menganut sistem totaliter. Ada banyak variasi pada rejim di negara-negara komunis ini. Di Rusia sendiri, rejim yang paling totaliter adalah ketika zaman Stalin. Semua lawan politiknya disingkirkan, kalau perlu dengan pembunuhan, seperti yang terjadi pada salah seorang pendiri negara Rusia itu sendiri, yakni Leon Trotzky. Pada zaman Kruschev misalnya, terjadi pelunakan-pelunakan sistem. Kini, Gorbachev melanjutkan pelunakan-pelunakan yang telah dirintis pendahulunya ini, sehingga beberapa intelektual terkenal yang dttahan pada saat ini mulai dibebaskan. Variasi ini juga terjadi antar negara. Di negara-negara Eropa Timur misalnya, terdapat rejim-rejim yang otoriterisme dan totaliterismenya berbeda-beda kadarnya. | 3 | Setelah Allende dilantik menjadi presiden, pemerintah yang dipimpinnya berkiblat ke kelas bawah dan kelas menengah kecil. Kaum kapitalis besar yang memonopoli pasar, dimusuhi. Termasuk juga perusahaan-perusahaan asing yang berperan besar, kalau tidak menguasai, perekonomian Chili. Kelompok kapitalis besar ini kemudian berusaha merebut kembali kekuasaan melalui jalan demokratis, tapi mereka gagal. Pada pemilihan umum tahun 1973 untuk anggota-anggota DPR, usaha untuk merebut dua-pertiga mayoritas suara di parlemen (sehingga mereka dapat menjatuhkan presiden secara konstitusional) tidak berhasil, meskipun pemilihan itu dilakukan dalam tingkat inflasi yang sangat tinggi, sehingga sebenarnya sangat merugikan pemerintah Allende. Karena itulah, perebutan kekuasaan dilakukan melalui kudeta militer, dan kelas menengah yang tadinya mendukung pemerintah yang demokratis, kini beralih pada pemerintah militer yang otoriter.4 Hasilnya adalah pemerintah yang dipimpin oleh Jenderal Auguste Pinochet yang berkuasa sampai sekarang tanpa melalui pemilihan umum.5 Pertanyaan kita, apakah pemerintah Pinochet di Chili, dan pemerintah-pemerintah lainnya yang sejenis (seperti pemerintah militer di Argentina dan Brasil sebelum kembali ke pemerintah yang demokratis yang sekarang ini; pemerintah di Iran ketika zaman Shah; pemerintah militer di Pakistan dan Bangladesh sekarang; pemerintah di Uganda ketika zaman Idi Amin; dan banyak lagi contoh lainnya) merupakan rejim-rejim fasis? Ciricirinya tampaknya sama: pemerintah memiliki kekuasaan yang besar, tidak demokrasis dan menjalankan sistem kapitalisme 4 Dengan otoriter dimaksudkan pemerintahan yang mendasarkan dirinya pada kekuasaan yang tersentralisir. Partai-partai di luar partai pemerintah mungkin ada, ideologi-ideologi lain di samping ideologi yang dianut pemerintah mungkin dibiarkan tumbuh tapi pemerintahan dijalankan atas dasar kekuasaan yang besar yang terpusat pada tangan pemerintah. Ini jelas berbeda dengan rejim yang totaliter, di mana semuanya serta diseragamkan. Dengan demikian, totaliterisme merupakan salah satu bentuk dari otoriterisme. 5 Uraian yang lebih rinci tentang proses perkembangan di Chili ketika itu dapat dilihat pada Budiman, Jalan Demokrasi ke Sosialisme: Pengalaman Chili di Bawah Allende, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987. | 4 | Nomor 14, September - 2007 monopoli yang menekan kebebasan buruh untuk berserikat. Juga biasanya nasionalisme sangat ditekankan, seakan-akan semua yang dibuat pemerintah adalah untuk kepentingan bangsa. Negara diidentikkan dengan bangsa. Kalau ada seorang individu berbeda pendapat dengan negara, maka dia adalah pengkhianat bangsa. Semua ini tidak syak lagi merupakan ciri dari rejim fasis. Karena itu memang ada ahli-ahli ilmu sosial yang menamakannya sebagai rejim fasis Dunia Ketiga.6 Tapi kalau kita amati secara lebih seksama, maka tampak ada sesuatu yang absen pada rejim-rejim di Dunia Ketiga ini: tidak ada ideologi kuat yang mengikat. Bahkan terjadi proses depolitisasi dan de-ideologisasi dari massa. Rejim di Dunia Ketiga ini seringkali hanya menekankan aspek teknokratis dari pembangunan. Rakyat pada dasarnya dihambat untuk berpartisipasi dalam politik. Ini jelas berbeda dengan rejim totaliter fasis dan komunis, di mana rakyat digerakan secara emosional melalui sebuah ideologi politik yang kuat. Menurut O’Brien,7 fasisme dimulai dengan sebuah partai politik dengan ideologi yang kuat, yang kemudian mendapat dukungan massa, terutama dari kelas menengah. “Yang membuat fasisme kuat dan sukses adalah karena ia berhasil membentuk sebuah gerakan massa di kalangan kelas menengah dan memakai gerakan massa ini sebagai basis dari sebuah rejim yang otoriter. Karena itulah, fasisme hanya terkalahkan, harus kita ingat, melalui sebuah 6 Beberapa ahli ilmu sosial di Amerika Latin beranggapan bahwa rejim-rejim militer yang otoriter di kawasan tersebut merupakan rejim fasis. Tapi rejim-rejim ini memang berbeda dengan rejim fasis yang ada di Eropa, karena negara-negara di sini merupakan negara bekas jajahan yang ekonominya tergantung pada negara-negara kapitalis industri besar. Marcos Kaplan menyebutnya sebagai Fasisme Amerika Latin, Helio Jaguaribe sebagai Fasisme Kolonial dengan ciri, bila di Eropa negara bersekutu dengan kelas menengah, di Amerika Latin negara bersekutu dengan modal asing sebagai ganti kelas menengah yang masih lemah di negara-negara Dunia Ketiga. Lihat Phil O-Brien, “The Emperor has no Clothes: Class and State in Latin America” dalam Fitzgerald et.all., (eds), 1976, hal. 43. 7 Phil O’Brien, op.cit. | 5 | perang dunia,” demikian O’Brien. Lalu apa nama rejim otoriter dan totaliter yang menggejala di Dunia Ketiga, kalau bukan rejim fasis? O’Donnell8 menamakan sebagai negara otoriter birokratis. Ciri-ciri negara ini memang di samping otoriter, juga sifatnya yang birokratis. Artinya segala sesuatu diselesaikan melalui prosedur kantor yang “dingin.” Tidak dengan ideologi politik yang lebih “panas.” Sifat teknokratis-birokratis ini dapat dipahami kalau kita mempelajari sebab-sebab munculnya negara otoriter birokratis ini. Menurut O’Donnell, negara ini timbul karena terjadinya krisis dalam pembangunan pada taraf industri substitusi impor. Pada satu titik, proses ISI ini mengalami kejenuhan di pasar dalam negerinya. Untuk berekspansi, dibutuhkan industri yang berorientasi ekspor. Untuk ini dibutuhkan modal yang besar untuk melakukan proses industrialisasi hulu. Modal ini, karena jumlahnya yang besar, hanya bisa dikumpulkan melalui kerjasama dengan pengusaha-pengusaha asing, khususnya perusahaan-perusahaan transnasional. Untuk dapat menarik modal asing, diperlukan sebuah pemerintah yang dapat menjamin stabilitas politik. Para penanam modal jelas tidak akan mau menanamkan modalnya di suatu negara di man pemerintahnya lemah dan gejolak politik sering terjadi. Dari studi kasus di Argentina, O’Donnell berhasil menunjukkan bahwa modal asing yang dibutuhkan baru mau masuk pada saat pemerintah di bawah Juan Peron yang kurang stabil digulingkan dan diganti oleh sebuah pemerintah militer yang otoriter. Berbeda dengan Peron yang mengembangkan ideologi Peronisme, pemerintah militer yang baru bersikap teknokratis dan birokratis. Massa cenderung dihambat keterlibatannya ke dalam politik.9 8 Guillermo O’Donnell, “Reflections on the Patterns of Change in the Bureaucratic Authoritarian State,” dalam Latin America Research Review 12, No. 1, winter 1978. 9 Guillermo O’Donnell, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics, Berkeley: Institute of International Studies, University of | 6 | Nomor 14, September - 2007 Dengan demikian negara otoriter birokratis memang mirip dengan konsep Helio Jaguaribe tentang negara fasis kolonial, yakni sebuah negara yang otoriter, yang bekerjasama dengan modal internasional. Satu usaha lain untuk menggolongkan tipe rejim di Amerika Latin dilakukan oleh Schmitter. Menurut dia, rejim yang menggejala di Amerika Latin adalah rejim korporatis. Rejim ini muncul akibat tersendatnya proses pembangunan. Maka negara melakukan inisiatif untuk mengambil alih kepemimpinan pembangunan dengan cara memaksakan stabilitas politik. Massa dipecah menjadi golongangolongan fungsional, dan pemerintah tidak langsung berhubungan dengan massa tapi melalui perwakilan dan golongan-golongan ini. Negara korporatis di sini merupakan sesuatu yang dipaksakan, semacam proses modernisasi defensif dari atas, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan proses pembangunan melalui cara depolitisasi massa.10 Maka muncullah sebuah negara otoriter yang menghambat partisipasi massa. Pembangunan secara teknokratis dijalankan oleh negara. Massa diwakili oleh wakil-wakilnya, dan wakil-wakil ini makin lama makin lebih mendekatkan dirinya ke atas (kepada siapa mereka tergantung) daripada mendekati massa di bawah. Maka korporatisme lebih merupakan ideologi untuk mengabsahkan kekuasaan negara daripada mengikutsertakan partisipasi massa secara nyata melalui perwakilannya.11 Dari pendapat-pendapat tadi, kita tampaknya mendapatkan kesan yang kuat bahwa memang sudah muncul sebuah bentuk rejim otoriter (dan kadang-kadang juga totaliter) baru di Dunia Ketiga, yang berlainan dengan rejim fasis di Eropa. Ciri-ciri rejim ini adalah sifatnya yang otoriter (dan totaliter), bersifat teknokratis California, 1973. 10 Philippe Schmitter, “Still the Century of Corporation?,” dalam The Review of Politics 36, No. 1, Januari 1974. 11 Phil O’Brien, op.cit., hal. 41-42. | 7 | dalam menjalankan pembangunannya, melakukan depolitisasi massa, dan bekerjasama dengan kapitalisme internasional. Nama rejim ini, apakah negara otoriter birokratis, atau fasisme Dunia Ketiga, atau negara korporatis tampaknya kurang penting. Yang jelas rejim seperti ini ada. Barangkali sudah tiba waktunya sekarang untuk menanyakan mengapa rejim-rejim otoriter dan totaliter ini bermunculan di zaman modern? Faktor-faktor apa yang mendukungnya? Ada tiga kelompok teori yang mencoba menjelaskan gejala ini, kelompok teori psikologi, kebudayaan dan sosial historis. Kelompok teori psikologi menyoroti dari analisis psikologi individual. Kelompok teori ini berkembang di Barat, di kalangan ahli ilmu sosial liberal. Teori kebudayaan tampaknya kurang mengakar di dunia Barat, karena kebudayaan mereka yang moderen, rasional, pragmatis dan individualistis sulit menerima adanya nilai-nilai yang otoriter. Kelompok teori kebudayaan lebih berkembang di Timur, di mana masyarakat masih mengalami kebudayaan peralihan dari feodalisme ke modernisme, dari kolektivisme ke individualisme. Sedangkan teori sosial historis atau struktural historis berkembang di Barat maupun di Timur. Teori ini menjelaskan adanya rejim otoriter dan totaliter dari sejarah perkembangan kelompok-kelompok masyarakat yang ada, kekuatan politik mereka dan kepentingan ekonominya. Teori psikologi misalnya dikemukakan oleh filsuf Italia, Benedetto Croce yang menjelaskan fasisme sebagai akibat dari „kehancuran hati nurani, depresi dan keracunan warga akibat perang.“ Maka kesadaran akan pentingnya kemerdekaan jadi berkurang. 12 Friedrich Meinecke mengatakan hal yang hampir sama. Fasisme timbul karena keseimbangan kejiwaan antara impuls rasional dan irasional terganggu. Gangguan ini terjadi karena dirangsangnya keserakahan manusia terhadap kekayaan material pada zaman 12 Dikutip dari Ernesto Laclan, Politics and Ideology in Marxist Theory, London: New Left Book, 1977, hal. 82. | 8 | Nomor 14, September - 2007 Pencerahan dan ketika terjadi proses industrialisasi moderen.13 Kemudian Erich Fromm, seorang ahli ilmu jiwa menguraikan bahwa manusia yang bangkit menjadi individu dihadapkan pada dua pilihan. Atau dia bersatu dengan dunia yang berdasarkan cinta kasih dan produktivitas, atau dia mencari keselamatan secara buta dengan meleburkan dirinya ke dalam kekuatan luar dan menghancurkan kemerdekaan dan kemandiriannya sebagai individu. Pada pilihan yang kedua ini orang memang jadi merasa „bahagia“ karena tak usah berpikir sendiri dan tidak usah bertanggungjawab. Meskipun harga yang harus dia bayar adalah kemerdekaannya sendiri. Gejala inilah yang oleh Fromm kemudian dinamakan sebagai kecenderungan kebanyakan manusia untuk takut kepada kemerdekaan, karena kemerdekaan berarti tanggung jawab terhadap pilihannya. Gejala inilah yang menimbulkan fasisme.14 Teori kebudayaan berkembang di masyarakat yang masih setengah feodal, Indonesia tidak terkecuali. 15 Dalam menjelaskan kebudayaan politik di Indonesia, Mattulada misalnya membagi masyarakat menjadi tiga lapisan: kelompok penguasa yang memperoleh kekuasaannya melalui kekuatan adikodrati, kelompok pengabdi penguasa yang memegang jabatan, dan kelompok rakyat jelata yang biasanya menurut saja kepada atasan. Tentang kolompok ketiga ini, Mattulada berkata: Pola-pola tindakannya dalam masyarakat, terutama sejauh yang menyangkut urusan kekuasaan adalah sejauh mungkin „mengiyakan“ dan lebih lanjut mengikutinya dengan setia.16 Sikap seperti ini jelas menyuburkan tumbuhnya otoriterisme dan totaliterisme. Dalam keadaan seperti ini, perubahan masyarakat 13 Ibid. Ibid. 15 Miriam Budiardjo (ed), Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984. 16 Mattulada, “Kebudayaan Politikm dan Keadilan Sosial: Tinjauan Historis” dalam Ismid Hadad (ed), Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial, Jakarta: LP3ES, 1979, hal. 105. 14 | 9 | „baru akan mungkin terjadi kalau dimulai dari lapisan atas masyarakat.“17 Secara lebih canggih, ahli Indonesia yang terkenal, Benedict Anderson menjelaskan mengapa dalam konsep kekuasaan budaya Jawa tidak dikenal adanya oposisi. Dalam salah satu artikelnya yang terkenal, dia menjelaskan bahwa dalam Kebudayaan Jawa, kekuasaan merupakan sesuatu benda yang konkrit, yang jumlahnya terbatas dalam jagad raya ini.18 Jumlah kekuasaan yang ada ini tetap, tidak bisa bertambah atau berkurang. Karena itu, setiap penguasa bila kepingin aman, harus mengumpulkan kekuasaan sebanyak-banyaknya. Kekuasaan yang ada di luar dirinya, misalnya pada kaum oposisi, berarti mengurangi porsi kekuasaan di tangannya. Kekuasaan tersebar menurut prinsip zero-sum-game. Akibat adanya persepsi kebudayaan seperti ini, maka penguasa Jawa pada dasarnya bersikap alergis terhadap oposisi. Kekuasaan mau dipegang sebanyak-banyaknya di dalam tangannya. Dengan kata lain, penguasa Jawa mempunyai kecenderungan untuk menjadi otoriter dan totaliter. Kritik terhadap penguasa memang masih mungkin, tapi harus dinyatakan dalam bentuk yang tidak menunjukkan adanya kekuasaan tandingan. Menurut Anderson, kritik dapat dinyatakan oleh para petapa dan para resi, yang jelas menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik pada kekuasaan duniawi. Atau dapat juga kritik dinyatakan oleh para punakawan, badut istana, dalam bentuk setengah lelucon. Semua kritik yang menunjukkan ciri-ciri kekuasaan tandingan akan dibasmi. Kelompok teori sosio historis atau struktural historis lebih melihat kepada kekuatan-kekuatan dan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Timbulnya fasisme memang cukup mengejutkan masyarakat Barat, karena bukankah kehidupan masyarakat sipil (civil society) sudah sangat kuat dan demokrasi 17 Ibid. Benedict Anderson, “Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa” dalam Miriam Budiardjo (ed.), op.cit. 18 | 10 | Nomor 14, September - 2007 sudah mentradisi? Mengapa tiba-tiba muncul sebuah pemerintah yang totaliter, dan pemerintah ini didukung oleh massa? Apalagi pemerintah yang seperti ini muncul di Jerman yang tradisi kebudayaannya sudah dapat dianggap sangat tinggi. Salah satu dari prototipe dari pendekatan sosio historis adalah uraian dari Marx tentang negara Bonapartis. Dalam menguraikan bentuk negara ini, Marx dihadapi sautu pertanyaan bagaimana sebuah negara bisa menjadi otonom, berdiri di atas kelas-kelas yang ada dan bukan sekedar alat dari kelas yang dominan. Marx akhirnya sampai pada kesimpulan, karena kelas yang seharusnya menjadi dominan dalam masyarakat tertentu gagal untuk menegakkan hegemoni kelasnya atas kelas-kelas lainnya. Kalau pertentangan antara kelas yang (seharusnya) dominan ini melawan kelas lainnya yang makin bertambah kuat itu dibiarkan, maka ada kemungkinan sistem yang ada bisa hancur. Karena itulah negara melakukan intervensi untuk menyelamatkan sistem, dan lahirlah negara Bonapartis yang mengatasi kelas-kelas yang ada.19 Otto Bauer, yang sebagian penjelasannya sudah dikutip pada permulaan tulisan ini, termasuk salah seorang penganut teori sosio historis. Dalam menguraikan timbulnya fasisme, dia menyebut terjadinya tiga proses sejarah yang saling berkaitan. (1). Perang Dunia I mengakibatkan jatuhnya banyak orang dari kehidupan kelas menangah. Orang-orang ini kemudian membentuk kelompok fasis. (2). Krisis ekonomi sesudah perang juga memiskinkan orang-orang dari kelas menengah bawah dan kaum tani. Orang-orang ini kemudian memindahkan dukungannya dari partai-partai yang memperjuangkan demokrasi kepada partai-partai atau kelompok yang lebih militan. Karl Marx, The Eighteeth Brumaire of Louis Bonaparte, New York: International Publisher, 1963. 19 | 11 | (3). Krisis ekonomi ini juga mengurangi keuntungan kaum kapitalis besar. Mereka butuh mengeksploitir buruh-buruhnya secara lebih intensif. Hal ini tak dapat dilakukan dalam suatu sistem yang demokratis. Karena itu mereka lalu berpaling kepada kelompok fasis sebagai jalan keluar.20 Masih banyak contoh yang dapat diberikan dari kelompok teori sosio historis ini. Tapi, kedua contoh tadi kiranya cukup untuk memberikan gambaran apa kira-kira dari teori sosio historis, dan apa bedanya dengan kelompok teori psikologi dan kebudayaan. Indonesia Bagaimana keadaannya di Indonesia? Apakah Indonesia pada saat ini dapat digolongkan menjadi rejim yang otoriter atau totaliter? Pertanyaan ini memang tidak mudah dijawab. Hal ini disebabkan, dalam kenyataannya realitas selalu lebih majemuk daripada teori. Teori selalu menuju pada penggambaran idiel dari tipe yang diuraikan, sedangkan realitas merupakan campuran dari pelbagai tipe, yang satu lebih dominan daripada yang lainnya. Untuk Indonesia sekarang, sulit untuk dibantah, bahwa memang sumber kekuasaan sekarang ada di tangan pemerintah. Hampir semua kemauan pemerintah pada dasarnya tidak dapat ditentang, karena lembaga-lembaga nonpemerintah tidak cukup kuat (secara politis) untuk menentangnya. Pemerintah hanya dapat dikritik dalam hal-hal yang bersifat teknis belaka, misalnya pelaksanaan program tertentu kurang baik dijalankan, karena pelaksanaannya kurang kompeten; atau perusahaan-perusahaan negara sebaiknya diswastakan karena orang-orang yang mengurus kurang bekerja secara efisien, dan sebagainya. Ini pun tergantung pada pemerintah, mau melayani atau tidak kritik-kritik ini. 20 Tom Bottomore (ed.), op.cit., hal. 162. | 12 | Nomor 14, September - 2007 Apakah pemerintah yang sekarang merupakan pemerintah yang totaliter? Kalau menurut definisi formalnya, jelas tidak. Di Indonesia tidak hanya ada satu partai, tapi tiga. Ada pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Ada parlemen, dan sebagainya. Tapi, juga tidak dapat disangkal bahwa kecenderungan ke arah totaliterisme memang ada. Misalnya, meski ada tiga partai, tampaknya partai yang mendukung pemerintah sangat berkuasa dan sangat menentukan. Juga ada kecenderungan untuk memaksakan berlakunya satu ideologi politik saja. Adanya kecenderungan untuk memonopoli kontrol terhadap media massa, sarana-sarana pelaksana dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Adalah tugas kita semua, baik yang di pemerintah maupun di luar pemerintah, untuk mencegah supaya hal ini tidak terjadi. Sesudah mengatakan hal ini, maka pertanyaan kita adalah faktorfaktor apa yang menyebabkan terjadinya kecenderungankecenderungan ini? Teori yang dominan, seperti dikatakan sebelumnya dalam tulisan ini, adalah teori kebudayaan. Kecenderungan otoriterisme dan totaliterisme merupakan penjelmaan dari kehidupan kebudayaan yang ada, khususnya kebudayaan Jawa. Teori psikologi biasanya dikembalikan kepada teori kebudayaan ini. Pada diri individu ada kecenderungan untuk manut ke atas, karena itulah nilai kebudayaan yang ada.21 Kelemahan dari teori kebudayaan ini pertama-tama karena sifatnya yang a-historis. Kebudayaan kurang dikaitkan dengan kejadiankejadian atau peristiwa sosial yang terjadi di sekitarnya, ia seakanakan tidak tersentuh oleh peristiwa-peristiwa sosial yang ada. Kalaupun ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa kaitan ini ada, mereka pada umumnya tidak dapat menjelaskan bagaimana persisnya interaksi antara nilai-nilai budaya dengan peristiwaperistiwa sosial di sekitarnya. Lihat Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1974. 21 | 13 | Akibatnya, nilai-nilai budaya seakan-akan terus ada pada suatu masyarakat, dari dulu sampai sekarang. Dinamika perkembangan dan perubahan nilai-nilai ini tidak atau belum dapat dijelaskan. Nilai-nilai ini memang kemudian berbenturan dengan nilai-nilai kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia, tapi tidak dapat dijelaskan mengapa kemudian nilai-nilai Barat yang menang, atau mengapa nilai-nilai kebudayaan Jawa pada dasarnya masih terus hidup dan menjelma dalam pelbagai bentuk kehidupan. Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan nilai-nilai kebudayaan ini? Kelemahan kedua dari teori kebudayaan adalah persangkaannya bahwa masyarakat merupakan sesuatu yang homogen, tidak terdiri dari kelompok-kelompok atau kelas yang berbeda. Misalnya, dalam masyarakat orang Jawa dapat dipertanyakan, apakah benar semua lapisan masyarakat Jawa mengikuti apa yang disebut nilai-nilai kebudayaan Jawa? Koentjaraningrat, salah seorang ahli paling canggih di Indonesia yang menganut teori kebudayaan, secara selintas telah menunjukkan bahwa jawabannya tidak. Dalam bukunya yang sangat populer,22 dia menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai, misalnya kemandirian, atau sikap vertikal atau selalu manut ke atas antara kaum priyayi (kelas menengah) dan wong cilik (kelas bawah).23 Demikian juga tentang teori kebudayaan mengenai kekuasaan (Jawa), kelemahan yang disebut tadi dapat dipakai sebagai kritik terhadapnya. Sampai berapa jauh nilai-nilai kebudayaan tentang kekuasaan dan tentang pengabdian masih tetap berlaku di Indonesia moderen sekarang? Kemudian, tidakkah terdapat perbedaan dalam cara dan intensitas penghayatan nilai-nilai ini Ibid., hal. 43-47. Dalam tulisannya yang lain yang membahas konsep kekuasaan Koentjaraningrat bahkan membicarakan perubahan konsep ini dalam beberapa kurun waktu, serta perbedaan dalam masyarakat kecil dan besar. Meskipun demikian, pembahasannya tidak atau kurang menekankan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Yang lebih ditekankan adalah perbedaan/perubahan persepsi kekuasaan. Lihat Koentjaraningrat “Kepemimpinan dan Kekuasaan: Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi” dalam Miriam Budiardjo (ed.) op.cit. 22 23 | 14 | Nomor 14, September - 2007 pada kaum priyayi (kelas menengah dan atas, kelompok yang dominan dalam masyarakat) dan pada wong cilik (kelas bawah, rakyat jelata?) Juga tidakkah terdapat perbedaan antara masyarakat yang hidup di kota-kota besar dengan masyarakat yang hidup di desa-desa. Suatu penelitian yang intensif mengenai sub-kebudayaan yang ada di Indonesia, dan bukan hanya kebudayaan yang makro saja, masih merupakan agenda yang harus dilaksanakan. Tapi yang lebih penting lagi, diperlukan suatu teori kebudayaan yang dapat menjelaskan dinamika dakhil atau internal dari perkembangan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Kritik-kritik ini tidak mengatakan bahwa nilai-nilai kebudayaan tentang kekuasaan dan pengabdian merupakan sesuatu yang tidak ada di Indonesia. Nilai-nilai ini ada dan memang berperan dalam perkembangan masyarakat politik kita. Tapi penjelasan yang datang dari kubu teori kebudayaan saya anggap masih belum memuaskan. Kecenderungan otoriter dan totaliter dari negara kita barangkali dapat dijelaskan dengan melihat perkembangan negara itu sendiri dan kelompok-kelompok masyarakat di sekitarnya sepanjang sejarah. Mari kita mulai dengan zaman kolonial. Negara kolonial dulu memang dibuat menjadi kuat, karena dimaksudkan untuk menjajah. Negara kolonial dulu kira-kira sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alavi, bahwa negara seperti ini dibuat untuk mengatasi semua kelas dan kelompok yang ada di masyarakat yang dijajah.24 Aparatur negara berkembang sedemikian rupa, sehingga dalam hal kekuatan politik dan militernya, tak ada kelompok dalam masyarakat tersebut yang dapat menandinginya. Pada zaman kolonial masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orangorang Eropa yang kebanyakan terdiri dari orang Belanda. Mereka merupakan kelompok kelas atas, terdiri dari orang-orang di 24 Hamzah Alavi, “The State in Post Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh.” | 15 | pemerintahan dan para pengusaha besar (pemilik perkebunan, industrialis, pedagang internasional, dan sebagainya). Kelompok kedua adalah orang Cina (dan orang Asia lainnya, seperti Jepang, India, dan lain-lain). Orang-orang Cina ini menguasai perdagangan dalam negeri. Kebanyakan mereka tergolong kelas menengah. Kelompok orang-orang Indonesia asli atau pribumi sendiri kebanyakan adalah petani. Sebagian dari mereka masuk ke dalam pemerintahan kolonial Belanda, menjadi pamong praja. Sebagian ada yang berdagang, terutama yang dari Sumatera. Tapi mayoritas dari mereka adalah petani miskin. Sehingga kelompok ini termasuk ke dalam kelas bawah. Keadaan ekonomi ketiga kelompok ini pada tahun 1930 dinyatakan oleh Paauw sebagai berikut: Kalau pendapatan rata-rata dari orang Indonesia yang bekerja diberi indeks satu, maka pendapatan rata-rata orang Asia yang bekerja adalah lima, dan orang Eropa empat-puluh-tujuh. Pada tahun 1939 perbedaan ini jauh lebih menyolok lagi: Indonesia satu, Asia delapan dan Eropa enam-puluh-satu.25 Pemerintah kolonial memang sengaja menghalangi orang-orang pribumi untuk menjadi pengusaha. Sebagai kekuatan kolonial yang kecil (bandingkan dengan Inggris atau Spanyol), mereka sangat tergantung pada pengusaha-pengusaha pribumi untuk membantu mereka memerintah. Dengan demikian, kaum bangsawan dirangkulnya, dan diberi kekuasaan administratif, meski terbatas. Kekuatan administrator pribumi ini akan menjadi berbahaya bagi pemerintah kolonial kalau mereka juga memiliki kekuatan ekonomi. Karena itulah, kegiatan ekonomi dipegang oleh orangorang Belanda dan Cina. Burjuasi pribumi dengan demikian gagal tumbuh di Indonesia. Sebagai gantinya yang muncul dari kalangan pribumi adalah kelompok pamong praja. 25 Douglas S. Paauw, “Frustrated Laour-Intensive Development: The Case of Indonesia,” dalam Eddy Led (ed.), 1981. | 16 | Nomor 14, September - 2007 Burjuasi Cina yang muncul, pada titik tertentu, juga dianggap berbahaya. Pembantaian orang-orang Cina pada tahun 1740 di Jakarta merupakan usaha pemerintah Belanda untuk mencegah tumbuhnya dan menjadi kuatnya burjuasi ini. Kaum ibu dan anakanak pun turut menjadi korban dalam peristiwa itu. Ini semua membuktikan betapa kejamnya kekuasaan kolonial,26 (Kemasang, 1986). Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan, struktur kemasyarakatan kolonial ini masih bertahan, yakni, perusahaanperusahaan besar, industri dan perkebunan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha Belanda, perdagangan dalam negeri oleh orang-orang Cina, sedangkan orang-orang pribumi menjadi petani, ditambah dengan pembesar-pembesar negara. Tapi pembesar negara ini tidak memiliki sumber-sumber ekonomi. Burjuasi pribumi tidak ada, dan usaha untuk membentuknya melalui Program Benteng pada tahun 1950-an gagal.27 Negara yang memiliki kekuatan politik ini baru memperoleh kekuatan ekonominya setelah terjadi nasionalisasi perusahaanperusahaan Belanda (kemudian juga perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika) yang dimulai pada tahun 1957. Perusahan-perusahaan ini kemudian dikuasai negara, dan dikelola oleh militer. Pada titik ini dimulailah peran militer dalam sektor ekonomi. Sejak tahun 1985, peran kamu militer bertambah lagi dengan beralihnya kekuasaan politik ke tangan mereka. Pemerintah yang kemudian dikenal dengan pemerintah orde baru pada dasarnya merupakan pemerintah yang didominir oleh kaum militer, yang menguasai aparat-aparat birokrasi politik, dan prasarana ekonomi. 26 A.R.T. Kemasang, “Bagaimana Penjajah Belanda Mengebiri Burjuasi Domestik di Jawa,” Krisis (Salatiga), No. 1, Tahun 1, Juli 1986. 27 K.D. Thomas dan J. Panglaykim, Indonesia – The Effect of Past Politics and President Suharto’s Plans for the Future, Australia: Committee for Economic Development of Australia, 1973. | 17 | Bagaimana dengan lembaga atau kelompok-kelompok di luar pemerintah? Apakah mereka cukup kuat mengimbangi pemerintah, dan menuntut supaya kepentingannya diperhatikan? Di sektor ekonomi, terdapat pengusaha asing, pengusahapengusaha Indonesia keturunan Cina (non-pribumi) dan pengusahapengusaha Indonesia asli (pribumi). Pengusaha asing jelas kuat dalam segala hal: modal, teknologi dan jalur pemasaran. Mereka dibutuhkan oleh pemerintah karena kekuatan mereka di ketiga sektor ini, plus bantuan pinjaman-pinjaman dari negara asal pengusaha terebut. Pengusaha asing ini menekan pemerintah Indonesia untuk sistem ekonomi yang terbuka dan kompetitif, baik di dalam maupun di luar negeri. Tentu saja ini sesuatu yang wajar bagi kepentingan mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa berkompetisi dengan siapa saja di kalangan pengusaha nasional. Kemudian terdapat sektor pemerintah. Sektor ini praktis menguasai sebagian besar perekonomian Indonesia, melalui ratusan BUMN termasuk perusahaan tambang minyak Pertamina, bankbank negara, dan sebagainya.28 Dengan adanya sektor negara yang besar ini, maka sektor swasta sebenarnya hanya berperan secara periferik dalam kehidupan ekonomi. Bahkan sebagian orang mengatakan peran swasta hanyalah merupakan subkontraktor proyek-proyek pemerintah. Setelah sektor pemerintah, maka sektor non-pemerintah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha non-pribumi. Sebuah penelitian tentang penanaman modal menunjukkan angka-angka sebagai berikut: 28 Jumlah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) semuanya ada 215 buah, termasuk Pertamina. Untuk menggambarkan besarnya kawasan perusahaan negara ini, di sektor perbankan misalnya, 70% kredit yang beredar berasal dari bank-bank negara. Belum lagi diperhitungkan saham-saham bank negara di lembaga-lembaga non bank. Di bidang produksi, misalnya di sektor pertambangan adanya perusahan-perusahaan raksasa milik negara seperti Pertamina, PT. Timah dan PN Batubara sudah menggambarkan posisi kuat dari pemerintah. (Kompas, 14 Februari 1987). | 18 | Nomor 14, September - 2007 Penanaman Modal Dalam Negeri Negara 58,75% Non-Pribumi 26,95% Pribumi 11,20% Lain-lain 3,10% SUMBER: Tempo, 14 Maret 1981: 71. Suatu hal yang menarik dari pengusaha non-pribumi ini adalah bahwa posisi politik mereka sangat lemah. Ketika zaman kolonial pengusaha Cina ini mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial dalam rangka menghambat pengusaha pribumi untuk berkembang. Sebagai akibat, pengusaha Cina atau non-pribumi ini kurang disukai, terutama oleh mereka yang terlibat dalam dunia bisnis. Keadaan ini masih berlangsung sampai sekarang. Karena itu, pengusaha-pengusaha non-pribumi sangat membutuhkan perlindungan dari pemerintah yang berkuasa. Dari pihak pemerintah, tampaknya ada kebutuhan untuk memakai pengusaha non-pribumi sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan. Adanya burjuasi pribumi yang kuat dan mandiri akan merupakan tantangan bagi pemerintah yang berkuasa, paling sedikit membatasi kekuasaan pemerintah. Hal ini tidak terjadi kalau burjuasi yang muncul adalah burjuasi nonpribumi yang secara politis lemah. Lalu, bagaimana dengan burjuasi pribumi? Menarik sekali ternyata pengusaha-pengusaha pribumi ini muncul dan menjadi kuat karena koneksinya dengan para birokrat negara, baik koneksi bisnis maupun koneksi kekeluargaan. Dengan adanya hubungan yang dekat antara birokrat negara dan pengusaha pribumi, maka kekuasaan politik para birokrat ini jadi tidak terganggu, karena pengusaha pribumi ini tergantung pada fasilitas yang diberikan negara. Kebanyakan pengusaha pribumi ini memang bukan pengusaha yang produktif, bukan entrepreneur, sehingga kesuksesan usahanya sangat tergantung pada fasilitas yang diberikan. Dengan demikian, | 19 | pengusaha-pengusaha ini pun tidak dapat diangap sebagai burjuasi, dalam arti mereka bukan pengusaha kuat yang mandiri yang dapat menampilkan dirinya sebagai kekuatan tandingan terhadap negara. Dalam keadaan seperti ini, posisi pemerintah orde baru tampaknya cukup kuat dalam menghadapi tantangan kelas menengah. Kelas menengah yang ada terlalu lemah, kelas burjuasi tampaknya belum muncul di Indonesia. Sedikitnya untuk masa yang sekarang ini. Tantangan yang datang dari kelas bawah kelihatannya juga lemah. Kelas bawah, baik kaum tani maupun kaum buruh, tampaknya belum berhasil mengorganisir dirinya menjadi kekuatan yang mandiri. Ini mungkin disebabkan karena trauma 1965, yakni ketika PKI mencoba mengorganisir mereka tapi emudian berakhir dengan terumpasnya gerakan ini. Sejak itu, pemerintah tampaknya secara ketat mengatasi segala macam gerakan di kalangan kelas bawah, supaya semacam peristiwa tahun 1965 tidak terjadi lagi. Segala macam gerakan yang mengarah kepada kemungkinan terjadinya pertentangan kelas, segera ditumpas secara dini. Karena itu pertentangan yang terjadi tampaknya beralih kepada persengketaan suku, khususnya Islam dan Kristen. Persengketaan ini, tidak dapat disangkal, sedikit banyak berbau pertentangan kelas juga. Golongan pribumidan Islam mewakili orang-orang kelas bawah, sedangkan golongan non-pribumi/Cina dan Kristen mewakili kelas menengah. Kalau kita mau berbicara tentang tipe, lalu tipe apakah negara Indonesia yang sekarang? Sekali lagi, seperti sudah dinyatakan sebelumnya, kenyataan selalu lebih majemuk daripada teorinya. Indonesia jelas bukan negara otoriter ataupun totaliter, meskipun kecenderungan ke arah itu ada. Kecenderungan ini disebabkan karena pelbagai faktor, antara lain nilai-nilai kebudayaan yang masih ada di mana rakyat kelas bawah cenderung untuk menerima dan patuh kepada kekuasaan, dan juga perkembangan sejarah kelompok-kelompok masyarakat yang ada memang lemah dalam | 20 | Nomor 14, September - 2007 menghadapi negara. Juga jelas Indonesia bukan merupakan negara totaliter mkomunis. Apakah Indonesia termasuk tipe negara fasis? Ini juga sulit dikatakan. Memang ada beberapa ciri fasisme yang dapat dikenakan, tapi kemudian terdapat ciri-ciri lain yang menyangkalnya. Misalnya, ada kecenderungan kuat untuk mengidentifkan keinginan negara sebagai keinginan bangsa. Individu yang berpendapat dan cenderung dituduh sebagai tidak patuh kepada cita-cita bangsa ini. Kemudian ada partai pelopor yang kuat yang mendukung pemerintah, tapi harus dicatat bahwa partai ini terbentuk sesudah pemerintah yang kuat lahir, bukan sebelumnya. Ideologi yang dianut oleh partai ini juga merupakan ideologi negara yang disebarluaskan ke masyarakat. Bahkan masyarakat diharuskan menganut ideologi ini. Tapi harus dicatat pula bahwa ideologi ini lebih merupakan ideologi pemersatu bangsa, bukan ideologi yang secara emosional dapat menggerakkan massa seperti halnya komunisme ataupun Nazi-isme. Bahkan ada kecenderungan yang kuat pemerintah Orde Baru berusaha untuk melakukan depolitisasi massa. Apakah ini berarti bahwa Indonesia lebih mirip dengan rejimrejim yang ada di Dunia Ketiga? Kemudian, rejim yang mana: negara birokratis otoriter, atau negara korporatis? Sekali lagi kita mengalami kesulitan untuk memasukkan Indonesia ke dalam salah satu kotak secara bulat. Adanya proses depolitisasi massa memang lebih mendekatkan Indonesia pada rejim-rejim yang ada di Dunia Ketiga. Tapi sulit untuk dikatakan bahwa Indonesia merupakan rejim otoriter birokratis, karena pemerintah otoriter yang kuat sudah ada di Indonesia bahkan ketika dilakukan proses industri substitusi impor.29 Padahal, menurut orang yang melahirkan konsep ini, Guillermo O’Donnell, negara otoriter birokratis muncul pada saat peralihan dan proses industri substitusi impor ke industri 29 Arief Budiman, “The Emergence of The Capitalist Bureaucratic State in Indonesia.” Mimeograph, 1986. | 21 | yang berorientasi ekspor. Negara korporatis juga sukar untuk dikatakan sebagai tipe negara kita sekarang. Memang ada kecenderungan yang kuat, dimulai sejak presiden Soekarno, untuk mengelola sistem politik kita berdasarkan sistem perwakilan golongan fungsional, seperti wakil buruh, wakil tani, wakil pemuda, dan sebagainya. Lahirnya Golongan Karya juga disebabkan adanya pemikiran ini. Tapi dalam kenyataannya, pada pemerintah yang sekarang golongan-golongan fungsional ini kurang diberi peran politik oleh pemerintah. Golongan Karya sendiri tidak terlalu menekankan dirinya sebagai kelompok dari orang-orang yang berkarya (ini pun suatu konsep yang terlalu luas, karena praktis seluruh penduduk Indonesia dapat dimasukkan ke dalam kategori ini), tapi lebih menekankan ideologi Pancasila dan Pembangunan dalam memainkan kartu politiknya. Maka sekarang tentunya terpulang kepada kita untuk menentukan, tipe mana yang menurut kita paling dekat dalam menggolongkan pemerintah Orde Baru yang sekarang. Kembali kepada judul tulisan ini, kebudayaan kekuasaan atau sosiologi kekuasaan, pilihan saya sendiri jatuh kepada telaah kekuasaan dari sudut sosiologi. Bagi saya pendekatan sosiologi dalam mempelajari gejala kekuasaan lebih memberikan penjelasan dan kejelasan tentang gejala kekuasaan ini, bukan saja sebagai gejala, tapi juga asal mula perkembangannya serta kemungkinan perubahannya. Ini tidak berarti nilai-nilai kebudayaan tidak ada, paling sedikit sebagai gejala. Tapi, untuk saya sendiri, saya lebih senang menjelaskan adanya nilai-nilai kebudayaan ini dengan melihat struktur masyarakat di mana nilai-nilai tersebut menggejala, dan kemudian menjelaskan timbulnya nilai-nilai tersebut dari interaksi kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Misalnya, dalam melihat masyarakat yang berorientasi vertikal ke atas, selalu menunggu petunjuk dari atas, maka yang harus dipertanyakan adalah apakah | 22 | Nomor 14, September - 2007 nilai-nilai ini tidak berubah bila misalnya kelompok di bawah ini bisa hidup secara lebih mandiri? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan dari suatu pendekatan sosiologis. Akhirnya yang perlu saya katakan bahwa tulisan ini bertujuan untuk melemparkan gagasan-gagasan, yang semoga dapat membuat kita berpikir kembali dalam menelah persoalan yang dibahas, termasuk saya sendiri. >>><<< Yayasan Penebar adalah institusi nir-laba independen. Kami berharap saudara/i (individu) maupun organisasi bersedia mendukung aktivitas kami. Kami menerima donasi, hibah dan dukungan tak mengikat dalam bentuk apapun. Bila saudara/i bermaksud mendukung kami dengan mendonasikan uang, rekening bank kami adalah: BCA (Cabang Cimanggis), rekening Tahapan BCA, nomor account: 166 1746276. | 23 |