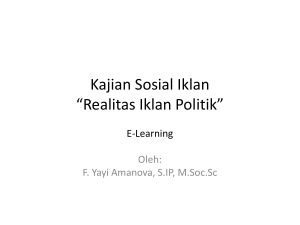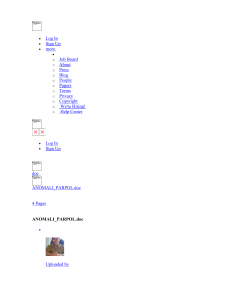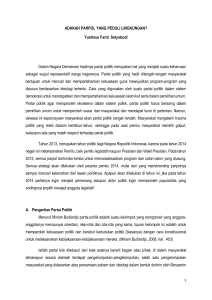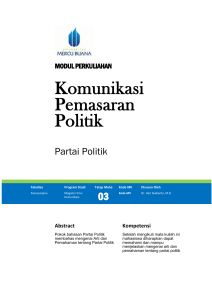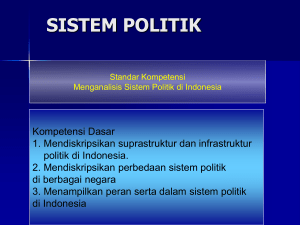EKUALITAS DAN DINAMIKA POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI
advertisement

EKUALITAS DAN DINAMIKA POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA Oleh : Dr.H.Pandji Santosa,Drs.,M.Si. — Dosen FISIP UNLA Abstract, Elections in Indonesia, which will be held on 9 April 2009 seem to have diwamai by the emergence of many new parties . As with the old political parties , their appearance was greeted cool people , some people are skeptical memiai that new parties can bring improvements or significant changes to public aspirations . On the other hand it is understood that it is the nation 's political transition towards a major change in democracy . In a democratic system of government , political parties serve as an ideal representation of the interests of citizens in channeling political interests and aspirations towards legislative and executive seats in the election . Besides functioning political parties also bequeathed to democratic values and to prepare future leaders with the vision of a more democratic . However, many new political parties that continue to emerge that indicate that such a large appetite for politicians scramble horn power. If we look closely, there really is not a strong democratic state which party a lot . In the United States alone there are only two parties , Republican and Democrat . In English too. It was hard to be denied , with a multi-party system is only effective for the nascent state or just out and authoritarian systems , but becomes ineffective for a country whose government is relatively stable . As in Indonesia is relatively stable , it is no longer relevant to a multiparty system in the tens of excessive party . Bipartai system also certainly not feasible , because of party political bias hitherto trusted completely Keywords : Election , Government . Party Politics , Democracy I. PENDAHULUAN Pemilihan umum di Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 9 April tahun 2009 nampaknya telah diwamai oleh munculnya banyak partai baru. Seperti halnya parpol lama, kemunculan mereka disambut dingin masyarakat, sebagian kalangan skeptis memiai bahwa parpol baru dapat membawa perbaikan atau perubahan signifikan terhadap aspirasi publik. Pada sisi lain dapat dipahami bahwa hal itu merupakan transisi politik bangsa menuju perubahan besar dalam berdemokrasi. Reaksi publik yang menunjukan sikap apatis dan cenderung tidak rneyakini bahwa system tersebut bisa berjalan secara efektif juga diikuti rasa pesimis dan sisnisme yang tinggi terhadap sepak terjang para aktor politiknya. Jika path fase awal reformasi, fenomena politik di tanah air dicirikan oleh gairah politik publik yang sangat besar terhadap setiap proses politik, seperti pendirian partai dan kampanye pemilu, kini seolah terjadi arus balik dan partisipasi publik. Dan seluruh survey atau jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagal lembaga, bisa dipastikan bahwa tak ada satupun hasil survey yang menunjukan persepsi publik yang positif terhadap peran parpol misalnya. seluruh survey menunjukan bahwa parpol hanya dianggap sebagai kendaraan politik belaka dan para aktor politik untuk menuju panggung kekuasaan, ketimbang sebagai lembaga representasi politik yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan demokratis, parpol idealnya berfungsi sebagai representasi kepentingan warga negara dalam menyalurkan kepentingan dan aspirasi politik menuju kursi legislatif dan eksekutif dalam pemilu. Selain itu parpol juga berfungsi mewariskan nilai-nilai demokrasi dan menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan dengan visi yang lebih demokratis. Namun, tidak sedikit parpol baru yang terus bermunculan itu menunjukkan nafsu politisi yang sedemikian besar untuk berebut tanduk kursi kekuasaan. Kalau dicermati, sebenarnya tidak ada negara demokratis kuat yang partainya banyak. Di Amerika Serikat saja hanya ada dun partai, Republik dan Demokrat. Di inggris pun demikian. Rasanya sulit disangkal, dengan sistem multipartai hanya efektif untuk negara yang baru lahir atau barui keluar dan sistem otoriter, tapi menjadi tidak efektif untuk negara yang pemerintahnya relatif stabil. Seperti di Indonesia relatif stabil, maka tidak relevan lagi system multipartai eksesif yang mencapai puluhan partai. Sistem bipartai juga tentu belum layak, karena partai politik sampai sekarang belum bias dipercaya sepenuhnya. Satu pertanyaan yang mesti dikaji yakni, mengapa parpol-parpol baru itu terus bermunculan? Sistem multipartai yang diterapkan sejak fase awal reformasi kemudian dilanjutkan oleh sejumlah inovasi prosedural lainnya seperti sistem pemilihan presiden langsung, pemilihan kepala daerah langsung dan dibukanya pintu masuk bagi kandidat non partai untuk bertarung dalam pilkada. Terdapat pula kecendrungan bahwa liberalisasi sistem politik ini akan terus bergulir dengan rancangan UU pemilu yang semakin mengarah kepada sistem distrik dan penghapusan nomor urut. Namun demikian, seiring dengan perubahanperubahan pada ranah kelembagaan tadi, pesimisme publik terhadap prospek demokratisasi di negeri ini malahan semakin mencolok. Tulisan ini akan berupaya untuk mengkaji kesenjangan antara proses demokrasi dan harapan publik untuk hidup secara demokratis rnelalui suatu analisis terhadap keberadaan partai politik, skenario konflik dan dinamika system demokrasi di Indonesia. II. EKUALITAS POLITIK William Liddle (1998), pernah berkata idealnya Indonesia memiliki kurang dan 10 partai, bahkan di bawah lima. Dalam realitasnya banyaknya parpol di Indonesia setelah masa reformasi hingga sekarang tidaklah kondusif bagi kehidupan politik nasional. Pasalnya, hampir semua parpol, baik yang besar maupun yang kecil, tidak pemah sepi dan konfik yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Kondisi seperti itu menyebabkan energi parpol habis terkuras hanya untuk soal-soal yang tidak substansial. Konflik-konflik selalu muncul menjelang atau sesudah kongres atau muktamar partai. Nyaris tidak ada diskusi atau perdebatan yang signifikan dalam partai mengenai soal-soal yang lebih mendasar daripada sekadar menyodorkan wacana ribut-ribut bagi kekuasaan untuk mendapatkan posisi tertinggi dalam partai. Ada beberapa alasan politis yang dapat dipahami. Pertama, adanya kebangkitan pretorianisme politik. Masa peralihan dari habitus lama ke habitus baru, sejak keruntuhan Soehartoisme pada 1998. Di koridor logika inilah kemunculan berbagai parpol baru tumbuh. Ketika tidak ada organisasi politik yang cukup berwibawa, setiap kekuatan sosial dalam masyarakat akan menjelma menjadi kekuatan politik yang dengan agresif berupaya mempengaruhi proses politik. Kedua, adanya kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Dengan lahirnya parpol-parpol baru ini merupakan pertanda bahwa legitimasi pemerintah yang diproduksi oleh parpol-parpol lama sudah lapuk sehingga perlu ada pemerintah baru yang dihasilkan oleh parpol-parpol baru. Hal ini bermakna ganda. Positif sebagai salah satu kondisi penting untuk menghasilkan suatu “pemerintah yang bertanggung jawab (Lively, 1975), sekaligus negatif sebagai bukti ketidakstabilan politik. Ketiga, mencari jalan untuk merebut kekuasaan. Boleh jadi, agresivisme mendirikan parpol baru di kalangan segelintir pelaku politik ini mencerminkan mentalitas “haus kekuasaan”. Bahwa dengan mendirikan partai otomatis ada jalan untuk meraih jabatan. Umumnya, paradigma ini ada pada para pemaín politik baru yang kesulitan bergabung dengan partai lama atau bisa juga para pemain lama yang tidak lagi diperhitungkan oleh partainya. Apa pun alasan dasar di balik pendirian partai-partai ini, yang pasti demokrasi bukan sistem sekali jadi. Dalam proses pendidikan politik, munculnya fenomena parpol baru ¡ni mengandung implikasi kontradiktif. Pertama, memperluas ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik karena substansi demokrasi adalah kesetaraan politik. Lebih jelasnya, ada dua bentuk kesetaraan, yakni kesetaraan retrospektif dan kesetaraan prospektif. Kesetaraan retrospektif artinya setiap orang memiliki peluang yang sama dan setara untuk terlibat dalam proses politik, sedangkan kesetaraan prospektif artinya setiap orang tidak boleh dícegah atau dihambat untuk terlibat dalam proses politik (Jack Lively, 1975: 30-52). Maka, dalam konteks kesetaraan politik (political equality), kehadiran partaipartai baru tersebut merupakan manifestasi hak politik untuk terlibat dalam politik. Kedua, melemahkan “suara rakyat” yang menjadi sumber kekuasaan politik karena banyaknya partai membuat suara rakyat terpecah-pecah dan ujung-ujungnya, yang menang dalam pemilihan umum hanyalah “mayoritas kecil” yang tidak mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Konsekuensinya, suara rakyat tidak tercecer ke mana-mana dan menjadi tidak berharga karena mengalir ke partai-partai kecil yang kalah. Akibatriya, yang duduk dalam system politik, mewakili seluruh rakyat, adalah para wakil yang hanya memperoleh dukungan tidak lebih dan 20 persen suara dalam pemilu, seperti banyak anggota DPR hasil Pemilu 2004. Harapan adanya pembaharuan akan selalu muncul, bukanlah nama partainya, namun dapat diukur kinerjanya. Kalau setiap partai yang sudah ada memperbarui kinerjanya maka kepercayaan rakyat akan tumbuh. Dampaknya partai tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Buat apa membuat partai baru kalau kinerjanya sama saja dengan partai lama yang sudah ada? Hal ini justru akan memperburuk iklim demokrasi. Sebab partai yang ada dan terus bermunculan tanpa disertai kinerja yang baik akan menimbulkan antipati dari masyarakat. Masyarakat akan “trauma” dengan yang namanya parpol. Kalau saja sindrome parpolnus barunus tidak segera diobati, maka bersiap-siaplah untuk melihat kekecewaan rakyat yang Iebih besar lagi. III. DINAMIKA POLITIK INDONESIA Maraknya aksi unjuk rasa dewasa ini menggambarkan betapa dinamisnya demokrasi di Indonesia. Fenomena itu muncul manakala sikap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah bersebrangan dengan hati nurani rakyat atau bukan merupakan pilihan yang terbaik (better choice) dan bukan pula sebagai kebutuhan yang dituntut rakyatnya (need community). Tak sedikit persoalan yang tak sesuai dengan kehendak publik menimbulkan ketidakpuasan dan menjadi born waktu yang setiap saat meledak mengarah pada anarki. Alhasil, demokrasi yang telah dibangun sedemikian rupa ternoda dengan aksi-aksi di luar batas norma bangsa yang bermartabat. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998, negeri ini merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di duma setelah Amerika Serikat dan India. Namun, masih ada kecenderungan masyarakat kita memaknai kebebasan demokrasi sebagai sesuatu yang tak terbatas. Tak heran bila setiap persoalan yang tak sesuai dengan kehendak massa, sering kali berujung pada pemaksaan kehendak secara massif dengan segala keradikalannya. Dalam 10 tahun terakhir ini, bisa kita saksikan serangkaian aksi anarki yang telah memakan ribuan korban jiwa. Masih hangat dalam ingatan kita, kasus Ambon dan Maluku sejak (1999), Sampit (2000), Timika, Papua (2006) dan terakhir Tuban, Jawa Tengah (2006). Ini merupakan ilustrasi demokrasi negeri ini yang sudah diluar batas. Ironis memang, sebagai negara hukum, kondisi seperti ini secara tak langsung mencerminkan sebagai negara barbar yang akan mengancam proses demokrasi yang tengah berjalan. Bila saja kondisi dan aksi pemaksaan kehendak massif tersebut terus berlangsung, dikhawatirkan makna demokrasi itu tidak akan berarti apa-apa bagi bangsa ini. Yang lebih memprihatinkan lagi apabila muncul sikap phobi dari masyarakat terhadap demokrasi bahwa demokrasi dianggap sebagai ancaman baru. Dan bukan sebaliknya, demokrasi yang dibangun merupakan landasan penting bagi pembangunan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat menuju kesejahteraan bersama, sebagai negara yang berdaulat dan sejajar dengan negara-negara lain yang sudah maju lebih dulu. Dalam perspektif demokrasi munculnya sikap anarki, menurut NJ Smelser (1983), ada enam hal yang memengaruhinya. Pertama, structural strain, yakni kejengkelan atas tekanan sosia! berlarut yang tidak terimbangi oleh kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Pada posisi ini apa yang dipandang tertinggi dalam politik harus yang terbaik bagi masyarakatnya (The best regine is good society). Kedua, social condusiveness, yaitu dalam kondisi sosial tertentu yang dapat memungkinkan munculnya aksi di luar batas norma yang ada. Secara psikologis, menurut Gustave Le Bon (1975) dalam teori “Group Coheivenes”-nya, massa yang bergerombol sangat mudah tersulut untuk melakukan anarki, vandalisme, bahkan konflik sosial yang sangat besar. Sebab semakin besar jumlah massa, semakin lupa diri dan tak terkendali kelakuan mereka. Mereka berani melawan petugas, membakar kendaraan, dan merusak fasilitas umum, bahkan !ebih jauh lagi sampai bersifat crime and criminal. Ketiga, generalized hostile belief, yaitu berkembangnya prasangka kebencian terhadap sesuatu, misalnya pemerintah, kelompok ras, agama, atau lawan politik. Massa sudah sangat sulit diajak berpikir secara objektif untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik, sebab sudah tertanam suatu stigma kalau suatu objek tertentu adalah musuh yang harus disingkirkan. Apalagi jalur hukum, sering kali tidak sesuai lagi dengan yang mereka harapkan. Keempat, mobilization for action (mobilisasi massa untuk beraksi), yaitu adanya tindakan nyata dan massa dalam mengorganisasikan diri untuk bertindak. Biasanya aksi anarki hampir selalu didahului oleh demonstrasi massa dalam jumlah yang relatif banyak. Tahap ini merupakan determinan terakhir dan kumulasi determinan yang memungkinkan pecahnya kekerasan. Kelima, lack of social control (melemahnya fùngsi control sosial), dalam hal ini aparat keamanan berwenang seperti tentara dan polisi yang menangani situasi untuk menghambat terjadinya anarki. Semakin kuat determinan kontrol sosial, semakin kecil kemungkinan meletusnya anarkisme, dan sebaliknya bila kewibawaan aparat penegak hukum dilapangan merosot sangat mungkin akan terjadi aksi anarki. Keenam, precipitating factor, yaitu peristiwa dalam kondisi tertentu yang bisa mengawali atau memicu terjadinya aksi anarki. Indikator tersebut, merupakan amunisi yang siap meledak kapan saja. Sementara detonatornya bisa jadi dibentuk oleh statemen seseorang, keputusan politik atau hukum, atau yang bisa memicu konflik sosial lainnya. Faktor lain yang memengaruhi konflik demokrasi dan berujung kepada sisi anarki yakni terhambatnya proses dialogis yang sehat dan terbuka. Di sini betapa pentingnya komunikasi demokrasi yang mampu menjembatani berbagai komunitas dan berbagai elemen dengan pluralitas gaya hidup dan beragam orientasi nilai yang tidak dapat direduksi oleh Negara maupun kekuatan-kekuatan lain. Menurut Alfian, dalam bukunya Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia (1993), komunikasi politik menghubungkan semua bagian dan sistem politik, dan juga masa kini dengan masa lampau, sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Bilamana komunikasi itu berjalan lancar, wajar, dan sehat maka sistem politik itu akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan zaman. Hal ini biasanya terjadi pada suatu sistem politik yang handal, yaitu sistem politik yang mampu mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya secara terus menerus. Lebih jauh lagi, komunikasi demokrasi dan tersedianya ruang publik sebagai wadah aspiratif komunikatif menunjukkan pentingnya pemahaman bangsa terhadap demokrasi yang disebut “demokrasi deliberatif’ sebagai upaya merekonstruksi proses komunikasi dalam konteks negara modem yang demokratis. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas sebuah rencana kebijakan publik diuji lebih dulu melalui konsultasi publik atau wacana publik. Demokrasi deliberatif yakni meningkatkan intensitas partisipasi rakyat dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang atau produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah semakin mendekati harapan rakyat yang diperintah. Artinya, demokrasi deliberatif tidak mengambil keputusan berdasarkan jumlah minoritas atau mayontas, tetapi didasarkan pada proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap berbagai macam kritik, saran, perbaikan dan revisi yang dilakukan secara terbuka, penuh pertimbangan, diskursif dan juga argumentatif. Jadi, pertimbangan utamanya adalah prosedur memperoleh opini masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, yakni legitimitas tenletak bukan pada fakta bahwa mayoritas telah diraih, melainkan fakta bahwa cara meraihnya itu dilakukan dengan fair dan adil. Pada konteks ini, Eisenstadt (2002) mengungkapkan, ruang publik yang sehat setidaknya mensyaratkan adanya empat elemen yang harus dipenuhi. Pertama, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik yang di pinggir atau yang di tengah pusaran kekuasaan dalam sebuah proses interaksi yang sehat dan manusiawi. Kedua, adanýa proses interaksi dalam bentuk wacana publik yang sehat di antara elemen-eIemen masyarakat tersebut. Proses interaksi sosial bisa berupa negosiasi, kontestansi kuasa, bahkan konfrontasi yang berjalan di atas rules of the game yang disepakati bersama, seperti undang-undang, adat lokal, dan sejenisnya. Ketiga, isu yang dikembangkan dalam wacana publik senantiasa terkait dengan kepentingan segenap warga masyarakat, bukan sekadar representasi dan kepentingan sekelompok atau segelintir masyarakat, dalam mendefinisikan apa yang terbaik bagi mereka secara keseluruhan. Keempat, faktor otoritas sebagai arbiter legitimate dalam proses kontestansi kuasa yang diperankan oleh agen-agen pemerintah. Seharusnya peran arbiter di sini tidak lebih dan sekadar mengatur lalu lintas public discourse dimaksud, dan tidak lebih dari itu. Namun, dalam kondisi itu pemerintah sering tidak bisa bertindak netral dalam demokrasi deliberatif, tidak hendak menganjurkan sebuah revolusi, melainkan reformasi negara hukum dengan melakukan gerakan wacana publik di berbagai bidang sosial, politik, dan kultural untuk meningkatkan partisipasi demokratis para warganegara. Dengan cara ini, jurang yang selarna ini menganga antara komunitas masyarakat, eksekutif dan yudikatif dapat dijembatani melalui saluran-saluran komunikasi politis yang sehat dan terbuka. IV. PENUTUP Jika harapan untuk hidup damai sejahtera bisa diwujudkan dan tantangan partai politik untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia kedepan harus tercapai, maka partai politik hendaknya dapat mempertahankan fungsinya sebagai partai politik yang mampu mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan membawa masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang lebih adil, lebih makmur dan berkemanusiaan. Pertanyaan tentang apakah setiap masalah bisa diselesaikan secara demokratis dan elegan melalui jalur hukum, bukan dengan caracara kekerasan maka pantaslah budaya dan etika politik yang sehat dapat mendorong semakin majunya demokrasi di Indonesia. Keberadaan partai politik peserta pemilu yang saat ini sudah final, kini dituntut untuk bisa menghidupkan semangat politik rakyat, dan menghilangkan sikap apatis rakyat pada pola politik Indonesia. Kita berharap keberadaan partai politik baru bénar-benar melakukan koreksi pada sistem demokrasi Indonesia. Dan pilihan terhadap model kepemimpinan partai politik yang mengedepankan semangat kolektifitas, dapat menjadi lokomotif penghidupan politik dan budaya gotong-royong yang kini mulai kehilangan wujud. Penyederhanaan partai politik selanjutnya dimulai dapat merupakan salah satu langkah tepat untuk diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk. Meski jumlah partai politik sedikit, asal didukung kader-kader yang kuat maka akan menjadi energi demokrasi yang luar biasa dan akan membangun kehidupan demokrasi yang tepat. Pemilu sebagai ajang ujian yang sesungguhnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan apakah system ini mampu mengantarkan pemerintahan yang stabil atau tidak. Sehingga kemudian akan bisa menciptakan kemakmuran bagi bangsa dan Negara sesuai dambaan semua rakyat. DAFTAR PUSTAKA Almond, Gabriel, dan Verba, Sidney, Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi dì Lima Negara, Jakarta: Bina Aksara,1984. Cox, Gary W. 1997. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems. Cambridge: Cambridge University Press. . Gould C, Carol, Demokrasi Ditinjau Kembali, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993. . Inter-Parlementary Union, Parlements of The World A Comparative Reference Compendium, Second Edition, Volume I, New York: The International Center For Paliamentary Documentation Of The Inter-Parlementari Union, 1990. Juan J. Linz dan Alfred Stepan, ‘Mendefinisikan dan Membangun Demokrasi”, dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi, ed., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Bandung: Mizan LIPI-Ford Foundation, 2001, hal. 25-49. Katz, Richard S. (1997): Democracy and Elections. New York and Oxford, Oxford University Press. Larry Diamond. 1999. Developing Democracy: Toward Consolidation Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press; juga terjemahannya dengan judul yang sama (Yogyakarta: IRE, 2003)., hal. 73-116. Lijphart, Arend. 1994. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945- 1990.Oxford: Oxford University Press. Liliaard ER & Grant WN. Turnout Differences Among Registered Voters. Southeastern Political Review Muhamad Asfar. Sistem Proporsional Terbuka. Jakarta: Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 2002. O’Donnell dan Philippe C. Schmitter. 1993. Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian Jakarta: LP3ES., hal. 6 Sargen, Lyman Tower, Idiologi Politik kontemporer, Jakarta : Bina Aksara, 1998. Simamora, Sahat, Pembangunan Politik dan Prospektif, Jakarta : Bina Aksara, 1985. Suseno, Franz Magnis, Etika, Politik, Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT Gramedia, 1991. Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.