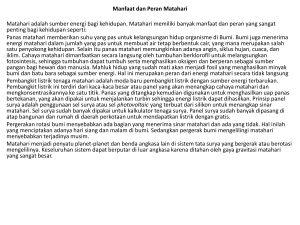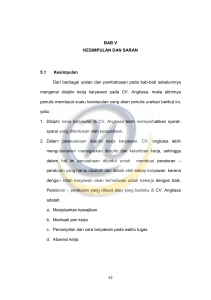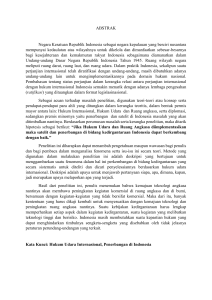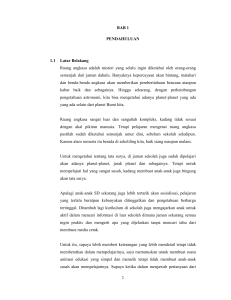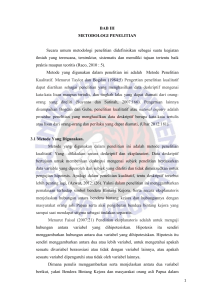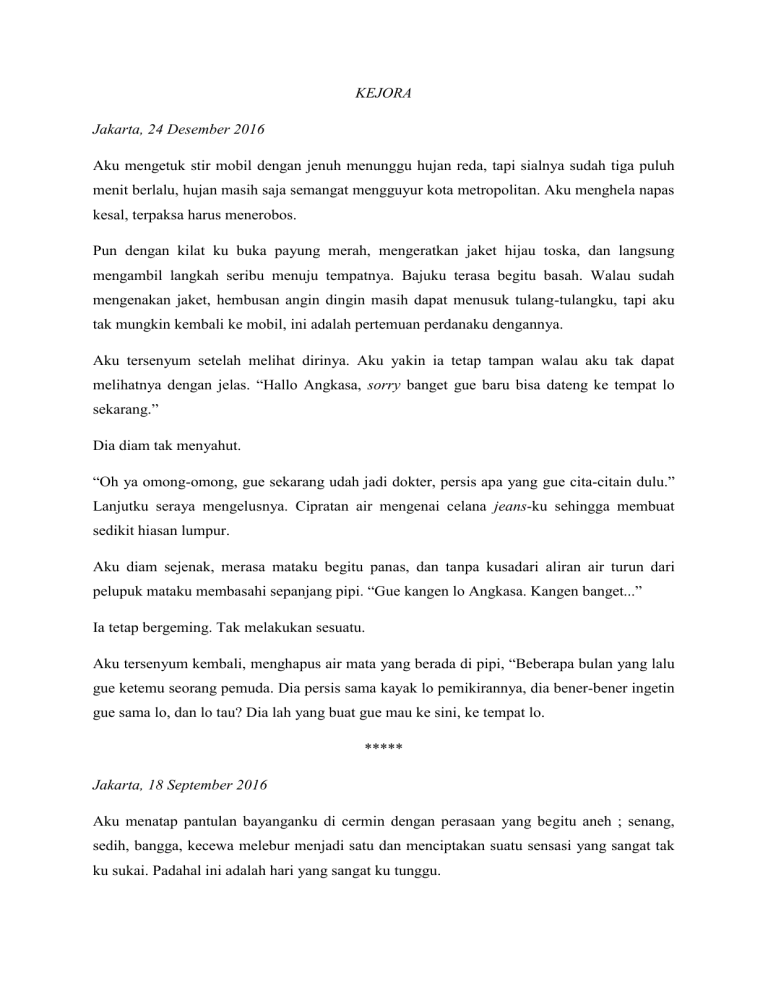
KEJORA Jakarta, 24 Desember 2016 Aku mengetuk stir mobil dengan jenuh menunggu hujan reda, tapi sialnya sudah tiga puluh menit berlalu, hujan masih saja semangat mengguyur kota metropolitan. Aku menghela napas kesal, terpaksa harus menerobos. Pun dengan kilat ku buka payung merah, mengeratkan jaket hijau toska, dan langsung mengambil langkah seribu menuju tempatnya. Bajuku terasa begitu basah. Walau sudah mengenakan jaket, hembusan angin dingin masih dapat menusuk tulang-tulangku, tapi aku tak mungkin kembali ke mobil, ini adalah pertemuan perdanaku dengannya. Aku tersenyum setelah melihat dirinya. Aku yakin ia tetap tampan walau aku tak dapat melihatnya dengan jelas. “Hallo Angkasa, sorry banget gue baru bisa dateng ke tempat lo sekarang.” Dia diam tak menyahut. “Oh ya omong-omong, gue sekarang udah jadi dokter, persis apa yang gue cita-citain dulu.” Lanjutku seraya mengelusnya. Cipratan air mengenai celana jeans-ku sehingga membuat sedikit hiasan lumpur. Aku diam sejenak, merasa mataku begitu panas, dan tanpa kusadari aliran air turun dari pelupuk mataku membasahi sepanjang pipi. “Gue kangen lo Angkasa. Kangen banget...” Ia tetap bergeming. Tak melakukan sesuatu. Aku tersenyum kembali, menghapus air mata yang berada di pipi, “Beberapa bulan yang lalu gue ketemu seorang pemuda. Dia persis sama kayak lo pemikirannya, dia bener-bener ingetin gue sama lo, dan lo tau? Dia lah yang buat gue mau ke sini, ke tempat lo. ***** Jakarta, 18 September 2016 Aku menatap pantulan bayanganku di cermin dengan perasaan yang begitu aneh ; senang, sedih, bangga, kecewa melebur menjadi satu dan menciptakan suatu sensasi yang sangat tak ku sukai. Padahal ini adalah hari yang sangat ku tunggu. Hari wisudaku. Untuk kesekian kalinya aku menghela napas. Menatap refleksiku sendiri di sana, sekali lagi, yang sedang mengenakan jubah dan sebuah toga dengan sempurna. Sempurna. Sentuhan lembut seseorang di pundak menyadarkanku. Tanpa menoleh aku bisa melihat dari pantulan cermin seorang wanita paruh baya yang sedang berdiri tepat di belakangku. Astaga, aku bahkan tak mendengar pintu kamarku terbuka. “Angkasa pasti bangga banget sama kamu Diandra.” Seperti sensor gelombang elektronik, kupingku sensitif mendengar namanya. Kucoba untuk tersenyum, namun seperti ada seutas tali tak kasat mata yang menahan. “Aku harap juga gitu, Bu.”. Bila saja ia masih di sini, dan seketika hatiku terasa sesak mengingat sosok dirinya. “Lekaslah bersiap. Ayah udah menunggu di meja makan,” ucapnya seraya mencium ujung keningku. Lagi-lagi aku teringat dirinya. Seperti sebuah film tua yang sudah berputar ribuan kali di dalam kepala. Kavandra Angkasa. Pria yang harusnya di sini sekarang, memberikanku semangat dan ucapan selamat. Kakakku satu-satunya yang sangat kusayangi. Bahkan setelah delapan tahun ia meninggalkan kami, senyumannya masih terekam jelas. Matanya yang tiba-tiba hilang dan hanya menyisakan garis lurus kala dia tertawa, suara barinton yang akan dia keluarkan bila aku membuat kesalahan, semua itu menghadirkan ingatan dari tahun-tahun yang telah lewat. ***** Aku masih ingat betul hari itu. Liburan kenaikan kelas. Puncak yang menjadi latarnya. Waktu itu Angkasa berusia empat belas tahun, sedangkan aku tujuh tahun, usia yang menurut orang-orang, tak mungkin kakak-beradik bisa sangat akrab. Tapi Angkasa membuktikan bila opini mereka salah, ia justru lebih banyak menghabiskan waktu denganku, saat pemuda seusianya menghabiskan waktu mereka untuk hangout dengan teman-temannya. Banyak hal yang kami lakukan di Puncak ; menangkap belalang, piknik, memancing ikan, tak ketinggalan mengayuh perahu kecil berwarna merah di danau dekat kami menginap saat senja menghampiri, hanya ada aku dan Angkasa, karena Ayah dan Ibu sedang menyiapkan makan malam. “Kejora nanti kalo udah gede mau jadi apa?” tanya Angkasa membuka percakapan. Aku yang sedang asik mengamati alam sekitar menoleh ke arahnya. Tersenyum dan menjawab dengan polos, “Dokter.” “Kenapa?” Aku diam sejenak, memikirkan jawaban yang tepat. “Soalnya kalo jadi dokter, Kejora bisa nyembuhin Nenek, Kakek, Ayah, Ibu, Paman, Tante, sama Kak Angkasa.” Ia tersenyum manis mendengarnya, “Hmmm... misalkan Kak Angkasa sakit Kejora yang rawat kakak ya?” Aku mengangguk dengan cepat. “Iya, nanti Kejora kasih cokelat biar kakak cepet sembuh.” Ia tertawa kecil seraya mengelus rambutku dengan lembut, “Oke, kalo gitu Kejora nanti belajar yang rajin biar bisa jadi dokter.” “Emangnya kak Angkasa mau jadi apa kalo udah gede?” “Mau jadi pemilik rumah sakitnya. Biar nanti Kejora bisa bareng sama kakak,” ucap Angkasa sambil tersenyum menunjukan giginya. “Iya. Kejora juga mau terus bareng sama kakak.” Balasku ceria, begitu berharap agar semua itu tercapai. Tanpa pernah tahu, takdir ternyata punya rencana yang berbeda.. ***** “Aku keluar sebentar, Bu. Nanti aku pulangnya sebelum makan malam,” ucapku pada Ibu yang sedang asik menonton tv. Pergi ke Kafe Seribu Mimpi, adalah cara untuk menghilangkan penat yang berkecamuk di kepalaku. Denting bel, derit pintu serta harum kayu manis dan aroma kopi menguar di seluruh penjuru kafe, kala aku membuka pintu. Khas aroma kafe. Hari ini kafe terlihat begitu ramai, beruntung masih ada satu tempat duduk yang tersisa walau berada di pojok ruangan. Dengan langkah cepat aku menuju tempat duduk tersebut, takuttakut ada seseorang yang mendahului, tetapi sepertinya Dewi Fortuna sedang tak berpihak, karena secara bersamaan seorang pria berambut cokelat gelap duduk di hadapanku. Aku menyipitkan mata tanda tak terima, “Maaf, tapi kayaknya gue duluan yang duduk di sini.” Ia mengangkat satu alisnya,”Oh gitu? Tapi gue kok merasa yang lebih dulu duduk di sini ya?” “Tapi maaf, gue yang lebih dulu,” ucapku sopan tetapi tak mau kalah tentu saja, bagaimana bisa aku mengalah setelah menempuh jalan yang jauh? “Gimana kalau kita duduk bareng aja? Toh, udah nggak ada tempat duduk yang kosong lagi.” Sarannya yang kuterima dengan terpaksa. Enggan memperpanjang konflik. Sejujurnya, aku bukanlah tipe gadis yang mudah akrab dengan orang baru, tapi bukan juga seorang introvert. Beberapa detik kemudian seorang pelayan sudah berdiri di depan meja kami – aku dan pria entah siapa - menyodorkan daftar menu, tanpa melihatnya terlebih dahulu aku langsung berkata, “Caramel Macchiatto satu.” Si pelayan dengan sigap menulis pesananku, melirik pria yang berada di hadapanku ia sepertinya terlihat bingung untuk memilih apa yang akan ia pesan, matanya begitu serius menatap deretan menu, kemudian tanpa kuduga ia sekilas melirikku dan berkata, “Hm... gue juga deh. Caramel Macchiatto satu.” Aku mengernyit heran mendengar pesananya. Kenapa harus sama sih? Si pelayan ternyum ramah. “Atas nama siapa?” “Diandra Kejora.” “Aditya Purnama.” Katanya, menunggu itu membosankan. Namun itu tidak berlaku bagiku jika ketika menunggu aku memiliki novel di tangan. Seperti saat ini, ketika menunggu pelayan kembali hadir dengan minuman yang kupesan, aku meraih novel Looking For Alaska karya John Green. Novel yang menjadi hadiah ulang tahunku yang ke lima belas dari Kavandra Angkasa. Hadiah terakhirnya untukku. Ia pergi meninggalkanku pada malam hujan, Desember delapan tahun lalu. Ia mengalami kecelakaan saat menjemputku, dan mengakibatkan pendarahan pada otaknya, saat itu ia sempat menerima penanganan medis, tapi Tuhan berkehendak lain. Ia memanggilnya. Kavandra Angkasa pergi untuk selama-lamanya. Meninggalkan diriku dengan penyesalan dan rasa bersalah. Andai saja dulu aku tak merajuk memintanya untuk mejemputku, menghilangkan sedikit rasa cemburu karena ia lebih memperhatikan pacarnya sejak masuk kuliah, dan bisa lebih berani untuk pulang ke rumah sendirian. Sebuah suara barinton berdehem mengejutkanku, ragu-ragu aku mengalihkan pandanganku ke arahnya. Ia mengangkat alisnya yang kanan dan bibirnya membentuk garis tipis. Namun samar-samar aku bisa melihat sudut bibirnya sedikit terangkat walau hanya seperkian mili. “ Bintang Kejora, kan?” tanya pria itu. “Apa?” kataku lirih. “Nama lo.” Ia berhenti sebentar, memberikan waktu untukku mencerna ucapannya. “Bintang kejora?” Aku mengerjap mata beberapa kali, dan mulai mengerti maksud ucapannya, “Diandra Kejora, nggak ada bintang.” Koreksiku. Aku mengamati dirinya untuk beberapa saat, ia terlihat seperti pria berumur dua puluh tahunan dengan tubuhnya yang tegap dan rahangnya yang kokoh. “Diandra Kejora?” tanya pria itu lagi yang nantinya ku ketahui bernama Aditya Purnama. Aku mengernyit heran. Tapi sesaat kemudian aku mengangguk dengan mantap. “Iya,” Ia berdehem, “Oke.” Kemudian melanjutkan perkataannya. “Kejora ya... it’s a star. You are the stars I wish upon. Will you make my dreams come true?” Hening menyergap. Aku pun kembali membaca novel yang berada dalam genggaman, tapi kegiatanku terhenti setelah mendengar ucapannya yang lebih tidak penting. “Kejora dan Purnama. Nama yang... kedengeran serasi banget, kan?” ucapnya sambil tersenyum jahil. Entah mengapa mendengar itu aku langsung menggeleng cepat, menolak dengan keras ucapan ngawurnya, karena menurutku ada yang lebih serasi, “Nggak. Kejora cocoknya sama Angkasa. Kejora dan Angkasa.” Kukira ia akan berbicara dengan nada yang menjengkelkan, tetapi aku salah. Anehnya ia malah tersenyum. “Kenapa harus Angkasa?” “Karena kejora letaknya di angkasa. Jadi secara teknis kejora cocoknya sama angkasa.” Aku mengutip perkataan Kavandra Angkasa saat kami masih kecil. Perkataan seorang bocah laki-laki yang sampai sekarang masih kuingat. Ia mengangguk lalu berkata, “Tapi Kejora ada, kalau Purnama ada. Kan bintang cocoknya sama bulan.” “Nggak juga. Justru kalau nggak ada angkasa kejora dan purnama juga nggak bakal ada. Angkasa itu bukan cuma langit yang isinya awan, gas, udara, tapi lebih luas. Lebih kompleks. Angkasa memuat planet, matahari, satelit, bintang, dan bulan. Jadi kalau nggak ada angkasa otomatis nggak ada kejora, dan juga purnama.” Jelasku panjang lebar. Kurasa aku mulai tertarik dengan topik pembicaraan ini. Walau terdengar amat sangat tidak penting dan ngawur. Purnama hendak membalas ucapanku tetapi terhenti saat seorang pelayan meletakan dua caramel Macchiatto. “Permisi, dua caramel macchiatto atas nama Diandra Kejora dan Aditya Purnama.” Aku mengambil salah satunya kemudian tersenyum ke arah pelayan sebagai ucapan terima kasih, meminumnya dalam diam kemudian melirik Purnama sekilas yang juga sedang meminum caramel machiatto-nya, “Lo bener, tapi bagi gue itu semua hanya perspektif lo, Kejora. Mau itu angkasa, kejora, purnama, itu semua penting. Lo bisa bayangin gimana malam hari kalo nggak ada purnama, bulan. Bukan cuma gelap, kejora, bintang juga nggak bakal keliatan, karena purnama atau orang awam biasanya sebut sebagai bulan, tugasnya memantulkan cahaya matahari. Intinya semua itu hanya soal perspektif dan paradigma.” “Termasuk ngomongan ngawur lo tentang Kejora dan Purnama?” ucapku sedikit menyindir. Ia terkekeh sejenak, “Lo juga sama ngawurnya Kejora, lo kan nanggepin omongan gue, dan bilang Kejora cocoknya sama Angkasa.” Aku memutar mata jengah. “Terserah deh.” Kemudian meminum caramel macchiatto-ku kembali, dan mencoba tidak memperdulikan kehadirannya. Tetapi kemudian ia kembali bersuara, “Kalo gitu... apa perspektif lu tentang kematian?” Aku hampir saja tersedak, jantung berpacu melebihi batas normal, tubuhku untuk beberapa saat terasa kaku, diam mencoba mencerna apa maksud dari ucapannya, lalu berusaha untuk menjaga suaraku terdengar senetral mungkin. Mengabaikan bayangan tentang kematian Kavandra Angkasa. “Kenapa... lo nanya itu?” Purnama tersenyum begitu tipis, bahkan aku tak yakin kalau itu sebuah senyuman, “ Gue juga nggak tau kenapa. Ah... gue dulu punya sepupu cewek. Namanya mirip-mirip lo, Diana Bintang. Karena gue anak tunggal akhirnya gue jadi deket sama dia. Tapi, delapan tahun lalu dia meninggal karena kecelakaan mobil di bulan Desember, dan sukses membuat dunia gue jungkir balik. Gue sempet ngerasa Tuhan nggak adil. Kenapa Tuhan harus ngambil Bintang? Kenapa nggak orang lain aja?” ia terdiam sesaat. Aku bisa melihat kilatan matanya yang menggambarkan perasaan terluka yang begitu dalam dan berkaca-kaca, dan anehnya aku juga kembali merasa perasaan itu lagi. Perasaan kehilangan. Perasaan yang paling kubenci. “Lo tau Kejora? Butuh banyak waktu buat bertingkah seolah semuanya baik-baik aja. Seakan nggak ada yang terjadi. Bahkan walau udah lewat delapan tahun, gue masih aja kadang ngerasa Tuhan nggak adil. Ah sial... kenapa gue jadi curcol ke lo? Sorry Kejora, anggep aja gue orang absurd,” ucapnya sambil tertawa lirih. Aku tersenyum tulus, mengerti bagaimana sakitnya kehilangan seorang yang sangat disayangi. “Nggak apa-apa, gue tau rasanya kok. Gue juga kehilangan seseorang yang sangat berarti bagi gue. Cuma bedanya, gue belum bisa kayak lo. Gue masih terjebak di labirin, Purnama.” Keningnya bertransformasi menjadi berkerut, “kenapa?” Aku tersenyum kecil kemudian menatap kedepan, “Karena bagi gue... dia bukan cuma sekedar seseorang. Tapi, dia angkasa gue. Seperti yang gue bilang, kalau nggak ada angkasa maka nggak bakal ada kejora. “Kenapa?” tanya Purnama untuk kedua kalinya. “Karena bagi gue, apa artinya hidup kalau orang yang sangat berarti buat lo udah nggak ada di dunia ini? Seakan alasan lo buat hidup lenyap menjadi debu, dan sia-sia. Jadi, bukannya lebih baik mati?” Ia menghela napas kasar seakan tak terima dengan apa yang ku ucapkan, “Lo terlalu dramatis Kejora. Hidup ini bukan cuma sekadar untuk seseorang. Terus lo ikutan meninggal kalau orang itu juga meninggal. Walau awalnya gue juga mikir gitu. Tapi show must go on. Mau gimana juga hidup terus berjalan, jadi berhenti berpikiran sempit kayak anak TK.” Aku menyipitkan mata tak terima dengan ucapannya, “Lo nggak tau apa-apa, Purnama. Lo bahkan bagi gue cuma pria asing.” Ia terdiam sejenak, menatapku tajam kemudian mulutnya kembali bersuara, “Gue emang cuma pria asing yang tiba-tiba ceramahin lo tentang kehidupan, gue juga nggak tau apa-apa tentang hubungan lo dengan orang itu, tapi itu alasan gue berani ngomong kayak gini sama lo. Karena gue cuma pria asing. Lo tau? Seperti yang gue bilang ini semua cuma sekadar persepktif dan paradigma, dan gue rasa paradigma lo tentang kehidupan itu sangat lah sempit.” “Terus gimana caranya biar paradigma gue jadi luas, hah?” ucapku dengan nada sinis. Purnama tersenyum. “Gue pasti kedengeran sok tau banget, tapi coba buat berpura-pura seakan semuanya baik-baik saja, sampai lo lupa caranya berpura-pura, dan berpikir kalau orang yang berarti buat lo pasti nggak bakal suka kalo lo seumur hidup cuma nangisin kepergian dia.” Aku mendengus geli mendengar ucapannya, “Lo ngomong kayak makan kacang tanah tau nggak?” “Trust me Kejora, pertending to be ok is the best way,” ucapnya sambil tersenyum menunjukan deretan giginya. Keheningan kembali menyelimuti kami. Sibuk dengan pikiran masing-masing. Mungkin perkataan Purnama ada benarnya juga. Tapi aku tak mungkin kan melupakan sosok Kavandra Angkasa? Ia terlalu berarti untuk dilupakan. ***** Jakarta, 24 Desember 2016 Aku kembali mengelus batu nisan Angkasa, seraya membaca tulisan yang tertera di sana. Sebagian diriku masih tak bisa mempercayai bila ada seseorang yang begitu berarti untukku dikubur di dalam tanah ini. Tapi seperti kata Purnama, show must go on, aku harus bangkit dari keterpurukanku. Angkasa juga tak akan pernah suka bila aku seperti ini terus, meratapi kematiannya. Aku menghapus air mataku, kemudian berkata dengan suara serak bergetar menahan tangis, “Gue... gue udah relain kepergian lo Angkasa. Walau rasanya berat, tapi apa yang bisa gue lakuin selain itu?” Aku menggigit bibir, meminimalisir rasa perih yang kini bersarang di dadaku, dan tanpa bisa kubendung lagi air mata kembali turun. “Gu... gue harap... lo tenang di sana, Angkasa” Entah sudah berapa lama menangis, tapi yang kutahu adalah bahwa sekarang hujan telah reda. Aku menghela napas, mencoba mengatur kontrol diriku. Kemudian menatap makam Angkasa. Mencoba tersenyum dengan tulus, “Gue harus pulang sekarang Angkasa, Ayah dan Ibu pasti khawatir. Tapi tenang aja kalo ada waktu—bukan besok tapi, gue bakal ke sini lagi, gue bakal usahain buat rajin dateng ke sini. “Dadah Angkasa, semoga lo tenang di sana, gue sayang lo.” Satu hal yang kuketahui sekarang, bahwa melepaskan sesuatu bukan berarti melupakannya. Hidup itu seperti secangkir kopi, ada rasa manis dan juga pahit. Tetapi, rasa pahit bukanlah suatu alasan kenapa kopi itu menjadi tak enak, justru rasa pahit itu merupakan hal yang unik. Seperti hidup, rasa pahit merupakan sebuah batu loncatan agar kita bisa lebih dewasa, iya kan Angkasa? hembusan angin pelan membelai pipiku lembut. Aku tersenyum. Aku tahu jawabannya.