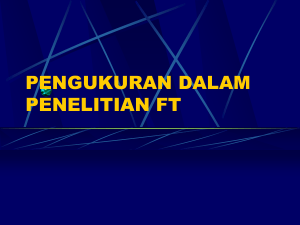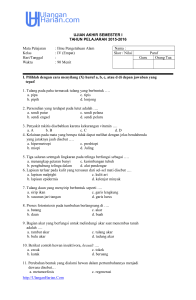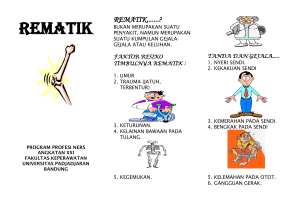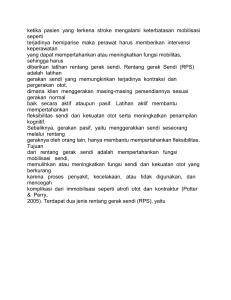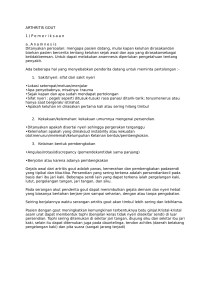Uploaded by
common.user72090
Manajemen Fisioterapi pada Gangguan Aktivitas Fungsional Karena Hiperuricemia dan Diabetes Melitus
advertisement

Dibacakan Tanggal BAGIAN : PATOLOGI KLINIK RSWS PERIODE : Di LAPORAN KASUS MANAJEMEN FISIOTERAPI PADA GANGGUAN AKTIVITAS FUNGSIONAL BERUPA MUSCLE CRUMP ET CAUSA GANGGUAN METABOLIME HIPERURICEMIA DAN DIABETES MELITUS OLEH : Nurul Fauziah Arifin R024201006 Andi Nurul Fadillah R024201008 Fani Yuanita Pratiwi R024201014 Fivi Elvira Hasan R024201020 Yunita Rahmayanti R024201040 Ainun Djalila Nur Rahman R024201041 Intruktur Klinis: dr. Irda Handayani, M.Kes, Sp.PK Residen Pembimbing dr. Widya Pratiwi DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN 2020 LEMBAR PENGESAHAN Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa berikut : Nurul Fauziah Arifin R024201006 Andi Nurul Fadillah R024201008 Fani Yuanita Pratiwi R024201014 Fivi Elvira Hasan R024201020 Yunita Rahmayanti R024201040 Ainun Djalila Nur Rahman R024201041 Adalah benar telah menyelesaikan telaah kasus dengan judul “Manajemen Fisioterapi Pada Gangguan Aktivitas Fungsional Berupa Muscle Crump Et Causa Gangguan Metabolisme Hipererucimia dan Dabetes Melitus” pada bagian Patologi Klinik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan telah mendiskusikannya dengan pembimbing. Makassar, 07 Oktober 2020 Mengetahui, Clinical Instructor 1 dr. Irda Handayani M. Kes, Sp. PK Clinical Educator Riska Nuramalia, S.FT., Physio, M.Biomed ii KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kasus ini sebagai tanggung jawab penulis dalam mengakhiri stase patologi klinik dengan judul “Manajemen Fisioterapi Pada Gangguan Aktivitas Fungsional Berupa Muscle Crump Et Causa Gangguan Metabolisme Hiperuricemia dan Diabetes Melitus”. Sholawat dan taslim semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kasus ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan penulis, namun berkat kerja sama tim, penulis mampu menyelesaikan tugas ini. Harapan penulis semoga laporan kasus yang diajukan dapat diterima dan diberi kritikan, masukan yang mendukung sehingga dapat memperbaiki jika terdapat kesalahan didalamnya dan semoga dapat bermanfaat bagi sejawat. Makassar, 7 Oktober 2019 Tim Penulis iii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................................ ii KATA PENGANTAR ................................................................................................................... iii DAFTAR ISI.................................................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................................... 3 A. Anatomi dan Fisiologi ............................................................................................................ 3 B. Etiologi ................................................................................................................................... 6 C. Patofisiologi ............................................................................................................................ 8 D. Tanda dan gejala klinis .......................................................................................................... 9 E. Komplikasi Hiperurisemia .................................................................................................... 10 F. Pencegahan Hiperurisemia .................................................................................................... 11 G. Diagnosis Banding ............................................................................................................... 12 H. Pemeriksaan dan Penegakan Diagnosis ............................................................................... 12 I. Prinsip latihan Hiperurisemia .............................................................................................. 13 BAB III MANAJEMEN FISIOTERAPI ...................................................................................... 14 A. Data Umum Pasien ............................................................................................................ 14 B. Pemeriksaan Fisioterapi (Model CHARTS) ...................................................................... 14 C. Diagnosis Fisioterapi ......................................................................................................... 23 D. Problem Fisioterapi ............................................................................................................ 23 E. Program .............................................................................................................................. 23 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................................................... 24 A. Hasil ................................................................................................................................... 24 iv B. Pembahasan........................................................................................................................ 24 1. Pemeriksaan Hematologi................................................................................................ 24 2. Pertimbangan Hematologi Dalam Pemberian Exercise ................................................. 46 3. Pemeriksaan Kimia Klinik ............................................................................................. 47 4. Pertimbangan Kimia Klinik Dalam Pemberian Exercise ............................................... 53 5. Pemeriksaan dan Intervensi Fisioterapi.......................................................................... 55 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 62 v BAB I (PENDAHULUAN) Hiperuricemia merupakan keadaan dimana di dalam darah seseorang terdapat jumlah asam urat yang berlebihan. Kadar asam urat yang berlebihan ini dapat menimbulkan gejala akibat adanya penumpukan kristal asam urat di sendi atau disebut dengan gout. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hiperurisemia adalah jenis kelamin, IMT, asupan karbohidrat dan asupan purin. Asupan purin merupakan faktor risiko paling kuat yang berhubungan dengan kejadian hiperurisemia. (Anonim, 2012). WHO mendata penderita gangguan sendi di Indonesia mencapai 81% dari populasi, hanya 24% yang pergi ke dokter, sedangkan 71%nya cenderung langsung mengkonsumsi obatobatan pereda nyeri yang dijual bebas. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling tinggi menderita gangguan sendi jika dibandingkan dengan negara di Asia lainnya seperti Hongkong, Malaysia, Singapura dan Taiwan. Penyakit sendi secara nasional prevalensinya berdasarkan wawancara sebesar 30,3% dan prevalensi berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan adalah 14% (Riskesdas 2007-2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit sendi adalah umur, jenis kelamin, genetik, obesitas dan penyakit metabolik, cedera sendi, pekerjaan dan olah raga. (Anonim, 2012). Hiperurisemia yang merupakan kondisi predisposisi untuk gout, sangat berhubungan erat dengan sindrom metabolik seperti : hipertensi, intoleransi glukosa, dislipidemia, obesitas truncal, dan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular. Didapatkan bukti bahwa hiperurisemia sendiri mungkin merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kardiovaskular. Insiden dan prevalensi gout di seluruh dunia tampaknya meningkat karena berbagai alasan, termasuk yang iatrogenik. 1 Untuk Epidemiologi pria memiliki tingkat serum asam urat lebih tinggi daripada wanita, yang meningkatkan resiko mereka terserang hiperuricemia. Perkembangan hiperuricemia sebelum usia 30 tahun lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita. Namun angka kejadian hiperuricemia menjadi sama antara kedua jenis kelamin setelah usia 60 tahun. Sedangkan wanita mengalami peningkatan resiko hiperuricemia setelah menopause, kemudian resiko mulai meningkat pada usia 45 tahun dengan penurunan level estrogen karena estrogen memiliki efek urikosurik, hal ini menyebabkan hiperuricemia jarang pada wanita muda. 2 BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) A. Anatomi dan Fisiologi Sendi secara sederhana merupakan pertemuan antar tulang. Sendi memberikan adanya segmentasi pada rangka manusia dan memberikan kemungkinan variasi pergerakan. Sendi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis jaringan ikat yang dominan secara fungsional berdasarkan jumlah gerakan. Klasifikasi persendian : 1. Persendian Fibrosa : sendi tetap dimana jaringan fibrosa yang terdiri dari kolagen menghubungkan tulang. Sendi fibrosa biasanya tidka dapat digerakkan (sinartrosis) dan tidak memiliki rongga sendi. mereka dibagi lagi menjadi sutura, gomposis, dan sindesmosis. a) sutura adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan jaringan ikat fibrosa rapat dan hanya ditemukan pada tulang tengkorak. Contoh sutura adalah sutura sagital dan sutura parietal. b) gomposis adalah persendian tidak bergerak antara gigi dan soketnya di rahang bawah dan rahang atas. Ligamentum periodontal adalah jaringan fibrosa yang menghubungkan gigi ke soket. c) Sindesmosis adalah persendian yang dapat digerakkan (amphiarthroses). Pada sendi syndesmosis, kedua tulang disatukan oleh membran interoseus. Misalnya, tibia terhubung ke fibula, membentuk sendi tibiofibular tengah, dan ulna menempel pada jari-jari, membentuk sendi radio-ulnaris tengah. 3 2. Persendian kartilago: pada sendi tulang rawan, tulang menempel oleh tulang hialin atau fibrokartilago. Bergantung pada jenis tulang rawan yang terlibat, persendian diklasifikasikan lebih lanjut sebagai sendi tulang rawan primer dan sekunder. a) Sendi tulang rawan primer, juga dikenal sebagai synchondroses, hanya melibatkan tulang rawan hialin. Sendi ini mungkin sedikit bergerak (amphiarthroses) atau tidak bergerak (synarthroses). Contohnya sendi antara epifisis dan diafisis tulang panjang yang tumbuh. b) Sendi tulang rawan sekunder, juga dikenal sebagai simfisis, mungkin melibatkan hialin atau fibrokartilago. Sendi ini sedikit bergerak (amphiarthroses). Contoh klasik adalah simfisis pubis. 3. Persendian synovial : Sendi sinovial bergerak bebas (diartrosis) dan dianggap sebagai sendi fungsional utama tubuh. Rongga sendi mencirikan sendi sinovial. Rongga dikelilingi oleh kapsul artikular, yang merupakan jaringan ikat fibrosa yang melekat pada setiap tulang yang berpartisipasi tepat di luar permukaan artikulasinya. Rongga sendi berisi cairan sinovial, yang disekresikan oleh membran sinovial (sinovium), yang melapisi kapsul artikular. Tulang rawan hialin membentuk tulang rawan artikular, menutupi seluruh permukaan artikulasi setiap tulang membran sinovial kontinu. Beberapa sendi sinovial juga memiliki fibrokartilago terkait, seperti menisci, di antara tulang yang mengartikulasikan. Sendi sinovial sering diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan jenis gerakan. Ada enam klasifikasi seperti: engsel (siku), sadel (sendi karpometakarpal), planar (sendi acromioclavicular), poros (sendi atlantoaxial), condyloid (sendi metacarpophalangeal), dan bola dan soket (sendi pinggul). 4 Tujuan utama sendi sinovial adalah untuk mencegah gesekan antara tulang artikulasi rongga sendi. Sementara semua sendi sinovial adalah diartrosis, tingkat pergerakannya bervariasi di antara subtipe yang berbeda dan seringkali dibatasi oleh ligamen yang menghubungkan tulang. a. Sendi engsel adalah artikulasi antara ujung cembung satu tulang dan ujung cekung tulang lainnya. Jenis sambungan ini uniaksial karena hanya memungkinkan pergerakan dalam satu sumbu. Di tubuh, sumbu gerakan ini biasanya menekuk dan meluruskan, atau fleksi dan ekstensi. Contohnya termasuk sendi siku, lutut, pergelangan kaki, dan interphalangeal. b. Sendi condyloid, atau sendi ellipsoid, didefinisikan sebagai artikulasi antara depresi dangkal satu tulang dan struktur bulat tulang atau tulang lainnya. Jenis sendi ini biaksial karena memungkinkan dua sumbu gerakan: fleksi / ekstensi dan medial / lateral (abduksi / adduksi). Contohnya adalah sendi metacarpophalangeal tangan antara metacarpal distal dan phalanx proksimal, umumnya dikenal sebagai buku jari. c. Sendi sadel adalah artikulasi antara dua tulang yang berbentuk pelana, atau cekung di satu arah dan cembung di arah lain. Jenis sendi ini biaksial, dan salah satu contohnya adalah sendi karpometakarpal pertama antara trapezium (karpal) dan tulang metakarpal ibu jari pertama. d. Sendi planar didefinisikan sebagai artikulasi antara tulang yang datar dan berukuran serupa. Jenis sambungan ini multiaxial karena memungkinkan banyak gerakan. Namun, ligamen sekitarnya biasanya membatasi sendi ini pada gerakan kecil dan kencang. Contohnya termasuk sendi intercarpal, sendi intertarsal, dan sendi acromioclavicular. 5 e. Sendi poros adalah artikulasi dalam cincin ligamen antara ujung bulat dari satu tulang dan tulang lainnya. Jenis sendi ini uniaksial karena, meskipun tulang berputar di dalam cincin ini, tulang melakukannya di sekitar sumbu tunggal. Contohnya adalah sambungan atlantoaksial antara C1 (atlas) dan C2 (sumbu) dari vertebra, yang memungkinkan gerakan kepala dari sisi ke sisi. Contoh lain adalah sendi radioulnar proksimal. Jari-jari berada di ligamentum radial annular, yang menahannya saat berartikulasi dengan takik radial ulna, yang memungkinkan pronasi dan supinasi. f. Sendi bola dan soket adalah artikulasi antara kepala bulat dari satu tulang (bola) dan cekungan tulang lainnya (soket). Jenis sendi ini multiaxial: memungkinkan fleksi / ekstensi, abduksi / adduksi, dan rotasi. Satu-satunya sendi bola dan soket tubuh adalah pinggul dan bahu (glenohumeral). Soket dangkal rongga glenoid memungkinkan rentang gerak yang lebih luas di bahu; soket yang lebih dalam dari acetabulum dan ligamen pendukung pinggul membatasi pergerakan tulang paha. B. Etiologi Gangguan metabolisme yang mendasarkan artritis gout adalah hiperurisemia yang didefinisikan sebagai peninggian kadar urat lebih dari 7,0 ml/dl untuk pria dan 6,0 ml/dl untuk wanita. Etiologi dari artritis gout meliputi usia, jenis kelamin, riwayat medikasi, obesitas, konsumsi purin dan alkohol 1. Jenis Kelamin Pria memiliki tingkat serum asam urat lebih tinggi daripada wanita, yang meningkatkan resiko mereka terserang artritis gout. Perkembangan artritis gout sebelum usia 30 tahun lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita. Namun angka kejadian artritis gout menjadi sama antara kedua jenis kelamin setelah usia 60 tahun. Sedangkan 6 wanita mengalami peningkatan resiko artritis gout setelah menopause, kemudian resiko mulai meningkat pada usia 45 tahun dengan penurunan level estrogen karena estrogen memiliki efek urikosurik, hal ini menyebabkan artritis gout jarang pada wanita muda. 2. Riwayat Medikasi Penggunaan obat diuretik merupakan faktor resiko yang signifikan untuk perkembangan artritis gout. Obat diuretik dapat menyebabkan peningkatan reabsorpsi asam urat dalam ginjal, sehingga menyebabkan hiperurisemia. 3. Obesitas Obesitas dan indeks massa tubuh berkontribusi secara signifikan dengan resiko artritis gout. Obesitas berkaitan dengan terjadinya resistensi insulin. Insulin diduga meningkatkan reabsorpsi asam urat pada ginjal melalui urate anion exchanger transporter-1 (URAT1) atau melalui sodium dependent anion cotransporter pada brush border yang terletak pada membran ginjal bagian tubulus proksimal. Dengan adanya resistensi insulin akan mengakibatkan gangguan pada proses fosforilasi oksidatif sehingga kadar adenosin tubuh meningkat. Peningkatan konsentrasi adenosin mengakibatkan terjadinya retensi sodium, asam urat dan air oleh ginjal. 4. Konsumsi purin dan alkohol Konsumsi tinggi alkohol dan diet kaya daging serta makanan laut (terutama kerang dan beberapa ikan laut lain) meningkatkan resiko artritis gout. Mekanisme biologi yang menjelaskan hubungan antara konsumsi alkohol dengan resiko terjadinya serangan gout yakni, alkohol dapat mempercepat proses pemecahan adenosin trifosfat dan produksi asam urat. Alkohol juga dapat meningkatkan asam laktat pada darah yang menghambat 7 eksresi asam urat. Alasan lain yang menjelaskan hubungan alkohol dengan artritis gout adalah alkohol memiliki kandungan purin yang tinggi sehingga mengakibatkan over produksi asam urat dalam tubuh C. Patofisiologi Artritis gout disebabkan oleh reaksi inflamasi yang muncul sebagai respons terhadap pengendapan kristal monosodium urat ke dalam sendi pasien hiperurisemia. Peradangan yang diinduksi monosodium urat ini didorong oleh komponen sistem kekebalan bawaan yang biasanya memberikan respons imun nonspesifik awal untuk patogen yang menyerang. Proses awal dari respon inflamasi artritis gout terjadi ketika makrofag yang ada di dalam kristal monosodium urat fagositosis rongga sendi (Gbr. 1). Internalisasi kristal monosodium urat ini kemudian memicu pembentukan perancah protein yang dikenal sebagai inflamasi di dalam sitosol makrofag. Inflamasom adalah kompleks protein dengan berat molekul tinggi yang menyediakan platform untuk pemrosesan enzimatik dari pro-IL-1β yang tidak aktif menjadi IL1β yang aktif secara biologis, yang kemudian disekresikan dari sel. Menariknya, kristal monosodium urat saja mungkin tidak cukup untuk memicu aktivasi / pelepasan IL-1β dari makrofag, sebaliknya membutuhkan ko-stimulasi dengan asam lemak bebas atau lipopolisakarida untuk melepaskan IL-1β. Mengingat bahwa konsumsi alkohol atau makanan besar dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi asam lemak bebas, masuk akal bahwa keterlibatan asam lemak bebas dalam memicu pelepasan IL-1β mungkin merupakan faktor penting dalam perkembangan artritis gout yang akan melebar. Seiring waktu, peradangan akut yang menyertai serangan artritis gout yang berulang dapat berujung pada kerusakan sendi patologis. Akumulasi kristal monosodium urat yang berkepanjangan menimbulkan tophi yang terdiri dari kristal monosodium urat dalam matriks 8 lipid, protein, dan mukopolisakarida. Enzim, seperti matriks metaloproteinase, dan osteoklas resorptif tulang diproduksi secara lokal di dalam tofi ini, yang mengakibatkan erosi tulang progresif. Selain itu, peningkatan kadar sitokin proinflamasi yang muncul selama artritis gout yang akan melebar. juga dapat menyebabkan kerusakan tulang. IL-1 adalah molekul kunci dalam proses kerusakan tulang dan tulang rawan dan memainkan peran penting dalam pembentukan osteoklas. Gambar 2.1 D. Tanda dan gejala klinis 1. Asimtomatik Seseorang dapat menderita hiperurisemia, tetapi tidak timbul gejala asam urat. Ini disebut "hiperurisemia asimtomatik" dan memang demikian biasanya tidak membutuhkan perawatan. 9 2. Akut Serangan awal gout berupa nyeri yang berat, bengkak dan berlangsung cepat, lebih sering di jumpai pada ibu jari kaki. Ada kalanya serangan nyeri di sertai kelelahan, sakit kepala dan demam. 3. Interkritikal Stadium ini merupakan kelanjutan stadium akut dimana terjadi periode interkritikal asimtomatik. Secara klinik tidak dapat ditemukan tanda-tanda radang akut. tahap ini merupakan tahap penderita mengalami serangan gout arthritis yang lebih sering dan berulang – ulang namun tidak menentu. 4. Kronik Di tahap ini asam urat penderita sudah menumpuk dan mengkristal di berbagai jaringan ikat tubuh penderita khususnya pada persendian penderita. E. Komplikasi Hiperurisemia Komplikasi dapat timbul pada gout akibat tophi. Tophi adalah gumpalan kristal urat yang mengeras di bawah kulit yang terbentuk dari penumpukan kristal monosodium urat pada sendi yang terkena. Tophi ini dapat menyebabkan kerusakan pada sendi dan jaringan di sekitarnya, menyebabkan nyeri kronis, dan bahkan dapat menyebabkan kelainan bentuk. Berbagai komplikasi ginjal juga dapat terjadi. Komplikasi tersebut antara lain, batu ginjal, batu asam urat, dan nefropati asam urat akut dan kronis. Komplikasi tersebut tidak hanya disebabkan oleh gout itu sendiri, tetapi juga oleh penyakit yang sering menyertai asam urat, seperti hipertensi, hiperlipidemia, penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa obat yang diresepkan oleh pasien untuk mengobati asam urat dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut. 10 F. Pencegahan Hiperurisemia Terapi penurunan urat serum harus dimulai mencegah kekambuhan pada orang dengan riwayat asam urat dan salah satu dari berikut ini: setidaknya satu per tahun pada orang dengan penyakit ginjal kronis stadium 2 atau lebih besar, tophi, atau riwayat nefrolitiasis (batu ginjal). Serum urat harus diturunkan ke target kurang dari 5 sampai 6 mg per dL (297 sampai 357 µmol per L), tergantung pada kristal dan beban tophaceous. Serum normal kadar urat tidak mengecualikan diagnosis gout. Ini harus dipantau secara berkala untuk menilai pencegahan terapi pada pasien dengan gout berulang dan riwayat peningkatan kadar urat. Selama periode bebas gejala, pedoman diet berikut dapat membantu melindungi dari serangan asam urat di masa mendatang. Tetap terhidrasi dengan baik. Batasi berapa banyak minuman manis yang Anda minum. Batasi atau hindari alkohol, bukti terbaru menunjukkan bahwa bir kemungkinan besar meningkatkan risiko gejala asam urat, terutama pada pria. Produk susu rendah lemak sebenarnya memiliki efek perlindungan terhadap asam urat, jadi ini adalah sumber protein. Batasi asupan daging, ikan, dan unggas. Pertahankan berat badan yang diinginkan. Pilih porsi yang memungkinkan untuk mempertahankan berat badan yang sehat. Menurunkan berat badan dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Tetapi hindari puasa atau penurunan berat badan yang cepat, karena hal itu dapat meningkatkan kadar asam urat untuk sementara. 11 G. Diagnosis Banding Diagnosis banding hiperurisemia dapat dibuat berdasarkan kondisi yang menjadi penyebabnya. Hiperurisemia dapat disebabkan oleh over produksi atau kurangnya ekskresi asam urat. Over produksi asam urat bisa terjadi akibat asupan makanan tinggi purin; gangguan metabolisme purin akibat defisiensi hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT) atau overaktivitas phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) synthetase; dan peningkatan penghancuran atau pergantian sel misalnya pada polisitemia vera, penyakit Paget, atau rhabdomyolisis. Penurunan ekskresi asam urat dapat disebabkan penyakit ginjal, konsumsi obat. Pada hiperurisemia diagnosis banding yang perlu dipikirkan adalah osteoarthritis dan rheumatoid arthritis. Diagnosis dapat dibedakan dengan mengukur kadar asam urat serum, pemeriksaan faktor rheumatoid, dan pemeriksaan radiologi H. Pemeriksaan dan Penegakan Diagnosis Menurut The European League Against Rheumatism (EULAR) berdasarkan klinis temuan. Perkembangan cepat dengan nyeri yang parah, bengkak yang mencapai puncaknya dalam enam hingga 12 jam, dalam kombinasi dengan eritema di atasnya, kemungkinan besar mengindikasikan peradangan kristal. Tes diagnostik definitif untuk gout adalah identifikasi kristal urat dalam cairan sinovial yang disedot dari sendi yang terkena. Namun, dalam praktiknya tes ini tidak sering dilakukan (hanya dalam 11% kasus). Menurut American College of Rheumatology, adanya enam atau lebih dari gambaran klinis berikut menandakan diagnosis gout: 1. Lebih dari satu serangan artritis akut 2. Peradangan maksimum berkembang dalam 24 jam 3. Serangan monoartritis 12 4. Eritema di atas sendi yang terkena 5. Sendi metatarsophalangeal pertama yang nyeri atau bengkak 6. Serangan sepihak pada sendi tarsal 7. Tophus (dicurigai atau terbukti) 8. Hiperurisemia 9. Pembengkakan asimetris dalam persendian yang terlihat melalui radiografi 10. Kista subkortikal tanpa erosi terlihat pada radiograf 11. Kultur cairan sendi negatif untuk organisme selama serangan akut I. Prinsip latihan Hiperurisemia Prinsip latihan untuk hiperurisemia adalah latihan fisik dilakukan secara rutin 3−5 kali seminggu selama 30−60 menit. Olahraga meliputi latihan kekuatan otot, fleksibilitas otot dan sendi, dan ketahanan kardiovaskular. Olahraga bertujuan untuk menjaga berat badan ideal dan menghindari terjadinya gangguan metabolisme yang menjadi komorbid gout. Namun, latihan yang berlebihan dan berisiko trauma sendi wajib dihindari. 13 BAB III (MANAJEMEN FISIOTERAPI) A. Data Umum Pasien Nama : Tuan SL Usia : 68 Tahun Jenis Kelamin : Laki-Laki Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Perdos Unhas Blok AG 13 T-Rea Jaya Vital Sign Tekanan Darah : 120/80 mmHg Nadi : 80x/menit Pernafasan : 20x/menit Suhu : 360 C B. Pemeriksaan Fisioterapi (Model CHARTS) 1. Chief of Complaint Nyeri pada bahu kiri dan rasa keram pada kaki sebelah kiri. 2. History Taking Pasien mengeluh nyeri pada bahu sebelah kiri dan rasa keram pada kaki sebelah kiri. Pasien juga memiliki keluhan penglihatan kabur pada kedua matanya dalam minggu ini. Mual dan muntah tidak ada. Demam dan batuk tidak ada. Pasien memliki riwayat penyakit DM kurang lebih sejak 3 tahun lalu. 14 3. Asymetric a) Inspeksi Statis 1) Anterior - Raut wajah menahan sakit - Raut wajah pasien terlihat cemas 2) Lateral - Postur agak kifosis - Knee semifleksi b) Inspeksi dinamis 1) Pasien datang dengan sedikit pincang. 2) Berat badan ditumpukan pada kaki yang sehat (dextra) c) Palpasi o Shoulder 1) Suhu : Normal 2) Kontur kulit : Normal 3) Oedem : (-) 4) Tenderness : (+) m.deltoid, m.pectoralis mayor o Ankle 1) Suhu : Normal 2) Kontur kulit : Normal 3) Oedem : (+) pada pergelangan kaki 4) Tenderness : (-) 15 d) Pemeriksaan Fungsi Gerak Dasar (PFGD) PFGD Aktif Regio Gerakan Dexra Sinistra Fleksi Full ROM Terbatas, nyeri Ekstensi Full ROM Terbatas, nyeri Adduksi Full ROM Terbatas, nyeri Abduksi Full ROM Terbatas, nyeri Rotasi internal Full ROM Terbatas, nyeri Rotasi eksternal Full ROM Full ROM Protraksi Full ROM Full ROM Retraksi Full ROM Full ROM Fleksi Full ROM Full ROM Ekstensi Full ROM Full ROM Abduksi Full ROM Full ROM Adduksi Full ROM Full ROM Endorotasi Full ROM Full ROM Eksorotasi Full ROM Full ROM Fleksi Full ROM Terbatas, nyeri Ekstensi Full ROM Terbatas, nyeri Plantarfleksi Full ROM Terbatas, nyeri Shoulder Hip Knee Ankle 16 Dorsifleksi Full ROM Terbatas, nyeri Inversi Full ROM Terbatas, nyeri Eversi Full ROM Terbatas, nyeri Dexra Sinistra PFGD Pasif Regio Gerakan Fleksi Full ROM Terbatas, nyeri Ekstensi Full ROM Terbatas, nyeri Adduksi Full ROM Terbatas, nyeri Abduksi Full ROM Terbatas, nyeri Rotasi internal Full ROM Terbatas, nyeri Rotasi eksternal Full ROM Full ROM Protraksi Full ROM Full ROM Retraksi Full ROM Full ROM Fleksi Full ROM Full ROM Ekstensi Full ROM Full ROM Abduksi Full ROM Full ROM Adduksi Full ROM Full ROM Endorotasi Full ROM Full ROM Eksorotasi Full ROM Full ROM Fleksi Full ROM Terbatas, nyeri Ekstensi Full ROM Terbatas, nyeri Plantarfleksi Full ROM Terbatas, nyeri Dorsifleksi Full ROM Terbatas, nyeri Shoulder Hip Knee Ankle 17 Inversi Full ROM Terbatas, nyeri Eversi Full ROM Terbatas, nyeri 4. Restrictive a) Limitasi ROM : Regio gerakan Shoulder (Fleksi, Ekstensi, Adduksi Abduksi & Rotasi Internal) dan Ankle (Plantarfleksi, Dorsifleksi, Inversi & Eversi). b) Limitasi ADL : Walking, Praying, Dressing & Toileting c) Limitasi Pekerjaan : (+) pekerjaan terganggu untuk melakukan pekerjaannya d) Limitasi Rekreasi : Tidak terganggu 5. Tissue Impairment and Physchological Prediction a) Muskulotendinogen : Suspect spasme m.deltoid, m.pectoralis mayor b) Osteoarthrogen : Suspect osteoarthritis shoulder joint sinistra, gout arthritis ankle sinistra c) Neurogen :- d) Psikogen : Kecemasan 18 6. Spesific test a) VAS Shoulder Ankle Nyeri diam :2 Nyeri diam :2 Nyeri tekan :4 Nyeri tekan :5 Nyeri gerak :6 Nyeri gerak :6 b) Neer’s Sign Hasil : (-) IP : Tidak ada Subacromial impingement c) Hawkins-Kennedy Test Hasil : (-) IP : Tidak ada Subacromial impingement d) Scarf Test Hasil : (+) nyeri sinistra IP : Disfungsi AC Joint e) Painful Arch Hasil : (+) nyeri sinistra IP : Masalah pada sendi acromioclavicular f) Knee Anterior & Posterior Drawer Test Hasil : (-) IP : Tidak ada tear ligament cruciatum anterior dan posterior 19 g) Knee Valgus & Varus Test Hasil : (-) IP : Tidak ada tear pada ligament lateral dan collateral knee h) Apley’s Test Hasil : (-) IP : Tidak ada tear meniscus i) Clarke Sign Hasil : (-) IP : Tidak ada condromalacia patella j) Thompson’s Test Hasil : (-) IP : Tidak ada rupture tendon achilles k) Inversion Tallar Tilt Test Hasil : (-) IP : Tidak ada sprain lig. talofibular anterior, lig. calcaneofibular, lig. calcaneocuboid l) Eversion Tallar Tilt Test Hasil : (-) IP : Tidak ada sprain pada ligament deltoid m) Heel Tap Test Hasil : (-) IP : Tidak ada fraktur pada ankle 20 n) Homan’s Sign Hasil : (-) IP : Tidak ada implikasi deep vein thrombophlebitis o) Tinel’s Foot Test Hasil : (-) IP : Tidak ada tarsal tunnel syndrome p) Muscle Manual Test (MMT) M.Deltoid : Hasil : nilai 3 IP : Full ROM, mampu melawan gravitasi M.Pectoralis Mayor : Hasil : nilai 3 IP : Full ROM, mampu melawan gravitasi q) HRS-A : Hasil : 16 IP : Kecemasan ringan r) Hasil Radiologi : - Aligment shoulder joint sinistra tampak baik - Gambaran osteofit kecil di daerah tuberculum mayor os. humerus dan acromio os. clavicula kiri disertai gambaran sklerotik subchondral - Mineralisasi tulang baik - Sela sendi glenohumerale dan acromioclavicularis kiri baik - Jaringan lunak sekitarnya baik 21 s) Laboratorium Pemeriksaan Hasil Hasil 4 Oktober 5 Oktober Nilai Rujukan Satuan Hematologi WBC 6.6 6.3 4.00-10.0 10̂3/ul RBC 5.78 5.98 4.00-6.00 10̂6/ul HGB 16.6 17.4 12.0-16.0 gr/dl HCT 48 50 37.0-48.0 % MCV 83 83 80.0-97.0 fL MCH 29 29 26.5-33.5 pg MCHC 35 35 31.5-35.0 gr/dl PLT 207 205 150-400 10̂3/ul RDW-CV 12.4 11.9 10.0-15.0 PDW 9.5 10.7 10.0-18.0 fL MPV 8.9 9.4 6.50-11.0 fL PCT 0.00 0.00 0.15-0.50 % NEUT 57.7 61.8 52.0-75.0 % LYMPH 32.6 29.6 20.0-40.0 % MONO 6.4 5.8 2.00-8.00 10̂3/ul EO 2.1 1.9 1.00-3.00 10̂3/ul BASO 1.2 0.9 0.00-0.10 10̂3/ul Kimia Darah GDP 138 139 110 mg/dl GD2PP 209 273 <200 mg/dl HbA 1 c 7.7 8.2 4-6 % Fungsi Ginjal Ureum 29 31 10-50 mg/dl Kreatinin 1.20 1.20 L (<1,3); P mg/dl (<1.1) 22 Profil Lipid Kolestrol total - 204 200 mg/dl Kolestrol HDL - 50 L (>55); P mg/dl (>65) Kolestrol LDL - 156 <130 mg/dl Trigliserida - 82 200 mg/dl P (2.4-5.7) mg/dl Asam Urat Asam Urat 8.6 9.9 L (3.4-7.0) C. Diagnosis Fisioterapi “Gangguan gerak fungsional ekstremitas superior dan inferior berupa cramp e.c gangguan sistem metabolic (Hiperuricemia dan Diabetes Melitus)” D. Problem Fisioterapi a) Kecemasan b) Nyeri c) Keterbatasan ROM d) Kekakuan Sendi e) Kelemahan Otot f) Penurunan Fleksibilitas Otot g) Gangguan Sirkulasi Darah dan ADL E. Program a) Komunikasi Terapeutik b) Manual Therapy c) Peripheral Point Mobilization d) Exercise Therapy (Stretching, Strengthening, Ankle Pumping Exercise) 23 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Hasil pemeriksaan hematologi pasien pada tanggal 5 Oktober didapatkan bahwa terjadi peningkatan hemoglobin, hematocrit, dan basophil. Sedangkan pada pemeriksaan kimia klinik pada tanggal 4 Oktober dan 5 Oktober didaptkan bahwa pasien tersebut mengalami gangguan metabolisme berdasarkan nilai GDP, GD2PP, dan HBA1C mengalami pengingkatan dan mengindikasikan bahwa pasien tersebut mengalami Diabetes Melitus. Selain itu pasien mengalami peningkatan pada pemeriksaan LDL, penurunan HDL, dan peningkatan nilai asam urat. B. Pembahasan 1. Pemeriksaan Hematologi Pemeriksaan panel hematologi (hemogram) terdiri dari leukosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, indeks eritrosit dan trombosit. Pemeriksaan hitung darah lengkap terdiri dari hemogram ditambah leukosit diferensial yang terdiri dari neutrofill (segmented dan bands), basofil, eosinofil, limfosit dan monosit. Rentang nilai normal hematologi bervariasi pada bayi, anak anak dan remaja, umumnya lebih tinggi saat lahir dan menurun selama beberapa tahun kemudian. Nilai pada orang dewasa umumnya lebih tinggi dibandingkan tiga kelompok umur di atas. Pemeriksaan hemostasis dan koagulasi digunakan untuk mendiagnosis dan memantau pasien dengan perdarahan, gangguan pembekuan darah, cedera vaskuler atau trauma. 24 a. White Blood Cell (WBC)/ Leukosit Nilai normal : 3200 – 10.000/mm3 SI : 3,2 – 10,0 x 109/L Deskripsi: Fungsi utama leukosit adalah melawan infeksi, melindungi tubuh dengan memfagosit organisme asing dan memproduksi atau mengangkut/ mendistribusikan antibodi. Ada duatipe utama sel darah putih: 1) Granulosit: neutrofil, eosinofil dan basofil 2) Agranulosit: limfosit dan monosit Leukosit terbentuk di sumsum tulang (myelogenous), disimpan dalam jaringan limfatikus (limfa, timus, dan tonsil) dan diangkut oleh darah ke organ dan jaringan. Umur leukosit adalah 13-20 hari. Vitamin, asam folat dan asam amino dibutuhkan dalam pembentukan leukosit. Sistem endokrin mengatur produksi, penyimpanan dan pelepasan leukosit. Perkembangan granulosit dimulai dengan myeloblast (sel yang belum dewasa di sumsum tulang), kemudian berkembang menjadi promyelosit, myelosit (ditemukan di sumsum tulang), metamyelosit dan bands (neutrofil pada ahap awal kedewasaan), dan akhirnya, neutrofil. Perkembangan limfosit dimulai dengan limfoblast (belum dewasa) kemudian berkembang menjadi prolimfoblast dan akhirnya menjadi limfosit (sel dewasa). Perkembangan monosit dimulai dengan monoblast (belum dewasa) kemudian tumbuh menjadi promonosit dan selanjutnya menjadi monosit (sel dewasa). Implikasi klinik: 1) Nilai krisis leukositosis: 30.000/mm3. Lekositosis hingga 50.000/mm3 mengindikasikan gangguan di luar sumsum tulang (bone marrow). Nilai leukosit yang sangat tinggi (di 25 atas 20.000/mm3) dapat disebabkan oleh leukemia. Penderita kanker post-operasi (setelah menjalani operasi) menunjukkan pula peningkatan leukosit walaupun tidak dapat dikatakan infeksi. 2) Biasanya terjadi akibat peningkatan 1 tipe saja (neutrofill). Bila tidak ditemukan anemia dapat digunakan untuk membedakan antara infeksi dengan leukemia 3) Waspada terhadap kemungkinan leukositosis akibat pemberian obat. 4) Perdarahan, trauma, obat (mis: merkuri, epinefrin, kortikosteroid), nekrosis, toksin, leukemia dan keganasan adalah penyebab lain leukositosis. 5) Makanan, olahraga, emosi, menstruasi, stres, mandi air dingin dapat meningkatkan jumlah sel darah putih 6) Leukopenia, adalah penurunan jumlah leukosit <4000/mm3. Penyebab leukopenia antara lain: a) Infeksi virus, hiperplenism, leukemia b) Obat (antimetabolit, antibiotik, antikonvulsan, kemoterapi) c) Anemia aplastik/pernisiosa d) Multipel mieloma 7) Prosedur pewarnaan: Reaksi netral untuk netrofil; Pewarnaan asam untuk eosinofil; Pewarnaan basa untuk basofil 8) Konsentrasi leukosit mengikuti ritme harian, pada pagi hari jumlahnya sedikit, jumlah tertinggi adalah pada sore hari 9) Umur, konsentrasi leukosit normal pada bayi adalah (6 bulan-1 tahun) 10.00020.000/mm3 dan terus meningkat sampai umur 21 tahun 10) Manajemen neutropenia disesuaikan dengan penyebab rendahnya nilai leukosit. 26 b. Red Blood Cell (RBC)/Eritrosit Nilai normal: Pria: 4,4 - 5,6 x 106 sel/mm3 SI unit: 4,4 - 5,6 x 1012 sel/L Wanita: 3,8-5,0 x 106 sel/mm3 SI unit: 3,5 - 5,0 x 1012 sel/L Deskripsi: Fungsi utama eritrosit adalah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan mengangkut CO2 dari jaringan tubuh ke paru-paru oleh Hb. Eritrosit yang berbentuk cakram bikonkaf mempunyai area permukaan yang luas sehingga jumlah oksigen yang terikat dengan Hb dapat lebih banyak. Bentuk bikonkaf juga memungkinkan sel berubah bentuk agar lebih mudah melewati kapiler yang kecil. Jika kadar oksigen menurun hormon eritropoetin akan menstimulasi produksi eritrosit. Eritrosit, dengan umur 120 hari, adalah sel utama yang dilepaskan dalam sirkulasi. Bila kebutuhan eritrosit tinggi, sel yang belum dewasa akan dilepaskan kedalam sirkulasi. Pada akhir masa hidupnya, eritrosit yang lebih tua keluar dari sirkulasi melalui fagositosis di limfa, hati dan sumsum tulang (sistem retikuloendotelial). Proses eritropoiesis pada sumsum tulang melalui beberapa tahap, yaitu: 1.Hemocytoblast (prekursor dari seluruh sel darah); 2. Prorubrisit (sintesis Hb); 3. Rubrisit (inti menyusut, sintesa Hb meningkat); 4. Metarubrisit (disintegrasi inti, sintesa Hb meningkat; 5. Retikulosit (inti diabsorbsi); 6. Eritrosit (sel dewasa tanpa inti). Implikasi klinik : 1) Secara umum nilai Hb dan Hct digunakan untuk memantau derajat anemia, serta respon terhadap terapi anemia 27 2) Jumlah sel darah merah menurun pada pasien anemia leukemia, penurunan fungsi ginjal, talasemin, hemolisis dan lupus eritematosus. c. HGB (Hemoglobin) Nilai normal : Pria : 13 - 18 g/dL SI unit : 8,1 - 11,2 mmol/L Wanita: 12 - 16 g/dL SI unit : 7,4 – 9,9 mmol/L Deskripsi: Hemoglobin adalah komponen yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen (O2) dan karbon dioksida (CO2). Hb tersusun dari globin (empat rantai protein yang terdiri dari dua unit alfa dan dua unit beta) dan heme (mengandung atom besi dan porphyrin: suatu pigmen merah). Pigmen besi hemoglobin bergabung dengan oksigen. Hemoglobin yang mengangkut oksigen darah (dalam arteri) berwarna merah terang sedangkan hemoglobin yang kehilangan oksigen (dalam vena) berwarna merah tua. Satu gram hemoglobin mengangkut 1,34 mL oksigen. Kapasitas angkut ini berhubungan dengan kadar Hb bukan jumlah sel darah merah. Penurunan protein Hb normal tipe A1, A2, F (fetal) dan S berhubungan dengan anemia sel sabit. Hb juga berfungsi sebagai dapar melalui perpindahan klorida kedalam dan keluar sel darah merah berdasarkan kadar O2 dalam plasma (untuk tiap klorida yang masuk kedalam sel darah merah, dikeluarkan satu anion HCO3). Penetapan anemia didasarkan pada nilai hemoglobin yang berbeda secara individual karena berbagai adaptasi tubuh (misalnya ketinggian, penyakit paru-paru, olahraga). Secara umum, jumlah hemoglobin kurang dari 12 gm/dL menunjukkan anemia. Pada penentuan status anemia, jumlah total hemoglobin lebih penting daripada jumlah eritrosit. 28 Implikasi klinik : 1) Penurunan nilai Hb dapat terjadi pada anemia (terutama anemia karena kekurangan zat besi), sirosis, hipertiroidisme, perdarahan, peningkatan asupan cairan dan kehamilan. 2) Peningkatan nilai Hb dapat terjadi pada hemokonsentrasi (polisitemia, luka bakar), penyakit paru-paru kronik, gagal jantung kongestif dan pada orang yang hidup di daerah dataran tinggi. 3) Konsentrasi Hb berfl uktuasi pada pasien yang mengalami perdarahan dan luka bakar. 4) Konsentrasi Hb dapat digunakan untuk menilai tingkat keparahan anemia, respons terhadap terapi anemia, atau perkembangan penyakit yang berhubungan dengan anemia. Faktor pengganggu 1) Orang yang tinggal di dataran tinggi mengalami peningkatan nilai Hb demikian juga Hct dan sel darah merah. 2) Asupan cairan yang berlebihan menyebabkan penurunan Hb 3) Umumnya nilai Hb pada bayi lebih tinggi (sebelum eritropoesis mulai aktif) 4) Nilai Hb umumnya menurun pada kehamilan sebagai akibat peningkatan volume plasma 5) Ada banyak obat yang dapat menyebabkan penurunan Hb. Obat yang dapat meningkatkan Hb termasuk gentamisin dan metildopa 6) Olahraga ekstrim menyebabkan peningkatan Hb Hal yang harus diwaspadai 1) Implikasi klinik akibat kombinasi dari penurunan Hb, Hct dan sel darah merah. Kondisi gangguan produksi eritrosit dapat menyebabkan penurunan nilai ketiganya. 2) Nilai Hb 20g/dL memicu kapiler clogging sebagai akibat hemokonsenstrasi 29 d. HCT Nilai normal: Pria : 40% - 50 % SI unit : 0,4 - 0,5 Wanita : 35% - 45% SI unit : 0.35 - 0,45 Deskripsi: Hematokrit menunjukan persentase sel darah merah tehadap volume darah total. Implikasi klinik: 1) Penurunan nilai Hct merupakan indikator anemia (karena berbagai sebab), reaksi hemolitik, leukemia, sirosis, kehilangan banyak darah dan hipertiroid. Penurunan Hct sebesar 30% menunjukkan pasien mengalami anemia sedang hingga parah. 2) Peningkatan nilai Hct dapat terjadi pada eritrositosis, dehidrasi, kerusakan paru-paru kronik, polisitemia dan syok. 3) Nilai Hct biasanya sebanding dengan jumlah sel darah merah pada ukuran eritrosit normal, kecuali pada kasus anemia makrositik atau mikrositik. 4) Pada pasien anemia karena kekurangan besi (ukuran sel darah merah lebih kecil), nilai Hct akan terukur lebih rendah karena sel mikrositik terkumpul pada volume yang lebih kecil, walaupun jumlah sel darah merah terlihat normal. 5) Nilai normal Hct adalah sekitar 3 kali nilai hemoglobin. 6) Satu unit darah akan meningkatkan Hct 2% - 4%. Faktor pengganggu 1) Individu yang tinggal pada dataran tinggi memiliki nilai Hct yang tinggi demikian juga Hb dan sel darah merahnya. 2) Normalnya, Hct akan sedikit menurun pada hidremia fi siologis pada kehamilan 30 3) Nilai Hct normal bervariasi sesuai umur dan jender. Nilai normal untuk bayi lebih tinggi karena bayi baru lahir memiliki banyak sel makrositik. Nilai Hct pada wanita biasanya sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. 4) Juga terdapat kecenderungan nilai Hct yang lebih rendah pada kelompok umur lebih dari 60 tahun, terkait dengan nilai sel darah merah yang lebih rendah pada kelompok umur ini. 5) Dehidrasi parah karena berbagai sebab meningkatkan nilai Hal yang harus diwaspadai : Nilai HCT <20% dapat menyebabkan gagal jantung dan kematian, Nilai Hct >60% terkait dengan pembekuan darah spontan e. MCV Nilai normal: Pria : 40% - 50 % SI unit : 0,4 - 0,5 Wanita : 35% - 45% SI unit : 0.35 - 0,45 Deskripsi: Hematokrit menunjukan persentase sel darah merah tehadap volume darah total. Implikasi klinik: 1) Penurunan nilai Hct merupakan indikator anemia (karena berbagai sebab), reaksi hemolitik, leukemia, sirosis, kehilangan banyak darah dan hipertiroid. Penurunan Hct sebesar 30% menunjukkan pasien mengalami anemia sedang hingga parah. 2) Peningkatan nilai Hct dapat terjadi pada eritrositosis, dehidrasi, kerusakan paruparu kronik, polisitemia dan syok. 31 3) Nilai Hct biasanya sebanding dengan jumlah sel darah merah pada ukuran eritrosit normal, kecuali pada kasus anemia makrositik atau mikrositik. 4) Pada pasien anemia karena kekurangan besi (ukuran sel darah merah lebih kecil), nilai Hct akan terukur lebih rendah karena sel mikrositik terkumpul pada volume yang lebih kecil, walaupun jumlah sel darah merah terlihat normal. 5) Nilai normal Hct adalah sekitar 3 kali nilai hemoglobin. 6) Satu unit darah akan meningkatkan Hct 2% - 4%. Faktor pengganggu 1) Individu yang tinggal pada dataran tinggi memiliki nilai Hct yang tinggi demikian juga Hb dan sel darah merahnya. 2) Normalnya, Hct akan sedikit menurun pada hidremia fi siologis pada kehamilan 3) Nilai Hct normal bervariasi sesuai umur dan jender. Nilai normal untuk bayi lebih tinggi karena bayi baru lahir memiliki banyak sel makrositik. Nilai Hct pada wanita biasanya sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. 4) Juga terdapat kecenderungan nilai Hct yang lebih rendah pada kelompok umur lebih dari 60 tahun, terkait dengan nilai sel darah merah yang lebih rendah pada kelompok umur ini. 5) Dehidrasi parah karena berbagai sebab meningkatkan nilai Hal yang harus diwaspadai : Nilai HCT <20% dapat menyebabkan gagal jantung dan kematian, Nilai Hct >60% terkait dengan pembekuan darah spontan f. MCH Perhitungan : MCH (picogram/sel) = hemoglobin/sel darah merah 32 Nilai normal : 28– 34 pg/ sel Deskripsi: Indeks MCH adalah nilai yang mengindikasikan berat Hb rata-rata di dalam sel darah merah, dan oleh karenanya menentukan kuantitas warna (normokromik, hipokromik, hiperkromik) sel darah merah. MCH dapat digunakan untuk mendiagnosa anemia. Implikasi Klinik: 1) Peningkatan MCH mengindikasikan anemia makrositik 2) Penurunan MCH mengindikasikan anemia mikrositik. g. MCHC Nilai Normal Nilai MCHC normal adalah antara 32 sampai 36% Deskripsi Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) adalah konsentrasi hemoglobin rata-rata untuk setiap sel darah merah. Nilai MCHC dihitung dengan membagi hemoglobin dengan massa sel darah merah (Hematokrit) sehingga didapatkan hasil dalam satuan persen (%) atau gram/desiliter (g/dL). Implikasi Klinik 1) Jika kadar MCHC terlalu tinggi, bisa mengindikasikan bahwa sel-selnya bersifat hyperchromic. Artinya ada konsentrasi hemoglobin yang tinggi di setiap sel darah merah. Hal ini ditandai dengan warna merah yang lebih padat. 33 2) Jika dalam tes darah MCHC rendah, berarti kadar hemoglobin dalam setiap sel darah merah lebih rendah dari normal. Hal ini mengindikasikan bahwa sel-selnya bersifat hypochromic yang ditandai dengan warna yang kurang pekat alias pucat. 3) Gejala MCHC rendah meliputi sesak napas, kelelahan, lemas, kulit pucat, pusing, kulit mudah memar, dan kehilangan stamina. Faktor pengganggu 1) peningkatan konsentrasi hemoglobin sel darah merah termasuk kekurangan vitamin B12, penyakit hati, dan komplikasi luka bakar sekunder. 2) Gejala MCHC tinggi terlihat pada pasien dengan anemia hemolitik autoimun (sistem kekebalan tubuh menghancurkan sel darah merah sendiri), spherocytosis herediter (kelainan bawaan yang menyebabkan anemia dan batu empedu), dan anemia makrositik. 3) Penyebab dari MCHC rendah dalam darah ada berbagai alasan antara lain anemia, khususnya anemia mikrositik hipokrom adalah penyebab umum MCHC rendah Selain itu, kekurangan zat besi akibat ketidakmampuan tubuh menyerap zat besi, berbagai kondisi medis yang menyebabkan malabsorpsi zat besi meliputi operasi bypass lambung, penyakit Crohn, dan penyakit Celiac, kehilangan darah besar akibat perdarahan hebat akibat siklus menstruasi yang lama, perusakan dini sel darah merah, keracunan timbal, kanker, dan nfeksi Parasit. h. PLT (Trombosit) Nilai normal : 170 – 380. 103/mm3 SI : 170 – 380. 109/L Deskripsi: 34 Trombosit adalah elemen terkecil dalam pembuluh darah. Trombosit diaktivasi setelah kontak dengan permukaan dinding endotelia. Trombosit terbentuk dalam sumsum tulang. Masa hidup trombosit sekitar 7,5 hari. Sebesar 2/3 dari seluruh trombosit terdapat disirkulasi dan 1/3 nya terdapat di limfa. Implikasi klinik: 1) Trombositosis berhubungan dengan kanker, splenektomi, polisitemia vera, trauma, sirosis, myelogeneus, stres dan arthritis reumatoid. 2) Trombositopenia berhubungan dengan idiopatik trombositopenia purpura (ITP), anemia hemolitik, aplastik, dan pernisiosa. Leukimia, multiple myeloma dan multipledysplasia syndrome. 3) Obat seperti heparin, kinin, antineoplastik, penisilin, asam valproat dapat menyebabkan trombositopenia 4) Penurunan trombosit di bawah 20.000 berkaitan dengan perdarahan spontan dalam jangka waktu yang lama, peningkatan waktu perdarahan petekia/ekimosis. 5) Asam valproat menurunkan jumlah platelet tergantung dosis. 6) Aspirin dan AINS lebih mempengaruhi fungsi platelet daripada jumlah platelet. Faktor pengganggu 7) Jumlah platelet umumnya meningkat pada dataran tinggi; setelah olahraga, trauma atau dalam kondisi senang, dan dalam musim dingin 8) Nilai platelet umunya menurun sebelum menstruasi dan selama kehamilan 9) Clumping platelet dapat menurunkan nilai platelet 10) Kontrasepsi oral menyebabkan sedikit peningkatan 35 Hal yang harus diwaspadai: 1) Pada 50% pasien yang mengalami peningkatan platelet ditemukan keganasan 2) Pada pasien yang mengalami peningkatan jumlah platelet yang ekstrim (>1000 x 103/mm3) akibat gangguan myeloproliferatif, lakukan penilaian penyebab abnormalnya fungsi platelet. 3) Nilai kritis: penurunan platelet hingga < 20 x 103/mm3 terkait dengan kecenderungan pendarahan spontan, perpanjangan waktu perdarahan, peteki dan ekimosis. 4) Jumlah platelet > 50 x 103/mm3 tidak secara umum terkait dengan perdarahan spontan i. RDW-CV Nilai Normal : 11,5 % - 14,5% Deskripsi : Red cell distribution width (RDW) adalah suatu hitungan matematis yang menggambarkan jumlah anisositosis (variasi ukuran sel) dan pada tingkat tertentu menggambarkan poikilositosis (variasi bentuk sel) sel darah merah tepi. Nilai RDWCV (coefficient variation) sangat baik digunakan sebagai indikator anisositosis ketika nilai MCV adalah rendah atau normal dan anisositosis sulit dideteksi. Implikasi Klinik : 1) Penyebab umum peningkatan RWD adalah defisiensi zat besi, vitamin B12, atau asam folat. 2) RDW meningkat setelah mendapatkan transfuse darah, seperti halnya juga pada penderita anemia hemolitik dan trombotik. 36 3) Peningkatan RWD juga berhubungan dengan penyakit hati, pecandu alkohol, keadaan inflamasi, dan penyakit ginjal. 4) RWD adalah prediktor hasil yang independen pada pasien dengan fibrosis paru idiopatik. 5) RWD juga berhubungan dengan beberapa penyakit kardivaskular seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, venous thromboembolism (VTE), dan hipertensi pulmonal. Hal yang harus diwaspadai : 1) RWD-CV kurang akurat digunakan pada nilai MCV yang tinggi. 2) RWD-SD secara teori lebih akurat untuk menilai anisositosis terhadap berbagai nilai MCV j. PDW Normal : 10,0 – 18,0 fL Deskripsi Platelet distribution width (PDW) merupakan indikasi variasi ukuran trombosit yang menjadi tanda pelepasan platelet aktif. PDW adalah variasi ukuran diameter trombosit yang beredar dalam darah perifer. Pemeriksaan PDW juga merupakan gambaran dari masa hidup trombosit yang pendek yang timbul akibat destruksi trombosit. PDW berada dalam hubungan terbalik dengan jumlah trombosit. Implikasi Klinik : 1) Nilai PDW yang tinggi menunjukkan peningkatan produksi trombosit retikulasi yang besar. 37 2) Indeks PDW dapat menjadi faktor risiko untuk penyakit jantung koroner, kegagalan trombolisis, dan infark miokard. 3) Peningkatan PDW mendeteksi terjadinya pembengkakan trombosit atau terjadinya perubahan morfologi pada platelet seperti terjadinya tromboemboli. 4) Nilai PDW yang meningkatkan menggambarkan peningkatan proses trombopoietik. k. MPV Normal : 6,5-11,0 µm Deskripsi : Mean platelet volume (MPV) adalah ukuran diameter rata – rata trombosit yang beredar dalam darah perifer. Oleh karena trombosit muda berukuran lebih besar maka MPV yang tinggi merupakan pertanda peningkatan produksi trombosit muda atau sebagai kompensasi lebih cepatnya penghancuran platelet. MPV berada dalam hubungan terbalik dengan jumlah trombosit. Implikasi klinik : 1) Peningkatan MPV ataupun PDW diakibatkan oleh meningkatnya proporsi trombosit muda sehingga terjadi perbedaan variasi ukuran trombosit yang beredar dalam darah perifer. 2) Peningkatan MPV mengindikasikan terjadi trompositopenia yakni penurunan jumlah trombosit. 3) Peningkatan MPV dapat terjadi pada keadaan inflamasi akut seperti infark miokard sindrom metabolik, dan DBD 38 4) MPV dapat digunakan sebagai penanda aktivasi inflamasi pada inflammatory bowel disease Hal yang harus diwaspadai : 1) PDW merupakan penanda yang lebih spesifik untuk aktivasi trombosit dibandingkan MPV 2) Nilai PDW dan MPV akan lebih tinggi pada DSS atau grade III DBD dan cenderung normal atau rendah pada grade I dan II DBD l. PCT Normal : PCT < 0,5 ng/ml Risiko tinggi sepsis : PCT > 2 ng/ml Deskripsi Procalcitonin (PCT) adalah suatu protein fungsional yang terdiri dari 114 sampai 116 asam amino. PCT memiliki fungsi khusus dan tubuh mengatur kadarnya dengan sangat ketat. PCT merupakan suatu protein yang terlibat dalam imunopatogenesis sepsis. PCT adalah pemeriksaan biomarker untuk infeksi bakteri dengan atau tanpa sepsis. PCT memiliki sensitivitas dan spesifikasi terhadap bacteremia sebesar 76% dan 69%. Waktu paruh kadar PCT adalah 24 – 36 jam. Implikasi Klinik : 1) PCT sebagai panduan untuk memberikan terapi antibiotic pada infeksi saluran napas atas akut. 2) Pada pasien stabil, antibiotik disarankkan untuk diberikan bila kadar PCT > 0,25 ng/ml. 39 3) Jika kadar PCT dalam 24 jam pertama di ICU dibawah 2 ng/ml, sepsis akibat infeksi bakteri dapat diekslusi. 4) Jika kadar PCT diatas 2 ng/ml, kemungkinan sepsis akibat infeksi bakteri dan jika diatas 10 ng/ml maka terjadi sepsis akibat infeksi bakteri besar (positive predictive value 80%) 5) Peningkatan PCT dapat ditemukan pada kondiri SIRS (systemic inflammatory response syndrome) berat, distress napas akut, keganasan, malaria, infeksi jamur, dan kondisi pasca operasi. Yang harus diperhatikan : 1) Pada pasien kritis antibiotik dihentikan bila kadar PCT < 0,5 ng/ml 2) Lakukan pengecekan ulang PCT setelah 6 – 12 jam (bila rawat inap) m. Neutrofil Nilai normal: Segment : 36% - 73% SI unit : 0,36 – 0,73 Bands : 0% - 12% SI unit : 0,00 – 0,12 Deskripsi: Neutrofil adalah leukosit yang paling banyak. Neutrofil terutama berfungsi sebagai pertahanan terhadap invasi mikroba melalui fagositosis. Sel ini memegang peranan penting dalam kerusakan jaringan yang berkaitan dengan penyakit noninfeksi seperti artritis reumatoid, asma dan radang perut. Implikasi klinik: 1) Neutrofillia, yaitu peningkatan persentase neutrofill disebabkan oleh infeksi bakteri dan parasit, gangguan metabolit, perdarahan dan gangguan myeloproliferatif. 40 2) Neutropenia yaitu penurunan persentase neutrofill, dapat disebabkan oleh penurunan produksi neutrofill, peningkatan kerusakan sel, infeksi bakteri, infeksi virus, penyakit hematologi, gangguan hormonal dan infeksi berat. 3) Shift to left atau peningkatan bands (sel belum dewasa) terjadi ketika neurofil muda dilepaskan kedalam sirkulasi. Hal ini disebabkan oleh infeksi, obat kemoterapi, gangguan produksi sel (leukemia) atau perdarahan. 4) Shift of the right atau peningkatan segment (sel dewasa) terjadi pada penyakit hati, anemia megalobastik karena kekurangan B12 dan asam folat, hemolisis, kerusakan jaringan, operasi, obat (kortikosteroid) 5) Peningkatan jumlah neutrofil berkaitan dengan tingkat keganasan infeksi. 6) Derajat neutrofil lia sebanding dengan jumlah jaringan yang mengalami infl amasi. 7) Jika peningkatan neutrofil lebih besar daripada peningkatan sel darah merah total mengindikasikan infeksi yang berat. 8) Pada kasus kerusakan jaringan dan nekrosis (seperti: kecelakaan, luka bakar, operasi), neutrofil lia terjadi akibat peningkatan zat neutrofil lik atau mekanisme lain yang belum diketahui. Faktor pengganggu: 1) Kondisi fisiologi seperti stres, senang, takut, marah, olahraga secara sementara menyebabkan peningkatan neutrofil. 2) Wanita yang melahirkan dan menstruasi dapat terjadi neutrofilia 3) Pemberian steroid: puncak neutrofi lia pada 4 hingga 6 jam dan kembali normal dalam 24 jam (pada infeksi parah, neutrofi lia tidak terjadi) 4) Paparan terhadap panas atau dingin yang ekstrim 41 5) Umur: – Anak-anak merespon infeksi dengan derajat leukositosis neutrofi lia yang lebih besar dibandingkan dewasa – Beberapa pasien lanjut umur merespon infeksi dengan derajat netrofil yang lemah, bahkan ketika terjadi infeksi parah 6) Resistensi – Orang pada semua kisaran umur dalam kondisi kesehatan lemah tidak merespon dengan neutrofi lia yang bermakna 7) Myelosupresif kemoterapi Hal yang harus diwaspadai: Agranulositosis (ditandai dengan neutropenia dan leukopenia) sangat berbahaya dan sering berakibat fatal karena tubuh tidak terlindungi terhadap mikroba. Pasien yang mengalami agranulositosis harus diproteksi terhadap infeksi melalui teknik isolisasi terbalik dengan penekanan pada teknik pencucian tangan n. Limfosit Nilai normal : 15% - 45% Deskripsi: Merupakan sel darah putih yang kedua paling banyak jumlahnya. Sel ini kecil dan bergerak ke daerah infl amasi pada tahap awal dan tahap akhir proses infl amasi. Merupakan sumber imunoglobulin yang penting dalam respon imun seluler tubuh. Kebanyakan limfosit terdapat di limfa, jaringan limfatikus dan nodus limfa. Hanya 5% dari total limfosit yang beredar pada sirkulasi. 42 Implikasi klinik: 1) Limfositosis dapat terjadi pada penyakit virus, penyakit bakteri dan gangguan hormonal 2) Limfopenia dapat terjadi pada penyakit Hodgkin, luka bakar dan trauma. 3) Virosites (limfosit stres, sel tipe Downy, limfosit atipikal) adalah tipe sel yang dapat muncul pada infeksi jamur, virus dan paratoksoid, setelah transfusi darah dan respon terhadap stres. 4) Perubahan bentuk limfosit dapat digunakan untuk mengukur histokompabilitas. 5) Jumlah absolut limfosit < 1000 menunjukkan anergy Faktor pengganggu 1) Limfositosis pada pediatri merupakan kondisi fi siologis pada bayi baru lahir yang meliputi peningkatan sel darah putih dan limfosit yang nampak tidak normal yang dapat keliru dengan keganasan sel 2) Olahraga, stres emosional dan menstruasi dapat menyebabkan peningkatan limfositosis Hal yang harus diwaspadai: Penurunan limfosit < 500/mm3 menunjukkan pasien dalam bahaya dan rentan terhadap infeksi, khususnya infeksi virus. Harus dilakukan tindakan untuk melindungi pasien dari infeksi. o. Monosit Nilai normal : 0%-11% Deskripsi: Monosit merupakan sel darah yang terbesar. Sel ini berfungsi sebagai lapis kedua pertahanan tubuh, dapat memfagositosis dengan baik dan termasuk kelompok makrofag. Manosit juga memproduksi interferon. 43 Implikasi klinik: 1) Monositosis berkaitan dengan infeksi virus, bakteri dan parasit tertentu serta kolagen, kerusakan jantung dan hematologi. 2) Monositopenia biasanya tidak mengindikasikan penyakit, tetapi mengindikasikan stres, penggunaan obat glukokortikoid, myelotoksik dan imunosupresan. p. Eosinofil Nilai normal : 0% - 6% Deskripsi Eosinofil memiliki kemampuan memfagosit, eosinofil aktif terutama pada tahap akhir infl amasi ketika terbentuk kompleks antigen-antibodi. Eosinofil juga aktif pada reaksi alergi dan infeksi parasit sehingga peningkatan nilai eosinofil dapat digunakan untuk mendiagnosa atau monitoring penyakit. Implikasi klinik: 1) Eosinofilia adalah peningkatan jumlah eosinofil lebih dari 6% atau jumlah absolut lebih dari 500. Penyebabnya antara lain: respon tubuh terhadap neoplasma, penyakit Addison, reaksi alergi, penyakit collagen vascular atau infeksi parasit. 2) Eosipenia adalah penurunan jumlah eosinofil dalam sirkulasi. Eosipenia dapat terjadi pada saat tubuh merespon stres (peningkatan produksi glukokortikosteroid). 3) Eosinofil cepat hilang pada infeksi pirogenik 4) Jumlah eosinofil rendah pada pagi hari dan meningkat pada sore hari hingga tengah malam. 5) Eosinofilia dapat disamarkan oleh penggunaan steroid dan dapat meningkat dengan L-triptofan 44 Faktor pengganggu 1. Ritme harian: jumlah eosinofil normal terendah pada pagi hari, lalu meningkat dari siang hingga setelah tengah malam. Karena itu, jumlah eosinofi l serial seharusnya berulang pada waktu yang sama setiap hari. 2. Situasi stres, seperti luka, kondisi pasca operasi, tersengat listrik menyebabkan penurunan eosinofil 3. Setelah pemberian kortikosteroid, eosinofil menghilang. Hal yang harus diwaspadai Eosinofil dapat tertutup oleh penggunaan steroid. Berikan perhatian pada pasien yang menerima terapi steroid, epinefrin, tiroksin atau prostaglandin. q. Basofil Nilai normal : 0% - 2% Deskripsi: Fungsi basofil masih belum diketahui. Sel basofil mensekresi heparin dan histamin. Jika konsentrasi histamin meningkat, maka kadar basofil biasanya tinggi. Jaringan basofi l disebut juga mast sel. Implikasi klinik : 1) Basofilia adalah peningkatan basofil berhubungan dengan leukemia granulositik dan basofilik myeloid metaplasia dan reaksi alergi 2) Basopenia adalah penurunan basofil berkaitan dengan infeksi akut, reaksi stres, terapi steroid jangka panjang. 45 2. Pertimbangan Hematologi Dalam Pemberian Exercise Berdasarkan hasil pemeriksaan hematologi didapatkan hasil tuan X didapatkan bahwa terjadi peningkatan hemoglobin, hematocrit dan basophil. Pemeriksaan hemoglobin pada tanggal 4 Oktober nilainya sebesar 16,6 (normal) sedangkan pada tanggal 5 Oktober yaitu sebesar 17,4 (melebihi batas maksimal nilai rujukan), hal tersebut juga sejalan dengan hasil pemeriksaan hematocrit, pada pemeriksaan tanggal 4 Oktober sebesar 48 (normal). sedangkan pada tanggal 5 Oktober nilainya menjadi 50 (melebihi batas maksimal nilai rujukan). Hemoglobin adalah komponen yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen (O2) dan karbon dioksida (CO2). Hb tersusun dari globin (empat rantai protein yang terdiri dari dua unit alfa dan dua unit beta) dan heme (mengandung atom besi dan porphyrin: suatu pigmen merah). Pigmen besi hemoglobin bergabung dengan oksigen. Hemoglobin yang mengangkut oksigen darah (dalam arteri) berwarna merah terang sedangkan hemoglobin yang kehilangan oksigen (dalam vena) berwarna merah tua. Satu gram hemoglobin mengangkut 1,34 mL oksigen. Hematokrit menunjukan persentase sel darah merah tehadap volume darah total. Peningkatan nilai hemoglobin dan hematocrit dapat terjadi pada eritrositosis, dehidrasi, kerusakan paru-paru kronik, polisitemia dan syok. Sedangkan pasien tidak memiliki riwayat penyakit tersebut. Sehingga, penyebab peningkatan nilai hemoglobin dan hematocrit terjadi karena dehidrasi ataupun syok. Oleh karena itu, saat melakukan exercise perhatikan pasien agar tidak mengalami dehidrasi dan tetap menyediakan air mineral untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh pasien. Pemeriksaan basophil pada tanggal 4 Oktober sebesar 1,2 (normal 0,00 – 0,10) kemudian hasil pemeriksaan menunjukkan penurunan walaupun belum mencapai batas normal yakni sebesar 0,9. Basofil berperan dalam reaksi alergi, jaringan basofil I disebut juga 46 sel mast. Jika konsentrasi meningkat makka kadar basofil meningkat, hal itu sering kali dikaitkan dengan reaksi alergi yakni hipersensitivitas tiper I. reaksi tipe 1 ini dapat terjadi sebagai suatu gangguan sistemi atau reaksi local dengan gejala yang sering dijumpai yani obstruksi saluan pernapasan atas sehingga diikuti oleh kesulitan bernapas. Untuk mewaspadai hal tersebut dalam pemberian intervensi Fisioterapi sebaiknya dilakukan dengan intensitas rendah disesuaikan dengan dosis dan zona latihan pasien, breathing exercise disetiap sesi latihan juga dapat diterapkan dalam intervensi ini terlebih jika pasien terlihat sesak. Jika pasien terlihat sesak napas berat maka tindakan Fisioterapi perlu ditunda sementara. 3. Pemeriksaan Kimia Klinik a. Glukose Puasa_(GDP) 1) Definisi: GDP adalah pengukuran glukosa darah yang diambil setelah Anda berpuasa atau belum makan/minum apa pun selain air selama 8 hingga 10 jam. Ini seringkali merupakan tes pertama yang dilakukan untuk membantu mendeteksi diabetes. 2) Hasil atau nilai rujukan: a) Level Gula darah kurang 5.6mmol / L (100 mg / dl) dianggap normal. b) Kadar antara 5,6 dan 7mmol / L (100 dan 126 mg / dl) berarti Anda berisiko terkena diabetes tipe 2 (pra-diabetes). c) Kadar 7mmol / L (126 mg / dl) atau lebih tinggi berarti Anda menderita diabetes. d) Kadar Gula Darah <70 mg / dL, ini menunjukkan kadar gula yang sangat rendah yang terjadi karena dosis insulin atau obat diabetes yang berlebihan, kelaparan lebih dari 12 jam dengan asupan makan malam yang buruk 47 e) Gula Darah kurang dari 110 mg / dL, menunjukkan gula darah kisaran gula normal, orang yang tidak menderita diabete, pasien diabetes yang terkontrol dengan baik f) Gula Darah lebih 200 mg / dL, ini menunjukkan kadar gula darah sangat tinggi, menunjukkan diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dan jika diuji tes GDP pertama kali, berarti orang tersebut menderita diabetes b. Glukose 2 jam PP (GD2PP) 1) Definisi : GDPP atau gula darah 2 jam postprandial (GD2PP) yaitu tes toleransi glukosa dilakukan untuk mengukur kemampuan tubuh untuk memproses glukosa. Kadar gula darah yang diperiksa saat 2 jam setelah minum larutan glukosa 75 gram. Pemeriksaannya dilakukan setelah GDP, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan GDP, Anda akan diberikan asupan air dengan 75 gram gula. 2) Hasil/ nilai rujukan: a) Nilai normal glukosa 2 jam PP: di bawah 7,8 mmol/L atau 140 mg/dL b) Prediabetes (toleransi glukosa terganggu): 7,8-11,1 mmol/L atau 140-199 mg/dL c) Diabetes: di atas 11,1 mmol/L atau 200 mg/dL dalam lebih dari satu kali pemeriksaan. 48 c. HBA 1c_(HbA 1c) 1) Definisi: Pemeriksaan HbA1c adalah pemeriksaan darah yang penting untuk melihat seberapa baik pengobatan terhadap diabetes. Artinya pemeriksaan Hemoglobin A1C ini akan menggambarkan rata-rata gula darah selama 2 sampai 3 bulan terakhir dan digunakan bersama dengan pemeriksaan gula darah biasa untuk membuat penyesuaian dalam pengendalian diabetes melitus. Hemoglobin ditemukan dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika diabetes tidak terkontrol (yang berarti bahwa gula darah terlalu tinggi terus menerus), maka gula akan menumpuk dalam darah dan menggabungkan diri dengan hemoglobin sehingga menjadi "terglikasi. 2) Hasil/nilai rujukan a) Kisaran nilai normal HbA1c adalah antara 4% sampai 5,6%. b) Kadar HbA1c antara 5,7% sampai 6,4% mengindikasikan peningkatan risiko diabetes, c) Kadar 6,5% atau lebih tinggi mengindikasikan diabetes. d. Ureum_(Ureum) 1) Definisi Ureum darah adalah produk sisa metabolisme protein di dalam tubuh. Saat Anda mengonsumsi protein, hati akan memecahnya agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Dari proses tersebut akan tercipta ureum atau urea yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga, hati akan mengeluarkannya melalui darah agar bisa menuju ke ginjal. Di ginjal, urea akan diolah agar bisa dikeluarkan melalui urine saat Anda buang air kecil. Biasanya, sedikit urea juga masih akan tersisa di darah, tapi dalam jumlah 49 yang tidak membahayakan.Apabila ginjal mengalami kerusakan, pengeluaran urea melalui urine akan terganggu. Akibatnya, ia akan menumpuk di dalam darah dan kadar ureum darah pun akan meningkat. Sebaliknya, apabila pada pemeriksaan laboratorium kadar ureum darah ditemukan terlalu rendah, maka ada beberapa gangguan kesehatan yang juga mungkin Anda derita. 2) Hasil atau nilai rujukan a) Laki-laki dewasa: 8-24 mg/dL b) Perempuan dewasa: 6-21 mg/dL c) Anak usia 1-17 tahun: 7-20 mg/dL e. Kreatinin 1) Definisi Tes kadar kreatinin adalah salah satu pemeriksaan untuk mengevaluasi fungsi ginjal. Kadar senyawa ini akan diketahui melalui tes darah dan tes urine. Kreatinin merupakan limbah sisa produk yang dihasilkan oleh proses metabolisme otot. Kreatinin dalam darah akan disaring oleh ginjal dan dibuang dalam bentuk urine. 2) Hasil/ nilai rujukan yaitu a) Laki-laki 0,6–1,2 mg/dL b) Wanita 0,5–1,1 mg/dL f. Kolesterol total 1) Definisi Kolesterol merupakan lemak yang diproduksi oleh tubuh manusia terutama didalam hati. Darah mengandung 80% kolesterol yang diproduksi oleh tubuh sendiri dan 20% dari makanan. Kolesterol yang ada didalam darah berikatan dengan protein 50 dan ditransportasi keseluruh tubuh. Kolesterol sangat penting bagi tubuh, namun bila kadar kolesterol dalam darah berlebihan akan berbahaya bagi kesehatan. Kadar kolesterol yang melebihi batas normal disebut hiperkolesterolemia. 2) Hasil atau nilai rujukan Normal : < 200 mg/dL Hiperkolesterolemia : 200 – 400 mg/dL g. Kolesterol HDL 1) Definisi High density lipoprotein (HDL) merupakan lipoprotein yang mengangkut kolesterol lebih sedikit. HDL sering disebut kolesterol baik karena dapat membuang kelebihan kolesterol jahat di pembuluh arteri kembali ke liveruntuk diproses da dibuang. 2) Hasil atau nilai rujukan Laki – laki : > 55 mg/dL Perempuan : > 65 mg/dL h. Kolesterol LDL 1) Definisi Low density lipoprotein (LDL) merupakan lipoprotein yang mengangkut paling banyak kolesterol ddalam darah. LDL dinamakan kolesterol jahat karena kadar LDL yang tinggi menyebabkan mengendapnya kolesterol dalam darah sehingga terjadi trauma pada dinding pembuluh darah atau terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. 51 2) Hasil atau nilai rujukan Normal : < 130 mg/dL i. Trigliserida 1) Definisi Trigliserida merupakan jenis lemak (lipid) darah yang ikut menyusun molekul lipoprotein dan berfungsi sebagai sarana transportasi energy dan menyimpan energy. Asam lemak dari trigliserida dimanfaatkan sebagai sumber energy yang diperlukan oleh otot – otot tubuh untuk bekerja atau disimpan sebagai cadangan energy dalam bentuk lemak atau jaringan adiposa. 2) Hasil atau nilai rujukan Normal : 200 mg/dL High : 200 – 499 mg/dL Very High : >500 mg/dL j. Asam Urat 1) Definisi Asam urat adalah asam berbentuk Kristal yang merupakan produk akhir dari metabolism atau pemecahan purin. Setiap orang memiliki asam urat didalam tubuh karena pada setiap metabolism normal dihasilkan asam urat. Senyawa asam urat memiliki sifat sukar larut dan mudah mengendap jika kadarnya meningkat beberapa milligram saja. Meningkatnya asam urat dalam darah disebut hiperurisemia, yaitu kelarutan asam urat dalam darah melewati ambang batasnya sehingga menyebabkan timbunan asam urat dalam bentuk garam (monosodium urat). 52 2) Hasil atau nilai rujukan Perempuan : 2,4 – 5,7 mg/dL Laki – laki : 3,4 – 7,0 mg/dL 4. Pertimbangan Kimia Klinik Dalam Pemberian Exercise Hasil pemeriksaan kimia klinik tuan X pada tanggal 4 dan 5 Oktober menunjukkan hasil dari pemeriksaan GDP, GD2PP, dan HbA1C mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pasien tersebut mengalami gangguan system metabolic khususnya penyakit Diabetes Melitus. Oleh karena itu dalam hal ini seorang fisioterapi perlu melakukan exercise yang juga membantu untuk mengontrol gula darah pasien. Exercise dianjurkan untuk semua pasien diabetes mellitus (DM) jika tidak ada kontraindikasi. Namun, penting untuk mengetahui dampak exercise terhadap kadar glukosa darah mereka. Penyesuaian dosis insulin diperlukan ketika individu dengan DM melakukan exercise untuk memastikan bahwa kadar glukosa plasma mereka diatur. Exercise memfasilitasi penyerapan insulin yang disuntikkan melalui peningkatan aliran darah ke otot dan ini dapat menyebabkan hipoglikemia. Oleh karena itu, tempat suntikan insulin tidak boleh di ekstremitas atau otot berkontraksi selama latihan. Respon insulin terhadap latihan dan risiko hipoglikemia berbeda dari satu pasien ke pasien lainnya dan oleh karena itu evaluasi dan edukasi individu adalah wajib mengenai durasi dan intensitas latihan, penempatan injeksi. Hasil pemeriksaan kimia klinik tuan X pada tanggal 5 Oktober menunjukkan adanya peningkatan pada kolesterol dan LDL serta penurunan pada kadar HDL. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan riwayat DM yang dimiliki pasien, dijaringan lemak terjadi penurunan efek insulin sehingga lipogenesis berkurang dan lipolisis meningkat, hal ini memicu lipotoxicity yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar LDL. Peningkatan kadar LDL dalam darah dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, 53 aterosklerotik atau gangguan kardiovaskuler. Dalam penyusun program intervensi, seorang fisioterapis perlu memperhatikan dan melakukan assessment lengkap terhadap gejala dari peningkatan LDL dan kolesterol yang mungkin dialami pasien. Dalam melakukan intervensi, seorang fisioterapis disarankan menggunakan perhitungan zona latihan dengan batas bawah 20% dan batas atas 30% kemudian mengecek zona latihan secara berkala serta dapat ditingkatkan jika pasien tidak mudah mudah mengalami kelelahan. Skala borg dapat digunakan untuk menilai sesak napas yang mungkin dialami pasien sebagai kompensasi dari sel tubuh yang kekurangan oksigen, untuk intervensinya direkomendasikan menggunakan breathing exercise. Pemeriksaan hipertensi juga diperlukan dalam anamnesis umum, hipertensi menandakan adanya gangguan pada kardiovaskular. Dalam menerapkan latihan harus selalu memperhatikan zona latihan, dosis latihan, kelelahan pasien atau kondisi pernapasan pasien serta tidak disarankan menggunakan elektroterapi yang akan mempengaruhi dan menyebabkan masalah yang lebih serius nantinya pada sirkulasi darah dan sistem kelistrikan jantung. Hasil pemeriksaan kimia klinik juga menunjukkan adanya peningkatan pada kadar asam urat, pemeriksaan pada tanggal 4 oktober mengalami peningkatan dari batas normal yakni 86 mg/dL kemudian pada tanggal 5 Oktober semakin mengalami peningkatan yakni 9,9 mg/dL. Berdasarkan kondiri tersebut, pasien tentu saja akan mengalami keluhan adanya keram pada ekstremitas bawah. seorang Fisioterapis dapat mempertimbangkan intervensi yakni pumping action pada ankle untuk memperlancar aliran darah balik, jika pasien mengalami nyeri tanpa ada risiko penyakit kardiovaskular maka alat elektroterapi dapat digunakan namun jika disertai dengan risiko terkena penyakit kardiovaskular maka direkomdasikan untuk menerapkan latihan passive atau myofascial release untuk 54 membebaskan adhesi dari jaringan lunak yang berada disekitar sendi akibat peningkatan asam urat, ketika nyeri menurun dapat menerapkan latihan ROM aktif dan penguatan otot – otot pada ekstremitas bawah utamanya daerah yang sering mengalami keram, tentunya latihan ini tetap harus mempehatikan zona latihan karena pasien mengalami riwayat penyakit metabolik. 5. Pemeriksaan dan Intervensi Fisioterapi a. Intervensi Fisioterapi : Intervensi Fisioterapi pada OA Shoulder Joint : No Problem Metode Dosis 1. Kecemasan Komunikasi teraupetik F : 1x/sehari I : Fokus T : Interpersonal approach T : Sepanjang terapi 2. - Nyeri - LGS/ROM Manual therapy F : 3x/minggu I : 10x repetisi preset, sebnyak 3 set/intervensi dan istirahat 30 detik/set (MWM). 8 detik hitungan, 3x repetisi (Friksen) T : MWM dengan gerak rolling dan gliding. Dan Friksen T : 2 menit 3. Kekakuan sendi Peripheral point Mobilization F : 3x/minggu I : 8 hitungan, 3 kali repetisi dan istirahat 5 detik/repetisi T : Traksisi-Translasi T : 1 menit 4. Kelemahan otot Exercise therapy F : 3x/minggu 55 I : 8 hitungan, 3 kali repetisi T : Strengtening (Active resisted exercise, ke segala arah) T : 1 menit 5. Penurunan Fleksibelitas otot Exercise therapy F: 3x/minggu I : 8x hitungan, 3 kali repetisi T : Streching (pasif stretching, ke segala arah T : 1 menit Intervensi Fisioterapi pada Hiperurisemia Ankle Joint dengan Riwayat DM : No Problem Metode Dosis 1. Kecemasan Komunikasi teraupetik F : 1x/sehari I : Fokus T : Interpersonal approach T : Sepanjang terapi 2. Nyeri Manual therapy F : 3x/minggu I : 8 hitungan, 3x repetisi T : MWM dengan gerak rolling dan gliding. Dan Friksen T : 1 menit 3. LGS/ROM Exercise therapy F : 3x/seminggu I : 8 hitungan, 3x repetisi preset, sebnyak 3 set/intervensi dan istirahat 10 detik/set T : Aromex, Promex, Assisted exercise T : 2 menit 4. Kekakuan sendi Peripheral point Mobilization F : 3x/minggu I : 8 hitungan, 5 kali repetisi dan istirahat 3 detik/repetisi 56 T : Traksisi-Translasi T : 1 menit 5. Kelemahan otot Exercise therapy F : 3x/minggu I : 8 hitungan, 3 kali repetisi T : Strengtening (Active resisted exercise, ke segala arah) T : 1 menit 6. - Penurunan Fleksibelitas otot - Rasa kram/kebas Exercise therapy F: 3x/minggu I : 8x hitungan, 5 kali repetisi T : Streching (pasif stretching, ke dorsi fleksi T : 1 menit 7. Sirkulasi darah Exercise therapy F : 1x/hari I : 15 hitungan, 3 kali repetisi T : Ankle pumping T : 1 menit 8. Resistensi Isulin MVT Pankreas F : 3x/hari I : 8 hitungan, 3 kali repetisi T : direct, indirect, induction techniques T : 1 menit b. Evaluasi Fisioterapi OA Shoulder Joint & Hiperurisemia Ankle Joint dengan Riwayat DM (setelah 3 minggu terapi) : No Problem Parameter Evalusi Sesaat Pre Post Interpretasi 1. Kecemasan HRS-A 16 10 Ada penurunan tingkat kecemasan 2. Nyeri VAS diam: 2 gerak: 6 tekan: 4 diam:1 gerak: 4 tekan: 2 Ada penurunan tingkat nyeri ada penurunan 57 3. 4. c. Kekuatan Otot MMT 3 4 Good, komtraksi otot dengan sendi penuh, mampu melawan gravitasi dengan tahanan minimal LGS ROM goniometer terbatas Flx: 155° Ada peningkatan Ext: 45° LGS pada shoulder Abd: 150° Add: 35° I.R. Abd: 55° E.R Add: 80° Kemitran : Melihat kondisi pasien, kemitraan multiprofesi sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus seperti ini. Kemitraan dapat dilakukan bersama beberapa tenaga kesehatan, seperti: dokter spesialis radiologi, dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis penyakit dalam, hingga ahli gizi, yang dimana akan membantu dalam proses penyembuhan pasien apabila membutuhkan rujukan perawatan medis lainnya. d. Home Program Exercise : Shoulder : 1. Strengthening & stretching exercise 2. Muscle stabilization 3. ROM exercise Scapular muscle stabilization-isotonic exercise Strengthening exercise, shoulder extension-isometric 58 Strengthening exercise, shoulder external rotation-isometric Strengthening exercise, shoulder internal rotation-isometric ROM & Stretching exercise Shoulder elevation stretch Strengthening exercise, shoulder external rotation-isotonic Strengthening exercise, shoulder internal rotation-isometric Finger lader exercise Strengthening exercise shoulder internal rotation-isotonic Strengthening exercise, shoulder abduksi-isotonic Ankle : 1. Berolah raga ringan seperti jalan atau senam ringan dan menghindari jogging atau lari dengan intensitas sedang selama 30 menit, secara rutin 3-5 kali perminggu. 59 2. Renang 3. ROM exercise 4. Strengthening & stretching exercise Berenang memberikan terapi latihan pada ankle, sehingga dapat memperlancar sirkulasi darah + ROM exercise Strengthening exercise Streching exercise + ROM exercise e. Modifikasi : Modifikasi program fisioterapi disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi setelah pemberian intervensi beberapa kali, hasil evaluasi laboratorium, foto radiologi yang didaptkan dari perkembangan hasil terapi yang tercapai oleh pasien. Modifikasi dapat 60 berupa peningkatan atau penurun dosis terapi terkait frekuensi, intensitas, teknik dan time/durasi waktu latihan. 61 DAFTAR PUSTAKA Chilappa, C. S., Aronow, W. S., Shapiro, D., Sperber, K., Patel, U., & Ash, J. Y. (2010). Gout and hyperuricemia. Comprehensive Therapy, 36, 3–13. https://doi.org/10.1136/ard.36.5.487-b Cnar, Y., Demirci, H., & Satm, I. (2013). Principles of Exercise and Its Role in the Management of Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus - Insights and Perspectives, (January 2013). https://doi.org/10.5772/50503 Cope PJ, Ourradi K, Li Y, Sharif M. Models of osteoarthritis: the good, the bad and the promising. Osteoarthr. Cartil. 2019 Feb;27(2):230-239. Gonzalez, E. B. (2012). An update on the pathology and clinical management of gouty arthritis. Clinical Rheumatology, 31(1), 13–21. https://doi.org/10.1007/s10067-011-1877-0 Hainer, B. L., Matheson, E., & Travis Wilkes, R. (2014). Diagnosis, treatment, and prevention of gout. American Family Physician, 90(12), 831–836. Herlambang, U. (2019). FKP.N. 22-19 Her p. Hijriana, I., Suza, D. E., & Ariani, Y. (2016). Pengaruh Latihan Pergerakan Sendi Ekstremitas Bawah Terhadap Nilai Ankle Brachial Index (Abi) Pada Pasien Dm Tipe 2. Idea Nursing Journal, 7(2), 32–39. Hikmatyar, G., & Larasati, T. A. (2013). Penatalaksanaan Komprehensif Arthritis Gout dan Osteoarthritis pada Buruh Usia Lanjut Comprehensive Management of Arthritis Gout and Osteoarthritis in Old Age Workers. Hughes, B. S., & Vincent, M. (2012). Gout managing gout and hyperuricaemia Uric Acid Levels Are Associated Elevated Levels Is Not Required Routinely If The Patient Does Not. 4(March), 79–83. Kopke, A., & Greeff, O. B. W. (2015). Hyperuricaemia and gout. South African Family Practice, 57(1), 6–12. https://doi.org/10.36303/sagp.2020.3.0014 Majid, A., & Puspitha, A. (2012). The Effect of Active Range of Motion Exercise on Sensory Neuropathy in Diabetes Mellitus Patients. 1(2), 101–109. Narinda, Suryandari (2017). Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Menggunaan Metode Spektrofotometer dan Metode Strip. Jurnal e-Biomedik (eBm). Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi.p:1 Pratiwi, R. M. (2018). Pengaruh Resistance Exercise Terhadap Perbaikan Neuropati Diabetikum, Ankle Brachial Index Dan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes 62 Melitus Tipe 2 Halaman. 1–206. Perhimpunan Reumatologi Indonesia. (2018). Pedoman diagnosis dan pengelolaan gout. Jakarta: Perhimpunan Reumatologi Indonesia Trisnowiyanto, B. (2016). BBeda Pengaruh Intervensi Peregangan Dan Mobilisasi Sendi terhadap Perbaikan Keterbatasan Lingkup Gerak Sendi. Jurnal Kesehatan, 7(2), 182. https://doi.org/10.26630/jk.v7i2.186 Wahyu Widyanto, F. (2017). Artritis Gout Dan Perkembangannya. Saintika Medika, 10(2), 145. https://doi.org/10.22219/sm.v10i2.4182 63