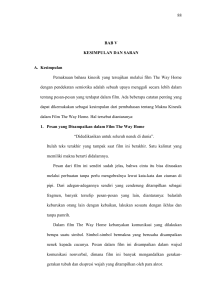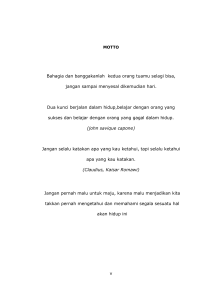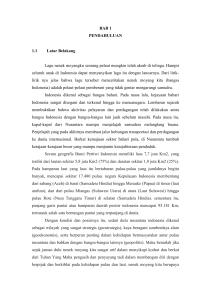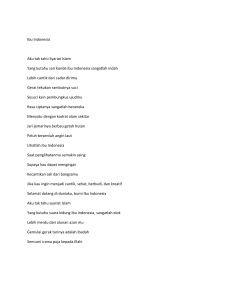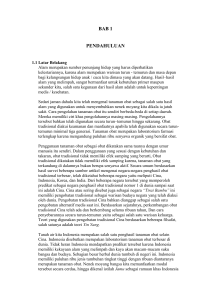CERPEN: POHON KERAMAT Ada sebatang pohon yang dianggap keramat di dusunku. Kami menamainya sebagai pohon pendengar. Hampir setiap hari ada orang yang datang kepadanya. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Ada juga di jam-jam subuh ketika kebanyakan orang terlelap. Karena terlalu banyak warga dusun yang datang, maka kunjungan ke pohon pendengar harus berdasar izin dari kepala dusun. Dia yang mengatur pertemuan antara warga dengan pohon keramat. Namun seiring banyaknya orang yang datang, kepala dusun memutuskan untuk menunjuk satu orang untuk mengurusnya. Pemilihannya tidak asal. Orang itu harus berasal dari garis keturunan dukun. Orang pintar. “Apa nenek pernah ke sana? Ke pohon keramat?” tanyaku sembari memetiki daun kangkung yang akan disantap saat makan siang nanti. Nenek tersenyum, membuat keriput di wajahnya makin kentara. “Untuk apa?” “Karena manusia tidak dapat dipercaya, bukan tempat menyimpan rahasia. Pohon itu tidak akan menceritakan rahasiamu pada siapapun. Aman,” jawabku. “Benarkah?” timpalnya. Begitu saja. Nenek tidak pernah menjelaskan alasan penolakannya untuk datang kepada pohon keramat. Setahuku, juga setahu orang-orang, Nenek adalah salah satu dari kelompok kecil yang tidak pernah muncul, mendatangkan dirinya ke hadapan pohon keramat. Seolah nenek dan golongannya tidak setuju pohon tersebut keramat. Bahwa pohon tersebut tidak ada bedanya dengan pohon-pohon lain. Beberapa desas-desus menyatakan, nenek pergi ke pohon lain. Ia sengaja tidak menceritakannya karena takut orang-orang mengetahui letak pohonnya sehingga dia tidak dapat mengunjungi pohon keramatnya kapan pun diinginkan. Beberapa menyatakan pikiran nenek agak terganggu. Karena sudah sewajarnya warga dusun pergi ke pohon keramat. Penolakan pohon keramat nampaknya tidak begitu saja diterima oleh warga dusun. Mereka memang tidak suka apa bila ada orang yang tidak sependapat dengan kebenaran mayoritas. Salah satu hal yang membuat nenek tetap aman adalah usia. Seandainya nenek masih muda, pasti beliau sudah dihakimi orang-orang desa, termasuk kepala dusun. “Melamun saja!” tegur nenek. “Aku tidak melamun. Aku memetik daun kangkung,” sergahku, malu. Kulanjutkan proses memetiki daun kangkung. Nenek memandangiku dari balik kacamata yang digunakannya. Seolah-olah memerhatikan apakah aku memetik daun kangkung dengan benar. Tapi aku tahu bukan itu. Ada alasan lain. Ia ingin mengajakku bicara. “Apa?” celetukku karena agak jengah dipelototi seperti itu. “Apa kau akan pergi ke pohon keramat?” tanyanya. Wah! Topik yang tidak kusangka akan muncul dari bibirnya. Biasanya nenek hanya memberikan jawaban sekenanya, ambigu, ngambang. Tapi hari ini dia yang menanyaiku. “Aku belum cukup umur,” dengusku. Hal itu harusnya sudah jelas. Mereka yang pergi ke pohon keramat minimal berumur dua puluh lima. Sementara aku masih belasan. “Kuharap mereka mengubah peraturan mengenai umur. Anak muda juga punya permasalahan, tidak hanya orang tua,” sambungku. “Benar!” sahut nenek sembari mengangguk-angguk. “Semua manusia memiliki permasalahan sesuai dengan level mereka.” “Jadi yang nenek maksud, kami, anak muda levelnya masih rendah sehingga tidak perlu datang ke pohon keramat?” tuntutku, tidak setuju. “Bukan hanya anak muda, orang tua sepertiku yang sudah hampir mati ini juga tidak perlu ke sana,” tegas nenek tajam. Aku balik menatap nenek. “Mungkin karena nenek tidak memiliki rahasia untuk....” “Oh! Aku jelas memiliki rahasia. Semua manusia memiiki rahasia. Hanya saja aku tidak perlu membagikannya kepada pohon yang dipuja-puja itu,” potong nenek. Aku diam. Mencoba menjejalkan penjelasan nenek. Tapi cara pikirku mulai mirip orang-orang yang suka menggunjingkan nenek. “Karena nenek punya pohon keramat lain yang tidak dipuja orang-orang,” konklusiku. Atau lebih tepatnya konklusi warga dusun. Nenek menggeleng mantap. “Kenapa harus menceritakan rahasiamu kepada sebatang pohon? Dia bahkan tidak akan memberimu solusi,” katanya. “Karena pohon tidak akan menceritakan rahasiamu pada siapapun,” jawabku, cepat. “Karena rahasia terlalu menyesakkan untuk disimpan sendiri.” “Mengapa kamu yakin rahasiamu tidak terbongkar gara-gara pohon?” “Karena dia tidak punya mulut. Dia bukan manusia. Pohon tidak dapat bicara!” ujarku, setengah membentak. Nenek aneh sekali mempertanyakan hal yang sudah jelas begitu. Membuat amarahku meletup saja. “Apa kau yakin, tidak akan ada yang mendengarkan rahasiamu kecuali pohon itu?” lanjut nenek, mengacuhkan amarah cucunya yang gampang tersulut. Aku membuka mulut, berusaha mengatakan sesuatu. Keraguan itu muncul. Aku tidak tahu jawabannya, aku tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. “Penjaga pohon keramat akan melakukan tugasnya dengan baik,” kataku, tanpa nada yang mantap. “Tentu orang itu mengatur agar satu orang dengan orang lainnya tidak datang secara bersamaan,” angguk nenek. Aku membenahi posisi dudukku. Meletakkan batang kangkung yang tengah kupetiki. Fokus pada obrolan. “Apa itu artinya....” aku menelan ludah. Tidak berani melanjutkan karena omonganku bisa menjadi penistaan. Jawabannya mendadak muncul. Tentunya ada alasan lain kepala dusun tidak menyerahkan jabatannya kepada orang lain. “Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau sudah bijak dengan tidak menyerukan pemikiranmu itu,” tawa nenek seolah mampu membaca pikiranku, seolah nenek adalah seorang dukun saja. “Pohon pengintai....” bisikku lambat-lambat. Nenek mengangguk. “Kurasa sekarang sudah saatnya bagiku untuk memberikan alasannya padamu. Bukan karena kamu bertanya untuk menghakimi, tapi aku memberikannya ketika aku merasa kau sudah siap. Ketika kau bertanya untuk memahami.” “Kurasa selama ini aku tidak menggunakan telingaku dengan baik,” sahutku, malu. “Kau lebih jago menggunakan mulutmu,” jawab nenek tanpa tedeng aling-aling. Mengalir begitu saja dari mulutnya. Nenek yang misterius, lemah dan sering kali menghabiskan waktunya untuk merajut, kini berubah menjadi sosok kharismatik di hadapanku. Sosok yang memiliki pemikiran luas dan mendalam, bagaikan samudera. Dia tidak mengajakku berenang ke sana, sebelum aku menjadi perenang yang baik. Selama ini dia menghalangiku karena kemampuanku belum baik, tapi hari ini nenek sudah mulai percaya padaku. Rasa bangga membuncah dari dalam diriku. Nenek mempercayaiku, cucunya. “Pohon keramat itu tidak ada. Setidaknya ketika aku anak-anak. Pohon itu menjadi buah bibir di antara warga dusun ketika aku menginjak remaja. Umurku baru dua belas ketika menikah dengan kakekmu. Saat itulah pohon itu menjadi keramat,” tutur nenek. “Menjadi keramat,” ulangku dalam bisikkan. “Orang tuaku tidak ada yang pergi ke sana, karena menurut mereka pohon tersebut biasa-biasa saja. Aku juga tahu sejarah sehingga tidak mudah terseret arus. “Jadi mengapa pohon itu bisa sangat dipuja sedemikian rupa?” “Konstruksi yang dilatarbelakangi oleh kekuasaan. Kau tahu mengapa pemimpin kita sangat langgeng kekuasaannya?” tanya nenek, beliau tengah memberikan lampu dalam ruangan pikiranku yang selama ini gelap. “Karena ia mengetahui segalanya berkat pohon itu,” jawabku, mulai bisa menyeimbangkan pemikiran dengan nenek. Tapi tetap saja ada yang mengganjal dalam pikiranku. “Orang-orang mempercayainya. Lebih banyak yang setuju daripada tidak. Sudah menjadi kebenaran bahwa pohon itu keramat.” “Meski kau tahu salah, apa kau akan tetap menyetujuinya sebagai kebenaran?” “Mereka tidak suka jika ada orang yang tidak berbisik pada pohon itu. Orang-orang membicarakan nenek dari belakang,” kataku. “Tentu saja orang-orang itu bergosip di belakang. Kalau sudah berani menyatakan langsung, posisi mereka tidak akan di belakang,” tawa nenek. “Biarpun aku setuju dengan nenek. Aku tetap akan ke sana karena aku takut orang-orang tidak benar-benar menerimaku, aku tidak suka ada gosip,” ujarku. “Oh, aku memang tidak memintamu buat setuju seratus persen denganku. Hidupmu, pilihanmu. Hanya saja aku yakin kau akan memilih hal-hal yang akan diucapkan ketika sudah berhadapan dengan pohon itu,” tegas nenek. “Tentu, aku akan berhati-hati,” gumamku. Di satu sisi aku ingin datang ke pohon itu, di sisi lain aku ingin menghindarinya. “Karena kau sudah tahu kalau rahasiamu tidak aman di sana,” angguk nenek. Aku memandangi daun-daun kangkung yang sudah kupetik. “Lalu di manakah kita harus meletakkan rahasia agar aman?” “Di kepalamu sendiri,” jawab nenek, cepat. “Tapi sangat berat untuk menyimpan semuanya seorang diri,” sergahku. “Sudah kukatakan, rahasia terlalu menyesakkan untuk disimpan sendiri.” “Kau bisa menemukan orang yang dapat kau percaya. Orang yang bisa menjaga rahasiamu. Hanya saja bila orang menjaga rahasiamu, kau juga harus menjaga rahasianya sebagai pengikat,” nasehat nenek. “Kurasa akan sulit.” “Benar-benar sulit,” tandas nenek. “Kau harus mencari orang yang dapat memahamimu, demikian pula kau mengenalnya dengan baik. Ini bukan perkara mudah.” “Bagaimana kalau aku berbisik pada pohon lain saja? Bukankah kita sampai pada suatu persetujuan bahwa pohon manapun hanya diam saja ketika kita bicara padanya?” usulku. “Lalu mengapa harus ke pohon? Sama saja bicara pada kangkung, pada mangkok, pada lampu. Mereka tetap diam, tidak memberi jalan keluar apa pun. Kemudian apa bedanya dengan menjaga pikiranmu tetap berada di kepala?” “Karena aku berharap dapat mengutarakannya.” “Kau ingin mulutmu bicara tapi tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada solusi untuk permasalahanmu setelah mulutmu bicara.” Nenek menyentuh tanganku. “Intinya, jika tidak ingin diketahui orang lain, simpan untuk dirimu sendiri.” “Apakah itu yang selama ini nenek lakukan?” Nenek menggeleng. “Tidak. Aku tidak menyimpan semua rahasiaku, buktinya hari ini aku membuka mulutku padamu karena aku selalu merasa berdialog lebih menyenangkan daripada bercerita pada pohon. Mirip orang sakit jiwa!” Aku tersenyum masam. Aku sakit jiwa. Orang-orang di dusunku sakit jiwa. Mungkin yang waras hanya nenek dengan golongannya juga si kepala dusun itu sendiri yang melakukan konstruksi akan pohon keramat. Kepala dusun yang maha kuasa, membentuk sebuah kebenaran untuk kepentingannya. Tapi bukankah kebanyakan pemegang kekuasaan memang demikian? Peraturan di buat untuk melanggengkan kekuasaan, berlandaskan kepentingan mereka, bukan karena warganya. Sementara warga, menganggap kebenaran itu sebagai sesuai yang luhur. Bebas nilai dan hanya berisi kebaikan semata. Membutakan. Menulikan. Membuat pemikiran menjadi tumpul. Tidak ubahnya denganku yang lebih memilih mengikuti arus daripada melawannya. “Nenek kau sungguh berani, kau orang yang hebat,” sahutku. “Kau juga pemberani, aku sedang menyirami bibit keberanian itu dari dalam dirimu,” ujarnya sembari mengusap-usap telapak tanganku. Aku tertawa. “Bagaimana kau melakukannya?” “Dengan membuatmu berpikir. Setelah kau memiliki pijakan yang kuat, kau akan lebih berani karena kau bisa menjawab pertanyaan yang bertujuan buat menyerangmu.” “Apa maksudmu aku sebagai anak muda harus mengadakan revolusi?” tanyaku, ragu. “Lakukan bila kau memang memiliki dorongan dari dalam dirimu. Bukan karena aku. Saat itulah kau siap. Hanya saja sebenarnya tidak bersedia mengikuti arus sudah merupakan resistensi. Wacana revolusi tentunya akan lebih butuh perjuangan.” Aku mengangguk, pilihanku sudah berubah. “Aku tidak akan datang ke pohon keramat hanya karena takut dipergunjingkan orang-orang. Aku tidak akan ke sana karena aku tahu itu bukanlah hal yang bijak.” “Tepat!” seru nenek sembari memberikan kedua jempolnya padaku. “Jadi apa yang harus kulakukan untuk memulainya?” Kuharap nenek dapat memberiku lebih banyak petunjuk. “Sekarang? Kau harus menyelesaikan kangkungmu itu kemudian memasaknya. Aku sudah mulai lapar…” “… Kau juga akan butuh banyak tenaga jika ingin melakukan resistensi. Menghadapi orang-orang yang tidak mau diajak berpikir, hanya menerima kebenaran tanpa mempertanyakannya, itu melelahkan.” Tamat