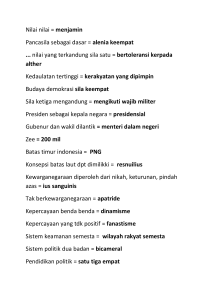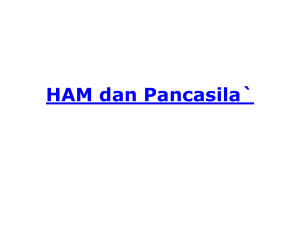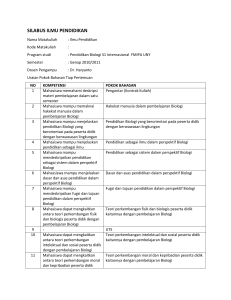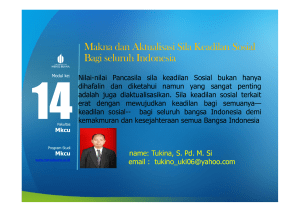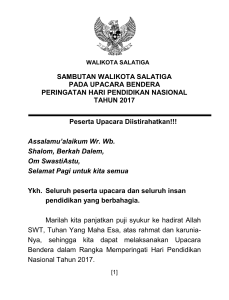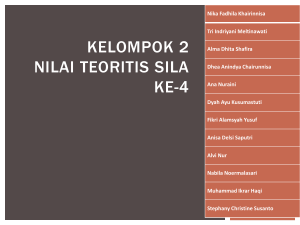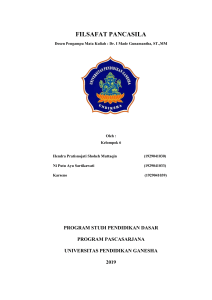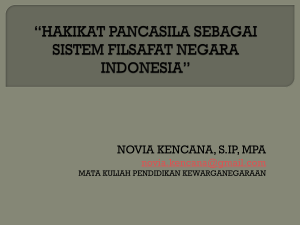Uploaded by
common.user41345
Filsafat Pancasila: Analisis Filsafat Pendidikan Indonesia
advertisement

FILSAFAT PANCASILA Dosen Pengampu Mata Kuliah : Dr. I Made Gunamantha, ST.,MM Oleh : Kelompok 6 I Wayan Purwadana (1929041017) Hendra Pratisnojati Shoheh Muttaqin (1929041030) Ni Putu Ayu Sartikawati (1929041033) Ketut Sri Puji Wahyuni (1929041034) Karseno (1929041039) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 2019 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pancasila sebagai filsafat pendidikan merupakan suatu pandangan yang dijadikan sebagai dasar atau acuan di dalam menyelenggarakan pendidikan serta mampu mengkritisi setiap pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang didalamnya mengandung ciri khas dan karakter dari bangsa Indonesia sehingga di dalam melaksanakan pendidikan yang meliputi tri pusat pendidikan yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah harus disesuaikan dengan nilai yang terkandung di dalam pancasila yang pada akhirnya akan mencetak cendikiawan yang berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Rusaknya moral yang terjadi di Indonesia sebagian besar telah terbukti karena adanya pendidikan baik di keluarga, masyarakat maupun sekolah yang kurang sesuai dengan kandungan yang terdapat dalam nilainilai pancasila. Pendidikan karakter yang kurang diperhatikan oleh setiap pendidik menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya moral tersebut dan hal itu menyebabkan ketidak tercapaian tujuan pendidikan Indonesia yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia harus cerdas, dalam hal ini tidak hanya cerdas dalam pengetahuan ataupun wawasannya tetapi juga cerdas akan akhlak maupun moral dari bangsa Indonesia. Salah satu contoh pendidikan di Indonesia yang terjadi pada lingkungan sekolahan lebih mendominasi transfer of knowledge yaitu menstransferkan pengetahuan kepada peserta didik. Hal ini akan memberi dampak pada aktualisasi peserta didik yang dikuasai oleh kekuasaan seorang pendidik, jika hanya yang diberikan adalah pengetahuan maka karakter peserta didik tidak akan diciptakan dari kondisi seperti ini seperti percaya diri, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya yang justru menjadi kunci utama dari pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan pendidikan Indonesia, harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang nantinya diharapkan dapat dimaknai dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia dalam mendukung terselenggaranya pendidikan. Selain itu perlu adanya keseimbangan pendidikan dari tri pusat pendidikan yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia ? 2. Bagaimana Pancasila sebagai filsafat pendidikan ? 3. Bagaimana aspek ontologis, epitemologis dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Pancasila? 4. Bagaimana implikasi pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia dalam praktik pendidikan di Sekolah Dasar ? 5. Bagaimana konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui maksud pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia 2. Untuk mengetahui Pancasila sebagai filsafat pendidikan 3. Untuk mengetahui aspek ontologis, epitemologis dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Pancasila 4. Untuk mengetahui Implikasi pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia dalam praktik pendidikan di sekolah dasar. 5. Untuk mengetahui konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan. BAB II PEMBAHASAN A. Pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia tidak saja sebagai dasar negara RI, tetapi juga alat untuk mempersatukan bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum positif dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia ( Aziz, 1984:70). Filsafat adalah proses berfikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu. Sementara filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang kependidikan berdasarkan filsafat. Filsafat pendidikan juga dapat dimaknai sebaga kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat umum dan menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis (Jalaludin, 2007:19). Bruner dan Burns dalam bukunya Problem in Education and Philosophy mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah merupakan tujuan filsafat, yaitu untuk membimbing kearah kebijaksanaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan realisasi dari ide-ide filsafat. Pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia merupakan suatu dasar yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang sesuai pada nilai-nilai luhur dan dapat dijadikan dasar untuk mengkritisi permasalahan yang terjadi di praktik pendidikan di Indonesia. Suatu pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pendidikan berperan penting dalam menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa. Maka dari itu, pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sistem pengajaran nasional. Bagi bangsa Indonesia, keyakinan atau pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Karenanya sistem pendidikan nasional harus dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila itu sendiri. Sistem pendidikan nasional dan sistem filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Sejak pendidikan itu ada di Indonesia, praktiknya sudah memperhatikan pada nilai-nilai yang ada di dalam pancasila yang isinya mencakup: 1) ketuhanan Yang Maha Esa, 2) kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) persatuan Indonesia, 4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5) keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dari kandungan tersebut akan berdampak pada beberapa kinerja dari proses pendidikan seperti metode pembelajaran yang akan dilaksanakan, pendekatan dalam proses pendidikan dan materi yang akan disampaikan oleh siswa, hal itu tidak akan terlepas dari nilai-nilai pancasila yang harus termuat dan diselipkan dari setiap pendidikan yang diberikan agar sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tidak hanya mencerdaskan bangsanya namun juga mencerdaskan moral agar berbudi yang sesuai dengan pancasila. Penyesuaian antara pendidikan apa yang akan diberikan dengan kandungan dari pancasila itu sendiri membuat adanya kesesuaian dengan tujuan dari bangsa Indonesia. Tujuan khusus dari pendidikan Indonesia yaitu mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik dari aspek secara keseluruhan baik kognitif, afektif dan psikomotorik, sedangkan kita tahu bahwa setiap manusia itu unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda dan untuk membentuk potensi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia maka harus benar-benar dilandaskan pada pancasila yang telah memberikan sarana sebagai acuan dari segala kehidupan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. Maka dari itu, sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, pelajaran Pancasila masih diberikan, agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, Hal itu membuktikan bahwa pancasila sangat berdampak besar bagi terbentuknya generasi-generasi unggul Indonesia yang luas akan pengetahuannya dan memiliki moral yang baik sehingga akan mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mampu untuk memfiltrasi pengaruh negatiif dari perkembangan zaman yang saat ini telah dibawa oleh budaya barat, tetapi dengan adanya pendidikan yang berlandaskan pancasila maka generasi Indonesia akan mampu untuk membentuk benteng dalam dirinya untuk tetap bernilai pancasila dan tidak akan terpengaruh begitu saja dari pengaruh negatif dari luar yang membuat sesuatu yang dapat menghilangkan cerminan dari bangsa indonesia itu pudar. B. Alasan Pancasila dijadikan filsafat pendidikan Indonesia. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan. Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undangundang Dasar 1945 yang didalamnya diatur bahwa pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Aristoteles mengatakan, bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara (Rapar; 1988). Demikian juga dengan Indonesia, pendidikan selain sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan,sosial budaya juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya. Suatu bangsa menjadi kuat serta menguasai bangsa-bangsa lainnya dengan sistem pendidikannya yang kuat demikian juga sebaliknya sistem pendidikan yang lemah akan menjadikan suatu bangsa tidak berdaya (Tadjab; 1994). Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, bahwa Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari - hari. Karenanya sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari dan mencerminkan identitas Pancasila. Cita dan karsa bangsa Indonesia diusahakan secara melembaga dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup dan folosofi tertentu, inilah dasar pikiran mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional dan sistem filsafat pendidikan Pancasila adalah sub sistem dari sistem negara Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek rohaniah atau spiritual sistem pendidikan nasional, tiada sistem pendidikan nasional tanpa filsafat pendidikan. Sistem pendidikan yang dialami sekarang merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia yang merupakan fungsi utama dan dari segi materinya digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa (Dardodiharjo, 1988.17). Pancasila merupakan dasar Negara yang menjadi ciri khas dan dasar Negara bangsa Indonesia dan dapat membedakan suatu pandangan dari Negara lain. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun pemikiran mengenai praktik pendidikan yang ada di Indonesia dan telah disesuaikan dengan nilai yang harus dibangun kepada setiap rakyat yang bertempat tinggal di Indonesia. Di dalam pancasila terdapat isi yang harus dimaknai oleh peserta didik agar sejalan dengan pendidikan yang diharapkan dan berbasis Pancasila, untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya diperlukan pemikiran yang sungguh- sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai pancasila itu dapat dilaksanakan, dalam hal hal ini pendidikan tentunya yang berperan utama. Pancasila sebagai pandangan bangsa Indonesia yang menjiwai dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dengan perkataan lain bila dihubungkan pancasila dengan kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan nasional itu, dasarnya adalah Pancasila. Hal di atas merupakan alasan mengapa pancasila dijadikan sebagai filsafat pendidikan Indonesia karena sebenarnya bagi Indonesia warga Negara yang pintar tidak cukup untuk menjadikan manusia seutuhnya namun Indonesia ingin mewujudkan bangsa Indonesia yang pintar dan bermoral dengan didasarkan pada aspek nilainilai pancasila, dapat diuraikan dari setiap butir pancasila bahwa setiap butirnya memiliki tujuan yang sesuai sebagai dasar pelaksanaan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas secara kognitif maupun moralnya, uraian nya sebagi berikut : a) Ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila yang pertama pendidikan memilih pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu mengutamakan hal-hal yang dapat memperkuat nilai-nilai keimanan bagi peserta didik agar selalu taqwa dan beriman sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, selain itu agar peserta didik mampu memaknai suatu pendidikan dengan didasarkan pada kewajiban mereka sebagai makhluk Tuhan untuk selalu menuntut ilmu dan dengan adanya pendidikan yang didasarkan pada sila ini maka output yang akan dihasilkan yaitu terciptanya insan atau peserta didik yang berakhlak mulia. b) Kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam sila kedua pendidikan menjadikan pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu membentuk setiap peserta didik yang mampu untuk memberikan perlakuan sebagaimana layaknya manusia dan nantinya seseorang yang telah mendapatkan pendidikan itu dapat menghargai hak manusia yang sesuai dengan makna dari sila ini c) Persatuan Indonesia, dalam sila ketiga pendidikan menjadikan pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu untuk menjadikan peserta didiknya dapat bersatu dengan peserta didik lainnya, hal ani menunjukkan bahwa ketika terjadinya proses pendidikan maka ada saat mereka harus belajar dari lingkungan sosialnya, dari lingkungan social yang ada dan hal ini memungkinkan setiap orang untuk bersatu dan meminimalisir adanya diskrimantif antar perbedaan yang menjadi corak dari bangsa Indonesia, sehingga terbuktilah dengan adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika yang dapat dimaknai bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman sehingga di dalam proses pendidikan harus ada proses saling bertukar pengetahuan dan sebagainya yang menungkinkan setiap orang dapat menjalin kebersatuan untuk memenuhi suatu kebutuhan pendidikan. d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam sila keempat pendidikan menjadikan pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengharuskan suatu pendidikan dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih demokratis,aktif, dan kritis di dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan usaha dari dalam maupun dari luar, maka biasannya pendidikan di 3 pusat lingkungan telah memberikan berbagai usaha agar seseorang dapat lebih kritis lagi seperti dimasyarakat bahwa terdapat organisasi yang memungkinkan partisipasi oleh setiap orang untuk mengatasi hal-hal yang bersangkutan dengan program atau kinerja dari setiap organisasi tersebut. e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila ke lima pendidikan menjadikan pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengungkapkan secara abstrak bahwa suatu pendidikan harus mampu menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan sosial bagi lingkungan yang ditempati nya dalam arti bahwa ketika seseorang sedang berbaur dengan temannya maka orang itu tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lainnya, sehingga biasanya hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan sejak kecil bahwa seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga jika memilih teman harus adil dan tidak boleh memandang pangkat maupun derajatnya. C. Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Filsafat Pendidikan Pancasila 1. Aspek Ontologis Filsafat Pendidikan Pancasila Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Ontos berarti yang berada (being) dan Logos berarti pikiran (logic). Jadi, Ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada/berada atau dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang “yang ada” atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Sedangkan, menurut istilah adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Disisi lain, ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Secara ontologis, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas lima sila memiliki satu kesatuan dasar ontologis maksudnya setiap sila bukan merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri. Manusia merupakan pendukung pokok dari sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai filsafat, mempunyai abstrak umum dan universal. Yang dimaksud isi yang abstrak disini bukannya pancasila sebagai filsfat yang secara operasionalkan telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila. a. Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa Sila pertama menjiwai sila-sila yang lainnya. Di dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dengan sila pertama ini kita diharapkan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk menjadikan manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah. Karena itu, di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat ditanamkan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila. b. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab Manusia yang ada dimuka bumi ini mempunyai harkat dan martabat yang sama, yang diperlikan sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan fitrahnya sebagai hamba Allah (Darmodiharjo, 1988: 40). Pendidikan tidak membedakan usia, agama dan tingkat sosial budaya dalam menuntut ilmu. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu, mendapat perlakuan yang sama, kecuali tingkat ketaqwaan seseorang. Pendidikan yang harus dijiwai Pancasila sehingga akan melahirkan masyarakat yang susila, bertanggung jawab, adil dan makmur baik spiritual maupun material. c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia Sila ketiga ini tidak membatasi golongan dalam belajar. Ini berarti bahwa semua golongan dapat menerima pendidikan, baik golongan rendah maupun golongan tinggi, tergantung kemampuannya untuk berpikir. d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan Sila keempat ini sering dikaitkan dengan kehidupan demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan ditangan rakyat. Bila dilihat dari dunia pendidikan, maka hal ini sangat relevan, karena menghargai orang lain demi kemajuan. Disamping itu, juga sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Jadi dalam menyusun pendidikan, diperlukan ide-ide dari orang lain demi kemajuan pendidikan. e. Sila kelima, Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam sistem pendidikan nsional, maksud adil dalam arti yang luas mencakup seluruh aspek pendidikan yang ada. Adil disini adalah adil dalam melaksanakan penddikan: antara ilmu agama dan umum itu seimbang, serta pendidikan tidak boleh membeda-bedaka siswa. 2. Aspek Epistemologis Filsafat Pendidikan Pancasila Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian epistimologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenahi pengetahuan. Epistimologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar (teori of knowledges). Epistimologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal muasal, sumber, metode, struktur dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Secara epistemologis Pancasila sebagai filsafat yaitu sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Sedangkan susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan yaitu Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Dengan filsafat kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan dan berwarga Negara. Untuk itu Indonesia telah menemukan filsafat Pancasila. a. Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa Pancasila lahir tidak secara mendadak, tetapi melalui proses panjang. Pancasila digali dari bumi Indonesia yang merupakan dasar Negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan arah untuk mencapai cita-cita dan perjanjian luhur rakyat Indonesia (Widjaya, 1985: 176-177). Dengan demikian, pancasila bersumber dari bangsa Indonesia yang prosesnya melalui perjuangan rakyat. Bila kita hubungkan dengan Pancasila maka dapat kita ketahui bahwa apakah ilmu itu didapat melalui rasio atau dating dari Tuhan. b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Manusia itu mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Pancasila adalah ilmu yang diperoleh melalui perjuangan yang sesuai dengan logika. Dengan mempunyai ilmu moral, diharapkan tidak lagi kekerasan dan kesewenangwenangan manusia tehadap yang lain. c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia Proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerjasama atau produk hubungan dengan lingkungannya. Potensi dasar dengan faktor kondisi lingkungan yang memadai akan membentuk pengetahuan. d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Himat Kebijaksanan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan Manusia diciptaka Tuhan sebagai pemimpin dimuka bumi ini untuk memakmurkan umat manusia. Seorang pemimpin mempunyai syarat untuk memimpin dengan bijaksana. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan memang mempunyai peranan sangat besar, tapi tidak menutup kemungkinan peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk manusi Indonesia seutuhnya. Jadi dalam hal ini diperlukan suatu ilmu keguruan untuk mencapai guru yang ideal, guru yang kompeten. Setiap manusia bebas mengeluarkan pendapat dengan melalui lembaga pendidikan. Setiap ada permasalahan diselesaikan dengan jalan musyawarah. e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ilmu pengetahuan sebagai perbendaharaan dan prestasi individu serta sebagai karya budaya umat manusia merupakan martabat kepribadian manusia. Dalam arti luas, adil diatas dimaksudkan seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal ini didapatkan melalui pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Dalam sistem pendidikan nasional yang intinya mempunyai tujuan tertentu. Di bidang sosial, dapat dilihat pada suatu badan yang mengkoordinir dalam hal mengentaskan kemiskinan, dimana hal-hal ini sesuai dengan butirbutir Pancasila. 3. Aspek Aksiologis Filsafat Pendidikan Pancasila Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu: axios yang berarti nilai. Sedangkan logos berarti teori/ ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksioloagi adalah ilmu yang membecirakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijalan yang baik pula karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan dijalan yang tidak benar. Dalam filsafat Pancasila, terdapat tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. 1. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 2. Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. 3. Nilai praktis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbansa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Aksiologi menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber dan hakikat nilai secara kesemestaan. Aksiologi Pancasila pada hakikatnya sejiwa dengan ontologi dan epistemologinya. Pokok-pokok aksiologi itu dapat disarikan sebagai berikut: o Tuhan yang Maha Esa sebagai mahasumber nilai, pencipta alam semesta dan segala isi beserta antarhubungannya, termasuk hukum alam. Nilai dan hukum moral mengikat manusia secara psikologis-spiritual: akal dan budi nurani, obyektif mutlak menurut ruang dan waktu secara universal. Hukum alam dan hukum moral merupakan pengendalian semesta dan kemanusiaan yang menjamin multieksistensi demi keharmonisan dan kelestarian hidup. o Subyek manusia dapat membedakan hakikat mahasumber dan sumber nilai dalam perwujudan Tuhan yang mahaesa, pencipta alam semesta, asal dan tujuan hidup manusia (sangkan paraning dumadi, secara individual maupun sosial). o Nilai-nilai dalam kesadaran manusia dan dalam realitas alam semesta yang meliputi: Tuhan yang mahaesa dengan perwujudan nilai agama yang diwahyukan-Nya, alam semesta dengan berbagai unsur yang menjamin kehidupan setiap makhluk dalam antarhubungan yang harmonis, subyek manusia yang bernilai bagi dirinya sendiri (kesehatan, kebahagiaan, etc.) beserta aneka kewajibannya. Cinta kepada keluarga dan sesama adalah kebahagiaan sosial dan psikologis yang tak ternilai. Demikian pula dengan ilmu, pengetahuan, sosio-budaya umat manusia yang membentuk sistem nilai dalam peradaban manusia menurut tempat dan zamannya. o Manusia dengan potensi martabatnya menduduki fungsi ganda dalam hubungan dengan berbagai nilai: manusia sebagai pengamal nilai atau ‘konsumen’ nilai yang bertanggung jawab atas norma-norma penggunaannya dalam kehidupan bersama sesamanya, manusia sebagai pencipta nilai dengan karya dan prestasi individual maupun sosial (ia adalah subyek budaya). “Man created everything from something to be something else, God created everything from nothing to be everything.” Dalam keterbatasannya, manusia adalah prokreator bersama Tuhan. Martabat kepribadian manusia secara potensial-integritas bertumbuhkembang dari hakikat manusia sebagai makhluk individu-sosial-moral: berhikmat kebijaksanaan, tulus dan rendah hati, cinta keadilan dan kebenaran, karya dan darma bakti, amal kebajikan bagi sesama. 1) Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa Percaya pada Tuhan merupakan hal yang paling utama dalam ajaran Agama. Dilihat dari segi pendidikan, sejak dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi, diberikan pelajaran agama dalam hal ini merupakan subsistem dari sistem pendidikan. 2) Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dalam kehidupan umat beragama, setiap manusia tidak membedakan keturunan, ras, dan kedudukan: dimata Tuhan semua sama, kecuali ketaqwaan seseorang. Inilah sebagian kecil contoh nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan umat beragama. 3) Sila ketiga, Persatuan Indonesia Agama mengajarkan supaya bersatu dalam mencapai tujuan yang dicitacitakan. Mengajarkan untuk taat pada pemimpin. Di dalam pendidikan, jika kita ingin berhasil, kita harus berkorban demi tercapainya tujuan yang didambakan. Yang jelas warga Negara punya tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengsisi kemerdekaan ini. Bercerai berai kita runtuh, bersatu kita teguh. 4) Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan Sejak zaman kerajaan, Indonesia sudah ada sikap gotong royong dan musyawarah. Setiap hasil musyawarah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan. 5) Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Adil berarti seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam segi pendidikan, adil itu seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama di mana ilmu agama adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional. Mengembangkan perbuatan yang luhur, menghormati hak orang lain, suka member pertolongan, bersikap hemat, suka bekerja, menghargai hasil karya orang lain dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Dengan berdasarkan butir-butir dari sila kelima ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai-nilai yang ada pada sila kelima ini telah ada sebelum Islam datang. Nilai-nilai ini sudah menjadi darah daging dan telah diamalkan di Indonesia. Filsafat Pendidikan Pancasila adalah tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar Negara Pancasila sebagai Sistem Kenegaraan Republik Indonesia. Kesadaran memiliki dan mewarisi sistem kenegaraan Pancasila adalah dasar pengamalan dan pelestariannya, sedangkan jaminan utamanya ialah subjek manusia Indonesia seutuhnya. Subjek manusia Indonesia seutuhnya ini terbina melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila D. Implikasi pancasila sebagai filsafat pendidikan indonesia dalam praktik pendidikan di Sekolah Dasar Implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan nasional, yakni tercapainya dasar dan tujuan Pancasila. Implikasi pendidikan lainnya yang berdasarkan adalah dalam rangka pada nilai-nilai menentukan ideal program kurikulum, dan dalam kurikulum tujuan pendidikan harus tergambar dengan jelas. Program tersebut mencerminkan arah dan tujuan yang hendak dicapi dalam proses pendidikan. Dalam kurikulum tidak saja dijabarkan serangkaian ilmu pengetahuan yang harus diajarkan oleh guru kepada siswa, akan tetapi juga segala kegiatan yang bersifat pedagogis (mendidik), seperti yang tertuang dalam Pancasila. Filsafat pancasila telah menjadikan dasar terselenggarannya praktik pendidikan dan sebagai sarana mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan harus mempunyai dasar untuk menyusun program dan terlaksannya suatu pendidikan yang berkualitas dan sesuai pada dasar Indonesia itu sendiri yaitu pancasila. Maka dari itu implementasi pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia : 1) Sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa maka suatu Misalnya : sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran guru harusnya mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Di dalam proses pembelajaran guru menyelipkan nilai-nilai ketuhanan pada setiap isi materi seperti halnya siswa di ajarkan untuk selalu bersyukur terhadap ciptaan tuhan,contoh : alam, makhluk hidup, adanya system pernapasan dan sebagainya. Membiasakan adanya jam untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. 2) Sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab maka dapat implikasi di dalam kelas adalah : Guru memperlakukan siswa dengan baik tanpa menggunakan kekerasan baik secara lisan maupun perbuatan. Guru memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Guru memahami potensi yang ada pada setiap peserta didik. 3) Sesuai dengan sila ke tiga yaitu persatuan Indonesia : guru mampu menciptakan situasi yang menimbulkan kerjasama didalam belajar, antara anak dengan anak, antara anak dengan guru, begitu pula antara sesama guru (diskusi, presentasi dan pengajaran pola kolabarasi) dengan diadakannya upacara bendera setiap hari senin maka dapat mempersatukan peserta didik. Mengadakan program ekstrakurikuler, pramuka, calss meeting, kerja bakti dan sebagainya yang bertujuan untuk mempersatukan peserta didik satu dengan lainnya. 4) Sesuai dengan sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan : Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dalam setiap proses pembelajaran. Adanya pemilihan pengurus kelas dengan cara musyawarah dan voting. Guru mampu memberikan solusi terhadapan kesulitan belajar siswa baik secara materi maupun metode yang digunakan di dalam kelas. 5) Sesuai dengan sila ke lima yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila itu Contohnya : Guru tidak membeda bedakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya dalam hal pemberian sangsi, materi dan bimbangan saat proses pembelajaran. Dalam penerimaan siswa baru, sekolah tidak memprioritaskan uang sumbangan yang lebih besar. Seorang siswa tidak memilih milih teman, ia mampu berteman dengan siapa saja dan berlaku adil kepada semua temannya. E. Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan. Ki Hadjar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu Tri Pusat Pendidikan: (1) pendidikan keluarga; (2) pendidikan dalam alam perguruan; dan (3) pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Ki Hadjar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini, yaitu Taman Indria (balita). Konsep belajar ini adalah Tri No, yaitu nonton, niteni dan nirokke. Nonton (cognitive), nonton di sini adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Niteni (affective) adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca indera, dan nirokke (psychomotoric) yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak (Dwiarso, 2010: 1). Ketika anak didik sudah menginjak pada pendidikan Taman Muda (Sekolah Dasar), kemudian Taman Dewasa dan seterusnya maka konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara adalah Ngerti, Ngroso lan Nglakoni. Model pendidikan ini dimaksudkan supaya anak tidak hanya dididik intelektualnya saja (cognitive), istilah Ki Hadjar Dewantara 'ngerti', melainkan harus ada keseimbangan dengan ngroso (affective) serta nglakoni (psychomotoric). Dengan demikian diharapkan setelah anak menjalani proses belajar mengajar dapat mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian akhir dari hasil pendidikan, menurut Ki Hadjar Dewantara, adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral Taman Siswa, yaitu mampu melaksanakan Tri Pantangan yang meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan dan tidak melanggar kesusilaan (Ki Suratman, 1987 : 13). 1) Konsepsi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Progresivisme Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Konsep Ki Hadjar Dewantara pada sistem among mengatakan bahwa sistem among yang berjiwa kekeluargaan bersendikan 2 dasar, yaitu: (1) kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepatcepatnya dan sebaik-baiknya; (2) kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Oleh karena itu antara Ki Hadjar Dewantara dengan filsafat progresivisme sama-sama menentang pendidikan yang bercorak otoriter, karena hal itu akan menyebabkan kesulitan dalam pencapaian tujuan pendidikan.Sistem among melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdekanya, mematikan kreativitasnya .Konsep jiwa merdeka ini selaras dengan filsafat progresivisme terhadap kebebasan untuk berpikir bagi anak didik, karena merupakan motor penggerak dalam usahanya untuk mengalami kemajuan secara progresif. Antara filsafat Ki Hajar dengan progresivisme terdapat perbedaan, jika dalam progresivisme ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan adalah ilmu hayat, antropologi, psikologi dan ilmu alam, sedangkan dalam konsep Ki Hadjar Dewantara di samping ilmu yang umum, kesenian merupakan bagian yang penting dalam kurikulum pendidikan. Bila dipandang dari progresivisme maka pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang pengetahuan hanya sebagian yang memiliki kesesuaian, karena progresivisme lebih menekankan pada pandangan pragmatisme yang bersifat empirik. Menurut pragmatisme, proses mengetahui adalah fakta yang ditangkap oleh pengalaman yaitu pancaindera. Sedangkan, pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang pengetahuan lebih lengkap karena pengetahuan itu adalah hasil cipta, rasa dan karsa. Pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang belajar nampak pada konsep mengenai Tri Pusat Pendidikan, bahwa anak didik tidak semata-mata hanya belajar di sekolah tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat (dalam alam pemuda). Pendidikan alam keluarga akan mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin yang meliputi jasmani dan rohani. Di dalam alam keluarga orangtua berperan sebagai guru (pemimpin laku adab), sebagai pengajar (pemimpin kecerdasan serta pemberi ilmu pengetahuan) dan menjadi contoh laku sosial. Selanjutnya dalam alam perguruan, institusi ini berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran (perkembangan intelektual) serta memberikan ilmu pengetahuan. Menurut Ki Hadjar Dewantara, memaparkan agar pendidikan alam perguruan tidak hanya mementingkan intelek sehingga bersifat tak berjiwa, yang akan berpengaruh kuat terhadap tumbuhnya egoisme dan materialism, sehingga pendidikan intelektual harus disesuaikan dengan kodrat alam dan pendidikan keluarga. Kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru dengan anak atau pemuda, bersatu paham, misal dalam bidang agama, bidang politik, dalam kebangsaan, sehingga sistem Tri Pusat Pendidikan itu akan tercapai. Terwujudnya Tri Pusat Pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa ini yang berkarakter Ing Ngarsa Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karsa dan Tut Wuri Handayani. Para pemimpin yang diidealkan Ki Hadjar Dewantara ini di masa depan akan menghasilkan pemimpin yang tangguh karena merupakan pemimpin yang disiplin terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakatnya. Pemimpin berkarakter Ing Ngarsa Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karsa dan Tut Wuri Handayani tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, tidak akan melakukan manipulasi keuangan atau korupsi, dan tidak akan melanggar kesusilaan. Bila pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang belajar dibandingkan dengan pandangan progresivisme maka tidak jauh berbeda. Hal ini karena salah satu dasar yang digunakan dalam sistem among, yaitu kemerdekaan, secara paedagogis merupakan syarat untuk membantu perkembangan segala potensi anak didik tanpa tekanan dan hambatan. Anak didik dengan bawaan kodratnya diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi. Jadi pendidik hanya melakukan Tut Wuri Handayani, kecuali masalahmasalah yang dihadapi anak didik tersebut membahayakan dirinya sendiri, baru pendidik mengambil alih tindakan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. 2) Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Esensialisme Esensialisme mempunyai tinjauan mengenai kebudayaan dan pendidikan yang berbeda dengan progresivisme, jika progresivisme menganggap bahwa banyak hal itu mempunyai sifat yang serba fleksibel dan nilai-nilai itu berubah dan berkembang, maka esensialisme menganggap bahwa dasar pijak semacam ini kurang tepat. Dalam pendidikan, fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, pelaksanaan yang kurang stabil dan tidak menentu (Barnadib, 1982: 38). Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru (penyerahan kultur), tidak hanya berupa “pemeliharaan” akan tetapi juga “memajukan” serta dengan maksud “memperkembangkan” kebudayaan, menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan (Dewantara, 2011: 344). Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa kesenian yang dipakai sebagai alat pendidikan dalam Taman Siswa tetap bermaksud mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak ke arah keindahan pada khususnya, namun keindahan di dalam rangkai-annya dengan keluhuran dan kehalusan sehingga layak bagi hidup manusia yang beradab dan berbudaya. Jadi ada perkembangan jiwa anak “dari natur ke kultur” (Dewantara, 2011: 353). Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dibandingkan dengan filsafat pendidikan esensialisme sangat mirip, karena esensialisme berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Kebudayaan yang diwariskan merupakan kebudayaan yang telah teruji oleh segala jaman, kondisi dan sejarah (Noor Syam, 1983: 260). Nilai-nilai kebudayaan bukanlah nilai-nilai yang statis tetapi juga mengalami kemajuan. Ki Hadjar Dewantara mengatakan hendaknya usaha kemajuan ditempuh melalui petunjuk “Trikon”, yaitu: kontinyu dengan alam masyarakat Indonesia sendiri. Artinya, secara kontinyu kebudayaan harus diestafetkan atau diberikan kepada generasi penerus secara terus-menerus. Kemudian konvergen dengan budaya luar. Artinya, penerima nilai-nilai budaya dari luar dengan selektif dan adaptif dan akhirnya bersatu dengan alam universal, dalam persatuan yang konsentris yaitu bersatu namun tetap mempunyai kepribadian sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang maju tetapi tetap berkepribadian Indonesia (Dewantara, 1994: 371). Landasan berpikir esensialisme mengatakan bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang pada sendirinya sebagai substansi spiritual jiwa membina dan menciptakan diri sendiri (Barnadib, 1982: 55). Tinjauan filsafat pendidikan esensialisme tentang pandangan Ki Hadjar Dewantara mengenai pengetahuan dan belajar dapat dikatakan sebagai asosianisme, mengatakan bahwa gagasan atau isi jiwa itu terbentuk dari asosiasi unsur-unsur yang berupa kesan-kesan yang berasal dari pengamatan. Kesan-kesan tersebut disebut tanggapan yang dapat diumpamakan sebagai atom-atom jiwa (Barnadib, 1982: 49), Jadi pandangan Ki Hadjar Dewantara dengan esensialisme tentang belajar tidak bertentangan karena keduanya mengatakan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan digunakan panca indera kemudian diolah oleh akal sehingga gambaran jiwa (batin) terbentuk. Sumbangan Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Bagi Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara merintis/menggali kepribadian asli Indonesia. Kepribadian yang mengandung arti harkat diri atau kemanusiaan. Beliau merintis pendidikan nasional agar bangsa Indonesia yang akan datang memiliki kepribadian nasional dan sanggup membangun masyarakat baru yang bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Konsep dasar kependidikan Ki Hajar Dewantara yang sekaligus diterima sebagai prinsip kepemimpinan bangsa Indonesia adalah: a. “ing ngarsa sung tulada” berarti guru sebagai pemimpin (pendidik) berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. Guru harus bisa menjaga tingkah lakunya supaya bisa menjadi teladan (Soeratman. 1985: 127). Dalam pembelajaran, apabila guru mengajar menggunakan metode ceramah, ia harus benar-benar siap dan tahu bahwa yang diajarkannya itu baik dan benar. b. “ing madya mangun karsa” yang berarti bahwa seorang pemimpin (pendidik) ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat, berswakarsa dan berkreasi pada anak didik (Soeratman 1985: 127). Hal ini dapat diterapkan bila guru menggunakan metode diskusi. Sebagai nara sumber dan sebagai pengarah guru dapat memberi masukan-masukan dan arahan. c. “tut wuri handayani” yang berarti bahwa seorang pemimpin (pendidik) berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab (Idris, 1983). Ketika guru berada di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan, dapat terjadi anak didik akan berusaha bersaing, berkompetisi menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Metode Among Cara mengajar dan mendidik dengan menggunakan “metode Among” dengan semboyan Tut Wuri Handayani artinya mendorong para anak didik untuk membiasakan diri mencari dan belajar sendiri. Mengemong (anak) berarti membimbing, memberi kebebasan anak bergerak menurut kemauannya. Guru atau pamong mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, bertugas mengamat amati dengan segala perhatian, pertolongan diberikan apabila dipandang perlu. Anak didik dibiasakan bergantung pada disiplin kebatinannya sendiri, bukan karena paksaan dari luar atau perintah orang lain. (Soeratman, 1985: 79) Among berarti membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan sang anak. Dengan demikian anak dapat berkembang menurut kodratnya. Hubungan murid dan pamong seperti keluarga. Murid memanggil gurunya dengan sebutan “ibu” atau “bapak” berbeda dengan sekolah lain pada jaman itu yang memanggil gurunya dengan sebutan “tuan”, “nyonya”, “nona”, “ndoro”, “den Behi” atau “mas Behi”. (Soeratman, 1985: 79) Dengan menggunakan dasar kekeluargaan dalam metode among hubungan antara murid dan guru sangat erat. Pengertian keluarga juga dipakai untuk sendi persatuan. Sifat keluarga mengandung unsur unsur : 1. Cinta mencintai sesama anggota keluarga 2. sesama hak dan sesama kewajiban 3. tidak ada nafsu menguntungkan diri dengan merugikan anggota lain. 4. kesejahteraan bersama 5. sikap toleran (Soeratman, 1985: 119) Selain asas kekeluargaan Pendidikan di Taman Siswa menggunakan sistem Tri Pusat.yaitu 1. Pusat keluarga, buat mendidik budi pekerti dan laku sosial 2. Pusat perguruan, sebagai balai wiyata untuk usaha mencari dan memberikan ilmu pengetahuan di samping pendidikan intelek 3. Pusat pergerakan pemuda, sebagai daerah merdekanya kaum pemuda atau “kerajaan Pemuda” untuk melakukan penguasaan diri, yang amat penting untuk pembentukan watak’ (Soeratman, 1985: 83) Dalam memberi pelajaran, supaya tidak membosankan dan menyenangkan, contoh-contoh yang dipakai diambilkan dari kehidupan seharihari yang dikenal oleh murid (Soeratman, 1985: 121). Dengan demikian pelajaran yang diberikan menjadi gamblang (jelas) dan dapat meresap pada ingatan anak didik. Hal ini cocok dengan model kontekstual. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Pancasila sebagai Sistem filsafat mengandung pandangan nilai pemikiran yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan yang utuh. Pancasila juga memiliki ciriciri yang utuh, dan memiliki 3 landasan yaitu landasan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi yang salinb berkaitan satu sama lain. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara indonesia, pandangan hidup bangsa dan jiwa bangsa indonesia ini yang sudah mulai menurun. Pelaksanaan yang bisa lakukan oleh masyarakat indonesia, khusunya bagi pelajar adalah mencintai dan membina persatuan, tidak membedabedakan ras, suku, agama dll, saling menghormati dan saling bergotong-royong membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. B. Saran Setelah kita membahas dan menyimpulkan makalah ini, maka kami menyarankan agar memperhatikan dan memahami semua permasalahan ini. Hendaknya kita mengaplikasikan semua apa yang telah kita bahas itu ke dalam kehidupan sehari-hari. DAFTAR PUSTAKA https://www.academia.edu/36350141/MAKALAH_PANCASILA_SEBAGAI_FI LSAFAT_PENDIDIKAN_NASIONAL 29/11/2019 https://afidburhanuddin.wordpress.com/2012/11/28/ontologi-epistimologi-danaksiologi-dalam-pengetahuan-filsafat/ https://ruhcitra.wordpress.com/2008/12/16/pancasila-sebagai-sistem-filsafat/ https://www.researchgate.net/publication/307523746_FILSAFAT_PENDIDIKAN _KI_HADJAR_DEWANTARA_DAN_SUMBANGANNYA_BAGI_PENDIDIK AN_INDONESIA 16/11/19 http://islamiceducation001.blogspot.com/2015/05/pancasila-sebagai-dasarfilsafat.html16/11/19 http://pendidiksd.blogspot.com/2016/01/pancasila-sebagai-filsafatpendidikan.html 16/11/2019 http://eprints.uny.ac.id/7371/1/p-16.pdf. Implementasi Ajaran Ki Hajar Dewantara Dalam Pembelajaran Matematika Untuk Membangun Karakter Siswa 29/11/2019