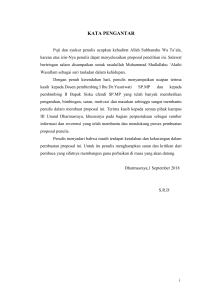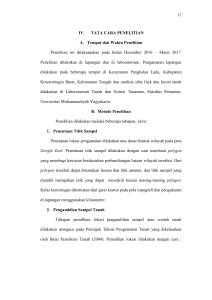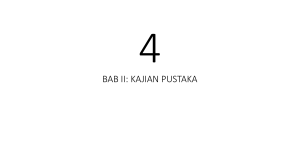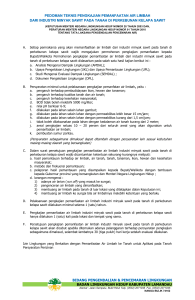LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN TAHUNAN Disusun Oleh : Kelompok 17 1. Chika Eldita H0717027 2. Dwi Alma I.P. H0717041 3. Naufal Ghazy H0717098 4. Nurmara Salsabila H0717103 5. Rizki Mulyawati H0717121 LABORATORIUM EKOLOGI DAN MANAJEMEN PRODUKSI TANAMAN PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2018 HALAMAN PENGESAHAN Laporan Praktikum Teknologi Produksi Tanaman Tahunan ini disusun untuk melengkapi tugas mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tahunan dan telah diterima, disetujui dan disahkan oleh Co-Assiten dan Dosen Mata Kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tahunan pada: Hari : Tanggal : Disusun dan diajukan oleh : Kelompok 17 1. Chika Eldita H0717027 2. Dwi Alma I.P. H0717041 3. Naufal Ghazy H0717098 4. Nurmara Salsabila H0717103 5. Rizki Mulyawati H0717121 Mengetahui, Dosen Koordinator Praktikum Co-Assisten Teknologi Produksi Tanaman Tahunan Dr. Ir. Pardono, M.S. Ifan Primadiyono NIP. 195508061983031003 NIM. H0716065 KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan sebuah praktikum dan menyelesaikan penyusunan Laporan Praktikum Teknologi Produksi Tanaman Tahunan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya kelak di yaumul akhir. Dalam menyelesaikan Laporan Praktikum Teknologi Produksi Tanaman Tahunan ini penulis mendapat bantuan baik secara moril maupun materiil dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut : 1. Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga acara praktikum berjalan lancar dan Laporan Praktikum Teknologi Produksi Tanaman Tahunan ini dapat terselesaikan dengan baik. 2. Dosen Pengampu yang telah membimbing penulis dalam mata kuliahTeknologi Produksi Tanaman Tahunan. 3. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik berupa doa maupun materi. 4. Kepada tim Co-Asisten yang sudah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 5. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuannya dalam menyusun laporan ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dan semoga laporan praktikum ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin. Surakarta, Desember 2018 Penulis DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................... ii KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv DAFTAR TABEL ............................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... vii I. IDENTIFIKASI MORFOLOGI KELAPA SAWIT ............................ 1 A. Pendahuluan ..................................................................................... 1 1. Latar Belakang ............................................................................ 1 2. Tujuan Praktikum ........................................................................ 1 B. Metodologi Praktikum ..................................................................... 2 1. Waktu dan Tempat Praktikum .................................................... 2 2. Alat dan Bahan ............................................................................ 2 3. Cara Kerja ................................................................................... 2 C. Hasil Pengamatan ............................................................................. 3 D. Pembahasan .................................................................................... 23 E. Kesimpulan dan Saran .....................................................................27 1. Kesimpulan ............................................................................... 27 2. Saran .............................................................................................27 II. IDENTIFIKASI DEFISIENSI UNSUR HARA TANAMAN KELAPA SAWIT.......................................................................................................29 A. Pendahuluan ................................................................................... 29 1. Latar Belakang .............................................................................29 2. Tujuan Praktikum ...................................................................... 29 B. Metodologi Praktikum .................................................................... 29 1. Waktu dan Tempat Praktikum .................................................. 29 2. Alat dan Bahan .......................................................................... 30 3. Cara Kerja ................................................................................. 30 C. Hasil Pengamatan ........................................................................... 31 D. Pembahasan .................................................................................... 38 E. Kesimpulan dan Saran .....................................................................43 1. Kesimpulan ............................................................................... 43 2. Saran .......................................................................................... 43 III. PERAWATAN TANAMAN KELAPA SAWIT, KAKAO, KOPI DAN KARET ..................................................................................................... 45 A. Pendahuluan ................................................................................... 45 1. Latar Belakang .......................................................................... 45 2. Tujuan Praktikum ...................................................................... 45 B. Metodologi Praktikum ................................................................... 45 1. Waktu dan Tempat Praktikum .................................................. 45 2. Alat dan Bahan .......................................................................... 46 3. Cara Kerja ................................................................................. 46 C. Hasil Pengamatan ........................................................................... 47 D. Pembahasan .................................................................................... 57 E. Kesimpulan dan Saran .....................................................................60 1. Kesimpulan ............................................................................... 60 2. Saran .............................................................................................61 IV. PENYADAPAN TANAMAN KARET .................................................. 63 A. Pendahuluan ................................................................................... 63 1. Latar Belakang .......................................................................... 63 2. Tujuan Praktikum ...................................................................... 63 B. Metodologi Praktikum ................................................................... 63 1. Waktu dan Tempat Praktikum .................................................. 63 2. Alat dan Bahan .......................................................................... 63 3. Cara Kerja ....................................................................................64 C. Hasil Pengamatan ........................................................................... 65 D. Pembahasan .................................................................................... 67 E. Kesimpulan dan Saran .................................................................. 70 1. Kesimpulan ............................................................................... 70 2. Saran .............................................................................................71 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Identifikasi Morfologi Kelapa Sawit .................................................... Tabel 2.1 Hasil Pengamatan Defisiensi Unsur Hara Kelapa Sawit(Elaeis guineensis) ....................................................................... Tabel 3.1 Hasil Pengamatan Indikasi Pertumbuhan Tanaman Tahunan .............. Tabel 3.2 Hasil Pengamatan Defisiensi Unsur Hara Tanaman Tahunan ............. Tabel 3.3 Hasil Pengamatan Serangan OPT Tanaman Tahunan ......................... Tabel 4.1 Hasil Penyadapan Karet ....................................................................... DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Pola Filotaksis Kelapa Sawit ........................................................... I. IDENTIFIKASI MORFOLOGI KELAPA SAWIT A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Minyak sawit (Elaeis) adalah tanaman industri penting yang memproduksi minyak goreng, minyak industri, dan bahan bakar (biodiesel). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan tua diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah produsen minyak sawit kedua di dunia setelah Malaysia. Di Indonesia penyebarannya di wilayah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Minyak sawit berupa pohon yang tingginya bisa mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu ada juga beberapa akar napas yang tumbuh ke arah sisi atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. Seperti jenis palem lainnya, daun kelapa sawit menyatu. Daun hijau gelap dan pelapis berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman ditutupi dengan pelepah sampai usia 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, pelapukan kering akan dilepas sehingga penampakannya menjadi mirip dengan kelapa. Bunga jantan dan betina terpisah tetapi berada dalam satu pohon (monoecious diclin) dan memiliki waktu pematangan yang berbeda, sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk yang panjang dan tajam sedangkan bunga betina terlihat lebih besar dan mekar. 2. Tujuan Praktikum Tujuan praktikum acara identifikasi morfologi kelapa sawit ini adalah mahasiswa dapat mengetahui bagian-bagian dari tanaman kelapa sawit terutama bagian atas yang meliputi : batang, bunga,daun, dan buah kelapa sawit. B. Metodologi Praktikum 1. Waktu dan Tempat Praktikum Praktikum acara Identifikasi Morfologi Kelapa Sawit ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 November 2018 di Laboratorium Fakultas Pertanian UNS Surakarta 2. Alat dan Bahan a. Alat 1) Sabit 2) Pisau 3) Penggaris 4) Alat Tulis 5) Tali Rafia 6) Meteran 7) Oven 8) Timbangan 9) Gunting 10) Kertas b. Bahan 1) Tanaman Kelapa Sawit Dewasa 2) Pelepah Daun Kelapa Sawit 3) Bunga Jantan 4) Betina Kelapa Sawit 5) Buah Kelapa Sawit. 3. Cara Kerja 1. Identifikasi batang kelapa sawit a. Menghitung jumlah daun kelapa sawit yang ada dari ujung sampai terbawah b. Menentukan pola filotaksis / pola duduk daun dalam batang tanaman kelapa sawit c. Mengukur panjang satu pelepah daun d. Mengukur lilit batang batang bagian bawah e. Mengukur tinggi tanaman kelapa sawit secara simulasi dengan menggunakan prinsip trigonometri Tan a = y/x Tinggi batang = y + r a = sudut yang terbentuk antara pengamat dan ujung batang kelapa sawit y = tinggi batang dari mata pengamat sampai ujung batang kelapa sawit r = tinggi batang dari pangkal batang sampai mata pengamat x = jarak antara pengamat dan batang 2. Identifikasi daun kelapa sawit a. Mengambil satu pelepah daun yang utuh b. Mengidentifikasi bagian-bagian daun kelapa sawit dan menulisnya c. Mengukur panjang pelepah daun (dari ujung pelepah sampai denganperiode) d. Mengukur panjang pelepah total e. Menghitung jumlah daun dalam satu pelepah dan mengukur luas daun dan helaian daun kelapa sawit dengan metode Gravimetri Rumus Gravimetri LD = Wr÷Wt×LK Wr = berat kertas replikasi daun Wt = berat kertas total LK = luas kertas total f. Pelepah daun dibagi menjadi tiga bagian, selanjutnya setiap bagain diambil empat daun, dua dari kiri dan dua lainnya dari bagian kanan g. Luas daun yang diambil dihitung dan dirata-rata untuk setiap bagiannya h. Mengalihkan rataan luas daun tersebut dengan jumlah heleain pada setiap bagian i. Hasil perhitungan luas daun masing-masing bagian kemudian dijumlahkan j. Mengukur panjang helaian daun k. Menggambar dan memberi keterangan daun kelapa sawit dan helaian daun beserta tulang daunnya. 3. Identifikasi alat reproduksi kelapa sawit a. Menentukan bunga jantan danbetinakelapasawit b. Menggambar masing-masing bunga tersebut dengan nama bagiannya c. Menentukan kemungkinan macam penyerbukan yang mungkin terjadi pada tanaman kelapa sawit 4. Identifikasi buah kelapa sawit a. Mengambil buah dari tandan buah kelapasawit yang ada b. Mengamati warna, bentuk, dan ukuran buah mentah dan matang c.Menggambar buah utuh, penampang melintang buah kelapa sawit dan memberi keterangan lengkap bagian-bagiannya C. Hasil Pengamatan Tabel 1.1 Identifikasi Morfologi Kelapa Sawit No Identifikasi Gambar Foto Keterangan a. Jumlah daun per pelepah 148 buah b. Panjang pelepah 472,5 1. Batang Kelapa cm Sawit c. Diameter batang bawah 135,35 cm d. Tinggi tanaman (..) a. Panjang pelepah daun tanpa petiole 419 cm b. Panjang pelepah daun 2. Daun Kelapa dengan petiole Sawit 472,5 cm c. Luas daun 99,42 cm d. Panjang daun terpanjang 84 cm a. Fungsi bagian a. Bunga Jantan a. Bunga jantan bunga jantan 1) Pedicellus : sebagai tangkai induk pendukung bunga 2) Reseptacullum : b. Bunga Betina 3. b. Bunga Betina sebagai tempat bertumpu bagian Alat bunga lainnya Reproduksi 3) Peduncullus : sebagai penghubung tangki bunga dengan batang b. Fungsi bagian bunga betina 1) Pedicellus : sebagai induk pendukung bunga a. Eksoskarp, bagian kulit buah berwarna 4. Buah Kelapa Sawit kemerahan dan licin b. Mesoskarp, serabut buah yang mengandung banyak minyak c. Endoskarp, cangkang pelindung inti d. Inti sawit (kernel), sebetulnya adalah biji yang merupakan bagian dalam perbanyakan generatif tanaman Sumber : Logbook Gambar 1.1 Pola Filotaksis Kelapa Sawit D. Pembahasan Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) termasuk tanaman tropis yang diduga berasal dari Nigeria (Afrika Barat) karena pertama kali ditemukan di padang gurun negara. Berdasarkan bukti fosil, sejarah dan linguistik, tanaman kelapa sawit diyakini berasal dari pantai tropis Afrika Barat. Minyak sawit adalah tanaman monositik, batangnya tidak memiliki kambium dan umumnya tidak bercabang. Batang berfungsi sebagai struktur di mana daun, bunga dan buah menempel. Batang ini juga berfungsi sebagai organ penimbunan makanan yang memiliki sistem pembuluh yang mengangkut air dan nutrisi mineral dari akar ke kanopi dan fotosintat dari dun ke seluruh bagian tanaman. batang pohon silindris dengan diameter 20-75 cm. Menurut Yan Fauzi et al (2012), tanaman yang masih muda, batang tidak terlihat karena tertutup oleh pelepah daun. Pertumbuhan batang tergantung pada jenis tanaman, kesuburan tanah, dan iklim setempat. Batangnya ditutupi oleh pangkal pelepah daun tua, semakin tua daun pelepah daun mulai rontok, kerugian dimulai dari bagian tengah batang yang kemudian memanjang ke atas dan ke bawah. Kelapa sawit adalah tanaman yang termasuk Kingdom Plantae, Divisi Spermatophyta, Kelas Angiospermae, Ordo Monocotyledone, Famili Arecaceae (dahulu disebut Palmae), Subfamili Cocoideae, Genus Elaeis, Spesies E. Guineensis Jarq, E. Oleifera (H. B. K.) Cortes, E. Odora. Menurut Pahan (2015), daun kelapa sawit adalah daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun adalah sekitar 6,5 - 9 m (tergantung varietas). Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit dapat ditanam per satuan luas sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Jumlah daun pada setiap pelepah berkisar dari 250-400 helai. Produksi daun pelepah selama satu tahun bisa mencapai 20-30 pelepah. Daun terdiri dari bagian-bagian. Koleksi daun (leaflet) yang memiliki helai (lamina) dan daun anak-anak (pelepah). Rachis yang merupakan tempat di mana daun terlampir. Daun (tangkai daun) adalah bagian antara daun dan batang. Daun selubung yang berfungsi sebagai pelindung dari tunas dan memberi kekuatan pada batang. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah di daerah tropis yang beriklim basah, yaitu sepanjang garis khatulistiwa yaitu 15º LU sampai 15º LS. Diluar zona tersebut biasanya pertumbuhan tanaman kelapa sawit agak terhambat sehingga masa awal produksinya juga terhambat. Umumnya tanaman kelapa sawit tumbuh optimum pada dataran rendah dengan ketinggian 200-500 m dari permukaan laut (dpl). Ketinggian lebih dari 600 m dpl tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit.Perbedaan ketinggian tempat akan mempengaruhi suhu, tingkat pencahayaan dan curah hujan pada tanaman kelapa sawit. Cahaya merupakan faktor utama sebagai sumber energi dalam fotosintesis,kekurangan cahaya akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan. Kekurangan cahaya pada saat pertumbuhan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, batang akan tumbuh cepat namun lemah, daunya lebih kecil, tipis, dan pucat. Hal tersebut sesuai literasi dari Gtuneland (2011) yang menyatakan bahwa pengaruh cahaya bukan hanya tergantung kepada intensitas (kuat penyinaran) saja, namun berkaitan juga dengan panjang gelombangnya. Penyinaran yang kurang karena kabut dan terlindungi awan di daerah dataran tinggi menyebabkan daun tanaman akan menebal dan berwarna hijau tua, sedangkan di daerah dataran rendah penyinaran yang panjang menyebabkan daun lebih lebar, warnanya lebih hijau,ketebalan daun lebih tipis, yang berfungsi mempercepat proses transpirasi. Tanaman kelapa sawit dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif dan bagian generatif. Bagian vegetatif meliputi akar, batang, dan daun sedangkan bagian generatif merupakan perkembangan dari bunga dan buah. Bagian vegetatif tanaman kelapa sawit terdiri dari akar (Radix), yang menurut Putranto (2010), akar kelapa sawit adalah akar serabut, yang memiliki sedikit percabangan, membentuk anyaman rapat dan tebal. Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil. Pada saat dalam fase kecambah memiliki akar tunggang yang memanjang ke bawah selama 6 bulan sampai 15 cm, dan kemudian perakaran akan berubah menjadi akar serabut. Akar primer pada umumnya berdiameter 6-10 mm, keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal dan menghujam ke dalam tanah dengan sudut yang beragam. Selanjutnya akar primer membentuk akar sekunder yang diameternya 2-4 mm. Akar sekunder bercabang membentuk akar tertier yang berdiameter 0,7-1,2 mm dan umumnya bercabang lagi membentuk akar kuarterner.Akar yang paling aktif dalam menyerap air dan unsur hara adalah akar tersier dan kuarterner yang berada di kedalaman 0-60 cm dengan jarak 2-3 meter dari pangkal pohon . Batang (Caulis), tanaman kelapa sawit berbatang lurus, tidak bercabang. Bakal batang disebut plumula (seperti tombak kecil). Pada tanaman dewasa diameternya mencapai 45-60 cm. Bagian batang bawah biasanya lebih gemuk, disebut bonggol dengan diameter 60-100 cm. Pertambahan tinggi batang kelapa sawit dipengaruhi oleh jenis tanaman, tanah, iklim, pupuk, kerapatan tanam dan lain-lain. Pertumbuhan batang kelapa sawit terbagi menjadi dua fase. Sejak ditanam sampai berumur 3,5 tahun, pertumbuhan batang difokuskan pada pembentukan pangkal batang hingga diameternya mencapai 60 cm dan pertumbuhan meninggi sangat kecil. Setelah 3,5 tahun, batang tumbuh ke atas dengan kecepatan hingga 60 cm/tahun, tetapi melambat pada umur di atas 15 tahun. Pertumbuhan dipengaruhi faktor genetik, kecepatan meninggi batang kelapa sawit juga oleh kompetisi memperoleh cahaya matahari. Kekurangan cahaya matahari mendorong batang kelapa sawit tumbuh cepat ke atas dan mengurangi potensi hasil. Jarak tanam yang terlalu rapat mengakibatkan kerugian secara ekonomi akibat penurunan hasil. Batang kelapa sawit terdapat pangkal pelepah-pelepah daun yang melekat dan sukar terlepas, meskipun daun telang kering dan mati. Batang tanaman kelapa sawit diselimuti bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Pelepah yang mengering akan terlepas sehingga menjadi mirip dengan tanaman kelapa. Menurut Andoko dan Widodoro (2013) daun (Folium), daun kelapa sawit terdiri dari beberapa bagian, yaitu kumpulan anak daun (leaflets) yang mempunyai helaian (lamina) dan tulang anak daun (midrib), Rachis yang merupakan tempat anak daun melekat, Tangkai daun (petiole) yang merupakan bagian antara daun dan batang, Seludang daun (sheath) yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberi kekuatan pada batang. Seperti jenis palma lainnya, daunnya tersusun majemuk, bersirip genap, dan bertulang sejajar. Anak-anak daun (foliage leaflet) tersusun berbaris dua sampai ke ujung daun yang panjangnya 7-9 meter. Di tengahtengah setiap anak daun terbentuk lidi sebagai tulang daun. Jumlah anak daun di setiap pelepah berkisar 250-400 helai daun. Bagian Generatif kelapa sawit terdiri dari bunga (Flos), kelapa sawit merupakan tanaman monoecious (berumah satu), artinya bunga jantan dan bunga betina berada pada satu pohon, tetapi tidak pada tandan yang sama. Tanaman kelapa sawit yang berumur 3 tahun sudah mulai dewasa dan mulai mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan berbentuk lonjong memanjang, sedangkan bunga betina agak bulat. Bunga betina dan jantan (sex ratio) sangat dipengaruhi oleh pupuk dan air. Jika tanaman kekurangan pupuk atau kekurangan air, bunga jantan akan lebih banyak keluar. Produktivitas akan menjadi baik jika unsur hara dan air tersedia dalam jumlah yang banyak dan seimbang. Sex ratio mulai terbentuk 24 bulan sebelum dipanen, artinya calon bunga (primordia) telah terbentuk dua tahun sebelum panen. Bagian generatif lain yaitu Buah, bunga kelapa sawit betina yang telah diserbuki akan tumbuh menjadi buah dan matang pada 5,5 bulan kemudian. Buah kelapa sawit berbentuk lonjong membulat dengan panjang 2-3 cm dan bergerombol pada tandan yang muncul dari setiap ketiak daun. Jumlah buah biasa mencapai sekitar 2000 buah pada setiap tandan dengan tingkat kematangan yang bervariasi. Karena pengaruh klorofil, buah kelapa sawit muda berwarna hujau, meski demikian ada beberapa varietas yang buahnya sejak muda berwarna ungu. Buah kelapa sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah dan kandungan minyak bertambah sesuai dengan kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak bebas FFA (free fatty acid) akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya. Praktikum identifikasi morfologi kelapa sawit meliputi identifikasi batang kelapa sawit berupa jumlah daun per pelepah terdiri dari 148 helai, panjang pelepah memiliki panjang sebesar 472,5 cm, kemudian menghitung diameter batang bawah dengan cara mengukur keliling batang bawah menggunakan meteran kemudian didapat keliling sebesar 425 cm lalu dihitung menggunakan rumus keliling lingkaran dan didapat diameter batang bawah kelapa sawit sebesar 135,5 cm. selanjutnya mengukur tinggi pohon kelapa sawit dengan membuat ilustrasi, diumpamakan pohon kelapa sawit sama dengan tinggi orang yang berdiri sejauh 1081 cm dari pohon dan tinggi orang sebesar 165 cm. Selanjutnya membentuk merebahkan tubuh orang tersebut, sehingga pada ilustrasi akan didapatkan dua segitiga yang terbentuk. Dari kedua segitiga itu dihitung dengan perbandingan dan akan didapat nilai tinggi pohon kelapa sawit sebesar 11,08 meter. Rumus filotaksis pada batang kelapa sawit bernilai 3/8. Identifikasi kemudian dilanjutkan pada bagian daun kelapa sawit, yang diidentifikasi dari daun kelapa sawit adalah panjang pelepah daun tanpa petiole sebesar 419 cm, panjang daun dengan petiole sebesar 472,5 cm kemudian menghitung luas daun dengan metode grafimetri di dapatkan luas daun total sebesar 596,53 cm, kemudian juga didapatkan helaian daun terpanjang sebesar 84 cm. Bagian-bagian dari daun kelapa sawit antara lain : ibu tangkai daun, petiole, pelepah, anak daun, tulang daun. Identifikasi selanjutnya adalah mengidentifikasi alat reproduksi kelapa sawit yang berupa bunga jantan dan bunga betina.Menurut Putranto (2010) Tanaman kelapa sawit mengadakan penyerbukan silang (cross pollination). Artinya, bunga betina dari pohon yang satu dibuahi oleh bunga jantan dari pohon yang lainnya dengan perantara angin dan atau serangga penyerbuk. Bunga jantan dan betina memiliki kesamaan pada bagiannya yakni memiliki pedicellus yang berfungsi sebagai induk untuk mendukung bunga. Reseptacullum yang berfungsi sebagai tempat bertumpu bagian-bagian bunga lainnya. Peducullus yang berfungsi sebagai penghubung tangkai bunga dengan batang atau cabang primer. Identifikasi yang terakhir adalah mengidentifikasi bagian buah kelapa sawit, buah kelapa sawit jika dipotong melintang akan terlihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya berupa kernel yaitu sebagai bagian generatif untuk perbanyak atau bibit dan sebagainya bahan baku PKO (Palm Kernel Oil). E. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : a. Sebuah. Bagian dari kelapa sawit terdiri dari batang elips, pohon kelapa sawit, bunga jantan dan betina terpisah dan buah kelapa sawit. b. Bunga jantan memanjang terdiri dari serbuk sari, kelopak bunga, dan tangkai bunga c. Bunga betina berbentuk bulat memiliki bagian yang terdiri dari batang, kelopak bunga, putik dan tandan batang. d. Buah sawit memiliki susunan buah, yaitu pericarp (daging buah) yang terbungkus oleh exocarp (kulit), mesocarp, dan endocarp (shell). Inti memiliki testa (kulit), endosperm, dan embrio. e. Posisi daun pada batang 3/8 berarti setiap tiga putaran ada 8 daun. 2. Saran Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya lebih teliti dalam melakukan identifikasi terhadap tanaman kelapa sawit agar dapat mengetahui secara bagian-bagian morfologi kelapa sawit dan menghitungtinggi pohonmaupundiameter batang. lebih teliti dalam II. IDENTIFIKASI DEFISIENSI UNSUR HARA TANAMAN KELAPA SAWIT A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Penyakit defisiensi pada tanaman kelapa sawit merupakan perhatian besar untuk memastikan pertumbuhan normal yang akan mengarah pada produksi hasil panen yang lebih besar. Kekurangan nutrisi atau tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan karenanya asupan nutrisi yang cukup sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang optimal dan proses ini tidak dapat didasarkan pada perkiraan. Elemen mineral penting dapat diatasi dengan menambahkan jumlah nutrisi tertentu dan jenis nutrisi yang akurat ke tanaman melalui tanah. Ketersediaan pendekatan konvensional untuk menentukan status gizi yang mengandung tanaman memiliki beberapa kerugian. Misalnya, analisis tanah dan pengambilan sampel daun untuk analisis kimia keduanya dikenal baik melibatkan prosedur yang membosankan, biaya intensif dan memakan waktu. Saat ini di perkebunan kelapa sawit, diagnosis kekurangan gizi kebanyakan dilakukan secara manual yang didasarkan pada penilaian yang dimiliki oleh tenaga ahli minyak sawit yang mendiagnosis penyebab dan kemungkinan penyakit kelapa sawit. Komposisi nutrisi yang dipegang oleh pohon kelapa sawit sangat penting terutama selama tahap pertumbuhan dan perkembangan. Penyerapan keseimbangan mikronutrien dan makronutrien penting untuk memastikan pertumbuhan yang sehat yang akan menghasilkan potensi yang lebih tinggi dalam produksi buah segar kelapa sawit. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, jumlah nutrisi yang tidak mencukupi di pabrik kelapa sawit akan mempengaruhi pertumbuhan, produktivitas dan secara tidak langsung mengungkap gejala yang dapat diamati pada permukaan daun sebagai indikasi salah satu dari tiga kategori kekurangan nutrisi yaitu nitrogen, kalium, dan magnesium. Ketidakseimbangan atau disproporsi nitrogen dinyatakan dengan selebaran hijau pucat atau kuning seragam dan laju pertumbuhan pohon yang berkurang tajam, dengan jaringan pelepah dan rachis berubah menjadi warna kuning cerah dan selebaran meruncing yang menggulung ke dalam. Selanjutnya, kekurangan kalium dalam minyak sawit ditunjukkan dengan mengubah bintik-bintik hijau pucat pada pinnae dari daun yang lebih tua terjadi menjadi bintik-bintik persegi kuning-oranye dan ujung daun pinnae akan semakin mengering. Ini dapat dibedakan berdasarkan munculnya bercak oranye konfluen. Sementara itu gejala karena kekurangan magnesium terungkap karena variasi warna pada selebaran yang terkena cahaya khusus dari hijau zaitun ke tambalan oker sedangkan pinna yang dinaungi tetap hijau bersama dengan perubahan daun dari oker ke kuning cerah yang berubah menjadi nekrotik. 2. Tujuan Praktikum Praktikum Identifikasi Defisiensi Unsur Hara Tanaman Kelapa Sawit bertujuan agar mahasiswa terampil melakukan identifikasi keharaan, sehingga dapat melakukan tindakan secara tepat untuk mengatasi kekurangan hara pada pertanaman kelapa sawit. B. Metodologi Praktikum 1. Waktu dan Tempat Praktikum Praktikum Identifikasi Defisiensi Unsur Hara Tanaman Kelapa Sawit dilaksanakan pada hari Minggu 4 November 2018 pada pukul 08.00- selesai di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian UNS di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. 2. Alat dan Bahan a. Alat 1) Pisau 2) Penggaris 3) Alat tulis b. Bahan 1) Pertanaman kelapa sawit 3. Cara Kerja Secara fisiologi/ Visual Identifikasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut : a. Perbandingan warna hijau daun dengan warna hijau yang baku (hijau gelap). Warna daun yang hijau-gelap merupakan ciri keadaan hara tanaman yang baik. Sementara apabila warnanya menjadi hijau pucat atau kekuning- kuningan, maka dapat dipastikan bahwa tanaman tersebut mengalami defisiensi dan atau pengaruh faktor lingkungan seperti temperature yang ekstrim, penyebab penyakit, atau kesalahan penyemprotan. b. Adanya tanda dan gejala (Sympotm) defisiensi hara. Cara yang paling mudah, untuk mendapatkan gambaran adanya gejala atau tanda defisiensi hara adalah dengan membandingkan daun dengan foto tanaman yang mengalami defisiensi. Selain itu, dengan melihat tanda atau gejalanya, sebagai berikut: 1) Tanda atau gejala defisiensi muncul dari daun yang tertua 2) Tanda atau gejala defisiensi muncul dari daun yang termuda 3) Membandingkan pertumbuhan tanaman dengan plot tanaman yang tidak mendapat pemupukan (teknik window). C. Hasil Pengamatan Tabel 2.1 Hasil Pengamatan Defisiensi Unsur Hara Kelapa Sawit(Elaeis guineensis) No Tanggal Defisiensi Penunjuk Ciri - ciri Foto Defisiensi defisiensi (daun tertua/ termuda) 1 4-11-2018 N Daun tua Daun menguning (klorosis) mulai dari anak daun. Daun pucat atau kaku. Kekurangan N menyebabkan bewarna daun kuning pucat. Tanaman yang mengalami defisiensi umumnya pada daun tua bewarna hijau pucat, dan kemudian kuning dan (khlorosis), menyebabkan nekrosis. Nekrosis berkembang dari ujung mulai dan pinggir daun. 2 Mn Daun muda Muncul warna bercak-bercak hitam kecoklatan. Sumber: Logbook D. Pembahasan Unsur hara merupakan faktor yang mutlak dibutuhkan oleh tanaman untuk melengkapi unsur daur hidupnya, mulai dari fase vegetatif sampai generatif. Unsur-unsur tersebut menjadi bagian bagi pertumbuhan tanaman yang penting, karena disebut sebagai unsur hara esensial. Fungsi dari berbagai unsur hara bagi tanaman berbeda-beda. Ketersediaanya di tanah pun harus tetap terjaga. Jumlah unsur hara yang dibeerikan pada media tanam harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Gejala dari defisiensi unsur hara tersebut berbeda-beda sehingga perlakuan dalam pemberian unsur hara harus disesuaikan. Hidayat (2012) mengatakan bahwa pengamatan gejala defisiensi hara pada kelapa sawit penting dilakukan untuk menentukan ketepatan dosis pupuk yang digunakan. Defisiensi adalah kekurangan meterial (bahan) yang berupa makanan bagi tanaman untuk melangsungkan hidupnya. Kebutuhan tanaman akan unsur hara berbeda-beda tergantung dari jenis tanamannya. Unsur hara dalam tanah apabila tidak tersedia maka pertumbuhan tanaman akan terhambat dan produksinya menurun. Menurut Susila (2013) defisiensi unsur hara dapat menimbulkan tanda-tanda tertentu pada tanaman yang kadang sulit dibedakan dengan serangan penyakit. Beberapa gejala defisiensi seringkali tampak bersama-sama (komplikasi defisiensi) dan sulit dalam menentukan penyebabnya, sehingga analisis tanah atau uji tanah sangat membantu dalam mengungkap masalah-masalah hara dalam tanah. Menurut pendapat Firmansyah (2010) jenis dan kegunaan unsur hara perlu diketahui sebab pengetahuan itu meningkatkan ketepatan perawatan, pemupukan, dan efektivitas pupuk terhadap produksi tanaman. Pramurjadi et al(2017) mengatakan bahwa gejala serangan OPT sangat beragam, demikian pula defisiensi hara. Keterbatasan pengetahunan pelaku usaha agribisis dalam mengenali gejala serangan OPT dan difisiensi hara pada tanaman di lapangan menghambat upaya pengendalian. Ketersediaan unsur hara esensial apabila kurang dari jumlah yang dibutuhkan tanaman, maka tanaman akan terganggu metabolismenya yang secara visual dapat terlihat dari penyimpangan-penyimpangan pada pertumbuhannya. Gejala kekurangan unsur hara ini dapat berupa pertumbuhan akar, batang atau daun yang terhambat (kerdil) dan klorosis pada berbagai organ tanaman. Gejala yang ditampakkan tanaman karena kekurangan suatu unsur hara dapat menjadi petunjuk kasar dari fungsi unsur hara yang bersangkutan. Gejala kekurangan suatu unsur hara yang ditampakkan tanaman tidak selalu sama. Gejala tersebut dapat berbeda, tergantung spesies tanaman, tingkat keseriusan masalah, dan fase pertumbuhan tanaman. Gejala serangan hama memperlihatkan tanda secara visual yang jelas seperti daun robek, bengkak, dan yang lainnya. Menurut Supriyo et al (2013) berdasarkan mobilitas unsur hara dalam tanaman dibagi menjadi 2, yaitu unsur mobil dan imobil. Unsur mobil adalah unsur hara yang dapat ditranslokasikan dari jaringan tua ke jaringan muda pada saat jaringan muda tersebut terjadi kekurangan hara (defisiensi). Sebaliknya unsur imobil adalah unsur hara yang tidak dapat ditranslokasikan. Imobilitas unsur hara pada tanaman dicirikan dengan munculnya gejala defisiensi dimana defisiensi unsur mobil selalu dimulai dari daun tua (bawah), sedangkan imobil pada daun muda. Unsur mobil yaitu N, K, Mg dan unsur imobil yaitu unsur mikro B, Zn, Cu, Fe. Bedasarkan pengamatan ditemukan bahwa tanaman kelapa sawit mengalami defisiensi undur hara N dan Mn. Firmansyah (2010) mengatakan bahwa nitrogen (N) merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan berguna oleh tanaman untuk pertumbuhan, kekurangan N mengakibatkan pertumbuhan tanaman menurun. Gejala kekurangan unsur hara N adalah pertumbuhan terhambat dan daun tua bewarna hijau pucat kekuningan. Gejala defisiensi unsur hara Mn pada kelapa sawit ditandai dengan adanya bercak coklat kehitaman pada daunnya. E. Kesimpulandan Saran 1. Kesimpulan Berdasarkan praktikum identifikasi defisiensi unsur hara pada tanaman kelapa sawit yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan antara lain : a. Defisiensi adalah kekurangan meterial (bahan) yang berupa makanan bagi tanaman untuk melangsungkan hidupnya. b. Defisiensi unsur hara dapat menimbulkan tanda-tanda tertentu pada tanaman yang kadang sulit dibedakan dengan serangan penyakit. c. Imobilitas unsur hara pada tanaman dicirikan dengan munculnya gejala defisiensi dimana defisiensi unsur mobil selalu dimulai dari daun tua (bawah), sedangkan imobil pada daun muda. d. Tanaman kelapa sawit yang diamati mengalami defisiensi unsur hara N dan Mn, dimana defisiensi N terjadi pada daun tua dan defisiensi Mn terjadi pada daun muda. 2. Saran Berdasarkan praktikum identifikasi defisiensi unsur hara pada tanaman kelapa sawit diberikan saran, antara lain : a. Pengamatan dapat dilakukan dengan lebih teliti supaya didapatkan hasil yang sesuai. b. Praktikan sebaiknya membawa seluruh peralatan yang dibutuhkan sehingga proses identifikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. III. PERAWATAN TANAMAN TAHUNAN (KELAPA SAWIT, KARET, KAKAO DAN KOPI) A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Tanaman kelapa sawit (Elaei guineensis Jacq) saat ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting di sektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya, hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia. Melihat pentingnya tanaman kelapa sawit dewasa ini dan masa yang akan datang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan penduduk dunia akan minyak sawit, maka perlu dipikirkan usaha meningkatan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit secara tepat agar sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Salah satu diantaranya adalah bahan perbanyakan tanaman berupa bibit, untuk itu perlu tindakan kultur eknis atau perawatan bibit yang baik antara lain dengan jalan pemupukan pada waktu di pembibitan awal an di pembibitan utama. Tanaman karet (Hevea brasiliensis) termasuk dalam famili Euphorbiacea, disebut dengan nama lain rambung, getah, gota, kejai ataupun hapea. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting sebagai sumber devisa non migas bagi Indonesia, sehingga memiliki prospek yang cerah. Upaya peningkatan produktivitas tanaman tersebut terus dilakukan terutama dalam bidang teknologi budidaya dan pasca panen. Tanaman karet dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan lateks yang banyak maka perlu diperhatikan syarat-syarat tumbuh dan lingkungan yang diinginkan tanaman ini. Apabila tanaman karet ditanam pada lahan yang tidak sesuai dengan habitatnya maka pertumbuhan tanaman akan terhambat. Lingkungan yang kurang baik juga sering mengakibatkan produksi lateks menjadi rendah. Sesuai habitat aslinya di Amerika Selatan, terutama Brazil yang beriklim tropis, maka karet juga cocok ditanam di Indonesia, yang sebagian besar ditanam di Sumatera Utara dan Kalimantan. Kakao merupakan salah satu produk pertanian yang memiliki peranan yang cukup nyata dan dapat diandalkan dalam mewujudkan program pembangunan per-tanian, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendorong pengembangan wilayah, peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan/ devisa negara. Pengusahaan kakao di Indonesia sebagian besar merupakan perkebunan rakyat. Nasional terus menjalani pertumbuhan yang nyata sehingga produksi kakao nasional juga meningkat seiring dengan peningkatan luas arealnya, namun demikian produktivitasnya stabil bahkan menurun. Tanaman kopi merupakan komoditas ekspor unggulan yang dikembangkan di Indonesia karena mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia. Permintaan kopi Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat karena seperti kopi Robusta mempunyai keunggulan bentuk yang cukup kuat serta kopi Arabika mempunyai karakteristik cita rasa (acidity, aroma, flavour) yang unik dan ekselen. Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan penghasilan kopi. Semua kopi yang tersebar di dunia merupakan jenis kopi yang terdapat di indonesia. Selain memiliki rasa yang unik, kopi indonesia juga memiliki aroma yang khas sehingga masyarakat eropa menyukai akan kopi tersebut. Tak sedikit pula perkebunan perkebunan besar baik itu milik pemerintah maupun swasta membudidayakan tanaman kopi untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin hari semakin banyak. 2. Tujuan Praktikum Mahasiswa terampil melakukan perawatan pada tanaman tanaman kelapa sawit, kakao, kopi dan karet seperti pengendalian gulma, teknik pemupukan, pemangkasan dll. B. Metodologi Praktikum 1. Waktu dan Tempat Praktikum Praktikum Teknologi Produksi Tanaman Tahunan Acara 3 (Perawatan Tanaman Kelapa Sawit, Kakao, Kopi dan Karet) ini dilakukan pada hari Minggu, 4 November 2018 di Laboratorium Pertanian UNS Jumantono. Pukul 08.00-selesai. 2. Alat dan Bahan Alat : a. Cangkul b. Sabit c. Gergaji kayu d. Ember Bahan : a. Tanaman kelapa sawit b. Tanaman kakao c. Tanaman karet d. Pupuk urea e. SP36 f. KCL g. Alas untuk mencapur pupuk 3. Cara Kerja a. Pemupukan 1) Membuat piringan 2) Menentukan dosis pemupukan a. Menentukan lebar piringan pada sekitar batang tanaman kelapa sawit, kakao, kopi dan karet yang aka dilakukan penyiangan, dengan berpedoman panjang pelepah daun atau lebar tajuk tanaman. b. Membersihkan daerah sekeliling/ melingkar barang membentuk lingkaran atau piringan. c. Menggemburkan tanah pada daerah piringan. d. Melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit, kakao, karet dan kopi dengan cara menebarkannya pada daerah piringan dengan dosis tertentu. e. Cara pemberian pupuk diperhatikan secara seksama agar pemupukan dapat terlaksana secara efisien. Pemberian pupuk pada tanaman tahunan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a) Pupuk N ditaburkan secara merata pada piringan mulai jarak 50 cm sampai dipinggir luar piringan. b) Pupuk P dan K ditabur secara merata dari jari-jari 1,0 m hingga jarak 3,0 m (dari pangkal pokok 0,75 sampai 1,0 m di luar piringan) c) Tiap komoditas 3 macam perlakuan yaitu : dosih rendah, anjuran dan tinggi. d) Setelah dipupuk tanaman harus disiram setiap hari selama 1 minggu. e) Pengamatan lanjutan dilakukan 2 minggu sekali. b. Pemangkasan a. Memangkas cabang yang tidak produktif (cabang tua, cabang adventif, wiwilan, terserang hama/penyakit). b. Memangkas tajuk tanaman yang terlalu rimbun. C. Hasil Pengamatan Tabel 3.1 Hasil Pengamatan Indikasi Pertumbuhan Tanaman Tahunan No Perlakuan Tanggal 1. Sebelum perlakuan 4 -Kelapa November Sawit 2018 -Kakao -Karet -Kopi 2. Sesudah perlakuan Komoditas Indikasi Pertumbuhan Keliling Jumlah Jumlah Batang (cm) Pelepah Tunas/ Pelepah Baru 340 25 - -Kelapa Sawit -Kakao -Karet -Kopi 65 120 27 8 53 - 340 25 - 65 120 27 8 53 - Sumber : Logbook Tabel 3.2 Hasil Pengamatan Defisiensi Unsur Hara Tanaman Tahunan No Perlakuan Tanggal Komoditas Indikasi pertumbuhan Defisiensi Tanda Foto Minggu 4 a.Kelapa Mg -Tulang November sawit daun 2018 menguning -Daun kering 1 Sebelum perlakuan b.Kakao Cu -Ujung daun kering c. Karet N -Helai daun menguning d.kopi 2 Setelah perlakuan Sumber : Logbook p -Tulang daun menguning Sabtu 17 a.Kelapa November sawit 2018 Cu -Ujung daun kering b.Kakao Cu -Ujung daun kering c.Karet N -Daun menguning d.Kopi N -daun menguning Tabel 3.3 Hasil Pengamatan Serangan OPT Tanaman Tahunan No Perlakuan Tanggal 1 Sebelum perlakuan 2 Setelah perlakuan Komoditas Serangan OPT Jenis Tanda Minggu 4 a.Kelapa Ulat api Daun November sawit berlubang 2018 b.Kakao Ulat Daun berlubang c. Karet Rayap Batang rapuh dan kopong d.kopi Kutu dompolan Semut rangrang Tulang dau terdapat putih putih seperti lilin Buah terkikis b.Kakao Ulat grayak Daun berlubang c.Karet Tungau karet Bercak daun berwarna coklat Sabtu 17 a.Kelapa November sawit 2018 Foto d.Kopi Sumber: Logbook Penggerek Buah kopi hitam berlubang D. Pembahasan Perawatan tanaman kelapa sawit sangat dibutuhkan, agar hasil produksi yang dihasilkan menjadi optimal. Pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tak langsung agar dapat memeuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman. Tujuan dilakukan pemupukan antara lain untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman. Proses pemupukan sangat berperan dalam memastikan keberhasilan produksi tanaman tersebut. Menurut Junedi (2012) pohon sawit yang akan diperlakukan dengan pupuk adalah tumbuh dan berbuah normal pada umur TM 9 tahun. Pupuk perlakuan disebar sekitar pokok sawit terlebih dahulu dibersihkan dari gulma. Pupuk organik yang digunakan adalah pupuk kandang asal kotoran sapi, dipilih yang matang, dosis menurut perlakuan juga ditaburkan disekeliling pohon secara merata. Sedangkan pupuk anorganik yang digunakan adalah Urea 46%, TSP 46% dan KCl 45%. Panen dilakukan dalam beberapa periode. Apabila buah matang secara serempak dapat dipanen sekaligus, tetapi apabila tidak bisa bersamaan, dapat dilakukan 2 kali. Pohon kopi pada stadia TBM yaitu pada umur 1 sampai dengan 2 tahun, kopi sudah memer-lukan seluruh unsur hara untuk pertumbuhan vegetatifnya meliputi N, P, K dan Mg. Cara penaburan pupuk adalah disebar merata di sekeliling pohon dengan jarak tabur tergantung dari umur tanaman. Umur tanaman 1-2 tahun pupuk ditabur disekeliling pohon dengan jarak 25-50cm dari pohon, Umur tanaman 3-5 tahun pupuk ditabur disekeliling pohon dengan jarak 50-100 cm dari pohon, Umur tanaman 6-10 tahun pupuk ditabur disekeliling pohon dengan jarak 100-150 cm dari pohon, Umur tanaman >10 tahun pupuk ditabur disekeliling pohon dengan jarak 150-200 cm dari pohon. Umumnya untuk memenuhi kebutuhan unsur hara N digunakan pupuk urea dimana jenis pupuk tersebut cepat bereaksi dalam larutan tanah, mudah didapat di pasaran dan harganya relatif murah Kandungan N total berkisar antara 45 –46 %. Keuntungan menggunakan pupuk urea adalah mudah diserap tanaman. Kandungan N yang tinggi pada urea sangat dibutuhkan pada pertumbuhan awal tanaman kakao. Menurut Sitorus (2014) metode pemupukan tanaman kakao dilakukan dengan membuat alur sedalam kurang lebih 10 cm di sekeliling batang kakao. Alur tersebut memiliki diameter sekitar setengah tajuk tanaman cokelat. Waktu pemupukan tanaman kakao lebih baik dilakukan pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. Tanah yang kekurangan belerang (S), maka urea dapat diganti dengan ZA dengan dosis 2,2 kali dari Urea, atau KCl dapan diganti dengan ZK dengan dosis1,2 kali dari KCl. Tanah kondisi masam dengan kandungan Ca tersedia rendah,pupuk kieserit dapat diganti dolomit dengan dosis 1,5 kali dari kieserit. Jika TSP tidak tersedia dapat diganti dengan SP-36 sebesar 1,3 kalidari dosis TSP, dan jika hanyaada SP-18 maka dosisnya 2,6 kali dari dosis TSP atau 2 kali dari dosis SP-36. Pemupukan merupakan kegiatan penting bagi perkebunan karet. Beberapa penelitian menunjukan bahwa pemupukan pada tanaman karet berpengaruh pada pertumbuhan, status hara, peningkatan produksi dan ketahanan terhadap penyakit. Tahap-tahap melakukan pemupukan dengan cara manual circle yaitu: Lubang dibuat melingkari lubang tanaman dengan jarak disesuaikan dengan umur tanaman. Hal ini disebabkan akar tanaman semakin luas seiring dengan pertambahan umurnya. Pemberian urea ke-1,2,3, dan 4 masing-masing setelah tanaman berumur 2,5,8, dan 12 bulan di lapangan. Tiap pemberian : seperempat dosis dalam setahun. Pemberian pertama dan kedua termasuk dosis TSP, KCL dan Kieserit pada tahun ke-1,2 di lapangan, masingmasing pada bulan Februari dan Agustus/September. Diberikan menjelang daun tumbuh kembali setelah masa gugur daun. Pemangkasan atau purining adalah langkah pembuangan beberapa bagian pada tanaman seperti cabang dan ranting untuk mendapatkan bentuk tertentu, sehingga dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi agar cahaya matahari mampu menyinari, mempermudah mendeteksi hama penyakit, serta mempermudah proses panen tanaman tersebut. Jenis-jenis pemangkasan yaitu pemangkasan pucuk,prinsipnya adalah menghilangkan tunas apikal, yaitu tunas yang tumbuh di pucuk batang tanaman. Hormon akusin dan sitokinin pada tanaman mempengaruhi pertumbuhan pucuk tanaman sehingga pertumbuhan tanaman bagian atas lebih cepat dibandingkan pertumbuhan percabangan dan membentuk kanopi tanaman. Pemangkasan pucuk bertujuan untuk mengurangi persaingan hasil fotosintesis di antara daun degan buah. Pemangkasan bentukdilakukan untuk membentuk kerangka tanaman yang diinginkan. Pemangkasan bentuk bertujuan untuk membentuk kerangka pohon yang diinginkan, dimana percabangannya diatur dengan arah yang menyebar dan produktif sehingga pertumbuhan batang dan cabang lebih kuat. Pemangkasan pemeliharaan, menurut Boerhendhy dan Khaidir (2010) pemangkasan ini dilakukan sesudah pemangkasan bentuk, tanaman dipelihara dan dipertahankan bentuknya. Kemudian membuang percabangan yang terserang hama penyakit dan lain sebagainya sehingga percabangan produktif kembali. Cabang yang kurang produktif dipangkas agar unsur hara yang diberikan dapat tersalur kepada batang-batang yang lebih produktif. Pemangkasan peremajaan,pemangkasan meremajakan pertumbuhan tanaman. Maksud ini dari diperlukan untuk meremajakan yaitu mengganti tajuk tanaman yang lama atau tua dengan yang baru yang masih produktif. Cara pemangkasan peremajaan ialah dengan menebang pohon, mengurangi percabangan atau merobohkan pohon. Boerhendy (2010) mengatakan bahwa tanaman karet saat ini sudah banyak dikembangkan klonklon unggul baru yang berproduksi tinggi. Dalam rangka perluasan areal maupun peremajaan,klon-klon berproduksi rendah sebaiknya mulai diganti dengan klon-klon berproduksi tinggi. Mempertahankan produksi tetap stabil dianjurkan melakukan diversifikasi klon. Setiap 350400 ha areal yang diremajakan atau tanaman baru minimal ditanam 23 klon. Terdapat 2 metode pemangkasan bentuk yaitu; metode toraja dan metode kandelaber. Tujuan pangkasan bentuk dalam budidaya kopi bertujuan membentuk kerangka tanaman yang kuat dan seimbang. Tanaman menjadi tidak terlalu tinggi, cabang-cabang lateral dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan lebih panjang. Selain itu kanopi pertanaman lebih cepat menutup. Hal ini penting untuk mencegah rumpai dan erosi. Pemangkasan kakao bertujuan untuk mempermudah manajemen hama, penyakit, panen buah dan agar diperoleh produksi yang tinggi. Ada beberapa pelaksanaan pemangkasan yaitu pemangkasan bentuk, cabang primer yang tumbuh dari jorget dipelihara tiga, dipilih yang tumbuh kuat dan seimbang. Ujung cabang primer pada batas 75-100 cm dari jorget, dipotong. Cabangcabang sekunder diatur zig-zag diatur yang tumbuhnya seimbang ke segala arah. Awal tumbuhnya cabang sekunder sekitar 30 cm dari jorget. Pemangkasan produksi, cabang/tunas yang dipangkas pada pangkas pemeliharaan ini adalah tunas air (wiwilan), cabang yang meninggi > 3m, cabang sakit, cabang balik, cabang overlapping atau yang menaungi, intinya semua cabang tidak produktif yang menyebabkan kanopi rimbun. Tunas air dibuang 2-4 minggu sekali dan pangkas pemeliharaan 4-6 kali per tahun. Pemendekan Kanopi, pangkasan pemendekan kanopi, tujuannya untuk memelihara ketinggian tanaman 3-4 m, dilakukan setahun sekali pada awal musim hujan. Pemangkasan pada kelapa sawit bertujuan untuk memudahkan pengambilan tandan kelapa sawit, meningkatkan proses fotosintesis dan memberikan hasil buah tandan (BTS) segar yang tinggi, dan mengurangi tandan busuk yang disebabkan oleh ulatMarasmius palmivorus. Pemangkasan sanitasi dilaksanakan untuk membersihkan tanaman kelapa sawit dari pelepahpelepah yang mengganggu dan menjaga tingkat keseimbangannya. Waktu pengerjaan pemangkasan ini bertepatan dengan saat melakukan kastrasi yakni ketika tanaman sudah berusia sekitar 17-19 bulan. metode pelaksaannya ialah membuang pelepah-pelepah sawit yang tampak mengering. pemangkasan pertama dilakukan sebelum proses pemanenan yang pertama kali dilaksanakan. Caranya adalah membuang seluruh pelepah yang terletak di bawah TBS yang posisinya paling rendah sehingga pertumbuhan TBS akan lebih optimal. Setelah pelakasanaan pemangkasan pertama, maka tidak perlu dilakukan lagi pemangkasan lanjutan hingga usia pohon mencapai 4 tahun atau letak TBS yang terendah minimal berada 1 meter di atas permukaan tanah. Gejala defisiensi unsur hara mikrodapat dilihat secara visual, hal ini sesuai dengan pendapat Steanus (2015) yang menyatakan bahwabeberapa gejala defisiensi unsur mikro pada tanaman karet yang dapat dilihat secara visual diantaranya: 1. Zinc (Zn): Luas daun akan mengecil dibanding daun pada umumnya. Permukaan daun bengkok dan bergelombang. Selain itu, tulang daun akan berwarna kuning karena mengalami klorosis. 2. Copper (Cu) : Layunya daun pada bagian atas, kemudia lambat laun menjadi coklat dan gugur. Gugur daun ini menyebabkan batang meranggas dan tunas apikal mengalami kematian. Pertumbuhan tunas baru berkembang melalui meristem batang. Unsur fosfor (P) merupakan salah satu yang sangat esensial dibutuhkan tanaman kelapa sawit. Purwati (2013) mengatakan bahwa unsur fosfor (P) bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Fosfor berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan, serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji dan buah. tanah yang kekurangan fosfor, tanaman akan menampakkan gejala yaitu; warna daun seluruhnya berubah kelewat tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Tepi daun, cabang dan batang terdapat warna merah ungu yang lambat laun berubah menjadi kuning. Defisiensi unsur makro pada tanaman kopi adalah Nitrogen (N), bermanfaat pada pembentukan klorofil dan penyerapan air. Kekuarangan unsur ini berakibat daun luruh, mengguning dan menggulung (dimulai dari daun tua) serta pucuk mengalami kematian. Posfor (P), unsur ini berperan dalam proses fotosintesis, respirasi, penyimpanan energi dan pembelahan sel. Akibat yang ditimbulkan dari kekurangan P yaitu : pertumbuhan terhambat dan daun memucat yang dimulai dari daun muda. Kalium (K), adalah unsur hara yang berperan dalam proses fotosintesis dan sintesa protein. Gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan unsur hara ini yaitu warna daun memudar dan terjadi nekrosis (bercak coklat) pada ujung daun. Kalsium (Ca), keberadaan unsur ini dapat merangsang pertumbuhan akar dan daun serta mempengaruhi penyerapan unsur hara lainnya. Kekurangan Ca berakibat daun menguning, yang dimulai dari bagian tengah sampai ke tepi daun. Defisiensi unsur makro pada tanaman kakao adalah tanaman membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang banyak karena merupakan penyusun utama komponen sel tanaman yaitu asam amino dan asam nukleat. Defisiensi N akan cepat menghambat pertumbuhan. Gejala yang tampak bila terjadi defisiensi N adalah klorosis, yaitu daun yang berwarna kuning, khususnya pada daun tua yang terbawah. Daun yang lebih muda tidak menunjukkan gejala tersebut karena N dapat dimobilisasi dari daun yang lebih tua. Jadi pada daun yang lebih muda akan menunjukkan warna hijau terang dan daun yang lebih tua menunjukkan warna hijau kekuningan . Bila defisiensi N terjadi secara perlahan maka tanaman akan menjadi ramping dan berkayu. Terbentuknya kayu pada batang menunjukkan adanya kelebihan karbohidrat karena tidak dapat diubah menjadi asam amino atau senyawa N lainnya. Fosfor dalam bentuk fosfat merupakan senyawa penting untuk sel tanamanmeliputi gula-fosfat yang merupakan intermediet dalam respirasi dan fotosintesis sertafosfolipid yang menyusun membran sel. Fosfor juga merupakan komponen nukleotida yang digunakan untuk energi metabolisme (ATP)DNA dan RNA. Gejala defisiensi P menyebabkan pertumbuhan menjadi kerdil saat tanaman muda dan warna daun hijau gelap (kadang-kadang hijau ungu gelap) dengan perubahan bentuk daun.Gejala lainnya terbentuk batang yang ramping tetapi tidak berkayu dan matinya daun tua. Potasium berada dalam tanaman dalam bentuk kation K+, yang berperan penting dalam regulasi potensial osmotik sel tanaman. K juga mengaktivasi beberapa enzim yang terlibat pada respirasi dan fotosintesis. Gejala defisiensi K ditunjukkan dengan klorosisnya daunatau bagian tepi daun, yang kemudian berkembang menjadi nekrosis pada bagian ujung daun. K dapat dimobilisasi kedaun muda, jadi gejala defisiensi awalnya tampak pada daun dewasa dekat dengan bagian basal tanaman. Daun menjadi keriting dan menggulung. Batang menjadi lemah, dengan internodus yang memendek. Organisme pengganggu tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, ataupun menyebabkan kematian pada tanaman. Menurut Putra (2011) organisme pengganggu tanaman yang sangat berperan menyebabkan penurunan hasil produktifitas perkebunan kakao adalah serangga. Menurut Supartha dkk (2008), serangga pengganggu tanaman perkebunan kakao di Indonesia adalah serangga penggerek buah kakao (PBK) dan kepik penghisap cairan buah kakao (Helopeltissp.). Hama serangga yang paling merugikan adalah serangan dari kelompok PBK yaitu Conopomorpha cramerella Snell. (Lepidoptera; Gracillariidae). Ciri-ciri buah kakao yang terserang hama PBK adalah buah tampak matang sebelum waktunya (berwarna setengah hijau dan setengah kuning). Buah menjadi lebih berat dan bila diguncang tidak terdengar suara ketukan antara biji dengan dinding buah. Hal itu terjadi karena timbulnya lendir dan kotoran pada daging buah dan rusaknya biji-biji di dalam buah akibat aktifitas larva C. cramerella. Hama penggerek kelapa sawit dapat merusak tandan. Hama ini diidentifikasi sebagai Tirathabarufivena Walker atau T. mundella Walker. Di IndonesiaTirathaba sp. dikenal sebagai hama penggerek tandan buah kelapa sawit baik di Indonesia maupun Malaysia yang menyebabkan fruit set rendah. Hama ini awalnya akan menyerang bunga dan buah muda. Praktek sanitasi yang buruk khususnya pada buah busuk menjadi tempat berkembang biak ideal hama. Gejala serangan ditandai dengan adanya kotoran ulat berupa butiranbutiran berwarna merah tua kecoklatan kemudian mengering. Adanya kotoran yang berwarna merah menandakan bahwa terdapat stadia ulat yang sedang aktif menggerek buah. Kotoran ulat bisa terdapat pada bunga jantan yang belum mekar atau pada bunga dan buah kelapa sawit. Menurut Berlian (2013) beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya produktivitas karet di indonesia adalah serangan hama penyakit. Penyakit akar putih (JAP) yang disebakan oleh patogen Rigidoporus microporus (R. microporus) merupakan penyakit penting pada tanaman karet. JAP dapat menyerang semua umur tanaman, tetapi lebih banyak pada kebun karet muda. Tanaman yang terserang daunnya akan tampak kusam, melengkung ke bawah, daun menguning, mudah rontok. Serangan berat menyebabkan akar busuk sehingga tanaman mudah rebah. Hama tanaman putih contohnya adalah Hama Bubuk Buah (Steptiadoderas hampeiFerr), hama ini menyerang dengan meletakkan telurnya kedalam biji kopi yang sudah mengeras sekitar tujuh hari, lalu berubah menjadi ular selama 14 hari dan 5 hari stadium kepompong. Diperkirakan hama ini dapat bertelur 35-55 butir dan terbang pada radius 350 meter sehingga kerugian akibat dari hama ini mencapai 40-50% dari total produksi. Untuk mengatasinya memusnahkan sumber-sumber infeksi dan pemutusan siklus hidup melalui petik buah kopi yang telah terserang hama buah bubuk. Praktikum TPT tahunan acara 3 tetang perawatan tanaman tanaman tahunan (kelapa sawit, karet, kakao dan kopi) dapat diamati bahwa perawatan yang dilakukan pada tanaman tahunan adalah pemupukan dengan menggunakan pupuk Urea, KCL, dan SP-36. Cara pemukannya yaitu dengan membuat lingkaran mengelilingi tanaman tahunan dan pupuk disebar di piringan tersebur secara memutar. Pemangkasan dilakukan dengan memotong cabang yang tidak produktif. Pengamatan yang dilakukan adalah mengamati indikasi pertumbuhan tanaman tahunan, defisiensi dan OPT. Keliling batang, jumlah pelepah dan jumlah tunas baru pada kelapa sawit adalah 340 cm, 25 dan tidak ada tunas baru. Keliling batang, jumlah pelepah dan jumlah tunas baru pada kakao adalah 65 cm, 8 dan tidak ada tunas baru. Keliling batang, jumlah pelepah dan jumlah tunas baru pada karet adalah 120 cm, 0 dan tidak ada tunas baru. Keliling batang, jumlah pelepah dan jumlah tunas baru pada kopi adalah 27 cm, 53 dan tidak ada tunas baru. Kelapa sawit mengalami defisiensi Mg dengan tanda tulang daun menguning dan daun kering. Kakao mengalami defisiensi Cu dengan ujung daun kering. Karet mengalami defisiensi N dengan tanda helai daun menguning dan daun kering. kopi mengalami defisiensi P dengan tanda tulang daun menguning. OPT pada kelapa sawit adalah ulat api dengan tanda daun berlubang. OPT pada kakao adalah ulat dengan tanda daun berlubang. OPT pada karet adalah rayap dengan tanda batang rapuh dan kopong. OPT pada kopi adalah kutu dompolan dengan tanda tulang daun terdapat putih putih seperi lilin. Hal tersebut sesuai dengan literatur yang ditulis oleh Wiryadiputra (2012) bahwa Hama penggerek buah kopi (PBKo, Hypothenemus hampei) (Coleoptera: Curcu-lionidae) merupakan hama utama yang sangat merusak pada budidaya kopi di seluruh dunia. Larva yang menetas akan segera menggerek keping biji (endosperma) kopi yang telah mengeras dan berkembang sampai menjadi dewasa pada liang gerekan dalam buah kopi. Setelah perlakuan tanaman tahunan diamati lagi pada Sabtu, 17 November 2018. Hasil pengamatan adalah tidak terjadi perubahan pada pertumbuhan tanaman karena jarak waktu antara pemberian pupuk dengan pengamatan terlalu dekat. Kelapa sawit dan kakao mengalami defisiensi Cu dengan ciri ciri ujung daun mengering sedangkan karet dan kopi mengalami defisiensi N dengan ciri daun menguning. OPT pada kelapa sawit adalah semut rangrang dengan tanda buah terkikis. OPT pada kakao adalah ulat grayak dengan tanda daun berlubang. OPT pada karet adalah tungau karet dengan tanda bercak daun berwarna coklat. OPT pada kopi adalah penggerek kopi dengan tanda buah hitam berlubang. E. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan Berdasarkan pemacaran acara 3 tentang Perawatan Tanaman Tahunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi) dapat disimpulkan bahwa : a. Cara pemupukan tanaman tahunan (kelapa sawit, karet, kakao, kopi) adalah dengan cara membuat piringan sesuai dengan umurnya lalu pupuk ditaburkan pada piringan tersebut. b. Pemangkasan atau purining adalah langkah pembuangan beberapa bagian pada tanaman seperti cabang dan ranting untuk mendapatkan bentuk tertentu, sehingga dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi agar cahaya matahari mampu menyinari, mempermudah mendeteksi hama penyakit, serta mempermudah proses panen tanaman tersebut. c. Organisme pengganggu tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, ataupun menyebabkan kematian pada tanaman. d. Defisiensi pada tanaman tahunan akan mengurangi hasil produksi dari tanaman tahunan itu sendiri maka harus dilakukan pemupukan secara berkala. 2. Saran Praktikum acara 3 Perawatan Tanaman Tahunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi) sudah berjalan dengan baik, diharapkan untuk setiap praktikan lebih fokus dalam melakukan praktikum. Para co-ass diharapkan dapat memberi penjelasan dengan lebih mendalam. IV. PENYADAPAN TANAMAN KARET A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Karet (Hevea brasiliensis) merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Brasil, Amerika Selatan. Karet pertama di Indonesia ditanam di Kebun Raya Bogor. Bagian yang dimanfaatkan dari karet adalah getahnya. Getah tanaman ini biasa dimanfaatkan untuk lateks, lump, dan crumb rubber. Hasil turunannya adalah ban, bola, sepatu, mainan karet, karet gelang, sarung tangan, dan lain sebaginya. Karet menjadi salah satu komoditas yang bernilai tinggi sehingga patut dibudidayakan. Hasil karet Indonesia biasa diekspor dan mendatangkan devisa yang cukup tinggi bagi Indonesia. Hal tersebut membuat budidaya karet memiliki prospek yang baik dimasa depan. Getah karet yang mampu dimanfaatkan dapat diambil dari pohon karet setelah melalui suatu proses. Proses tersebut disebut penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan pemutusan atau pelukaan pembuluh lateks sehingga lateks menetes keluar dari pembuluh lateks ke mangkuk penampungan yang dipasang pada batang karet. Proses penyadapan memerlukan teknik-teknik tertentu agar mendapatkan hasil dengan kualitas dan kuantitas optimal. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penting diadakan praktikum penyadapan karet. Hal ini dikarekan karet merupakan salah satu tanaman yang proses produksinya melalui tahapan penyadapan agar mendapatkan hasil. Praktikum ini sangat penting karena dengan mengetahui teknik penyadapan yang benar, diharapkan kedepannya apabila praktikan menjadi praktisi mengefisiensikan biaya produksi karet. 2. Tujuan Praktikum dalam bidang karet dapat Tujuan praktikum acara penyadapan tanaman karet ini adalah mahasiswa terampil dalam melakukan penyadapan tanaman karet dan mengetahui teknik penyadapan yang tepat. B. Metodologi Praktikum 1. Waktu dan Tempat Praktikum Praktikum acara penyadapan tanaman karet ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 November 2018 di Laboratorium Fakultas Pertanian UNS Jumantono. 2. Alat dan Bahan a. Alat 1) Mal Sadap 2) Pisau Sadap 3) Paku 4) Mangkok 5) Talang 6) Lateks 7) Meteran b. Bahan 1) Tanaman Karet. 3. Cara Kerja a. Menentukan Matang Sadap 1) Memilih pohon yang sudah matang sadap (umur 4,5-6 tahun, lilit batang minimal 45 cm, diukur 100 cm di atas pertautan okulasi (DPO)). b. Persiapan Buka Sadap 1) Mal sadap dipasang untuk mempermudah membuat bidang sadap 2) Pisau sadap berujung runcing dan bertangkai untuk menoreh kulit waktu menggambar bidang sadap 3) Talang sadap yaitu selebar 2,5 cm, panjang 8 cm berguna untuk mengalirkan lateks ke mangkok sadap 4) Memasang mangkok sadap untuk menampung lateks c. Pelaksanaan Penyadapan 1) Menyadap pohon karet menggunakan pisau sadap dari kiri atas ke kanan bawah sesuai gambar bidang sadap 2) Membuat kedalaman irisan sadap 1-1,5 mm dari cambium 3) Ketebalan sadap 1,5-2 mm setiap penyadapan 4) Penyadapan dilakukan pada pagi hari bila cukup terang C. Hasil Pengamatan Tabel 4.1 Hasil Penyadapan Karet No 1 Tanaman Karet Warna Lateks Putih Foto D. Pembahasan Karet (Hevea brasiliensis) merupakan tanaman perkebunan yang baik dalam konteks ekonomi masyarakat maupun sumber devisa non migas bagi negara. Karet merupakan tanaman yang berasal dari Brasil, Amerika Selatan. Damanik (2012), mengatakan bahwa Syarat tumbuh karet adalah terletak pada daerah antara 10o LU-10o LS dengan curah hujan 1500-4000 mm/tahun dengan rata-rata bulan kering 0-4 bulan pertahun, dan elevasi > 500 m diatas permukaan laut. Di Indonesia, karet banyak ditanam di Sumatra, Kalimatan, dan Jawa. Venkatachalam et al. (2013) mengatakan bahwa pohon karet memiliki tinggi sekitar 30-40m. Potensial produksinya sekitar 600-900 kg/ha. Bahan tanam karet adalah okulasi dua varietas. Karet memiliki batang yang lurus dan daun majemuk. Karet tidak memerlukan naungan pada semua fase hidupnya.Menurut Ulfah et al. (2015), terdapat beberapa syarat penyadapan karet. Penyadapan karet dikatakan baik apabila memproduksi lateks yang banyak, biaya yang rendah dan tidak mengganggu kesinambungan produksi tanaman. Syarat karet dapat disadap adalah pohon telah matang sedang. Hal tersebut dicirikan dengan keliling batang lebih besar dari 45 cm pada ketinggian 130 cm diatas kaki gajah pertautan okulasi dengan usia diatas 4-5 tahun. Dua sistem sadap karet yang umum dilakukan, yaitu sistem double cutting dan cacah runcah. Ismail et al. (2016) mengatakan bahwa Double cutting adalah metode penyadapan yang dilakukan secara bersamaan antara sadap ke bawah dan sadap ke atas. Sistem cacah runcah adalah sistem sadap karet yang dilakukan pada tanaman yang akan dibongkar (replanting). Menurut Ritonga (2016), langkah-langkah menyadapan adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah membuat garis sadar depan dan sadar belakang dengan membagi lingkar batang menjadi dua bagian. Langkah kedua adalah separuh lingkar batang diukur dengan arah Timur-Barat sehingga nantinya arah bidang sadap adalah Utara-Selatan. Langkah ketiga yaitu mal sadap dipasang pada garis sadar depan dan dibuat garis miring menurut mal sadap dengan pisau mal, dari garis sadar belakang sampai dengan garis sadar depan 0,5 S. Sudut kemiringan bidang sadap adalah 30-40º untuk bidang sadap bawah, dan 45º untuk bidang sadap atas. Langkah terakhir Penggambaran dilakukan setiap 6 bulan untuk mengontrol kemiringan dan konsumsi kulit. Berdasarkan hasil pengamatan, warna karet yang disadap adalah putih bersih pada saat masih berbentuk cair dan menjadi putih tulang saat sudah membeku. Warna putih tulang pada saat membeku ini bisa dipengaruhi adanya campuran kotoran-kotoran dari udara atau reaksi kimia yang telah terjadi selama proses pembekuan. Menurut Wiyanto (2013), warna merupakan salah satu parameter kualitas karet. Karet yang berwarna putih bersih memiliki kualitas diatas karet yang berwarna hitam atau keabuan. E. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : a. Syarat tumbuh karet adalah terletak pada daerah antara 10o LU-10o LS dengan curah hujan 1500-4000 mm/tahun dengan rata-rata bulan kering 0-4 bulan pertahun, dan elevasi > 500 m diatas permukaan laut. b. Karakteristik pohon karet adalah tingginya sekitar 30-40m, berbatang lurus, berdaun majemuk, berbahan tanam okulasi, dan tidak memerlukan naungan dengan potensial produksinya sekitar 600-900 kg/ha. c. Syarat karet dapat disadap adalah pohon telah matang sedang dengan ciri-ciri keliling batang lebih besar dari 45 cm pada ketinggian 130 cm diatas kaki gajah pertautan okulasi dengan usia diatas 4-5 tahun. d. Cara penyadapan adalah dengan membuat bidang sadap, memasang mal sadar, dan membuat garis-garis sadap. e. Berdasarkan hasil pengamatan, lateks yang dihasilkan berwarna putih. 2. Saran Berdasarkan pemaparan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya dilakukan perawatan yang benar terhadap pohon karet agar dapat dimanfaatkan selain untuk praktikum. DAFTAR PUSTAKA Adi, P. 2013. Kaya dengan bertani sawit. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Andoko, Agus dan Widodoro. 2013. Berkebun kelapa sawit "si emas cair". Jakarta: Agro Media Pustaka. Berlian I, Budi S, Hananto H. 2013. Mekanisme antagonisme Trichoderma spp. terhadap beberapa patogen tular tanah. Warta Perkaretan. 32(2): 74-82. Boerhendhy I, Khaidir A. 2010. Optimalisasi produktivitas karet melalui penggunaan bahan tanam, pemeliharaan, sistem eksploitasi, dan peremajaan tanaman. J Litbang Pertanian. 30(1) : 23-30. Damanik, Sabarman. 2012. Pengembangan karet (Havea brasiliensis) berkelanjutan di Indonesia. Perspektif 11(1) : 91-102 Firmansyah MA. 2010. Teknik pembuatan kompos. J Litbang Pertanian. 1(1) : 1—19. Gtuneland. 2011. Karakteristik fisik dan produksi kelapasawit (ElaeisguineensisJacq.) pada tiga agroekologi lahan. J Media Pertanian (1) : 2. Hidayat W. 2012. Manajemen pemupukan pada perkebunan kelapa sawit ( Elaeis guineensis Jacq.) di Tambusai Estate, PT. Panca Surya Agrindo, First Resources Ltd., Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Bogor : Institut Pertanian Bogor. 49-84. Ismail, Muhamad, Supijatno.2016. Penyadapan tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell Arg.) di Kebun Sumber Tengah, Jember, Jawa Timur. Bul. Agrohorti 4(3) : 257-265 Junedi H, Arsyad AR, Yulfita F. 2012. Pemupukan kelapa sawit berdasarkan potensi produksi untuk meningkatkan hasil tandan buah segar (tbs) pada Lahan Marginal Kumpeh. J Penelitian Universitas Jambi Seri Sains. 14(1) : 29-36. Pahan. 2015. Panduan lengkap kelapa sawit manajemen agribisnis dari hulu ke hilir. Bogor : Penebar Swadaya. Pramurjadi, Andy et al. 2017. Sistem pakar identifikasi gangguan organisme pengganggu tanaman dan defisiensi hara tanaman hias krisan. J Informatika Pertanian 26(2) : 67—90. Purwati MS. 2013. Respon pertumbuhan bibit kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) terhadap pemberian dolomit dan pupuk fosfor. Ziraa’ah. 36(1):2531. Putra IGAP, Ni Luh W, Ni Made S. 2011. Inventaris serangga pada perkebunan kakao (Theobroma cacao) laboratorium unit perlindungan tanaman Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. J Biologi. 14(1) : 19-24. Ritonga, Ali Imran.2016.Teknik penyadapan tradisional pada tanaman karet di Tapanuli Selatan. Jurnal Nasional Ecopedon 3(1) : 17-20 Sitorus UKP, Balonggu S, Nini R. 2014. Respons pertumbuhan bibit kakao (Theobroma cacao L.) terhadap pembibitan abu boiler dan pupuk urea pada media tanam. J Online Agroekoteknologi. 2(3) : 1021-1029. Stevanus CT, Jamin S, Thomas W. 2015. Peran unsur mikro bagi tanaman karet. Warta Perkaretan. 34(1):11-18. Supriyo A, Dirgahayuningsih R, dan Minarsih S. 2013. Kajian bahan humat untuk meningkatkan efisiensi pemupukan npk pada bibit kelapa sawit di tanah sulfat masam. J AGRITECH. 15(2) : 14—24. Susila KD. 2013. Studi keharaan tanaman dan evaluasi kesuburan tanah di lahan pertanaman jeruk desa Cenggiling, kecamatan Kuta Selatan. J AGROTOP. 3(2) : 13—20. Ulfah, Diana, Gt.A.R. Thamrin, Tri W.N. 2015. Pengaruh waktu penyadapan dan umur tanaman karet terhadap produksi getah (Lateks). Jurnal Hutan Tropis 3(3) : 247-252 Venkatachalam, Perumal, Natesan G., Palanivel S., dkk. 2013. Natural rubber producing plants : an overview.African Journal of Biotechnology 12(12) : 1297-1310 Wiryadiputra S. 2012. Keefektifan insektisida cyantraniliprole terhadap hama penggerek buah kopi (Hypothenemus hampei) pada kopi arabika. Pelita Perkebunan. 28(2): 100-110. Wiyanto, Nunung K. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas karet perkebunan rakyat. Jurnal Agribisnis Indonesia 1(1) : 39-58 Yan Fauzi et al. 2012. Kelapa sawit. Penebar Swadaya: Bogor. LAMPIRAN Pemupukan tanaman kopi Pemangkasan tanaman kelapa sawit Penyiraman pupuk tanaman karet Pemupukan tanaman kakao Pemupukan tanaman kelapa sawit Pemupukan tanaman karet Logbook acara 3 Logbook acara 1 Logbook acara 4 Logbook acara 2