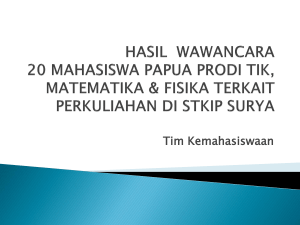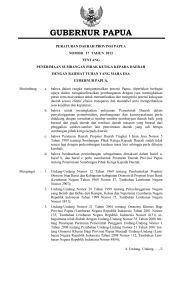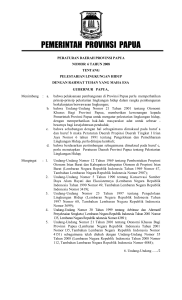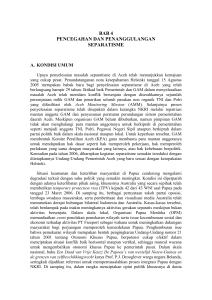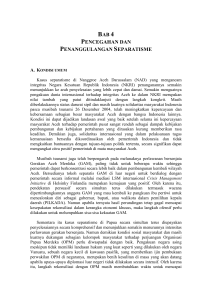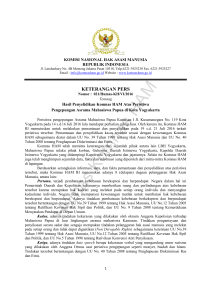OPERASI MILITER PAPUA Kondisi Politik Papua
advertisement

OPERASI MILITER PAPUA Kondisi Politik Papua Sebelum Menjadi Wilayah Indonesia. Tumbuhnya paham "nasionalisme Papua" di Irian Jaya mempunyai sejarah yang panjang dan pahit. Sebelum dan selama Perang Dunia II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan millinerian, mesianic dan "cargo-cultis". Mungkin yang paling terbuka dari gerakan seperti itu adalah gerakan "koreri" di kepulauan Biak, gerakan "were atau wege" yang terjadi di Enarotali dan gerakan "Simon Tongkat" yang terjadi di Jayapura. Berhadapan dengan kebrutalan Jepang pada waktu itu, gerakan koreri di Biak mencapai titik kulminasinya pada 1942 dengan sebuah proklamasi dan pengibaran bendera.1 Dengan masih didudukinya sebagian besar kepulauan Indonesia oleh Jepang, pemerintah Belanda di Nieuw Guinea dihadapkan kepada kekurangan personil yang. terlatih di berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pada tahun 1944 Resident J.P. van Eechoud yang terkenal dengan nama "vader der Papoea's" (Bapak orang Papua) mendirikan sebuah sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (bestuurscbool) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara l944 sampai 1949. Sekolah inilah yang melahirkan elit politik terdidik (borjuis kecil terdidik) di Nieuw Guinea. Residen J.P. van Eechoud mempunyai misi khusus untuk menanamkan nasionalisme Papua dan membuat orang Papua setia kepada pemerintah Belanda. Untuk itu setiap orang yang ternyata pro-Indonesia ditahan atau dipenjarakan dan dibuang ke luar Irian Jaya sebagai suatu tindakan untuk mengakhiri aktivitas pro Indonesia di IrianJaya. Beberapa orang yang menempuh pendidikan Eechoud dan kemudian meniadi terkemuka dalam aktivitas politik antara lain: Markus dan Frans Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Herman Wajoi, Silas Papare, Albert Karubuy, Mozes Rumainum, Baldus Mofu, Elieser Jan Bonay, Lukas Rumkorem, Martin Indey, Johan Ariks, Herman Womsiwor dan Abdullah Arfan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 ikut mempengaruhi para pemuda terdidik tersebut di atas yaitu antara lain Silas Papare, Albert Karubuy, dan Martin Indey. Pada tahun 1946 di Serui, Silas Papare dan sejumlah pengikutnya mendirikan organisasi politik pro-Indonesia yang bernama Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Di Manokwari pada 17 Agustus 1947 dilakukan upacara penarikan bendera merah putih yang dipimpin oleh Silas Papare. Upacara itu dihadiri antara lain oleh Johans Ariks, Albert Karubuy, Lodewijk dan Barent Mandatjan, Samuel Damianus Kawab, dan Franz Joseph Djopari. Upacara tersebut untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, seluruh peserta tersebut di atas harus masuk tahanan Polisi Belanda selama lebih dari tiga bulan. Pemerintah Belanda menghadapi tentangan yang berat dari organisasi PKII sebab mereka mengklaim seluruh Indonesia Timur termasuk West Nieuw Guinea (Irian Barat/Jaya) adalah wilayah Republik Indonesia. Dua nasionalis Papua lainnya yaitu Frans Kaisiepo dan Johan Ariks bergabung dengan Silas Papare. Johan Ariks kemudian menjadi orang yang sangat anti-Indonesia setelah mengetahui bahwa ada usaha dari Indonesia untuk mengintegrasikan Irian Jaya dengan Republik Indonesia dan bukan sebaliknya membantu kemerdekaan Irian Jaya sendiri. Pada 16-24Juli 1946 dilakukan konferensi Malino, hadir pada konferensi tersebut tokoh nasionalis Papua Frans Kaisiepo yang memperkenalkan nama "Irian" bagi West Nieuw 1 Bagian dari penjelasan fakta-fakta ini dikutip dari John RG Djopari, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993. Cerita tentang kehidupan pada Abad XIX di kawasan Papua dilukiskan secara lengkap dengan menarik oleh Kal Muler. Lihat Kal Muller, Mengenal Papua, Daisy World Book, Jayapura, 2008. Guinea dan secara tegas menuntut West Nieuw Guinea ke dalam Indonesia Timur. Tuntutan itu disampaikan dalam konferensi yang dipimpin oleh wakil pemerintah Belanda Dr. HJ. van Mook, namun hal ini ditolak oleh van Mook karena Belanda masih berkepentingan dengan Nieuw Guinea. Selain gerakan politik PKII, maka terdapat juga suatu gerakan pro-Indonesia yang disebut gerakan nasionalis dari Soegoro Admoprasodjo yang pada waktu itu menjabat sebagai direktur pendidikan pamongpraja di Kotanica-Hollandia. Soegoro membina dan menghimpun semua orang Jawa, Sumatera, Makassar, Bugis, dan Buton yang ada di Nieuw Guinea sebagai kekuatan yang pro-Indonesia. Kegiatannya itu kemudian diketahui oleh pemerintahan Belanda dan sebagai konsekuensinya, aktivitasnya dilarang. Ia diberhentikan sebagai direktur dan dikirim ke Batavia/Jakarta oleh Resident van Eechoud. Berbeda dengan PKII yang dibina Dr. Sam Ratulangi yang tengah menjalani pembuangan oleh Belanda ke Serui, maka pada 1954 dokter Gerungan mendirikan suatu gerakan politik di Hollandia yang bernama Komite Indonesia Merdeka (KIM). Gerakan atau organisasi politik itu dipimpin oleh sejumlah pemimpin Papua yaitu Marten Indey, Nicolaas Jouwe, dan Korinus Krey. Nicolaas Jouwe kemudian menjadi seorang pemimpin Papua yang antiIndonesia. Untuk mewujudkan dan menumbuhkan nasionalis Papua sebagai suatu misi dan cita-cita, van Eechoud melarang aktivitas PKII dan KIM, dan juga menangkap para pemimpinnya serta membuang mereka ke Makassar, Jawa,dan Sumatera. Mereka yang dibuang yaitu Silas Papare, Albert Karubuy, N.L. Suwages, Lukas Rumkorem dan Raja Rumagesang. Namun kegiatan PKII dan KIM terus berlanjut di bawah tanah dengan dipimpin oleh beberapa tokoh seperti Steven Rumbewas, Korinus Krey, Martin Indey, Abraham Koromat, Samuel Damianus Kawab, Elieser Jan Bonay, dan EIi Ujo. Untuk itu, Marten Indey, Kawab, Krey, dan Ujo pernah menikmati penjara untuk beberapa saat, tapi semangat perjuangan itu terus hidup dan dilanjutkan di bawah tanah, yaitu semangat pro-Indonesia atau semangat ingin menggabungkan Nieuw Guinea dengan Indonesia. ElieserJan Bonay kemudian menjadi Gubernur pertama Irian Jaya untuk kurang dari satu tahun (1961-1964) yang kemudian pada 1970 meninggalkan Irian Jaya dan menjadi pendukung dan tokoh OPM serta berdomisili di Belanda. Bonay pada mulanya adalah tokoh yang pro-Indonesia. Pada awal integrasi, ia dijadikan sebagai Gubernur Irian Jaya yang pertama. Namun, pada 1964, ia mendesak agar segera dilakukan Act of Free Choice di Irian Jaya bagi Kemerdekaan Irian Jaya sendiri dan desakan itu disampaikan ke PBB. Ia diberhentikan sebagai Gubernur dan diganti oleh Frans Kaisiepo. Pemberhentian tanpa menduduki posisi lain dalam jajaran pemerintahan apalagi status kepegawaiannya tidak diperhatikan oleh pemerintah dan akhirnya ia mengkoordinir berbagai kegiatan dan rapat "gelap" di Jayapura dan melakukan hubungan "rahasia" dengan para tokoh OPM di luar negeri. Setelah mengetahui bahwa ia akan ditangkap oleh pihak keamanan karena kegiatannya yang membantu OPM, maka ia memutuskan diri lari ke Belanda melalui Papua New Guinea. Untuk menghadapi PKII dan KIM, maka pemerintah Belanda mendirikan Gerakan Persatuan Nieuw Guinea dengan satu-satunya tujuan untuk menentang pengaruh Indonesia. Gerakan ini mempunyai sejumlah tokoh Papua yang terkenal, yaitu Markus Kaisiepo, Johan Ariks, Abdullah Arfan, Nicolaas Jouwe, dan Herman Womsiwor, di mana mereka itu kemudian menjadi pendukung yang kokoh bagi pemerintah Belanda dan nasionalisme Papua. Pada 1960 dibentuklah suatu "uni perdagangan" yang pertama di Nieuw Guinea yang bernama Christelijk Werkneemers Verbond Nieuw Guinea (Serikat Sekerja Kristen Nieuw Guinea) yang pada mulanya hanya berhubungan dengan pemerintah Belanda dan pekerjapekerja kontraktor Eurasia, dan dalam waktu yang singkat keanggotaan orang Papua menjadi 3.000 orang. Organisasi ini yang pada gilirannya bersama Gerakan Persatuan Nieuw Guinea membentuk dasar dan pemimpin dari Partai Nasional. Dalam tiga bulan menjelang akhir 1960, pemerintah Belanda membentuk beberapa partai dan organisasi atau gerakan politik sebagai perwujudan dari kebijakan politik dari Kabinet De Quay untuk mempercepat pembentukan Nieuw Guinea Raad melalui pemilihan umum, yaitu realisasi dari politik dekolonisasi untuk Nieuw Guinea yang dilakukan secara bertahap. Adapun berbagai partai dan organisasi atau gerakan politik tersebut adalah:2 (1) Partai Nasional (Parna) (Ketua Umum: Hermanus Wajoi) (2) Democratische Volks Partij (DVP) (Ketua: A. Runtuboy) (3) Kena U Embay (KUD) (Ketua: Essau Itaar) (4) Nasional Partai Papua (Nappa) (Anggota: NMC Tanggahma) (5) Partai Papua Merdeka (PPM) (Ketua: Mozes Rumainum) (6) Committee Nasional Papua (CNP) (Ketua: Willem Inury) (7) Front Nasional Papua (FNP) (Ketua: Lodewijk Ayamiseba) (8) Partai Orang Nieuw Guinea (PONG) (Ketua: Johan Ariks) (9) Eenheids partij Nieuw Guinea (APANG) (Ketua: L. Mandatjan) (10) Sama-Sama Manusia (SSM) (11) Persatuan Kristen Islam Radja Ampat (Perkisra) (Ketua: M.N. Majalibit) (12) Persatuan Pemuda-Pemudi Papua (PERPEP) (Ketua : AJF Marey). Partai Nasional (Parna) dipimpin oleh orang-orang yang beraliran nasionalis Papua yang menghendaki suatu pemerintahan sendiri dan secara tegas menolak penggabungan dengan Indonesia. Propaganda anti-Indonesia terus ditingkatkan, dimana pada saat itu West Nieuw Guinea akan diberikan pemerintahan sendiri (kemerdekaan) oleh Belanda pada 1970 dimana bentuk dan isi dari pemerintahan itu kemudian akan ditentukan. Janji ini yang menyebabkan sebagian dari pemimpin Papua tidak mengungsi ke negeri Belanda pada saat Belanda harus meninggalkan Irian Jaya, tapi mereka memutuskan untuk tinggal dan ingin memilih dan menerima kenyataan janji itu setelah Irian Jaya digabungkan dengan Indonesia. Beberapa pemimpin Parna yang terkenal adalah Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Herman Womsiwor, Frits Kirihio kemudian dikirim untuk belajar ke Belanda dan berubah pikirannya menjadi pro-Indonesia. Frits Kirihio kemudian berjuang untuk meyakinkan dunia bahwa West Nieuw Guinea merupakan bagian dari Indonesia, dan ia diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. Silas Papare menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan mereka membentuk suatu Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Silas Papare sangat aktif dalam kegiatan front ini dan diikutkan pada delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membicarakan masalah lrian Jaya pada 1922. Pada 1958 hingga 1961 sejumlah pemuda Papua melintas batas ke Indonesia, yang oleh pemerintah Indonesia diterima dan dijadikan atau dilatih menjadi tentara dalam rangka persiapan perebutan kembali Irian Jaya dari pemerintah Belanda. Beberapa pemuda yang terkenal pada waktu itu antara lain AJ. Dimara, Benny Torey, Marinus Imbury (almarhum), Zadrack Rumbobiar, Melkianus Torey, dan Metu-salim Fimbay. Akibat tekanan internasional sehubungan dengan adanya sengketa dengan Indonesia, pemerintah Belanda di Irian Jaya sesuai terpaksa mempercepat pembangunan infrastruktur teknis ekonomi, dengan anjuran pembentukan pasar bagi pertanian rakyat dan sama sekali menghindari campur tangan dari pencangkokan ekonomi Hindia Belanda. Juga menganjurkan dasar pengajaran yang dilakukan secara luas atas wilayah dan bersamaan 2 John RG Djopari, op cit., hal. 33. dengan itu dibentuk suatu elit-Papua (Irian Jaya) yang modern, meminjamkan dan merangsang supaya seia-sekata dalam mempercepat pengembangan masyarakat sehingga dapat dibentuk dewan daerah dan dewan Papua, penolakan kembali situasi kekuasaan dengan menggantikan para pejabat orang Indonesia di lrian Jaya mulai dari atas ke bawah dengan fungsionaris Belanda yang berkecimpung dalam struktur pemerintah daerah di Irian Jaya yang kemudian dialihkan kepada orang Irian Jaya. Selain itu, pihak Belanda juga mempercepat Papuanisasi dari kader rendah hingga menengah. Terutama di Hollandia dan Manokwari, para kader nasionalis Papua dibentuk menjadi elit-politik dengan kemampuan berdiskusi dengan baik. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia di Papua Nugini yang terkenal dengan Bully beef club yang melahirkan para pemimpin Partai Panggu yang nasionalis radikal di Perguruan Tinggi Administrasi Port Moresby. Pemilihan Umum untuk Nieuw Guinea Raad diselenggarakan pada 18-25 Februari 1961 Aktivitas partai politik dalam rangka pemilihan tersebut menonjol dan penting terutama di Hollandia dan Manokwari, sebab di kedua tempat tersebut banyak berdomisili orang-orang Belanda, Indo-Belanda, Indonesia (Ambon, Menado, Jawa, Makassar, Bugis, Buton, dll) serta kader-kader Papua yang terdidik (kader rendah dan menengah). Pada tanggal 5 April 1961, Nieuw Guinea Raad diresmikan atau disahkan untuk mulai bekerja. Kewenangan yang penting dari Nieuw Guinea Raad adalah hak petisi atau mengajukan permohonan, hak interpelasi atau meminta keterangan, menyampaikan nasehat tentang undang-undang dan peraturan umum pemerintah yang mengikat bagi Irian Jaya, tugas bantuan berdasarkan hak amandemen/usul perubahan terhadap ketentuan ordonansi-ordonansi, tugas-bantuan terhadap pelaksanaan dari anggaran yang berhubungan dengan tinjauan dan pengamatan pada umumnya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Nieuw Guinea Raad memiliki kekuasaan legislatif bersama dengan pemerintah dan mnelaksanakan beberapa pengawasan terhadap anggaran belanja. Dalam perencanaan pembentukan Nieuw Guinea Raad, Belanda menyadari bahwa lembaga itu pada awalnya mempunyai sarana latihan demokrasi. Pada tahun 1960, telah dibentuk sebuah batalyon sukarelawan Papua (Papua Vrtjwillegers Korps) dan berkedudukan di Arfai-Manokwari. Setelah pembentukan Nieuw Guinea Raad, pada awal 1962 dilanjutkan dengan pembentukan 10 dewan daerah (streekraad). Implementasi dari "demokrasi kolonial" ini bertujuan untuk menindas perasaan-perasaan pro-lndonesia. Masalah Nieuw Guinea terus menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda, dimana Belanda terus melaksanakan politik dekolonisasi dan ingin menjadikan Nieuw Guinea sama kedudukannya dengan Suriname dan Antillen. Sengketa yang berkepanjangan itu mendorong Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Joseph Luns, pada 1961 mengajukan suatu rencana pemecahan masalah Nieuw Guinea pada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sidang Umum pada 28 November 1961. Rencana Luns terdiri dari 4 (empat) pasal sebagai berikut. Pertama, harus ada jaminan tentang adanya suatu undang-undang penentuan nasib sendiri bagi orang Papua/IrianJaya. Ke dua, harus ada kesediaan sampai terbentuknya pemerintah dengan persetuiuan internasional. Ketiga, sehubungan dengan kesediaan tersebut juga akan diberikan kedaulatan. Keempat, Belanda akan terus membiayai perkembangan masyarakat, ke taraf yang lebih tinggi.3 Secara garis besar rencana ini mengandung pengertian bahwa perlu ada jaminan bagi orang Papua untuk menentukan nasibnva sendiri, dan dunia internasional menjamin terbentuknya suatu pemerintahan yang berdaulat, dan untuk itu Belanda memikul beban pembangunan/pengembangan masyarakat Papua ke taraf yang lebih tinggi/baik. Sebelum 3 Ibid., hal 35. rencana Dr. Joseph Luns tersebut dibuat pada Oktober 1958 dalam suatu konferensi antara para pejabat Belanda dan Australia, dicapailah suatu kesepakatan adanya kerjasama untuk pembentukan "Persatuan Melanesia" (Melanesische Unie), yang mencakup wilayah-wilayah Nieuw Guinea, Bismarck, dan Kepulauan Solomon sebagai suatu federasi. Tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut dari usaha persatuan itu. Satu tahun kemudian diadakan lagi suatu konferensi antara Belanda dan Australia di Canbera pada 2l-22 Oktober 1959 dan dilanjutkan di Hollandia pada Maret 1960, dengan agenda dasar mendiskusikan berbagai kemungkinan untuk mempersatukan Nieuw Guinea (wilayah Belanda dan Australia) menjadi satu negara di kemudian hari dan pemerintah Australia menyetujuinya. Usaha gagal dilakukan karena Indonesia terus menuntut pengembalian Nieuw Guinea sehingga mendesak Dr. Joseph Luns untuk membuat rencana tersebut di atas. Di Nieuw Guinea, sebagai jawaban atas rencana Luns yang akan didiskusikan di PBB, maka 5 (lima) dari anggota Nieuw Guinea Raad yang dipimpin oleh Mr. de Rijke merancangkan suatu manifesto dan membentuk suatu Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang. Komite ini menyelenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh 70 orang Papua terdidik. Dalam pertemuan ini, di Hollandia menghasilkan: Bendera Nasional Papua, lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", nama bangsa "Papua" dan nama negara "West Papua atau Papua Barat".4 Pekerjaan Komite Nasional itu, hasilnya kemudian diajukan kepada Nieuw Guinea Raad dan segera mendapatkan persetujuannya. Mr. de Rijke mempunyai peranan yang besar dalam melahirkan hasil dari Komite Nasional tersebut atas. Hasil ini menyebabkan pemerintah Belanda menunjukkan simpati penuh serta dukungan atau bantuan mereka pada aliran nasional yang tumbuh di Nieuw Guinea atau IrianJaya, karena Belanda yakin bahwa dengan politik dekolonisasi semacam ini akan membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa tuntutan-tuntutan dari Indonesia untuk mengembalikan Nieuw Guinea itu tidak berdasar, dan akan membuka jalan ke arah transisi dalam perdamaian untuk mencapai dominasi neokolonial. Pada 1 November 1961, bendera nasional Papua dikibarkan sejajar atau bersamaan dengan bendera Belanda dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan pada saat itu. Kegiatan itu mendapatkan publisitas dengan cepat dan meluas baik di Nieuw Guinea, maupun ke penjuru dunia. Untuk kepentingan publisitas, dicetak, dan dibuat bendera dalam berbagai ukuran, lagu kebangsaan, dan logo bendera dalam berbagai ukuran yang disebarluaskan teruama kepada seluruh masyarakat Papua mulai dari kota sampai ke kampung-kampung yang dapat dijangkau oleh aparat pemerintah. Kegiatan dari Komite Nasional tersebut mendapatkan kritik dari sekelompok orang Papua, karena mereka menilai bahwa Komite Nasional belum sepenuhnya mewakili seluruh rakyat Papua, dan tindakan yang diambil atau dilakukan tergesa-gesa. Kelompok itu kuatir terhadap rencana Luns apabila tidak diterima dalam Sidang Umum PBB (28 Oktober 196l) sehingga mereka mengajukan alternatif lain seandainya rencana Luns itu benar-benar demikian, maka pemerintah Belanda harus menghormati janjinya pada tahun 1960 yaitu pemberian pemerintahan sendiri atau kemerdekaan kepada bangsa Papua, dan bila perlu di bawah bimbingan Belanda. Perlu dicatat pula bahwa Batalyon Sukarelawan Papua yang dibentuk pada 1960 dan berkedudukan di Arfai-Manokwari itu selain merupakan embrio dari Tentara Nasional Papua, juga dipersiapkan untuk menghadapi konfrontasi bersenjata dengan Republik Indonesia. 4 Penjelasan tentang penggunaan nama Papua bisa dibaca secara panjang lebar dalam Yorrys Th. Raweyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka, Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2002, hal. 1-8. Indonesia Merebut Papua Dari Belanda Untuk menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda di atas, maka Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 196l di Yogyakarta, yang isinya sebagai berikut: Pertama, gagalkan pembentukan "Negara Papua" buatan Belanda kolonial. Kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan Kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Dalam piudatonya, Soekarno menyatakan, “Bangsaku sekalian! Di Sumatera, di Jawa, di Borneo, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dari Sabang sampai Merauke!”.5 TRIKORA merupakan momentum politik yang penting, sebab dengan TRIKORA maka pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian di PBB yang dikenal dengan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 mengenai Nieuw Guinea. Supaya pemerintah Belanda tidak malu maka penyerahan Nieuw Guinea kepada Indonesia dilakukan melalui UNTEA yaitu suatu badan PBB yang dibentuk untuk itu. Penyerahan ini dilakukan pada 1 Mei 1963. Sedangkan pemerintah Belanda menyerahkan penyelenggaraan administrasi pemerintah kepada UNTEA pada 1 Mei 1962.6 Isi perjanjian tersebut antara lain, pertama, apabila PBB telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaannya atas Irian Jaya kepada UNTEA. Kedua, terhitung 1 Mei 1963, UNTEA sebagai pemikul tanggung jawab administrasi pemerintah di lrian Jaya menyerahkan kepada Indonesia. Ketiga, untuk akhir 1969, di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Cboice dalam mana orang Irian Jaya dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan status/kedudukan yang lain. Keempat, Indonesia dalam tenggang waktu itu akan mengembangkan/membangun kebersamaan orang Irian Jaya, sehingga orang Irian Jaya pada akhir 1969 akan menentukan status negerinya. Secara garis besar ke-4 butir tersebut di atas menyatakan tentang pengalihan pengurusan Nieuw Guinea dari Belanda kepada Indonesia melalui UNTEA pada 1 Mei 1963. Paling lambat pada akhir 1969 harus dilakukan pemilihan bebas untuk menentukan nasib Nieuw Guinea oleh orang Papua sendiri apakah bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri (merdeka). Indonesia berkewajiban untuk membangun dalam kurun waktu itu (dari 1963 sampai 1969) sampai pada pelaksanaan pemilihan bebas. Menurut Pasal XVIII Perjanjian New York (Indonesia-Belanda) tahun 1962, memuat ketentuan rinci mengenai pelaksanaan hal penentuan nasib sendiri (Act of Free Choice) yang diatur untuk dibuat oleh Indonesia dengan"nasehat, bantuan, dan partisipasi" PBB yang meliputi 4 butir sebagai berikut. Pertama, konsultasi atau musyawarah dengan sembilan dewan perwakilan mengenai prosedur dan cara-cara untuk mengetahui kebebasan pernyataan kehendak rakyat. Kedua, 5 6 John RG Djopari, op cit., hal 119. Uraian detil mengenai upaya pengambilan Papua dari tangan Belanda dari sudut pandang pemerintah Indonesia bisa dilihat pada Baharuddin Lopa, Jalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat, PN Percetakan & Periklanan Daya Upaya, Jakarta, 1962. Buku lain yang juga banyak mengungkap sisi heroisme dari pihak Indonesia bisa dilihat dari buku biografi Benny Murdani dan si Pending Emas Herlina. Sedangkan catatan proses politik yang lebih lengkap bisa dilihat pada Dr. PBR de Geus, Masalah Irian Barat: Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer, Yayasan Jayawijaya, Jakarta, 2003. Baca juga tulisan Tarmidzy Thamrin tentang sejarah penggabungan Papua dari yang tadinya berada di bawah struktur pemerintahan Belanda ke Indonesia dalam Drs. H. Tarmidzy Thamrin, Boven Digul: Lambang Perlawanan Terhadap Kolonialisme, CISCOM-Cottage, Surabaya, 2001. Sedangkan sisi rekayasa dan operasi intelijen yang dilakukan untuk menggagalkan Pepera bisa dilihat dalam Yorrys Th Raweyai, op cit. dan juga Aziz Ahmadi (ed), Feisal Tanjung: Terbaik Untuk Rakyat, Terbaik Bagi ABRI, Penerbit Yayasan Dharmapena Nusantara, Jakarta, 1999, hal. 222-253. dalam jangka waktu ditetapkan oleh persetujuan tersebut, ditentukanlah tanggal yang pasti untuk pelaksanaan Act of Free Choice. Ketiga, suatu formulasi yang jelas sehingga penduduk dapat menentukan apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia. Keempat, suatu jaminan bagi semua penduduk pribumi untuk ikut memilih dalam rangka penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktek internasional. Indonesia menurut Pasal XXII perjanjian itu juga akan menjamin hak-hak penduduk Irian Barat, termasuk hak-hak dan kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk bergerak dan berkumpul. Sesaat sebelum TRIKORA dicetuskan oleh Presiden Soekarno, terjadi penolakan PBB atas tuntutan Indonesia mengenai persoalan Irian Jaya pada akhir 1957. Saat itu, dilakukan kebijaksanaan dan tindakan menasionalisasikan seluruh perusahaan Belanda yang ada di Indonesia pada awal tahun 1958. TRIKORA juga merupakan ajang bagi terciptanya serangan-serangan militer terbatas dari Indonesia melawan Belanda di Irian Barat pada akhir tahun 1961 sehingga ikut mempercepat pencapaian perjanjian tersebut di atas antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat atau Nieuw Guinea menanggapi usul-usul Ellsworth Bunker. Pada tahun 1962, para elit Papua mulai ragu-ragu, bimbang dan bingung dengan keputusan 15 Agustus 1962 (Perjanjian New York) bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil-alih pemerintahan di Irian Barat menyusul delapan bulan pengawasan dari badan PBB yang bernama UNTEA. Pada bulan September 1962, dilakukan Konggres Nasional yang didorong oleh ketua Parna Herman Wajoi dan anggota Nieuw Guinea Raad Nicolaas Tanggahma. Kongres tersebut diikuti 90 elit politik Papua (pemimpin-pemimpin rakyat) dan memutuskan untuk menerima perjanjian 15 Agustus 1962 dengan keraguan. Kongres ini pada akhirnya menyetujui kerja sama dengan PBB dan pemerintah Indonesia, dan menuntut UNTEA untuk menghormati bendera dan lagu nasional Papua dan bahwa pemilihan umum harus diadakan pada 1963 segera setelah masa kerja resmi dari UNTEA. Berbagai perasaan yang diekspresikan pada masa itu adalah tidak pro-Belanda, tidak proIndonesia, tapi pro-Papua. Mereka merasa dikhianati oleh Belanda dan merasa kuatir terhadap nasionalis-Indonesia yang sudah mulai memberi kesan bahwa tidak ada keperluan untuk mengadakan pemilihan umum, kaum elit tersebut mengarahkan kepercayaannya kepada PBB. Tampak jelas pemerintah Belanda berupaya menumbuhkan nasionalisme di Nieuw Guinea menghasilkan 3 (tiga) kelompok borjuis/elit politik kecil Papua terdidik yang berorientasi politik. Antara lain kelompok Pro-Papua dan pro-Indonesia. Yang pro-Papua terbagi dua yaitu yang kerjasama dengan Belanda dan yang tidak kerjasama dengan Belanda. Mereka yang "pro-Papua dan kerja sama dengan Belanda" adalah mereka yang pada saat Belanda harus meninggalkan Irian Barat ikut berimigrasi ke negeri Belanda seperti: Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe dan kawan-kawan beserta keluarganya, sekalipun kemudian dari negeri Belanda mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. Mereka yang"proIndonesia" adalah mereka yang berjuang untuk mengintegrasikan Irian Barat denganIndonesia seperti Silas Papare, Alben Karubuy, Marten Indey, Lukas Rumkorem, dan kawan-kawannya. Sedangkan mereka yang "pro-Papua dan tidak kerjasama dengan Belanda" adalah mereka yang menantikan realisasi janji Belanda pada tahun 1960, dan menantikan pelaksanaan AFC, di Irian Barat pada 1969 seperti Johan Ariks, Herman Wajoi, Mori Muzendi, Willem Inurf, Nicolaas C. Tanggahma, Izaac Hindom, Permenas Hans Torey, Mozes Rumainum, Baldus Mofu, Aser Demotekay, Tontji Meset, Abdullan Arfan, Clemens Kiriwaib, FKT Poana, Terianus Aronggear, Dolf. A. Faidiban, Alex Robert Wamafma, Johanes Rombobiar, A. Mambrisau dan kawan-kawan. Papua di Bawah UNTEA UNTEA mulai menjalankan roda pemerintahan di Irian Barat dengan berbagai kesulitan yang terus dihadapi sebagai konsekuensi dari proses peralihan kekuasaan. Mandat utama UNTEA adalah pertama, memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kedua, mengumumkan dan menerangkan secara luas semua ketentuan dalam persetujuan Indonesia dan Belanda serta memberitahukan kepada penduduk Papua mengenai penyerahan pemerintahan kepada pihak Indonesia. Termasuk mengenai penentuan nasib sendiri sebagaimana telah dicapai dalam persetujuan tersebut. UNTEA memeiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan baru dan mengubah peraturan yang telah ada sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada padanya. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mempekerjakan pegawai bangsa Indonesia maupun Belanda dalam berbagai kedinasan. Perkecualian diberlakukan untuk jabatan tertinggi seperti direktur departemen, residen dan kepala polisi harus dijabat oleh pejabat berkebangsaan selain Indonesia dan Belanda.7 Selain para pejabat sipil internasional, UNTEA terpaksa bekerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia di Irian Barat yang waktu itu dipimpin Sudjarwo Tjondronegoro, SH serta perwakilan Belanda yang dipimpin LJ. Goedharta. Pemerintahan UNTEA akhirnya dapat berjalan lancar dan relatif tenang serta damai. Namun demikian terdapat beberapa insiden yang dapat ditanggulangi yaitu di Sorong dan Manokwari. Keberhasilan UNTEA itu ditandai dengan antara lain berjalannya semua dinas umum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban, dipertahankannya stabilitas perekonomian dengan persediaan barang-barang pokok yang cukup. Selesainya berbagai proyek umum seperti rumah sakit, dermaga, sekolah, pusat penelitian pertanian, penflnpanan air minum, gedung perwakilan ralyat dan gedung pengadilan, perluasan jalan dan lapangan terbang. UNTEA benar-benar melaksanakan rugasnya dengan baik sehingga segala sesuatu dipersiapkan dan pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat sepenuhnya kepada Pemerintah Republik. Sebelum penyerahan kekuasaan kepada Indonesia, pada Desember 1962, suatu delegasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang Irian Barat (Papua) yang dipimpin oleh Elieser Jan Bonav mendesak agar penyerahan kekuasaan oleh UNTEA kepada Indonesia dilakukan sebelum tanggal 3l Desember 1962. Delegasi itu menyampaikan usulnya kepada pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, dan Sekretaris Jenderal PBB. Usul tersebut ditolak oleh Belanda dimana Perdana Menteri De Quay menyatakan bahwa perjanjian New York harus dihormati dan untuk itu harus menunggu hingga 1 Mei 1963. Sekretaris Jenderal PBB menolak karena menurut peraruran tata tertib PBB bahwa suatu perutusan yang ingin menghadap haruslah disponsori oleh sebuah negara anggota PBB. Indonesia harus bersikap netral di sini agar tidak timbul penilaian yang salah terhadap Indonesia, sehingga delegasi itu kembali tanpa diterima oleh Sekretaris Jenderal PBB sejak tanggal 19 Desember 1962. Berbagai demonstrasi pro-Indonesia muncul di berbagai kota seperti Kotabaru, Manokwari, Ransiki, Biak, Merauke, Enarotali dan Kokonao yang pada intinya menuntut perpendekan masa pemerintahan IINTEA. 7 Pemerintahan UNTEA sendiri dibagi dalam 8 departemen yang terdiri dari Department of Cultural Affairs (including Education), Department of Economic Affairs, Department of Finance, Department of Internal Affairs, Department of Public Health, Department of Public Works, Department os Social Affairs and Justice, dan Department of Transport and Power. Sedangkan untuk dukungan administrasi, pemerintahan UNTEA dijalankan oleh sebuah sekretariat pemerintah yang strukturnya sama dengan di masa pemerintahan Belanda yang masingmasing dikepalai oleh seorang residen. Ada enam divisi yaitu Hollandia (Jayapura), Biak, Manokwari, Fak-Fak dan Central Highlands (Pegunungan Jayawijaya). Lihat John RG Djopari, op cit., hal. 55. Pada 14 Januari 1963 di Kotabaru, suatu delegasi yang dipimpin oleh 18 pemimpin rakyat menyampaikan suatu pernyataan kepada Administrator UNTEA, Dr. Djalal Abdoh yang berisikan, “Kami rakyat Irian Barat dengan ini menyatakan: Pertama, menuntut perpendekan pemerintahan UNTEA. Kedua, berggabung segera kepada Republik Indonesia secara mutlak dan tanpa syarat. Ketiga, setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945. Keempat, menghendaki adanya negara kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Kelima, menghendaki otonomi yang seluasluasnya dalam Republik Indonesia bagi wilayah Irian Barat.” Pada 15 Januari 1963, terjadi demonstrasi rakyat Merauke yang menimbulkan insiden yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka ketika anggota Polisi Irian Barat di bawah pemerintahan UNTEA melepaskan tembakan terhadap Bendera Merah Putih yang dibawa oleh para demonstran untuk membubarkan mereka, hal itu disambut dengan protes keras oleh Komandan Pasukan kontingen Indonesia Kolonel Sudarto yang menganggap bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Sebelum itu, yaitu pada awal Januari 1963, rakyat Irian Barat yang pro-Indonesia terutama di Kotabaru dibagi-bagikan bendera Merah Putih, lencana Garuda Pancasila dan Gambar Presiden Soekarno. Adapun tuntutan mereka dengan berbagai resolusi maupun pernyataan politiknya adalah penggabungan dengan Republik Indonesia secara mutlak dan tanpa syarat. Dan, perpendekan masa pemerintahan UNTEA di Irian Barat serta penolakan terhadap plebisit. Pada Oktober 1962, di Sorong terjadi insiden antara TNI Patimura di bawah pimpinan Lettu Nusi dengan polisi setempat dipimpin oleh Letnan G. Dimara. Insiden tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh UNSF-UNTEA. Juga pada Desember 1962, di Manokwari, Batalyon Papua atau PVK melakukan penyerangan terhadap pasukan Indonesia dari Kodam Brawijaya yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom dan kawan-kawan, di mana oleh LNSF-UNTEA Awom dan 20 temannya diberhentikan dari PVK setelah terlebih dulu dipenjarakan selama satu bulan. Walaupun dalam perjalanan pemerintahan UNTEA dihadapkan kepada berbagai permasalahan, namun dapat dikatakan bahwa UNTEA berhasil dalam tugasnya dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Indonesia dengan baik sesuai dengan persetujuan New York seperti pada lampiran II. Papua di Bawah Indonesia dan di Jaman Orde Baru Setelah daerah Irian Barat secara de jure dan de facto berhasil dikembalikan ke negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka wilayah kekuasaan Republik Indonesia meliputi Sabang-Merauke yaitu seluruh wilayah bekas jajahan pemerintahan Belanda. Sehubungan dengan itu pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden (Pen.Pres) Nomor 1 Tahun 1963 sebagai kebijaksanaan untuk segera melaksanakan pemerintahan di wilayah Irian Barat atau Irian Jaya dalam masa peralihan sehingga susunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Irian Jaya sarna dengan daerah Indonesia lainnya. Penpres Nomor 1 Tahun 1963 ini adalah ketentuan pokok mengenai pemerintahan dalam masa peralihan dengan memperhatikan Penpres Nomor 1 Tahun 1962 dan UU Nomor 1 Tahun 1957 serta beberapa ketentuan atau peraturan lainnya mengenai pemerintahan daerah. Dalam Pasal 4 Penpres No 1 tahun 1963 dijelaskan bahwa, Pemerintah Afdeling, Onderafdeling dan Distrik termasuk badan perwakilannya yang ada menjelang penyerahan Pemerintahan seluruhnya kepada Republik Indonesia, membantu Pemerintah Propinsi Irian Barat menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing menurut petunjuk Gubernur. Jelaslah bahwa struktur pemerintahan di tingkat Afdeling, Onderafdeling dan Distrik belum diubah atau disesuaikan dengan struktur pemerintahan di daerah Indonesia lainnya. Keadaan Politik dan Keamanan Sebelum bergabung dengan Indonesia, di bawah pemerintahan Belanda telah terbentuk beberapa organisasi atau partai politik yang telah memilih Niew Guinea Raad. Partai-partai politik tersebut sebenarnya dengan sendirinya dengan peralihan kekuasaan dari Belanda ke UNTEA dan dari UNTEA ke Indonesia sudah tidak berfungsi lagi. Namun karena statusnya yang mengambang dan membutuhkan penegasan tentang status tersebut, maka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pembinaan politik dalam negeri, pada 1 Desember 1963 para wakil rakyat Irian Barat mengadakan musyawarah di Kotabaru (Jayapura) membicarakan tentang keamanan daerah yang berhubungan dengan perkembangan politik dewasa itu. Sebagai tindak lanjut ke arah keamanan politik demi stabilisasi dan normalisasi sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1963 yang berlaku khusus untuk Irian Barat, maka musyawarah itu telah menyetujui untuk mengeluarkan pernyataan tentang pembubaran semua organisasi politik di Irian Barat. Adapun isi dari pernyataan itu adalah sebagai berikut: PERNYATAAN I. Bahwa Daerah Irian Barat adalah sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. II. Bahwa hanya ada satu dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945, sedang Manipol merupakan haluan negara dan Pancasila merupakan ideologi negara. III. Bahwa semua ideologi negara yang berhaluan lain atau tidak sesuai dengan dasar-dasar yang sah dari Negara Republik Indonesia sebagai yang tersebut di atas maka itu adalah merupakan alat pemecah kesatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan apa yang telah ditandaskan di atas dan sesuai pula dengan keinginan rakyat Irian Barat untuk tetap bersatu-padu dengan daerah-daerah lain di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dipisah-pisahkan lagi, maka dengan ini kami menyatakan bahwa: (1) Semua partai-partai politik atau organisasi-organisasi politik lainnya yang didirikan pada waktu penjajahan Belanda mulai terhitung tahun 1950 s/d Agustus 1962, dinyatakan bubar, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan politik pada dewasa ini. (2) Partai-partai politik dan organisasi-organisasi politik lainnya yang menyatakan bubar adalah i. Commite National Papua ii. Front Nasional Papua (FNP) iii. Nasional Partij Papua (Nappa) iv. Partai Nasional (Parna) v. Democratische Volks Partij (DYP) vi. Panai Papua Merdeka ePM) vii. Kena U Embay (KUE) (3) Tanggal pembubaran mulai terhitung I Mei 1963 tepat dengan hari kembalinya Irian Barat ke wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Demikianlah pernyataan ini dibuat oleh kami bersama di Kotabaru pada tanggal yang tersebut di atas. Kotabaru/Irian Barat, 1 Desember 1963. Kami yang bertanda: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Willem Inury (ttd) mantan Ketua Komite Nasional Papua Lodewijk Ajamiseba (ttd) mantan Ketua Umum Front Nasional Papua (FNP) Nicolaas M.C. Tanggahma (ttd) mantan Anggota Nasional Partai Papua (Nappa) Hermanus Wajoi (ttd) mantan Ketua Umum Partai Nasional (Parna) Manuel Waromi (ttd) mantan Sekretaris Democratische Volks Partij (DVP) Mozes Rumainum (ttd) mantan Ketua Umum Partai Papua Merdeka (PPM) Pilatus Keratua (ttd) mantan Penasehat Kena U Embay (KUE) Essau Ittar (ttd) mantan Ketua Kena U Embay (KUE) Pembubaran partai politik itu merupakan suatu langkah penting yang berkaitan dengan usaha memantapkan proses integrasi dengan Indonesia, sebab partai-partai politik tersebut merupakan produk dari sistem pemerintahan Belanda. Sejumlah pernyataan kemudian dilakukan oleh rakyat Irian Jaya. Pernyataan rakyat itu dimulai di Manokwari pada 9 Oktober 1962. Rincian banjirnya pernayataan itu adalah sebagai berikut. Pada 1962 terdapat 2l pernyataan, pada 1963 terdapat 25 pernyataan, pada 1964 terdapat 7 pernyataan, pada 1965 terdapat 4 pernyataan, pada 1968 terdapat 3 pernyataan, pada 1967 terdapat 23 pernyataan, pada 1968 terdapat 35 pernyataan. Jadi jumlah keseluruhan pernyataan rakyat yang merupakan kebulatan tekad untuk berintegrasi dengan Indonesia ada 118 pernyataan rakyat. 8 Pada hakekatnya,lahirnya berbagai pernyataan tersebut merupakan hasil gemilang yang dicapai oleh pemerintah Indonesia melalui direktorat khusus atau direktorat sosial politik dan lembaga Operasi Khusus Irian Barat (OPSUS) untuk mencapai kemenangan pada Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969. Selagi dilakukan penggalangan dan pembinaan ke arah integrasi dengan Indonesia terutama oleh OPSUS, maka di pihak lain para kader nasionalis Papua yang dibentuk oleh Belanda dulu juga menghimpun kekuatan dengan membentuk organisasi atau perkumpulan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Barat terlepas dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Di Jayapura, dibentuklah suatu organisasi dengan bentuk gerakan di bawah tanah oleh Aser Demotekay, mantan kepala distrik Demta Kabupaten Jayapura pada 1963. Gerakan ini diberi nama Gerakan menuju Kemerdekaan Papua Barat. Di Manokwari pada 1964 terbentuk sebuah gerakan yang diberi nama "Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat" yang oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak keamanan dan kejaksaan disebut sebagai "Organisasi Papua Merdeka" atau OPM. Kedua gerakan yang dibentuk itu mulai melakukan gangguan terhadap keamanan atau mulai melakukan pemberontakan baik secara radikal maupun secara pembinaan ideologi Papua Merdeka atau Papua Barat mulai dari 1963 sampai sekarang, namun dalam hal ini penulis hanya membatasi diri pada aktivitas pemberontakan selama 20 tahun, yaitu dari 1964 sampai 1984. Selanjutnya mengenai Act of Free Choice atau PEPERA itu dilaksanakan pada 1969. Musyawarah penentuan pendapat rakyat Irian Barat dimulai di Merauke pada 14 Juli dan 8 Ibid., hal 73. berakhir di Jayapura pada 2 Agustus 1969. Musyawarah yang diselenggarakan di 8 kota di IrianJaya itu disaksikan utusan PBB bernama Dr. Fernando Ortiz-Sanz, duta besar dari Bolivia untuk PBB yang oleh Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas yang berkaitan degan palaksanaan Act of Free Choice di Irian Jaya pada 1969. Untuk mengatur bagaimana Act of Free Choice dilaksanakan di Irian Jaya, maka Ortiz-Sanz tiba di Jayapura pada 22 Agustus 1969 dengan tiga orang staf ditambah atau didampingi Mr. Sudjarwo Tjondronegoro, pembantu khusus Menteri Luar Negeri Indonesia untuk masalah Irian Jaya. Setelah melakukan kunjungan ke wilayah dan memperoleh data tentang cara pelaksanaan PEPERA, maka pada tanggal 1 Oktober 1968 sebagai wakil PBB Ortiz-Sanz menerima bentuk musyawarah rakyat yang dilakukan pada 1969 nanti. Dewan Musyawarah PEPERA yang dibentuk pada 8 kota di Irian Jaya itu mewakili berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Jumlah anggota Dewan Musyawarah PEPERA sebanyak 1.025 orang dari jumlah penduduk sebesar 809.337 orang. Selain wakil dari PBB atau Ortiz-Sanz, maka pelaksanaan PEPERA tersebut disaksikan juga oleh duta besar dari Thailand, Belanda, Australia, Jerman Barat, Selandia Baru, dan Burma. Walaupun terjadi beberapa insiden yang berupa protes maupun demonstrasi pada hari penyelenggaraan PEPERA di Merauke, Fak-Fak, Manokwari, Paniai dan Jayapura, acara musyawarah itu dapat berjalan dengan sukses dimana rakyat Irian Jaya melalui Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) secara aklamasi memutuskan untuk bergabung ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berintegrasi dengan berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Sebelum PEPERA diselenggarakan, pada tanggal 12 Februari 1969 di Jayapura diselenggarakan suatu demonstrasi masyarakat yang secara tertib menuju ke kediaman Ortiz-Sanz dengan menyerahkan sebuah resolusi untuk menuntut penyelenggaraan pemilihan pada 1969 tidak secara musyawarah tetapi menurut ketentuan Perjanjian New York yaitu dengan cara one man one vote. Juga resolusi yang disampaikan itu menyampaikan keinginan rakyat Irian Barat untuk merdeka sendiri sesuai dengan janji Belanda dan menyampaikan protes terhadap tindakan dari aparat atau tentara Indonesia yang melakukan sejumlah penangkapan terhadap para tokoh Irian Barat serta pengikutnya dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Delegasi yang dipimpin oleh Herman Wajoi dan Penehas Hans Torrey BA itu kemudian diterima oleh Ortiz-Sanz dan berjanji akan melanjutkannya kepada Sekretaris Jenderal PBB U Thant. Demonstrasi massa yang tertib semula dengan menyanyikan lagu rohani "Laskar Kristen Maju" itu kemudian bubar saat mendengar tembakan panser kavaleri yang tidak disengaja. A. Irian Barat Sebagai Bagian Dari NKRI Proses pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilangsungkan mulai tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. Seperti diketahui, pada akhirnya hasil penentuan pendapat rakyat ini yang memperoleh suara terbanyak ialah kelompok pro integrasi. Dengan demikian dianggap bahwa masyarakat Papua menyatakan keinginannya untuk berada dalam wadah Negara Republik Indonesia. Hasil PEPERA ini pun dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dalam sidangnya pada tanggal 19 November 1969 yang dituangkan dalam resolusi Nomor 2504, yang isinya antara lain mengesahkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri di Irian Jaya sesuai dengan Persetujuan New York tahun 1962. Pengesahan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemerintah RI untuk menyatakan bahwa seluruh proses PEPERA sudah sesuai ketentuan internasional dan hasilnya telah pula diterima oleh komunitas internasional. Berbeda halnya dengan kolompok yang pro-integrasi, kelompok yang berkeinginan agar Papua membentuk negara sendiri dan berpisah dari Republik Indonesia, tidak dapat menerima proses dan hasil PEPERA. Argumentasi yang disampaikan oleh kelompok pro-pemisahan ini dilandasi oleh adanya berbagai intimidasi yang dilakukan oleh otoritas dan aparat bersenjata Republik Indonesia selama masa sosialisasi PEPERA di berbagai daerah di Papua. Selain itu, sebagian dari kelompok ini juga memandang bahwa PEPERA yang hanya ditentukan oleh perwakilan kelompok masyarakat (bukan dengan mekanisme ‘one man one vote’) tidak sah untuk dokualifikasikan sebagai proses yang adil dalam penentuan nasib sendiri. Pasca PEPERA menyebabkan menguatnya gerakan sipil untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terlepas dari adanya perbedaan tajam argumentasi antara kelompok prointegrasi dengan kelompok pro-pemisahan diantara masyarakat Papua, pada faktanya sejak peralihan kekuasaan pemerintahan kepada Pemerintah RI pada 1 Januari 1963 telah terjadinya begitu banyak peristiwa kekerasan, yang sebagian diantaranya layak untuk diselidiki lebih lanjut guna memastikan apakah peristiwa tersebut tergolong sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dari peristiwa tersebut dilatari oleh perbedaan pandangan politik antara bergaung atau berpisah dengan Negara RI. Salah satu lembaga non pemerintah merilis data bahwa selama kurun waktu sekitar 40 tahun (sejak PEPERA hingga era tahun 1990-an), diperikirakan sebanyak 100.000 orang Papua telah menjadi korban berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua. Kuatnya perlawanan kelompok masyarakat Papua yang pro-pemisahan telah membuat otoritas Negara RI melakukan sejumlah operasi militer dalam rangka mengeliminir gerakan-gerakan anti pemerintah RI. Sekadar menyebut contoh, sejak tahun 1962 hingga 1971 dilakukan operasi militer dengan Sandi Winumurti I dan II guna melakukan penggalangan dan pengamanan sebelum, selam dan sesudah proses PEPERA. Antara tahun 1970 hingga 1985 dilaksanakan Operasi Tumpas dengan sasaran melumpuhkan basis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan tahun 1977 dilakukan operasi militer dengan mengerahkan pesawat pembom yang mengakibatkan hancurnya 17 desa dan diperkirakan menelan korban ribuan jiwa, termasuk kelompok anak-anak, orang tua dan perempuan, di wilayah sekitar pegunungan Jayawijaya9. Selain itu, masih terdapat sejumlah operasi militer lainnya yang diterapkan di tanah Papua. B. Dasar Hukum Pemberlakuan Kondisi Kenegaraan Kondisi kehidupan suatu negara senantiasa dinamis dari masa ke masa. Ada kalanya suatu negara hidup dalam keadaan tertib sejak berdirinya hingga saat ini, namun ada juga negara yang sering menghadapi situasi tidak normal dalam sejarah perjalanan kehidupan kenegaraannya. Pada umumnya, seluruh aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh suatu negara dibuat dan diperuntukkan bagi kehidupan kenegaraan dalam situasi normal karena pada prinsipnya situasi tidak normal atau situasi darurat tidak dapat diprediksi secara persis keadaannya. Namun demikian, setiap pemerintah, termasuk pemerintah Republik Indonesia, biasanya tetap berupaya melakukan langkah-langkah antisipasi apabila secara tiba-tiba terjadi keadaan yang tidak normal, melalui pembentukan hukum keadaan darurat atau bahaya. 9 9-10. Lihat Majalah SAMPARI, Edisi 02 Februari 2006 (Jakarta: Solidaritas Nasional Untuk Papua, 2006) hal. Keadaan bahaya dapat bervariasi bentuknya, mulai dari yang paling ringan tingkat ancaman bahayanya hingga yang paling besar ancaman bahayanya terhadap kelangsungan kehidupan suatu negara. Keadaan bahaya kenegaraan dapat berkaitan dengan hal-hal berikut: 1. Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar negeri; 2. keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri; 3. keadaan bahaya karena peperangan di dalam negeri atau ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di dalam negeri; 4. keadaan bahaya karena kerusuhan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; 5. keadaan bahaya karena terjadinya bencana alam (natural disaster) atau kecelakaan dahsyat yang menimbulkan kepanikan, ketegangan dan mengakibatkan pemerintahan konstitusional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya; 6. keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu atau menyebabkan mekanisme administrasi negara tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara yang tidak mendukung atau di mana ketersediaan keuangan kenegaraan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya tugastugas pemerintahan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara sebagaimana mestinya, sementara kebutuhan untuk bertindak sudah sangat genting dan mendesak untuk dilakukan; dan 8. keadaan lain di mana fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional yang sah tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya10. Sejarah perjalanan eksistensi negara Republik Indonesia merupakan sejarah berliku dalam memperoleh kemerdekaannya. Pengalaman menghadapi berbagai situasi tidak normal ketika berusaha memperoleh status merdeka dari kolonialisme bangsa-bangsa asing, telah membuat para pemimpin negara mengantisipasi kondisi kebangsaan yang tidak normal dalam kehidupan kenegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan penelusuran sejarah hukum, undang-undang pertama yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengantisipasi kondisi yang tidak menentu pasca Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ialah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, yang diundangkan pada tanggal 6 Juni 1946. Pemberlakuan undang-undang tersebut kemudian diikuti dengan pernyataan pemberlakuan keadaan bahaya atas beberapa wilayah Republik Indonisia, yakni Daerah Istimewa Surakarta pada tanggal 6 Juni 1946, wilayah Jawa dan Madura pada tanggal 7 Juni 1946 dan keadaan bahaya di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 28 Juni 1946. Kemudian, pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, yang dikeluarkan pada masa sistem pemerintahan parlementer dan penyiapan perubahan konstitusi oleh Dewan Konstituante. Selanjutnya, setelah Presiden Sukarno mengumumkan bahwa konstitusi negara Republik Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hukum keadaan darurat atau bahaya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya11, yang diundangkan pada 16 Desember 1959. Hingga saat ini, undang-undang tersebutlah yang menjadi dasar hukum pemberlakuan keadaan tidak normal di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, segala kebijakan dan atau tindakan negara c.q pemerintah untuk 10Jimly 11 Asshidiqie, Hukum Tata Negara Darurat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 68. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor1908 memberlakukan keadaan bahaya di wilayah hukum Republik Indonesia haruslah mengacu kepada undang-undang tersebut. Pemberlakuan kondisi kenegaraan tidak normal atau keadaan bahaya dalam wilayah Republik Indonesia sesungguhnya merupakan kewenangan presiden dalam kapasitasnya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, yang berbunyi “Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) undangundang tersebut, maka keadaan bahaya ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu darurat sipil, darurat militer atau darurat perang. Syarat pemberlakuan keadaan bahaya menurut ketentuan pasal ini ialah: 1. Apabila keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; 2. Apabila timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga 3. Apabila hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Dengan demikian tahap pertama yang wajib dilakukan oleh penguasa atau pemerintah untuk memberlakukan keadaan bahaya ialah adanya suatu pernyataan atau deklarasi keadaan bahaya di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan “Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang”. Dengan demikian, maka satu-satunya pihak yang berwenang untuk mencabut kondisi darurat atau keadaan bahaya hanyalah presiden selaku panglima tertinggi angkatan perang. Berdasarkan studi yang dilakukan Tim Pengkajian, sejauh ini tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa setelah peralihan tanggungjawab administrasi wilayah Papua dari Belanda kepada Republik Indonesia, negara c.q pemerintah Republik Indonesia pernah menetapkan Papua sebagai wilayah dalam status bahaya. Hal ini agak berbeda dengan pemberlakuan kondisi wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yang pernah beberapa kali ditetapkan sebagai wilayah darurat. Sebagai perbandingan, Propinsi Nanggroe Aceh Darusaalam (NAD) pernah dinyatakan dalam keadaan bahaya atau darurat melalui sejumlah Keputusan presiden, yakni Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan pada 18 Mei 200312. Dengan Keputusan Presiden tersebut, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam keadaan bahaya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 19 Mei 2003. Dengan pertimbangan bahwa situasi bahaya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum kondusif, pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 12 Lihat Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 200413. Status keadaan bahaya dengan tingkatan darurat sipil di Propinsi NAD tersebut dicabut pada akhirnya dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan oleh Presiden RI pada 18 Mei 200514. Dengan demikian, meskipun secara faktual sama-sama terjadi gerakan bersenjata baik di Aceh maupun Papua, namun terdapat 2 (dua) pola penanganan yang berbeda secara yuridi oleh pemerintah dalam menyikapi gerakan bersenjata di kedua wilayah tersebut. Dalam kasus gerakan bersenjata di Aceh, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan prosedur hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni dengan membuat deklarasi atau pernyataan keadaan bahaya melalu sejumlah keputusan presiden dan peraturan presiden yang mencabut keadaan bahaya tersebut. Atas dasar pernyataan kepala negara tersebutlah aparat militer melaksakan tugas-tugasnya melakukan sejumlah operasi serta aktivitas pemerintahan lain sesuai tingkatan keadaan bahaya yang telah ditentukan dari waktu ke waktu. Semestinya pemerintah RI terlebih dahulu menetapkan status keadaan bahaya di Papua sebelum menindaklanjutinya dengan berbagai kebijakan yang bersifat operasional oleh aparat militer, sebab hal tersebut secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 195 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya. Meski status keadaan bahaya dapat diberlakukan atas sebagian wilayah hukum suatu negara, namun hal tersebut bukan berarti bahwa aparat negara bebas melakukan segala tindakan sewenang-wenang yang dapat berakibat terlanggarnya hak-hak asasi manusia penduduk atau warga masyarakat di wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui, hak asasi manusia hanya dapat dikurangi atau dibatasi dengan undang-undang15. Pengurangan atau pembatasan hak-hak asasi manusia dalam keadaan bahaya harus memenuhi sejumlah persyaratan, yakni: 1. Hanya bersifat untuk sementara waktu; 2. Dimaksudkan untuk mengatasi keadaan krisis; dan 3. Dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan normal guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental16. Dalam teori hukum tata negara, apabila keadaan darurat atau bahaya memang ada dan diberlakukan secara praktik, tetapi tidak didahului oleh suatu proklamasi atau deklarasi 13Dengan keputusan presiden ini, selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 19 Mei 2004, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berubah statusnya menjadi bahaya darurat sipil. Lebih lanjut lihat Keputusan Presiden 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 46. 14Dengan diterbitkannya peraturan presiden tersebut, terhitung mulai tanggal 19 Mei 2005 wilayah Propinsi NAD kembali statusnya menjadi tertib sipil. Lebih lanjut lihat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 42. 15 Lihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 16 Jimly Asshidiqie, op cit, hal. 97. secara resmi, maka keadaan darurat yang demikian hanya dapat diakui sebagai ‘emergency de facto’ yang sangat rawan dan mudah disalahgunakan atau lemah dalam legitimasinya. Praktik pemberlakuan keadaan darurat yang demikian sulit untuk dianggap sah dan ‘legitimate’ karena hanya didasarkan atas kehendak subjektif oleh para penentu kebijakan saja17. Dengan demikian, sejauh tidak ada deklarasi pemberlakuan keadaan bahaya atas suatu wilayah tertentu oleh presiden/panglima tertinggi, maka status wilayah tersebut berada dalam kondisi tertib sipil dan tindakan-tindakan keamanan yang dilakukan hanya sebatas tindakan penegakan hukum oleh aparat kepolisian Negara. C. Operasi dan kebijakan Militer di Papua D.I. Latar belakang/motif digelarnya operasi militer Operasi militer di Papua secara umum bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah Indonesia terhadap wilayah Papua dari gerakan separatisme, khususnya kelompok masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selain itu, diduga, motif operasi militer di Papua adalah agar pemerintah pusat tetap menguasai sumber daya alam Papua yang sangat kaya, khususnya dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia sejak 1967. Beberapa laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia menunjukkan beberapa motivasi lain lahirnya operasi militer di Papua, yaitu untuk mempertahankan penguasaan sumber daya alam dan bahan tambang di Papua. Sebagai contoh adalah pengerahan pasukan militer18 di wilayah konsesi tambang PT. Freeport19, bisnis kayu gaharu20, bagi-bagi konsesi hutan di Papua melalui berbagai perizinan terutama hak 17 Lebih lanjut lihat Jimly Asshidiqie, op cit, hal. 293 – 302. 18 “Uang Keamanan: Pertambangan Freeport dan Uang Keamanan di Indonesia”, Global Witness, 2005 . 19 Freeport Sulphur, kemudian menjadi Freeport McMoRan, sebuah perusahaan AS, mulai melakukan kegiatan eksplorasi di Papua bagian selatan pada tahun 1960. Perusahaan tersebut menandatangani kontrak produksi dengan Indonesia pada tahun 1966, tiga tahun sebelum diberlakukannya kekuasaan Indonesia atas Papua. Soeharto bersama resimnya yang didukung militer sangat mebutuhkan modal asing, dan Freeport diberi keleluasaan besar dalam menyusun ketentutuan-ketentuan dari investasinya sendiri. Tambang tersebut dikelola oleh anak perusahaan bernama Freeport Indonesia, yang dikendalikan oleh Freeport McMoRan yang berbasis di Amerika Serikat. 20 Menurut Norkelis Kewa Ama (Wartawan Harian Kompas) dalam artikelnya berjudul “Mengapa Sulit Masuk ke Asmat”, Kisah perburuan gaharu di Papua dimulai sejak 1990 ketika sejumlah hutan gaharu di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumbawa (NTB) mulai punah. Pemburu dan pemodal mulai melirik Papua sebagai daerah sasaran perburuan gaharu. Perburuan dimulai di hutan-hutan pedalaman Jayapura, kemudian beralih ke Mimika, terus sampai pedalaman Merauke yakni wilayah suku Asmat. Walau menghadapi berbagai kesulitan geografis namun pemburu ini mencarter helikopter untuk berburu gaharu di pedalaman Papua. Di Mimika, tahun 2001 terjadi pembantaian tujuh pencari gaharu asal Sulawesi di Kali Kopi, Mimika oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pencarian gaharu diduga dibekingi oknum aparat keamanan, yang pada saat itu membangun pos komando khusus di Kali Kopi untuk memantau dan mengawasi keamanan para pencari gaharu. World Wide fund for Nature (WWF) Bioregion Sahul, Papua melaporkan, pemburu gaharu saat ini menguasai sebagian Taman Nasional Laurentz. Mereka berhasil membujuk penduduk setempat kemudian masuk ke pedalaman Taman Nasional Laurentz, merusak hutan dan satwa di dalam taman itu. Mereka tidak hanya mengambil gaharu, tetapi sekali jalan mereka juga mengambil burung cenderawasih, kasuari, rusa, dan kanguru serta tumbuhtumbuhan tertentu. Para pemburu gaharu ini mendapat dukungan kuat dari pengumpul di kota. Mereka dibekali bahan makanan dan uang selama berburu di hutan, kata Direktur WWF Bioregion Sahul, Benya Mambay. Informasi yang diterima seorang pemburu gaharu yang tidak bersedia disebut namanya, mereka mendapat senjata (pistol) dari aparat keamanan selama berburu gaharu di hutan Kali Kopi, Mimika. Tetapi syaratnya, hasil perburuan gaharu dan hewan lain yang ditemukan di hutan dibagi dengan anggota TNI itu. Berburu gaharu di pengusahaan hutan (HPH)21 terutama di rezim Soeharto22, maupun untuk melindungi praktek aparat militer yang sering menyelundupkan binatang langka dan dilindungi dari Papua ke Pulau Jawa, terutama untuk diperdagangkan23. Contoh betapa eratnya kaitan antara operasi militer dengan sumber daya alam dapat dilihat pada peristiwa berikut. Pada 31 Maret 2001, berlatar belakang protes terhadap sebuah perusahaan penebangan kayu di wilayah Wasior oleh warga Papua, tiga karyawan perusahaan dibunuh oleh segerombolan warga Papua yang bersenjata. Kemudian pasukan huru-hara Brimob dikirim untuk memburu para pembunuh dan melindungi perusahaan penebangan kayu yang lain, sehingga banyak warga desa ketakutan dan melarikan diri. Pada tanggal 3 Mei 2001, pasukan Brimob menyerang warga sipil yang mungkin tengah menuju pulang setelah menghadiri sebuah perayaan. Enam warga dilaporkan tewas, baik ditembak polisi maupun karena tenggelam24. Namun secara umum, operasi militer di Papua berawal untuk memobilisasi dan “mengintimidasi” rakyat Papua agar memilih bergabung (berintegrasi) dengan Indonesia pasca transisi pemerintahan di Papua yang dipegang oleh UNTEA sejak tahun 1963 sampai menjelang dilaksanakannya PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969. Menurut penuturan seorang mantan petinggi militer ke Komnas HAM, pelanggaran HAM banyak terjadi pada saat masa transisi kekuasaan UNTEA yaitu dengan digelarnya operasi khusus dibawah pimpinan Ali Murtopo25. Bentuk pelanggaran HAM tersebut diantaranya adalah pembunuhan, penculikan, dsb. Namun data tentang bentuk pelanggaran secara lebih kongkret, jumlah korban, dan lokasi yang spesifik (locus delicti) tidak mudah untuk ditelusuri. Sedangkan bentuk-bentuk operasi militer yang dipergunakan di Papua adalah merupakan operasi teritorial, operasi intelijen, dan operasi tempur. Operasi militer bertujuan untuk secara persuasif membujuk masyarakat agar mensukseskan Pepera dengan memenangkan Indonesia. Operasi ini dilakukan diantaranya dengan pendampingan masyarakat, sosialisasi, maupun pembangunan daerah. Operasi teritorial ini adalah operasi militer yang paling soft karena lebih menekankan pada cara-cara yang persuasif untuk menarik simpati rakyat. Bentuk operasi lain yang biasanya dilakukan bersamaan dengan operasi teritorial adalah operasi intelijen. Operasi intelijen bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kondisi suatu wilayah atau kelompok masyarakat, maupun untuk melakukan kalkulasi sikap dan Papua penuh risiko dan tantangan. Kondisi geografis yang sulit ditempuh, berikut kehadiran OPM yang menguasai sebagian wilayah hutan rimba. Karena itu pemburu gaharu sering bekerja sama dengan aparat keamanan sehingga mendapat akses ke pedalaman. 21 Kompas, 8 Agustus 2001. Jumlah resmi HPH di Papua saat ini sebanyak 53, dengan luasan sekitar 13 juta hektar 22 Industri kayu di Papua dikuasai kalangan elit dari zaman Soeharto. Pemain terbesar adalah Djajanti Group, yang pemegang sahamnya termasuk saudara sepupu Soeharto, yaitu Sudwikatmono, serta mantan pejabatpejabat dan petinggi militer. Sebuah perusahaan besar lainnya, yakni Barito Pacific Timber, dikelola oleh bekas konco Soeharto, Prayogo Pangestu. Kedua konglomerat tersebut menanggung hutang sangat besar kepada negara setelah krisis finansial 1997-1998 namun secara politik masih memiliki koneksi yang kuat. Sebuah perusahaan yang lebih kecil, yaitu Hanurata, dikuasai oleh keluarga Soeharto. Diperkirakan para jenderal purnawirawan, politisi Jakarta, serta pengusaha besar pun memegang HPH. 23 Baca hasil studi WWF atas praktek penyelundupan satwa liar Papua yang telah merugikan negara triyiunan rupiah setiap tahunnya. 24 Indonesia: ICG, Sumber Daya dan Konflik di Papua, ICG, 12 September 2002. 25 FGD Tim Komnas HAM dengan narasumber, Bogor, 14 Mei 2009. kecenderungan sosial politik suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Hasil dari operasi intelijen ini untuk selanjutnya akan dipergunakan untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan atas suatu wilayah atau kelompok masyarakat yang dijadikan target operasi intelijen. Jika operasi intelijen menunjukkan kecenderungan suatu wilayah atau kelompok masyarakat melakukan resistensi atas kehendak penguasa, maka pilihan yang diambil adalah melancarkan operasi tempur dengan kekuatan bersenjata, baik dari satuan organik maupun kombinasi dengan pasukan non-organik. Dari berbagai bentuk operasi militer tersebut, operasi tempur adalah yang paling sering terjadi, terutama sejak dilancarkan di era pemerintahan Soekarno melalui Komando Trikora 1 Desember 1961. Operasi tempur menjadi wajah yang mendominasi wajah pemerintah Indonesia bagi rakyat Papua dan sepertinya menjadi sebuah sikap politik dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memperlakukan rakyat Papua. Pemerintah Indonesia lebih memilih pengerahan kekuatan bersenjata daripada mempergunakan pendekatan dialogis dan kultural dalam menghadapi rakyat Papua. D.II. Sejumlah Operasi Militer di Papua Selama periode dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1998, tercatat oleh Tim Komnas HAM setidaknya telah dilancarkan 44 (empat puluh empat) operasi militer di wilayah Papua. Model operasi militer tersebut terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu sebelum pelaksanaan PEPERA dengan tujuan untuk memenangan PEPERA dan sesudah pelaksanaan PEPERA dengan tujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, menyukseskan Pemilu, dan menumpas gerakan OPM. D.II.a. Operasi-operasi militer sebelum PEPERA (1961-1969) Pada masa sebelum digelarnya PEPERA tahun 1969, setidaknya tercacat telah digelar operasi-operasi militer sebagai berikut: 1. Operasi Jayawijaya (1961-1962) Setelah Komando Trikora dicanangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 1961, operasi militer dilakukan dengan cara menginfiltrasi tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan “sukarelawan”.26 Pada waktu itu, salah satu perwira yang diterjunkan sebagai infiltran adalah Benny Moerdani (Menhanham/Pangab periode tahun 1983-1988 dan Menhankam periode tahun 1988-1993). Ia bergabung dengan pasukan yang berkekuatan 206 orang yang berasal dari RPKAD dan Kompi II Batalyon 530/Para dari Kodam Brawijaya. Pasukan ini diterjunkan ke Merauke dengan sandi Operasi Jayawijaya. Fase infiltrasi bertujuan untuk membentuk basis-basis gerilya dan mempersiapkan pembentukan pos terdepan bagi upaya menguasai Papua yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Di fase ini, tentara Indonesia masih menjadi bagian dari pasukan bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Pada fase ini, sebanyak 10 kompi (sekitar 1.000 orang) prajurit ABRI dikerahkan 26 Lebih detil kisah infiltrasi parea sukarelawan ke tanah Papua melalui sejumlah gelombang operasi militer bisa dilihat dalam R. Ridhani, Mayor Jenderal Soeharto: Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, PT Pustaka Sinar Harapan, jakarta, 2009. Baca juga Usamah Hisyam, Feisal Tanjung: terbaik Untuk Rakyat, Terbaik Untuk ABRI, Penerbit Yayasan Dharmapena Nusantara, Jakarta, 1999, hal. 219-253. ke Papua. Fase berikutnya setelah melakukan infiltrasi adalah dengan melancarkan serangan-serangan terbuka (open attack) di berbagai daerah strategis seperti Biak, Fak-Fak, Sorong, Kaimana, dan Merauke. Fase ketiga adalah konsolidasi pasukan sebagai kekuatan militer di Papua dengan tujuan untuk mengukuhkan eksistensi kekuasaan militer di Papua melalui pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam). Sejak saat itulah masyarakat Papua untuk pertama kalinya mengetahui Negara Indonesia lewat sepak terjang tentara-tentara Indonesia yang sangat tidak bersahabat bagi rakyat Papua. Bisa dikatakan bahwa kesan pertama rakyat Papua terhadap Indonesia adalah kekerasan dan kekejaman militer, bukannya sebuah negara yang santun, bertoleransi, dan menghormati kultur masyarakat. Setelah perjanjian New York (New York Agreement) ditandatangani 15 Agustus 1962, Benny Moerdani dipindahkan ke Holandia (Jayapura) sebagai komandan sementara seluruh pasukan infiltran Indonesia di Papua Barat. Perjanjian New York adalah perjanjian yang difasilitasi oleh Pemerintah Amerika Serikat atas nama Pemerintah Indonesia untuk menyerahkan kekuasaan atas Papua Barat dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia. Di dalam artikel II Perjanjian tersebut, pemerintah Belanda akan menyerahkan kekuasaan secara administrasi ke United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang didirikan di bawah yurisdiksi Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan administrasi ke Pemerintah Indonesia. Pada artikel XVIII Perjanjian tersebut juga menyebutkan adanya jaminan agar rakyat Papua diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya secara bebas (Act of Free Choice), apakah akan memilih bergabung dengan Indonesia ataukah akan berdiri sendiri. Periode 1962-1969 adalah masa transisi kekuasaan di Papua yang melibatkan secara intensif interaksi antara PBB yang representasikan oleh UNTEA dan pemerintah Indonesia yang direpresentasikan oleh kekuatan militer. Pengerahan pasukan infiltran juga merupakan pelaksanaan atas Perjanjian New York. Seluruh pasukan infiltran ini diorganisasi ke dalam Kontingen Indonesia (Kontindo) sebagai bagian dari United Nation Security Forces (UNSF) yang merupakan aparat gabungan di bawah otoritas UNTEA. Konsentrasi pasukan ini pada mulanya adalah di wilayah Merauke, Kaimana, Fak-Fak, dan Sorong. Semua pasukan Indonesia ini kemudian dibagi dalam empat datasemen, yaitu Datasemen A di Merauke, Datasemen B di Kaimana, Datasemen C di FakFak, dan Datasemen D di Sorong. Walaupun tentara Indonesia diperbantukan di United Nations Security Forces (UNSF), komando atas mereka tetap di bawah Panglima Mandala. Artinya, pasukan ini merupakan pasukan yang tidak terpisahkan dari ABRI. Sehingga tanggung jawab organisatoris dan administrasi tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Pada fase awal di Papua, keberadaan ABRI setidaknya memiliki dua misi27. Misi pertama secara formal adalah sebagai alat kelengkapan UNTEA, dan yang kedua secara informal adalah untuk melanjutkan Komando Trikora28 yang dicanangkan Presiden Soekarno. Maka dari itu, ABRI dalam Kontindo lebih berkepentingan untuk mengawasi UNTEA agar tidak merugikan Indonesia dan menekan kekuatan sosial politik orang-orang Papua yang menentang Indonesia. Dengan mengintrodusir pendekatan militer di masa transisi kekuasaan tahun 1962-1969, menyebabkan rakyat Papua memandang Indonesia sama dengan kekerasan dan kekejaman. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas rakyat Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh anggota 27 Socrates Sofyan Yoman, Pemusnahan Etnis Malanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, Yogyakarta, 2007. ABRI yang menjadi representasi Indonesia di Papua selama bertahun-tahun. Sikap ABRI atas reaksi orang Papua bukannya mencari jalan penyelesaian secara damai, melainkan mengintensifkan kekerasan dengan skala yang lebih besar melalui operasi militer dengan menjadikan Papua sebagai wilayah Operasi Militer. Walaupun intensitas operasi militer di Papua sangat sering (setidaknya tercatat ada 16 operasi militer antara tahun 1961-1998), namun tidak pernah ada penetapan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Papua adalah daerah tertib sipil29. Akibatnya, lingkaran kekerasan menjadi tidak terputus di Papua sampai sekarang30. Para infiltran yang tergabung dalam Kontindo adalah inti kekuatan ABRI di Papua ketika Kodam XVII/Tjendrawasih dibentuk. Kodam XVII/Tjendrawasih yang awalnya bernama Kodam XVII/Irian Barat dibentuk melalui Surat Men/Pangad No. Kpts-1058/8/1962 pada tanggal 17 Agustus 1962 atau 2 hari setelah Perjanjian New York ditandatangani. Karena belum memiliki kekuasaan di Papua, Kodam hanya menjadi bayangan dengan fungsi mengawasi UNTEA dan gerak politik orang-orang Papua. Brigjen U. Rukman yang merupakan komandan Kontindo merupakan Pangdam XVII/Tjendrawasih pertama di Papua. Kodam XVII/Tjendrawasih kemudian direalisasikan secara nyata pada tanggal 12 Januari 1963 mendekati hari penyerahan administrasi pemerintahan Papua dari UNTEA ke Pemerintah Indonesia. Kodam ini kemudian membentuk komando teritorial pada tanggal 3 Maret 1963 menjadi Korem, 8 Kodim, 70 Puterpa, dan 20 Koorterpa. 2. Operasi Wisnumurti (1963-1965) Pada tahun 1963, Men/Pangad Jend. A. Yani mengeluarkan perintah Operasi Wisnumurti untuk mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa, Makasar, dan Maluku untuk mengembangkan kekuatan tempur dan staf Kodam XVII/Tjendrawasih. Tugas pokoknya adalah menegakkan kewibawaan Pemerintah Indonesia, menjamin keamanan dan ketertiban serta membantu pemerintah sipil dan membangun Irian Jaya Barat, khususnya untuk mengkounter gerakan separatis. Gerakan separatis dalam bentuk Perlawanan senjata OPM untuk pertama kalinya terjadi di Kebar, Manokwari, pada tanggal 26 Juli 1965. perlawanan ini dipimpin oleh Johanes Djambuani dengan kekuatan 400 orang yang berasal dari Suku Karun dan Ayamaru. Seiring dengan itu, Suku Arfak di Afai, Manokwari, melancarkan perlawanan yang dipimpin oleh Mayor Tituler Lodewick Mandatjan yang diikuti Kapten Tituler Barent Mandatjan dan Lettu Tituler Irogi Maedogda dengan mengajak penduduk lari ke hutan. Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada awalnya adalah reaksi orang-orang Papua atas sikap pejabat-pejabat Indonesia yang mengecewakan rakyat Papua karena mengintrodusir dan mengedepankan operasi militer dalam menghadapi rakyat Papua. Di samping itu, rakyat Papua merasa secara historis dan geneologis berbeda dengan kebanyakan ras Melayu, dan tidak pernah merasa menjadi bagian atau jajahan dari kerajaan-kerajaan yang kemudian melebur menjadi Negara Indonesia. Masyarakat Papua secara fisik maupun sosial berbeda dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Mayoritas orang Indonesia berasal dari Kamboja, sedangkan orang Papua adalah rumpun melanesia ras negroid di Pasifik. Secara sosial orang Papua memiliki otoritas tersendiri yang bersifat khas dalam mengatur, 29 30 FGD Tim Komnas HAM dengan Mayjen (Purn) Samsudin, Bogor, 14 Mei 2009. Pemusnahan Etnis Malanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, Socrates Sofyan Yoman, 2007. mengembangkan kebutuhan dan penyelesaian masalah berdasarkan hukum adat yang membebani hak dan kewajiban adat bagi para individu31. Kemudian di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1965, terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Permenas Ferry Awom dengan pengikutnya sebanyak 400 orang yang berasal dari Suku Biak, Ajamaru, Serui, dan Numfor yang menyerang asrama Yonif 641/Cenderawasih I. Akibatnya, 3 orang tentara Indonesia tewas. 3. Operasi Sadar (1965) Setelah terjadi penyerangan oleh gerakan OPM, diluncurkan Operasi Sadar dibawah komando Pangdam Brigjend R. Kartidjo untuk menghancurkan perlawanan OPM. Operasi ini tidak saja bertujuan untuk mematahkan perlawanan OPM di Manokwari, tetapi juga menegaskan kekuasaan Kodam XVII/Tjendrawasih atas seluruh wilayah Papua. Tugas utama adalah menghancurkan gerombolan yang bergerak di sekitar Manokwari dan Kebar, sekaligus untuk menangkap Ferry Awom dan Julianus Wanma. Operasi yang dilancarkan sejak 10 Agustus 1965 ini dilancarkan secara intensif dari kampung ke kampung yang menjadi basis perlawanan OPM. Dalam operasi ini dilaporkan 36 penduduk tewas. Operasi Sadar kemudian diperluas ke ke seluruh wilayah Papua pada 25 Agustus 1965, dipimpin langsung oleh Pangdam XVIII/Tjendrawasih. Operasi ini membagi wilayah Papua menjadi 4 sektor. Sektor I adalah daerah yang meliputi Manokwari dan sekitarnya yang menjadi pos terdepan operasi. Untuk itu dilancarkan operasi intelejen dan teritorial untuk mendukung operasi tempur. Di sektor lainnya yang belum muncul perlawanan OPM, dilancarkan operasi intelejen dan teritorial untuk mencegah meluasnya pengikut perlawanan OPM. 4. Operasi Bharatayudha (1966-1967) Operasi kemudian dilanjutkan oleh Brigjend R. Bintoro sepanjang 1966-1967 secara lebih massif. Nama operasi ini adalah Operasi Bharatayudha dengan mendatangkan pasukan dari Yonif 314/Siliwangi dengan dua kompi Yon 700/RIT dan 2 Kompi Yon 935/Brimob. Selain itu juga melibatkan 2 Ton KKO/ALRI, 1 Ton Kopasgat, dan 1 Tim RPKAD. Pasukan juga diperkuat dengan pesawat bomber B-26, 1 pesawat dakota, dan 1 kapal perang. Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan perlawanan dan memenangkan PEPERA. Dalam operasi ini dilaporkan timbul banyak korban jiwa. Sepanjang tahun 1967, operasi telah menembak mati 73 orang dan menangkap 60 orang dengan menyita 39 pucuk senjata. Sedangkan yang menyerahkan diri adalah sekitar 3.539 orang. 5. Operasi Wibawa (1967) Ketika Brigjend Sarwo Edi menjadi Pangdam XVIII/Tjendrawasih, digelar operasi baru yaitu Operasi Wibawa, dengan tugas utama memenangkan PEPERA untuk Indonesia. Kodam melakukan sinkronisasi operasi tempur, intelijen, dan teritorial. Pangdam juga memerintahkan agar pada setiap Kodim disiapkan kekuatan tempur. Dalam kerangka Operasi Wibawa untuk memenangkan PEPERA, di Kodam diperbantukan intelijen dari Den Dipiad dan dari Tim Karsa Yudha/RPKAD. Operasi ini secara keseluruhan melibatkan 6.220 personil.Untuk memenangkan Pepera, intimidasi oleh kekuatan bersenjata telah menyebabkan sebagian orang terpaksa memilih Indonesia. 31 Alternative Dispute Resolution Papua Merdeka, Foker LSM Papua, 28 Oktober 1999 Pada masa ini, pemerintah dan angkatan bersenjata Republik Indonesia memasukkan ribuan aparat keamanan dan petugas-petugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Papua Barat menjadi bagian integral dari Republik Indonesia bilamana ‘Act of Free Choice’ terjadi. Rakyat diintimidasi, terjadinya penangkapan dan penahanan di luar hukum, pembunuhan-pembunuhan. Akibatnya hanya 1.025 saja dari total 800.000 rakyat Papua waktu itu yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia untuk secara terpaksa memilih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia32. Selain itu, Pepera cacat secara hukum, karena tidak melibatkan rakyat Papua dalam sebuah musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam Perjajian New York, juga tidak diterapkan prinsip “one man one vote”33. Namun Operasi Wibawa ini tidak berjalan mulus. Perlawanan dilakukan di Enarotali. Kelompok bersenjata secara terang-terangan menolak untuk bergabung dengan Indonesia. Perlawanan ini dipimpin AR. Wamafma, Senen Mote, dan Thomas Douw. Perlawanan didukung oleh polisi asal Papua yang mendukung perlawanan. Untuk menghentikan perlawanan, Pangdam Brigjen Sarwo Edi memerintahkan penghancuran kelompok perlawanan. Untuk itu diterjunkan Batalyon Kopasanda dan pasukan dari Batalyon 724/Hasanudin untuk membantu pasukan di Kodim 1705/Nabire. Dalam operasinya, pasukan juga didukung diantaranya oleh Satgas AURI yang dilengkapi dengan pesawat B-26, Dakota, dan Hercules. Pasukan Yon 724/Hasanudin kemudian bergerak melancarkan operasi ke berbagai daerah di sekitar Paniai. Operasi yang dipimpin oleh Mayor Mochtar Yahya dan Mayor Sitompul ini menimbulkan korban jiwa sekitar 634 orang. Gencarnya operasi yang dilancarkan oleh Pangdam Sarwo Edi ini tidak lepas dari fungsinya sebagai Ketua Proyek Pelaksana Daerah. Sesuai dengan surat Mendagri No. 30/1969, Pangdam bertanggung jawab dalam pengendalian, penggerakan, dan koordinasi kegiatan semua aparatur pemerintah daerah, sipil, militer, dan swasta. Dengan kata lain, pangdam memegang kekuasaan tertinggi di Papua dalam menjalankan pemerintahan dan bertanggungjawab memenangkan Pepera. 6. Operasi Khusus Pemenangan Pepera (1961-1969) Kemudian juga dalam kerangka memenangkan PEPERA, dilaksanakan Operasi Khusus Pemenangan Pepera (OPSUS) dipimpin oleh Mayor Ali Martopo selama periode 19611969. Operasi ini bergerak dalam bidang intelijen dan sosial ekonomi dalam kerangka melancarkan operasi teritorial.34 Operasi pemenangan Pepera dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama bertujuan untuk menghancurkan kelompok perlawanan dan sekaligus memperluas sebaran pasukan ABRI ke daerah-daerah yang dikuasai. Selain itu di setiap Puterpa disiapkan 1 regu pasukan untuk melakukan operasi teritorial. Fase kedua adalah untuk memastikan daerah-daerah kepala 32 “Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Papua: Demi Persatuan Nasional dan Pembangunan”, John Rumbiak, Elsham Papua Online 33 Berburu keadilan di Papua: Mengungkap dosa-dosa politik Indonesia di Papua Barat, Yakobus F. Dumupa, 2006 34 Cerita detil operasi intelijen yang dilakukan sejumlah satuan RPKAD (sekarang Kopassus) bisa dibaca pada burung Pepera dimenangkan Indonesia. Fase ketiga dan keempat adalah memastikan kemenangan pada hari- H dan mengamankan hasilnya. Sejalan dengan proyek pemenanganan Indonesia dalam Pepera, ABRI menjalankan pula fungsi sosial dan politiknya. Untuk Kodam melancarkan program pergantian para pejabat kabupaten dan dinas-dinas yang diragukan loyalitasnya ke Indonesia. ABRI juga dirapatkan di kampung-kampung untuk mengawasi kehidupan masyarakat secara langsung. Juga dilancarkan proyek civilisasi dan kesehatan bekerjasama dengan zending dan misi yang berbeda. Di bidang ekonomi dengan mengontrol harga dan arus barang. Kegiatan-kegiatan ini disebut dengan civic mission ABRI di Papua. 7. Operasi Tumpas (1967-1970) Pada tahun 1967, dilancarkan Operasi Tumpas. Operasi ini dikonsentrasikan di wilayah Ayaamaru, Teminabuan, dan Inanwatan. Akibat operasi ini, diperkirakan terjadi pembunuhan massal di daerah-daerah tersebut yang jumlahnya sekitar 1.500 orang. Namun demikian, tidak ada pendataan yang pasti untuk mengungkap kebenaran statemen jumlah korban ini. Operasi militer di Papua semakin masif di sejak pergantian Presiden dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1968. Setelah ABRI sukses menjadi lokomotif Negara untuk memenangkan Pepera tahun 196935, tidak lantas operasi dan kebijakan militer di Papua berhenti ataupun berkurang. Pada 29 Januari 1970, Bridjend Acub Zainal ditunjuk menjadi Pangdam XVIII/Tjendrawasih. Pada bulan Mei 1970, wanita yang sedang hamil bernama Maria Monsapia disiksa dan ditembak di tempat oleh tentara. D.II.b. Berbagai Operasi Militer Pasca PEPERA Operasi-operasi militer pasca-PEPERA yang dimenangkan oleh Indonesia secara umum bertujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, mensukseskan Pemilu, dan menumpas gerakan separatis OPM. Operasi-operasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Operasi Pamungkas (1971-1977) Setelah berhasil memenangkan PEPERA dan untuk menyambut pelaksanaan Pemilu 1971, Kodam direorganisasi menjadi 3 Korem, 9 Kodim, dan 3 Yonif. Dalam persiapan Pemilu 1971, terjadi perlawanan terutama di Biak Utara dan Biak Barat, serta di kepala burung Manokwari. Untuk itu dilancarkan Operasi Pamungkas dengan pendekatan operasi teritorial dibantu intelejen dan tempur. Pelaksana operasi adalah Kodim Biak yang dibantu pasukan tempur Yonif 753 dan 752 Cinderawasih serta Dipiad. Pada Juli 1971, operasi ini dilancarkan di Manokwari untuk mengejar Ferry Awom yang belum menyerah. Operasi yang dipimpin Mayor Ahmad ini berhasil membujuk Ferry Awom dan 400 anggotanya untuk menyerah. Kemudian, pada 1974 terjadi pembunuhan di Kampung Busdori, Krisdori (Biak Barat) dan Ampobukor (Biak Utara), dimana sebanyak 45 orang disiksa dan dibunuh. 35 PBB melalui Resolusi No. 2504 mengesahkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang hasilnya Papua menjadi bagian dari wilayah Negara Indonesia 2. Operasi Koteka (1977-1978) Perlawanan orang Ndani (Lani) di daerah Jayawijaya diawali oleh perasaan tidak suka suku Ndani terhadap kebijakan Pemerintahan Indonesia yang memaksa mereka berganti pakaian, dari pakaian adat Koteka ke pakaian biasa. Sekitar 15.000 orang berkumpul untuk melakukan protes. Untuk menghadapi perlawanan ini, ABRI melancarkan Operasi Koteka. Di daerah Tiom, sekitar 4000 orang melawan dengan cara menyerang pos pemerintah. Akibatnya diterjunkan pasukan RPKAD yang di-drop dari helikopter. Penduduk mencoba menyelamatkan diri ke hutan, namun terus dihujani tembakan dengan pesawat/helikopter dari udara. Pada 1977-1978, di wilayah pelayanan Baptis, sebanyak 300 orang dibunuh oleh tentara. Ada yang dibunuh dengan cara memanaskan besi dan dimasukkan dalam dubur, ada yang dibunuh dengan mengiris tubuh dengan silet dan pisau dan digosok dengan rica yang ditumbuk dalam jumlah banyak. Ada pula yang disuruh gali kuburan sendiri dan dikuburkan sendiri setelah ditembak mati. Juga pada 1977-1978, terjadi operasi militer besar-besaran di daerah pedalaman Jayawijaya, yaitu di Piramit, Kelila, Bokondini, dan hampir seluruh daerah Jayawijaya. Tanpa membedakan jenis kelamin dan usia, orang Papua dimusnahkan dengan cara yang mengerikan. Menjelang Pemilihan Umum pada 1977, perlawanan kembali dilancarkan oleh Kelompok OPM di daerah daerah Tiom dan Kwiyawage (lembah di Baliem), Kobagma, Bokondini, Mulia, Ilaga, Piramid (Kabupaten Jayawijaya). Perlawanan ini dipicu oleh penempatan kesatuan-kesatuan ABRI di hampir seluruh Papua. Operasi militer untuk mematahkan perlawanan menjelang Pemilu 1977 dan Sidang Umum MPR 1978 ditingkatkan secara kualitatif dan kuantitatif. Selain itu perlawanan OPM juga terjadi di Enarotali, Biak, dan Mimika serta di sepanjang perbatasan dengan PNG. Era ini dianggap oleh orang Papua sebagai awal dari status “Daerah Operasi Militer” bagi Papua diterapkan36. Di areal PT. Freeport di Timika pada Juli 1977, penduduk yang ditengarai OPM melancarkan serangan ke pipa-pipa dan fasilitas milik PT.Freeport karena merasa kecewa atas kehadiran perusahaan itu yang menyengsarakan masyarakat, merampas tanah ulayat masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup. ABRI membalas perlawanan ini dengan menyerang kelompok OPM dari udara mempergunakan pesawat Bronco OV-10. Kemudian di daerah selatan Jayapura yang berdekatan dengan markas OPM diterjunkan pasukan dalam jumlah besar 10.000 orang tentara setelah daerah itu dibombardir dengan pesawat Bronco OV-10. Akibatnya diperkirakan sebanyak 1.605 orang pendukung OPM dan penduduk sipil di wilayah itu tewas. Sepanjang 1977-1978, Dubes Indonesia untuk Papua New Guinea (PNG) memperkirakan, sebanyak 1.800 orang tentara Indonesia dikerahkan beroperasi di hutan-hutan di perbatasan antara Indonesia dan PNG untuk melakukan pengejaran dan 3.000 pasukan bersiaga di lapangan. 3. Operasi Senyum (1979-1980) Menyadari bahwa operasi militer ini telah menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, Panglima ABRI Jendral TNI M. Yusuf mengumumkan akan mengurangi operasi militer di Papua dengan mengintrodusir kebijakan baru dengan nama Operasi Senyum. Melalui operasi ini, tidak dilaksanakan operasi militer besar-besaran, karena OPM dilihat mulai 36 Pemusnahan Etnis Malanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, Socrates Sofyan Yoman, 2007 mengecil dan tidak membahayakan. ABRI hanya melancarkan patroli di perbatasan dan tugas keamanan rutin. Pada tahun 1980-an, Kodam dinyatakan sebagai Kotama dalam jajaran Angkatan Darat. Dengan status ini, Pangdam adalah pimpinan di daerah untuk seluruh jajaran komando militer semua angkatan. Posisi Pangdam langsung berada di bawah Panglima ABRI. Panglima ABRI juga memiliki komando langsung pada Kotama AD, yaitu Kostrad dan Kopassus dengan perintah langsung dari Panglima ABRI dan Kodam hanya memfasilitasi. Hal Ini disebut sebagai BKO (Bawah Kendali Operasi). Di era ini, Papua tertutup bagi media sehingga tidak banyak operasi yang dilancarkan di Papua yang bisa diketahui oleh orang luar. Robin Osborne menyebut keadaan ini sebagai perang rahasia Indonesia di Papua. Pada awal tahun 1989-an, KOPKAMTIB mengeluarkan analisis bahwa kekuatan OPM sudah melemah dan terpencar-pencar dalam kelompok-kelompok kecil dengan senjata yang sangat terbatas. Gerakan OPM aktif di sekitar perbatasan dengan PNG. Sebagai respon atas informasi ini, diterjunkan pasukan baret merah (Kopassus). Pengerahan pasukan ini menakutkan penduduk di sekitar perbatasan. Akibatnya, ratusan orang dilaporkan melarikan diri (eksodus) ke PNG. Pengungsian ke PNG pada tahun 1984 semakin meningjat ketika Suku Muyu di Midiptana, Waropko, dan Merauke juga masuk ke wilayah PNG. Gerakan suku Muyu ini kemudian diikuti penduduk dari daerah lainnya yaitu Jayapura, Wamena, Sorong, Mimika, Manokwari, dan Fak-Fak. Seluruh pengungsi dari Papua yang masuk ke wilayah PNG diperkirakan berjumlah 10.000 orang. Sementara Yafet Kambai mencatat, dari seluruh pengungsi itu hanya sekitar 7.500 orang yang berhasil masuk PNG. Sedangkan sekitar 1.900 orang berdiam di perbatasan. Di PNG, seluruh pengungsi ditempatkan di Kamp East Westin dan Western Province. Gerakan pengungsian/eksodus ke PNG, selain dikarenakan faktor operasi militer di daerah perbatasan, juga disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut yaitu aktifitas OPM di daerah perbatasan, munculnya rasa kecewa masyarakat karena macetnya pembangunan di Papua, banyaknya operasi intelijen yang mengintimidasi penduduk, dan masuknya arus transmigrasi (dari Pulau Jawa) secara besar-besaran ke Papua, terutama di daerah sekitar perbatasan. Pengungsian ke PNG dalam kurun waktu tahun 1983-1984, juga dipicu oleh banyaknya penangkapan di kota Papua, terutama Jayapura oleh intelijen Kopassus. Mereka yang ditangkap ada sebanyak 20 orang yang berasal dari Universitas Cinderawasih dan pegawai gubernuran Irian Jaya. Salah seorang dari mereka adalah Arnold AP yang menjabat sebagai Kepala Museum Antroplogi Uncen. Penangkapan ini menimbulkan keresahan di Jayapura. 4. Operasi Gagak I (1985-1986) Operasi yang lain adalah Operasi Gagak I (1985-1986), yang dipimpin oleh Pangdam Mayjen H. Simanjuntak. Dalam operasi ini, pasukan dibagi dalam beberapa sektor. Yaitu Sektor A di perbatasan, Sektor B di tengah, dan Sektor C di kepala burung, dengan komando di Korem masing-masing. Sektor C yaitu daerah di Fak-Fak, memfokuskan operasinya di daerah C3, yaitu daerah kompleks Tembagapura, Agimuga, dan Timika. Pimpinan OPM yang hendak dikejar adalah Victus Wangmang. Pasukan yang dikerahkan berasal dari Yonif 752 dengan kekuatan 2 kompi dibantu Apter dan 2 SST hansip/Wanra. Dalam Operasi Gagak I ini tercatat 14 orang yang diduga OPM dibunuh dan 8 orang ditangkap beserta senjatanya yang dibawa/dipakai. 5. Operasi Gagak II (1986) Memasuki tahun 1986, operasi dilanjutkan dengan Operasi Gagak II, dengan pimpinan Mayjen Setiana. Tugas pokok operasi ini adalah menghancurkan Gerakan Pengacau Keamanan dan deteksi loyalitas rakyat. Pasukan yang dilibatkan adalah seluruh pasukan organik tempur dari teritorial Kodam VIII/Trikora, serta pasukan BKO dari Satgas Yonif 321/Kostrad, 6 Tim Intelpur Kostrad, 1 Kompi Yonzipur/Dip, 1 Kompi Yon Zipur/Brawijaya, satuan dari TNI AL dan AU serta Penerbad. Selama operasi ini ABRI melaporkan, sebanyak 21 orang terbunuh, 5 ditangkap, dan 12 orang menyerah dengan menyita 13 pucuk senjata. 6. Operasi Kasuari I (1987-1988) Kemudian digelar Operasi Kasuari I (1987-1988) dengan Pangdam Trikora waktu itu adalah Mayjend. Wismoyo Arismunandar, dengan tugas utama menghancurkan GPK secara fisik terutama di daerah sekitar perbatasan. Operasi ditekankan di wilayah Jayapura, FakFak, Paniai, dan Biak. Di daerah subsektor B1, sasaran adalah Enarotali dan Sugapa, dengan menerjunkan pasukan dari Yonif 753, Intel Laksusda, Kazipur 4/Diponegoro, Pleton Intelrem 173, Ru Marinir, 1 Pleton Kopaskhas AU, 1 Tim khusus Kodim Nabire dan 2 SKK Wanra. Kampung yang menjadi sasaran adalah kampung Tigitakaida, Seruai, Swaipak, Ampobukar, Supriori, dan Swainober di Biak Barat. 7. Operasi Kasuari II (1988-1989) Operasi militer ini dilanjutkan dengan Operasi Kasuari II (1988-1989), yang difokuskan di sepanjang perbatasan dengan PNG dengan titik tekanan adalah operasi teritorial, intelijen, tempur serta kamtibmas. Operasi teritorial diarahkan untuk membentuk desa binaan agar berpihak pada ABRI. Pasukan yang bertugas dan sektor (wilayah) operasi sama dengan Operasi Kasuari I. Kelly Kwalik muncul sebagai pimpinan OPM di daerah Agrimuka dan Tembagapura pada saat Operasi Kasuari II ini dilancarkan. 8. Operasi Rajawali I (1989-1990) ABRI melanjutkan operasi dengan menggelar Operasi Rajawali I (1989-1990) dan Operasi Rajawali II (1990-1991) dengan pimpinan Mayjen Abinowo dengan tujuan untuk menghancurkan OPM di sepanjang perbatasan dengan PNG. Jenis operasi adalah teritorial, intelijen, dan tempur secara terpadu dan serempak. Operasi teritorial ditujukan untuk pembentukan desa binaan dengan tujuan memisahkan rakyat dan GPK. Sementara operasi intelijen ditujukan untuk mengindentifikasi gerakan GPK dan menetralisir pengaruhnya. Sementara operasi tempur ditujukan untuk melancarkan patroli, pengejaran, dan penghancuran. Pasukan yang terlibat adalah pasukan organik Kodam VIII ditambah Yonif 621/Tanjungpura, Yonif 431/Brawijaya (diganti Yonif 310/Siliwangi), 1 Intelpur Kostrad, Satgas Dampak XX Kopasus, Satgas Udara 3 Heli Puma, 1 Cassa AL, dan 32 polsek dan 6 SKK/Wanra. Di masa inilah Thomas Wanggai mengibarkan bendera Melanesia barat di Jayapura. 9. Operasi Rajawali II (1990-1995) Pada 1990, operasi intelijen militer yang berintikan pasukan Kopassus di Papua meningkat. Penangkapan yang disertai pembunuhan terhadap orang-orang yang ditengarai OPM kerap terjadi di berbagai tempat. Operasi jenis ini mulai terkuak ketika terjadi pembunuhan terhadap penduduk kampung di Desa Wea, Tembagapura di bulan Oktober sampai Desember 1995. Dalam aksi ini, pasukan Yonif 752 melakukan penembakan secara membabi buta terhadap penduduk yang sedang berada di rumah-rumah mereka. Hal ini dipicu oleh pengibaran bendera bintang kejora, yang kemudian berakibat pada 11 orang terbunuh dan beberapa orang lainnya ditangkap. Pada 6 Oktober 1994, Marius Kwalik, Romulus Kwalik, Hosea Kwalik, dan Sebastinaus Kwalik, ditangkap oleh aparat militer dengan alasan keempat orang ini bekerjasama dengan Kelly Kwalik. Orang-orang ini ditahan dan disiksa di Pos tentara Koperapoka, Timika sampai pada 15 November 1994. Secara detil tercatat berbagai operasi militer yang digabung dengan operasi intelijen dan kadang operasi teritorial adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Nama Operasi Antrareja Aluguro Sikat Banteng I Banteng II Lintas Garuda Merah Garuda Putih Srigala Kancil I Kancil II Kancil III Naga Lumba-Lumba Lumbung Gurita Lumbung Jatayu Elang Alap-Alap Badar Besi Show of Force Cakra I Cakra II Merpati Sadar Wisnumurti Merpati Damai Nurti Janggi Imam Sura Bharata Yudha Tahun Musuh Yang Dihadapi Isu Operasi Mulai 1961 Belanda Maret 1962-Juni 1962 Juli 1962 1963-1965 1963 1966-1967 Melawan kolonial Belanda, disintegrasi 34 Penegak X 35 Sadar 36 Wibawa 37 Pamungkas 38 Koteka 39 Gagak I 40 Gagak II 41 Kasuari 01 42 Kasuari 02 43 Rajawali 01 44 Rajawali 02 Diolah dari berbagai sumber Maret 1967-Juni 1968 1967 1971 1977 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 OPM Disintegrasi Tabel Daftar Pangdam XVII/ Cendrawasih dan Operasi Yang Dilakukan No Nama Lama Tugas Keterangan 1 Brigjen U Rukman 1963-1964 - Operasi Wisnumurti I - Operasi Wisnumurti II 2 Brigjen Inf. Kartidjo 1964-1966 - Operasi Wisnumurti III - Operasi Wisnumurti IV - Operasi Giat - Operasi Tangkas - Operasi Sadar 3 Brigjen TNI R. Bintoro 1966-1968 - Operasi Bharatayudha 4 Brigjen TNI Sarwo Edi Wibowo 1968-1970 - Operasi Sadar - Operasi Bharatayudha - Operasi Wibawa 5 Brigjen Acub Zainal 1970- 1974 - Operasi Pamungkasa - Operasi Koteka 6 Brigjen Imam Munandar 1977-1978 - Berbagai operasi di daerah perbatasan 7 Brigjen C.I. Santosa 1978-1982 Belum teridentifikasi 8 Brigjen RK Sembiring Meliala 1982-1985 Belum teridentifikasi 9 Mayjen H. Simanjuntak 1985-1986 - Operasi Gagak I 10 Mayjen Setiana 1986-1987 - Operasi Gagak II 11 Mayjen Wismoyo Arismunandar 1987-1989 - Operasi Kasuari I - Operasi Kasuari II 12 Mayjen Abinowo 1989-1991 - Operasi Rajawali I - Operasi Rajawali II 13 Mayjen I Ketut Wardhana 1994-1995 - Operasi Rajawali III 14 Mayjen Johny Lumintang 1995-1996 Belum teridentifikasi 15 Mayjen Amir Sembiring 1998-1999 - Berbagai operasi daerah rawan 16 Mayjen Mahidin Simbolon 1999-2002 - Operasi Pengendalian Pengibaran Bendera Sumber Artikel KKPK