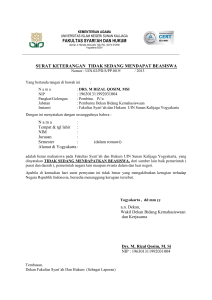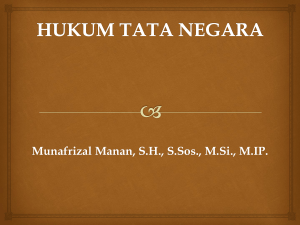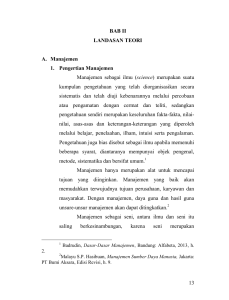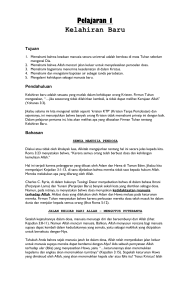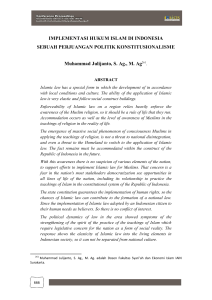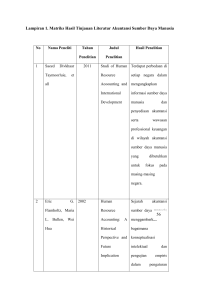Bab III - ScholarBlogs
advertisement
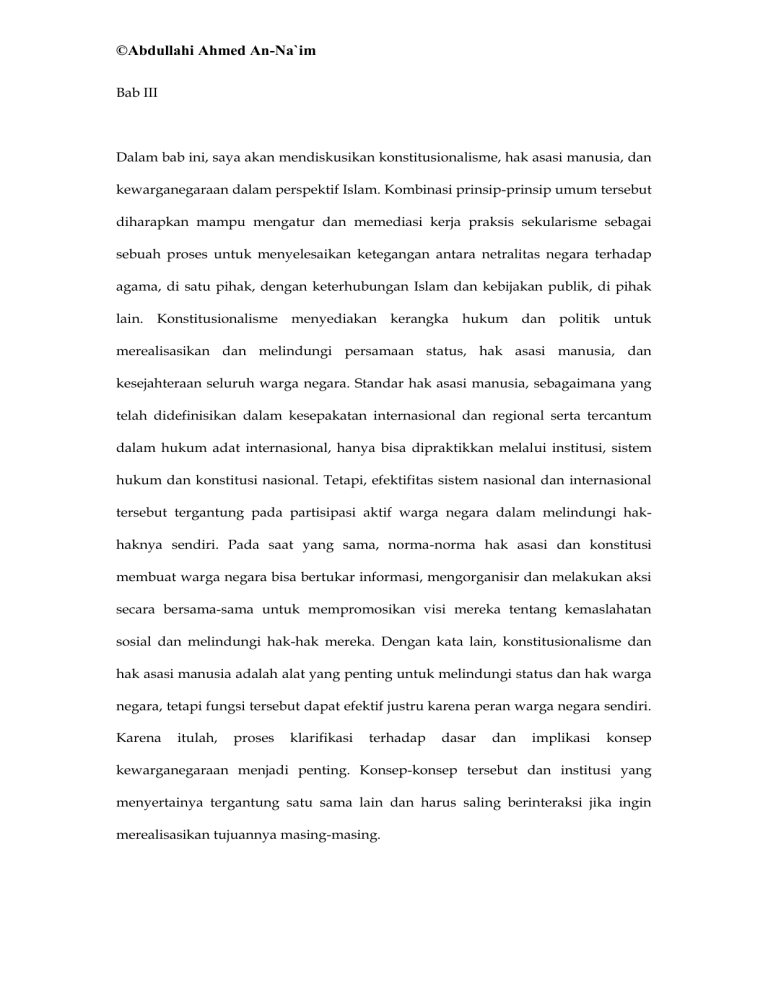
©Abdullahi Ahmed An-Na`im Bab III Dalam bab ini, saya akan mendiskusikan konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan dalam perspektif Islam. Kombinasi prinsip-prinsip umum tersebut diharapkan mampu mengatur dan memediasi kerja praksis sekularisme sebagai sebuah proses untuk menyelesaikan ketegangan antara netralitas negara terhadap agama, di satu pihak, dengan keterhubungan Islam dan kebijakan publik, di pihak lain. Konstitusionalisme menyediakan kerangka hukum dan politik untuk merealisasikan dan melindungi persamaan status, hak asasi manusia, dan kesejahteraan seluruh warga negara. Standar hak asasi manusia, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam kesepakatan internasional dan regional serta tercantum dalam hukum adat internasional, hanya bisa dipraktikkan melalui institusi, sistem hukum dan konstitusi nasional. Tetapi, efektifitas sistem nasional dan internasional tersebut tergantung pada partisipasi aktif warga negara dalam melindungi hakhaknya sendiri. Pada saat yang sama, norma-norma hak asasi dan konstitusi membuat warga negara bisa bertukar informasi, mengorganisir dan melakukan aksi secara bersama-sama untuk mempromosikan visi mereka tentang kemaslahatan sosial dan melindungi hak-hak mereka. Dengan kata lain, konstitusionalisme dan hak asasi manusia adalah alat yang penting untuk melindungi status dan hak warga negara, tetapi fungsi tersebut dapat efektif justru karena peran warga negara sendiri. Karena itulah, proses klarifikasi terhadap dasar dan implikasi konsep kewarganegaraan menjadi penting. Konsep-konsep tersebut dan institusi yang menyertainya tergantung satu sama lain dan harus saling berinteraksi jika ingin merealisasikan tujuannya masing-masing. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Dengan berusaha mengklarifikasi prinsip-prinsip tersebut dari perspektif Islam, saya berharap bisa mendapatkan legitimasi dari kalangan muslim yang harus menerima prinsip-prinsip tersebut jika mereka ingin menerapkannya secara efektif dalam masyarakatnya. Hubungan antara Islam dan prinsip-prinsip tersebut tidak terhindarkan, karena Islam mempengaruhi secara langsung legitimasi dan kekuatan prinsip-prinsip tersebut dan institusi yang menyertainya dalam masyarakat Islam kontemporer. Pada saat yang sama, hubungan ini akan memusingkan dan kontraproduktif ketika Islam disamakan dengan pemahaman sejarah atas syari’ah. Padahal, pemahaman historis tersebut mengandung beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan. Namun saya tegaskan, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa prinsip-prinsip umum hak asasi manusia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari’ah. Malah, saya merujuk pada beberapa pemikiran syari’ah tradisional yang masih relevan untuk kehidupan publik masyarakat muslim saat ini, meskipun bukan pada hal-hal yang menyangkut akidah, ibadah atau aspek-aspek lain dalam muamalah. Untuk menempatkan diskusi tentang konstitusionalisme, hak asasi manusia dan konsep kewarganegaraan dalam konteks buku ini secara keseluruhan, saya ingin mengingatkan pembaca bahwa tujuan utama buku ini adalah untuk meyakinkan bahwa pemisahan institusi negara dan Islam dengan tetap menjaga keterhubungan antara Islam dan politik merupakan hal yang perlu dan penting. Dengan kata lain, adalah penting untuk terus menjaga netralitas negara terhadap agama secara tepat karena manusia cenderung mengikuti pandangan pribadinya, termasuk agama. Tapi tujuan pemisahan ini tidak bisa dicapai melalui usaha menempatkan agama dalam ruang privat, karena usaha seperti ini tidak penting, pun tidak perlu. Malah, upaya ©Abdullahi Ahmed An-Na`im pemisahan Islam dan negara harus dilakukan dengan tetap mengakui fungsi publik Islam dan pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan publik dan undang-undang. Ketegangan seperti ini harus terus diselesaikan melalui upaya pemunculan “public reason” dalam kerangka konstitusionalisme, hak asasi manusia dan kewarganegaraan yang akan didiskusikan dalam bab ini. Saya akan mulai dengan mengklarifikasi pembedaan antara negara dan politik dan hubungannya dengan keharusan adanya “public reason”. Prinsip-prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia dan kewarganegaraan akan didiskusikan dalam tiga bagian berikutnya. Bab ini akan ditutup dengan kesimpulan dan sekaligus selayang pandang mengenai cara prinsip-prinsip tersebut beroperasi sebagai kerangka untuk mengatur berjalannya “public reason” yang diharapkan dapat mengatur hubungan antara Islam dan politik di satu sisi dan hubungan antara Islam dan negara di sisi lain. I. Negara, Politik dan “public reason” 1. Karakter negara modern Semua muslim saat ini tinggal di sebuah teritori yang disebut sebagai “the nation” state (negara bangsa), yang berdasarkan model Eropa dan telah menjadi model yang dimapankan melalui penjajahan, bahkan di negara yang secara formal tidak pernah dijajah. Menurut sarjana Barat, model negara seperti ini ditandai dengan adanya “administrasi dan tata hukum yang terpusat dan terorganisasi secara birokratis dan dijalankan oleh sekelompok administratur, serta mempunyai otoritas atas apapun yang terjadi di wilayah kekuasaannya, basis teritorial dan monopoli untuk menggunakan kekuasaan”.1 Karena saya khawatir terhadap karakter inheren negara yang opresif dan hegemonik, saya lebih suka merujuk pada karakter teritorial negara 1 Graeme Gill, The Nature and Development of the Modern State (New York: Palgrave Macmilan, 2003), hlm. 2-3 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im daripada klaimnya sebagai representasi satu bangsa yang koheren dan homogen. Berikut ini adalah ciri-ciri negara sebagai kawasan teritorial:2 Negara modern adalah organisasi birokratis yang terpusat, hirarkis, dan dibagi-bagi menjadi institusi dan organ yang berbeda yang memiliki fungsi masing-masing. Namun, institusi-institusi itu beroperasi sesuai dengan aturan formal dan struktur akuntabilitas yang hirarkis dan jelas pada otoritas pusat. Institusi-institusi negara yang terpisah namun berhubungan ini, berbeda dengan organisasi sosial lain seperti partai politik, organisasi sipil, dan asosiasi bisnis. Meskipun pembedaan ini terasa jelas dalam tataran teoritis, namun dalam praktiknya, institusi-institusi negara sebetulnya terhubung dengan organisasi-organisasi non-negara tersebut. Hubungan ini penting agar institusi-institusi negara mendapatkan legitimasi dan dapat berfungsi efektif. Tapi tentu saja, cakupan dan fungsi institusi negara berbeda dengan organisasi non-negara sebab institusi dan aparatur negara harus mengatur aktor non-negara dan harus menengahi perbedaan di antara mereka. Hubungan kompleks antara perbedaan teoritis dan keterhubungan praksis antara lembaga negara dan organisasi non negara ini adalah salah satu aspek penting dalam pembedaan antara negara dan politik. Domain organisasi negara modern lebih luas dari organisasi- organisasi lain karena saat ini domainnya mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan 2 Gill, The Nature and Development of the Modern State, hlm. 3-7 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im lain sebagainya. Fungsi lembaga negara yang komprehensif dan luas ini juga menandakan keunikan, otonomi, dan independensi negara dari organisasiorganisasi lain. Untuk menunaikan fungsi dan perannya yang beragam ini, negara harus memiliki kedaulatan eksternal maupun internal. Lembaga negara harus menjadi pemilik otoritas tertinggi dalam wilayah kekuasaannya. Negara juga harus menjadi representasi otoritatif dari warga negara dan aktor-aktor yang berada dalam kawasan kekuasaannya bagi pihak-pihak yang berada di luar wilayahnya. Untuk alasan yang sama yang telah disebut diatas, negara juga harus memiliki monopoli untuk menggunakan kekuatan dan pemaksaan secara sah. Kemampuan ini sangat esensial bagi negara agar ia bisa memberdayakan otoritasnya untuk melindungi kedaulatannya, menjaga keutuhan hukum dan tatanannya, serta mengatur dan menengahi perselisihan dan lain sebagainya Namun demikian, kekuasaan negara terbatas pada wilayahnya. Suatu negara, biasanya, tidak mempunyai otoritas di luar wilayah kekuasaannya. Organisasi non-negara seperti komunitas keagamaan atau tarikat sufi dapat beroperasi dimanapun; lepas dari batas-batas politis negara karena mereka didirikan berdasarkan fungsi dan bukan batasan geografis. Rakyat suatu negara sering memiliki ikatan dan identifikasi sentimentil terhadap negaranya, namun itu bukan karakter negara yang ©Abdullahi Ahmed An-Na`im penting. Konsep “negara bangsa” misalnya, memang mengasumsikan adanya kesamaan identitas semacam etnik atau bahasa antara warga negara. Tapi asumsi ini bisa keliru, karena kawasan tidak selalu identik dengan etnik, agama atau ikatan-ikatan popular lain. Ikatan-ikatan semacam itu mungkin saja beraku bagi beberapa kelompok dalam satu wilayah negara, dan mungkin juga bisa sama dan berlaku bagi orang lain yang tinggal di wilayah lain. Memang, hampir semua negara berusaha untuk menumbuhkan perasaan kesamaan identitas nasional, namun kesamaan bukanlah ciri esensial sebuah negara modern. Negara juga cenderung memiliki tipe pemerintahan yang berbeda. Bisa jadi pemerintahannya adalah partai demokrat liberal, satu partai, monarki dan lain sebagainya. Tapi juga harus dicatat, ciri ini juga bukan sebuah karakter definitif. Tak ada satupun dari rezim tersebut yang layak disebut negara jika ia tidak memiliki administrasi yang terpusat dan birokratis, kedaulatan, serta monopoli untuk menggunakan kekusaan dan pemaksaan. Beberapa elemen negara modern mungkin dimiliki oleh organisasi non-negara, tapi tidak ada satu pun dari organisasi itu memiliki seluruh karakter negara. Secara khusus kedauatan atas wilayah merupakan ciri pembeda negara dari organisasi non-negara karena kedaulatan ini tidak dimiliki oleh organisasi non-negara manapun. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Ciri negara modern tersebut di atas biasanya didiskusikan dalam konteks pengalaman negeri-negeri Barat, meskipun modelnya juga diterapkan di beberapa negara Asia dan Afrika yang berpenduduk muslim. Elaborasi seorang penulis mungkin akan membantu upaya kita untuk mengklarifikasi ciri-ciri negara yang kita maksud dalam perbincangan ini.3 Organisasi negara terdiri dari seperangkat aturan, peran dan sumber daya yang ditujukan untuk meraih seperangkat tujuan yang jelas. Meskipun semua negara dicirikan dengan pembedaan antara negara dan organisasi non-negara, tingkat pembedaannya tidak selalu sama persis dan setara. Sebagai aturan utama, negaranya biasanya berwatak sekular dengan memisahkan dirinya dari ruang-ruang spiritual penganut atau organisasi agama. Penting pula untuk dicatat, bahwa meskipun negara dan institusinya berbeda dengan masyarakat sipil dan organisasinya, bahkan relatif otonom satu sama lain, namun keduanya tetap saling memberikan dukungan. Sebagai pemilik kekuasaaan dan otoritas atas wilayah dan hak monopoli pemaksaan, negara adalah otoritas terakhir. Otoritas terakhir merupakan konsekuensi dari kepemilikan negara atas kedaulatan dan integritas wilayah. Namun otoritas ini pun akan melemah, jika kedaulatan dan integritasnya hilang. Kedaulatan wilayah berarti negara memiliki kontrol eksklusif atas warga yang tinggal di wilayahnya dan wilayah ini tidak bisa dibagi dengan pihak lain kecuali atas persetujuan dan kerjasama negara itu sendiri. Dengan demikian, intervensi negara atau pihak luar lain dianggap melanggar prinsip kedaulatan wilayah yang dimiliki negara, kecuali bila intervensi itu dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Pengecualian ini sah karena dengan menandatangi Piagam PBB, semua negara yang 3 Gianfranco Poggi, The State: Its Nature, Development and Prospects (Stanford, California: Stanford University Press, 1990), hlm. 19-33. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im menjadi anggota PBB telah menyetujui otoritas yang dimiliki lembaga ini. Otoritas sentral negara berarti bahwa ia otonom. Hanya negara yang memiliki otoritas untuk membuat aturan yang mengatur cara kerjanya dan menjadi sumber bagi seluruh otoritas politik lain. Meskipun fungsi terakhir ini mungkin diserahkan pada organisasi atau pihak lain. Sentralitas negara juga berarti bahwa negara harus mengkoordinasikan fungsi dan aktifitas organ dan institusinya, karena merekalah yang memapankan kekuasaan negara. 4 Ciri negara yang lain dan relevan dengan pembicaraan kita saat ini adalah ia mendapatkan legitimasi demokratis atas kekuasaan dan otoritas yang dimilikinya. Ini berarti bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang paling mutlak atas negara, yang memang berfungsi untuk melayani mereka. Namun, meski rakyat memiliki otoritas dan kekuasaan mutlak, ketaatan mereka terhadap negara juga merupakan hal mutlak agar negara mampu melaksanakan fungsinya. Dukungan rakyat ternyata juga penting bagi negara yang dikuasai oleh rezim diktator atau kerajaan yang cenderung menjustifikasi dan melegitimasi otoritas mereka dengan “kehendak kolektif” dan “kepentingan rakyat”. Dari basis legitimasi inilah, konsep kewarganegaraan muncul untuk menjamin kesetaraan dan kesamaan hak dan kewajiban mereka di hadapan negara.5 Kombinasi legitimasi demokratis dan kewarganegaraan ini juga harus tercermin dalam watak dan fungsi hukum dalam sebuah negara. Apapun pandangan, sumber dan keputusan hukum di masa lalu, saat ini negara sudah semakin mampu mengambil alih fungsi pembuatan hukum dan tidak hanya memberlakukannya. Jika dulu otonomi hukum terletak pada statusnya sebagai seperangkat prinsip dan norma yang isi dan validitasnya 4 5 poggi, hlm. 22 Poggi, hlm. 28 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im bersumber dari agama, tradisi, dan praktik spontan masyarakat, maka saat ini hukum telah menjadi produk sekaligus instrumen kebijakan.6 Dari overview singkat di atas, negara modern bisa difahami sebagai representasi institusional sebuah kekuasaan politik, yang tidak lagi didapat dari otoritas personal seorang penguasa atau dari mereka yang mendapatkan otoritas dari penguasa. Kekuasaan politik negara, yang terpusat dan terlembaga, direfleksikan melalui struktur birokrasi dan organisasinya. Negara bahkan bisa memformalisasikan penggunaan kekuasaannya itu melalui standar dan prosedur hukum serta mempromosikan integrasi kekuasaan politik melalui legitimasi demokratis dan peningkatan pentingnya konsep kewarganegaraan sebagai prinsip yang mengatur hubungan negara dan masyarakat.7 2. Pembedaan Negara dan Politik Ciri-ciri negara yang telah saya kemukakan diatas jelas mengindikasikan adanya pembedaan antara domain negara dan politik secara umum, dimana negaralah yang menentukan isu-isu yang akan diperdebatkan dan dinegosiasikan di ruang politik dengan beragam formalitas dan proses. Negara juga diharapkan dapat membuat dan menegakkan aturan negosiasi bagi pihak-pihak yang berharap idenya terwakili dan diformulasikan sebagai kebijakan publik. Jangkauan negara modern sangat luas dan bahkan semakin diperluas hingga mencakup aspek-aspek eksistensi sosial lain seperti kesejahteraan sosial dan lingkungan. Meskipun berfungsi sebagai aktor utama yang memiliki jangkauan yang luas dalam struktur politik masyarakat, cakupan dan wilayah operasional negara dibatasi oleh dinamika relasi sosial di 6 7 Poggi, hlm. 29 poggi, hlm. 33 dengan penekanan khusus pada keaslian teks ©Abdullahi Ahmed An-Na`im sekelilingnya. Karena strukturnya yang formal, tugasnya yang penting, dan karakternya sebagai entitas yang otonom, negara tidak dapat mengeksplorasi secara penuh domain politiknya dalam masyarakat secara umum. Namun dengan ciri-ciri ini, tidak berarti negara menjadi berada “di atas” praktik politik massa atau terputus sepenuhnya dari masyarakat yang diaturnya. Karena untuk disebut sah, sebuah negara harus bisa mengakar di masyarakat, seperti halnya ia bisa menjaga otonomi operasional dan fungsionalnya dari politik keseharian. Relasi yang kompleks antara politik dan negara ini dapat difahami dari logika dan sikap negara yang harus otonom, namun mengakar dan terhubung dengan masyarakat. Sebagai institusi dan organ yang sangat kompleks, organisasi negara dapat dibagi secara vertikal berdasarkan fungsi dan secara horisontal berdasarkan geografi.8 Pembagian vertikal berhubungan dengan keberadaan “ruang utama” (major sphere) tempat berbagai aktor sosial bergabung dengan yang lainnya dan dengan negara: “dalam negara, ruang ini difahami sebagai bidang kebijakan (dan konstituen), dan ditandai dengan adanya berbagai departemen pelayanan publik yang dibentuk untuk melaksanakan bidang kebijakan tertentu seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, hukum, tatanan masyarakat dan urusan konsumen”.9 Sedangkan pembagian horisontal berarti pengorganisasian tata pemerintahan secara spasial. Negara, dengan demikian, bisa dibagi berdasarkan negara kesatuan ataupun negara federal, atau berdasarkan pembagian pemerintahan lokal atau regional.10 Pembagian vertikal berdasarkan fungsi juga dapat terbagi lagi secara horisontal melalui pembagian wilayah atau unit administratif. 8 Gill, hlm. 16 Gill, hlm. 16-17 10 Gill, hlm. 17 9 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Dalam pembagian vertikal, negara akan banyak berhubungan dengan berbagai aktor sosial dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan bidang kebijakan tertentu. Ia juga akan terlibat dalam hubungan-hubungan yang terus berkembang antara berbagai aktor negara dan politik dalam ruang sosial dan konstituen kebijakan yang lebih luas. Otonomi dan stabilitas negara tergantung pada kualitas hubungannya dengan berbagai segmen dalam masyarakat karena jika kualitas hubungan ini akan mempersulit kelompok tertentu untuk mengatur dan menguasai negara. Semakin normal politik negosiasi antar kelompok, semakin rendah pula kemungkinan kelompok-kelompok tersebut untuk tergoda dan mampu memaksakan kekuataannya untuk menguasai negara. Semakin banyak kelompok yang menyatakan klaimnya dan berpartisipasi dalam menekan negara, maka tidak akan ada satu kelompok pun yang mampu mengambil kontrol penuh atas institusi negara. Dengan cara seperti ini, otonomi negara akan lebih terjaga. Sebaliknya, bila sebagian kelompok tersisih dari percaturan politik praktis, mereka akan lebih termotivasi untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dan lebih tidak takut untuk mengalami kerugian dengan menantang premis dan operasi negara. Hubungan dinamis antara negara dan aktor sosial ini bersifat saling menguntungkan karena negara, pada dasarnya, mungkin konstituen. berkepentingan untuk mempengaruhi sebanyak “Untuk melaksanakan tugas, membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang dibuatnya, serta untuk melaksanakan fungsinya sebagai pembuat aturan bagi masyaraktnya, negara membutuhkan kerjasama konstituen-konstituen dan organisasi yang relevan tersebut. Sebagai gantinya, negara harus mengizinkan penetrasi institusinya.11 11 Gill, hlm. 17 pihak-pihak tersebut pada ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Mekanisme pertukaran kepentingan antar negara dan aktor sosial dan politik lain dapat berlangsung secara formal dan institusional seperti yang terjadi dalam proses tawar menawar negara dengan asosiasi dagang atau organisasi professional, kehadiran perwakilan NGO dalam institusinya, atau terlibatnya perwakilan NGO dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakannya. Mekanisme yang sama juga dapat ditempuh melalui cara informal seperti pengaruh atau hubungan perorangan. Apapun cara yang digunakan, itu tidak menjadikan negara sebagai satu-satunya perwakilan dari kelompok tertentu, bahkan negara tetap dapat menjaga otonominya karena ia mampu berinteraksi dengan berbagai kelompok. Dengan kata lain, kompetisi antar berbagai kelompok untuk mempengaruhi kebijakan negara, justru merupakan jaring pengaman bagi hadirnya kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaan negara. Bahkan, kompleksitas dan sentralitas negara justru berarti bahwa tidak ada kelompok atau kumpulan aktor-aktor sosial yang akan menantang otoritas negara atau menghilangkan otoritasnya dengan menekan salah satu institusi.12 Karena institusi negara tergantung pada otoritas sentral dan tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi seluruh aparatur negara, otonomi negara dicapai melalui pengaruh yang tak proporsional dari institusi non-negara. Dengan demikian, negara dapat difahami sebagai arena tempat aktor-aktor politik dan sosial berkompetisi untuk meraih tujuan-tujuannya. Namun pada saat yang sama, keragaman aktoraktor yang berpartisipasi dalam proses kompetisi ini juga menjamin otonomi negara.13 Negara dapat menempuh jalur ekonomi, sosial maupun budaya untuk mengikatkan dirinya 12 13 dengan Gill, hlm. 18 Gill, hlm. 18-19 kelompok-kelompok dalam masyarakat, misalnya dengan ©Abdullahi Ahmed An-Na`im mengangkat pegawai dari kelas sosial atau daerah tertentu dan menyediakan ruang bagi wakil rakyat terpilih untuk berpartisipasi atas nama konstituennya dalam proses pembuatan kebijakan negara. Perbedaan antara pegawai negara yang mewakili kelas sosial atau etniknya dengan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan adalah kebebasan kedua kelompok tersebut untuk mempertahankan ikatan identitasnya ketika mereka telah terpilih. Pegawai negara tidak boleh mempertahankan ikatan etnis dan sosialnya, tetapi wakil rakyat harus tetap mempertahankan ikatan tersebut karena ia terikat dengan konstituen yang memilihnya.14 Sebagai kesimpulan, legitimasi dan kekuatan negara tergantung pada keterhubungannya dengan aktor sosial dan politik lain dan juga pada otonominya dari pengaruh mereka. Semakin terhubung sebuah negara dengan masyarakatnya, akan semakin rendah resikonya untuk kehilangan otonomi. Banyaknya kelompokkelompok kepentingan yang bersaing untuk mempengaruhi kebijakan negara malah akan menjaga keseimbangan pengaruh yang mereka miliki terhadap negara. Otonomi negara juga akan relatif tidak terancam oleh satu kelompok atau beberapa kelompok, bila struktur negara tetap terpusat, kompleks, dan institusi-institusinya diatur dengan seperangkat aturan yang jelas. Karena penjelasan lebih lanjut tentang teori politik dan negara sudah tidak memungkinkan lagi, saya berharap bisa memanfaatkan ulasan mengenai ciri-ciri dan dinamika hubungan politik dan negara ini untuk menjelaskan pertanyaan utama kita yaitu: bagaimana hubungan negara dan masyarakat atau hubungan negara dan politik bisa dijembatani melalui “public reason”? 14 Gill, hlm. 20 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im 3. “Public reason” untuk Memediasi Konflik Kebijakan Diskusi kita yang telah lalu mengindikasikan bahwa legitimasi negara dapat diukur dari seberapa dalam dan organiknya hubungan antara negara dengan berbagai aktor non-negara dalam wilayah politik. Otonomi negara akan hilang atau berkurang bila negara hanya mengizinkan satu kelompok untuk mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pada salah satu institusinya atau bahkan negara secara keseluruhan. Dengan kata lain, pelaksanaan kombinasi legitimasi dan otonomi ini sangat tergantung pada dua persyaratan. Pertama, aktor non negara membutuhkan ruang yang aman untuk bersaing secara bebas dan sehat untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan melalui peran negara. Kedua, ruang yang tersedia tersebut harus dapat menjamin terbukanya kesempatan bagi sebanyak-banyaknya kelompok untuk berkompetisi. Semakin banyak dan beragam kelompok yang dapat bersaing secara bebas dan sehat untuk mengamankan kepentingan dan urusannya dalam sebuah kebijakan, semakin kecil pula kemungkinan mereka untuk mengontrol negara atau institusinya. Dua hal tersebut mengindikasikan apa yang saya istilahkan sebagai “public reason” dimana para aktor sosial dapat mempengaruhi negara dengan tetap tidak membahayakan otonomi negara. Konsep ini berisi beberapa elemen seperti prosedur efektif untuk menjamin partisipasi bebas dan sehat, pedoman mengenai isi dan etika debat publik, bahkan perangkat pendidikan dan perangkat lain yang digunakan untuk meningkatkan legitimasi dan efektifitas persyaratan tersebut. Dengan berpegang pada penjelasan mengenai ciri-ciri negara modern yang telah saya kemukakan diatas dan bagaimana ia harus dibedakan dengan politik, saya akan memberi penekananan pada beberapa point yang berkaitan dengan “public reason” sebagai berikut: ©Abdullahi Ahmed An-Na`im 1. Ruang bagi public reason harus tetap aman sehingga proses argumentasi terbangun dalam suasana yang mudah untuk dikendalikan oleh pemerintahan atau rezim tertentu atau dikontrol oleh satu kelompok sosial tertentu. Agar dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat, ruang bagi public reason harus didentifikasi sebagai negara, bukan sebagai satu rezim atau masa pemerintahan tertentu. 2. Selain itu, ruang bagi “public reason” harus diamankan melalui prinsip-prinsip konstitusionalisme, sekularisme yang menjamin netralitas negara terhadap agama, hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Prinsipprinsip tersebut merupakan elemen organisasi politik dan tata hukum sebuah negara, yang tidak akan mudah dibatalkan oleh pemerintahan apapun. Namun, meski berfungsi sebagai jaring pengaman, prinsip-prinsip tersebut bukanlah sesuatu yang absolut. Ia dapat berubah seperti Undang-Undang yang bisa diamandemen. Kadar netralitas negara terhadap agama bisa terus dinegosiasikan (hal ini akan secara khusus dijelaskan nanti dalam bab 4), pun prinsip hak asasi manusia terus bisa tumbuh dan berkembang. Sistem politik dan hukum sebuah negara harus memungkinkan adanya ketentuanketentuan khusus yang berlaku pada saat gawat darurat, tetapi tetap harus tunduk pada jaring pengaman ini agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan pengecualian ini. Tujuan prinsip-prinsip ini adalah agar aturan yang menjamin public reason itu tidak mudah diubah hanya untuk memenuhi keinginan sekelompok kecil masyarakat tertentu. 3. Selain menyediakan jaring pengaman, negara tidak boleh mempengaruhi wacana public reason dengan membatasi jumlah pihak yang boleh terlibat dalam ruang public reason dengan mendiskriminasi kelompok agama, komunitas atau kelompok minoritas tertentu. Sebaliknya, negara ©Abdullahi Ahmed An-Na`im harus dapat menyediakan ruang bagi sebanyak mungkin warga negara, baik sebagai individu atau bagian dari kelompok tertentu, untuk mewakili dan berdebat mengenai kebijakan publik. Ini tentu saja bukan perkara mudah, karena banyak pemerintahan yang bertindak atas nama negara tergoda untuk memanipulasi public reason untuk kepentingannya sendiri. 4. Meskipun negara harus mempersiapkan aturan dan pedoman dasar public reason, namun domain public reason tetap harus berada di wilayah civil society. Dengan kata lain, meskipun negara mengatur public reason, bukan berarti public reason adalah institusi negara. Posisi ini justru memperkokoh status otonom negara karena negara dapat mendorong adanya keragaman di kalangan aktor sosial politik sekaligus menyediakan ruang bagi terciptanya debat, konsensus, dan aliansi di kalangan mereka. Karena istilah “public reason” telah banyak digunakan oleh kalangan sarjana Barat, nampaknya disini saya perlu mengklarifikasi pengertian “public reason” yang saya gunakan dalam tulisan ini. Saya akan terlebih dahulu mengulas secara singkat istilah “public reason” seperti yang digunakan oleh Jhon Rawls dan beberapa komentar mengenainya. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana debat tentang istilah ini berkaitan dengan makna “public reason” yang saya gunakan dalam perbincangan Islam, Negara dan Politik. Rawls berpendapat bahwa public reason adalah ciri utama relasi negara dan rakyat dalam tatanan negara yang demokratis dan konstitusional.15 Menurutnya, “ide tentang public reason menetapkan bagian terdalam landasan moral dan nilai-nilai 15 John Rawls, Political Liberalism, (expanded edition, New York: Columbia University Press, 2003), hlm. 212-254, hlm. 435-490. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im politik yang menentukan relasi antara pemerintahan yang demokratis dan konstitusional dengan rakyatnya”.16 Ia mendefinisikan public reason sebagai: “reason ini disebut public karena tiga hal. Pertama, jika reason itu muncul dari warga negara yang bebas dan setara. Kedua, jika reason ini berisi tentang kemaslahatan publik yang berkaitan dengan masalah keadilan politik yang fundamental yang mempermasalahkan esensi undang-undang dasar dan soal keadilan dasar. Ketiga, watak dan isinya yang memang publik, diungkapkan dengan penalaran publik melalui sekumpulan konsep keadilan politik rasional yang telah difikirkan secara rasional pula, untuk memenuhi kriteria resiprositas.17 Dengan demikian, bagi Rawls ruang public reason menyinggung masalah “esensi undang-undang dasar dan masalah keadilan dasar yaitu hak-hak dan kebebasan fundamental yang mungkin termasuk dalam undang-undang dasar dan masalah keadilan dasar yang berkaitan dengan keadilan sosial dan ekonomi serta hal lainnya yang tidak terbahas dalam undang-undang dasar. Fokus spesifik ini memperlihatkan bahwa Rawls memandang public reason “tidak berlaku untuk semua diskusi politik tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental”.18 Ia membedakan antara cakupan public reason dengan apa yang dia sebut sebagai “latar belakang kultural” (background culture) masyarakat sipil yang mewujud dalam bentuk asosiasi seperti gereja, universitas, dan lain sebagainya.19 Menurutnya, reason yang muncul dalam ruang-ruang tersebut, meskipun tidak sepenuhnya “privat” dan diungkapkan dalam ruang “sosial”, namun tetap saja bersifat “non-public” jika dibandingkan 16 Rawls, hlm. 441-442 Rawls, hlm.442 18 Rawls, hlm. 442 19 Rawls, hlm. 443 17 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im dengan masyarakat secara keseluruhan.20 Bahkan, reason yang diungkapkan dalam media pun tidak dianggap “public reason” oleh Rawls.21 Ruang yang tepat bagi public reason menurut Rawls adalah “forum politik publik” (public political forum) yang mungkin terjadi dalam tiga keadaan. “Pertama, perdebatan pada hakim untuk menentukan keputusan, terutama hakim-hakim di Mahkamah agung. Kedua, perdebatan pegawai pemerintahan, terutama mereka yang duduk di kursi eksekutif dan para pembuat undang-undang. Ketiga, perdebatan calon pejabat negara dan manajer kampanyenya, terutama, dalam orasi publik, platform partai dan ungkapan-ungkapan politiknya.”22 Dalam keadaankeadaan itulah, penerapan public reason mengambil bentuk yang khusus dan tertentu. Meskipun, “justifikasi publik yang diperlukan untuk reason yang muncul dalam tiga keadaan itu sama dengan reason yang muncul dalam keadaan lain”, namun, mungkin akan berlaku lebih ketat bagi para hakim, terutama yang berada di mahkamah agung.23 Pandangan Rawls mengenai “public reason” menyaratkan adanya demokrasi konstitusional yang sudah mapan dan didukung oleh adanya tertib hukum. Warga negara memiliki hak untuk mendasarkan pandangannya pada apa yang dia sebut sebagai “doktrin-doktrin yang komprehensif” atau pandangan dunia yang luas seperti agama, moralitas atau filsafat. Namun, doktrin-doktrin tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai public reason.24 “public reason” juga tidak boleh “mengkritisi atau menyerang” doktrin-doktrin komprehensif manapun, baik doktrin itu doktrin 20 Rawls, hlm. 220 Rawls, hlm. 444 22 Rawls, hlm. 442-443 23 Rawls, hlm. 231-240 24 Rawls, hlm. 441 21 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im keagamaan atau bukan. “Public reason” harus diartikulasikan dalam konsep dan nilai politik fundamental. “Syarat utama doktrin yang dimunculkan dalam domain public reason adalah doktrin tersebut dapat difahami dan menerima rezim demokratis konstitusional serta gagasan mengenai hukum yang sah.”25 Meskipun demikian, Rawls nampaknya masih menerima kemungkinan pengungkapan doktrin-doktrin komprehensif dalam public reason pada situasi tertentu, tergantung pada tingkat ekslusivitas dan inklusivitas pandangan terhadap doktrin yang digunakan. Jika sifatnya ekslusif, doktrin komprehensif tersebut tidak boleh diungkapkan kepada publik meskipun ia mendukung “public reason”. Tetapi bila pandangannya inklusif, siapapun bisa menjadikan doktrin tersebut sebagai sumber nilai-nilai dasar politik yang mereka anut dan mengungkapkannya untuk memperkuat “public reason”.26 Pandangan yang ekslusif bisa digunakan dalam “masyarakat yang sudah lebih teratur” (more or less well ordered society), dimana keadilan dan hak-hak dasar warga negara terjaga dengan baik sehingga ekspresi “public reason” cukup menggunakan nilai-nilai politik yang tumbuh di masyarakat sendiri dan tidak perlu merujuk pada doktrin komprehensif apapun. Rawls membedakan kondisi ini dengan kondisi dimana terjadi “perselisihan serius antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang hampir teratur (nearly well ordered society)” mengenai penerapan salah satu prinsip keadilan”. Misalnya perselisihan berbagai kelompok mengenai masalah dukungan pemerintah terhadap pendidikan agama. Dalam situasi seperti itu, penjelasan di sebuah forum publik tentang “bagaimana doktrin komprehensif yang diyakini oleh seseorang sesuai dengan nilainilai politik” mungkin dapat mengokohkan dan melegitimasi public reason itu 25 26 Rawls, hlm. 441 Rawls, hlm. 247 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im sendiri.27 Rawls mengambil contoh orang-orang yang berjuang menghapus perbudakan berdasarkan nilai-nilai agama pada abad 19 di Amerika Serikat. Saat itu non-public reason dari gereja-gereja tertentu mendukung kesimpulan akhir public reason.28 Contoh lainnya adalah gerakan perjuangan hak-hak sipil, Meskipun Martin Luther King Jr. memperoleh rujukan perjuangannya dari nilai-nilai politik dalam konstitusi, ia tetap menggunakan non-public reason untuk melegitimasi perjuangannya. Dalam dua kasus di atas, para pemimpin gerakan penghapusan perbudakan dan perjuangan hak-hak sipil memang menyetujui cita ideal public reason, tetapi konteks sejarah perjuangan mereka mengharuskan penggunaan doktrin komprehensif untuk memperkuat nilai-nilai politik yang sedang mereka perjuangkan. Gerakan mereka, pada intinya, justru memperkuat cita ideal “public reason” karena mereka menggunakan pandangan inklusif doktrin komprehensif tersebut. Dengan demikian, batasan yang tepat untuk “public reason” akan sangat tergantung pada konteks historis dan sosialnya.29 Saya tidak mungkin mereview semua debat yang berlangsung di kalangan sarjana barat tentang ide Rawls ini, tapi saya akan menjelaskan secara singkat 2 kritik yang akan sangat berguna untuk menjelaskan istilah “public reason” yang saya gunakan dalam buku ini. Pertama, kritik Habermas terhadap ide Rawls terutama mengenai pembedaan antara istilah “doktrin komprehensif” dengan “nilai-nilai politik” (political values).30 Habermas juga mempertanyakan pengertian Rawls mengenai istilah “political” dalam istilah “nilai-nilai politik” dan pembedaan domain privat dan domain publik dalam kehidupan sosial. Menurut Habermas, “Rawls 27 Rawls, hlm. 248-249 Rawls, hlm. 249-250 29 Rawls, hlm. 251 30 Jurgen Habermas, “Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks on Jhon Rawls’ Political Liberalism”, in The Journal of Philosophy, 92: 3 (March 1995): 109-131, pada hlm.118-119 28 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im memperlakukan ruang nilai-nilai politik (political value sphere), yang dalam masyarakat modern ruang ini dibedakan dari ruang nilai-nilai kultural (cultural value sphere), sebagai sesuatu yang sudah begitu adanya”. Rawls juga telah membagi identitas seseorang menjadi identitas politik publik dan identitas pra politik yang non publik di luar pencapaian swa legislasi yang demokratis”.31 Bagi Habermas, ide Rawls ini bertentangan dengan fakta sejarah mengenai pergeseran batas-batas ruang publik dan privat. Kedua, penekanan Habermas terhadap ruang-ruang independen dan ruang-ruang non-pemerintah yang merupakan arena penting bagi tumbuh dan berkembangnya “public reason”. McCarthy menyimpulkan pandangan Habermas ini sebagai berikut: “bagi Habermas, forum publik independen yang terpisah dari sistem ekonomi dan administrasi kenegaraan dan lebih memiliki tempat di dalam asosiasi-asosiasi sukarela, gerakan-gerakan sosial termasuk media massa merupakan sumber utama kedaulatan rakyat. Idealnya, public reason yang diungkapkan dalam ruang nonpemerintah bisa diterjemahkan menjadi kekuasaan administratif negara yang sah, melalui prosedur pembuatan keputusan yang sah dan terlembagakan seperti prosedur pemilihan dan legislatif. Dalam bahasa Habermas, “kekuasaan yang tersedia bagi administrasi ini muncul dari public reason… Opini publik yang bekerja melalui prosedur-prosedur demokratis memang tidak bisa memerintah secara langsung, tetapi bisa mengarahkan kekuatan administratif tersebut pada tujuantujuan tertentu.32 Untuk menyimpulkan bagian ini, saya akan mengungkapkan pengertian “public reason” yang saya gunakan dalam buku ini dan bagaimana pengertian ini berkaitan 31 Habermas, hlm.129 Thomas McCarthy, “Kantian Constructivism and Reconstructivism: Rawls and Habermas in Dialogue. Dalam Ethics 105: 1 (Oktober 1994): 44-63 pada hlm. 49 32 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im dengan ide-ide yang telah dikemukakan oleh sarjana-sarjana Barat. Saya mendefinisikan “public reason” dalam bab 1 sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh alasan dan tujuan sebuah kebijakan publik atau undang-undang dalam bentuk penalaran yang menyediakan kemungkinan bagi seluruh warga negara untuk menerima, menolak bahkan membuat ajuan tandingan melalui mekanisme debat publik tanpa berresiko dikenakan tuduhan makar, membangkang atau murtad. Ide saya ini mungkin didukung oleh pendapat Rawls dan Habermas, namun pengalaman masyarakat Barat yang menjadi konteks pemikiran mereka, mungkin tidak akan terlalu relevan untuk pengalaman masyarakat yang saya sebutkan dalam buku ini. Ide Rawls mengenai pembedaan antara konsep politik dan doktrin komprehensif, misalnya, akan berguna bagi saya untuk menentukan kerangka bagi ekspresi public reason. Namun pembedaan ini mengasumsikan adanya sebuah tatanan undang-undang dan masyarakat yang stabil yang memiliki kondisi kondusif bagi tumbuhnya debat mengenai isu-isu public reason. Sebuah keadaan yang sulit ditemui di dunia Islam. Karena itu, saya lebih suka mengambil pendapat-pendapat tersebut untuk memperkuat argumen yang saya buat tanpa mengidentifikasi diri secara khusus pada salah seorang di antara mereka atau berpartisipasi dalam debat kalangan Barat. Saya mengajukan sebuah pandangan mengenai public reason yang berakar pada tradisi civil society dan ditandai dengan adanya persaingan sehat antara berbagai aktor sosial untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui peran negara. Dengan merujuk pada ciri-ciri negara yang telah disebutkan diatas, pelaksanaan public reason di ruang non-negara justru akan semakin melebarkan legitimasi dan otonomi negara. Ruang public reason menyediakan tempat bagi warga negara sebuah forum dan mekanisme untuk menuntut hak-hak mereka atas negara. Keberadaan sebuah ©Abdullahi Ahmed An-Na`im forum yang egaliter dan inklusif, tempat dimana warga negara memiliki hak untuk berpastisipasi, menguatkan fakta bahwa negara bukan merupakan bagian dari satu kelompok atau beberapa kelompok tertentu. Meskipun ruang public reason harus dilindungi dan diatur berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, ketiga prinsip itu pun harus mendapatkan legitimasi dari proses public reason. Saya akan mengulang tema ini dalam bagian kesimpulan, setelah mendiskusikan masing-masing prinsip tersebut dalam kaitannya dengan pikiran saya dalam buku ini secara keseluruhan. II. Konstitusionalisme dalam Perspektif Islam Tata pemerintahan yang konstitusional merujuk pada adanya seperangkat prinsip yang membatasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah sesuai dengan hak-hak fundamental warga negara dan komunitas, serta sesuai dengan tata hukum yang menjamin hubungan antara individu dan negara diatur oleh prinsip-prinsip hukum yang jelas, bukan oleh kehendak elit penguasa yang despotik.33 Saya menggunakan istilah konstitusionalisme untuk memayungi jaringan sejumlah lembaga, proses dan budaya yang lebih luas, yang diperlukan untuk menjalankan tata pemerintahan yang konstitusional secara efektif dan berkelanjutan.34 Saya sendiri lebih tertarik pada seperangkat nilai, lembaga serta proses politik dan sosial yang dinamis dan komprehensif, daripada penerapan formal prinsip-prinsip umum yang abstrak atau aturan-aturan hukum yang spesifik. Prinsip-prinsip hukum dan undang-undang memang relevan dan penting, tetapi implementasi prinsip-prinsip tersebut secara 33 J.T McHugh, Comparative Constitutional Traditions (New York: Peter Lang, 2002, hlm. 2-3 Alan S. Rosenbaum, Introduction to Constitutionalism the Philosophical Dimension, ed. Alan S. Rosenbaum (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1988), hlm. 4-5; Louis Henkin, “A New Birth of Constitutionalism: Genetic Influences and Genetic Defects” dalam Constitutionalism, Identity, Differences and Legitimacy, ed. Michel Rosenfeld (Durham, North Carolina: Duke University Press, 1994), hlm. 39-53; dan Constitutionalism, eds. J. Roland Pennock and John W. Chapman (New York: New York University Press, 1979). 34 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im efektif dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui konsep konstitusionalisme yang lebih luas dan dinamis. Pemahaman dasar tentang konstitusionalisme yang saya sebutkan disini berdasarkan pada dua hal. Pertama, konsepsi yang beragam mengenai prinsipprinsip dan lembaga-lembaga konstitusionalisme harus dilihat sebagai pendekatan komplementer terhadap model pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab yang bisa beradaptasi pada perubahan waktu dan tempat, daripada sebagai representasi dikotomi yang tajam atau pilihan-pilihan yang kategoris. Karena definisi konsep ini merupakan produk pengalaman masyarakat yang hidup dalam keadaan tertentu, maka menetapkan hanya satu pendekatan terhadap definisi atau cara implementasi konsep ini dan mengenyampingkan pendekatan lain, menjadi tidak masuk akal dan tidak penting. Baik berdasarkan dokumen tertulis atau tidak, konsep ini bertujuan untuk menegakkan tatanan hukum, menjalankan pembatasan yang efektif terhadap kekuasaan pemerintah, dan melindungi hak asasi manusia. Pemahaman yang lebih universal terhadap konstitusionalisme mungkin akan berkembang dari waktu ke waktu, tapi pemahaman ini harus merupakan hasil analisis komparatif terhadap pengalaman praksis, bukan hasil usaha pemaksaan satu definisi ekslusif yang berdasarkan satu ideologi atau tradisi filsafat tertentu. Kedua, saya sangat percaya bahwa prinsip-prinsip tersebut hanya bisa direalisasikan dan dikembangkan melalui praktik dan pengalaman. Karenanya, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, misalnya, hanya bisa dicapai melalui praktik aktual yang kondusif bagi adanya koreksi teori dan modifikasi praktik, bukan dengan menunda sampai sebuah kondisi ideal bagi pelaksanaan konsep itu dicapai oleh penguasa. Usaha-usaha untuk mencapai kedaulatan rakyat dan keadilan sosial itulah yang ©Abdullahi Ahmed An-Na`im justru menyediakan kesempatan bagi munculnya keadaan yang lebih kondusif bagi pelaksanaan konstitusionalisme yang sukses dan berkelanjutan. Dengan demikian, akhir sebuah tata pemerintahan yang konstitusional justru direalisasikan melalui pengalaman mempraktikkan prinsip-prinsip konstitusional dalam konteks masingmasing masyarakat. Pengalaman praksis tersebut, pada akhirnya, akan mempengaruhi refleksi teoritis terhadap prinsip-prinsip tersebut dan meningkatkan cara praktiknya di masa yang akan datang. Praktik Lokal dan Prinsip-Prinsip Universal Secara umum, konstitusionalisme merupakan respon tertentu terhadap paradoks dasar pengalaman praksis sebuah masyarakat. Di satu sisi, sudah jelas bahwa seluruh anggota masyarakat tidak mungkin dapat berpartisipasi secara sejajar dalam pelaksanaan urusan-urusan publiknya. Namun di sisi lain, jelas pula bahwa orang cenderung untuk memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda berkaitan dengan hal-hal seperti kekuasaan politik, alokasi dan pengembangan sumber daya ekonomi, serta pelayanan dan kebijakan sosial. Disinilah negara menjadi pihak yang berperan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik kepentingan itu. Namun dalam praktiknya, fungsi tersebut juga dijalankan oleh aparatur negara (manusia), dan bukan oleh badan resmi yang abstrak dan lembaga yang netral. Konstitusionalisme, dengan demikian, berfungsi memberikan ruang bagi pihakpihak yang memiliki kontrol langsung terhadap aparatur negara untuk memastikan bahwa pandangan dan kepentingan mereka dipenuhi oleh mereka yang bertugas untuk mengatur negara itu. Realitas inilah yang menjadi dasar bagi semua aspek konstitusionalisme, baik yang berkaitan dengan struktur dan lembaga negara maupun aktivitasnya dalam membuat dan menjalankan kebijakan publik dan administrasi keadilan. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Dengan demikian, tata pemerintahan konstitusional mengharuskan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak indidividu dan masyarakat karena makna dan implementasi kedua hak ini berkaitan satu sama lain. Contohnya, menghormati kebebasan individu untuk mengutarakan pendapat, keyakinan dan berorganisasi adalah satu-satunya cara untuk melindungi hak kebebasan kelompok etnik dan agama tertentu. Tapi, kebebasan individual itu akan bermakna dan bisa dijalankan secara efektif dalam konteks kelompok yang relevan. Selain itu, karena hak merupakan alat untuk merealisasikan tujuan keadilan sosial, stabilitas politik dan perkembangan ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat, hak harus difahami sebagai sebuah proses dinamis daripada aturan-aturan hukum yang abstrak. Namun, hak-hak seperti kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi tidak akan berguna tanpa adanya lembaga-lembaga untuk menjalankannya termasuk adanya kemampuan untuk mengajukan dan menindak perbuatan pegawai pemerintahan dan menjaga mereka agar tetap akuntabel. Karena itu, pegawai pemerintahan seharusnya tidak boleh menyembunyikan kegiatannya, menutup-nutupi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya. Yang secara umum berarti transparansi kegiatan pegawai negara adalah sebuah kebutuhan. Transparansi ini dapat dicapai melalui perundang-undangan, aturan administratif dan juga kebebasan pers, serta kemungkinan adanya tuntutan atas pegawai negara yang menyalahgunakan kekuasaannya atau menghindari tanggung jawabnya. Transparansi administratif dan finansial tidak mungkin menghasilkan akuntabilitas politik dan hukum, bila tidak disertai adanya lembaga yang independen dan kompeten yang bisa menginvestigasi kemungkinan pelanggaran dan bisa menyelesaikan pertikaian. Namun sayangnya, proses-proses yang berkaitan dengan ©Abdullahi Ahmed An-Na`im masalah-masalah teknis tentang adminitrasi peradilan dan hukum sampai persiapan praktis untuk mengamankan independensi kehakiman atau akuntabilitas politik pejabat terpilih, tidak bisa didiskusikan secara detail sekarang. Aspek konstitusionalisme yang terpenting berkaitan dengan motivasi psikologis dan kemampuan sosiologis warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolektif mempromosikan dan melindungi hak dan kebebasan. Penegakan semua prinsip, lembaga dan proses konstitusionalisme tergantung pada kerelaan dan kemampuan warga negara untuk berbuat demi kemaslahatan bersama, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok golongan dan lapisan masyarakat tertentu. Tentu saja aspek-apek motivasi dan kemampuan itu sulit untuk dihitung dan diverifikasi, tetapi semuanya melibatkan motivasi warga negara untuk selalu mengetahui urusan-urusan kemasyarakatan dan selalu bertindak secara kolektif. Agen dan lembaga publik yang dioperasikan oleh warga negara tidak saja harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lokal, tetapi juga harus ramah, responsif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Inilah makna yang paling mendasar dan praksis dari kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat mengatur dirinya sendiri melalui pegawai publik dan wakilnya yang sudah terpilih. Jadi, konstitusionalisme pada intinya adalah bagaimana merealisasikan dan mengelola ide ideal ini dengan cara yang dinamis dan berkelanjutan, dengan menyeimbangkan stabilitas yang diperlukan sekarang dengan kebutuhan akan adaptasi dan pengembangan di masa yang akan datang. Prinsip konstitusionalisme kadang-kadang diekspresikan dalam istilah hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) dimana rakyat berhak menentukan secara bebas status politik mereka dan meraih kemajuan ekonomi, sosial dan ©Abdullahi Ahmed An-Na`im kultural mereka. Hak ini kadang-kadang disalahfahami sebagai hak untuk memisahkan diri dari negara yang sudah ada. Adalah lebih baik untuk melihat pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, daripada melihatnya sebagai sesuatu yang harus dipenuhi sekaligus setelah meraih kemerdekaan politik dari kekuasaan kolonial luar. Benar bahwa kedaulatan negara merupakan kondisi awal untuk pemenuhan hak untuk menentukan nasib diri. Tapi kedaulatan negara saja tidak selalu penting dan cukup dalam segala situasi. Negara terpisah tidak selalu penting bagi mereka yang ingin merealisasikan hak menentukan nasib sendiri, karena hak itu bisa dicapai dalam kerangka negara yang sudah ada, asal pemerintahannya akuntabel dan representatif. Negara terpisah mungkin juga tidak akan cukup, karena rakyat juga bisa ditindas lagi oleh hegemoni internal kelompok penguasa dan ideologi eksklusif atau kekuatan kolonial luar.35 Karena kekuasaan kolonial biasanya lebih mudah dihadapi daripada hegemoni internal, saya akan secara khusus membahas bahayanya melegitimasi hegemoni dan penindasan semacam itu dalam masyarakat Islam saat ini, dengan mengungkapkan pentingnya agama dalam upaya menekan kekuatan oposisi politik dan akuntabilitas pemerintah. Konstitusionalisme selalu berkaitan dengan kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kejadian-kejadian yang membentuk kehidupan mereka baik pada tingkat personal, keluarga maupun masyarakat. Konstitusionalisme berkaitan dengan upaya penataan dan pengamanan ruang publik untuk rakyat agar mereka dapat mencari, bertukar, berdebat dan menilai sebuah informasi secara bebas serta dapat bergabung dengan yang lain agar dapat melakukan sesuatu untuk mencapai 35 Lihat misalnya Abdullahi A. An-Na’im dan Francis M. Deng, “Self-Determination and Unity: The Case of Sudan, dalam “Law and Policy, Vol. 18 (1996), hlm.199-223 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im tujuannnya. Konsep dasar ini juga mengindikasikan bahwa kesamaan akses itu harus disediakan bagi seluruh anggota masyarakat karena hidup mereka ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang sedang terbentuk. Dalam praktiknya, prinsip seperti ini menimbulkan persoalan lain yang terkait dengan pembedaan antara status warga negara (citizen) yang memiliki keanggotaan penuh serta seperangkat hak dan kewajiban, dengan permanen residen (permanent resident) yang hanya memiliki separuh keanggotaan, serta dengan orang asing (aliens) yang jelas-jelas tidak memiliki hak untuk terlibat dalam proses-proses demokrasi konstitusional. Prinsip konstitusionalisme berisi beberapa prinsip umum seperti pemerintahan yang representatif, transparansi, akuntabilitas, pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta independensi lembaga kehakiman. Tapi, ini bukan berarti bahwa semua prinsip-prinsip ini harus ada agar konstitusionalisme dapat diimplementasikan dengan sukses di sebuah negara. Kenyataannya, prinsip-prinsip dan kondisi itu hanya bisa muncul dan berkembang dalam berbagai model melalui proses trial and error yang terus menerus.36 Pemerintahan yang representatif, transparansi, akuntabilitas bisa direalisasikan dalam berbagai model seperti sistem parlementer Inggris atau Sistem presidensial Perancis dan Amerika. Model-model tersebut bukan merupakan satu-satunya sistem sebuah negara, sistem itu dapat berubah dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di sana.37 Meski berhadapan dengan masalah dan kesulitan, setiap model negara konstitusional yang sukses pasti bekerja dengan totalitas dan ia terus bertransformasi dan menyesuaikan 36 D. Franklin dan M. Baun (ed.), Political Culture and Constitusionalism: A Comparative Approach (New York: M. E. Sharpe), hlm. 184-217 37 McHugh, Comparative Constitutional Traditions, hlm. 50-54, 57-58, 147, 149-150. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im diri dengan caranya sendiri dalam situasi krisis. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam kasus Perancis dan Jerman pada Abad ke -20.38 Pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga kehakiman, misalnya, bisa diamankan baik melalui penataan struktural dan institusional seperti yang terjadi di Amerika,39 atau dengan cara politik konvensi dan praktik tradisi dalam kultur politik negara seperti Inggris.40 Pembedaan yang ketat antara cara konvensi dan tradisi, di satu pihak, dengan cara struktural dan institusional, di pihak lain, bisa jadi salah, karena masing-masing model mungkin membutuhkan atau mengandaikan adanya model lain agar dapat berfungsi dengan baik. Perbedaan seperti ini lebih merupakan produk pengalaman sejarah dan konteks masing-masing negara, daripada hasil pilihan yang sengaja dibuat pada titik waktu tertentu.41 Yang paling penting dari semua itu adalah kemampuan sistem tersebut untuk mencapai tujuantujuan konstitusionalnya meskipun praktiknya berbeda-beda. Dengan mengatakan bahwa kita harus bertahan pada model tertentu yang sukses mengimplementasikan konstitusionalisme, bukan berarti bahwa sistem-sistem yang sudah ada itu juga kondusif untuk menjaga keberlanjutan implementasi beberapa prinsip konstitusionalisme seperti pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga negara dan independensi lembaga kehakiman. Meskipun ini hanya persoalan tingkat 38 William Safran, “The Influence of American Constitutionalism in Postwar Europe: the Bonn Republic Basic Law and the Constitution of the Fifth French Republic,” dalam American Constitutionalism Abroad, ed. George Athan Billias (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1990), hlm. 91-109. 39 McHugh, Comparative Constitutional Traditions, hlm. 35-36 40 McHugh, Comparative Constitutional Traditions, hlm. 47-63 41 lihat secara umum, McHugh, Comparative Constitutional Traditions; Michel Rosenfeld, “Modern Constitutionalism as Interplay Between Identity and Diversity,” in Constitutionalism, Identity, Differences, and Legitimacy, ed. Michel Rosenfeld (Durham, North Carolina, Duke University Press, 1994), hlm. 3-38. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im kecocokan, namun beberapa metode terbukti tidak cukup kuat karena mereka memang tidak menerapkan prinsip pokoknya. Contohnya, meskipun kekuasaan eksekutif untuk menunjuk dan mempekerjakan hakim merupakan satu hal yang tak terhindarkan, namun dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya pada mereka untuk melakukan penunjukkan tanpa melakukan cek atau pengawasan merupakan satu bentuk penyimpangan dari prinsip independensi lembaga kehakiman. Sebuah sistem yang menolak hak-hak dasar masyarakat tertentu seperti kesetaraan di hadapan hukum atau kesamaan akses terhadap fasilitas publik karena sentimen gender atau agama berarti menolak prinsip konstitusionalisme itu sendiri. Meskipun demikian, ini juga tidak berarti bahwa sistem yang tidak dapat diterima, bisa dengan mudah dan cepat digantikan oleh model lain yang lebih baik. Pengalaman paska kemerdekaan negara-negara Asia Afrika42 menunjukkan bahwa transplantasi struktur, lembaga dan proses yang dapat dengan mudah dilakukan di beberapa negara, ternyata membutuhkan adaptasi dan pengembangan yang cukup hati-hati di beberapa negara lain. Munculnya konsensus mengenai ciri-ciri konstitusionalisme, dan bagaimana mereka diturunkan dan diaplikasikan di masingmasing negara, merefleksikan pengalaman lokal dan global negara tersebut. Dengan kata lain, makna dan implikasi konstitusionalisme untuk sebuah negara adalah hasil interaksi prinsip-prinsip universal yang luas dengan proses dan faktor lokal yang spesifik. Namun perlu di catat, prinsip-prinsip universal sendiripun sebetulnya merupakan perluasan dari pengalaman-pengalaman berbagai negara yang dihasilkan dari pengalaman interaksi antara nilai-nilai universal dan lokal negaranya. 42 Lihat sebagai contoh, Okon Akiba, “Constitutional Government and the Future of Constitutionalism in Africa,” Constitutionalism and Society in Africa, ed. Okon Akiba (Burlington, Vermont: Ashgate Publishing Company, 2004), hlm. 7-16. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Islam, Syari’ah dan Konstitusionalisme Saya tertarik dengan hubungan antara Islam, Syariah dan Konstitusionalisme karena interaksi antara ketiga hal tersebut ada dalam hati dan pikiran ummat Islam.43 Ini bukan berarti bahwa Islam benar-benar secara ekslusif menentukan perilaku konstitusional penganutnya, karena perilaku konstitusional dan bahkan pemahaman dan praktik berIslam-nya ummat Islam juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi dan faktor lainnya. Ketertarikan saya lebih karena muslim tidak mungkin untuk mempertimbangkan konstitusionalisme secara serius jika mereka menilai konsep atau beberapa prinsipnya secara negatif; sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajiban agama mereka untuk melaksanakan syari’ah. Tapi sebagaimana yang sudah saya tekankan sebelumnya, pengetahuan dan praktik syariah apapun adalah selalu merupakan produk pemahaman dan pengalaman muslim, yang tidak mungkin mencakup seluruh aspek tentang Islam. Sumber atau kerangka undang-undang tradisional Islam biasanya diambil dari pengalaman komunitas awal muslim yang dibangun Nabi di Madinah setelah hijrah dari Mekah di tahun 622 H dan kemudian diteruskan oleh generasi pertama pengikutnya.44 Pola perilaku individu dan masyarakat, serta model hubungan dan lembaga sosial politik, umumnya selalu disandarkan dan dikaitkan dengan periode yang selalu dianggap sebagai model ideal bagi Muslim sunni itu. 43 45 Namun karena Lihat sebagai contoh, Ausaf Ali, “Contrast Between Western and Islamic Political Theory” in Modern Muslim Thought, Vol. 1, Modern Muslim Thought, Vol. 1 (Karachi, Pakistan: Royal Book Company), hlm. 181; Muhammad Asad, Principles of State and Government in Islam (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1985), hlm. 1-17, 22-23; Saba Habacy, Introduction to J.N.D. Anderson, Islamic Law in the Modern World (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1975), hlm. ix. 44 Lihat secara umum Kemal Faruki, The Evolution of Islamic Constitutional Theory and Practice from 610 to 1926 (Karachi, Pakistan: National Publication House, 1971). 45 Lihat Asad, State and Government in Islam, hlm. 24-29; Maimul Ahsan Khan, Human Rights in the Muslim World (Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2003), hlm. 143-240. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im sifatnya yang ideal itu pulalah, model tersebut tidak pernah bisa direplikasi secara utuh setelah Nabi dan sahabat-sahabatnya meninggal. Terlebih lagi, tidak ada kesepakatan di antara ummat Islam mengenai apa yang dimaksud dengan model Madinah itu dan bagaimana model itu diaplikasikan dalam konteks hari ini. Bagi mayoritas muslim sunni, masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidun (sampai terbunuhnya Ali pada tahun 660 M), merepresentasikan model ideal teori undang-undang dasar Islam yang paling otoritatif.46 Sementara itu, kalangan Islam syi’ah memiliki model ideal mereka sendiri yaitu imam-Imam Maksum sejak masa pemerintahan Ali. Jumlah imam-imam maksum ini tergantung pada sekte-sekte tertentu dalam syi’ah (apakah Ja’fari, Isma’ili, Zaydi dan lain sebagainya).47 Dengan demikian, baik sunni maupun syi’ah menganggap model yang tumbuh pada masa tersebut sebagai model yang paling ideal dan mencela generasi sesudahnya. Bahkan seringkali model ini mendapatkan justifikasi untuk dipaksakan karena terjadinya situasi-situasi tertentu seperti kekacauan internal atau invasi luar. Seperti yang sudah diungkapkan Anderson, “nampaknya lip-service lebih suka digunakan untuk mendukung syari’ah sebagai otoritas hukum yang paling fundamental dan untuk menggunakan konsep “darurah” guna menerapkannya dalam praktik, daripada membuat usaha real untuk mengadaptasikan hukum Islam tersebut pada situasi dan kebutuhan kebutuhan saat ini”. 48 46 Lihat al-Nabhani, the Islamic State; lihat juga Asad, State and Government in Islam, hlm. 24-29; A. Rahman I. Doi, Non-Muslims Under the Shri’ah (Islamic Law), (Lahore, Pakistan: Kazi Publication, 1981), hlm. 122 47 Lihat sebagai contoh Said Amir Arjomand, The Shadow of God and the Hidden Imam (Chicago: University of Chicago Press, 1984; and Farhad Daftary, The Isma’ilis: Their History and Doctrines (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). 48 Norman Anderson, Law Reform in the Muslim World (London: Athlone Press 1976), hlm. 36. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Karena itulah, saya mencoba untuk mempromosikan pemahaman syari’ah sebagai sesuatu yang dapat terus dipraktikkan oleh Muslim, daripada terus menerus memelihara harapan-harapan yang tidak realistis yang menghargai syariah hanya sebatas teori, bukan praktik. Dengan demikian, masalahnya adalah bagaimana menerjemahkan esensi keadilan dan implikasi praksis model historis tersebut, bukan berusaha mengulangnya dalam keadaan yang sangat berbeda ini. Contohnya, ajaran tentang syura. Ajaran ini tidak mengikat dan tidak pernah pula dipraktikkan dengan cara yang sistematik dan inklusif.49 Qs. 3: 159 menginstruksikan nabi untuk bermusyawarah (syawirhum) dengan pengikutnya, tapi jika ia telah menemukan jawabannya sendiri, ayat tersebut mengatakan bahwa ia harus melaksanakan keputusannya itu. Ayat lain yang sering dikutip berkaitan dengan syura adalah Qs 42: 38 yang menggambarkan orang-orang mu’min sebagai sebuah komunitas yang memutuskan masalah dengan musyawarah. Tapi ayat ini tidak menjelaskan bagaimana musyawarah itu dipraktikkan dan apa yang harus dilakukan bila terjadi ketidaksepakatan.50 Istilah syura dalam konteks ini, lebih banyak mengindikasikan keharusan untuk mendengarkan pendapat tanpa harus terikat olehnya. Seperti yang saya tunjukkan pada bab II, praktik Nabi dan para sahabat nampaknya membuktikan pemahaman ini. Praktik syura yang seperti ini kemudian menjadi norma yang berlaku dalam pemerintahan dinasti Umayah, Abbasiyah dan negaranegara yang tumbuh dalam masyarakat Islam pra modern. Namun demikian, dengan pemahaman syura yang seperti ini tidak berarti bahwa konsep tersebut tidak bisa dipakai sebagai dasar prinsip-prinsip undang-undang dasar yang terlembagakan dan melibatkan seluruh penduduk. Justru inilah bentuk 49 Tapi lihat Asad, State and Governmnet in Islam, hlm. 54-55 Noel J. Coulson, “The State and the Individual in Islamic Law”, International and Comparative Law Quarterly 1957, hlm. 49-60, pada hlm. 55-56. 50 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im evolusi dan pengembangan prinsip-prinsip Islam yang saya ajukan. Namun segalanya harus kita mulai dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan syura dan bagaimana ia pernah dipraktikkan. Menganggap syura sebagai sebuah prinsip yang sudah difahami dan dipraktikkan sebagai “pemerintahan yang berdasarkan undang-undang” dalam konteks modern, justru akan menjadi kontra-produktif, karena syura hanya akan digunakan untuk membenarkan praktik-praktik inkonstitusional. Lagipula, klaim tersebut masih dipertanyakan karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa syura pernah diimplementasikan dalam bentuk lembaga politik yang bisa mengelola pertikaian politik dan peralihan kekuasaan secara damai dan baik sepanjang sejarah Islam. Ini tentu saja berlaku dimanapun, karena konsep dan lembaga-lembaga tersebut berkembang secara gradual dan tak pasti selama kurang lebih 2 abad. Namun ini tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi pemahaman sejarah yang keliru bahwa muslim sudah mengetahui dan mempraktikkan prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional seperti itu. Pendekatan yang sama juga harus diterapkan untuk mengembangkan interpretasi syari’ah tradisional mengenai kesetaraan perempuan dan non-muslim serta kebebasan beragama. Fakta bahwa pembatasan itu memang terjadi pada beberapa masyarakat di masa lalu, tidak bisa menjustifikasi penerapannya secara terus menerus oleh masyarakat muslim sekarang. Malah, kita harus mengerti terlebih dahulu alasan justifikasi praktik-praktik tersebut itu dalam berbagai budaya lokal masyarakat Islam masa lalu, dan bagaimana praktik-praktik itu dilegitimasi sebagai interpretasi otoritatif syari’ah. Baru kemudian, kita mencari interpretasi alternatif yang lebih konsisten dengan budaya yang berkembang dan konteks masyarakat Islam sekarang. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Perlu saya tekankan disini bahwa aturan umum syari’ah menjamin kebebasan ummat Islam untuk melakukan dan meninggalkan syari’ah kecuali bila bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Secara teoritis, tidak ada pembatasan hakhak konstitusional dalam syari’ah, kecuali dalam keadaan tertentu. Tapi dalam praktiknya, aturan ini menjadi sangat kompleks karena syari’ah difahami berbeda oleh beragam mazhab dan para fuqaha berbeda pendapat hampir dalam semua masalah.51 Akibatnya, ummat Islam seringkali merasa tidak yakin, apakah, menurut syari’ah, mereka memiliki hak untuk melakukan dan meninggalkan kewajiban atau tidak. Buruknya, ketidakjelasan ini sering membuka kemungkinan bagi terjadinya manipulasi oleh para pemimpin atau elite keagamaan. Selain itu, ketidakjelasan ini juga memiliki konsekuensi serius terhadap hak-hak konstitusional ummat Islam seperti aturan mengenai pakaian perempuan (jilbab) dan aturan pemisahan laki-laki dan perempuan yang bisa mengganggu kebebasan personal dan kemampuan partisipasi mereka dalam kehidupan publik. Apapun pandangan orang tentang masalah ini, ternyata aturan mengenai hak-hak konstitusional perempuan dan non-muslim yang harus tunduk pada batasanbatasan tertentu, tidak pernah diperdebatkan. Misalnya, Qs. 4: 34 yang sering digunakan untuk menekankan prinsip otoritas laki-laki sebagai qawwam atas perempuan dan dengan demikian, menolak hak perempuan untuk memegang jabatan pubik apapun.52 Meskipun para fuqaha berbeda pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip ini, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang 51 Lihat secara umum, Wael B. Hallaq, “Can Shari’ah Be Restored,” Islamic Law and the Challenges of Modernity, eds. Yvonne Yazbeck Haddad and Barbara Freyer Stowasser (Walnut Creek, California: AltaMira Press, 2004), hlm. 26-36. 52 Ausaf Ali, “Role of Muslim Women Today,” Modern Muslim Thought, Vol. 1, hlm. 226-227; “The Development and Integration of Muslim Women as a Human Resource in the Islamic Economy in the Modern World,” Modern Muslim Thought, Vol. 1, hlm. 256-263. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im memberikan posisi setara kepada perempuan. Bahkan, prinsip ini kemudian diterapkan untuk menginterpretasi ayat lain dan bahkan diperkuat oleh berbagai ayat yang jelas-jelas memberikan hak yang tidak sama kepada perempuan dalam pernikahan, perceraian, warisan, dan lain-lain.53 Prinsip ini juga diterapkan pada ayat-ayat seperti QS. 24: 31, Qs. 33: 33, 53, 59 untuk membatasi hak perempuan berbicara dalam ruang publik atau untuk berkumpul dengan laki-laki. Akhirnya, kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya pun dibatasi.54 Dengan demikian, meskipun perempuan muslim memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam beragama dan mengungkapkan pendapat, kesempatan mereka untuk mendapatkan hak ini sangat dibatasi oleh larangan untuk mengakses ruang publik. Kombinasi ayat-ayat umum dan khusus semacam tadi juga digunakan untuk membatasi hak-hak non-muslim baik ahlul kitab maupun orang-orang kafir.55 Saya akan menjelaskan hal ini secara lebih luas dalam bagian mengenai “kewarganegaraan”. Sekarang saya hanya ingin menekankan bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan teoritis di kalangan sarjana muslim dan terdapat pula beragam variasi antara teori dan praktik, namun dalam khazanah interperetasi syariah tradisional, prinsip bahwa non-muslim tidak setara dengan muslim tidak pernah menjadi bagian dalam perdebatan tersebut. Interpretasi alternatif sangat mungkin dimunculkan, namun bukan dengan mengklaim bahwa pembatasan 53 Lihat sebagai contoh Abul A’la al-Maududi, Purdah and the Status of Women in Islam, diterjemahkan dan diedit oleh al-‘Ash’ari (Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd., 1979), hlm. 141158 54 Fatima Mernissi, Women in Islam: an Historical and Theological Enquiry, Mary Jo Lackland (pen.), (Oxford, England: Basil Blackwell Ltd., 1991), hlm. 49-81; Maududi, Purdah and the Status of Woman, hlm. 152-153. 55 Sebagai contoh lihat artikel “Dhimma” dalam Shorther Encyclopedia of Islam, (Leiden: EJ Brill, 1991), hlm. 76 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im semacam itu bukan bagian dari syari’ah yang pernah diinterpretasikan oleh muslim di masa lalu. Justifikasi sosiologis maupun poilitik apapun yang diajukan untuk menguatkan aspek-aspek syariah tersebut, aspek-aspek tersebut tidak lagi valid untuk konteks masyarakat islam modern. Larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau agama telah ada dalam undang-undang dasar negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara tersebut juga mengakui kovenan hak asasi manusia internasional yang menyaratkan adanya kesetaraan dan ketiadaan diskriminasi. Benar bahwa pemerintahan negara-negara tersebut jarang yang sudah melaksanakan semua aturan yang tertera dalam undang-undang dasar mereka, tetapi problem ini dimiliki oleh hampir semua negara. Sambil menekankan perlunya memahami dan meniadakan sebab-sebab masalah ini, menurut saya penting bagi seluruh muslim untuk mengungkapkan komitmen mereka pada nilai-nilai konstitusionalisme, hak asasi manusia dan kewarganegaraan.56 Namun itu saja tidak cukup, kita harus maju satu langkah lagi menuju apa yang saya sebut sebagai reformasi Islami. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung usahausaha untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan dan non-muslim dari sudut pandang syari’ah dan bukan sekedar untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat. Gerakan ini juga akan memberikan kontribusi bagi proses legitimasi nilainilai partisipasi politik, akuntabilitas dan kesetaraan di hadapan hukum. Pada akhirnya gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan prospek konstitusionalisme dalam masyarakat Islam. 56 Lihat Brems, Human Rights, hlm. 194-206; contoh diskursus muslim mengenai hal tersebut lihat juga, Khan, Human Rights in the Muslim World; Ausaf Ali, Modern Muslim Thought; Islamic Law and the Challenges of Modernity, eds. Yvonne Yazbeck Haddad and Barbara Freyer Stowassesr; Asad, State and Government in Islam. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Dalam menerapkan konsep undang-undang dasar dan kelembagaan yang telah berkembang selama 2 abad untuk menganalisa pengalaman masyarakat islam di masa lalu, saya akan menekankan bahwa perkembangan konsep-konsep dan lembaga-lembaga tersebut tidak membuat mereka menjadi tidak islami. Sebaliknya harus disadari bahwa perubahan drastis yang terjadi pada masyarakat Islam dalam konteks lokal dan global, menyebabkan model-model yang pernah berlaku di masa lalu tidak akan mampu untuk diterapkan secara langsung begitu saja. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menerjemahkan konsep-konsep ideal syari’ah menjadi model pemerintahan yang bisa berfungsi dengan baik saat ini, daripada sekedar menekankan bahwa ini adalah aplikasi modern yang diinspirasi oleh formulasi lama. Untuk menghindari kebingungan, saya ingin menekankan bahwa meskipun norma sosial dan moral masyarakat Madinah masih merupakan model ideal yang harus dicapai oleh seluruh muslim, struktur dan cara kerja model negara yang terjadi di masa itu tidak mungkin diterapkan dalam konteks masyarakat muslim saat ini. Daripada terus menerus berapologi dengan argumen negara Madinah tanpa tahu cara menerapkannya, adalah lebih baik baik muslim untuk menerapkan kembali nilai-nilai ideal dan semangat lembaga-lembaga sosial dan politik negara madinah dalam sistem pemerintahan, adminsitrasi peradilan dan relasi internasional yang lebih bisa berfungsi untuk konteks sekarang ini. Prinsipprinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia dan kewarganegaraan menurut saya justru menjadi alat yang lebih cocok untuk menjembatani ketegangan hubungan antara islam, negara dan masyarakat dalam masyarakat muslim saat ini, daripada terus secara tidak realistis menganut model dulu yang sudah tidak lagi berfungsi. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Konsep baiah57 contohnya. Saat ini konsep itu harus dilihat sebagai dasar yang otoritatif bagi perjanjian yang saling menguntungkan antara pemerintah dan rakyat secara keseluruhan, dimana pemerintah harus bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara sebagai imbalan atas penerimaan pihak kedua atas kekuasaan pihak pertama dan kepatuhan pihak kedua terhadap aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pihak pertama. Tapi sebetulnya, teori undang-undang dasar modern manapun, baik yang berdasarkan prinsip-prinsip islam atau tidak, harus mengembangkan sebuah mekanisme dan lembaga yang layak bagi terselenggaranya pemilihan, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi, seperti yang tertera dalam konsep baiah yang kita fahami sekarang. Konsep ini bisa dilaksanakan melalui pengembangan konsep sura menjadi prinsip yang mengikat pemerintah daripada sekedar konsultasi sukarela. Hak asasi manusia dan konsep “kewarganegaraan yang setara” sangat dibutuhkan bukan hanya untuk mengembangkan konsep sura modern ini, tapi juga untuk mengimplementasikan teori undang-undang dasar yang tepat dan inklusif bagi laki-laki dan perempuan, muslim dan non-muslim sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama di hadapan negara. Untuk menyimpulkan diskusi kita tentang konstitusionalisme dari perspektif Islam, saya akan mengulang kembali apa yang saya tekankan mengenai pentingnya peran umat muslim dalam melakukan proses mendamaikan ketegangan yang timbul dari konsep netralitas negara terhadap agama di satu pihak sambil menyadari peran positif Islam dalam mempengaruhi kebijakan publik dan undang-undang di pihak lain. Proses-proses tersebut haruslah dilakukan secara kontekstual dan hanya bisa 57 Bay’a berarti proses ratifikasi Imam atau khalifah pada periode awal masyarakat muslim. Ann K.S. Lambton, State and Government in Medieval Islam (Oxford, England: Oxford University Press, 1985), hlm. 18; Asad, State and Government in Islam, hlm. 69-70; al-Nabhani, The Islamic State, hlm. 278. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im difahami dalam konteks pengalaman masing-masing masyarakat. Saya sebetulnya menghargai kebutuhan sederhana akan (dan mungkin agak menyederhanakan) solusi kategoris, apakah dalam bentuk sebuh negara Islam yang berusaha menerapkan syariah atau dalam bentuk pemisahan ketat antara negara dan Islam, dengan asumsi bahwa pemisahan ini akan menetralisasi penagruh problematis islam atas negara. Tetapi, saya percaya bahwa masalah ini harus dilihat dari kerangka upaya negosiasi dan mediasi, daripada fusi atau separasi. Lagipula, sekali kita menyatakan bahwa hubungan antara Islam, masyarakat dan negara tergantung pada konteks politik dan sosial sebuah masyarakat, maka kita menyadari bahwa hubungan tersebut pasti dinamis, berkembang dan bisa dirubah serta ditransformasikan, bukan terus dipelihara secara rigid dan permanen dalam satu bentuk. III. Islam dan Hak Asasi Manusia Sebagaimana yang sudah saya tekankan di beberapa bagian dalam buku ini, berbicara mengenai Islam adalah betul-betul mengenai bagaimana muslim memahami dan mempraktikkan agama mereka, bukan sebagai agama dalam arti yang sangat abstrak. Lagipula, diskusi mengenai hubungan antara agama dan hak asasi manusia bukan berarti bahwa Islam, atau agama lain, bagi pemeluknya hanya satu-satunya hal yang bisa menjelaskan sikap dan perilaku mereka. Muslim bisa menerima atau menolak ide mengenai hak asasi manusia atau salah satu norma yang terdapat di dalamnya tidak karena pemahaman ortodoks mereka terhadap agama. bahkan, beragamnya tingkat penerimaan atau kepatuhan mereka terhadap norma-norma hak asasi manusia lebih mungkin terkait dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Islam saat ini, daripada dengan Islam itu sendiri. Dengan demikian, apapun peran Islam, ia tidak dapat difahami secara ©Abdullahi Ahmed An-Na`im terpisah dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana muslim menginterpretasi dan berusaha untuk mematuhi tradisi mereka sendiri. Karenanya menjadi salah, bila kita berusaha memprediksi atau menjelaskan tingkat kepatuhan ummat Islam terhadap nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sebuah konsekuensi teoritis hubungan antara Islam dan hak asasi manusia. Tetapi, menghubungkan Islam dan Hak Asasi Manusia tetap merupakan hal penting bagi mayoritas ummat Islam agar motivasi mereka untuk berpegang pada norma-norma hak asasi manusia tidak hilang begitu saja hanya karena mereka memahami norma-norma tersebut sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena jika mereka percaya bahwa hak-hak tersebut sesuai dengan sistem kepercayaan mereka, komitmen dan motivasi mereka untuk melindungi hak-hak tersebut akan bertambah. Hal kedua yang penting saya tekankan disini adalah bahwa prinsip-prinsip syari’ah pada dasarnya sesuai dengan hampir seluruh norma-norma hak asasi manusia, kecuali pada beberapa point yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan nonmuslim seperti yang akan saya diskusikan nanti. Point lain yang juga cukup serius dan akan kita diskusikan juga adalah yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Meskipun saya menganggap masalah-masalah tersebut sangat serius dan berusaha untuk menyelesaikannya melalui reformasi islami, saya lebih suka mengajukan sebuah proses mediasi daripada konfrontasi. Jika saya, sebagai muslim, diminta untuk memilih salah satu antara Islam dan hak asasi manusia, saya pasti akan memilih Islam. Daripada harus menghadapkan pilihan sulit ini kepada ummat Islam, saya kira lebih baik kita sebagai muslim mulai mempertimbangkan untuk mentransformasikan pemahaman kita terhadap syari’ah dalam konteks masyarakat ©Abdullahi Ahmed An-Na`im muslim saat ini. Saya percaya bahwa pendekatan ini bisa digunakan sebagai prinsip, sekaligus solusi pragmatis. Dengan demikian, menurut saya, masalah ini lebih baik difahami dengan menggunakan dua kerangka yaitu inherennya keterlibatan manusia dalam pemahaman dan praktik Islam, di satu pihak, dan universalitas hak asasi manusia di pihak lain. Pendekatan ini lebih realistis dan konstruktif, daripada sekedar mengungkapkan kecocokan atau ketidakcocokkan Islam dan hak asasi manusia dan mengambil keduanya dalam pemahaman yang absolut dan statis. Ketika kita menguji dinamika dan perkembangan hubungan Islam dan hak asasi manusia, kita akan menemukan bahwa Islam sebenarnya sangat mendukung hak asasi manusia.58 Universalitas Hak Asasi Manusia Ide revolusioner hak asasi manusia tetap merupakan tantangan ummat manusia hari ini, seperti pertama kali diproklamirkan pada tahun 1948. Ide ini sangat penting bagi ummat manusia, dan dengan demikian harus diakui, agar kita bisa mengklaim hak kita atas hak-hak tersebut. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan saya dalam buku ini, Muslim tidak harus mengabaikan agamanya hanya untuk mengakui hak-hak manusia tetapi mereka juga tidak boleh mendiskriminasi orang lain berdasarkan jenis kelamin, ras, kebangsaan, maupun agama. Karena untuk bisa menjustifikasi secara moral dan menyadari klaim hak asasi manusia kita tanpa melakukan diskriminasi kepada orang lain, ummat Islam harus menyadari bahwa yang lain pun memiliki hak sama dengan kita. Hal yang sama berlaku bagi seluruh ummat 58 Ini premis yang saya bangun dalam buku saya, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law (Syracuse University Press, 1990); dan didiskusikan secara lebih luas dalam berbagai buku saya edit seperti Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: Quest for Consensus (University of Pennsylvania Press, 1992); The Cultural Dimensions of Human Rights in the Arab World (Arabic) (Cairo, Egypt: Ibn Khaldoun Center, 1993); and Human Rights Under African Constitutions: Realizing the Promise for Ourselves (University of Pennsylvania Press, 2003). ©Abdullahi Ahmed An-Na`im manusia, dan bukan hanya bagi muslim. Namun dalam kesempatan saya akan memposisikan diri sebagai muslim yang berusaha mempromosikan pentingnya hak asasi manusia di kalangan muslim sendiri. Deklarasi hak asasi manusia telah berusaha tidak menggunakan agama apapun untuk menjustifikasi ide-ide dasarnya agar ia bisa menemukan dasar yang sama bagi mereka yang beragama maupun tidak. Tapi ini tidak berarti bahwa hak asasi manusa hanya bisa didasarkan pada justifikasi sekuler, karena cara seperti itu tidak bisa menjawab persoalan bagaimana melegitimasi dan mengesahkan hak asasi manusia berdasarkan perspektif yang sangat beragam di dunia ini. Logika yang dibangun dalam deklarasi itu justru memberikan kesempatan kepada para penganut agama atau kepercayaan tertentu untuk membangun komitmen mereka pada deklarasi itu, dengan menggunakan norma yang terdapat dalam kepercayaan atau agama yang mereka yakini. Begitupula dengan mereka yang membangun komitmennya atas dasar filfasat sekuler yang mereka pelajari. Semua orang berhak mendapatkan pengakuan hak asasi yang sama dari orang lain, tapi tidak dapat menentukan alasan yang digunakan orang lain untuk memberikan pengakuan tersebut. Ide hak asasi manusia muncul setelah Perang Dunia II sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan perlindungan hak-hak dasar di tengah berbagai kemungkinan dalam pentas politik nasional. Pandangan tersebut dibangun diatas kesadaran bahwa hakhak tersebut amat fundamental hingga harus dilindungi dengan konsensus dan kerjasama internasional agar keberadaannya diakui oleh undang-undang dasar dan ©Abdullahi Ahmed An-Na`im sistem hukum nasional.59 Dengan kata lain, tujuan membuat kewajiban hukum internasional untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia baik melalui prinsip-prinsip hukum adat atau perjanjian adalah untuk melengkapi pemenuhan hak-hak tersebut dalam konteks sistem domestik dan untuk mempromosikan implementasi praksisnya. Tujuan utama hak asasi manusia adalah untuk meyakinkan perlindungan yang efektif terhadap beberapa hal penting yang merupakan hak semua manusia dimanapun mereka berada, termasuk di negara yang tidak menjamin keberadaan hak itu dalam undang-undang dasar mereka. Ini tidak berarti bahwa deklarasi hak asasi manusia berbeda atau lebih tinggi kedudukannya daripada hak-hak yang terdapat dalam undang-undang dasar. Malah, perhormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam DUHAM dilakukan melalui pencantumannya dalam undang-undang dasar, anggaran dasar dan rumah tangga lembaga Negara. Tujuan Gagasan DUHAM, sebagaimana tujuan Undang-Undang Dasar, adalah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ketidakjelasan proses-proses politik dan administratif. Dengan kata lain, hak asasi manusia dalam DUHAM, seperti halnya hak yang terdapat dalam undang-undang dasar, harus tunduk pada kehendak mayoritas, meskipun bukan sekedar pilihan mayoritas. Namun bukan berarti hakhak tersebut absolut, karena banyak di antaranya yang layak dipilih karena berbagai alasan dan beberapa lainnya bisa ditunda karena alasan darurat. Gagasan DUHAM dengan demikian adalah agar hak asasi manusia, sebagaimana hak-hak yang 59 Eva Brems, Human rights: Universality and Diversity (the Hague, The Netherlands: Kluwer Law International, 2001), hlm. 5-7 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im tercantum dalam undang-undang dasar, tidak mudah dilanggar kecuali dalam kondisi dan keadaan tertentu.60 Dengan mempertimbangkan ketegangan yang terjadi antara gagasan dan prinsip HAM dengan kedaulatan nasional, mengakui HAM sebagai produk kesepakatan internasional adalah merupakan hal yang sangat penting. Tantangan yang dihadapi HAM dari prinsip kedaulatan nasional tidak akan dapat bisa diselesaikan tanpa adanya kerjasama internasional untuk melindungi HAM.61 Klaim komunitas internasional untuk berfungsi sebagai arbitrer, yang dapat melakukan tindakan untuk melindungi standar minimum HAM, tidak akan dianggap layak tanpa komitmen anggotanya untuk mendorong dan memberikan dukungan kepada yang lain dalam melakukan proses ini. Peran sebagai arbitrer tersebut lebih mungkin diterima oleh sebuah negara, jika dilakukan sebagai usaha bersama seluruh negaranegara lain, daripada jika hanya lahir dari kebijakan luar negeri satu atau sekelompok negara tertentu. Perlindungan HAM yang berkesinambungan tidak akan terrealisasikan melalui intervensi militer atau pemaksaan dari pihak luar, karena cara-cara seperti itu hanya dapat berlaku efektif dalam waktu yang temporer dan tidak menentu. Dengan kata lain, praktik perlindungan HAM hanya dapat dilakukan melalui peran negara, yang sebetulnya menjadi aktor yang sangat potensial untuk melanggar hak-hak tersebut. Hemat saya, DUHAM bisa menjadi instrumen yang kuat untuk melindungi kemuliaan manusia dan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap orang dimanapun mereka berada berkat universalitas kekuatan moral dan politik yang dimilikinya. 60 61 Brems, Human Rights, hlm. 305 Brems, Human Rights, hlm. 5-6, 309 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Bahwa DUHAM menyediakan standar yang sama yang harus dicapai oleh seluruh manusia dan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan DUHAM, berarti bahwa setiap kekuasaan hukum dan undang-undang di sebuah negara harus berusaha keras melindungi hak-hak tersebut. Prinsip hukum adat dan perjanjian internasional juga mencantumkan hak-hak dasar seperti kebebasan untuk berekspresi dan prosedur perlindungannya seperti penyelengaraan peradilan yang adil. Implementasi dan perlindungan HAM dengan demikian juga menyaratkan adanya standar kelembagaan dan struktural bagi aparatur negara62. Bagaimana standar-standar tersebut beroperasi seperti melalui pemisahan kekuasaan dan independesi kehakiman sudah diungkapkan dalam bagian yang lalu sebagai bagian dari konsep konstitusionalisme. Namun, pengakuan DUHAM sebagai norma hak asasi manusia universal lebih merupakan hasil proses konsensus global daripada sekedar sebuah hasil pemaksaan. Karena setiap masyarakat berpegang pada sistem normatif yang membentuk konteks dan pengalamannya, maka sebuah konsep universal tidak bisa begitu saja diproklamirkan dan diterapkan sama rata. Dengan kata lain, manusia baik laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, Afrika atau eropa, beragama maupun tidak, sama-sama mengetahui dan menjalani kehidupan di dunia sebagai dirinya sendiri. Dimanapun kita berada, kesadaran, nilai dan perilaku kita sebagai manusia dibentuk oleh tradisi agama dan kultural kita. Pertanyaannya dengan demikian adalah bagaimana mendapatkan, meningkatkan dan menjaga keberlangsungan konsensus terhadap norma HAM universal dalam konteks seperti ini? Apa karakter dan 62 Asbjørn Eide, “Economic and Social Rights,” in Human Rights: Concepts and Standards, ed. Janusz Symonides (Burlington, Vermont: Ashgate Publishing Company, 2000), hlm. 124-128. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im implikasi perbedaan relasi kuasa antara sejumlah partisipan dan budayanya dalam proses pembentukan konsensus itu? Ide mengenai universalitas hak asasi manusia sebagai produk pembentukan konsensus tidak boleh menjadi alat untuk mempertahankan atau menjustifikasi klaim sejumlah pemerintahan atau pemimpin negara bahwa rakyatnya dibebaskan atau dimaklumi untuk tidak melaksanakan standar-standar tersebut. Nyatanya, klaim-klaim tersebut memang dilontarkan oleh sejumlah elit penguasa, karena mereka mempersepsi hak asasi manusia sebagai “produk barat” dan, dengan demikian, merupakan hal yang asing bagi masyarakat Asia dan Afrika secara umum.63 Dalam kesempatan ini, saya ingin menolak klaim seperti itu dengan menekankan bahwa semua masyarakat sedang berusaha untuk mencapai dan mempertahankan komitmen yang genuine terhadap universalitas HAM dan prinsip penegakan keteraturan hukum dalam hubungan internasional. Secara khusus, saya menolak gagasan bahwa satu-satunya model yang valid untuk universalitas has asasi manusia harus dirumuskan oleh masyarakat Barat atau oleh kelompok masyarakat manapun dan untuk diikuti jika ingin dianggap sebagai manusia beradab. Jika memang hak asasi manusia adalah universal sebagai hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia di manapun mereka berada, maka hak asasi manusia harus integral dengan budaya dan pengalaman semua masyarakat dan bukan hanya integral dengan masyarakat Barat yang mencangkokkan nilai-nilai tersebut pada kelompok masyarakat lain. Untuk mendukung preposisi ini, saya akan menekankan dua hal. 63 Sebagai contoh lihat, Joanne Bauer and Daniel Bell (eds.), Human Rights in East Asia, (New York: Cambridge University Press, 1999). ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Pertama, jelas bahwa formulasi standar HAM internasional sangat merefleksikan pengalaman dan filsafat politik barat. Bahkan banyak artikel dalam DUHAM yang jelas-jelas menyalin bahasa The Bill of Rights-nya Amerika.64 Namun bukan berarti bahwa norma-norma hak asasi manusia dalam DUHAM merupakan hal yang asing dan tidak sesuai dengan masyarakat Afrika atau Asia yang juga membutuhkan perlindungan Hak asasi manusia dalam konteks masyarakatnya. Sebagaimana yang sudah saya ungkapkan di muka, formulasi standar HAM yang didasarkan pada model wilayah negara dan hubungan internasional Barat itu, sekarang merupakan bagian dari realitas yang dihadapi oleh masyarakat muslim dimanapun. Karena sekarang muslim harus bersentuhan dengan lembaga-lembaga Barat tersebut, mereka harus bisa mengambil manfaat dari jaring perlindungan yang sudah dikembangkan oleh masyarakat Barat untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakatnya sendiri.65 Sebaliknya, jika ada masyarakat muslim yang menolak Hak Asasi Manusia karena ia lahir dari Barat, maka mereka juga harus menolak negara yang berdasarkan wilayah dan perdagangan, ekonomi dan hubungan internasional lainnya, karena negara dan hubungan-hubungan internasional itu juga dibangun dan didasarkan pada konsep dan istilah Barat. Jika mereka tidak bisa menolak, maka mau tidak mau mereka harus menerima HAM sebagai cara yang efektif dan penting untuk meminimalisir pelanggaran HAM dan memperbaiki kerugian yang mungkin terjadi dalam konsep yang didasarkan pada model barat tersebut. Point kedua yang ingin saya tekankan disini juga bahwa aktivis has asasi manusia dan hukum internasional juga harus mendesakkan DUHAM sebagai dasar esensial 64 Lihat Brems, Human Rights, hlm. 17 Peter Baehr, Cees Flintermand and Mignon Sender, Pengantar untuk “Innovation and Inspiration: Fifty Years of The Unievrsal Declaration of Human Rights, eds. Baehr, Flintermadn and Senders (Amsterdam. The Netherlands: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 1999), hlm. 2 65 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im bagi masyarakat yang beradab, bukan malah meninggalkannya hanya karena kegagalan beberapa pemerintah untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Jika tidak, umat Islam dengan demikian harus mengakui bahwa masyarakat dan pemerintahan Baratlah, satunya-satunya, pembuat prinsip-prinsip tersebut. Padahal penegakan prinsip-prinsip tersebut juga tergantung pada kesediaan dan kemampuan masyarakat muslim sendiri. Prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia harus siap ditegakkan dan dipromosikan untuk menghadapi tantangan apapun yang datang dari sumber manapun karena prinsip-prinsip tersebut merupakan usaha bersama seluruh ummat manusia dimanapun mereka berada. Penting juga untuk dicatat bahwa seperti halnya hasil inisiatif manusia manapun, perlindungan hak asasi manusia hanya bisa dicapai melalui proses percobaan, proses terhenti dan memulai, dan juga proses kemunduran dan kemajuan. Seluruh individu dan masyarakat harus bahu membahu dan bekerja sama agar proses implementasi dan perlindungan hak-hak ini dapat menjadi usaha yang benar-benar universal. Ummat Islam, khususnya, justru harus menjadi partisipan aktif dalam proses ini, bukan sekedar mengeluh karena menjadi korban kesewenang-wenangan pemerintahannya atau obyek hegemoni Barat dalam hubungan internasional. Namun kesulitan menjalankan proses ini sudah muncul sejak akhir era Perang Dingin karena Negara-Negara yang tergabung dalam Blok Barat dan Blok Timur bekerjasama untuk mencapai kepentingan sesaat kebijakan luar negerinya tanpa menghiraukan norma-norma hak asasi manusia. Contoh sementara bisa ditemukan sepanjang tahun 90an, sejak dari Somalia hingga Rwanda, Bosnia hingga Chechnya, bahkan Irak di tahun 2003. tentu saja beberapa kebijakan luar negeri hak asasi manusia yang lama masih berlaku, karena perubahan fundamental dalam kebijakan ©Abdullahi Ahmed An-Na`im luar negeri tidak mungikn terjadi secara menyeluruh dan terjadi pada satu waktu. Tapi juga jelas bagi saya, bahwa ada penurunan kualitas yang terus menerus terjadi pada kebijakan lama tersebut, karena pemerintah yang bersalah menyaksikan dengan seksama seberapa besar kemungkinan mereka untuk lari dari pertanggung jawaban dan mereka yang termotivasi untuk memasukkan DUHAM ke dalam kebijaan luar negerinya juga mempertimbangkan seberapa besar kerugian yang mereka dapatkan jika mereka melindungi hak asasi manusia rakyatnya.66 Karena gerakan hak asasi manusia berhenti mendesakkan kepentingannya akibat lemahnya posisi tawar yang mereka miliki dalam politik nasional dan regional, pemerintah menjadi semakin berani untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang sesaat tanpa mempertimbangkan norma-norma hak asasi manusia. Penurunan tingkat urgensi HAM dalam kebijakan luar negeri sebuah negara, juga dilegitimasi melalui prosesproses demokratis seperti fenomena terpilihnya kembali George W. Bush dalam Pemilu Amerika kemarin. Padahal, Bush jelas-jelas tidak begitu konsen dengan HAM dan hukum internasional. Dengan mengatakan seperti ini, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ide HAM itu sendiri, atau memprediksikan ketidakberdayaannya dalam menghadapi kondisi domestik dan hubungan internasional. Saya hanya ingin mengalihkan fokus advokasi HAM kepada masyarakat agar HAM tidak lagi tergantung pada ketidakjelasan hubungan antar pemerintahan. Namun juga tidak berarti bahwa peralihan fokus ini akan menghentikan strategi advokasi HAM internasional, karena 66 Sebagai contoh lihat, David P. Forsythe, “Comparative Foreign Policy and Human Rights: the United States and Other Democracies”, dalam “Innovation and Inspiration: Fifty Years of The Universal Declaration of Human Rights, eds. Baehr, Flinterman and Senders, hlm. 161-167 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im strategi itu juga masih penting untuk melindungi HAM pada saat ini.67 Yang saya ingin ajukan adalah bagaimana kita mulai mengurangi ketergantungan pada advokasi internasional untuk melindungi hak asasi manusia, dengan mulai mengembangkan kapasitas komunitas lokal untuk melindungi hak mereka sendiri dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.68 Peralihan fokus dari advokasi internasional ke upaya lokal ini tentu tidak bisa dilakukan dengan mudah dan menyelesaikan kemunduran yang sedang terjadi, namun ini hanya satu upaya untuk melangkah maju. Dalam konteks masyarakat muslim, penguatan komunitas lokal ini bisa dilakukan dengan cara meyakinkan dan memotivasi ummat Islam untuk menerima dan mengimplementasikan hak asasi manusia. Saya menyadari bahwa hak sasi manusia bukanlah obat yang manjur dan universal bagi semua masalah yang muncul dalam masyarakat. Tapi norma dan lembaga-lembaga hak asasi manusia bisa memberdayakan orang untuk ikut serta dalam upaya politik dan hukum untuk menegakkan kemanusiaan dan keadilan sosial. Islam, Syari’ah dan Kebebasan Beragama Diskusi mengenai konflik antara syari’ah dan konstitusionalisme dan kemungkinan memediasi konflik tersebut dengan merujuk pada Islam secara lebih luas dapat diterapkan juga dalam kasus Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, kita akan mulai dengan mengklarifikasi ketegangan yang mungkin timbul antara Syariah dan Hak Asasi 67 Manusia kemudian mengeksplorasi cara-cara untuk menyelesaikan Sebagai contoh lihat, Robert F. Drinan, The Mobilization of Shame: a World View of Human Rights, (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2001); dan Claude E. Welch, Jr, (ed.), NGOs and Human Rights: Promise and Performance, (Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press), 2001. 68 Penjelasan mengenai usulan saya ini lihat “Introduction: Expanding Legal Protection of Human Rights in African Context”, dalam Abdullahi Ahmed An-Naim, ed., Human Rights under African Constitutions: Realizing the Promise for Ourselves, Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, hlm. 1-28; dan Abdullahi Ahmed an-Naim, “Human Rights in the Arab World: A Regional Perspective” Human Rights Quarterly, vol 23: 3, 2001 hlm. 701-32 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im ketegangan tersebut melalui reformasi Islami. Mengakui adanya konflik dan memahami sifatnya sangat penting untuk melakukan proses mediasi dan penyelesaian konflik. Nah, konflik yang terjadi antara Syari’ah dan Hak Asasi Manusia biasanya berkisar seputar isu hak perempuan dan non-muslim. Dalam kesempatan ini saya akan mengungkapkan area konflik yang lain yaitu kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan isu-isu hak asasi manusia dan kemudian mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan penyelesaian konflik antara syariah dan prinsip kebebasan beragama dalam hak asasi manusia melalui reformasi Islami. Untuk menghindari kebingungan, saya nyatakan bahwa saya percaya terhadap adanya kemungkinan, bahkan keharusan, untuk menginterpretasi ulang sumber-sumber Islam untuk menegaskan dan melindungi kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan. Disini saya berbicara sebagai seorang muslim yang menggunakan perspektif Islam, dan bukan sekedar berbicara sebagai orang yang mengakui kebebasan beragama hanya karena kebebasan beragama itu merupakan prinsip yang terdapat dalam DUHAM dan mengikat muslim menurut prinsip hukum internasional. Ada dua asalan mengapa diskusi mengenai hal ini menjadi penting. Pertama, konflik antara aturan agama dengan hak kebebasan beragama tidak hanya terjadi pada Islam tapi juga terjadi dalam tradisi agama dan ideologi lain. Contohnya, pemahaman tradisional terhadap teks Yahudi dan Kristen mengharuskan hukuman mati dan konsekuensi-konsekuensi lain bagi orang-orang yang murtad.69 Pelaksanaan ketentuan agama dengan menggunakan tindakan-tindakan seperti itu hampir sama dengan konsep pemberontakan (treason) yang tetap menjadi kejahatan 69 Argumen kitab suci untuk hukuman mati bagi pelaku murtad dan penghinaan ada dalam Deuteronomy 13: 6-9 dan Letivicus 24: 16; lihat juga Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 35 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im besar dalam sistem hukum Negara modern saat ini. Larangan murtad dalam tradisi syari’ah Islam bukan hanya sekedar bagian dari tradisi keagamaan, tapi juga terjadi dalam tradisi ideologi sekuler. Ketidaktundukkan seseorang pada doktrin Marxisme pada masa pemerintahan Uni Soviet mungkin dihukum lebih berat daripada fenomena murtad dan kejahatan dalam syari’ah. Satu hal penting yang juga perlu dicatat adalah bahwa prinsip-prinsip syari’ah jarang diaplikasikan secara sitematis dan ketat di masa lalu, bahkan lebih jarang pada masa sekarang. Meskipun demikian, keberadaan prinsip-prinsip tersebut menimbulkan konflik yang fundamental dengan ide dasar hak asasi manusia universal dan menjadi sumber pelanggaran terhadap praktik kebebasan beragama. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, saya merasa perlu untuk menghadapi isu ini untuk menegakkan integritas moral terhadap kepercayaan yang saya anut sekaligus menolak praktik pelanggaran hak asasi manusia ini meskipun hal ini mungkin jarang terjadi pada saat sekarang ini. Saya akan mendiskusikan konsep murtad dan konsep-konsep yang berkaitan dengannya dalam syari’ah untuk menjelaskan ketidakcocokkan prinsip–prinsip tersebut dengan kebebasan beragama dari perspektif Islam, bahkan tanpa harus merujuk pada norma hak asasi manusia modern. Penerapan prinsip netralitas Negara terhadap agama secara tepat akan mampu mengelimininasi kemungkinan konsekuensi negatif hukum murtad dan konsep lainnya. Namun tidak akan mungkin mampu untuk mengeliminasi implikasi sosial negatif dari prinsip-prinsip syariah tradisional tersebut. Aspek tersebut harus diselesaikan melalui langkahlangkah pendidikan secara terus menerus untuk mempromosikan pluralisme yang genuine dan berkelanjutan. Diskusi berikut ini berlaku untuk aspek sosial dan ©Abdullahi Ahmed An-Na`im hukum dengan memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip syari’ah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi secara moral maupun politis sehingga mereka tidak boleh dilaksanakan oleh negara maupun diterima oleh masyarakat Islam. Istilah arab “riddah” biasa diterjemahkan sebagai kemurtadan. Namun secara bahasa berarti “kembali” dan murtad berarti “orang yang kembali”.70 Dalam pemahaman syari’ah tradisional, riddah berarti berpalingnya kembalinya seseorang yang sudah menganut Islam menjadi kufur karena sengaja atau implikasi tertentu.71 Dengan kata lainm sekali seseorang memilih menjadi muslim, tak ada alasan baginya untuk mengubah agamanya. Menurut para fuqaha, riddah dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti menolak keberadaan tuhan atau sifat-sifat tuhan, menolak salah satu rasul Tuhan atau menolak status kenabian salah satu Nabi, menolak salah satu prinsip keagmaan seperti sholat lima waktu atau berpuasa di bulan ramadlan, menghalakan yang haram atau mengharamkan yang halal. Status murtad secara tradisional diberikan kepada muslim yang dianggap sudah beralih dari Islam, baik secara sengaja atau hanya sekedar ucapan, baik itu diungkapkan sebagai guyonan, out of stubborness, or out of conviction.72 Keberatan terhadap pendapat bahwa kemurtadan adalah sebuah kejahatan atau dianggap salah menurut aturan hukum syari’ah sehingga orang murtad harus mendapatkan hukuman atau konsekuensi-konsekuensi hukum lain adalah, karena pendapat ini sebetulnya bertentangan dengan sikap al-Qur’an sendiri. Dalam Qs. 2:217, 4:90, 5:54, 59, Qs.16:108, dan Qs.47:25, al-Qur’an memang mengutuk 70 The following review of classical Islamic jurisprudence of apostasy is based on Ibn Rushd, Bidayat al-Mugjtahid, vol. 2, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabic, not dated); and Nu`man Abd al-Razid al-Samar`i, Ahkam al-Murtad fi al-Shari`a al-Islamyia (Beirut: al-Dar al-Arabiya, 1968). In English see Shaikh Abdur Rahman, Punishment of Apostasy in Islam (Lahore, Pakistan: Institute of Islamic Culture, 1972). 71 Saeed and Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 36, 42 72 Saeed and Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 36-37 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im kemurtadan namun tidak menyebutkan dengan spesifik konsekuensi-konsekuensi legal perbuatan ini.73 Malah, al-Qur’an dengan jelas menyebutkan beberapa situasi yang menyiratkan bahwa orang murtad dapat terus hidup di tengah-tengah komunitas muslim. Contohnya Qs. 4: 137 yang bisa diterjemahkan sebagai berikut: “mereka yang beriman, kemudian kufur, kemudian beriman kembali, dan kemudian kufur kembali, dan terus berbuat demikian, Allah tidak akan mengampuni dan menunjukkan pada mereka jalan yang benar.” Jika memang benar al-Qur’an menetapkan hukuman mati bagi orang yang murtad, orang tersebut tidak akan terus hidup di tengah komunitas muslim untuk mengulangi kejahatan yang sama. Namun demikian, para fuqaha mempergunakan hadits untuk menetapkan hukuman mati bagi orang yang murtad dan konsekuensi-konsekuensi hukum lainnya seperti terhapusnya hak waris dari dan untuk orang yang murtad.74 Selain ketidakcocokkan dengan prinsip kebebasan beragama yang berulang kali ditekankan dalam al-Qur’an, ada dua aspek problematis yang terdapat dalam konsep murtad dalam tradisi hukum Islam tradisional yaitu ketidakjelasan dan kelemahan konsepnya dan ketidakjelasan dasar hukum untuk konsekuensikonsekuensi hukum yang harus diterima seorang yang murtad karena ia dianggap melakukan kejahatan besar. Sumber ketidakjelasan dan kelemahan konsep murtad sebetulnya terkait dengan definisi dan hukumannya serta kedekatan konsepnya dengan konsep kufr, sabb ar-rasul, zindiq, dan munafiq (nifaq). Fuqoha empat mazhab sunni mengklasifikasi kemurtadan pada tiga kategori: keyakinan, perbuatan dan ucapan. 3 kategori ini kemudian terbagi-bagi lagi kedalam 73 74 Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 57 Artikel “Murtad” dalam Shorter Encyclopedia of Islam, hlm. 413-414 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im beberapa bagian. Namun masing-masing kategori tersebut sebetulnya kontroversial. Contohnya kategori pertama dapat berbentuk keraguan terhadap eksistensi atau keabadian tuhan, keraguan terhadap pesan-pesan kenabian Muhammad atau Nabi lain, ragu terhadap qur’an, hari pembalasan, keberadaan surga dan neraka, atau ragu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan yang sudah menjadi konsensus (ijma) di kalangan muslim seperti sifat-sifat tuhan. Maka, dengan demikian, konsep murtad tidak berlaku pada persoalan yang tidak menjadi konsensus ummat. Padahal sebetulnya, tidak banyak konsensus yang terjadi di antara muslim termasuk mereka yang terdapat dalam daftar para fuqoha atau mazhab mengenai banyak hal. Misalnya karena ada kesamaan pendapat yang signifikan di kalangan muslim mengenai sifat-sifat Tuhan75, maka orang yang menolak atau menerima salah satu sifat tuhan yang ditetapkan atau ditolak oleh seorang ulama, dapat disebut murtad. Padahal, para ulama tidak membedakan konsep-konsep tersebut dan cenderung menggunakan kategori yang luas mengenai konsep murtad sehingga bisa mencakup seluruh aspeknya.76 Cara seperti ini justru membuat istilah murtad menjadi sangat luas dan samar, serta mengacaukan dasar hukum kejahatan dan hukumannya. Saya akan memberikan ilustrasi singkat mengenai hal ini. Karena murtad berarti kembali tidak mempercayai Islam setelah secara rela pernah memeluknya, berari murtad berkaitan erat dengan konsep kufur (kufr) yang berati penolakan terbuka terhadap pesan-pesan Islam.77 Meskipun berkali-kali menyebutkan istilah kufr dan iman, al-Qur’an tidak memberikan arahan yang jelas mengenai makna kedua istilah tersebut kecuali berkaitan dengan pengakuan 75 Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 37 (catatan kaki no. 13), hlm. 189 Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 37 77 Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 42 76 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im keimanan dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Al-Qur’an misalnya berulang kali menghubungkan konsep iman dengan mendirikan shalat, mengerjakan puasa atau beramal saleh, tapi tidak pernah mengungkapkan apa yang harus dilakukan pada mereka yang gagal mematuhi kewajiban tersebut kecuali hukuman pada hari kemudian. Al-Qur’an juga tidak dengan jelas menyatakan konsekuensi-konsekuensi yang akan didapatkan jika ummatnya mempertanyakan pengakuan iman itu sendiri. Contohnya, apakah makna menyatakan “tiada Tuhan selain Allah”? apa yang orang beriman ketahui dan harus mereka ketahui tentang Tuhan? Apa konsekuensi langsung dari beriman kepada Allah pada kehidupan personal dan perilaku muslim baik dalam level individual maupun dalam hubungannya dengan lembaga dan proses social, ekonomi dan politik di sekellingnya? Siapa yang memiliki otoritas untuk menghakimi perbedaan pendapat mengenai hal tersebut atau mengenai halhal lainnya setelah wafatnya Nabi Muhammad dan bagaimana caranya? Al-Qur’an membiarkan ummat Islam dengan sendirinya bergulat dengan persoalanpersoalan tersebut. Benar bahwa ummat Islam memiliki sunnah, teladan kehidupan Nabi sebagai sumber pedoman lain, namun sunnah juga memiliki ketidakjelasan yang sama. Dengan demikian, tidaklah heran jika perbedaan pendapat mengenai peran “perbuatan” (amal) dalam konsep iman terjadi. Beberapa ulama bisa menerima pengakuan lisan keimanan sebagai ciri status muslim seseorang, tapi beberapa ulama lain mengharuskan pengakuan lisan ini dibuktikan dengan melakukan perbuatan dan praktik tertentu. Bagi mereka yang mengharuskan adanya “perbuatan” sebagai bukti keimanan, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana status orang yang sudah mengaku muslim namun tidak melaksanakan ©Abdullahi Ahmed An-Na`im kewajibannya sebagai muslim. Persoalan lain timbul, siapa yang menilai bahwa seseorang sudah melaksanakan kewajiban agama atau belum dan konsekuensi apa yang harus diterima karena penilaian tersebut? Debat mengenai hal tersebut muncul dalam beragam bentuk; sejak dari pendapat dan perilaku kalangan Khawarij selama perang sipil pada abad ke-7, status Ahmadiyah di Pakistan sejak tahun 1950, bahkan hingga keberadaan sejumlah sekte-sekte pembunuhan dan terorisme.78 Ketidakjelasan ini kemudian diperparah dengan kesamaran dan ketidaksepakatan mengenai konsep-konsep lain. Kesamaran dan ketidakjelasan seperti ini juga terjadi pada larangan sabb al-naby. Sabb al-naby adalah penggunaan kata-kata hinaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, Tuhan, atau para Malaikat. Orang yang melakukan pelanggaran ini menurut tradisi ulama fiqih tradisional harus dihukum mati.79 Pada tahap selanjutnya, bentuk pelanggaran ini kemudian diperluas mencakup segala bentuk pelarangan dan mengungkapkan kata-kata hinaan kepada para Sahabat nabi. Sebagian Ulama tetap menganggap orang yang melakukan tindakan ini sebagai muslim, tapi ia harus menerima hukuman tertentu. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa tindakan seperti ini menyebabkan seseorang tidak layak lagi dianggap sebagai seorang muslim. Jika tindakan ini dilakukan oleh non-muslim, ia tidak dianggapp murtad, tetapi tetap harus dihukum mati. Seperti halnya ketentuan mengenai murtad, hukuman tindakan penghinaan ini juga berdasarkan beberapa peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, sementara dalam al-Qur’an sendiri tidak ada petunjuk jelas mengenai hal tersebut. Bahkan meskipun al-Qur’an menggunakan istilah sabb seperti dalam Qs. 6: 108, ia hanya menginstruksikan ummat Islam untuk 78 Sebagai contoh lihat, Khaled Abou el-Fadl, Rebellion and Violence in Islamic Law (New York: Cambridge University Press, 2001) 79 Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 37-38 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im berhenti mencaci dewa-dewa non-muslim, karena mereka juga sebetulnya menghina Tuhan. Namun al-Qur’an tidak menyebutkan hukuman apapun berkaitan dengan hal ini. Sementara para ulama merujuk pada beberapa peristiwa pada masa awal Islam untuk menetapkan hukuman mati bagi pelaku penghinaan, namun jelas sekali bahwa baik Qur’an maupun Sunnah tidak mengungkapkan keberadaan pelanggaran yang bernama “sabb al-naby” ataupun hukuman khusus terhadap pelakunya.80 Terdapat masalah yang sama menyangkut status hukum zindiq. Istilah zindiq digunakan dalam sumber-sumber syari’ah untuk menyebut orang zindiq yang ajarannya berbahaya bagi komunitas muslim dan menurut aturan syari’ah mereka layak untuk dihukum mati. Namun istilah zindiq dan kata turunannya tidak pernah muncul dalam al-Qur’an sama sekali, bahkan nampaknya merupakan istilah yang diserap Bahasa Arab dari Bahasa Persia. Istilah ini nampaknya pertama kali digunakan dalam kaitannya dengan eksekusi Ja’d bin dirham pada tahun 742 M— setelah lebih dari satu abad wafatnya nabi. “pada praktiknya apa yang difahami oleh kalangan konservatif sebagai zindiq adalah orang yang pengakuan Islamnya, menurut mereka, tidak cukup meyakinkan”.81 Namun, tidak tampak adanya kesamaan pendapat tentang definisi istilah yang mereka maksud. Bahkan terdapat perbedaan pendapat mengenai tipe-tipe perilaku yang dianggap sebagai perilaku zindiq atau membuat seseorang dihukumi zindiq. Misalnya orang yang mengaku muslim, tapi masih mengikuti ajaran agama lamanya. Namun bagaimana definisi ini dapat diketahui dan digunakan dalam kasus-kasus spesifik? Karena tiadanya definisi istilah yang jelas dan spesifik, tak heran bila beberapa ulama menganggap seseorang zindiq jika ia melakukan hal-hal terlarang dalam Islam seperti zina atau 80 81 Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 38-39 Article “Zindiq” Shorter Encyclopedia of Islam, hlm. 659 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im meminum arak.82 Pentingnya definisi yang jelas ini juga berkaitan dengan sikap sebagian ulama khususnya dari mazhab Hanafi dan Maliki menolak kemungkinan pelaku zindiq untuk mendapatkan pengampunan jika mereka menyesal, padahal orang murtad bisa mendapatkan kesempatan itu.83 Review singkat ini bisa dengan jelas memperlihatkan bahwa selalu ada kebingungan dan kesamaran dalam konsep-konsep tersebut dan bagaimana konsep tersebut didefinisikan. Bahkan ada juga ketidakjelasan mengenai dasar hukum bagi jenis hukuman yang ditetapkan bagi pelaku pelanggaran tersebut. Karena al-Qur’an tidak mendefinisikan konsep-konsep tersebut dengan jelas dan juga tidak menentukan hukuman tertentu yang harus ditimpakan pada pelaku pelanggaran tersebut saat mereka hidup, masyarakat Islam saat ini nampaknya bisa dan bahkan mungkin mempertimbangkan kembali aspek-aspek syariah tersebut dalam kerangka kebebasan beragama. Bahkan, nampaknya jumlah ayat-ayat al-Qur’an yang mendukung pandangan terakhir ini lebih banyak daripada ayat yang mendukung keharusan adanya ketentuan hukum bagi para pelaku pelanggaran tersebut.84 Dengan kata lain, seharusnya tidak ada hukuman atau konsekuensi legal apapun terhadap perbuatan murtad atau perbuatan sejenis lainnya, karena konsep iman dalam Islam mengandaikan dan mengharuskan adanya kebebasan untuk memilih dan tidak dapat dianggap sah jika dilakukan di bawah tekanan. Kemungkinan untuk mempercayai sesuatu secara logis mengharuskan adanya kebebasan untuk memilih. Dengan demikian seseorang tidak akan bisa mempercayai sesuatu tanpa ada kebebasan dan kemampuan untuk mempercayainya. 82 Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 40 Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 41, 54-55 84 Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 69-87 83 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Ketidakjelasan dan kemenduaan prinsip-prinsip syari’ah tersebut memicu lahirnya manipulasi dan pelanggaran terhadapnya demi tujuan-tujuan politik atau polemik. Banyak ulama besar yang dihormati dan diakui otoritasnya seperti Abu Hanifah, Ibn Hanbal, al-Ghazaly, Ibnu Hazm,dan Ibnu Taimiyyah pernah didakwa murtad semasa mereka hidup.85 Resiko semacam ini cenderung meniadakan kemungkinan terjadinya proses refleksi hukum dan teologi serta proses perkembangan dalam masyarakat muslim sendiri atau ummat secara umum. Mengemukakan alasanalasan meyakinkan mengenai pentingnya penghapusan doktrin murtad dan konsepkonsep lainnya untuk kepentingan Islam (sebagai suatu agama) dan masyarakat muslim secara keseluruhan, tanpa mengambil rujukan kepada norma-norma Hak asasi manusia, adalah untuk menunjukkan bahwa dalam Islam sendiri terdapat argumen dan pendekatan untuk melindungi kebebasan beragama. Cara ini sangat tepat untuk menunjukkan mempromosikan validitas dan efektivitas prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sendiri.86 Bagaimana hasil yang memuaskan ini bisa dicapai dalam praktik kehidupan sekarang? Dilema yang dirasakan oleh mereka yang mendukung reformasi semacam itu dalam masyarakat kita adalah apakah mereka harus mencapai tujuan mereka dengan mempergunakan korpus dan metodologi syariah yang sudah ada atau berusaha menghindari keterbatasan pendekatan tersebut dengan menerapkan pemisahan yang ketat antara agama dan negara. Menurut pendapat saya, kedua pendekatan tersebut memiliki keterbatasan. Di satu sisi, reformasi terhadap kerangka syariah tradisional tidak mungkin bisa menghapus semua gagasan mengenai murtad dan 85 Saeed dan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 30-31 Argumentasi Islam dan Hak Asasi Manusia mengenai pentingnya memerangi kejahatan-kejahatan ini lihat tulisan saya “Islamic Foundation of Religious Human Rihts, dalam John Witte, Jr., dan Johan D. Van der Vyver, (ed.), Religious Human Rights in Global Perspectives: Religious Perspective. (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996), hlm. 337-359. 86 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im konsep lainnya, karena hal semacam itu tentu saja tidak mungkin dibenarkan oleh metodologi ushul fiqih yang sudah diformulasikan oleh para ulama seperti al-Syafi’i 1200 tahun yang lalu. Ushul fiqih tradisional pasti mendukung penetapan hukuman mati atau ketentuan hukum lainnya pada orang murtad karena hukuman tersebut didasarkan pada aturan yang terdapat dalam sunnah, meskipun bukan al-Qur’an. Pada saat yang sama, konsep murtad dan konsep lainnya tidak bisa begitu saja dihapus dari ketentuan syari’ah tanpa justifikasi yang cukup, karena otoritas moral dan sosial syari’ah di tengah-tengah ummat muslim. Upaya penghapusan yang efektif dan berkelanjutan terhadap konsep-konsep tersebut sebagai upaya untuk menginterpretasi ulang syari’ah harus menggunakan logika Islam tradisional daripada sekedar menggantungkan diri pada otoritas negara sekular untuk menolak menerapkan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengannya. Reformasi Islam juga mengharuskan adanya reformasi ushul fiqih karena baik interpretasi tradisional maupun alternatif terhadap al-Qur’an dan sunnah adalah produk sebuah konteks historis tempat masyarakat muslim tinggal dan hidup. Dengan demikian untuk menghadapi transformasi politik, sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat muslim saat ini, sebagaimana yang ternah terjadi di masa perkembangan pemahaman syariah tradisional, metodologi interpretasi harus merefleksikan kondisi tersebut agar bisa menghasilkan formulasi syari’ah yang tepat. Ini bisa dilakukan dengan cara misalnya dengan menguji ulang logika penerapan sejumlah ayat Qur’an dan sunnah ke dalam prinsip-prinsip syariah dan menekankan ketidak cocokkan rujukan keagamaan lain untuk konteks masyarakat Islam saat ini. Dengan memahami pilihan-pilihan tersebut dibuat oleh manusia dan bukan merupakan perintah tuhan secara langsung, maka mempertimbangkan kembali relevansi teks tersebut untuk diterapkan dalam konteks sekarang dan ©Abdullahi Ahmed An-Na`im perlunya menekankan ulang konsep-konsep tersebut menjadi hal yang mungkin. Meskipun saya mengikuti model pendekatan yang sudah dikembangkan oleh ulama Sudan, Mahmoud Muhammad Toha,87 bukan berarti pendekatan lain tidak berlaku. Penting untuk dicatat, debat teologis ini mungkin memiliki dimensi politik dan kontekstual. Kemampuan seorang reformer untuk mendapatkan kepercayaan dari komunitas dan otoritas di kalangan anggotanya tergantung pada pemahamannya terhadap kompleksitas sejarah komunitasnya serta konteks, kepentingan dan aspirasi mereka. Kita bisa melihat contoh Mahmud Muhammad Toha yang mengadvokasikan pikirannya di Sudan selama 40 tahun dan ia tetap dihukum mati karena dakwaan murtad pada Januari 1985.88 karena itu, di samping harus memiliki metodologi refomasi yang koheren dan efektif, seorang reformer juga harus mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam mengadvokasikan ide-idenya. Ini juga berarti mempertimbangkan faktor atau kekuatan pendukung sekaligus kekuatan yang menentang proses reformasi yang diajukan. Negara, sebetulnya, berperan besar dalam prose-proses tersebut bukan saja dengan menghentikan usaha-usaha menerapkan syari’ah sebagai hukum positif, tapi juga melalui sistem pendidikan, upaya mempromosikan pemikiran kritis dalam media dan mengamankan ruang politik sosial dan politik agar debat publik dapat terlaksana dengan baik dan bebas. Namun negara dan komunitas international secara luas, sebetulnya juga bisa menjadi bagian dari masalah. Proses liberalisasi politik dan sosial yang diinginkan bisa mengancam posisi elite yang mengontrol 87 Mahmoud Muhammad Toha, The Second Message of Islam, (Syracuse University press, 1987). Abdullahi Ahmed an-Na’im, “The Islamic Law of Apostasy and its Modern Applicability: A Case from the Sudan”, Religion, vol. 16, 1986, hlm. 197-223. 88 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im negara, bahkan sekalipun mereka mengklaim sebagai elit yang memiliki orientasi politik sekular. Selain itu, negara-negara lain juga mungkin saja mendukung rezim opresif yang ada di negara-negara Islam atau menerapkan politik luar negeri yang keras dan malah menimbulkan konservatisme dan pembelaan membabi buta dalam masyarakat Islam, bukannya melahirkan kepercayaan dan tingkat keamanan yang justru lebih diperlukan untuk mendorong proses liberalisasi politik dan sosial internal. Meskipun tanggung jawab untuk mengamankan kebebasan beragama dalam masyarakat islam tergantung pada diri mereka sendiri, komunitas interrnasional juga mempunyai peran penting dalam menumbuhkan kondisi yang kondusif untuk kesuksesan usaha yang dilakukan masyarakat muslim tersebut. Proses ini membawa kita pada isu terakhir yaitu relevansi ide kewarganegaraan dalam proses ini, lagi-lagi dari perspektif Islam. IV. Kewarganegaraan Apapun argumennya, adalah sebuah fakta bahwa kolonialisme Eropalah yang mentransformasikan secara drastis dasar dan asal-ususl organizasi politik dan sosial dalam negara tempat muslim tinggal.89 Transformasi ini begitu mendasar dan sangat mendalam; menyebar pada seluruh aspek aktivitas ekonomi, proses politik, kehidupan sosial dan relasi komunal, pemenuhan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya sehingga membuat ide untuk mengembalikan semuanya pada sistem dan ide prakolonial menjadi tidak mungkin. Perubahan dan adaptasi apapun yang dilakukan pada sistem yang sekarang berlaku, hanya bisa dilakukan melalui konsep dan institusi post kolonial domestik dan global saat ini. Namun banyak muslim, bahkan mungkin mayoritas dari mereka di berbagai negara, belum bisa 89 Lihat James Piscatori, Islam in a Wold of Nation States (Cambridge: Cambridge University Press, 1986). ©Abdullahi Ahmed An-Na`im menerima beberapa aspek dalam proses transformasi ini termasuk berbagai konsekuensinya. Untuk mengklarifikasi dan memahami ketimpangan ini, saya akan memfokuskan bahasan ini pada persoalan kewarganegaraan yang ternyata mempunyai implikasi jangka panjang terhadap stabilitas politik, pemerintahan dan pengembangan yang konstitusional di dalam negeri serta hubungan internasional. Secara khusus, saya akan mengajukan hak asasi manusia sebagai kerangka untuk menggaris bawahi dan menyelesaikan ketegangan yang ada dalam ketimpangan pemahaman masyarakat Islam saat ini terhadap konsep kewarganegaraan. Manusia cenderung mencari dan mengalami tipe dan bentuk keanggotaan yang beragam dan saling bersinggungan dalam kelompok yang berbeda yang berdasarkan etnik, agama atau identitas kultural, afiliasi politik, sosial atau profesional atau kepentingan ekonomi. Motivasi untuk menjadi anggota sebuah kelompok cenderung terkait dengan alasan dan tujuan kelompok tersebut, tanpa membatasi atau mengurangi pentingnya bentuk keanggotaan yang lain. Nah, bentuk keanggotaan yang beragam dan bersinggungan ini tidak selalu ekslusif, karena keragaman tersebut justru bisa memenuhi tujuan masing-masing individu dan komunitas yang berbeda. Ini mungkin hanya sekedar sebuah model yang terlalu sederhana, karena dasar keanggotaan dalam sebuah kelompok tidak mungkin bisa didefinisikan dengan jelas. Interaksi yang terjadi mungkin akan menjadi kompleks dan tergantung pada faktor-faktor lain dan orang juga tidak selalu sadar dengan dasar-dasar tersebut atau secara konsisten berbuat dan berlaku sesuai dengannya. Namun hal penting yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa orang cenderung secara sadar atau setengah sadar untuk menjadi atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari sebuah kelompok karena tujuan-tujuan yang berbeda. Dan harus pula dicatat bahwa keanggotaan itu bukan hanya pada satu kelompok. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Istilah kewarganegaraan yang saya gunakan disini berarti sebagai sebuah bentuk keanggotaan dalam komunitas politik sebuah wilayah negara dalam konteks globalnya dan dengan demikian terkait dengan alasan dan tujuan tertentu, namun dengan tanpa membatasi kemungkinan bentuk keanggotaan lain. Ini bukan berarti bahwa setiap orang akan sadar sepenuhnya dengan bentuk atau tipe keanggotaan ini atau mereka akan menganggap bentuk keanggotaan ini sebagai sesuatu yang inklusif terhadap bentuk keanggotaan lain atau menyadari bahwa masing-masing bentuk keanggotaan memiliki tujuan dan alasan tertentu. Bahkan, di sini saya akan mengungkapkan bahwa ada kebingungan di kalangan muslim mengenai makna dan implikasi kewarganegaraan dalam sebuah wilayah negara, yang dibedakan meskipun tidak ekslusif, dengan bentuk dan tipe keanggotaan lain. Penting untuk dicatat bahwa kebingungan seperti ini tidak hanya terjadi pada masyarakat muslim atau terjadi karena mereka memeluk Islam. Contohnya ada kecenderungan umum di kalangan masyarakat utuk menghilangkan beberapa bentuk keanggotaan seperti keanggotaan berdasarkan etnis atau agama yang luntur karena afiliasi politik atau sosial. Dengan demikian, perkembangan negara bangsa model Eropa yang berbasis wilayah sejak abad 18 tidak hanya cenderung menyamakan konsep kewarganegaraan dengan kebangsaan, tapi juga terus menekankan pentingnya praktik konsep warga negara yang setara.90 Menyamakan konsep kewarganeganegaraan dengan kebangsaan adalah keliru karena keanggotaan seseorang dalam sebuah komunitas politik sebuah negara tidak selalu bersamaan dengan adanya perasaan memiliki. Pun tidak pula memperlihatkan hubungan apapun dengan cara orang merasa menjadi bagian dari sebuah negara 90 Derek Heater, A Brief History of Citizenship (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004). ©Abdullahi Ahmed An-Na`im atau lainnya. Lagipula, dalam teorinya hak-hak warga negara tunduk pada berbagai pembatasan hukum dan dalam praktiknya pada pembatasan tertentu, sebagaimana yang akan kita lihat dalam kasus kerudung yang terjadi di Perancis dalam bab 4 nanti. Seperti halnya nasionalisme, konsepsi dan praktik kewarganegaraan menjadi norma yang sudah diterima dalam hubungan politik domestik dan intenasional di seluruh dunia termasuk di kalangan masyarakat Islam. Bahkan konsep-konsep identitas dan kedaulatan yang memiliki nilai “menentukan nasib sendiri” (self-determination) sekarang dibangun di atas dasar yang sama dengan model Eropa. Dan bagusnya, konsepsi-konsepsi tersebut terus berkembang dan merefleksikan pengalamanpengalaman masyarakat lain terutama melalui proses dekolonisasi dan perkembangan norma-norma hak asasi manusia universal sejak pertengahan abad 20. Konsepsi-konsepsi kewarganegaraan, kedaulatan dan hak untuk menentukan diri sendiri yang sedang berkembang ini adalah konsep-konsep yang saya tawarkan kepada masyarakat muslim untuk diterima dan dipergunakan sebagai prinsip, dan bukan hanya sebagai konsesi pragmatis untuk menghadapi realitas pasca kolonial. Benar bahwa umat Islam di manapun sudah menerima konsep dasar kewarganegaraan sebagai dasar sistem politik dan undang-undang domestik mereka bahkan juga menjadi dasar bagi hubungan internasional mereka dengan negaranegara lain. Kewarganegaraan memang sudah menjadi dasar hubungan antar muslim, maka saya kemudian membutuhkan visa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saudi Arabia agar saya bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah disana dan tidak bisa berharap akan diterima bagitu saja di sana hanya karena saya seorang muslim ©Abdullahi Ahmed An-Na`im yang akan melaksanakan kewajiban agama saya. Meskipun dasar konsep kewarganegaraan sudah diterima, namun kita perlu melangkah satu tindak ke depan. Yaitu mengembangkan dan mempromosikan prinsip-prinsip kewarganegaraan di kalangan muslim agar mereka dapat memegang prinsip tersebut dan berusaha untuk merealisasikan pemahaman positif dan proaktif terhadap konsep kesetaraan warga negara untuk semua orang tanpa membedakan agama, jenis kelamin, etnis, bahasa atau opini politik apapun. Konsep kewarganegaraan harus menandakan adanya pemahaman bersama tentang kesetaraan posisi semua manusia dan partisipasi politik yang inklusif dan efektif untuk menjamin akuntabilitas pemerintah dalam menghargai dan melindungi hak asasi manusia semua pihak. Keinginan untuk menyebarkan pemahaman mengenai konsep kewarganegaraan ini ke seluruh dunia tentu saja bisa didasarkan pada berbagai macam pertimbangan, termasuk realitas pragmatis hubungan kekuasaan dalam sebuah masyarakat sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Namun, keinginan itu juga membutuhkan asas keagamaan, filosofis dan moral agar pengertian kewarganegaraan konsisten dengan norma-norma hak asasi manusia universal. Kombinasi dasar moral dan pragmatis ini bisa dilihat dalam apa yang disebut sebagai the golden rule prinsip resiprokal (mu’awada) dalam diskursus keislaman. Memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat dan empati adalah hal yang diperlukan dalam membangun sensibilitas moral di antara tradisi agama dan filasafat tertentu. Dan tentu saja menjadi syarat bagi adanya perlakuan yang sama dari orang lain. Dengan demikian, baik individu maupun komunitas dimanapun berada harus mengakui adanya kesamaan status warga negara, jika mereka ingin diperlakukan sama di negeri sendiri maupun di negeri lain. Karena itulah, ©Abdullahi Ahmed An-Na`im memahami konsep kewarganegaraan berdasarkan hak asasi manusia universal adalah merupakan dasar politik, hukum dan moral untuk menikmatinya. Ummat Islam sebetulnya sudah menerapkan ide-ide tersebut melalui hukum negaranya maupun hukum internasional, termasuk melalui kerjasama dengan orang lain untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan hak-hak asasi manusia universal dalam proses yang lebih luas. Standar dan proses internasional itu memang memberikan kontribusi untuk memahami dan melindungi hak-hak warga negara dalam level domestik. Dengan demikian, hubungan antara hak asasi manusia dan kewarganegaraan merupakan sesuatu yang inheren dan saling mendukung dalam hubungan antar keduanya. Jika kewarganegaraan difahami dari sudut pandang hak asasi manusia, maka sebagai seorang warga negara, muslim bisa berpartisipasi secara lebih efektif dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan hak asasi manusia. Dan ia bisa menikmati status kewarganegaraannya. Keterhubungan antara dua konsep tersebut mengasumsikan bahwa negara yang terikat oleh hukum internasional dan piagam-piagam hak asasi manusia lain adalah representasi warga negaranya. Namun realitasnya, ini tidak selalu sama di semua negara apalagi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Asia dan Afrika. Dengan demikian tantangannya adalah bagaimana menerapkan pendekatan hak asasi manusia ini dalam konsep kewarganegaraan sehingga proses ini pada akhirnya bisa memberikan kontribusi dalam merealisasikan prinsip akuntabilitas dan pemerintah yang demokratis. Masalahnya adalah bagaimana mempergunakan sumber daya yang ada, termasuk konsep kewarganegaraan dan hak asasi manusia yang sudah diterima, untuk mempromosikan sumber daya yang sama. Proses ©Abdullahi Ahmed An-Na`im pengembangan konsep kewarganegaraan dan hak asasi manusia ini akan dipengaruhi oleh jaringan faktor dan aktor yang kompleks dan luas baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Termasuk di dalamnya relasi sosial dan ekonomi, pengaruh sistem pendidikan dan aktifitas media dan juga seluruh konteks sejarah dan sosial politik aktual. Persepsi negatif dan hegemoni relasi kekuasaan yang mungkin mengurangi efektifitas dan relevansi konstitusionalisme dan hak asasi manusia, sebagaimana sudah disebutkan di muka, juga mungkin terjadi dalam konteks hubungan konsep kewarganegaraan dengan hak asasi manusia. Dengan pemahaman yang jelas terhadap kompleksitas proses dan hasil yang sulit diperkirakan, saya akan memfokuskan diskusi tentang konsep dzimmihood dalam syariah tradisional sesuai dengan tujuan buku ini. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, konsep dzimmi menandakan adanya perlindungan negara terhadap hak-hak dasar dan otonomi komunal yang terbatas masyarakat non-muslim (ahldzimmah) sebagai konsesi atas pengakuan mereka atas kedaulatan muslim.91 Meskipun konsep ini lemah untuk digunakan sebagai dasar bagi konsep kewarganegaraan dalam konteks negara muslim saat ini, namun ia terus memiliki pengaruh pada perilaku dan sikap ummat Islam. Konsep Dzimmi dalam Perspektif Sejarah Untuk membahas konsep dzimmi dalam syariah tradisional, perlu kiranya untuk mengklarifikasi dua elemen kebingungan metodologis yang mendasari beberapa diskursus keislaman yang keliru menginterpretasikan syari’ah atau memberlakukan 91 Lihat artikel “Dhimma” dalam Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden: EJ.Brill, 1991, hlm. 75-76; Mahmoud Ayoub, “Dhimmah in the Qur’an and Hadits”, Muslims and Others in Early Muslim Society, ed. Robert Hoyland (Trowbridge,Wiltshire, England: Ashgate Publishing Ltd., 2004), hlm. 25-26. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im prinsip-prinsipnya secara langsung.92 Pertama, fokus kita di sini adalah bagaimana para pendiri mazhab syari’ah memahami text yang relevan dalam al-Qur’an dengan cara yang sistematis. Jadi pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip syari’ah tentang dzimmi yang sudah ada, sebelum menguji kemungkinan untuk mereformasinya. Kedua, reformasi apapun yang diajukan harus mengikuti metodologi yang jelas dan sistematik, daripada sekedar pemilihan arbitrer berbagai sumber atau hanya sekedar merujuk sumber yang bertentangan, karena cara seperti itu pasti akan ditolak. Pun tidak ada gunanya mengutip ayat-ayat al-Qur’an atau sabda Nabi yang mendukung kesetaraan non-muslim tanpa menyebutkan ayat-ayat yang dapat dirujuk untuk mendukung pandangan yang menentangnya. Sistem dzimmi tradisional sebetulnya dikembangkan oleh para ulama sebagai bagian dari sebuah pandangan yang menentukan afiliasi politik berdasarkan afiliasi keagamaan dan bukan berdasarkan wilayah negara seperti yang terjadi pada saat ini.93 Dengan cara seperti itu, ide ini bertujuan untuk menggeser loyalitas politik dari ikatan kesukuan ke Islam sehingga keanggotaan dalam komunitas politik dapat diakses oleh siapapun yang menerima kepercayaan ini. Karena generasi awal ummat Islam percaya bahwa mereka adalah penerima agama wahyu terakhir, mereka berasumsi bahwa mereka mempunyai kewaiban untuk menyebarkan Islam melalu jihad yang bisa dilakukan, namun bukan satu-satunya, melalui penaklukan militer.94 92 Kebingungan metodologis terlihat pada misalnya A. Rahman I. Doi, Non-Muslims under Shari’ah (Islamic Law), (Lahore: Kazi publications, 1981); dan Maimul Ahsan Khan, Human Rights in the Muslim World: Fundamentalism, Constitutionalism, and International Politics, (Durham: Caroline Academic Press, 2003). 93 Michael G. Morony, “Religious Communities in Late Sassanian and Early Muslim Iraq”, Muslims and Others in Early Islamic Societies, ed. Robert Hoyland (Trowbridge, Wiltshire, England: Ashgate Publishing Ltd.,2004), hlm. 1-23 94 al-Nabhani, The Islamic State, hlm. 147 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Senada dengan keyakinan tersebut, para ulama menyarankan ummat Islam untuk mendakwahkan Islam dengan cara damai terlebih dahulu. Namun jika seruan tersebut ditolak, mereka boleh memaksa orang-orang kafir untuk menyerah dan memberlakukan ketentuan yang dipercayai oleh umat Islam sebagai wajib.95 Sistem ini, dengan demikian, mengandaikan adanya pembedaan tegas antara wilayah Islam (dar al-Islam) tempat muslim berkuasa dan syariah berlaku, dengan wilayah yang penduduknya memerangi Muslim (dar al-harb).96 Visi yang dibangun oleh sistem ini adalah bahwa kewajiban untuk menyebarkan islam dengan cara damai maupun perang tetap berlaku sampai seluruh dunia menjadi dar al-Islam. Pandangan ini, tak salah lagi, didukung oleh kesuksesan ummat Islam menaklukkan berbagai daerah sejak dari Afrika Selatan sampai Spanyol bagian selatan di Barat, Persia, Asia Tengah, dan Indian bagian utara di Timur setelah Rasulullah meninggal. Namun keterbatasan praktik karena ketidakpastian ekspansi yang dilakukan semakin jelas dari waktu ke waktu. Penguasa muslim kemudian harus menanda tangani kesepakatan damai (sulh) dengan orang-orang kafir yang sah sehingga wilayah tempat mereka tinggal dianggap wilayah yang mempunyai kesepakatan damai dengan ummat Islam (dar al-sulh).97 Berdasarkan model relasi non-muslim yang dikembangkan selama abad ke-7 dan 8 ini, syari’ah mengklasifikasikan manusia pada tiga kategori yaitu muslim, ahl al-kitab (mereka yang dianggap ummat Islam sebagai ummat yang juga menerima 95 lihat Lambton, State and Government itun Medieval Islam, hlm. 201; al-Nabhani, The Islamic State, hlm. 147-150 96 Ali, “Role of Muslim Women Today,” dalam Modern Muslim Thought, Vol. 1, hlm. 236; Doi, NonMuslim under shari’ah, hlm. 22-23; Lambton, State and Government in Medieval Islam, hlm. 201. 97 Muhammad Hamidullah, Muslim conduct of state, revised 5th edition (Lahore: Sh. M. Ashraf, 1968); Majid Khadduri, Islamic Law of Nations: Shaybani’s Siyar (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1966), hlm. 158-79; Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1955), hlm. 162-69, 245-46, 243-44; dan H.A. Gibb dan J. H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam (Leiden: E. J. Brill, 1953), s.v. ‘Ahl al-Kitab’, hlm.16-17, ‘Dhimma’, hlm. 75-76, ‘Dizya’, hlm. 91-92, ‘Kafir’, hlm. 205-06, and ‘Shirk’, hlm. 542-44. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im pewahyuan kitab suci seperti Kristen dan Yahudi), dan kafir. Status ahl al-kitab kemudian diperluas oleh para ulama hingga mencakup penganut agama Magi berdasarkan asumsi bahwa mereka juga menerima pewahyuan kitab suci.98 Namun skema dasar yang menyatakan bahwa hanya muslimlah yang berhak menjadi anggota penuh komunitas muslim sedangkan ahl al-kitab hanya anggota parsial tetap tidak bisa dirubah atau dimodifikasi menurut pandangan syari’ah. Orang kafir malah tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pengakuan hukum atau perlindungan seperti itu, kecuali mereka mendapatkan jaminan perlindungan temporer (aman) karena alasan-alasan praktis seperti perniagaan atau diplomat.99 Istilah dhimma merujuk pada perjanjian yang dibuat antara negara yang dipimpin oleh muslim dan komunitas ahl a-kitab agar mereka mendapatkan jaminan keamanan atas diri dan hartanya, kebebasan untuk melakukan kewajiban agamanya dengan otonomi komunal dan privat untuk mengelola urusan-urusan internalnya. Sebagai balasan, komunitas ahl al-kitab harus membayar pajak yang disebut jizyah dan mematuhi perjanjian yang mereka buat dengan negara.100 Mereka yang mendapat status dzimma didorong untuk memeluk Islam, tapi tidak diperbolehkan untuk menyebarkan keyakinannya. Ciri umum perjanjian dhimma biasanya berisi klausul yang melarang ahl-dzimmah untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik atau memegang jabatan yang akan memberinya kesempatan untuk memiliki otoritas atas ummat Islam.101 Namun, isi perjanjian itu bervariasi sesuai dengan waktu dan aplikasinya, pun tidak selalu konsisten dengan teorinya, karena beberapa alasan 98 Muhammad Abu Yusuf, Kitab al-kharaj (Cairo: al-Matba`a al-Salafiyya, 1963), hlm.128-30; Saeed and Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 13. 99 Shorter Encyclopaedia of Islam, ‘Kafir,’ hlm. 206. 100 Article, “Djizya,” Shorter Encyclopaedia of Islam, p. 91; Ali, “Contrast Between Western and Islamic Political Theories,” Modern Muslim Thought, Vol. 1, hlm. 192; Doi, Non-Muslims Under Shari’ah, hlm. 22-23. 101 Doi, Non-Muslims Under the Shari’ah, hlm. 115-116. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im pragmatis seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Namun karena komunitas yang berstatus dzimmah tidak dianggap sama dengan ummat Islam, dalam istilah modern mereka tidak mempunyai status kewarganegaraan penuh. Sementara itu, orang kafir selalu dianggap dalam keadaan perang dengan ummat Islam, kecuali jika mereka mendapatkan perlindungan sementara untuk melakukan perjalanan melewati atau tinggal sementara di daerah yang dikuasai oleh ummat Islam.102 Sedangkan status dan hak mereka yang tinggal di daerah yang memiliki perjanjian damai dengan ummat Islam (dar al-sulh) ditentukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.103 Sistem dzimmi jelas sudah tidak bisa dipertahankan lagi sekarang. Kegagalan Sudan untuk memahami keterbatasan konsep ini, misalnya, berujung pada meledaknya perang sipil di bagian selatan negeri ini.104 jika saja kita menilik lebih hati-hati konteks sejarah konsep ini, jelaslah bahwa ia merefleskikan standar yang berlaku dalam pemerintah dan hubungan antar komunitas saat itu. Konsep ini juga cukup disukai jika dibandingkan sistem lain pada saat itu. Namun, tidak ada sistem hukum internasional lain yang lebih efektif untuk melawan negara-negara Barat yang suka mendominasi negara lain atau menuntut sejumlah pemerintahan yang suka menindas rakyatnya kecuali tata hukum internasional dan perlindungan HAM yang berlaku sekarang. Hukum ini hanya bisa ditegakkan ketika masyarakat memegang teguh nilai-nilai kesetaraan dan tertib 102 Ausaf Ali, “Role of Muslim Women Today,” Modern Muslim Thought, Vol. 1 (Karachi, Pakistan: Royal Book Co., 2000), hlm. 236. 103 Gordon D. Newby, A Concise Encyclopaedia of Islam (Oxford, England: Oneworld Publications, 2002), hlm. 51. 104 Abdullahi Ahmed An-Na`im and Francis Deng, ‘Self -determination and Unity: the Case of Sudan,’ Law and Society, vol. 18 (1997), hlm. 199-223; Francis M. Deng, War of visions (Washington, DC: The Brookings Institution, 1995). ©Abdullahi Ahmed An-Na`im hukum dalam kebijakan dalam dan luar negerinya. Dengan cara inilah, mereka bisa memiliki landasan moral dan politik untuk menuntut hak yang sama dari masyarakat lain. Untuk merealisasikan hal ini, ummat Islam tidak saja harus menghapus sistem dzimmi dalam syari’ah secara formal, namun juga menolak nilainilai diskriminasi yang terdapat di dalamnya hingga mereka bisa menginternalisasi dan mengimplementasikan konsep kewarganegaraan modern yang sudah dijelaskan tadi. Trend ini sudah dimulai pada beberapa komunitas muslim, tugas kita sekarang adalah bagaimana mengembangkan dan mengamankan trend ini dari kemunduran. Dari Konsep Dzimmi menuju Kewarganegaraan Berbasis Hak Asasi Manusia Konsep warga negara berbasis hak asasi manusia berarti bahwa norma substantif, prosedur dan proses status ini, harus lahir dari, atau paling tidak sesuai dengan, standar HAM yang berlaku universal saat ini. Sebagaimana yang sudah kita diskusikan, tujuan utama HAM adalah untuk menjamin adanya perlindungan yang efektif terhadap sejumlah hak-hak dasar manusia dimanapun mereka berada, baik melalui sistem perundangan-undangan negara atau tidak. Piagam HAM internasional tidak mendefinisikan konsep warga negara secara rigid, namun ia berisi beberapa prinsip yang mungkin relevan atau bisa diaplikasikan di sebuah negara. Piagam HAM berisi beberapa prinsip fundamental seperti hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination), persamaan, anti diskriminasi yang disebutkan dalam pasal 1, 2 dan 3 Piagam PBB 1945, yang dianggap sebagai perjanjian yang mengikat semua negara, termasuk negara-negara tempat komunitas muslim tinggal. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat dalam perjanjian HAM lain seperti pasal 1 dan 2 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang disepakati tahun 1966. Dua kovenan tersebut dan ©Abdullahi Ahmed An-Na`im juga perjanjian lainnya menyebutkan Hak Asasi Manusia tertentu, seperti hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum dan kebebasan beragama, berlaku baik bagi negara Islam maupun non-Muslim.105 Realisasi konsep warga negara berbasis HAM di kalangan muslim ini hanya bisa dicapai melalui kombinasi tiga elemen. Pertama, transisi aktual dari konsep dzimmi menuju konsep warga negara dalam era post-kolonial. Kedua, bagaimana menjaga dan mengembangkan transisi ini melalui reformasi Islam yang kuat secara metodologis dan berkelanjutan secara politik agar nilai-nilai HAM berakar kuat dalam doktrin Islam. Ketiga, konsolidasi dua elemen pertama agar konsep ini menjadi diskursus lokal yang mampu menyelesaikan persoalan keterbatasan dan kelemahan konsep ini sekarang dan praktiknya dalam masyarakat Islam. Kombinasi elemen-elemen tadi bisa dilihat dalam pengalaman transisi India dan Turki sebagai Kerajaan Islam terakhir menjadi Negara Modern bermodel Eropa di awal abad 20. Namun sampai hari ini, seperti yang akan saya jelaskan dalam bab 5 dan 6, transformasi konsep warga negara yang terjadi di dua negara tersebut masih ambivalen, bermasalah dan tetap rawan terhadap kemungkinan terjadinya kemunduran. Mari kita lihat proses pengembangan konsep warga negara di India terlebih dahulu. Islam disebarkan di daerah India beberapa dekade setelah Rasulullah meninggal, namun umat Islam membutuhkan waktu berabad-abad untuk menjadi kelompok 105 United Nations, Human rights: a Compilation of International Instruments (New York: United Nations, 1994) volume 1; and Antonio Cassese, Self-determination of Peoples: a Legal Reappraisal (Cambridge: Cambridge University Press, 1995). ©Abdullahi Ahmed An-Na`im minoritas yang berkuasa di beberapa bagian negeri ini.106 Meskipun berasal dari etnis dan kelompok budaya yang berbeda (sebagian dari berasal Turki, Afganistan, Persia, Arab dan juga pribumi yang pindah agama), ummat Islam di India pelanpelan mengembangkan tradisi toleransi dan koeksistensi yang membuat mereka bisa berinteraksi dan berasimilasi dengan komunitas agama lain yang tinggal di sana. Namun tradisi ini baru dalam kerangka menjaga mutualisme simbiosis dengan tuantuan tanah beragama Hindu dan kelompok-kelompok elite lainnya, daripada sebuah tradisi yang mengakui konsep warga negara yang secara luas berlaku bagi seluruh masyarakat.107 Saya mengatakan ini bukan sebagai kritik, saya memahami bahwa konsep warga negara berbasis HAM memang belum diketahui komunitas manapun di dunia saat itu. Sistem kepegawaian dan administrasi negara yang dikembangkan oleh Akbar (15421605) telah memadukan semua kepentingan dan kelompok ke dalam hirarki yang sama. Namun stagnasi teknologi dan administrasi, perang sipil, dan invasi regional, lambat laun menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh kerajaan Mughal selama abad 18.108 Bahkan usaha-usaha untuk menghentikan penjajahan Inggris seperti yang dilakukan Shah Wali Allah (1703-72) dengan memperbaharui konsepkonsep syari’ah atau Gerakan jihadnya Sayyid Ahmad Barelwi (1786-1831), Hajji Shari’at Allah (1781-1840) dan Haji Muhsin (1819-62) pun gagal.109 Dislokasi ekonomi yang disebabkan oleh ekspansi pengaruh perusahaan East India sekaligus perubahan administrasi pendapatan dan peradilan yang diperkenalkan Inggris pada 106 I. H. Qureshi, “Muslim India Before the Mughals,” in The Cambridge History of Islam, P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, and Bernard Lewis (eds.) (New York: Cambridge University Press, 1996), hlm. 334. 107 S.A.A. Rizvi, “The Breakdown of Traditional Society,” in The Cambridge History of Islam, hlm. 67. 108 I.H. Qureshi, “India Under the Mughals,” in The Cambridge History of Islam, hlm. 52-57. 109 Rizvi, “The Breakdown of Traditional Society,” in The Cambridge History of Islam, hlm. 71-74. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im akhir abad 18, menyebabkan menurunnya kekuasaan dan otoritas ummat Islam di India.110 Melalui strategi politik, militer dan ekonomi yang direncanakan untuk meluaskan pengaruhnya di India, kerajaan Inggris akhirnya bisa mengambil alih kontrol pemerintahan di seluruh India pada pertengahan abad 19. Beberapa pemimpin muslim seperti Sayyid Ahmad Khan (1817-98) mempunyai sikap positif terhadap Inggris dan pengaruh Barat secara umum, tapi ia juga masih ambivalen dengan konsep warga negara dan jangkauan penerapannya di India. Ia nampaknya mengkombinasikan komitmen untuk melakukan modernisasi India sebagai negara kesatuan dengan tetap memelihara kecurigaan pada institusi-institusi populer yang demokratis. Usahanya memobilisasi ummat Islam India untuk beroposisi pada Indian National Congress merupakan tanda ambivalensinya terhadap usaha-usaha kemerdekaan, yang berakhir dengan pemisahan India dan Pakistan pada 1947.111 Nampaknya kita tidak mungkin membahas perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut saat ini, tapi saya ingin mencatat bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merefleksikan baik kemarahan Hindu terhadap hegemoni ummat Islam termasuk di dalamnya pada konsep dzimmi, maupun ketakutan Muslim terhadap dominasi Hindu. Ironisnya, meskipun banyak ummat Islam yang masih menjadi warga negera India, pemisahan tersebut tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi konsep warga negara bagi Ummat Islam di Pakistan. Di dua negara tersebut, konsep warga negara harus dikembangkan dan dilindungi dari bahaya pemisahan kategori Muslim dan non-muslim.112 110 Rizvi, “The Breakdown of Traditional Society,” in The Cambridge History of Islam, hlm. 77. Rizvi, “The Breakdown of Traditional Society,” in The Cambridge History of Islam, hlm. 67-96. 112 Aziz Ahmad, “India and Pakistan”, in P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis (eds.), The Cambridge History of Islam, (Cambridge: Cambridge University Press1970), volume 2A, hlm. 97-119. 111 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Pemahaman konsep warga negara berkembang dengan cara yang berbeda pada zaman Dinasti Ottoman dan Republik Turki. Fleksibilitas dan elastisitas sistem Millet dinasti Ottoman di Asia Barat dan Afrika Utara sudah merepresentasikan ketidaktergantungan dinasti ini pada konsep dzimmi sebagai bentuk respon mereka terhadap realitas ekonomis sosial dan militer yang mereka hadapi. Realitas-realitas tersebut mungkin difasilitasi dan terus didukung oleh proses penetrasi Barat dan keterbukaan Ottoman, yang akhirnya mentransformasi kerajaan ini dan membukakan jalan untuk proses transisi menuju terbentuknya Negara Turki sekuler pada tahun 1920. Selain faktor tersebut, ada pula faktor yang tak kalah pentingnya dalam pembentukan negara modern berbasis prinsip kewarganegaraan modern Turki, yaitu kemunculan gerakan-gerakan nasionalis di kalangan ummat muslim, yang berasal dari Arab dan Albania misalnya, dan juga kehadiran minoritas Kristen. Meskipun dilakukan perlahan dan bertahap, perubahan kebijakan dan praktik dinasti Ottoman dimulai pada saat dideklarasikannya Keputusan Tanzimat tahun 1839, yang menandai dimulainya proses formal pengakuan kesamaan status antara muslim dan non-muslim di hadapan sultan.113 Sementara keputusan Tanzimat pertama menegaskan syari’ah sebagai hukum negara, keputusan Tanzimat tahun 1856 justru menetapkan kesamaan status non-muslim, penghapusan jizyah, pelarangan sikap diskriminatif terhadap komunitas ahl al-dzimmah tanpa merujuk sedikitpun pada prinsip-prinsip Islam. Malah, aspek-aspek modern prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan anti-diskriminasi ditetapkan dalam pasal 8 - 22 konstitusi Ottoman tahun 1876. Prinsip-prinsip tersebut terus dijaga melalui 113 Cevdet Küçük, “Ottoman Millet System and Tanzimat”, in Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, vol. 4, (Istanbul: İletişim, 1986), hlm. 1007-24. ©Abdullahi Ahmed An-Na`im pengembangan konstitusi selama akhir masa dinasti Ottoman dan kemudian diperluas selama masa Republik sejak 1926. Proses yang terjadi di India dan Turki, juga terjadi di negara muslim lain selama abad ke-20 dan secara formal terus berkembang selama proses dekolonisasi pasca perang dunia II. Dengan demikian, konsep dzimmi tidak lagi dipraktikkan dan dianjurkan di negara muslim manapun yang telah mengintegrasikan diri dengan sistem negara yang berlaku sekarang.114 Walaupun transformasi tersebut secara formal dilaksanakan oleh kolonial Eropa, namun semua masyarakat Islam telah secara sukarela meneruskan sistem tersebut setelah mereka merdeka. Ummat Islam bahkan tidak menolak atau berusaha untuk memodifikasi sistem tersebut baik di tingkat lokal maupun internasional, malah penguasa di negara-negara Muslim justru aktif berpartisipasi untuk mengoperasikan sistem ini di dalam maupun luar negaranya.115 Namun ketegangan yang ditimbulkan oleh konsep dzimmi dan nilainilai yang terkandung di dalamnya masih tetap saja ada, seperti yang terjadi dalam kasus kontroversi mengenai kebolehan mengucapkan selamat Natal kepada ummat kristiani atau nikah antar agama di Indonesia116, perang sipil di Sudan117, kerusuhan bernuansa kekerasaan akibat penerapan syari’ah di negara-negara bagian Nigeria sejak tahun 2001.118 Ketegangan inilah yang menjadikan pentingnya peralihan ke konsep warga negara melalui reformasi Islami yang kuat secara metodologis dan berkelanjutan secara politis. 114 Saeed and Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, hlm. 13-14. James Piscatori, Islam in a World of Nation-states. 116 Darul Aqsha, Islam in Indonesia: a survey of events and developments from 1998 to March 1993 (Jakarta: INIS, 1995), hlm. 470-73; Greg Barton, Gagasan Islam Liberal (Jakarta: Paramadina,1999); and Mun’im A. Sirry, Fiqh Lintas Agama: membangun masyarakat inklusif-pluralis (Jakarta: Paramadina, 2004). 117 Jok Madut Jok, War and Slavery in Sudan (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001). 118 Simeon O. Ilesanmi, “Constitutional Treatment of Religion and the Politics of Human Rights in Nigeria”, African Affairs (2001), hlm. 529-54. 115 ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Sekedar mengulang diskusi yang telah lalu, premis utama pentingnya proses reformasi Islami adalah meskipun Qur’an dan Sunnah adalah sumber ketuhanan dalam Islam, tidak berarti bahwa makna dan implementasi keduanya dalam kehidupan sehari-hari lepas dari interpretasi dan perilaku manusia dalam konteks sejarahnya yang spesifik. Bahkan, rasanya tidak mungkin kita mengetahui dan menerapkan syari’ah dalam kehidupan ini tanpa adanya faktor manusia, karena Qur’an sendiri diungkapkan dalam Bahasa Arab (bahasa manusia) dan terkait dengan pengalaman sejarah masyarakat tertentu saat itu. Pendapat apapun yang diterima muslim sebagai bagian dari syari’ah sekarang atau kapanpun, bahkan jikapun disepakati secara anonim, pasti muncul sebagai pendapat manusia mengenai makna al-Qur’an dan sunnah atau merupakan praktik komunitas Islam. Pendapat dan praktik tersebut menjadi bagian dari Syari’ah melalui konsensus ummat Islam berabad-abad lamanya, dan bukan hasil dari keputusan spontan seorang penguasa atau kehendak sekelompok ulama. Dengan demikian, di samping pendapat yang telah disepakati, tentu ada alternatif formulasi syari’ah lain yang sama validnya dan bisa diterima oleh ummat Islam. Selain itu, reformasi yang berbasis metodologi yang kuat juga harus memperhatikan dua hal penting yang sudah disebutkan pada permulaan bab ini. Pertama, usaha reformasi harus bisa membedakan dua hal penting yaitu prinsip-prinsip syari’ah yang sudah ada dan telah ditetapkan oleh para ulama dengan kemungkinan reinterpretasi. Kedua, seseorang yang ingin melakukan reformasi harus menghindari memilih teks Qur’an dan sunnah yang nampaknya saling bertentangan secara arbitrer, tanpa memperhatikan teks-teks yang menguatkan pendapat oposisi. mempunyai kemungkinan dirujuk untuk ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Metodologi reformasi yang berdasarkan premis diatas dan memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan nampaknya adalah metodologi yang diajukan Ustadz Mahmud Muhammed Toha. Metodologinya mendukung adanya peralihan dari penggunaan ayat-ayat Madaniyah ke ayat-ayat Makiyah sebagai dasar bagi aspek sosial dan politik syari’ah. Alasan pentingnya peralihan ini adalah karena ayat-ayat yang diturunkan pada masa awal pewahyuan lebih merepresentasikan pesan-pesan universal Islam, sedangkan ayat-ayat sesudahnya lebih merupakan respon spesifik terhadap konteks historis ummat manusia saat itu. Melalui metodologi ini, Ustaz Mahmud juga menunjukkan bahwa alasan yang digunakan dalam sistem dzimmi untuk melegitimasi konsep jihad yang agresif dan diskriminasi terhadap non- muslim berupa ayat-ayat madinah itu, sifatnya temporer. Point utama dalam perbincangannya adalah Islam disebarkan pertama kali melalui cara-cara damai dengan menggunakan pesan-pesan universal yang diturunkan dalam periode Mekkah. Namun, setelah pesan-pesan tersebut tampak tidak realistis bagi konteks negeri Arab abad ke-7, maka pesan-pesan yang lebih cocok secara historis pun diturunkan di Madinah termasuk konsep jihad yang agresif dan diskriminasi terhadap non-muslim itu. Dengan demikian, pesan Madinah yang turun belakangan justru lebih dulu diterapkan sebagai Syari’ah sejak abad ke-7. Dengan memahami bahwa kondisi saat ini sudah mungkin untuk mengimplementasikan pesan-pesan dakwah damai dan non diskriminatif yang datang lebih dulu, Ustadz Mahmoud menyerukan pentingnya peralihan ini melalui konsep dan metodologi ijtihad yang baru. Dengan cara seperti ini, Metodologi Taha ini mampu secara eksplisit mengenyampingkan ayat-ayat yang mendasari konsep dzimmi sebagai bagian dari syari’ah, walaupun mereka tetap menjadi bagian dari al-Qur’an. Karena proses ©Abdullahi Ahmed An-Na`im pemilihan ayat-ayat al-Qur’an yang sesuai atau tidak, selalu menjadi tugas para fuqaha, maka jika pilihan-pilihan dulu diganti dengan yang baru maka hendaknya itu difahami sebagai sebuah revisi terhadap apa yang pernah dilakukan ummat Islam di masa lalu, bukan revisi terhadap al-Qur’an atau sunnah itu sendiri. Kerangka yang ditawarkan Taha mampu menyediakan metodologi interpretasi Qur’an dan Sunnah yang sistematis dan koheren, daripada sekedar sebuah proses pemilihan serampangan terhadap sejumlah ayat al-Qur’an seperti yang dilakukan oleh ulama modern lain yang ternyata gagal untuk menjelaskan apa yang terjadi pada ayat-ayat yang tidak mereka pilih. Dengan metodologi Taha, beberapa ayat relevan yang turun pada periode Makkah dapat mendukung pengembangan konsep warga negara modern dari sudut pandang Islam.119 Meskipun saya menganggap pendekatan Taha ini sangat meyakinkan, saya tetap membuka diri pada metodologi lain yang bisa mencapai tingkat reformasi yang sama dengan metodologi Taha. Tapi bagaimana caranya kita menetapkan bahwa metodologi ini atau itu kuat dan bisa diaplikasikan dalam perspektif Islam, layak dipilih untuk digunakan menghapus sistem dzimmi tradisional? Pertama, alasan yang sudah saya tekankah sejak semula, Aturan Emas (Golden Rule) atau doktrin Islam tentang resiprositas bahwa seorang muslim harus mengakui kesetaraan derajat orang lain jika mereka ingin diberi pengakuan yang sama. Kedua, adalah sebuah kemunafikan jika kita tetap memegang sistem dzimmi secara teoritis, padahal kita menyadari bahwa konsep itu tidak pernah diterapkan di masa lalu dan juga tidak relevan untuk diterapkan di masa yang akan datang. Dengan tetap mempertahankan interpretasi yang tidak realistis terhadap syariah yang seperti itu dalam tingkat teoritis, sambil mengabaikannya dalam tingkat praktis, justru akan merusak kredibilitas dan 119 Taha, the Second message of Islam; and An-Na`im, Toward an Islamic Reformation ©Abdullahi Ahmed An-Na`im koherensi Islam sebagai agama. jika ada orang yang khawatir bahwa konsep ini sulit diterima oleh kalangan muslim, saya hanya akan meminta kesempatan untuk mempresentasikan ini secara bebas dan terbuka kepada mereka, agar mereka bisa menentukan sendiri keputusannya. Agar debat publik yang bebas dan terbuka tentang masalah-masalah seperti ini bisa terjadi, maka penting bagi masyarakat muslim untuk menjaga penuh kebebasan mereka untuk berpendapat, berekspresi dan memiliki keyakinan tertentu. Manusia tidak bertanggung jawab atas keputusan atau perbuatan yang dilakukannya, jika ia tidak memiliki kebebasan untuk memilih, dan kebebasan memilih itu tidak bisa didapatkan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang relevan, agar ia bisa mendebat dan menilai argumen yang berbeda. Karena itulah, mengapa saya selalu menekankan pentingnya peran konstitusionalisme dan hak asasi manusia sebagai kerangka fikir dan jaring pengaman yang berguna untuk menegosisasikan hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat dalam konteks masyarakat Islam saat ini. Kesemuanya itu menuntut adanya otoritas publik yang bisa menjaga tatanan dan hukum, mengatur debat dan refleksi, dan memutus pertikaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan masuk akal. Keberadaan otoritas itu diimplementasikan dengan kehadiran institusi-institusi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, mengamankan pemerintahan yang konstitusional dan perlindungan HAM tidak saja penting bagi kebebasan beragama ummat Islam dan non-muslim yang hidup di sebuah negara, tetapi juga untuk ketahanan dan pengembangan Islam itu sendiri. Kebebasan untuk memiliki pendapat yang berbeda dan berdebat selalu esensial untuk pengembangan syari’ah, karena itu memungkinkan munculnya ide-ide baru, yang bila diterima, akan menjadi sebagai konsensus yang berkembang di sekeliling mereka, sampai ide-ide ©Abdullahi Ahmed An-Na`im itu matang dan menjadi prinsip-prinsip yang mapan melalui penerimaan dan praktik beberapa generasi ummat Islam di berbagai tempat dan waktu. Daripada melakukan sensor terhadap pemikiran-pemikiran baru yang justru sebetulnya kontra-poduktif untuk pengembangan doktrin-doktrin Islam, adalah lebih penting untuk menjaga berlangsungnya kemungkinan munculnya inovasi dan perbedaan pendapat karena itulah cara agama merespon kebutuhan penganutnya. Kesimpulan Sepanjang buku ini saya sudah menekankan pentingnya perspektif Islam untuk menjaga netralitas negara terhadap agama di samping pentingnya menjaga keterhubungan antara Islam dan politik di sisi lain. Namun masih ada ketegangan yang belum terselesaikan menyangkut konsep-konsep seperti konstitusionalisme, HAM, dan warga negara dalam perspektif Islam, statusnya yang diformulasikan di tengah masyarakat Barat dan aplikasinya di tengah masyarakat Islam Asia dan Afrika. Bisakah konsep-konsep yang berkembang melalui pengalaman masyarakat Barat diaplikasikan di tempat lain? Jawabannya ya. Saya percaya penerapan itu bukan saja mungkin, tetapi juga penting dengan menyediakan ide-ide, asumsiasumsi, dan institusi-institusi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut agar bisa diadaptasikan secara lebih baik dengan konteks lokal dan masyarakat yang berbeda. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di tengah masyarakat muslim menjadi penting karena mereka terus hidup dalam model negara Eropa setelah merdeka dari penjajahan. Model Negara Eropa ini nampaknya akan terus berlanjut sebagai kerangka dominan politik domestik dan hubungan internasional di masa yang akan datang. Bahkan trend globalisasi dan integrasi regional seperti Uni-Eropa, Uni- ©Abdullahi Ahmed An-Na`im Afrika yang beroperasi melalui peran negara sering menghadapi resistensi yang kuat dari pendukung konsep tradisional kedaulatan nasional atau teritorial. Realitasrealitas tersebut menuntut implementasi prinsip-prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan yang ternyata penting untuk mengatur kekuasaan negara dan mengorganisasi relasi antara individu dan komunitas di bawah model negara Eropa ini. Dengan demikian, pentinglah kiranya untuk mengembangkan prinsip-prinsip tersebut dalam masyarakat muslim sebagai parameter yang mengatur politik domestik dan hubungan mereka dengan masyarakat lain. Walaupun jelas dalam level teoritis, konsep seperti konstitusionalisme, HAM, dan kewarganegaraan masih perlu dispesifikasi dan diadaptasikan bila ingin diaplikasikan dalam konteks lokal. Agar relevan dan berguna, prinsip-prinsip teoritis tersebut harus bisa menjawab pertanyaan dan masalah yang muncul dari konteks sosio-ekonomi, politik dan tradisi budaya masing-masing masyarakat. Logis jika kemudian proses adaptasi prinsip universal dalam konteks lokal ini mungkin saja tidak bekerja di tempat atau waktu tertentu. Kegagalan proses ini mungkin terjadi dalam berbagai bentuk, baik pada level minor menyangkut susunan praktis seperti pemisahan kekuasaan atau judicial review, sampai pada ketidakcocokkan mengenai aspek-aspek fundamental atau substansiaal dalam konsep konstitusionalisme. Kegagalan ini bisa memiliki tingkat kesulitan yang beragam. Dengan demikian, saya merekomendasikan agar kita lebih memfokuskan diri pada dinamika dan proses internal untuk membangun dan mengkonsolidasikan konstitusionalisme, HAM dan kewarganegaraan di tengah masyarakat muslim dengan menggunakan istilah mereka sendiri dan bukan menyebutnya sebagai ©Abdullahi Ahmed An-Na`im pemaksaan Barat. Kegagalan atau kemunduran yang kita lihat dalam masyarakat Islam saat ini, merupakan sebuah kepastian dari proses evolusi dan pemapanan konsep-konsep tersebut, sekaligus dasar bagi kesuksesan di masa yang akan datang. Saya mengajukan pendekatan berbasis proses dan praktik yang memungkinkan kita untuk sampai pada analisis yang lebih dalam dan kaya. Pendekatan ini mengharuskan seseorang untuk mempertimbangkan dinamika sosial, budaya dan politik yang komplek dimana aktor-aktor negara dan non-negara, individu dan komunitas, kelompok-kelompok etnis, sosial dan agama memahami dan menghubungkan diri mereka dengan konsep-konsep dan implementasi konsepkonsep tersebut. Daripada melihat kegagalan yang tampak sebagai indikasi adanya cacat inheren dalam masyarakat, seseorang seharusnya mempertimbangkan adanya kemungkinan kelemahan dalam konsep itu sendiri atau kelemahan pada tingkat adaptasinya di masyarakat tertentu. Alangkah sombong dan picik, jika kita mengasumsikan bahwa kegagalan menerapkan konsep atau kerangka yang sudah definitif itu, terjadi karena ada hal yang salah dengan faktanya. Sebagaimana sudah saya tekankan di bagian awal bab ini, relevansi penerapan prinsip ini dalam masyarakat Islam adalah karena peran penting yang diembannya sebagai kerangka untuk menegosiasikan hubungan antara Islam dan negara, di satu pihak, dengan Islam dan politik di sisi lain. Review terhadap ciri-ciri negara modern di bagian awal bab ini menjadi relevan karena model negara tersebut masih terus dipraktikkan di negara-negara yang berpenduduk mayoritas atau minoritas muslim. Kemudian saya memperjelas pembedaan antara politik dan negara untuk mendukung ide saya untuk memisahkan Islam dari negara sambil tetap memelihara hubungan antara Islam dan politik. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab I, pemisahan antara negara dan Islam tidak berarti bahwa Islam menurunkan Islam ke ©Abdullahi Ahmed An-Na`im level privat karena prinsip-prinsip Islam sebetulnya masih bisa diajukan untuk diadopsi oleh negara menjadi kebijakan atau undang-undang negara. Namun pengajuan ini harus didukung oleh “public reason” yang berarti bahwa berbagai argumen bisa diperdebatkan oleh semua warga negara tanpa harus merujuk pada keyakinan agama. Namun praktik “public reason” ini membutuhkan jaring pengaman berupa prinsip-prinsip konstitusionalisme, HAM, dan kewarganegaraan yang sudah didiskusikan dalam bab ini. Bab berikutnya akan membahas pengalaman sekularisme negara-negara Barat, dan ini diharapkan akan memperjelas beberapa elemen dalam proposal saya.