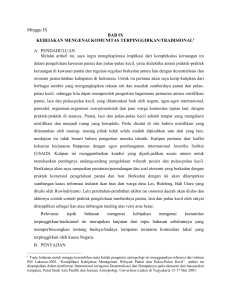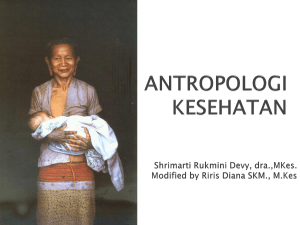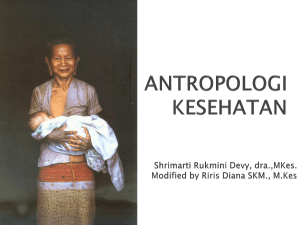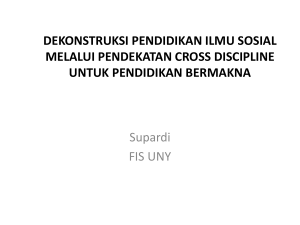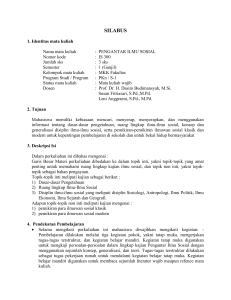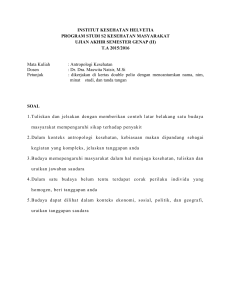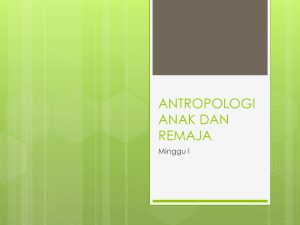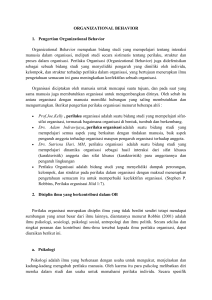Minggu VI BAB VI APRESIASI HIDUP KOMUNITAS DAN BUDAYA
advertisement

Minggu VI BAB VI APRESIASI HIDUP KOMUNITAS DAN BUDAYA1 A. PENDAHULUAN Barangkali khas ilmu antropologi, mungkin juga umumnya ilmu humaniora, paradigma ilmu ini terus bergeser dan simpang siur. Barangkali satu-satunya yang cukup luas disepakati adalah proses pengembangan pengetahuannya saja, yaitu melalui kerja lapangan yang panjang, hidup dengan orang lain, untuk memahami masyarakat dan budaya lain. Antropologi memiliki obsesi memahami lian yaitu orang yang berbeda dari dirinya sendiri untuk mengenali dirinya sendiri secara lebih tajam. Mengenai siapa lian dan apa itu kebudayaan, nyaris setiap antropologi memiliki pengertian sendiri. Prof. Koentjaraningrat (alm.), sang guru besar antropologi Indonesia, misalnya menggunakan konsep kebudayaan yang “meliputi” keseluruhan sistem nilai dan gagasan, sistem tingkah laku dan hasil tingkah laku manusia. Berdasar konsep itulah beliau “memetakan” manusia dan kebudayaan di Indonesia dalam sistem file etnografis mirip kumpulan etnografi GP Murdock dalam Human Relations Area Files (HRAF). Lebih dari itu beliau telah mencoba dengan rinci merujukkan pembangunan dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Kemudian ada Clifford Geertz yang secara sederhana dapat kita pahami sebagai jejaring makna yang dirajut sendiri oleh manusia, sehingga bersifat publik. Dalam karier Geertz, lian itu adalah orang Jawa, Bali, dan Marokko. Secara lebih sederhana lagi saya sering menerangkan kepada para mahasiswa, bahwa kebudayaan itu adalah semua saja yang kita tahu sama tahu (TST). Jadi belajar antropologi itu seperti latihan mata untuk melihat apa yang tidak nampak (dalam diri sendiri) dari penampakan orang lain (etnik). Tentu aktualisasi kebudayaan dalam hidup sehari-hari amat sangat beraneka ragam dan luas sekali bidangnya, serta tidak dapat direduksi hanya ke dalam sistem nilai. Dalam hidup sehari-hari orang beradu siasat untuk mencapai kepentingannya. Oleh karena itu dalam antropologi pun ada banyak sekali pengkhususan. Sudah jamak pula di kalangan antropologi, para antropolog itu berwacana dengan membuka pengalaman etnografisnya dalam masyarakat tertentu yang terkadang tidak seorangpun pernah mendengarnya. Karya antropologi tentu saja kemudian bermuatan politik. 1 Topic bahasan untuk minggu keenam mata kuliah pengantar antropologi ini mengambil referensi dari tulisan PM. Laksono. Rujukan Lembaga-lembaga Demokrasi Dalam Ranah Komunitas Lokal. Kini para antropolog biasanya setuju bahwa obyek dan subyek yang dipelajarinya terus bergeser, sementara pengalaman pribadi para penelitinya atau orang yang mempelajarinya juga terus bergeser sesuai dengan posisi historisnya. Oleh karena itu saya menyarankan untuk menempatkan hasil kerja antropologi, yaitu etnografi, sebagai pengetahuan reflektif dan apresiatif, yaitu pada penemuan eksistensi manusia sendiri. Oleh karena itu pengetahuan etnografik itu bermuatan unsur apresiasi, empati afektif dan kognitif sesuai dengan pengalaman hidup. Beretnografi itu seperti usaha untuk merekonstruksikan gadjah yang tidak nampak dari jejak kaki yang ditinggalkan dalam pikiran kita. Antropologi pertama-tama harus bersejarah karena berurusan dengan pengalaman hidup yang bergerak ke depan dan pemahaman ke belakang atas pengalaman itu. Selanjutnya antropologi berurusan dengan kritik pasca positifistik atas realisme empirik, yang menghindari teori-teori korespondensi sederhana dari kebenaran dan pengetahuan yang menyebabkan “fakta” menjadi urusan yang rentan (Geertz 1995: 167-168) Jika penampakan (fakta komunitas lokal/etnik) lian itu begitu rentan, lalu apa yang dapat dibicarakan dan dilakukan untuk merujukkan lembaga-lembaga demokrasi dengan fakta itu? B. PENYAJIAN Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia terbagi-bagi dalam begitu banyak sukubangsa dengan sejarah yang beraneka ragam. Ada masyarakat petani yang bertradisi kerajaan yang feodalistik dan kompleks serta ada masyarakat-masyarakat kesukuan yang masih mengembara di hutan-hutan. Kemudian di kota-kota banyak orang hidup di kampung-kampung marginal dengan kepadatan sosial dan spasial yang sangat tinggi tanpa layanan sosial dasar yang memadai. Dimana-mana kita temukan komunitas tempatan yang kehilangan aksesnya terhadap sumber-sumber hidup (tanah, hutan, air, dll). Saya sependapat, bahwa masyarakat tempatan adalah komunitas yang bukan saja sangat banyak jumlahnya tetapi sangat dinamis dan selalu berubah, bahkan juga tidak selalu terisolir. Dinamik itu merupakan bagian dari hidup masyarakat setempat yang telah melampaui masa yang panjang dengan perspektif yang tidak selalu tempatan. Di sini kita harus memahami budaya masyarakat setempat pun pernah mengalami kontak dengan dunia luar, namun dalam proses itu “warna” tempatan kuat bertahan karena masyarakat terutama para elitenya berhasil mengidentifikasikan dirinya dalam proses itu. Mereka bahkan mampu mengapropriasi atau mengambil alih budi bahasa “asing” justru untuk melestarikan ketidak setaraan sosial tradisionalnya daripada ikut tersamaratakan oleh gelombang pengaruh budi bahasa dan gaya hidup baru (Kaartinen 2000; Twikromo 2008). Akibatnya perubahan sosial selalu tertunda. Seiring dengan proses itu terjadi degradasi peningkatan sumber-sumber ekonomi setempat akibat eksploitasi yang berlebihan. Degradasi sumber-sumber setempat itu celakanya selalu diiringi peningkatan konsumerisme yang digerakkan oleh pesona mode di sector konsumtif dan bermuara pada krisis identitas dan disintegrasi sosial. Banyak orang saya lihat justru menjadi sangat positifistik padahal sumber-sumber tempatan kita itu terbatas dan terkait dengan tradisi sehingga tidak mungkin memuaskan pikiran macam itu. Terjadilah kemudian kompetisi tidak seimbang antara operasi para pemodal dan masyarakat tempatan misalnya pemegang HPH dan masyarakat setempat dalam pembalakan hutan. Kompetisi ini biasanya bermuara dalam konflik yang merumit menuju konflik horizontal yang tentu saja melumatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pasar (bebas) yang menjadi model impian ekonomi para pemilik modal. Pengaruh agama-agama universalis (Islam, Hindu, Budha dan Kristen) serta kolonialisme yang bervariasi kemudian juga investasi dan eksploitasi modal global di berbagai daerah telah menciptakan bukan hanya sekadar perbedaan tampilan konfigurasi antar masyarakat, tetapi di sana-sini juga telah menghasilkan jarak dan hirarki antar komunitas yang berbeda-beda. Menurut pola hubungan antara agama dan Negara saja, Abdulrahman Wahid (1996) misalnya menunjukkan paling tidak ada empat pola. Pertama pola Aceh dimana hukum agama adalah hukum Negara. Kedua adalah pola Minangkabau yang memberi tempat bagi artikulasi pendapat dan individuasi sentral. Ketiga adalah model Goa/Malaka/Malaysia dimana agama dipakai sebagai pembenar dari kesepakatan yang bertahap karena ada pencampur adukan Islam dengan budaya/tradisi setempat. Pola keempat adalah model Jawa dimana Islam tidak pernah diterima secara total oleh pusat kekuasaan. Di sini keraton tidak ikut campur dalam urusan agama. Pelaku feodalisme bukan hanya dari lingkaran keraton tetapi juga ada pseudo feodal dari kalangan agamawan. Di luar keempat pola itu masih akan banyak lagi ditemui konfigurasi sosial budaya lain yang berbeda-beda, sebagian lebih demokratis dan terbuka dibanding yang lainnya. Tugas: Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan membuat pertanyaan kritis atas pembacaannya serta terlibat aktif dalam diskusi di kelas. C. PENUTUP Tes formatif dan kunci tes formatif: mahasiswa diminta untuk membaca setiap materi sesuai topik bahasan setiap minggunya dan membuat pertanyaan kritis dari hasil membaca materi tersebut dan memberikan contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Petunjuk penilaian dan umpan balik: Kriteria pertanyaan bernilai A: pertanyaan kritis yang merupakan hasil dari review materi serta memiliki bobot untuk berpikir secara reflektif terkait dengan isu sosial. Kriteria pertanyaan bernilai B: pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan di dalam materi. Kriteria pertanyaan bernilai C: hanya menyuguhkan review tanpa membuat pertanyaan kritis. Tindak lanjut: akumulasi nilai