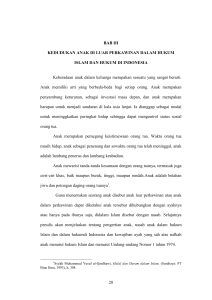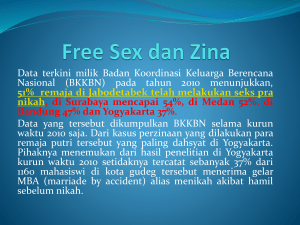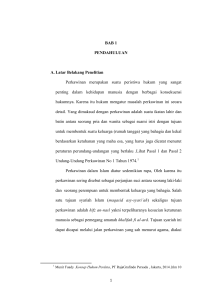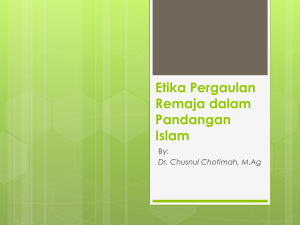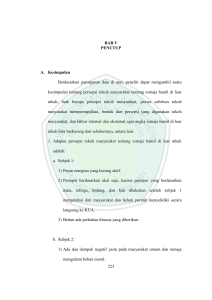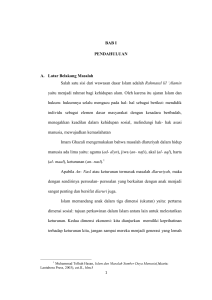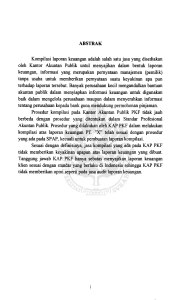nasab anak di luar perkawinan paska putusan mahkamah konstitusi
advertisement

NASAB ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-IIIV/2010 TANGGAL 27 PEBRUARI 2012 MENURUT TEORI FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh DRS. H, SYAMSUL ANWAR, SH, MH1 DRS. ISAK MUNAWAR, MH2 I PENDAHULUAN. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 lahir karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri 3 menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari’at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-Undung Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka Hj. Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal Ramdhan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah.4 Dan berakibat hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah serta status Muhammad Iqbal Ramdhan sebagai anak Moerdiono5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ayat (2)-nya menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat 1 Ketua pada Pengadilan Agama Kelas I A Majalengka. Hakim pada Pengadilan Agama Kelas I A Majalengka. 3 A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-IIIV/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tangal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon) halaman 1 2 4 Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 halaman 5 Putusan MK ibid halaman 6 4-5 2 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Perkawinan menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. UndangUndang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu ; pertama dari prespektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsif negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi 6 . Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum 6 Putusan MK ibid halaman 33-34 3 membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Kemudian Mahkama Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 19457. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan Mahkama Konstitusi tersebut adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materil undang-undang, yang dalam hal ini Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik8, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat ((3) jo Pasal 57 ayat (1) UUMK. Dan oleh karena itu pula putusan MK ini menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tentang hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuannya beserta segala konsekwensinya, baik anak itu adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan (anak zina), dan setelah anak itu lahir kedua orang perempuan dan laki-laki ini tidak pernah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang sah maupun setelah anak tersebut lahir kemudian kedua orang perempuan dan laki-laki itu mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang sah (anak di luar perkawinan), atau anak tersebut lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang tidak memiliki kepastian dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena peristiwa perkawinannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan). Putusan Mahakamah Konstitusi tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Pebruari Tahun 2012 sesuai Pasal 47 UUMK dan dengan terbitnya 7 8 Putusan MK halaman 35-36 A. Mukti Arto, ibid halaman 12-13 4 putusan MK ini, maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 KHI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.9 II PEMBAHASAN Poligami di bawah tangan dan konsekwensi hukumnya. Apabila dicermati kasus posisi tersebut bahwa almarhum Moerdiono selama hidupnya telah melakukan poligami di bawah tangan dengan istri keduanya bernama Hj. Aisyah dan dari istri keduanya itu dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, setelah Moerdiono meninggal dunia anak dari istri keduanya ini berkeinginan melegalisasikan statusnya sebagai bagian dari keluarga almarhum Moerdiono 10 , akan tetapi terjegal oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi persoalan dalam kasus ini sebenarnya adalah bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari poligami di bawah tangan ? hal mana persoalan ini tidak secara langsung berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagaimana yang ditunjuk Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu. Poligami di bawah tangan yang dilakukan Moerdiono dan istrinya tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karena itu pula tidak akan pernah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ketentuan yang bersifat perintah secara imperatif (wajib) terhadap suami yang akan berpoligami untuk memperoleh izin dari pengadilan, sedangkan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan syaratsyarat poligami yang harus dipenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Perkawinan yang melanggar ketentuan ini adalah termasuk perkawinan yang tidak dapat dilakukan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Status perkawinan poligami tersebut menurut Hukum Islam yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun terdapat larangan hukum sesuai Pasal 9 UUP tersebut kecuali diizinkan oleh pengadilan, akan tetapi apabila perkawinan itu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu” hal mana hukum agama bagi orangorang Islam Indonesia adalah Hukum Islam yang dimuat pada Pasal 14 KHI tentang 9 A. Mukti Arto, ibid halaman 22 Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 10 5 rukun-rukun materil perkawinan dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan syaratsyarat yang harus dipenuhi, serta tidak ada larangan syara’ untuk melakukan perkawinan haruslah dianggap sah menurut hukum. Hukum hanya memandang perwakinan poligami seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Artinya perkawinan poligami ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, maka konsekwensi dari perkawinan tersebut apabila tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan ini atau tidak ada hal lain yang membutuhkan bukti hukum tentang adanya perkawinan maka kehidupan sebagai suami istri dapat tetap berlangsung walaupun status perkawinannya tidak dapat dilindungi oleh negara, dan konsekwensi lain dari perkawinan poligami di bawah tangan ini adalah tentang status anak yang dilahirkannya. Dalam memecahkan masalah ini dapat diperhatikan ketentuan tentang pembatalan perkawinan. Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “barang siapa karena perkawinanya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UndangUndang ini. Demikian pula ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama” Apabila permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat dibuktikan secara hukum di hadapan sidang pengadilan, kemudian pengadilan menjatuhkan putusan dengan amar membatalkan perkawinannya, maka putusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang senada dengan ketentuan Pasal 75 huruf (b) KHI tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya walaupun ikatan perkawinannya telah dinyatakan batal secara hukum tetapi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak secara serta merta menghapuskan hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Apabila pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan, karena tidak ada bukti tertulis tentang peristiwa perkawinannya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada bukti akta nikah, maka konsekwensi terhadap anak-anak yang dilahirkannya juga merupakan anak-anak yang memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuannya itu, selama tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau tidak ada hal lain yang memerlukan bukti hukum yang menunjukan status anak tersebut. Persoalan krusial akan muncul ketika ada pihak yang keberatan terhadap status anak tersebut, maka dalam hal ini memerlukan pembuktian secara formal yaitu akta kelahiran, dan apabila akta kelahiran tersebut menyebutkan hubungan nasab anak terhadap kedua orang tuanya maka syarat pokok dari akta tersebut adalah adanya Buku Kutipan Akta Nikah kedua orang tuanya, dan seandainya akta kelahiran anak itu tidak dapat diterbitkan maka status hukumnya 6 adalah adanya anak itu sama saja dengan tidak ada secara hukum, sehingga anak itu nasabnya tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya. Sesuai pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pencatatan kelahiran berasaskan peristiwa kelahiran yang apabila orang tua anak tersebut tidak dapat menyerahkan bukti perkawinannya, maka secara otomatis akan tertulis pada akta kelahiran anak dari seorang ibu saja11 dan dalam hal inilah titik singgung antara konsekwensi anak yang dilahirkan dari poligami di bawah tangan dengan konsekwensi anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dimana kedua peristiwa itu memiliki substansi yang berbeda akan tetapi berakibat hukum yang sama. Persoalan perkawinan poligami di bawah tangan kualitas permasalahannya lebih rumit dari pada perkawinan monogami di bawah tangan, sebab perkawinan monogami di bawah tangan bagi masyarakat Islam statusnya dapat memiliki kepastian dan kekuatan hukum setelah mendapatkan isbat dari pengadilan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Kebolehan isbat nikah pada ketentuan ini dibatasi ayat (3) huruf (e) yang menyatakan “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Halangan dimaksud adalah larangan kawin sesuai Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang tidak dapat dilakukan sesuai Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu berkaitan dengan poligami tanpa izin pengadilan. Mengenai pencatatan poligami seperti ini juga di larang oleh undangundang sebagaima Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43” Oleh karena itu perkawinan poligami di bawah tangan menurut undang-undang adalah perkawinan yang melanggar prosudur undang-undang dan keberadaannya tidak dapat dilakukan toleransi. Walaupun demikian ketatnya aturan yang mengatur perkawinan poligami di bawah tangan dan perkawinan monogami di bawah tangan, akan tetapi izin pengadilan dan pencatatan perkawinan substansinya berkaitan dengan prosudur dan administrasi tentang perkawinan. Dengan pelanggaran terhadap prosudur dan administrasi ini undang-undang tersebut tidak menyatakan berakibat substansi perkawinannya menjadi tidak sah, dan demikian pula akibat hukum terhadap anak yang dilahirkannya tidak dapat dikatagorikan sebagai anak tidak sah atau anak di luar perkawinan. Oleh karena itu pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan 11 Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 7 dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Buktibukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu. Solusi ini juga sebenarnya mengandung konsekwensi apabila seorang anak dinyatakan sebagai anak sah dari hasil perkawinan poligami di bawah tangan tersebut, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, akan berakibat secara tersirat pengadilan telah mengakui adanya perkawinan yang menurut undang-undang terdapat halangan. Dari gambaran tersebut menunjukan bahwa setiap peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi prosudur hukum yang berlaku baik yang berkaitan dengan materi hukum maupun yang berkaitan dengan legalitas formal adalah akan menimbulkan persoalan yang krusial dan seolah-olah lahirnya keturunan sebagai akibat perkawinan tersebut bila tidak dilindungi oleh hukum maka prosudur hukum itu yang disalahkan. Peristiwa perkawinan yang mumpuni dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum selain harus memenuhi rukun syar’iy juga harus memenuhi rukun tautsiqy. Satria Effendi (Allah yarham)12 mencatat fatwa Syekhul Azhar (Guru Besar) yang pada waktu itu dijabat oleh DR. Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq, fatwa tersebut menyatakan bahwa al-jiwaz al-‘urf adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syakh Jaad al-haq mengklasifikasikan ketentuan pernikahan kepada dua katagori, yaitu rukun syar’iy dan rukun yang bersifat al-tawstiqi. Rukun syar’iy adalah rukun yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Rukun ini adalah rukun yang ditetapkan Syari’at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam Kitab-kitab Fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majles yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara’ serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti 12 Prof. DR. H. Satria Effendi M.Zein, MA, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer,(Jakarta: Prenada Media, cet. II 2006) halaman 33-37 8 yang telah dibentangkan dalam kajian fikih, dan tidak terdapat larangan hukum syara’. Oleh Ulama Besar ini, rukun-rukun tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari’at Islam itu telah secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syar’i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah. Rukun yang bersifat tawutsiqy adalah rukun tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negative dari pihakpihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya sebagai upaya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-undang perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931 menyatakan tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya dekumen resmi pernikahan. Namun demikian menurut fatwa Jad al-Haq Ali Jaad alHaq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar’iy nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukun seperti diatur dalam Syari’at Islam. Fatwa Syekh Al-Azhar tersebut, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di suatu negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencacatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menegaskan bahwa perauran perundangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan setiap muslim yang mengadakan perkawinan, sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga peradilan. Misalnya jika dikemudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli waris. Lebih jelas lagi Wahbah Al-Zulaily dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu 13 , secara tegas membagi syarat nikah yang harus dipenuhi, menjadi 13 DR. Wahbah Al-Zuhaily, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, (Bairut: Dar Al-fikr 1985) Juz VIII halaman 36 9 syarat syar’iy dan syarat tautsiqy. Syarat syar’iy maksudnya suatu syarat dimana keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat tautsiqy adalah suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidak jelasan di kemudian hari. Syarat tausiqi tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat tautsiqy, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat syar’iy, karena merupakan unsur pembentuk prosesi pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, disamping sebagai syarat tautsiqy. Contoh syarat tautsiqy dalam al-Qur’an adalah syarat pencatatan jual beli dengan tidak secara tunai, sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 282, “Ya ayyuhalladzina aamanuu idza tadayantum bidaidin illa ajalin musamma faktubuh” dan pada ayat setelahnya dinyatakan “wa in kuntum ‘ala safarin wa lam tajidu katiban farihanumm maqbuudlah” Apabila penggalan dua ayat ini, dipahami secara tektual belaka tanpa mengaitkannya dengan ajaran pada ayat berikutnya, maka kesimpulan yang segera diperoleh adalah adanya kemestian pencatatan utang piutang dan kewajiban memberikan barang tanggungan sebagai jaminan utang. seolah-olah utang-piutang tidak dianggap sah apabila tidak dicatatkan dan atau tidak ada barang jaminan. Pemahaman seperti ini tidak sejalan dengan pemahaman para ulama yang ahli dibidangnya. Sebab menurut kesimpulan para ulama, kedudukan pencatatan dan barang jaminan, hanyalah sebagai alat bukti belaka dan sebagai jaminan bahwa utang tersebut akan dibayar sesuai waktu yang dijanjikannya. Kesimpulan para ulama tersebut adalah karena pemahaman ayat di atas dihubungkan dengan ayat setelahnya “fa in amina ba’dlukun ‘ala ba’dlin falyuaddi alladzi u’tumina amanatahu” ayat terakhir ini menunjukan pancatatan dan barang jaminan adalah alat tautsiq, apabila tautsiq atau kepercayaan itu telah ada pada masing-masing pihak, maka pencatatan dan barang jaminan itu tidak diperlukan lagi dan utang piutang merupakan amanah yang wajib dibayar. Dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa hukum materil dari suatu peristiwa perkawinan, sebagaimana juga pada peristiwa hukum yang lainnya adalah aturan hukum yang menentukan unsur unsur pembentuk dari peristiwa hukum itu, sah atau tidak sahnya suatu perbuatan itu adalah merupakan berbuatan hukum, tergantung pada aturan hukum materil tersebut, tidaklah tergantung pula pada aturan hukum yang berdimensi hukum pembuktian. Misalnya sah atau tidak sahnya jual beli tergantung pada aturan materil tentang terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur jual beli itu, ada pembeli ada penjual, ada barang yang dijualbelikan dan ada uang sebagai ukuran harga barang yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli, penjual dan pembeli mengadakan 10 perikatan jual beli. apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka secara hukum jual beli tersebut adalah sah secara materil tanpa harus memperhatikan hukum pembuktiannya, begitu pula dalam pernikahan untuk menetukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan tergantung pada unsur-unsur pembentuk pernikahan itu sendiri yang telah ditentukan oleh hukum yang dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dillakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal ini menunjukan unsur-unsur peristiwa perkawinan tergantung pada hukum agama masing-masing yang akan melaksanakan perkawinan itu. Oleh karena itu unsur unsur pembentuk suatu peristiwa perkawinan di Indonesia akan berbeda-beda, untuk ummat Islam harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang dalam hal ini Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan hukum sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah sah apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dengan tanpa harus memasukan hukum formilnya, dengan batasan tidak terdapat larangan syara’ untuk melangsungkan perkawinan itu. Hukum pembuktian dalam suatu peristiwa perkawinan adalah ketentuan hukum yang berfungsi untuk menegakan hukum materil tentang perkawinan itu, ketika terjadi persengketaan, keraguan adanya perkawinan atau hal-hal lain yang memerlukan bukti perkawinan. Oleh karena itu pelanggaran prosudur berpoligami yang berakibat bermasalah terhadap pencatatan perkawinan tidaklah relepan bila dinyatakan menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, sebab prosudur poligami dan pencatatan perkawinan tidak termasuk unsur-unsur pembentuk perkawinan itu menurut hukum. Terpenuhinya prosudur poligami sehingga dapat dilakukan pencatatan perkawinan berkaitan dengan hukum formil tentang pembuktian untuk mengabadikan peristiwa perkawinan poligami itu. Dengan demikian pencatatan perkawinan poligami tidak menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, melainkan dengan pencacatan perkawinan poligami menentukan terbukti adanya perkawinan atau tidak terbukti adanya. Apabila suatu perkawinan poligami terdapat cacatan dalam Akta Nikah, maka secara hukum perkawinan tersebut harus dinyatakan ada, dan sebaliknya apabila perkawinan poligami tidak tercatat dalam Akta Nikah, maka secara hukum perkawinan tersebut harus dinyatakan dianggap tidak terbukti adanya dan perkawinan yang demikian tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu tidak dicatatnya poligami di bawah tangan, karena tidak dilakukan sesuai prosudur hukum, dalam hukum Islam tidak mempengaruhi substansi sah atau tidak sahnya perkawinan poligami itu, pergaulan antara suami istri dalam perkawinan yang demikian tidak dapat dikatagorikan perzinaan, demikian pula akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya tidak dapat 11 dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekwensi hukumnya, seperti akibat pekawinan poligami itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya. Akan tetapi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut hanya berlaku secara natural (alamiyah) saja. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Hukum Islam (syari’at Islam) sesuai karakteristiknya memiliki dimensi almashlahah bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat ummat manusia secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penciptaannya sebagai khalifah yang bertugas untuk melestarikan bumi ini (Al-Qur’an Surat Hud ayat 61)14 Menurut Lahmudin Nasutioan 15 Al-Mashlahah berasal dari Bahasa Arab yang jamaknya al-mashaalih, merupakan kata sinomin dengan kata manfaat (keuntungan) dan lawan kata (akronim) dengan mafsadat (kerusakan). Secara majazi, kata tersebut dapat dipergunakan untuk suatu tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan ladzah (rasa enak) dan selalu diupayakan untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian Hukum Islam, mashlahah memiliki pengertian yang khusus walaupun tidak terlepas dari pengertian aslinya, yaitu Jalb al-manfa’at wa daf’u almadlar artinya menarik manfaat dan menolak kemadaratan.16 Ulama fikih sepakat bahwa terbentuknya syari’ah (fikih) yang merupakan turunan dari al-Qur’an dan alHadis (wahyu) terkandung tujuan utama yang disebut dengan mashlahah yang merupakan penjelmaan rahmah Allah terhadap ummat manusia secara umum, agar dapat menjalani tatanan kehidupannya sebagai mana mestinya dan terhindar dari segala hal yang merusak tatanan kehidupan itu. Maashlahah dilihat dari segi objek dan kekuatannya, terdapat tiga macam mashlahah, yaitu mashlaha dlaruriyah, mashlahah hajjiyah dan mashlahah tahsiniyah. Mashlahah dlaruriyah menurut Abu Zahrah disebut juga dengan mashlahah haqiqiyah adalah mashlahah yang keberadaannya berhubungan langsung dengan kebutuhan esaensi (pokok/primer) manusia, yaitu yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perlindungan agama (hafdhu al-diin), pemeliharaan dan Al-Qur’an Surat Hud ayat 61 “hua ansyaa’akum min al-ardhi wa ista’marakum fiiha” artinya Dia (Allah) yang menumbuhkembangkan kamu dari bumi, dan kamu diminta untuk mema’murkan bumi. 15 Lahmudin Nasutioan, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi’I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), halaman 127 16 Abd Al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiq (Barirut: Dar al-Fikr. 1991), halaman 176 14 12 perlindungan jiwa (hafdhu al-nafs), pemeliharaan dan perlindungan akal (hafdhu alaql), pemeliharaan dan perlindungan keturunan (hidhu al-nasl) , dan pemeliharaan dan perlindungan harta (hifdhu al-mal).17 Pemeliharaan dan perlindungan agama adalah melindungi seseorang untuk beragama sesuai dengan kepercayaannya dengan adanya larangan memfitnah dan melecehkan agama, larangan sesat dari agama yang dianut, larangan menistakan agama, larangan selalu berbuat anarhis dan berbuat kerusakan.18 pemeliharaan dan perlindungan terhadap agama sebagai esensi pokok yang diwujudkan dalam bentuk syari’ah adalah agar ummat manusia tidak melepaskan diri hubungannya dengan Sang Khalik Allah SWT sebagai hubungan religius transendental. Oleh karena itu setiap hukum yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam wahyu baik yang bersifat qauliyah (al-Qur’an), maupun yang bersifa ma’nawiyah (al-hadis), sebab bila manusia telah melepaskan diri hubungannya dengan Allah SWT, akan berimplikasi negatif pada kehidupan bermasyarakat secara umum. Pemeliharaan dan perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap segala hak hidup yang layak, yang diantaranya pemeliharaan dan perlindungan kebebasan berbuat, kebebasan berfikir, kebebasan berbicara, kebebasan bertempat tinggal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hak asasi manusia19. Pemeliharaan dan perlindungan terhadap akal adalah memelihara dan melingdungi akal dari segala hal yang akan berakibat kerusakan akal. Oleh karena itu Hukum Islam mengharamkan khamr dan segala bentuk narkoba. 20 Pemeliharaan terhadap keturunan adalah pemeliharaan dan perlindungan bagi setiap anak dengan status yang jelas, harus diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang disekitar orang tuannya, baik sisi jasmaninya maupun ruhaninya.21 Untuk menjamin terpeliharaanya keturunan ini dalam hukum Islam diharamkan melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan, dan terbentuknya lembaga perkawinan yang disyari’atkan. Dan pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta adalah memelihara dan melindungi harta dari segala bentuk-bentuk dlalim, pencurian, penipuan dan penghancuran.22 Apabila kepentingan-kepentingan tersebut tidak dipelihara dan tidak dilindungi oleh hukum, maka tatanan kehidupan manusia akan mengalami ketidak nyamanan, dan kehancuran, karena unsur-unsur pokok yang membentuk kehidupan ini telah tidak ada. Mashlahah hajjiyah adalah mashlahah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sekunder (tidak esensial) kehidupan manusia manusia, sedangkan mashlahah tahsiniyat adalah mashlahah yang berhubungan dengan kebutuhan manusia yang bersifat estetika 17 Imam Al-Sayuthi, Al-Isybah Wa al-Nadha’ir, (Bairut: al-Maktabah, 1989). halaman 397 Imam Al-Suyuthi, Ibid. 19 Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Bairut: Dar Al-fikr, 198) halaman 278. 20 Abu Zahrah, Ibid. halaman 279 21 Abu Zahrah, Ibid. halaman 280 22 Abu Zahrah, Ibid. 18 13 Suatu ketentuan perundang-undangan atau hukum yang dibentuk berdasarkan mashlahah, esensinya untuk menciptakan kebaikan, ketertiban, keselamatan dan kebahagian hidup manusia, atau terhindar dari hal-hal yang dapat merusak tatanan kehidupan secara umum. Mashlahah dalam hal ini terbagi kepada tiga macam23 yaiu Mashlahah al-mu’tabarah, yaitu mashlahah yang ditunjuk Syara’ baik secara langsung maupun tidak langsung dan berfungsi sebagai dalil dalam pembentukan suatu hukum, Mashlahah al-mulgha, yaitu mashlahah yang secara rasional dianggap baik, akan tetapi tidak diperhatikan dalam nash, dan ada petunjuk nash yang menolaknya dan Mashlahah al-mursalah, disebut juga dengan istilah al-ishtislah, yaitu suatu mashlahah yang dipandsang baik oleh akal pikiran, sejalan dengan tujuan hukum Syara’ dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak ada nash Syara’ yang menunjuknya dan tidak ada pula yang menolaknya. Mashlahah dalam bentuk yang terakhir adalah salah satu teori yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan, yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kemadaratan yang akan terjadi. Mashlahah mursalah menurut Wahbah al-Zuhaili 24 adalah beberapa sifat yang melekat (al-mulaimah) pada tindakan dan selaras dengan tujuan Syara’, tetapi tidak ada dalil tertentu yang membenarkannya atau menolaknya. Hukum yang dibangun berdasarkan mashlahah mursalah ini akan mencapai kemaslahatan yang sejati dan terhindar dari kerusakan. Sedangkan menurut Muhammad Sa’id al-Ramdan al-Buti yang dikutif Abdul Manan 25 bahwa hakikat mashlahah al-mursalah adalah setiap manfaat yang tercakup dalam jiwa syari’ah dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkannya. Kemudian Abdul manan menyimpulkan bahwa maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan, apa yang lebih baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan jiwa syari’ah dalam merekontruksi bangunan hukum, kebaikan dan keselarasan tersebut tidak terdapat dalil yang mengakuinya.26 Syari’ah (hukum Islam) dalam bentuk nilai-nilai dasar berdimensi absolut, abstrak, abadi dan universal, ia bersifat transendental karena bersumber wahyu ilahiyah, sedangkan syari’ah dalam bentuk asas-asas umum dan asas-asas hukum praktis yang berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai dasar yang harus dipertimbangkan dengan norma hukum praktis, baik dalam bentuk fikih maupun perundang-undangan.27 Syari’ah dalam bentuk berupa peraturan hukum konkrit baik yang dimuat dalam doktrin hukum (fikih) maupun perundangan yang berlaku dalam suatu negara tertentu substansinya konkrit, relatif, temporer, dan lokal. Ia bersifat dinamis logis transendental. Dinamis berimplikasi bahwa norma hukum yang diciptakan disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan (elastisitas atau harakah) 23 DR. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) halaman 17 24 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Bairut Dar al-Fikr al-Muasir, 1986), halaman 757 25 DR. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum, op.cit. halaman 266 26 Abdul Manan, Ibid, halaman 267. 27 A. Mukti Arto, loc. Cit. halaman 12-13 14 yang tidak berhenti pada suatu titik tertentu, melainkan terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Terhadap peraturan hukum yang konkrit ini berlaku kaidah-kaidah hukum “al-hukmu yadurru ma’a illatihi wujuudan wa ‘adaman, taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkan wa al-azminah, al-hukm manuuthun bi a-mashlahah al-mu’tabarah” logis berarti hukum tersebut sesuai dengan kebenaran yang rasional dan transendental berarti hukum itu harus berpijak pada nilai-nilai dasar syari’ah yang ditetapkan dalam wahyu ilaahi, agar menghasilkan kebenaran ilaahiyah28 Berdasarkan hal tersebut, maka syari’ah (hukum Islam) memiliki daya elastisitas dan elaktibilitas yang selalu selaras dengan perkembangan kondisi dan situasi, baik lokal maupun global. Perbuatan zina atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar ikatan perkawinan adalah perbuatan nista dan tidak dibenarkan oleh aturan manapun, oleh agama apapun dan oleh negara apapun, walaupun dalam katagori yang sedikit berbeda. Dalam Islam berpuatan zina dengan segala bentuknya baik dilakukan suka-sama suka, maupun tidak, dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga maupun telah berkeluarga adalah terlarang dan termasuk perbuatan dosa besar, bahkan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan hukuman rajam atau jilid29. Demikian tegasnya hukum Islam terhadap pelaku zina, karena apabila perzinaan dibiarkan dan menjadikannya sebagai perbuatan yang biasa dilakukan, akan berakibat kehidupan manusia yang seharusnya berada pada tatanan kehidupan terhormat sesuai martabat manusia itu sendiri, dengan merebaknya perzinaan akan berakibat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu dan akan mengganggu bangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegana (social socity) 30 apabila perzinaan diperbolehkan dan dibiarkan dalam masyarakat, maka kehidupan manusia sama saja dengan kehidupan binatang yang bebas dari nilai-nilai. Akibat 28 Ibid, halaman 13 Abd Al-Rahman Al-Jaziiry, menyatakan fazzina min al-asbaabi alati taqwidhu da’aima alumami wa tuhaddimu majdaha wa tajlibu lahaa al-dzilla wa al-isti’maara li’annahu mu’athilun linnasli al-qawiy al-shalihi al-mutanaashiri, wa qaatili linnakhwati wa al-syahaamati wa mumayyitu liljar’ati wa al-syaja’ah wa qaathi’u lirrahmi allati turabbitu baina al-naas wa allati ‘ala nidhaamiha wa taqdiiriha tbna’ kaafahtu al-rawaabith al-insaniyah min al-ubuwwah wa albunuwwah wa al-ukhuwwah wa saa’iri al-qarabah artinya perzinaan adalah merupakan salah satu sebab robohnya dan hancurnya pondasi bangunan kehidupan ummat manusia dalam bermasyarakat yang layak dan bermartabat, dengan melegalkan zina akan membawa masyarakat kejurang kehinaan dan kenistaan, karena dengan perbuatan zina akan menyia-nyiakan keturunannya, sebagai unsur utama pembentuk masyarakat manusia itu, perzinaan berakibat membunuh semangat dan kemandirian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dengan perzinaan berakibat memutuskan mata rantai silah al-rahmi (hubungan silaturrahmi) melalui ikatan al-ubuwwah wa al-bunuwwah wa al-ukhuwwah wa saa’iri al-qarabah yang seharusnya terjalin sebagai pengikat antar ummat manusi dalam membangun hubungan antar satu individu dengan individu yang lain secara menyeluruh. Abd Al-Rahman Al-Jaziiry, Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzaahib Al-Arba’ah, Jilid V (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra’, tt) halaman 57 30 Muhammad Aly Al-Shabuny, Rawa’i al-Bayan bi tafsiir ayat al-Ahkam min Al-Qur’an, Juz II, halaman 52 29 15 lain dari perbuatan zina ini adalah berakibat langsung menelantarkan anak-anak yang dilahirkannya, sebab seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan berakibat melahirkan anak, lakilaki dan perempuan itu tidak terikat hubungan hukum dan demikian pula dengan anak yang dilahirkannya itu. Oleh karena itu di antara mereka tidak terikat hak dan kewajiban. Dengan demikian Islam memandang bahwa zina dengan segala bentuknya adalah merupakan tindak pidana umum yang disyari’atkan untuk menjaga stabilitas masyarakat dan menghindari kemadaratan yang akan dialami anak-anak yang dilahirkannya31 Demikian pula hukum Perkawinan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar dan pemeliharaan keturunan yang dilahirkannya, disamping mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah, sebagaimana yang dikandung dalam Q.S. al-Ruum ayat 21, yang artinya ; • Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Rum (30) : 21) Di Indonesia, peraturan tentang (hukum) perkawinan diatur dalam UU Nomor I Tahun 1974 yang selanjutnya secara rinci dilengkapi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang keberlakuannya diatur dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991. Pembicaraan perkawinan dan segala permasalahannya tentu tidak lepas dengan status anak yang dilahirkan, baik yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami isteri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang terikat tali perkawinan yang sah maupun hubungan suami isteri di antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Untuk kasus yang pertama tidaklah menjadi pembahasan di sini, yang menjadi bahasan di sini adalah kasus yang kedua. Pengertian Anak Di luar Nikah dan Dasar Hukumnya Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam hukum perdata umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah : 1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 31 Muhammad Aly Al-Shabuny, ibid halaman 53 16 2. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Di samping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : • “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”. Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang status anak li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak ada mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu Bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah : 1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah. 2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawainan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi. 3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami. Karena itu untuk mendekatkan pengertian “anak di luar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminology yang tertera dalam kitab fikih 32 yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ulama fikih membuat terminology anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah.-Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi’) antara dua orang 32 Lihat Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwaal al-Syakhshiyah, (Bairut: Dar Alfikr al-‘Araby 1957) halaman 404, lihat juga Wahbah al-Zuhaily, fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984) Juz VII halaman 675 17 yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan. Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang popular dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya.-Hal tersebut mungkin bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan “seorang suami dapat menyengkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana definisi yang dikemukaan oleh ulama fikih di atas, adalah istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah”, sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : • “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. • Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak atau janin yang pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.-Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah : 1. Apabila orang tua salah satu atau keduannya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina. 2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin. 18 • Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 KHI, adalah : “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah : 1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya. 2. Anak Yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih. 3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili’an (diingkari) oleh suaminya. 4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan. 5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan. Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh Bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya. Sedangkan angka 1, 2 dan 3 adalah termasuk dalam kelompok anak zina’ Penetapan Nasab Anak Menurut Fikih. Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat antara calon mempeplai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kekuatan ikatan perkawinan tersebut yang terikat bukan saja lahiriyahnya saja, melainkan juga terikat batiniyahnya antar suami istri itu dan antar suami istri dengan masing-masing orang tuannya. Akibat hukum adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bukan saja antar suami istri itu, melainkan juga dengan pihak lain yaitu adanya hak-hak yang harus diterima anakanak yang dilahirkannya. Hak anak yang paling pertama yang dilahirkan dari orang tuannya adalah hak nasab bagi anak, hak mendapatkan penyusuan, hak mendapatkan pengasuhan, hak memperloh perwalian, hak menerima biaya hidup dan hak kewarisan. Nasab Anak-anak Terhadap Orang Tuanya. Dalam pembahasan tentang nasab anak tersebut terdapat tiga kaidah hukum yang harus dijadikan patokan, yaitu: 1. Masa kehamilan anak dalam kandungan ibunya batas minimalnya 6 bulan setelah masa perkawinan. Pada masa sekarang, dimana kecanggihan teknologi semakin pesat dalam berbagai bidang ilmu pengatehuan, termasuk dalam bidang ilmu kebidanan yang mempelajari tentang embriologi dalam kandungan seorang ibu, melalui perhitungan exsakta janin yang ada dalam kandungan itu dapat diketahui kapan seorang ibu 19 mulai mengandung janin itu dan dapat diketahui pula kapan ibu hamil itu akan melahirkan anaknya. Dengan ilmu exsakta ini pada masa sekarang akan lebih meyakinkan pembuktian untuk menghubungan nasab anak kepada kedua orang tuanya, dari pada diukur dengan ukuran 6 bulan setelah perkawinan, yang dihasilkan dari kebiasaan-kebiasaan seorang ibu dapat melahirkan. Walaupun demikian kaidah ini masih dapat digunakan sebagai bukti awal bahwa anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah masa perkawinannya diduga bukan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah menurut hukum dan sebagai bukti yang lengkap dan meyakinkan dalam hal ini menurut penulis adalah buklti keterangan ahli. Penentuan batas minimal 6 bulan masa kehamilan setelah terjadi hubungan suami istri yang nyata menurut Mayoritas ulama dan setelah adanya akad perkawinan menurut ulama al-Hanafiyah 33 , yang dijadikan sandaran ahli hukum Islam secara mayoritas adalah didasarkan pada hadis “qaala Rasulullah SWA alwalad lilfirasy wa lil’aahir al-hijru” 34 maksud hadis ini menurut Wahbah alZuhaily adalah bahwa seorang anak nasabnya dapat dihubungkan terhadap ayahnya hanya dalam perkawinan yang sah, yang dimaksud al-firasy dalam hadis tersebut adalah seorang perempuan menurut pandangan kebanyakan ulama, adapun perzinaan tidak dapat dijadikan sebab adanya hubungan nasab antara ayah pezina dengan anak zinanya, sebab seorang pezina berhak menerima hukuman rajam atau dilempar dengan batu. Seorang perempuan tidak dapat dinyatakan dengan firasy kecuali perempuan itu memungkinkan dapat melakukan hubungan suami istri. Adapun batas maksimum seorang ibu mengandung janin, terjadi perbedaan pendapat menurut Imam Malik selama lima tahun, menurut Imam Syafi’iy selama empat tahun, menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dua tahun, sesuai yang dinyatakan ‘Aisyah ra bahwa seorang perempuan hamil tidak melebihi dua tahun. Muhammad bin al-hakm menjelaskan bahwa seorang perempuan hamil paling lama satu tahun hijriah dan menurut Dhahiriyah selama sembilan bulan tidak lebih dari itu. Abu Zahrah35 dalam hal ini menegaskan bahwa penentuan waktu lamanya hamil seorang ibu, tidak didasarkan pada nash, melainkan berdasarkan kebiasaan suatu daerah, menurut penelitian yang dilakukan sekarang diperkirkirakan masa maksimun kehamilan adalah sembilan bulan, ditambah satu bulah untuk kehatihatian menjadi sepuluh bulan, begitu pula menurut Ibnu Rusyd dalam masalah ini dikembalikan kepada kebiasaan suatu daerah dan ilmu kedokteran. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 tentang hukum perkawinan yang berlaku di Mesir, batas maksimum masa kehamilan adalah satu tahun Masehi atau 365 hari, penentuan ini diperlukan untuk mengantisipasi gugatan nafkah iddah dan gugatan yang berkaitan dengan nasab (hubungan darah) untuk menetapkan hak kewarisan dan menetapkan wasiat bagi anak yang dikandung itu. 2. Penyebab penetapan nasab dalam akad yang fasid terhadap anak adalah adanya hubungan sexsual suami istri secara nyata. 33 Wahbah Al-Zuhaily, ibid halaman 676 Hadis ini diriwayatkan al-Jama’ah selain al-Turmudzy 35 Muhammad Abu Zahrah, ibid halaman 452 34 20 Seorang anak dapat dihubungkan nasabnya kepada orang tuanya, bilamana orang tua tersebut telah melakukan hubungan badan secara nyata dan apabila orang tua itu belum melakukan hubungan suami istri secara nyata, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada orang tuanya. Yang dimaksud hubungan suami istri secara nyata dalam hal ini adalah terjadinya pembuahan ovum (induk telor) seorang istri oleh spermatozoid suaminya, baik pembuahan itu terjadi dalam vagina maupun diluar vagina istri, suami istri yang telah melakukan hubungan badan, kemudian istri mengandung janin dan usia kandungannya berjalan enam bulan atau lebih, maka anak tersebut nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuannya. Masa kehamilan tersebut diperhitungkan sejak terjadinya hubungan suami istri, bukan dari akad perkawinannya, karena penyebab adanya nasab dalam hal ini adalah adanya hubungan badan. Adapun akad yang sah menurut hukum, ulama sepakat adalah sebagai penyebab penetapan nasab anak yang lahir dalam ikatan perkawinannya, dengan demikian kelahiran anak yang bukan sebagai akibat perkawinan yang sah, baik dilakukan sebelum adanya perkawinan itu, maupun yang dilahirkan dalam perkawinan yang pembuahannya terjadi sebeluam adanya perkawinan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada orang tuanya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hanya dengan adanya akad perkawinan yang sah saja yang menyebabkan adanya nasab bagi anak, walaupun suami istri itu setelah akad perkawinan tidak pernah bertemu, misalnya seorang istri berada di wilayah Timur dan suaminya berada di wilayah Barat dan pernikahannya itu melalui utusan atau tulisan. Imam Ahmad, Imam al-Syafi’iy dan Imam Malik berpendapat bahwa seorang anak dapat ditetapkan nasabnya yang disebabkan akad perkawinan yang sah dan lahir ditengahtengah kehidupan berumah tangga atau dalam iddah, apabila memungkinkan terjadinya hubungan badan antara suami istri itu, apabila tidak mungkin karena berjauhan atau sama sekali tidak pernah bertemu, maka nasab anak itu tidak dapat ditetapkan, pendapat ini juga dipegang oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad ra mengisyaratkan dalam riwayat harb, bahwa ia telah menentukan ketentuan hukum dalam periwayatannya tentang seorang yang menthalak istrinya sebelum membina rumah tangga, dan istrinya itu melahirkan dan suaminya itu mengingkari anak tersebut, beliau menyatakan anak itu nasabnya ditiadakan dari suaminya itu, dengan selain li’an.36 3. Perzinaan tidak berakibat adanya nasab. Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan “al-waladu lilfiraasy wa al-‘ahiir lilhijr artinya anak bagi pemilik tempat tidur (perempuan) dan pezina harus dihukum rajam37. Karena tetapnya nasab merupakan ni’mah (anugrah), Abu Zahrah, ibid halaman 453, menurut beliau karena syarat li’an adalah adanya pengingkaran anak yang dilahirkan istrinya atau menuduh istrinya berbuat zina, kedua dalil tersebut tidak ada dalam kasus itu, melainkan dengan lahirnya anak sebelum membina rumah tangga dalam satu rumah adalah satu-satunya dalil bahwa istrinya itu telah melakukan perbuatan zina. 37 Hadis ini diriwayatkan al-Jama’ah dari Aby Hurairah ra. Redaksi hadis ini dalam riwayat al-Bukhary adalah al-walad lishahib al-firasy. Ulama al-Syafi’iyah, al-Malikiyah dan al-Hanabilah menyatakan bahwa yang dimaksud firasy dalam hadis ini adalah nama seorang perempuan, dan dalam kamus firasy itu adalah istrinya seorang laki-laki (Abd Al-Rahman Al-Jaziiry, loc.cit. halaman 120. 36 21 sedangkan tindak pidana bukanlah ni’mah melainkan berhak menerima hukuman. Perzinaan yang tidak berakibat adanya nasab adalah setiap perbuatan melakukan hubungan badan diluar ikatan perkawinan yang sah, dan tidak termasuk hubungan badan yang syubhat yang menggugurkan hukuman had, sebab apabila hubungan badan itu merupakan hubungan badan yang syubhat sehingga menghapuskan sifatsifat tindak pidana atau menggugurkan hukuman had, maka apabila dari hubungan badan itu melahirkan anak, menurut pendapat yang lebih raajih 38 anak tersebut dapat ditetapkan nasabnya, akan tetapi apabila seorang menda’wakan (mengangkat) nasab anak yang dilahirkan seperti kelahiran yang lainnya, walaupun sebenarnya tidak diketahui nasabnya, maka nasab anak itu dihubungkan terhadap orang itu dengan syarat tidak disebutkan anak itu sebagai hasil zina, apabila tidak demikian anak itu tidak dapat ditetapkan nasabnya. Dan nasab yang seperti ini dinamakan nasab bi al-da’wah (pengakuan nasab anak).39 Madzhab Malikiyah menyatakan penetapan nasab dengan pengakuan, tidak cukup hanya tidak menyebutkan bahwa anak itu hasil zina, melainkan mesti tidak diketahui kedustaannya dengan beberapa tanda-tanda, misalnya seoarang anak temuan dan tidak menjelaskan pengakuan nasabnya secara akal atau ibu dari anak tersebut adalah istri dari suami yang lain. Ibnu al-Qasim40 menyatakan apabila anak itu diketahui sebagai anak temuan atau anak pungut, pengakuan nasab anak tersebut tidak dapat ditetapkan kecuali dengan bukti-bukti, berbeda dengan seorang perempuan yang mengakui seorang nasab anak, pernyataan perempuan itu dapat diterima walaupun anak tersebut hasil zina, karena anak zina nasabnya dihubungkan kepada ibunya. Kaidah-kaidah tersebut adalah merupakan asas pokok yang berkaitan dengan ketentuan hukum penetapan nasab anak dalam keadaan yang berbeda-beda, yaitu adanya anak atau kelahiran anak itu setelah suami istri menjalankan kehidupan berumah tangganya atau ketika istri menjalankan masa iddah, maupun sebagai akibat dari hubungan badan yang subhat pada akad perkawinan yang fasid atau yang lainnya. Seandainya kelahiran anak itu sebagai akibat hubungan badan yang subhat, dan anak itu dilahirkan dalam keadaan hidup, akan tetapi masa kandungannya kurang dari enam bulan yang dihitung sejak berhubungan badan setelah perkawinan, maka nasabnya tidak dapat ditetapkan, karena diyakini awal kehamilan istri tersebut terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri. Dan apabila kelahiran anak itu setelah enam bulan, maka nasab anak itu ditetapkan sebagai anaknya dan keberadaan anak itu tidak dapat disangkal walaupun dengan cara li’an, karena terjadinya li’an hanya berlaku dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan perempuan itu dinyatakan sebagai istrinya yang sah, sedangkan dalam perkawinan yang subhat seorang perempuan itu tidak dapat dinyatakan sebagai istri dalam berbagai keadaan. 38 Pendapat yang lebih rajiih maksudnya pendapat yang dipilih ulama dari segi keuatan dalilnya. 39 40 Abu Zahrah, ibid Ibnu Qayyim, I’lam al-Muaqi’in 22 Seorang anak dapat ditetapkan nasabnya sebagai akibat dari perkawinan yang sah dan masa kelahirannya enam bulan atau lebih setelah perkawinan, harus memenuhi tiga syarat, Yaitu: 1. Suami memungkinkan dapat menghamili istrinya. Apabila seorang suami masih anak-anak, dan tidak mungkin dapat menghamili istrinya, maka anak tersebut tidak dapat ditetapkan nasabnya, karena keadaan suami yang masih anak-anak adalah merupakan qarinah yang pasti, bahwa kehamilan istri bukan dari suaminya itu. Ulama sepakat bahwa syarat yang menjadi dasar adanya berbagai hubungan nasab adalah adanya pembuahan ovum oleh spermatozoid dari suami yang telah matang, suatu hal yang tidak mungkin anak lahir dari suami yang masih anak-anak. 2. Tidak ada pengingkaran suami terhadap anak yang dilahirkan. Untuk adanya penetapan nasab anak, tidak terjadi adanya pengingkaran dari pihak suami terhadap anak yang dilahirkan dengan terjadinya li’an. Seorang suami yang me-li’an istri dengan cara mengingkari anak yang dilahirkan istrinya dapat dibenarkan apabila mengingkaran tersebut tidak didahului dengan pengakuan baik secara tegas maupun tidak secara tegas, sebab penetapan nasab melalui pengakuan pihak suami, pengakuan itu mengikat suami dan menggugurkan haknya untuk mengingkari, pengakuan dengan tidak tegas misalnya suami mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk kelahiran anaknya dan menerimanya dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Pengakuan secara tegas adalah suami mengakui kehamilan istrinya itu dari suami tersebut sebelum melahirkan, walaupun masa kehamilan istrinya kurang dari enam bulan antara pengakuan dan kelahiran, sebab pengakuan dalam hal ini berlaku bagi anak yang dilahirkan dan menggugurkan haknya untuk mengingkari. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengingkaran anak, berlaku apabila memenuhi dua syarat, yaitu tidak didahului dengan pengakuan dan terjadinya li’an. Apabila telah terjadi li’an maka anak tersebut tidak dapat ditetapkan nasabnya terhadap suami yang mengingkari itu, hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam li’an. 3. Antara suami istri setelah menikah pernah hidup bersama. Apabila suami istri setelah akad perkawinannya pernah hidup bersama, walaupun hanya satu malam, dan setelah itu suaminya, pergi merantau jauh ke luar daerah, setehun kemudian sumainya baru pulang dan ternyata telah ada anak yang dilahirkan istrinya, maka dalam hal ini gugur hak suami untuk mengingkari anak yang dilahirkan istrinya.41 41 Kitab Undang-Undang Hukum Suria Pasal 129 menyatakan seorang anak dapat dihubungkan nasabnya terhadap orang ayah kandungnya dengan ketentuan : 1. Anak yang dilahirkan setiap istrinya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan dua syarat: a. Dilahirkan setelah lewat akad perkawinan dengan masa kehamilan batas minimal. b. Antara suami istri selama ikatan perkawinannya pernah hidup bersama sebagai suami istri atau suami istri itu tidak pernah berpisah selama kehamilan istrinya dengan batas maksimal. 2. Apabila syarat-syarat pada ayat 1 tidak terpenuhi, maka nasab anak itu tidak dapat dihubungkan terhadap suaminya, kecuali adanya pengakuan dari suaminya. 23 Penetapan Nasab Anak Dalam Masa Iddah Seorang istri yang sedang menjalankan masa iddah kemudian melahirkan anak, masa kandungannya kurang dari enam bulan dari perkawinannya, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya kecuali dengan pengangkatan anak, karena anak itu telah menjelma sebagai janin sebelum enam bulan dari perkawinannya, hal ini menunjukan bahwa kehamilan perempuan tersebut terjadi sebelum perkawinan, akan tetapi sah dihubungkan nasabnya dengan pengakuan anak, sebagaimana anak yang tidak diketahui nasabnya, dengan syarat anak itu jelas-jelas bukan hasil zina, sebagaimana menurut Madzhab Abu Hanifah. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam kasus seorang perempuan melahirkan, masa kehamilannya kurang dari enam bulan sejak melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang fasid atau pada hubungan suami istri yang syubhat, karena kehamilan tersebut sebelum adanya nasab. Apabila kelahiran anak tersebut setelah enam bulan atau lebih ketentuan hukumnya berbeda sesuai dengan perbedaan masa iddah. Seorang istri yang sedang menjalankan masa iddah dari thalak dengan tiga kali sucian, apabila menurut pengakuannya telah selesai masa iddahnya dan terlihat tidak dalam keadaan hamil, setelah itu ternyata perempuan tersebut melahirkan anak, apabila masa kehamilannya kurang dari enam bulan sejak adanya pengakuan, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepadanya, karena adanya kedustaan pada pengakuannya dengan meyakinkan, karena jelas ketika dia menyatakaan pengakuannya sedang ia dalam keadaan hamil dan apabila masa kehamilannya enam bulan atau lebih sejak adanya pengakuan, maka anak itu tidak dapat ditetapkan nasabnya, karena tidak dapat dipastikan dustanya, karena pengakuan dapat dijadikan bukti sebelum dapat dibuktikan keduastaannya, dan bukti tersebut tidak ada. Dan apabila perempuan tersebut tidak mengakui telah selesai masa iddahnya, dan thalaknya termasuk thalak ba’in, ternyata setelah itu melahirkan anak dengan batasan waktu lebih dari dua tahun setelah jatuh thalak, maka anak itu tidak dapat ditetapkan nasabnya, karena batas maksimal kehamilan adalah selama dua tahun, maka apabila melebihi dua tahun dan ketika perempuan itu dijatuhi thalak tidak dalam keadaan hamil berdasarkan keyakinan, maka anak tersebut tidak dapat ditetapkan nasbnya kedapa mantan suami yang menthalaknya itu. Pada ketentuan perundang-undangan Mesir Nomor 25 Tahun 1929 menyatakan gugatan tentang status anak atau asal usul anak dari seorang perempuan yang sedang menjalankan masa iddah, baik iddah wafat maupun iddah thalak, bila kelahiran anak itu melebihi dua tahun Masehi atau sama dengan 395 hari, maka gugatan seperti ini harus dinyatakan ditolak. Aturan ini berdasarkan penelitian ilmu kebidanan yang menyatakan janin tidak mungkin ada dalam kandungan ibunya melebihi dua tahun lamanya. Dan apabila seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah thalak raj’iy, kemudian ternyata melahirkan seorang anak, maka nasab anaknya dapat 3. Apabila kedua syarat sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas terpenuhi, nasab anak terhadap suaminya melekat dan tidak dapat diingkari kecuali dengan cara li’an. 24 ditetapkan kepada kedua orang tuanya, kapan saja kelahiran anak itu, selagi iddahnya tidak berpindah menjadi iddah dengan bulan, hal ini disebabkan pada masa iddah tersebut suami dapat meruju’nya kembali kapan saja jika dikehendaki dankarena thalak raj’iy tidak menghilangkan kepemilikan atas ikatan perkawinannya. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang anak dapat dihubungkan nasabnya terhadap orang tuanya harus terpenuhi tiga aspek secara komulatif, yaitu anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, bukan hasil dari hubungan badan di luar ikatan perkawinan (zina), suami istri telah melakukan hubungan badan secara nyata dan anak tersebut berada dalam kandungan ibunya minimal 6 bulan, terhimpunya ketiga aspek tersebut juga disyaratkan suami memungkinkan dapat menghamili istrinya, antara suami sitri telah pernah hidup bersama dalam satu ranjang dan suami tidak pernah mengingkari anak yang dilahirkannya. Dengan demikian apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka seorang anak nasabnya tidak dapat dihubungkan terhadap suami dari ibunya itu. Teori-teori fikih yang dikemukakan ulama tersebut menunjukan bahwa adanya ikatan nasab 42 antara orang tua (ayah dan ibu) dengan anak-anaknya, melahirkan doktrin hukum yang berbeda-beda, tergantung pada keadaan ikatan perkawinannya, kelahiran anak itu masih dalam ikatan perkawinan yang masih utuh atau ketika istri menjalani masa iddah atau disebabkan hubungan badan yang syubhat dalam akad yang dinyatakan fasid atau yang lainnya. Oleh karena itu yang menjadi kaidah umum adanya ikatan nasab antara anak dengan orang tuanya (ayahnya) adalah adanya ikatan perkawinan yang sah dan diukur dari masa kehamilan ibunya minimal 6 bulan setelah adanya akad perkawinan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, atau istri telah selesai menjalankan masa iddah raj’iy, dan masa kehamilannya kurang dari 6 bulan yang dihitung mulai dari selesai masa iddah, atau istri selesai menjalankan masa iddah thalak ba’in dengan masa kehamilan kurang dari enam bulan, kecuali akad perkawinannya menjadi fasid, maka adanya ikatan nasab didasarkan pada adanya hubungan badan secara nyata dan kehamilan istrinya lebih dari 6 bulan setelah hubungan badan itu. Dari kaidah umum ini melahirkan konsekwensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dan oleh karena itu ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal. Kemudian persoalan yang timbul adalah, apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan Konstitusi Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) ?. 42 Nasab adalah terminologi fikih yang melambangkan ikatan antara an ak dengan orang tua atau orang tua dengan anak secara timbal balik (hubungan perdata yang disebabkan kelahiran dalam ikatan perkawinan. 25 Norma-norma hukum yang dimuat pada UUD 45 tersebut harus dibaca sesuai kronologisnya, Pasal 28 B ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28 B ayat (2) menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 28 D ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan ketentuan tersebut yang menjadi kata kunci adalah “melalui perkawinan yang sah” sebagaimana terdapat pada Pasal 28 B ayat (1) UUD 45, yang dimaksud perkawinan yang sah disini harus dibaca sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Norma dasar ini menghendaki bahwa setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan keturunan yang dibenarkan, yaitu keturunan yang diperoleh dari perkawinan yang sah menurut hukum agamanya, dan tidak melegalisasikan hak untuk mendapatkan keturunan dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah atau kumpul kebo. Oleh karena itu pula menurut UUD 45 ini keturunan (baca anak) yang sah adalah keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang berarti pula tidak melegalisasikan keturunan yang sah dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo). Pasal 28 B ayat (2) UUD 45 adalah turunan dari ayat sebelumnya, dalam ayat ini menunjukan hak-hak anak yang merupakan kewajiban orangtuanya yang sah untuk memberikan segala sesuatu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, demikian pula negara berkewajiban melindungi anak dari kekerasan (dalam rumah tangga) dan diskriminasi. Sedangkan Pasal 28 D ayat (1) menunjukan kewajiban negara terhadap setiap orang sebagai warga negara diharuskan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang dalam ayat ini kaitannya dengan anak adalah setiap anak baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun yang dilahirkan di luar perkawinan, termasuk di dalamnya anak-anak terlantar yang asal usulnya tidak diketahui atau tidinggalkan orang tuanya atau anak yang dibuang oleh ibunya, walaupun setatus dan identitas diantara mereka berbeda-beda. Ketentuan tersebut bila diterapkan dalam kasus misalnya A (perempuan) dan B (laki-laki), sebelum adanya ikatan perkawinan, mereka pernah berkumpul dalam satu ranjang, sehingga A melahirkan anak C, setelah itu A dan B menikah dan setahun setelah menikah lahirlah anak yang kedua D. Dengan demikian A dan B memiliki dua anak C dan D, C sebagai anak yang lahir di luar perkawinan (hasil kumpul kebo) dan D sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah. C dan D sebagai anak yang statatusnya berbeda menurut hukum karena penyebab kelahirannya berbeda, C hanya memiliki hubungan nasab dengan A sebagai ibunya, sedangkan hubungannya dengan B hanya sebagai ayah biologis, bukan ayah yang sah secara hukum oleh karena itu menurut UUD 45 B tidak memiliki hak untuk mengakui C sebagai anaknya, sedangkan D memiliki hubungan nasab baik dengan A sebagai ibunya maupun dengan B sebagai ayahnya. Membedakan setatus C dan D 26 dihadapan hukum bukanlah perlakukan diskriminasi, melainkan adanya dua peristiwa hukum yang berbeda yang mengharuskan statusnya berbeda, walaupun C dan D statusnya berbeda, kedua-duanya oleh negara harus diperlakukan sama. Apabila status C dan D status nasabnya disamakan, maka persamaan status ini akan bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) UUD 45 sebagaimana tersebut di atas, sebab seorang diberikan hak oleh hukum untuk mendapatkan keturunan “hanya” melalui perkawinan yang sah, arti kebalikan (mafhum mukhalafah) dari pasal ini adalah seorang tidak diberikan hak untuk mendapatkan keturunan dari hubungan badan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari penelaahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain sejalan dengan teori fikih, juga sejalan atau paling tidak, tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1), nampaknya kesimpulan ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertentangan dengan UUD 1945, karena menutup hak anak yang lahir di luar perkawinan atas adanya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya43. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubngan perdata dengan keluarga ayahnya”44 Tujuan perombakan (review) Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sebagaimana yang dikutif A. Mukti Arto45 adalah: 1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum, sehingga memilki akibat hukum. 2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya. 3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian. 4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (legal custady) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya. 43 Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 halaman 36 Putusan MK ibid halaman 37 45 A. Mukti Arto, loc.cit. halaman 5-6 44 27 6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain. 7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya. 8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya. 9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Tujuan-tujuan perombakan (review) Pasal 43 ayat (1) tersebut terlihat sangat erat kaitannya dengan hifdhu al-nasl yang merupakan salah satu tujuan pokok dari lembaga hukum perkawinan dalam hukum Islam. Oleh karena itu untuk meraih tujuan-tujuan itu dapat diraih secara benar dan pasti, bukanlah dengan merombak Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut, melaikan dengan cara me-review Undang-Undang Perkawinan secara keseluruhan yang selama ini dirasakan madul dan tidak tegas serta tidak memberikan sanksi apapun terhadap orang yang melanggarnya. Selain itu tujuan-tujuan tersebut tidak secara jelas menunjuk pada keadaan anak yang di atur dalam Pasal 43 ayat (1) itu, karena substansi yang diatur dalam pasal ini adalah tentang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan atau anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan kasus yang menjadi dasar permohonan yudisial review ini adalah kasuk anak Moerdiono dari istri sirinya yang bernama Hj. Aisyah Mokhtar. Kasus anak Moerdiono ini tidak dapat dikatagorikan anak di luar perkawinan sebagaimana yang ditunjuk Pasal 43 tersebut, melainkan anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah tangan sebagaimana telah di jelaskan di atas. Agar kasus ini tidak terulang, maka pasal-pasal tentang prosudur poligami dalam undang-undang perkawinan tersebut perlu ditinjau ulang, yang sebenarnya kasus-kasus seperti ini sangat banyak terjadi di masyarakat, hanya saja mereka tidak mempermasalahkannya dan atau tidak keberatan atas poligami tersebut, kehidupan diantara mereka tetap berlangsung dengan damai, hak dan kewajiban di antara mereka berjalan sebagai mana lazimnya. Apabila orentasi perombakan pasal ini ditujukan terhadap legalisasi nasab anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, maka implikasi negatifnya akan lebih dominan dari pada manfaat jaminan terhadap anak yang akan di raih. Implikasi negatif dalam contoh kasus di atas, tidak akan terlihat, karena ibu dan ayah biologis dari anak itu telah bersatu dalam ikatan perkawinan, akan tetapi pada kasus-kasus yang lain akan terlihat dengan jelas, misalnya A (istri) dan B (suami) di anatara mereka telah terjalin ikatan perkawinan dan telah memilik dua orang anak, yaitu C dan D, di pihak lain E (istri) dan F (suami) juga telah terjalin ikatan perkawinan dan telah memiliki dua orang anak, yaitu G dan H. Secara diam-diam F dan A menjalin hubungan intim sampai melakukan hubungan badan dan kemudian A melahirkan satu orang anak dari F yang bernama I, demikian pula B dan E 28 menjalin hubungan intim sampai melakukan hubungan badan dan E melahirkan seorang anak dari B yang bernama J, yang berarti I adalah anak dari ibunya A yang ayahnya F, berarti orang tua I itu adalah A dan F yang tidak memiliki hubungan ikatan perkawinan, demikian pula orang tua J adalah B dan E yang tidak memiliki hubungan ikatan perkawinan. Yang berarti dua keluarga ini akan membentuk empat keluarga secara silang. Masalah lain misalnya A (istri) B (suami) telah terikat perkawinan akan tetapi tidak memiliki anak, kerena B mandul, di pihak lain C (istri) dan D (suami) telah terikat perkawinan akan tetapi juga tidak memiliki anak, karena C mandul. Agar kedua keluarga ini sama-sama memiliki anak, maka terjadi kerja sama antara A dan D dengan melakukan hubungan badan, kemudian A melahirkan anak tiga orang yaitu E, F dan G, ketiga anak ini adalah anak silang yang dilahirkan A bukan dari suaminya, ayahnya adalah D yang tidak dilahirkan dari istrinya. Tatanan kehidupan pembentukan keluarga seperti ini pernah berlaku pada zaman jahiliyah dengan melegalisasikan nasab anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki yang tidak memiliki hubungan ikatan perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh Islam 46 hal-hal yang demikian akan berakibat pencemaran lembaga hukum perkawinan itu sendiri, mengacaukan silsilah keturunan, tidak terjamin adanya ketertiban umum dan akan melenyapkan sendisendi tatanan kehidupan manusia yang layak dan bermartabat. Mukti Arto, menyatakan bahwa adanya hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah karena semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan alasan sesuai pandangan ulama alHanafiyah bahwa dengan hubungan badan semata, telah menimbulkan hubungan mahram47 Argumentasi tersebut, tidak sesuai dengan teori fikih yang dibangun ulama terdahulu, karena hubungan mahram antara dua orang terdapat tiga penyebab, yaitu adanya hubungan badan (mushaharah), adanya hubungan nasab dan adanya hubungan sesusuan48 Muhammad Abu Zahrah49 menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya adalah melalui tiga sebab, yaitu disebabkan adanya hubungan kekerabatan (nasab), disebabkan adanya hubungan mushaharah dan disebabkan adanya hubungan sepersusuan. Yang dimaksud adanya hubungan mushaharah adalah istri-istri orang tua dan seterusnya ke atas, istri-istri dari anak cucu (keturunan), orang tua (para leluhur) dari istrinya dan anak cucu dari istri. Mukti Arto, menyatakan bahwa Abu Hanifah menafsirkan nikah yang dimuat dalam Surat al-Nisa ayat 22 dengan hubungan badan. Penafsiran yang demikian berakibat siapa saja perempuan yang telah disetubuhi orang tua baik dalam ikatan perkawinan, maupun di luar ikatan perkawinan adalah diharamkan untuk dinikahi oleh anaknya. Kebanyakan ulama mufassirin mengartikan an nakaaha dalam ayat itu adalah al-‘aqd ay nikaahu abaa’ikum al-faasid al-mukhalifu 46 Lihat Wahbah Al-Zuhaily, loc.cit halaman 675 Mukti Arto, loc. Cit. Halaman 15 yang dikutif dari Putusan MK halaman 35 48 Lihat Wahbah Al-Zuhaily, Op. Cit. Halaman 132 49 Muhammad Abu Zahrah, loc. Cit. Halaman 71-83 47 29 lidiinillah artinya akad ya’ni ikatan perkawinan ayah kamu yang fasiid yang bertentangan dengan agama Allah (Islam). 50 Demikian pula pengertian kalimat dakhaltum dalam Surat al-Nisa ayat 23: wa rabaa’ibukun allati fi hujuurikum min nisaa’ikum alllati dakhaltuim bihinna. Pengertian dakhaltum dalam ayat ini adalah ada sebagian ulama yang menduga syarat keharaman mushaharah dalam hal ini adalah hubungan badan baik yang dilakukan dengan istri-istrinya maupun dengan anak-anak tiri dari istrinya itu secara bersamaan. Penafsiran ini adalah penafsiran yang berasal dari khilasun dari ‘Aly bin Aby Thalib. Ibnu ‘Abas Jabir dan Zaid bin Tsabit, dan Mujaahid menyatakan hubungan badan pada kedua tempat itu (maksudnya istri dan anak). Jumhur Mufassirin menafsirkan ayat ini dengan tafsir yang berbeda yaitu dengan pengertian nikah yang sah, dan menurut Imam Syafi’iy keharaman mereka itu disebabkan adanya akad perkawinan yang sah, keharaman dalam ayat tersebut tidak sampai mengharamkan yang halal. 51 Mukti Arto 52 menegaskan bahwa analog dengan pendapat Abu Hanifah tersebut, maka hubungan darah menjadi dasar adanya hubungan perdata, yaitu hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak dan kewajiban, hubungan kewarisan dan hubungan perwalian. Dengan demikian menurut Mukti Arto hanya dengan hubungan badan menjadikan dasar adanya hubungan keperdataan, yaitu adanya hubungan nasab dan seterusnya.. padahal ayat al-Qur’an yang dibicarakan tersebut di atas, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, bertemakan mengenai hubungan mahram sebagai akibat adanya al-mushaharah, suatu hal yang tidak relevan akibat adanya al-mushaharah menjadi dasar adanya hubungan nasab. Tidak dimuat dalam teori fikih seorang yang karena adanya hubungan mushaharah, misalnya antara ibu tiri dengan anak tirinya, atau seorang menantu dengan ibu mertuanya, menjadikan mereka memiliki hubungan nasab, sehingga di antara mereka saling mewarisi. Kemudian Mukti Arto, mengutif ayat al-Qur’an Surat Al-Najm ayat 45-48, dan berdasarkan ayat al-Qur’an tersebut, Mukti Arto berkesimpulan bahwa dengan adanya hubungan darah akan berakibat menimbulkan hubungan hukum 53 kesimpulan ini adalah kesimpulan yang kurang tepat, sebab pada ayat ini tidak membicarakan hubungan darah menjadi penyebab adanya hubungan hukum, melainkan Allah mengkhabarkan tentang kekuasaan-Nya yang berhubungan dengan asal penciptaan atau asal kejadian manusia, kemudian manusia itu akan dikembalikannya lagi seperti sedia kala.54 Nilai-nilai yang dimuat hukum Islam yang bersifat universal dan berlaku global adalah nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua pihak, karena nilai-nilai itu berkaitan dengan prinsif hidup dan kehidupan secara menyeluruh demi menjunjung Lihat Al-Qurthuby, Al-Jamii’ Liahkaam Al-Qur’an (Bairut: Ihya al-Turats, 1985) Juz V halaman 103 51 Al-Qurthuby ibid halaman 106 52 Mukti Arto, loc. Cit. Halaman 16 53 Mukti Arti, ibid halaman 17 54 Ibnu Katsiir, menjelaskan bahwa Allah Kuasa menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan yang berasal dari air mani, kemudian dia meninggal dunia, setelah ia menyatu menjadi tanah, Allah Kuasa mengembalikannya seperti dalam keadaan semula, Ibnu Kasiir Tafsiir Al-Qur;an Al-‘Adhiim (Semarang, Maktabah wa Mathba’ah Toko Futra, tt) Juz VI halaman 259 50 30 tinggi harkat dan martabat manusia dimanapun dan kapanpun berada, ia tidak akan terpengaruh oleh apapun juga, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, tidak terpengaruh oleh keragaman budaya, ia tidak terpengaruh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara nilai-nilai yang berkaitan dengan nasab anak adalah prilaku prostitusti, kumpul kebo, atau sex bebas tidak dapat dibenarkan oleh aturan manapun, karena prilaku itu adalah pergaulan tanpa ikatan secara sah menurut hukum, oleh karena itu segala akibat dari pergaulan itu menjadi bebas nilai hukum, kedua belah pihak sebagai pelaku tidak akan berakibat adanya hak dan kewajiban, demikian pula terhadap sederetan akibat yang ditimbulkannya secara logis akan bebas nilai hukum pula, tidak akan pernah ada hak dan kewajiban. Apabila dibiarkan tetap terjadi seperti ini, maka apabedanya pergaulan kehidupan manusia ini dengan pergaulan dalam kehidupan binatang. Perampasan hak kepemilikan sebidang kebun orang lain tidak akan dibenarkan oleh aturan manapun, karena perampasan ini adalah pengalihan hak kepemilikan dengan tanpa adanya perikatan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu segala tanaman yang dihasilkan dari kebun itu, tidak akan pernah menjadi milik perampas walaupun benihnya milik perampas sendiri. Akibat adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya yang di lahirkan di luar perkawinan, yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara general baik terhadap anak sebagai akibat perzinaan, sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan, memilki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik 55 . Yang berkaitan dengan hak-hak anak menurut hukum adalah : 1. Hak Atas Nafkah56. Oleh karena status anak tersebut menurut hukum yang dimuat pada putusan MK mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya, maka yang wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut adalah ayahnya dan keluarga ayahnya. Baik sebagai ayah yang memiliki itakan perkawinan yang sah dengan ibunya maupun ayah/bapak alami (genetik), kewajiban tersebut adalah kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak. Karena anak dalam hal ini tidak berbeda dengan anak sah. Dengan demikian terhadap anak, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf © dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. 55 Putusan MK halaman 35 Yang dimaksud nafkah dalam hal ini adalah nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. 56 31 Pokok pikiran utama yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi yang merombak ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya adalah “tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya” pokok pikiran ini seolah-olah menjadi alasan yang mendasar bahwa seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan yang kemudian melahirkan anak, dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut akan melepaskan tanggung jawabnya sebagai ayah biologisnya, dengan demikian setelah ketentuan pasal tersebut di-review, ayah biologis tersebut dipaksa oleh hukum untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Seandainya putusan Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban nafkah, menurut penulis sifatnya kasuistik dan akan sejalan dengan logika hukum Islam, sebab masalah nafkah yang diperlukan untuk menunjang kehidupan anak, tidak ansih terkait dengan orang yang ada kaitannya dengan hubungan nasab, seperti apabila anak tersebut diangkat anak oleh orang lain, maka kewajiban nafkah akan beralih kepada ayah angkatnya, walaupun pada dasarnya pokok kewajiban itu dibebankan kepada orang yang terkait dengan hubungan nasab. Maka bila orentasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan seperti itu, menurut penulis dapat diterima, akan tetapi langkah terbaik bukanlah me-review pasal tersebut, melainkan cukup menambahkan satu ayat yang mebebankan tanggung jawab nafkah terhadap ayah yang menyebabkan anak lahir di luar perkawinan. Dengan penambahan ayat ini Mahkamah Konstitusi akan terlihat lebih bijak dan tidak akan mengundang polemik kontropersi yang berkepanjangan dalam masyarakat. 2. Hak Perwalian. Eksistensi wali dalam perkawinan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. Kemudian pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dari ketentuan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah ayah yang memilki hubungan nasab dengan anak perempuannya, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974, atau dengan kata lain anak perempuan itu lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan pasal ini melahirkan kaidah hukum bahwa 32 adanya hubungan hukum (nasab) antara seorang anak dengan kedua orang tuanya dan menyebabkan adanya hak wali terhadap ayahnya adalah disebabkan adanya ikatan perkawinan yang sah57 dan anak itu lahir dalam ikatan perkawinanya. Dengan demikian kelahiran anak selain yang ditentukan dalam aturan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan berakibat hukum ayah dalam kondisi seperti ini tidak berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan anak perempuannya, dan hak perwalian anaknya itu berada pada wali hakim. Karena Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak di-review oleh Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut tetap berlaku dan mengikat semua pihak. Oleh karena itu Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1Tahun 1974 yang telah di-review, menjadi anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan ayahnya serta dengan keluarga ibu dan ayahnya. Hubungan perdata dimaksud kecuali dalam hal wali nikah, yang berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan adalah wali hakim. 3. Hak Kewarisan. Kaidah umum yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam yang berkaitan dengan kualifikasi orang sebagai ahli waris yang disepakati ulama adalah orang yang memiliki hubungan nasabiyah (hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan yang sah), hubungan zaujiyah (perkawinan) dan hubungan al-wala (pelepasan status seseorang dari perbudakan). Berkaitan dengan hak kewarisan anak dari ayahnya adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena itu yang dimaksud anak dalam hubungan kewarisan adalah anak yang ditunjuk dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, termasuk di dalamnya anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan keabsahannya di akui oleh hukum karena dilakukan sesuai prosudur hukum, maupun dalam ikatan perkawinan yang sah tapi keabsahannya tidak diakui oleh hukum karena perkawinannya tidak memenuhi prosudur hukum, sepanjang keberadaannya tidak ada pihak lain yang keberatan. Dengan demikian ketentuan Pasla 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di-review oleh Mahkamah Konstitusi menjadi anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan ayahnya serta dengan keluarga ibu dan ayahnya. Hubungan perdata dimaksud juga dikecualikan dalam hak kewarisan. III. KESIMPULAN Dari pembahasan-pembahasan tersebut, penulis dapat mencatat beberapa kesimpulan, yaitu: 57 Ikatan perkawinan yang sah dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai hukum masingmasing agamanya, bagi orang Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu ayah yang berhak menjadi wali dalam kajian ini adalah ayah yang terikat hubungan perkawinan dengan ibu yang melahirkan anaknya itu, baik perkawinannya itu memenuhi prosudur hukum yang dalam perkawinan monogami dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam perkawinan poligami mendapatkan izin dari pengadilan kemudian dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maupun tidak memenuhi prosudur hukum seperti dalam perkawinan monogami di bawah tangan atau perkawinan poligami di bawah tangan. 33 1. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yang mengandung cacat hukum. Kasus yang didalilkan Pemohon adalah kasus anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan yang menurut hukum yang berlaku masih dimungkinkan mendapatkan jaminan hukum, sedangkan yang dimohonkan adalah me-review ketentuan Pasal 2 ayat (2) juga ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang status hukum anak yang lahir di luar perkawinan. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi menganalogikan anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan dengan anak yang lahir di luar perkawinan, padahal kedua status anak ini berada pada dua substansi yang berlainan menurut hukum. 3. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang senada dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, substansinya tidak bertentangan dan atau sebenarnya sejalan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga sejalan dengan Syari’at Islam. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan terutama dengan Pasal 28 B ayat (1) UUD 45 dan bertentangan dengan Syari’at Islam. Oleh karena itu putusan MK ini akan mengundang polemik dalam masyarakat muslim yang berkepanjangan. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan ta’at hukum, melainkan berupaya melegalisasikan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. 6. Pasal 43 ayat (1) yang telah di-review oleh putusam Makhama Konstitusi hanya berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam kewarisan. IV DAFTAR PUSTAKA Abd Al-Rahman Al-Jaziiry, Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzaahib Al-Arba’ah, Jilid V (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra’, tt) halaman 57 Abd Al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiq (Barirut: Dar al-Fikr. 1991), halaman 176 Aby Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-‘Anshary Al-Qurthuby, Al-Jamii’ Liahkaam Al-Qur’an (Bairut: Ihya al-Turats, 1985) Juz V halaman 103 Al-Imam Al-Jaliil Al-Hafidh Imaad Al-Din Aby Al-Fidaa’ Ismaa’il bin Katsir (Ibnu Kasiir) Tafsiir Al-Qur;an Al-‘Adhiim (Semarang, Maktabah wa Mathba’ah Toko Futra, tt) Juz VI halaman 259 DR. Wahbah al-Zuhaily, fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984) Juz VII halaman 675 DR. Wahbah al-Zuhaily, fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984) Juz VII halaman 675 DR. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) halaman 17 34 Imam Al-Sayuthi, Al-Isybah Wa al-Nadha’ir, (Bairut: al-Maktabah, 1989). halaman 397 Lahmudin Nasutioan, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi’I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), halaman 127 Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwaal al-Syakhshiyah, (Bairut: Dar Alfikr al-‘Araby 1957) halaman 404. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Bairut: Dar Al-fikr, 198) halaman 278. Muhammad Aly Al-Shabuny, Rawa’i al-Bayan bi tafsiir ayat al-Ahkam min AlQur’an, Juz II, halaman 52. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUUVIII/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tangal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon) halaman 1 Prof. DR. H. Satria Effendi M.Zein, MA, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer,(Jakarta: Prenada Media, cet. II 2006) halaman 33-37. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.