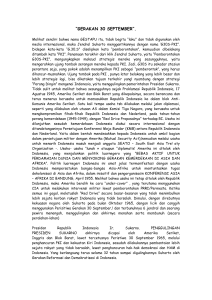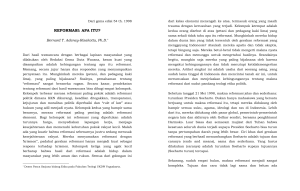MEMBANGUN PUBLIK:
advertisement
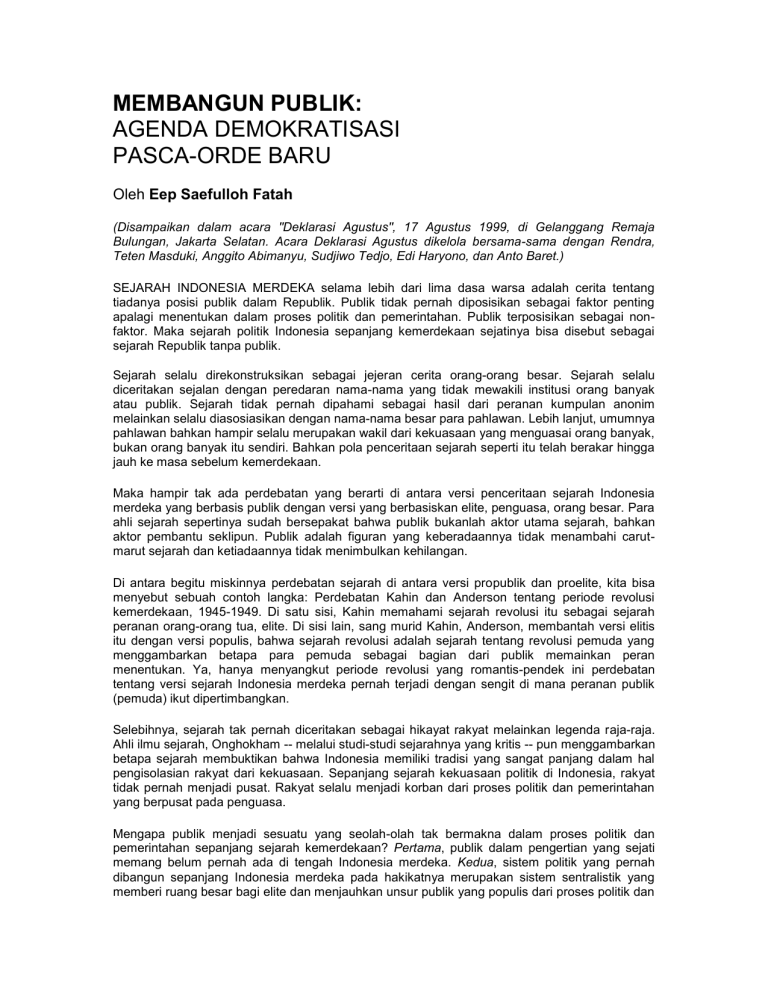
MEMBANGUN PUBLIK: AGENDA DEMOKRATISASI PASCA-ORDE BARU Oleh Eep Saefulloh Fatah (Disampaikan dalam acara "Deklarasi Agustus", 17 Agustus 1999, di Gelanggang Remaja Bulungan, Jakarta Selatan. Acara Deklarasi Agustus dikelola bersama-sama dengan Rendra, Teten Masduki, Anggito Abimanyu, Sudjiwo Tedjo, Edi Haryono, dan Anto Baret.) SEJARAH INDONESIA MERDEKA selama lebih dari lima dasa warsa adalah cerita tentang tiadanya posisi publik dalam Republik. Publik tidak pernah diposisikan sebagai faktor penting apalagi menentukan dalam proses politik dan pemerintahan. Publik terposisikan sebagai nonfaktor. Maka sejarah politik Indonesia sepanjang kemerdekaan sejatinya bisa disebut sebagai sejarah Republik tanpa publik. Sejarah selalu direkonstruksikan sebagai jejeran cerita orang-orang besar. Sejarah selalu diceritakan sejalan dengan peredaran nama-nama yang tidak mewakili institusi orang banyak atau publik. Sejarah tidak pernah dipahami sebagai hasil dari peranan kumpulan anonim melainkan selalu diasosiasikan dengan nama-nama besar para pahlawan. Lebih lanjut, umumnya pahlawan bahkan hampir selalu merupakan wakil dari kekuasaan yang menguasai orang banyak, bukan orang banyak itu sendiri. Bahkan pola penceritaan sejarah seperti itu telah berakar hingga jauh ke masa sebelum kemerdekaan. Maka hampir tak ada perdebatan yang berarti di antara versi penceritaan sejarah Indonesia merdeka yang berbasis publik dengan versi yang berbasiskan elite, penguasa, orang besar. Para ahli sejarah sepertinya sudah bersepakat bahwa publik bukanlah aktor utama sejarah, bahkan aktor pembantu seklipun. Publik adalah figuran yang keberadaannya tidak menambahi carutmarut sejarah dan ketiadaannya tidak menimbulkan kehilangan. Di antara begitu miskinnya perdebatan sejarah di antara versi propublik dan proelite, kita bisa menyebut sebuah contoh langka: Perdebatan Kahin dan Anderson tentang periode revolusi kemerdekaan, 1945-1949. Di satu sisi, Kahin memahami sejarah revolusi itu sebagai sejarah peranan orang-orang tua, elite. Di sisi lain, sang murid Kahin, Anderson, membantah versi elitis itu dengan versi populis, bahwa sejarah revolusi adalah sejarah tentang revolusi pemuda yang menggambarkan betapa para pemuda sebagai bagian dari publik memainkan peran menentukan. Ya, hanya menyangkut periode revolusi yang romantis-pendek ini perdebatan tentang versi sejarah Indonesia merdeka pernah terjadi dengan sengit di mana peranan publik (pemuda) ikut dipertimbangkan. Selebihnya, sejarah tak pernah diceritakan sebagai hikayat rakyat melainkan legenda raja-raja. Ahli ilmu sejarah, Onghokham -- melalui studi-studi sejarahnya yang kritis -- pun menggambarkan betapa sejarah membuktikan bahwa Indonesia memiliki tradisi yang sangat panjang dalam hal pengisolasian rakyat dari kekuasaan. Sepanjang sejarah kekuasaan politik di Indonesia, rakyat tidak pernah menjadi pusat. Rakyat selalu menjadi korban dari proses politik dan pemerintahan yang berpusat pada penguasa. Mengapa publik menjadi sesuatu yang seolah-olah tak bermakna dalam proses politik dan pemerintahan sepanjang sejarah kemerdekaan? Pertama, publik dalam pengertian yang sejati memang belum pernah ada di tengah Indonesia merdeka. Kedua, sistem politik yang pernah dibangun sepanjang Indonesia merdeka pada hakikatnya merupakan sistem sentralistik yang memberi ruang besar bagi elite dan menjauhkan unsur publik yang populis dari proses politik dan pemerintahan. Ketiga, akibat dari dua hal itu, politik tidak pernah bisa dikondisikan sebagai hubungan tawar menawar antara elite penguasa versus publik dalam kerangka mekanisme pertannggungjawaban publik (public accountability). Menurut hemat saya, ketiga soal mendasar itulah yang bisa dijadikan potret buram demokrasi Indnesia sepanjang kemerdekaannya. Memetakan wilayah kerja demokratisasi pasca-Orde Baru berarti membuat anatomi mengenai ketiga hal di atas; dan mengagendakan demokratisasi berarti mengubah ketiganya. Dalam konteks ini, demokratisasi politik sebetulnya sama artinya dengan memposisikan publik dalam Republik. Publik Apakah sejatinya publik itu? Apakah setiap kerumunan massa dengan sendirinya dapat diidentifikasi sebagai publik? Apakah massa yang diam dapat disebut sebagai publik? Apakah publik dilahirkan secara alamiah dan begitu saja di semua sistem politik dan karenanya tidak perlu dibangun? Publik yang sejati bukanlah kategori pasif melainkan aktif. Publik bukanlah kerumunan massa yang diam. Publik tidak pernah dilahirkan secara begitu saja dalam masyarakat melainkan selalu hasil proses bentukan sosial. Publik bukanlah sesuatu yang alamiah dalam setiap sistem politik, melainkan sesuatu yang harus dibentuk secara sosiologis. Publik adalah warga negara yang memiliki kesadaran akan dirinya, hak-haknya, kepentingankepentingannya. Publik adalah warga negara yang memiliki keberanian menegaskan eksistensi dirinya, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingankepentingannya terakomodasi. Dalam konteks ini, ada atau tidaknya publik di satu tempat, dalam satu sistem politik, bisa diukur dari ada tidaknya kepekaan masyarakat di tempat itu terhadap penindasan. Dengan demikian, ketiadaan perlawanan pada bentuk-bentuk penindasan di satu tempat merupakan indikasi bahwa tak ada publik di tempat itu. Karena itu, publik bukanlah kategori pasif melainkan aktif. Publik tidak ditandai oleh wujud fisik kerumunan manusia melainkan oleh ada tidaknya aktivitas politik dari kerumunan itu. Salah satu catatan buram kemerdekaan Indonesia selama ini adalah gagalnya proyek pembentukan publik semacam itu. Sentralisasi dan Terabaikannya Mekanisme Pertanggungjawaban Publik Rezim Sukarno maupun Soeharto adalah rezim yang bekerja di atas prinsip sentralisasi yang menindas keanekaan, individu, komunitas, dan lokalitas. Soekarno di atas jargon revolusi yang belum selesai dan dengan kerangka Demokrasi Termpimpin. Sementara Soeharto dengan jargon pembangunan atau stabilitas dan pertumbuhan dalam kerangka Orde Baru. Melalui Demokrasi Terpimpin, Sukarno menjalankan sentralisasi dengan biaya mahal berupa matinya demokrasi. Maka Sukarno, sekalipun dengan simbol-simbol populismenya, sejatinya mematikan publik. Soeharto dan Orde Barunya kemudian menjalankan praktik serupa dengan cara dan jubah berbeda. Memahami matinya publik dapat dilakukan dengan memahami rezimentasi yang dilakukan Orde Baru di bawah Soeharto. Rezimentasi selama masa Orde Baru dapat dibagi ke dalam lima fase. Fase pertama adalah fase konsolidasi awal rezim (1967-1974). Dalam fase ini rezim Orde Baru baru saja terbentuk dan sedang menata aliansi di dalam dirinya secara internal. Dalam fase ini, Soeharto belum menjadi siapa-siapa, bahkan pada awalnya kurang diperhitungkan oleh banyak orang. Soeharto masih menjadi bagian dari kekuatan politik militer secara kolektif; belum menjadi kekuatan politik mandiri. Fase rezimentasi ini tersokong oleh kemenangan mutlak Golkar -- memperoleh 62,8% suara -- dalam Pemilu 1971 yang dipenuhi represi, mobilisasi, serta ketiadaan kompetisi terbuka dan sehat. Peristiwa Malari 1974 kemudian melangkahkan kaki Orde Baru ke fase kedua (1974-1978). Dalam awal fase kedua ini, Soeharto disadarkan bahwa kedudukan politiknya sebagai presiden dan penguasa sebetulnya goyah dan sangat rentan oleh konflik intra-elite negara -- sebagaimana tercermin dari konflik Soemitro-Ali Moertopo. Maka Soeharto melakukan seleksi-ulang orangorang di sekelilingnya dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik mandiri. Jika dalam fase pertama terjadi penyingkiran elite politik gelombang pertama (Nasution dkk), maka dalam fase kedua terjadi penyingkiran elite politik gelombang kedua dalam skala lebih besar dan dramatis (Soemitro dkk). Dalam fase ini Soeharto menata kekuasaan Orde Baru untuk mempertinggi soliditas penguasaan militer atas Orde Baru sekaligus mulai membangun dirinya sebagai kekuatan politik mandiri. Munas II Golkar pada tahun 1978 di Denpasar menandai berhasilnya upaya Soeharto di atas dan membawa Orde Baru ke fase ketiga rezimentasi dirinya (1978-1985). Munas II Golkar itu menyepakati pembesaran kekuasaan Dewan Pembina yang memusat pada Ketua Dewan Pembina (Soeharto). Maka mulai saat ini Soeharto berhasil menjadikan Golkar sebagai instrumen politik yang langsung dikendalikan olehnya. Mulailah kekuasaan personal Soeharto terbentuk dalam rezim Orde Baru. Faksionalisme politik di dalam elite politik mulai sulit terbentuk karena tidak diberi peluang pembentukannya oleh Soeharto. Fase ini bisa disebut sebagai fase personalisasi dan sakralisasi kekuasaan Soeharto. Konfigurasi kekuasaan Orde Baru makin mengerucut ke dalam tangan pengendalian Soeharto; elemen-elemen kekuasaan Orde Baru lain praktis sudah berada di bawah penguasaan Soeharto secara hampir penuh Fase keempat rezimentasi Orde Baru terjadi antara 1985-1990. Awal fase ini ditandai oleh diundangkannya Paket UU Pembangunan Politik -- tentang partai politik, organisasi kemasyarakatan, pemilihan umum, susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPRD, dan referendum - yang melegalisasi format politik yang diinginkan dan dibangun oleh Soeharto. Dalam fase ini format politik Orde Baru yang otonom (dalam arti “antipartisipasi masyarakat”) dan sentralistis, bisa dikatakan “telah selesai pembentukannya”. Penguasaan Soeharto terhadap seluruh elemen kekuasaan Orde Baru makin menguat, terlebih-lebih setelah mulai terbentuk konglomerasi Keluarga Cendana. Fase kelima (1990-1998) ditandai oleh dipakainya simbol Islam sebagai identitas baru Soeharto dan Orde Baru. “Islamisasi” -- dalam pengertian sekadar simbolik -- ini memberikan basis legitimasi moral bagi Orde Baru tanpa mengubah karakter kekuasaannya sama sekali. Maka dalam fase ini, terjadi perubahan basis dukungan politik bagi Soeharto. Kalangan Islam-politik menjadi pilar baru yang penting. Fase ini juga ditandai oleh mulai munculnya tanda-tanda keretakan elite politik lantaran dua sebab: (1) konsekuensi dari naik daunnya tokoh-tokoh Islam-politik dan terkecewakannya tokohtokoh non-Islam-politik; dan (2) mulai rapuhnya usia biologis Soeharto yang membuat wacana suksesi kepempinan nasional -- beserta fenomena aliansi dan realiansi elite politik di dalamnya -makin menjadi wacana umum. Sekalipun demikian, faksionalisme politik di tubuh elite tidak dapat menemukan peluang untuk mengemuka dan memperlihatkan dirinya secara tegas karena tertelan oleh sosok Soeharto yang -- dengan basis kekuasaan politik dan ekonominya -- sudah menjadi Haji Muhammad the untouchable Soeharto. Soeharto jatuh dalam posisi seperti ini. Kelima fase yang dijalani Orde Baru di atas telah menghasilkan empat karakter operasi kekuasaan Orde Baru yang berpusat pada Soeharto. Pertama, sentralistis. Kekuasaan dikendalikan secara sentralistis dengan alasan pembangunan ekonomi dan stabilisasi. Kedua, personal. Setelah berkuasa selama 11 tahun (1967-1978) Soeharto berhasil mengambil alih kendali Orde Baru ke bawah tangannya. Kekuasaan kemudian mengalami personalisasi, terlebihlebih setelah Soeharto -- melalui putra-putrinya -- juga semenjak pertengahan 1980-an meluaskan kekuasaannya ke wilayah ekonomi. Ketiga, sakral. Kekuasaan yang telah mengalami sentralisasi, dan personalisasi, akhirnya tak terbendung -- sebagaimana telah banyak terbuktikan dalam hukum besi sejarah otoritarianisme di mana pun -- mengalami sakralisasi. Kekuasaan menjadi sakral, tidak bisa tersentuh, tidak bisa salah atau disalahkan, steril dari dosa. Kekuasaan yang sakral bahkan telah diposisikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah bukan fenomena kerja manusia biasa. Akhirnya, keempat, otonom. Kekuasaan Orde Baru bekerja dengan menghilangkan peluang bagi terbentuknya publik serta bagi meluasnya partisipasi publik. Kekuasaan bekerja dengan logikanya sendiri; otonom dari kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan Demokrasi Terpimpin-nya Sukarno, Orde Baru-nya Soeharto akhirnya bermuara pada matinya publik. Sentralisasi kekuasaan itu, baik di masa Sukarno maupun Soeharto, menuntut biaya yang sangat mahal. Ada tiga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai sentralisasi beserta instrumeninstrumennya: tidak tegaknya konstitusionalisme, terabaikannya etika dan moralitas politik; dan tidak berjalannya mekanisme pertanggungjawaban publik. Penguasa, parlemen, partai politik, birokrasi, dan lembaga-lembaga politik lainnya tidak merasa perlu melakukan pertanggungjawaban pada publik. Publik diperlakukan seolah-olah tak ada dan tidak diperlukan. Publik hanya dimanfaatkan untuk membangun legitimasi semu melalui proses pemilihan umum yang juga semu. Demokratisasi: Pendirian Institusi Publik Memposisikan publik dalam Republik sebagai hakikat demokratisasi berarti mendirikan institusiinsitusi publik. Kehadiran institusi publik tidak dapat dirasakan melalui papan nama, label, atau pengatasnamaan. Kehadiran institusi publik terasakan melalui terakomodasinya kepentingan publik dalam proses dan hasil kerja institusi itu. Partai politik an sich bukanlah institusi publik. Tetapi partai politik yang berorientasi pada kepentingan publik(-nya sendiri-sendiri) adalah institusi publik. Sebagai institusi publik, partai tak menggunakan mekanisme kedaulatan partai atau kedaulatan pengurus partai melainkan kedaulatan publik yang menjadi basis pendukung atau konstituennya. Demokratisasi menuntut partai politik yang ada sekarang menjadi institusi publik semacam itu. Partai-partai yang kemudian tinggi hati berhadapan dengan publik dan tuli pada aspirasi publik semestinya tidak memperoleh tempat dalam demokrasi. Bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, komite-komite aksi, dan institusi-institusi yang mengatasnamakan publik lainnya, an sich, bukanlah institusi publik sebelum mereka benar-benar menjadikan publik sebagai pelaku terpenting sekaligus orientasi di dalam aktivitasnya. Dalam konteks itu, membangun institusi-institusi publik berarti mereorientasikan berbagai organisasi dan komite itu sehingga tak lagi sekedar mengatasnamakan publik. Bahkan parlemen, birokrasi dan lembaga-lembaga formal kenegaraan lainnya, pada sejatinya perlu dijadikan sebagai institusi publik. Mereka semestinya menjadi perpanjangan tangan publik sekaligus melayani kepentingan-kepentingan publik. Pun tentara. Menghentikan politik tentara merupakan langkah reorientasi tentara ke khittah 1945, yakni menjadikan kembali mereka sebagai tentara rakyat yang berjuang membela negara, bukan menyokong pemerintah belaka, dan karenanya berjuang menjadi pembela publik. Tentara yang menjadi musuh publik adalah tentara yang menyalahi kodratnya. Pun oposisi, seyogianya dibangun sebagai institusi publik. Oposisi bisa efektif sebagai pendorong demokratisasi manakala mampu mempertahankan dua karakteristik utamanya: bekerja berbasis moralitas politik (tak sekadar anti-incumbency atau antipejabat yang sedang berkuasa melainkan prodemokrasi); dan otentik. Oposisi yang otentik adalah oposisi yang benarbenar berbasiskan publik. Oposisi menjadi otentik manakala ia atau mereka tak sekadar mengatasnamakan publik untuk membuatnya menjadi lebih gagah. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap oposisi tiban yang berdiri beramai-ramai setelah Soeharto jatuh -sementara mereka sendiri pernah menjadi bagian yang langsung dan nikmat dari kekuasaan Soeharto -- adalah konsekuensi dari ketidakotentikan oposisi. Maka membangun institusi-institusi publik berarti mengelola tiga bentuk pergeseran serius dalam proses dan produk institusi-institusi sosial-politik-ekonomi-budaya yang sudah tersedia saat ini. Yakni pergeseran serius dari prinsip totalitas ke pluralitas, perwalian ke perwakilan, pemanjaan ke pertanggungjawaban. Institusi sosial-ekonomi-politik-budaya mesti meninggalkan prinsip dasar kerja mereka yang lama, yakni prinsip totalitas. Selama ini institusi-institusi itu didirikan dengan tendensi menyeragamkan. Prinsip totalitas semacam ini mesti diubah menjadi prinsip pluralitas. Institusi justru berdiri untuk mewadahi keanekaan dan membiarkan keanekaan itu menjadi energi pokok dari pertumbuhan institusi. Partai politik, LSM, organisasi kemasyarakatan, komite-komite, parlemen, dan lain-lain seyogianya tumbuh di atas prinsip pluralitas seperti ini. Prinsip kerja institusi sosial-politik-ekonomi-budaya juga perlu diubah dari perwalian ke perwakilan. Dalam prinsip perwalian, pelaku ekonomi-sosial-politik-budaya merasa lebih tahu dari publik -- bahkan dalam hal apa yang diinginkan publik itu -- karena itu mereka tak merasa perlu membangun hubungan intens dengan publik. Mereka menempatkan dirinya sebagai wali dari publik. Ini mesti diubah menjadi perwakilan publik. Setiap pelaku memposisikan dirinya sebagai representasi atau wakil dari publik dan karenanya merasa perlu untuk terus menerus berkonsultasi dengan publik bahkan ada di tengah publik yang mereka wakili. Begitulah aktivis partai politik dan anggota parlemen -- sekadar menyebut misal -- mesti memposisikan dirinya bukan sebagai wali tetapi wakil. Dalam kerangka itulah, kerja institusi sosial-ekonomi-politik-budaya seyogianya diorientasikan dari model "pemanjaan publik" ke "pertanggungjawaban publik". Dalam model pemanjaan publik, para pelaku sosial-ekonomi-politik-budaya memanfaatkan keterbelakangan-keterbelakangan -semacam ketidaksadaran dan ketidakberanian publik -- untuk kepentingan mereka. Ini seyogianya diorientasikan menjadi model pertanggungjawaban publik. Mereka justru memposisikan dirinya sebagai pihak yang harus terus menerus mempertanggungjawabkan segala hal yang mereka lakukan pada publik. Para pemimpin misalnya, alih-alih memanfaatkan pemanjaan publik, justru mesti membangun hubungan pertanggungjawaban dengan publik. Pemimpin yang seenaknya saja mengambil sikap atau kebijakan publik tanpa memahami kepentingan publik mestinya tak diberi tempat lagi dalam demokrasi. Demokratisasi: Merebut Ruang Publik Memposisikan publik dalam Republik atau demokratisasi membawa tuntutan pekerjaan jangka pendek, yakni merebut dan menciptakan ruang-ruang publik. Sejarah demokratisasi yang sejati di mana-mana tidak pernah memperlihatkan adanya proses penghadiahan ruang publik. Ruang publik tidak pernah merupakan bingkisan melainkan sesuatu yang mesti direbut bahkan diciptakan. Ruang publik adalah tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka. Ruang publik bisa berwujud kebebasan pers, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi daerah, independensi dan keadilan sistem hukum. Perebutan ruang-ruang publik itu adalah agenda demokratisasi jangka pendek atau setidaknya menengah. Dalam kasus Portugal setelah Revolusi Bunga 1974, perebutan ruang publik dilakukan dan berhasil diperoleh selama sekitar tujuh tahun, dan kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi sistem politik baru yang demokratis. Dalam kasus Filipina, perebutan ruang publik membutuhkan waktu satu periode kepemimpinan Presiden Cory Aquino semenjak 1986. Dalam kasus Afrika Selatan pasca politik Apartheid, perebutan ruang publik terjadi secara dramatis di bawah kepemimpinan Nelson Mandela dalam waktu yang lebih pendek. Dalam kasus Uni Soviet, perebutan ruang publik dalam bentuk gerakan Perestroika dan Glasnost terjadi dalam waktu yang lebih pendek lagi semenjak 11 Maret 1985 dan berujung pada runtuhnya Uni Soviet Komunis pada akhir dekade 1980-an. Belajar dari pengalaman-pengalaman perebutan dan penciptaan ruang-ruang publik di sejumlah tempat di dunia dalam abad ke-20 ini, berarti menemukan beberapa pola. Pertama, pola revoluisoner. Sistem politik mengalami pergantian rezim secara total. Bisa total dalam arti seluruh elemen rezim baru benar-benar bersih dari unsur lama seperti di Afrika Selatan pasca politik Apartehid. Atau total dalam arti kepemimpinan rezim yang baru benar-benar menggalang rezimentasi yang bertentangan dengan rezim sebelumnya, seperti Uni Soviet di bawah Gorbachev. Dalam pola revolusioner ini perebutan ruang publik menjadi pekerjaan rezim baru yang bertaubatan nasuha. Dalam pola ini ruang-ruang publik bisa ada dalam posisi rentan manakala pergantian rezim kembali terjadi secara total. Rezim baru bisa saja kembali menutup ruang-ruang publik yang sudah mulai terbangun. Dalam pola ini, keterjagaan ruang publik hanya mungkin manakala di tengah perubahan revolusioner itu tumbuh gerakan sosial yang punya kapabilitas memadai. Kedua, pola persekutuan unsur reformis horizontal dan vertikal. Dalam pola ini, gerakan sosial membangun persekutuan horizontal (antarmereka) secara kuat dan bersekutu dengan agenagen reformis dalam kekuasaan. Dalam pola ini, perebutan ruang publik dimungkinkan oleh adanya gerak persekutuan di antara kekuatan politik kaki lima (gerakan sosial) dengan kubu reformis dalam blok kekuasaan negara. Ketiga, pola pertarungan vertikal. Dalam pola ini, perebutan ruang publik terjadi dalam bentuk gerakan sosial melawan kekuasaan atau rezim. Rezim yang bersikukuh makin lama makin terdesak oleh gerakan sosial yang menguat dan mengeras. Ruang-ruang publik terbangun sebagai buah keringat gerakan sosial. Dalam ketiga pola yang tersedia, variabel yang senantiasa harus ada adalah gerakan sosial. Dalam konteks ini, penguatan gerakan sosial merupakan agenda demokratisasi yang sulit ditawar. Demokratisasi: Penguatan Gerakan Sosial Memposisikan publik dalam Republik berarti memperkuat gerakan sosial. Gejala ke arah penguatan gerakan sosial ini sebetulnya telah ada bahkan semenjak Soeharto masih berkuasa. Dalam saat-saat akhir kekuasaan Soeharto, kemunculan, pengerasan, dan penguatan gerakan sosial tergambar melalui bangkitnya "kelas menengah politik", yakni anggota komunitas terdidik di perkotaan yang menjadikan kritisisme sebagai basis politik mereka. Kelas menengah politik ini dapat dibedakan dengan konsep kelas menengah yang lazim disebut oleh literatur ilmu sosial, terutama karena tidak membangun daya tawarnya vis a vis negara melalui modal. Mereka membangun daya tawarnya melalui intelektualitas dan organisasi politik. Kelas menengah politik itulah yang dalam tujuh atau delapan tahun terakhir kekuasaan Soeharto memperlihatkan gejala politisasi dan menjadi lebih artikulatif. Mereka membawa wacana yang sangat beragam -- termasuk wacana relatif baru semacam feminisme -- dan mengagendakan demokratisasi sebagai target gerakan. Bentuk artikulasi mereka terutama terwadahi dalam organisasi non-pemerintah (non-government oragnization, NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama LSM generasi ketiga dan keempat yang makin struktural pendekatannya dan mengalami politisasi secara tegas. Selain itu, mereka juga mengartikulasikan desakan ke arah demokratisasi melalui organisasi yang lebih bersifat politis ketimbang LSM. Misalnya dalam bentuk partai politik baru seperti yang diperlihatkan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) di bawah Budiman Sujatmiko, Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) di bawah Sri Bintang Pamungkas, dan Partai Mahasiswa ProDemokrasi (PMPD) di Ujung Pandang yang abortif. Bentuk artikulasi politik nonpartai juga terlihat seperti diwakili oleh lahirnya dan berkiprahnya serikat buruh alternatif (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia-nya Muchtar Pakpahan dan Serikat Buruh Merdeka Setia Kawannya HJC Princen), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), atau Majelis Rakyat Indonesia (MARI). Artikulasi kalangan ini bahkan sempat memiliki akses ke tataran politik formal ketika kepemimpinan Megawati Sukarnoputri dalam PDI masih diakui pemerintah. Dalam bentuknya yang lebih cair, politisasi gerakan sosial serupa terlihat di kalangan mahasiswa. Sekalipun pada tahun 1990-an ini kelompok studi sudah makin surut peranannya dan organisasi formal intra-kampus tidak juga bisa merevitalisasi diri setelah diperbolehkan kembali memiliki organ tingkat universitas, di kampuskampus muncul politisasi melalui pelbagai komite aksi. Dalam konteks itu, kritisisme dan radikalisme politik kemudian terlihat secara semakin tegas di kalangan mahasiswa -- sekalipun tidak setegas di masa awal Orde Baru (akhir 1960-an dan awal 1970-an) atau di penghujung 1970-an. Tumbuh, mengeras, dan menguatnya gerakan sosial juga terlihat di komunitas Islam, baik di kalangan modernis, neomodernis, maupun transformatif. Sebagaimana digambarkan Anders Uhlin dalam studinya tentang oposisi demokratis di Indonesia, dalam komunitas inipun tumbuh tuntutan demokratisasi. Tuntutan ini, menurut Uhlin, dalam batas tertentu diwadahi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) -- sekalipun wujudnya masih sangat kabur -- serta oleh organisasiorganisasi-organisasi massa lain yang berskala lebih kecil. Di kalangan Islam, dalam beberapa tahun belakangan ini, gerakan sosial bahkan mengartikulasikan diri dalam bentuk pengorganisasian massa -- sekalipun dengan isu-isu yang masih primordial dan tidak struktural. Dalam bentuk yang juga cair, gerakan sosial tumbuh di kantong-kantong kesenian dan kerjakerja kebudayaan. Telah cukup lama kalangan seniman dan budayawan membangun perlawanan terhadap rezimentasi di bawah kendali Soeharto. Mereka membangun pusat-pusat perlawanan dengan menggunakan kesenian dan kegiatan budaya -- dalam arti sempit -- sebagai instrumennya. Di saat-saat yang sangat dramatis menjelang kejatuhan Soeharto pada paruh pertama tahun 1998, gerakan sosial juga mengemuka sebagai alat desak yang efektif. Kemunculan gerakan sosial pasca Soeharto kemudian terjadi secara lebih dramatis. Dalam catatan Litbang Harian Kompas, misalnya, sepanjang Mei 1998 - Februari 1999 saja, tumbuh 181 partai politik di Indonesia. Belum lagi, gerakan-gerakan sosial yang memakai bentuk yang lebih nonformal semacam LSM, komite aksi, dan aksi-aksi sporadis. Gejala-gejala itulah yang kemudian menerbitkan optimisme pada kalangan tertentu bahwa gerakan sosial sedang tumbuh di Indonesia dan pada gilirannya bakal bisa mendesakkan demokratisasi. Sejauh pengamatan saya, optimisme ini sebetulnya masih mengidap sejumlah soal. Pertama, sekalipun kuantitas gerakan sosial berkembang selama tahun 1990-an, namun sejauh ini perkembangan kuantitatif itu belum diikuti oleh perkembangan kualitatif. Gerakan sosial masih menjadi gerakan sporadis, dan ad hoc. Kedua, gerakan sosial sejauh ini masih terjebak untuk sibuk merumuskan titik temu-titik temu artifisial dan sebaliknya kurang tertarik untuk mengatasi titik pecah-titik pecah substantif. Keadaan yang memang tertopang oleh kebijakan depolitisasi Orde Baru ini kemudian melembagakan miskomunikasi antarsegmen gerakan sosial hingga hari ini. "Sayap kanan" mencurigai "sayap kiri" sebagai destruktif, sebaliknya "sayap kiri" mencurigai "sayap kanan" sebagai pengkhianat kalangan progresif. Jika keadaan ini terus bertahan, sulit membayangkan gerakan sosial bisa menjadi kekuatan pendorong demokratisasi yang efektif. Ketiga, masih berkait dengan soal "kedua", daya dorong gerakan sosial bagi demokratisasi juga tereduksi secara internal oleh belum menggejalanya konvergensi di antara kelompok pendukung replacement (perubahan dengan penggantian rezim) dengan pendukung transplacement (perubahan sebagai hasil aliansi gerakan sosial dan faksi reformis dalam negara). Alih-alih konvergensi, yang terlihat adalah saling menjauh di antara dua kubu itu. Secara umum, gerakan sosial kubu transplacement dan replacement masih bekerja sendiri-sendiri dan dalam kasus tertentu saling kontraproduktif. Jika keadaan ini terus berlarut-larut, sulit mengharapkan gerakan sosial bisa memperkuat diri dan akhirnya mendorong demokratisasi. Keempat, di kalangan gerakan sosial terdapat potensi besar untuk melakukan radikalisasi tergopoh-gopoh, yakni menjadi radikal untuk radikal, bukan untuk mencapai target politik secara efektif. Kecenderungan radikalisasi semacam ini membuka peluang bagi kekuasaan untuk melakukan radikalisasi serupa guna menghentikan radikalisasi produk gerakan sosial. Celakanya, radikalisasi gerakan sosial ternyata menjadi arena bunuh diri, sementara radikalisasi kekuasaan terbukti berkekuatan berlipat-lipat dan efektif membunuh gerakan sosial. Dalam konteks itulah, gerakan sosial mesti diperkuat dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, seyogianya kita membiarkan tumbuhnya pusat-pusat gerakan sebanyak dan seberagam mungkin. Tidak diperlukan penyeragaman dan penyatuan pusat gerakan sosial. Setiap gerakan, sekecil dan seterfokus apapun, pada hakikatnya bisa memberikan sumbangan bagi proses demokratisasi. Dalam konteks ini, yang diperlukan bukanlah penyeragaman melainkan toleransi dan keterbukaan atau inklusivitas. Hal lain yang menurut hemat saya perlu dipertimbangkan adalah mengubah kecenderungan gerakan sosial selama ini dari sekadar berpuas diri dengan organisasi ke arah pembentukan jaringan. Menggunakan organisasi sebagai sarana gerakan sosial hanya akan membuat gerakan sosial memperoleh pencapaian atau hasil yang bersifat sementara, lokal, berjangka panjang. Untuk membuat gerakan sosial bisa memperoleh pencapaian yang berjangka panjang, lebih permanen dan menyeluruh, adalah membangun jaringan. Baik jaringan dalam pengertian fisik, dan terutama yang jaringan nonfisik dalam wujud toleransi, keterbukaan, dan saling percaya. Dengan organisasi, gerakan sosial boleh jadi akan berhenti menjadi kerumunan, namun dengan jaringan gerakan sosial bisa menjadi barisan. Akhirnya gerakan sosial perlu diperkuat dengan mengubah energi kemarahan yang selama ini menjadi pembentuk daya hidup gerakan sosial menjadi energi perlawanan politik. Kemarahan selalu merupakan sesuatu yang emosional, berjangka pendek, ad hoc, tak memiliki cita-cita, dan dengan mudah dipadamkan oleh hadiah-hadiah artifisial. Tapi, perlawanan politik adalah sesuatu yang rasional, berjangka panjang, permanen, bercita-cita, dan tak padam oleh hadiah-hadiah artifisial. Penutup: Kesabaran Revolusioner Demokratisasi dalam wujud memposisikan publik dalam Republik bukanlah pekerjaan mudah dan sebentar. Pada tataran pikiran, ia membutuhkan proses pergeseran paradigma (paradigm shift). Selama lebih dari empat dekade Sukarno-Soeharto, orang Indonesia dipaksa menggunakan paradigma "segala sesuatu harus berpusat pada negara atau penguasa". Dalam konteks pembangunan, misalnya, paradigma yang dipakai adalah pembangunan yang berpusat pada negara (state centered development) bukan pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development). Dalam kerangka pembangunan yang berpusat pada negara atau kekuasaan itulah publik menjadi sesuatu yang menggangu. Publik tidak diperlukan, kecuali sebagai objek dari pembangunan. Demokratisasi membutuhkan paradigma baru yang memusatkan segala sesuatu justru kepada publik. Publik adalah penentu dan subjek. Penguasa bertugas melayani publik dan bersikap sejalan dengan kemauan publik. Pergeseran paradigma ke arah paradigma baru yang berpusat pada rakyat, pada publik, semacam ini tentu butuh waktu dan keringat. Pada tataran praksis, demokratisasi dalam pengertian memposisikan publik dalam Republik membutuhkan upaya restrukturisasi yang tidak main-main. Struktur lama yang dibangun di atas faham negara integralistik -- negara totaliter yang terkendali-tersentralisasi, mengatasi segala sesuatu -- mesti dibongkar dan dibangun struktur baru yang mengorientasikan diri pada pemosisian (positioning ) publik secara layak. Dalam struktur baru itu, negara tidak lagi dibolehkan dan dibiarkan mengatasi individu, komunitas, lokalitas atas nama keseragaman. Negara justru memberi ruang lapang bagi tumbuhnya aktualitas individu, komunitas, lokalitas atas nama keanekaan. Dalam konteks pergeseran paradigma dan restrukturisasi itulah kita membutuhkan amandemen konstitusi, perubahan aturan dan tata aturan hukum dan perundang-undangan, penghentian politik tentara, netralisasi birokrasi, pengoptimalan pengawasan atas kekuasaan dari segala penjuru, otonomi yudikatif, konsolidasi sistem kepartaian demokratis-kompetitif, pengefektifan parlemen, dan kepemimpinan rasional-egalitarian. Memposisikan publik dalam Republik -- dalam konteks kebutuhan pergeseran paradigma dan retsrukturisasi -- pada hakikatnya merupakan sebuah kerja revolusi kebudayaan dalam pengertian yang luas. Celakanya, kita tak memiliki perangkat revolusioner segera sekarang sehingga yang tampaknya harus dikerjakan adalah tetap berpegang pada tujuan-tujuan perubahan revolusioner -- yang mendasar, menyeluruh, tuntas -- namun dengan kesediaan membangun infrastruktur revolusinya terlebih dahulu. Saya ingin menamakan keharusan di atas sebagai "kesabaran revolusioner". Kesabaran revolusioner adalah sesuatu yang seolah-olah kontradiktif di dalam dirinya namun sebetulnya tak. Kesabaran revolusiner adalah sebuah sikap seorang calon pemilik dan penggarap lahan yang tahu persis bahwa lahan miliknya sudah dibikin sertifikat atas nama orang lain. Dan dia bukan saja harus merebut lahan dan membuat sertifikat baru atas nama dirinya melainkan juga mesti menyiapkan semua peralatan untuk mengolah lahan itu bagi kegiatan cocok tanam yang sama sekali baru. Itulah kesabaran revolusioner yang sama maksudkan.