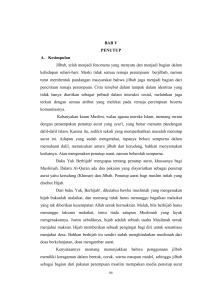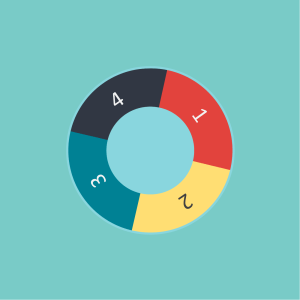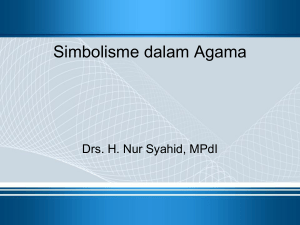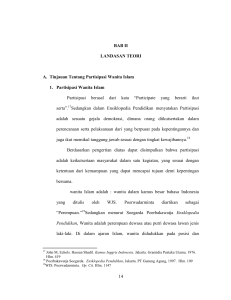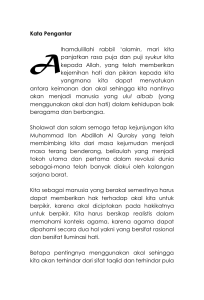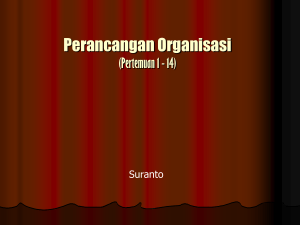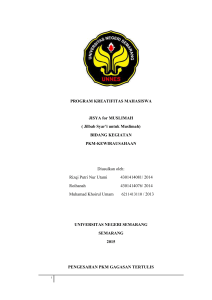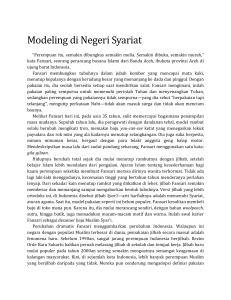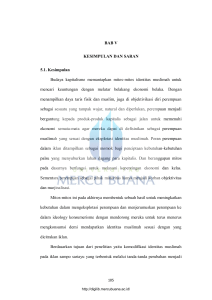Pernikahan: Hukum Agama Vs Hukum Negara
advertisement
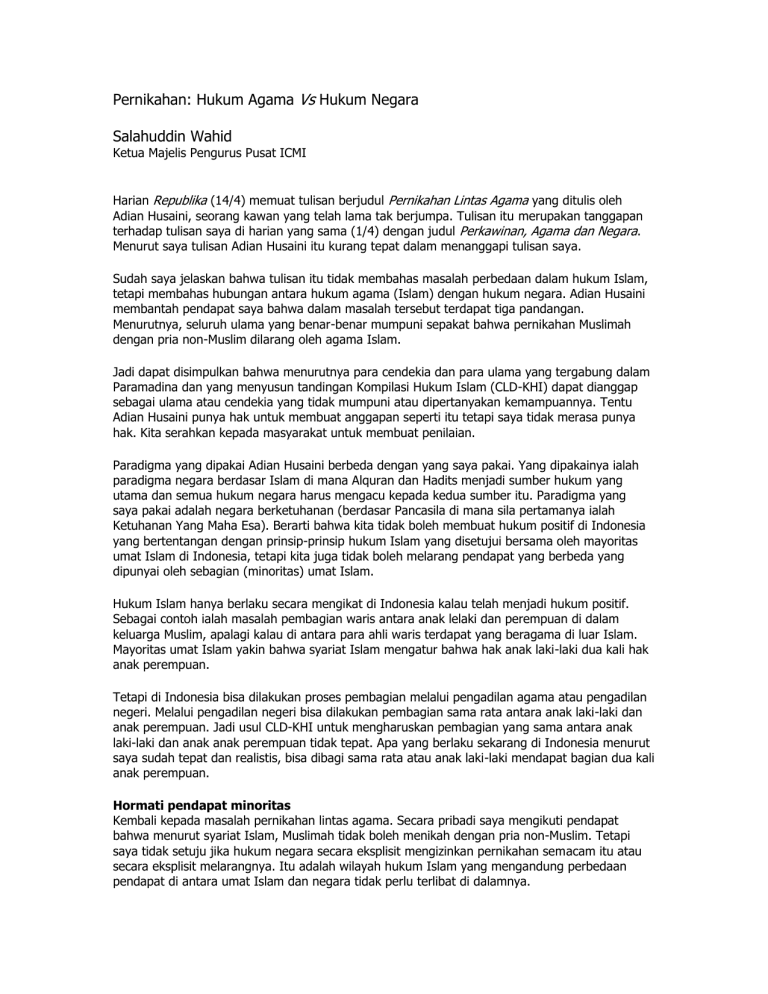
Pernikahan: Hukum Agama Vs Hukum Negara Salahuddin Wahid Ketua Majelis Pengurus Pusat ICMI Harian Republika (14/4) memuat tulisan berjudul Pernikahan Lintas Agama yang ditulis oleh Adian Husaini, seorang kawan yang telah lama tak berjumpa. Tulisan itu merupakan tanggapan terhadap tulisan saya di harian yang sama (1/4) dengan judul Perkawinan, Agama dan Negara. Menurut saya tulisan Adian Husaini itu kurang tepat dalam menanggapi tulisan saya. Sudah saya jelaskan bahwa tulisan itu tidak membahas masalah perbedaan dalam hukum Islam, tetapi membahas hubungan antara hukum agama (Islam) dengan hukum negara. Adian Husaini membantah pendapat saya bahwa dalam masalah tersebut terdapat tiga pandangan. Menurutnya, seluruh ulama yang benar-benar mumpuni sepakat bahwa pernikahan Muslimah dengan pria non-Muslim dilarang oleh agama Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurutnya para cendekia dan para ulama yang tergabung dalam Paramadina dan yang menyusun tandingan Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dapat dianggap sebagai ulama atau cendekia yang tidak mumpuni atau dipertanyakan kemampuannya. Tentu Adian Husaini punya hak untuk membuat anggapan seperti itu tetapi saya tidak merasa punya hak. Kita serahkan kepada masyarakat untuk membuat penilaian. Paradigma yang dipakai Adian Husaini berbeda dengan yang saya pakai. Yang dipakainya ialah paradigma negara berdasar Islam di mana Alquran dan Hadits menjadi sumber hukum yang utama dan semua hukum negara harus mengacu kepada kedua sumber itu. Paradigma yang saya pakai adalah negara berketuhanan (berdasar Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa). Berarti bahwa kita tidak boleh membuat hukum positif di Indonesia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang disetujui bersama oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, tetapi kita juga tidak boleh melarang pendapat yang berbeda yang dipunyai oleh sebagian (minoritas) umat Islam. Hukum Islam hanya berlaku secara mengikat di Indonesia kalau telah menjadi hukum positif. Sebagai contoh ialah masalah pembagian waris antara anak lelaki dan perempuan di dalam keluarga Muslim, apalagi kalau di antara para ahli waris terdapat yang beragama di luar Islam. Mayoritas umat Islam yakin bahwa syariat Islam mengatur bahwa hak anak laki-laki dua kali hak anak perempuan. Tetapi di Indonesia bisa dilakukan proses pembagian melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri. Melalui pengadilan negeri bisa dilakukan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi usul CLD-KHI untuk mengharuskan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan anak anak perempuan tidak tepat. Apa yang berlaku sekarang di Indonesia menurut saya sudah tepat dan realistis, bisa dibagi sama rata atau anak laki-laki mendapat bagian dua kali anak perempuan. Hormati pendapat minoritas Kembali kepada masalah pernikahan lintas agama. Secara pribadi saya mengikuti pendapat bahwa menurut syariat Islam, Muslimah tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim. Tetapi saya tidak setuju jika hukum negara secara eksplisit mengizinkan pernikahan semacam itu atau secara eksplisit melarangnya. Itu adalah wilayah hukum Islam yang mengandung perbedaan pendapat di antara umat Islam dan negara tidak perlu terlibat di dalamnya. Biarkan keadaan seperti sekarang berlangsung, dimana UU No 1/1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan dinyatakan sah jika sesuai dengan ketentuan agama masingmasing. Menurut pendapat mayoritas umat Islam di Indonesia, pernikahan antara Muslimah dengan pria non-Muslim itu dilarang oleh agama Islam. Jelas negara tidak boleh mengintervensi dengan mengijinkannya secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan, yang berarti tidak sesuai dengan pendapat mayoritas umat Islam. Tetapi negara harus menghormati pendapat minoritas umat Islam yang memperbolehkan pernikahan semacam itu, dengan cara memberikan kesempatan untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Catatan Sipil supaya pernikahan mereka sah menurut negara. Untuk bisa melakukan itu tampaknya kita harus menunggu lahirnya UU Catatan Sipil yang mengatur keharusan untuk mencatat atau mendaftar semua pernikahan di Indonesia. Kalau negara secara eksplisit di dalam UU melarang pernikahan itu, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan Muslimah dan pria non-Muslim yang menikah itu melanggar hukum negara dan dapat dikenakan sanksi. Demikian pula bila UU melarang poligami, pria yang melakukan poligami dan pasangannya dapat dikenakan sanksi. Tetapi bagaimana bila pernikahan pria poligami itu dilakukan di bawah tangan? Apakah pernikahan di bawah tangan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum negara dan dapat dikenai sanksi? Atau pernikahan di bawah tangan itu secara hukum negara dianggap tidak ada dan tidak dapat dikenai sanksi apapun? Kalau demikian keadaannya, maka pihak perempuan dan keturunannya akan mengalami perlakuan yang diskriminatif, karena ada kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan hak yang sama dengan istri pertama dan keturunannya. Isteri pertama dan keluarganya juga akan dirugikan tetapi si suami tidak bisa dikenakan sanksi apa-apa. Kekhawatiran Di atas dikatakan bahwa Adian Husaini memakai paradigma negara berdasar Islam dan saya memakai paradigma negara berketuhanan. Apakah paradigma yang dipakai oleh tim yang mengusulkan CLD-KHI? Tampaknya paradigma mereka cenderung ke arah negara sekuler. Tentu saja saya bisa keliru. Bahkan bagi Adian Husaini dan kawan-kawan, saya pun mungkin dikatakan mempunyai paradigma negara sekuler. Ukuran yang pasti tentang masalah itu memang tidak pasti. Sejauh pemahaman saya dalam konteks negara Indonesia, negara sekuler ialah negara yang tidak memberi kesempatan sama sekali untuk masuknya ketentuan syariat Islam yang partikular. Yang diterima ialah syariat Islam yang bersifat universal. Bagi mereka sumber hukum adalah hukum internasional yang bersifat universal, dan hanya ada satu hukum untuk suatu masalah tertentu yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama dan suku. Padahal di Indonesia bagi banyak kalangan, sumber hukum itu bisa hukum internasional, hukum adat dan hukum Islam. Contoh yang terbaik ialah bagaimana kita menyikapi pemakaian jilbab. Ketika Dr Daud Yusuf menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, pernah ada larangan bagi siswi SMAN/SLTA untuk memakai jilbab ke sekolah dan yang bersikeras memakainya harus keluar dari sekolah mereka. Itu adalah salah satu bentuk penerapan paradigma sekulerisme di negara kita. Sekarang kita lihat bahwa pemakaian jilbab ke sekolah sudah bebas. Dalam masalah jilbab, paradigma negara berdasar Islam tentu mengharuskan semua Muslimah memakai jilbab (contohnya di NAD). Dalam paradigma negara sekuler, dilarang untuk memakai jilbab di lembaga negara. Contohnya: Turki melarang mahasiswi universitas negeri memakai jilbab dan Prancis melarang siswi memakai jilbab di sekolah negeri. Tetapi Amerika Serikat mengizinkan tentara Muslimah memakai jilbab. Di Indonesia yang berparadigma negara berketuhanan, Muslimah boleh memakai jilbab sesuai kehendak dan keyakinannya. Tidak ada larangan dan tidak ada keharusan. Memakai jilbab karena kesadaran tentu lebih afdol daripada karena keharusan. Di sini kita lihat negara tidak mencampuri pendapat pribadi dan menghormatinya. Adian Husaini khawatir bila kita memperbolehkan pernikahan Muslimah dengan pria non-Muslim akan berakibat terlalu jauh sampai memperbolehkan pernikahan pria dengan pria atau perempuan dengan perempuan, dengan dalih menghormati hak asasi manusia. Kita harus memperhatikan dan menghormati adanya kekhawatiran itu. Kalau dalam masalah pernikahan Muslimah dengan pria non-Muslim kita masih memberi toleransi kepada (minoritas) umat Islam yang mengizinkan pernikahan Muslimah dengan pria non-Muslim, saya yakin tidak ada ulama atau cendekiawan Islam yang berpendapat bahwa Islam mengizinkan pernikahan sesama jenis. Pertanyaannya, apakah kita juga akan memberikan toleransi serupa kepada pernikahan sesama jenis demi menghormati HAM? Tentu tidak karena semua agama di Indonesia melarang pernikahan semacam itu. Nilai moral bangsa kita juga menolaknya. Kalau kita tidak menyetujui pernikahan semacam itu, bagaimana cara kita melarangnya? Apakah dengan cara tidak memberi izin untuk mendaftar atau kita menyatakan bahwa pernikahan semacam itu merupakan pelanggaran atau tindak pidana dan harus dikenakan hukuman. Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu dan kita tidak punya cukup ruang dalam tulisan ini.