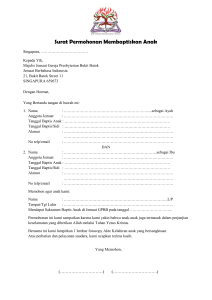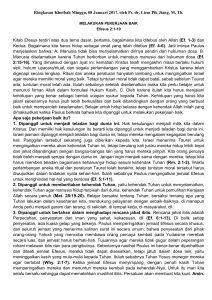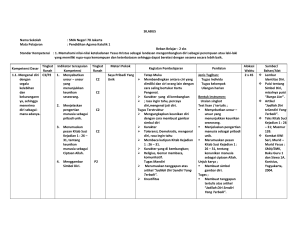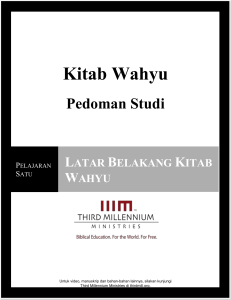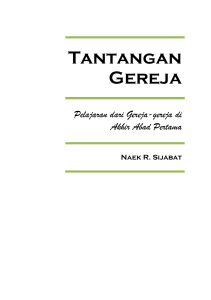Kotbah pada Perjamuan Kudus penutupan semester FTh UKDW
advertisement

"Apa semuanya ini percuma?" Kotbah pada Perjamuan Kudus penutupan semester FTh UKDW, Selasa, 8 MEI 2012 “Apa semuanya ini percuma? “Kotbah pada kebaktian Perjamuan Kudus penutupan semester FTh UKDW, Selasa, 8 Mei 2012, jam 7.30-9.00 Teks: Wahyu 14:6-13 Nas: Wahyu 14:13, “Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini”. 1. Sepanjang semester ini setiap minggu kita bersama-sama telah berusaha memahami kitab Wahyu dalam Pemahaman Alkitab, atau yang sekarang disebut “Diskusi Teologis”. Yang menarik kali ini adalah bahwa yang membawakan bahan adalah mahasiswa (s1, s2 dan s3), sedangkan yang memberi tanggapan adalah para dosen. Saya tidak bermaksud memberi rangkuman atas bahan-bahan yang sudah diberikan sebelumnya. Dalam pendahuluan ini saya hanya memberi sedikit kesan saya, bahwa agaknya kita semua tidak terlalu “happy” dengan kitab Wahyu. Tetapi tidak usah merasa terlalu bersalah karena hal ini, sebab memang tradisi Reformasi tidak pernah terlalu “happy” dengan kitab Wahyu. Pada jaman sebelum reformasi Calvin, di Muenster terjadilah pemberontakan kaum Anabaptis, yang menganggap bahwa kiamat sudah dekat dan kerajaan Allah sudah akan tiba, sehingga suasana menjadi kacau. Hal ini sudah diceritakan oleh pak Paulus (yang adalah keturunan Anabaptis), jadi tidak akan saya ulangi lagi. Saya hanya mau membagikan bahwa reformator Calvin si penulis buku yang menjadi standard untuk orang Calvinis, yaitu Institutio Religionis Christianae, mengalamatkannya kepada raja Perancis, Francois I, sebagai sebuah usaha membela diri, yaitu bahwa orang Calvinis tidak sama dengan orang Anabaptis yang suka memberontak itu (Hal ini dapat anda baca dalam pendahuluan buku tsb yang berupa sebuah surat kepada sang raja. Di situ dia tidak menyebut secara eksplisit kaum Anabaptis, tetapi dar i deskripsinya mengenai orang-orang yang dianggapnya pengacau itu kita bisa menduga bahwa yang dimaksudkannya adalah kaum Anabaptis). Kalau orang Anabaptis menggunakan kitab Wahyu, orang Calvinis tidak menggunakan kitab Wahyu. Namun patut dicatat bahwa sesudah peristiwa Muenster, kaum Anabaptis secara total berubah haluan: kalau tadinya mereka violent sekarang mereka non-violent, dan non-violent itu dijadikan ukuran mutlak apakah seseorang itu Anabaptis atau tidak. 2. Sejak itu orang Calvinis tidak atau jarang menggunakan kitab Wahyu. Apalagi ketika pada abad 19, orang di USA (kaum “Millerites”) mulai menggunakan lagi kitab Wahyu untuk menghitung-hitung kapan jadinya kiamat, lebih-lebih lagi orang Calvinis tidak membaca kitab Wahyu dan mempersalahkan semua pembaca kitab Wahyu sebagai “salah mengerti” kitab Wahyu. Karena selalu saja ada orang yang happy dengan kitab Wahyu dan rasa happy ini berkembang menjadi hobby menghitung kapan datangnya hari kiamat, maka secara hermeneutis, orang Calvinis tidak mempedulikan kiamat. Mereka mengakui bahwa Kristus akan datang untuk kedua kalinya dan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, tetapi kapan itu terjadi masa bodohlah dan ngapain mikirin kiamat kayak orang yang nggak ada kerjaan. Nah, ada juga orangorang yang tidak senang kepada kitab Wahyu bukan karena membuka kesempatan untuk menyongsong kiamat, tetapi karena isinya terlalu violent: hukuman-hukuman terhadap lawan-lawan Anak Domba digambarkan dengan fantasi yang bermandikan darah, dunia penuh dengan mayat-mayat yang bergelimpangan seperti di ladang pembantaian. Yesus yang di dalam Injil-Injil adalah Mesias Pembawa Damai yang tidak melawan ketika dikerasi, di dalam kitab Wahyu berubah menjadi Anak Domba yang dari dibantai menjadi pembantai. John Dominic Crossan yang terkenal itu dalam bukunya God and Empire misalnya mengajak pembaca kembali saja kepada Yesus sejarah, daripada menyembah Kristus iman yang sudah dikonstruksikan secara sangat kejam di dalam kitab Wahyu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa memangnya nggak ada lagi hikmah yang bisa diambil dari kitab Wahyu untuk keperluan pembangunan iman kita sekarang ini? Saya yakin kok masih ada, meskipun andaikata kita tidak lagi memperhatikan tema kiamat dan tema kekerasan di dalam kitab tersebut. 3. Salah satu tema positif yang sering digali adalah ketabahan dan/atau ketekunan, yang dalam bahasa Yunani disebut hupomone. Salah seorang mahasiswa STT DW (sewaktu belum menjadi fakultas) telah menulis skripsi dari kitab Wahyu, kemudian skripsi itu dibukukan dengan judulTeologi Ketabahan (sekarang penulisnya telah menjadi pendeta yang termasyur di ibukota). Jadi dalam menghadapi pelbagai macam tantangan berat, bahkan tantangan maut, yang diharapkan dari jemaat Kristus adalah kemampuan untuk bertahan, tabah dalam penderitaan. Kebetulan satu ayat sebelum nas kita, yaitu Wahyu 14:12 mengemukakan hal itu, “yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus”. Tetapi ayat selanjutnya yaitu nas kita berbicara mengenai mereka yang sudah mati, tetapi berbahagia. Bagaimana menghubungkan ketekunan atau ketabahan dengan kematian? Tentu saja anda bisa mengatakan bahwa kematian dapat berkaitan dengan ketabahan, karena kalau mati, kita akan mendapatkan ganjaran yang istimewa dari Tuhan, yaitu kebahagiaan. Tetapi saya pikir ketabahan hanya bermakna kalau dihubungkan dengan orang hidup bukan dengan orang mati. Maka di sini saya mencoba melengkapi pemikiran mengenai ketekunan dan ketabahan itu dengan tema kematian. 4. Seperti telah diinformasikan dalam presentasi para penyaji dan penanggap, konteks historis kitab Wahyu adalah ketujuh jemaat yang berada di Asia Kecil. Ketujuh jemaat berada di tujuh kota Yunani yang bersifat federasi (Yun: koinoon) dan merupakan koloni Romawi. Di sekolah kita belajar bahwa dijajah itu tidak baik, selalu diperas habis oleh si penjajah. Ya memang umumnya begitu, tetapi kadang-kadang kalau yang dijajah pintar, koloni bisa juga memanfaatkan si pengkoloni. Usahakan aja agar kita meniru Roma sampai habis-habisan, lebih Roma daripada Roma, sehingga mereka terbuai dan dalam keadaan seperti itu kita bisa membujuk mereka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bisnis dan finansial yang aduhai. Begitulah ketujuh kota itu melakukan kebijakan menjilat kepada Roma. Semua penguasa Roma diangkat menjadi dewa dan di kota-kota itu didirikanlah pusat-pusat pemujaan kaisarkaisar Roma. Tentu saja semua penduduk federasi harus bersatu dalam menjilat ini, tidak boleh ada yang mbalelo. Nah, ketujuh jemaat ini mengalami pergumulan: menyembah kaisar atau menyembah Tuhan? Ya tentu saja menyembah Tuhan, tetapi kalau begitu harus menghadapi kemarahan koloni. Dalam beberapa tulisan mengenai penganiayaan terhadap jemaat pada zaman kaisar Nero dan Domitianus, ada yang mengoreksi gambaran kita mengenai penganiyaan tsb: jangan diartikan bahwa ada sebuah program politik yang berkesinambungan dari pihak kaisar berupa penganiayaan terhadap jemaat Kristen. Penganiayaan-penganiayaan tsb bersifat sporadis dan lebih banyak berupa tekanan mental daripada fisik. Koreksi ini betul, namun andaikata penganiayaan tsb sporadis, apakah lalu berarti ringan? Saya kira tidak. Tanyakanlah kepada teman-teman pendeta dan majelis yang mengalami sendiri penyerbuan massa ke gereja mereka dan membakar gereja itu di hadapan mata mereka. Saya terus: penganiayaan Nero dan Domitianus bersifat sporadis, tetapi penganiayaan dari bangsa sendiri di federasi tujuh kota itu (jadi dalam konteks Asia Kecil dan bukan dalam konteks keseluruhan kekaisaran Romawi) tidak bersifat sporadis melainkan berkesinambungan, dan banyak korban yang jatuh. Di teks-teks yang merujuk kepada ketujuh jemaat hal itu dapat dilihat : di jemaat Smirna nampaknya ada saingan yaitu jemaat Yahudi yang melapor kepada yang berwajib mengenai sikap jemaat Smirna, sehingga mereka terancam akan menderita, namun diimbau agar setia sampai mati (Wahyu 2:10). Di jemaat Pergamus ada satu korban yang mati dibunuh di hadapan jemaat yaitu si Antipas (Wahyu 2:13). Di sini dan di jemaat Tiatira ada tekanan supaya mereka ambil bagian dalam makanan yang dipersembahkan pada berhala (baca: kaisar yang didewakan )(Wahyu 2:20). Jemaat Sardis tinggal sisa-sisa, dan sisa-sisa itupun sudah hampir mati (Wahyu 3:2). Begitu banyak korban yang jatuh sehingga jemaat menjadi bingung dan putus asa dan bertanya-tanya apakah semuanya ini percuma saja? Seruan mereka ditampung oleh si pelihat yang bernama Yohanes di Wahyu 6:10:”…Berapa lamakah lagi, ya Penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?” Berhadapan dengan pertanyaan teodise ini, teologi ketabahan tidak bisa memberi jawab dan karena itu tidak bisa dijadikan tema kitab Wahyu. Pertanyaan teodise ini harus dijawab dengan statement atau paling tidak penguraian yang bersifat teodise pula. Itulah yang dilakukan oleh penulis kitab Wahyu dengan membayangkan si pelihat Yohanes sedang melihat surga dan apa yang diputuskan di dalam surga mengenai masa depan dunia ini: Kejahatan adalah sesuatu yang kongkret dan selalu ada di dalam dunia ini. Tidak heran karena kalau ada Kristus maka selalu juga ada Antikristus atau si Jajal. Tetapi meskipun kejahatan merupakan sesuatu yang kongkret dan mendominasi dunia ini, kejahatan tidak kekal dan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Bahkan keadilan akan ditegakkan: mereka yang tadinya melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah, akan mengalami kekerasan yang sama sebagai hukuman terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Dalam logika apokaliptik mulai dari zaman PL sampai PB, kejahatan yang mendominasi dunia selalu berakhir, karena Tuhan mengakhiri sejarah dunia ini secara tiba-tiba. Kita mengatakannya kiamat, tetapi secara positif, akhir dari dunia ini berarti akhir dari kejahatan. Nah ini yang penting: akhir dari kejahatan adalah ditumpasnya kejahatan. 5. Orang beriman harus memisahkan diri dari dunia yang jahat itu. Ada garis batas yang amat tajam antara kejahatan dan kebaikan, antara “kita” dan “mereka”. Katakanlah mirip suasana revolusioner, di mana “kita” bertolakbelakang dengan “mereka” (meskipun sama-sama manusia). Di kitab Wahyu mereka yang dianggap “kita” adalah semua jemaat yang sudah mati karena penganiayaan, yang jumlahnya diwakili oleh angka 144.000. Jadi orang beriman di dalam konteks kisah kitab Wahyu sudah memisahkan diri dari dunia yang jahat melalui kematian mereka sebagai syahid. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai orang yang berbahagia seperti dikatakan dalam nas kita. Bukan itu saja, bahwa mereka yang mati itu kemudian dimuliakan di surga dan boleh bergabung dengan paduan suara surgawi yang bernyanyi nyanyian Musa dan nyanyian Anak Domba seperti juga yang akan kita nyanyikan nanti dalam Doa Syukur Agung, merupakan tanda bahwa penderitaan dan kematian warga jemaat bukan merupakan hukuman Tuhan terhadap mereka melainkan sebuah pembenaran Tuhan terhadap mereka. Mereka yang mati adalah bukan benih gereja seperti kata seorrang bapa gereja, melainkan wakil gereja, yang telah berhasil mempertahankan kebenaran sampai bersedia mati untuk itu. Jadi bukan negara yang benar mentang-mentang dia berkuasa melainkan gerejalah yang benar! Itu bisa kita lihat di Wahyu 13, dan sejak itu Wahyu 13 merupakan teks penting bagi siapa saja yang berhadapan dengan negara atau pemerintah yang mengangkat dirinya menjadi seperti Tuhan dalam kuasa yang totaliter sifatnya, dan merupakan pengimbang yang baik terhadap Roma 13 yang menganjurkan orang beriman agar setialah kepada para penguasa karena mereka adalah hamba Allah. Di Indonesia, kita mewarisi Roma 13 dari suasana spiritual jaman penjajahan. Mestinya karena sekarang jaman poskolonial, teologi kita harusnya teologi poskolonial, dan untuk itu Wahyu 13 bisa menjadi inspirasi! 6. Dalam praktek pemisahan total di antara kebaikan dan kejahatan tidak pernah bisa berhasil. Yesus sudah memberitahukan hal itu kepada jemaat melalui perumpamaan lalang dan gandum. Tetapi nampaknya bagi pelihat Yohanes, keadaan sudah gawat, cabut aja deh, biar gandum ikut tercabut, gpp… Bagi pelihat Yohanes, sudah tiba masa menuai, dan tuaiannya adalah dunia yang penuh orang jahat, yang disabit oleh Anak Manusia yang mengendarai kuda sambil mengayun-ayunkan sabit (Wahyu 14:14-20). Apakah jemaat selain yang 144.000 itu akan ikut tersabit? Ya nggak, karena yang 144.000 itu mewakili seluruh jemaat yang masih hidup. Mereka mati supaya yang lain hidup. Maka konsep orang-orang kudus yang sudah mati menjadi penting dalam rangka mempertahankan pemisahan total di antara yang baik dan yang jahat. Tetapi seperti sudah saya kemukakan dalam makalah saya mengenai “Skenario Kemenangan Akhir: fungsi gambar dan simbol di Wahyu 12-15” dan sudah dibagikan juga (dibaca nggak ya?), bahasa kitab Wahyu bersifat retoris dan harus dipahami sebagai retorik. Isinya adalah skenario mengenai masa depan dan bukan mengenai masa depan itu sendiri. Namun pembenaran Allah terhadap umat yang menderita dan mati dapat kita hubungkan dengan pembenaran Allah terhadap Yesus sebagai orang yang tidak bersalah namun menderita dan mati, dan pembenaran Tuhan terhadap Ayub dan Hamba Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yang menderita sebagai orang yang tidak bersalah. Mungkin dalam kitab Wahyu tidak ada tema utama, tetapi ada beberapa tema, dan salah satu tema penting adalah pembenaran Tuhan terhadap penderitaan dan kematian umatNya. Mungkin saya tidak happy dengan tema kiamat dan kekerasan akibat hukuman Tuhan di dalam kitab Wahyu, tetapi dengan tema pembenaran Tuhan terhadap umatNya, yang merupakan wujud dari perhatian dan solidaritasnya terhadap penderitaan manusia, saya happy. Mari datanglah, ya Tuhan, Maranatha, Amin. Wisma Labuang Baji,Yogyakarta, 22 April 2012.