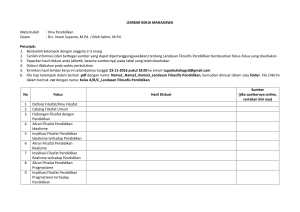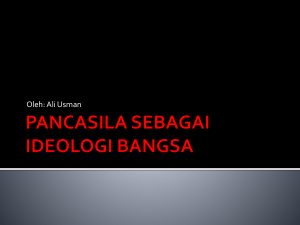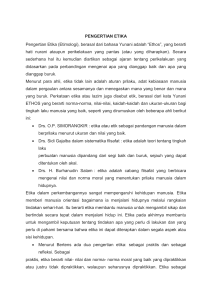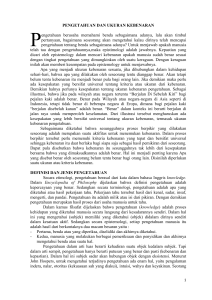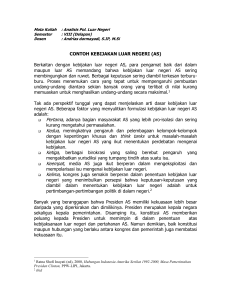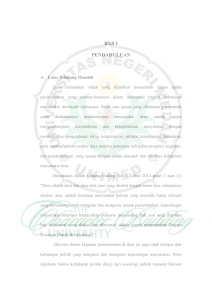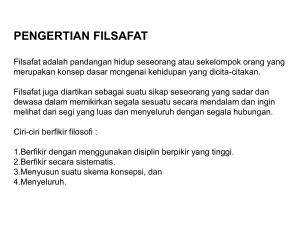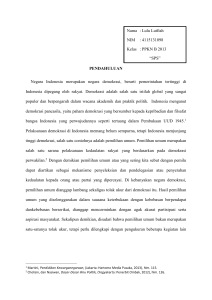Media Massa, Idealisme, dan Politik Populer
advertisement
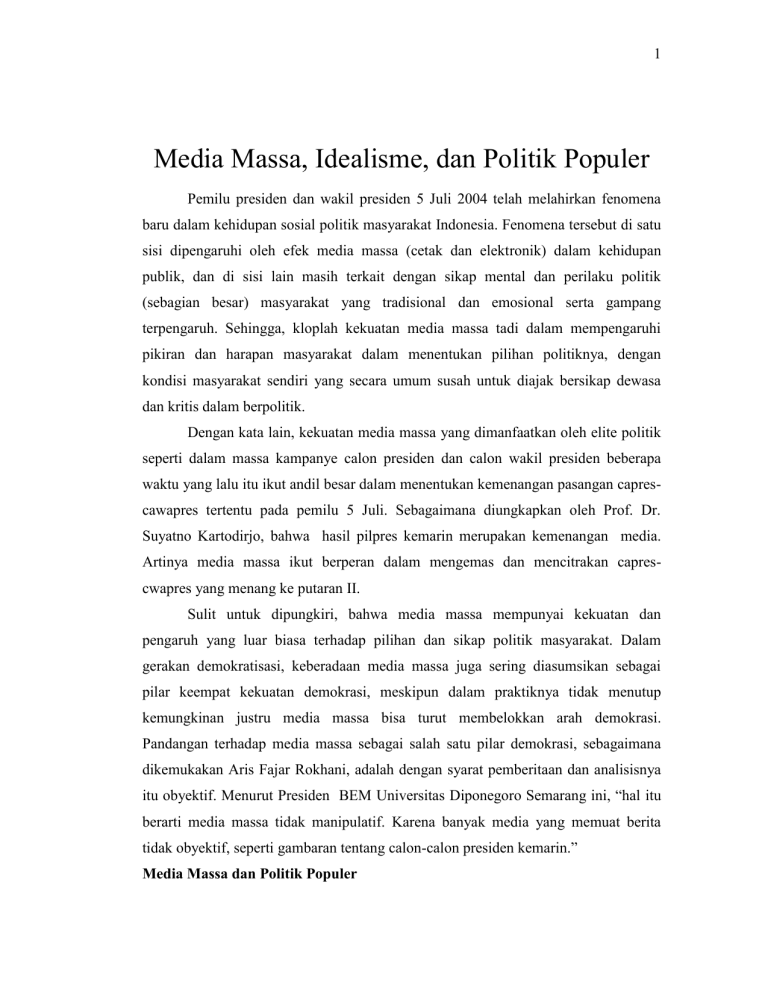
1 Media Massa, Idealisme, dan Politik Populer Pemilu presiden dan wakil presiden 5 Juli 2004 telah melahirkan fenomena baru dalam kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut di satu sisi dipengaruhi oleh efek media massa (cetak dan elektronik) dalam kehidupan publik, dan di sisi lain masih terkait dengan sikap mental dan perilaku politik (sebagian besar) masyarakat yang tradisional dan emosional serta gampang terpengaruh. Sehingga, kloplah kekuatan media massa tadi dalam mempengaruhi pikiran dan harapan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, dengan kondisi masyarakat sendiri yang secara umum susah untuk diajak bersikap dewasa dan kritis dalam berpolitik. Dengan kata lain, kekuatan media massa yang dimanfaatkan oleh elite politik seperti dalam massa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden beberapa waktu yang lalu itu ikut andil besar dalam menentukan kemenangan pasangan caprescawapres tertentu pada pemilu 5 Juli. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Suyatno Kartodirjo, bahwa hasil pilpres kemarin merupakan kemenangan media. Artinya media massa ikut berperan dalam mengemas dan mencitrakan caprescwapres yang menang ke putaran II. Sulit untuk dipungkiri, bahwa media massa mempunyai kekuatan dan pengaruh yang luar biasa terhadap pilihan dan sikap politik masyarakat. Dalam gerakan demokratisasi, keberadaan media massa juga sering diasumsikan sebagai pilar keempat kekuatan demokrasi, meskipun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan justru media massa bisa turut membelokkan arah demokrasi. Pandangan terhadap media massa sebagai salah satu pilar demokrasi, sebagaimana dikemukakan Aris Fajar Rokhani, adalah dengan syarat pemberitaan dan analisisnya itu obyektif. Menurut Presiden BEM Universitas Diponegoro Semarang ini, “hal itu berarti media massa tidak manipulatif. Karena banyak media yang memuat berita tidak obyektif, seperti gambaran tentang calon-calon presiden kemarin.” Media Massa dan Politik Populer 2 Media massa, terutama yang elektronik, memiliki kekuatan impresif terhadap perhatian dan pikiran publik serta daya jangkaunya tergolong luas karena bisa masuk ke pelosok-pelosok desa dengan seketika. Secara audio visual, publik bisa menyaksikan kampanye dan penayangan para kandidat presiden dan wakil presiden. Pengaruh dan kesan dari media audio visual seperti televisi tentu lebih kuat dan bertahan lama dalam memori publik ketimbang koran, selebaran, atau majalah. Kekuatan dan pengaruh seperti itulah yang ikut membentuk pilihan dan sikap politik masyarakat dalam pilpres 5 Juli. Melalui kekuatan media massa elektronik seperti televisi, tim kampanye capres-cawapres memplubikasikan jago-jagonya dan membuat pencitraan diri agar bisa diterima oleh masyarakat. Capres-cawapres dan tim suksesnya yang mempunyai kekuatan dana besar tentu akan gampang untuk menguasai media massa demi menyukseskan kampanyenya. Akibat lebih jauh dari kekuatan media massa seperti itu, muncullah kemudian budaya politik populer di kalangan masyarakat. Budaya politik ini oleh Nurdien H. Kistanto, Ph.D. disebutnya sebagai konsekuensi zaman, karena media massa menjadi suatu sarana yang luar biasa berikut akibat dan dampak yang ditimbulkannya. Menurut Dosen Fak. Sastra Universitas Diponegoro Semarang ini, “popularitas pada zaman sekarang ini memang sudah sangat jelas sebagai konsekuensi dari perkembangan media massa.” Dengan demikian bisa dikatakan, kemenangan pasangan capres-cawapres dalam pemilu 5 Juli kemarin itu dibantu oleh pengaruh media massa, meskipun seperti yang dikemukakan Nurdien H. Kistanto, hal itu tidak terjadi secara instan, karena para kandidat yang menang itu telah melalui proses sebelumnya. Meski begitu, menurut Muhammad Hilmi Faiq (Peneliti di Center for Religious and Social Studies, Malang), kemenangan pilpres kemarin adalah sebagai kemenangan kultur politik populer. Pandangan tersebut sepertinya semakin menguatkan pengaruh media massa sendiri yang selama ini telah banyak berperan dalam mempromosikan budaya populer 3 di kalangan masyarakat. Lewat berbagai program acara entertainment dan tayangan iklan yang menjajakan gaya hidup dan pilihan mode --pakaian, makanan, dan hiburan-- media massa, khususnya televisi, secara massif dan luas telah menggiring publik ke arah budaya populer. Begitulah, sampai-sampai politik pun tidak terkecuali dibentuk sebagai politik populer. Itulah yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kita dewasa ini, paling tidak seperti tercermin pada pemilu 5 Juli. “Yang menang sekarang adalah kultur politik populer, karena mereka bisa mengolah event dan menguasai media massa. Dengan tayangan di televisi misalnya, orang akan lebih cepat mengenal salah satu tokoh atau pemimpin karena sering tampil di televisi,” demikian ungkap Khaerul Umam. Lebih lanjut sutradara terkenal yang juga menjadi Ketua Lembaga Kebudayaan dan Seni PP Muhammadiyah ini menegaskan, “kultur politik populer ini mendominasi kehidupan masyarakat daripada mendewasakan politik untuk rakyat seperti melalui pendidikan politik yang dikemas oleh LSM atau lembaga-lembaga tertentu.” Senada dengan pendapat Khaerul Umam, menurut K.H. Drs. Nasrudin Razak, kultur politik populer itu terbentuk karena masyarakat Indonesia cenderung hedonistik dan lebih suka berhura-hura, sehingga mereka tidak ambil pusing dengan masalah masa depan bangsa ini. Dengan panjang lebar Ketua PWM Sulawesi Selatan ini menyebutkan, “masyarakat lebih suka pemimpin yang populer daripada yang memiliki idealisme, karena menurut mereka lebih bisa memberikan solusi meskipun berjangka pendek. Hal ini semacam politik bodrex, yakni politik yang dapat memberikan penyembuhan jangka pendek, meskipun selanjutnya akan mendapat penyakit yang lebih parah.” Fenomena politik seperti itu diprihatinkan oleh Novel Ali. Menurut Dosen Fisip Universitas Diponegoro ini, “pemilu kita lebih tampil sebagai aksesoris daripada sebuah proses. Aksesoris politik, aksesoris kekuasaan, itu lebih menonjol ketimbang suatu proses pendidikan politik untuk rakyat. Karenanya popularitas itu lebih dominan dan lebih menentukan ketimbang prestasi.” 4 Pendidikan Politik Budaya politik populer itu disinyalir kuat memiliki dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. “Kultur politik seperti itu jelas tidak sehat, karena rakyat kehilangan daya kritis sejatinya. Pilihan-pilihan politiknya adalah pilihan semu yang tidak didasari oleh kesadaran akalnya, tetapi pada keterkaguman sejenak,” tegas Muhammad Hilmi Faiq. Dengan kata lain, kultur politik populer akan menyuburkan pragmatisme politik yang hanya memikirkan kepentingan jangka pendek dan sesaat, mudah terpukau dengan figur seseorang yang dcitrakan secara manipulatif melalui media massa, dan bisa tidak peduli dengan nilai-nilai etika dan agama. Menurut Prof. Dr. H. Ambo Enre Abdullah, Rektor Unismuh Makassar, “pragmatisme politik itu marak karena kemiskinan rakyat yang berkepanjangan, sehingga rakyat lebih cenderung memilih yang praktis saja dan dapat menyelesaikan masalah jangka pendek.” Fenomena sosial politik yang memprihatinkan ini bisa dipandang sebagai kegagalan pendidikan politik kepada masyarakat. “Kita harus mengakui bahwa kegagalan pendidikan politik dapat berujung pada pragmatisme politik, karena masyarakat kita dewasa ini cenderung melupakan politik spiritualnya,” demikian pendapat Nasrudien Razak, Ketua PWM Sulawesi Selatan. Untuk menanggulangi hal itu, seperti dikatakan Sukardi Makobombang, infrastruktur politik harus diperkuat dengan bekal pendidikan politik. Mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta dan aktivis Forkot ini menjelaskan, “peran LSM, relawan dan lembaga kemahasiswaan sangat penting dalam memberdayakan politik rakyat. Sayangnya LSM dan lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan itu cenderung terbentur dengan masalah kucuran dana. Manakala dananya menipis atau tidak ada, maka mereka juga berhenti untuk melakukan aktivitasnya.” Melalui pendidikan politik itulah idealisme politik kembali bisa disemaikan dalam kehidupan masyarakat. Di tengah dominasi pragmatisme politik dan kehidupan masyarakat yang masih terkena dampak krisis multidimensi, memang tidak mudah 5 untuk berpihak pada idealisme politik itu. Seperti diakui oleh Dr. H. Qomari Anwar, MA, untuk menegakkan idealisme politik itu sangat sulit, karena kejujuran sudah tidak ada lagi. Rektor Uhamka Jakarta ini kemudian menuturkan, “idealisme itu identik dengan kejujuran. Selama para pelaku politik tidak berani jujur, maka idealisme akan luntur. Jadi kalau sudah tidak ada kejujuran, maka dari segi kemanusiaan sudah tidak menguntungkan bahkan akan muncul kebohongankebohongan publik dan berbagai bentuk penyimpangan.” Sedangkan dalam pandangan Prof. Dr. H. Ambo Enre Abdullah, kita masih mungkin menegakkan kembali idealisme politik dengan memenuhi kebutuhan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sebagainya. Rektor Unismuh Makassar ini yakin bahwa lembaga pendidikan sangat signifikan untuk memberdayakan rakyat, sehingga akan ikut berperan untuk menegakkan idealisme politik. Persoalan budaya politik tersebut diakui oleh Muhammad Arifin sebagai kelemahan dari pendidikan politik. Menurut ketua Umum BEM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini, “pendidikan politik tidak pernah dibebaskan sejak dulu. Hak berdemokrasi rakyat di Indonesia sudah lama dipasung. Karena itu perlu ada perbaikan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendidikan rakyat dengan betul.” Bisa jadi fenomena politik sekarang ini oleh Prof. Dr. Suyatno Kartodirjo disebutnya sebagai episode pertaruhan. “Bisa saja kinerja pemerintah besok tidak beres dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat, ya pasti akan dilengserkan oleh rakyat. Reformasi akan kembali digulirkan,” jelas Dosen Pascasarjana UNS ini. Pada akhirnya pendidikan politik diharapkan akan bisa mendewasakan masyarakat dalam berpolitik, sehingga mereka tidak salah pilih lagi dalam menentukan pemimpin bangsa. “Proses pendidikan politik tidak membutuhkan popularitas. Kita membutuhkan karya, kinerja, proses, dan efek,” demikian kata Novel Ali. Lebih jauh, idealisme politik yang dihasilkan lewat pendidikan tadi setidaknya akan mengurangi kultur politik populer yang melupakan substansi politik 6 dan program jangka panjang agenda bangsa. [tulisan: tiar; bahan: husni, k’ies, rif, sen, ton] Sumber: Suara Muhammadiyah Edisi 16 2004